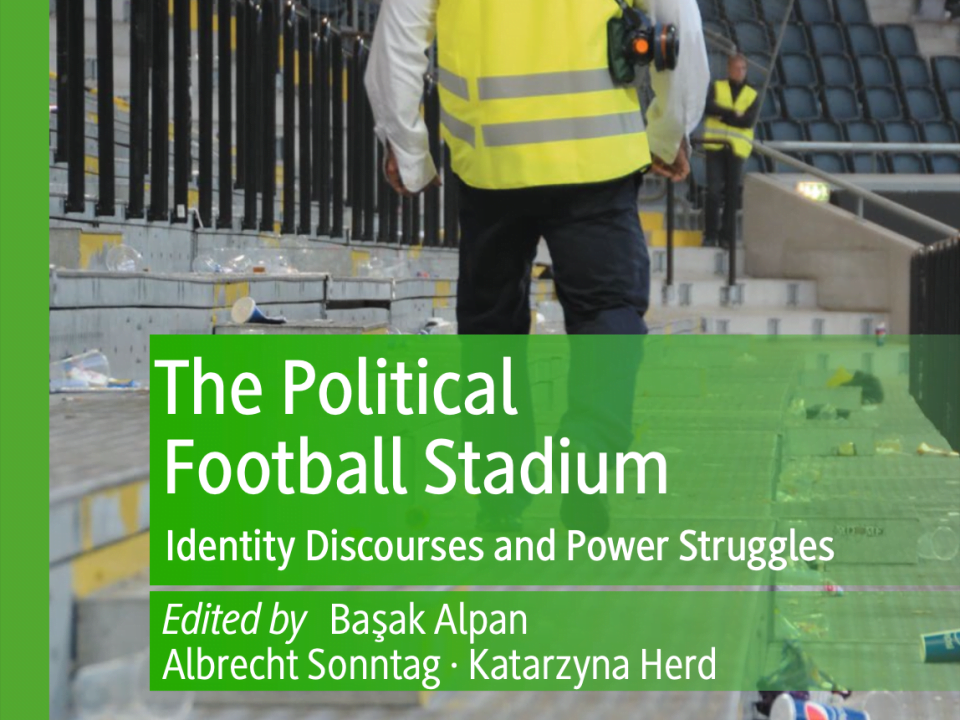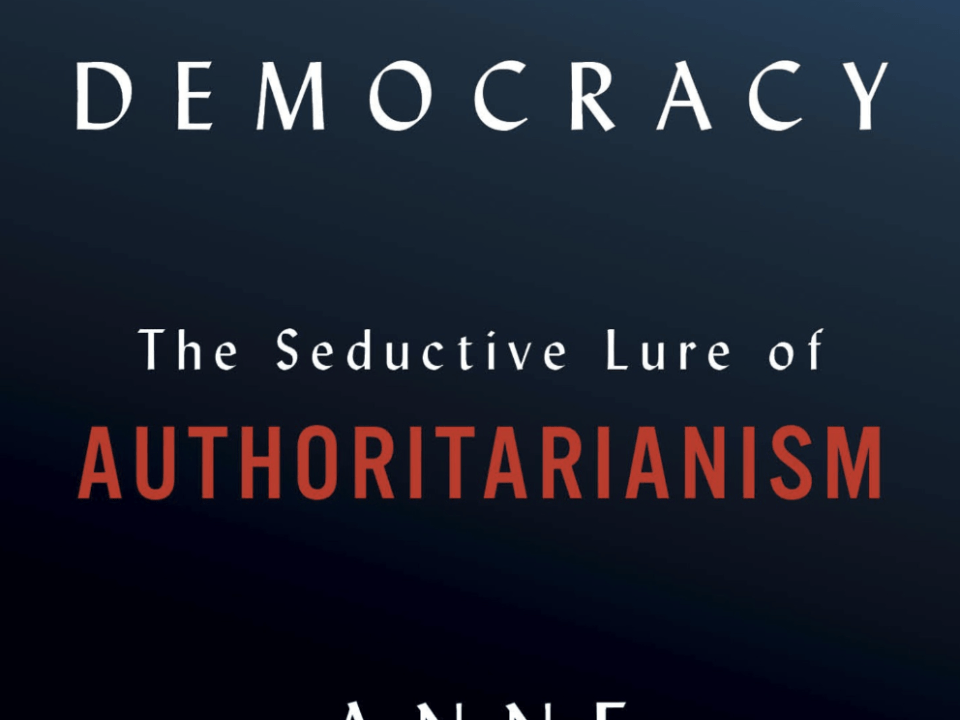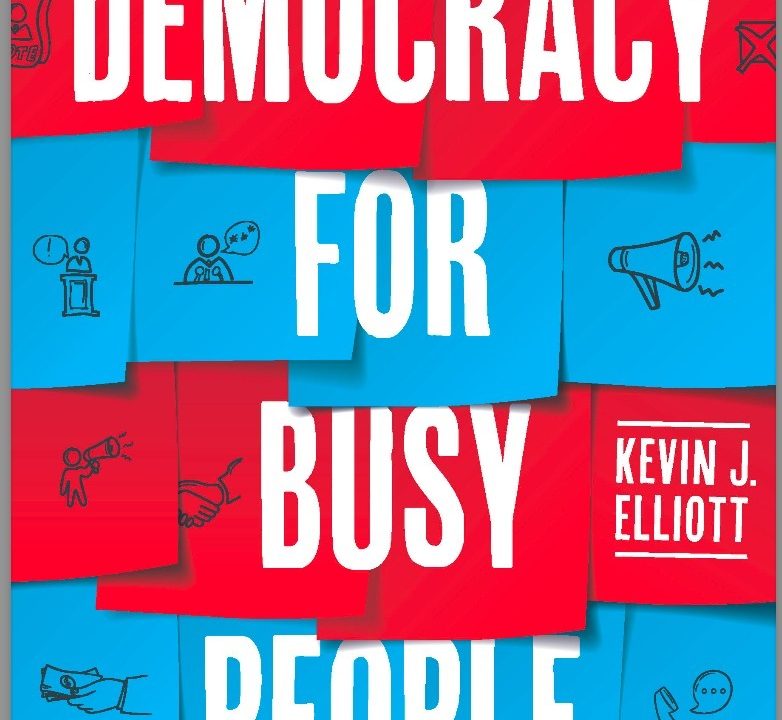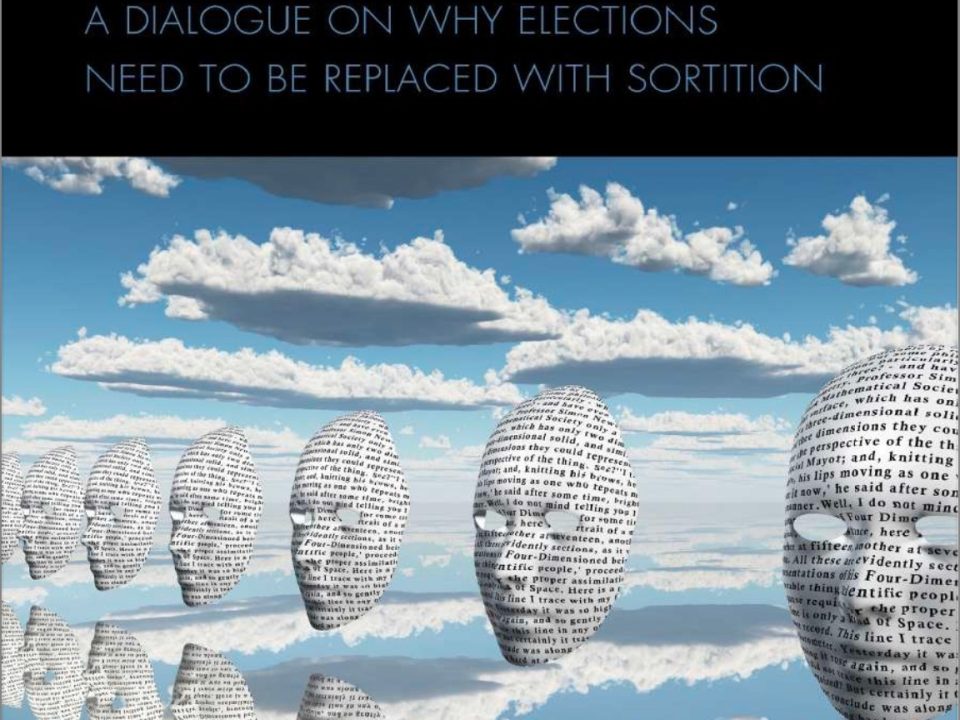Demokrasi, pada Akhirnya (Bisa) Tamat
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor-Bandung, 07022019
#BincangBuku #21
“Western democracy will survive its mid-life crisis. With luck, it will be a little chastened by it.
It is unlikely to be revived by it. This is not, after all, the end of democracy. But this is how democracy ends.”
—David Runciman. “How Democracy Ends.” (2018)
Dalam beberapa tahun terakhir ini ilmuwan politik berpikir keras. Apa yang terjadi dengan sistem demokrasi kita? Proses-proses demokratis menghasilkan sesuatu yang mengherankan—tidak seperti yang diharapkan dalam sistem politik demokrasi yang normal.
Demokrasi (dalam bahasa Yunani kuno: Demokrasia) kita tahu berawal dari gagasan di Yunani Kuno. Meskipun, seperti ditulis oleh Paul Cartledge, Democracy A Life (2016), bahwa Peraih Nobel, Amartya Sen, tidak sependapat bahwa demokrasi hanya merupakan kisah atau pencapaian khas Eropa, dan bukan hanya semata pencapaian peran budaya Yunani kuno. Bahkan B. Isakhan dan S. Stockwell yang bersama-sama menjadi editor untuk sebuah buku provokatif berjudul The Secret History of Democracy (2011), menyatakan bahwa demokrasi merupakan fenomena global yang juga berakar di Cina, Jepang, Asia Timur dan Tenggara, atau India.
Apapun itu, demokrasi kini dalam fasenya yang gamang. Sejumlah buku ditulis oleh para ilmuwan politik. Daron Acemoglu menulis Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012), Steven Levitsky dan rekannya Daniel Ziblatt menulis “How Democracies Die” (2018), James Miller mengupas kembali sejarah demokrasi dan prospeknya dalam bukunya Can Democracy Work? A Short History of Radical Idea, from Ancient Athens to Our World (2018) atau juga Robert Kuttner yang dengan galau pula mempertanyakan keberlanjutan demokrasi: “Can Democracy Survive Global Capitalism?” (2018). Semua buku itu mencerminkan adanya situasi demokrasi yang mencemaskan. Apakah yang terjadi?
Buku yang kita bincangkan kali ini adalah sebuah buku yang berani dan unik soal demokrasi. “How Democracy Ends” ditulis oleh David Walter Runciman (2018)—seorang Inggris yang mengajar ilmu politik dan sejarah di Cambridge University, dimana dia adalah Head of the Department of Politics and International Studies, Professor of Politics, dan a fellow of Trinity Hall, Cambridge.
TAK ADA YANG ABADI. Demikianlah juga dengan demokrasi sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan kemasyarakatan. Demokrasi telah selalu berhasil melalui halaman demi halaman sejarah hingga bentuknya seperti yang kita saksikan kini. Namun tidak ada seorang pun, bahkan Francis Fukuyama – yang menulis the end of history tahun 1989 – percaya bahwa demokrasi dengan segala manfaat baiknya akan abadi. Namun tidak sedikit yang pasti membayangkan bahwa sistem demokrasi adalah sistem politik final bagi makhluk homo sapien di bumi ini. Tak terbayangkan demokrasi akan tamat. Tidak ada yang berharap dan membayangkan demokrasi akan berakhir pada masa hidup kita saat ini.
Kecuali Runciman yang mempertanyakan: “Is this how democracy ends?”
Menurut Runciman, Trump bukan satu-satunya faktor yang menjadi indikasi adanya arah demokrasi yang berbeda kini. Tetapi fenomena masuknya Trump ke Gedung Putih merupakan gejala dari iklim politik yang tampaknya semakin tidak stabil, dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan saling tidak toleran, didorong oleh tuduhan liar dan intimidasi online, dialog keras kepala para pendukung masing-masing yang bebal, menenggelamkan satu sama lain dengan suara gaduh. Di banyak tempat, tidak hanya di Amerika Serikat, demokrasi mulai terlihat rusak. Dengan mengutip frase filosofis Runciman mengatakan:”… it looked like the reductio ad absurdum of democratic politics: any process that produces such a ridiculous conclusion must have gone seriously wrong somewhere along the way.” Proses apa pun yang menghasilkan kesimpulan konyol seperti itu pasti ada sesuatu yang salah.
Imajinasi politik kita terjebak dengan gambar-gambar usang seperti kegagalan demokrasi pada lanskap abad kedua puluh. Kita kembali ke tahun 1930-an atau 1970-an untuk gambaran tentang apa yang terjadi ketika demokrasi berantakan: tank di jalanan; para diktator bengis meneriakkan pesan persatuan nasional, kekerasan dan penindasan. Kepresidenan Trump memaksa orang untuk membandingkan dengan tirani masa lalu. Memang bayangan demokrasi yang dikebiri dan ditaklukkan menjadi tirani terjadi di beberapa tempat. Levitsky dan Ziblatt menuliskannya dengan baik dimana pemerintahan yang awalnya demokratis, berubah menjadi tiran meskipun melaui cara-cara yang konstitusional dan demokratis.
Dalam menilai perkembangan demokrasi ini Runciman mengambil pandangan yang berbeda. Ada bahaya lain: bahwa sementara kita mencari tanda-tanda kegagalan yang sudah dikenal, demokrasi kita malah menyimpang dan salah dengan cara-cara yang tidak kita kenal sama sekali. Ini merupakan ancaman yang lebih besar. Bagi Runciman tidak banyak kesempatan bahwa kita akan kembali ke tahun 1930-an. Kita tidak berada di fajar kedua fasisme, kekerasan dan perang dunia. Masyarakat kita sama sekali berbeda – terlalu makmur, terlalu tua, terlalu berjejaring – dan pengetahuan sejarah kolektif kita tentang apa yang salah sudah terlalu mengakar, tak mudah dilupakan.
Krisis demokrasi yang terjadi sekarang ini berbeda dengan krisis demokrasi masa lalu. Runciman menyebutkan ada tiga faktor yang membedakannya. Pertama, kekerasan politik bukan seperti apa yang terjadi pada generasi sebelumnya, baik dalam skala atau karakter. Demokrasi Barat adalah masyarakat yang pada dasarnya damai. Masih ada kekerasan, tentu saja. Tapi itu terjadi pada arena pinggiran politik kita dan relung imajinasi kita, tanpa pernah tiba di panggung utama. Kedua, ancaman bencana telah berubah. Jika prospek bencana pernah memiliki efek menggembleng, sekarang cenderung melemahkan. Krisis lingkungan misalnya merupakan ancaman yang justru akan melemahkan sistem demokrasi jika tidak dapat diatasi. Ketiga, revolusi teknologi informasi telah sepenuhnya mengubah pola permainan demokrasi. Kita menjadi tergantung pada bentuk komunikasi dan berbagi informasi yang tidak kita kontrol atau pahami sepenuhnya. Berdasarkan tiga faktor inilah buku ini disusun menjadi empat bagian dalam 430 halaman.
Semua fitur demokrasi ini konsisten dengan usianya yang semakin tua. Ketika demokrasi berakhir, kita mungkin akan terkejut dengan bentuknya yang baru. Bahkan kita mungkin tidak menyadari bahwa itu terjadi karena kita mencari di tempat yang salah. Hingga saat ini sistem demokrasi masih dianggap sistem yang terbaik, meskipun seperti pernah disampaikan Churchill yang menyebut bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan terburuk dari semua yang lain yang telah dicoba dari waktu ke waktu. Dia mengatakannya kembali pada tahun 1947—lebih setengah abad yang lalu. Apakah benar-benar tidak ada yang lebih baik untuk dicoba sejak saat itu?
Mungkin alternatifnya adalah otoritarianisme abad kedua puluh satu atau anarkisme abad kedua puluh satu—sesuatu yang tentu telah memberi pelajaran buruk. Atau sistem demokrasi diganti dengan apa yang disebut Gov-corp (h. 287). Mengubah negara demokrasi menjadi perusahaan besar (‘govcorp’), dengan CEO sendiri yang tidak dipilih. Warga menjadi tidak lebih dari sekedar pelanggan. Tidak ada lagi kebutuhan bagi penghuni (klien) untuk menaruh minat dalam politik apa pun. Bahkan, untuk melakukannya akan menunjukkan kecenderungan semi-kriminal. Jika gov-corp tidak memberikan nilai yang dapat diterima untuk pajak (sewa negara), mereka dapat memberi tahu fungsi layanan pelanggannya, dan jika perlu membawa kebiasaan mereka ke tempat lain. Gov-corp akan berkonsentrasi pada menjalankan negara yang efisien, menarik, vital, bersih, dan aman, dari jenis yang mampu menarik pelanggan. “No voice, free exit.” Atau bentuk-bentuk lain. Politik kita perlu imajinasi kreatif untuk menemukan inovasi dalam sistem politik. Tidak terjebak pada persepsi ‘kesempurnaan demokrasi modern.’
SEMUA DEMOKRASI – semua masyarakat – melihat nasib negara-negara lain dengan harapan melihat masa depan mereka sendiri. Ketika negara sahabat sedang bergerak, kita ingin tahu apakah itu berarti akan mengancam kita. Ketika demokrasi lain mulai runtuh, kita ingin tahu apakah ini peringatan akan nasib yang sama bakal menimpa kita. Politik demokrasi haus akan cerita-cerita moral, asalkan orang lain yang menjalaninya.
Pada akhir 1980-an, demikian diuraikan Runciman sebagai contoh, banyak komentator Barat memandang Jepang sebagai kekuatan yang akan datang: abad kedua puluh satu akan menjadi abad Jepang. Francis Fukuyama mengutip Jepang (bersama dengan UE) sebagai ilustrasi paling mungkin tentang apa yang dapat kita harapkan dari akhir sejarah: kemenangan demokrasi akan berubah menjadi stabil, makmur, efisien, dan hanya sedikit membosankan. Kemudian gelembung Jepang meledak – bersama dengan pasar saham Jepang – dan tiba-tiba masa depan menjadi milik pihak lain, bukan Jepang. Jepang malah menjadi dongeng tentang bahaya keangkuhan. Ketika negara itu memulai dasawarsa pertumbuhan nol dan stagnasi politiknya yang hilang, ia memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak lain. Gelembung bisa pecah di mana saja.
Yunani adalah contoh lainnya. Politisi di seluruh dunia Barat mengangkat Yunani sebagai contoh dari apa yang bisa terjadi jika negara demokrasi tidak mengendalikan utangnya. Meskipun Jepang dilanda kesulitan, Yunani juga demikian, demokrasi, faktanya terus berjalan. Hidup terus berputar.
Saat ini Jepang dan Yunani jarang dijadikan teladan oleh para politisi di negara demokrasi lain sebagai contoh nasib yang mungkin menanti kita semua. Mereka tidak lagi bekerja sebagai dongeng moralitas karena pesan mereka telah tumbuh terlalu ambigu. Jepang tetap terjebak dalam kebiasaan politik dan ekonomi namun tetap berfungsi dengan baik sebagai masyarakat yang stabil dan makmur yang menjaga warganya. Yunani lebih berantakan, namun tetap makmur dan damai menurut standar sejarah. Ada banyak, banyak tempat lebih suram dari ini. Krisis tidak pernah terselesaikan tetapi yang terburuk tidak pernah terjadi juga. Jadi pada satu sisi demokrasi mampu menjaga suatu negara tetap bisa berjalan dengan baik.
Namun ironisnya, menurut Runciman, Jepang dan Yunani yang sekarang menawarkan panduan terbaik tentang bagaimana demokrasi akan berakhir. Demokrasi yang stabil mempertahankan kapasitas luar biasa mereka untuk mencegah hal terburuk yang dapat terjadi tanpa menangani masalah yang mengancam.
“Some democracies, it seems, can absorb an awful lot of pain,” kata Runciman.
Masalah bagi demokrasi abad ke-21 adalah kebajikan-kebajikan positifnya mulai berantakan. Menghindari bencana saja tidak cukup. Agar demokrasi berkembang, ia perlu mempertahankan kemampuannya untuk menggabungkan manfaat nyata dengan pengakuan personal/pribadi (kebebasan berpendapat, berserikat, bebas dari rasa takut dsb). Menurut penilaian Runciman, itu tidak terjadi lagi. Memang masih ada manfaat dan masih ada pengakuan. Tetapi masing-masing dalam jalannya sendiri. Solusi untuk masalah bersama, yang semakin tergantung pada keahlian teknis, bergerak pada satu arah, menuju teknokrasi. Tuntutan untuk pengakuan, yang semakin diekspresikan dalam bahasa identitas pribadi, bergerak sebaliknya, menuju sesuatu yang dekat dengan anarkisme. Selama abad kedua puluh pengalaman kolektif perjuangan politik – baik untuk menyelesaikan masalah bersama maupun untuk meningkatkan pengakuan demokratis – menjaga demokrasi tetap utuh. Pada abad ke-21, pengalaman kemarahan politik yang terpencar membuatnya makin berantakan (h. 361).
Hal yang sama akan berlaku untuk sistem politik kita. Demokrasi hampir pasti akan runtuh pada saatnya. Kekuatan demokrasi adalah kemampuannya untuk memilah masalah sehingga bisa dikelola. Demokrasi masih tetap bertahan sepanjang ia mampu memberi solusi atas persoalan yang dihadapi sebuah masyarakat dan menjaga daya dukung yang tak terbatas (h. 366).
Demokrasi bukan kita. Hancurnya demokrasi bukanlah kehancuran kita. Keselamatan itu bukan keselamatan kita. Analogi antara kehidupan manusia dan kehidupan sistem politik hanya berjalan sejauh ini. Ada bahaya bahwa ketika demokrasi mulai reda, kita memberikan kompensasi yang berlebihan dalam upaya kita untuk mempertahankannya. Segala upaya kita curahkan seolah-olah hanya sistem demokrasi yang mampu menyelamatkan masyarakat, manusia.
Kita bisa menyelamatkan demokrasi dan menghancurkan dunia. Tidak ada alternatif yang lebih baik di sekitar saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada hal lain yang mungkin. Jika kita terus bersikeras bahwa demokrasi itu sakral – khususnya, jika kita berpikir bahwa mengolah pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya akan membawa kehidupan baru – kita pada akhirnya akan kehilangan pandangan tentang apa yang ingin kita capai. Kita hanya berjalan tanpa komimen, tanpa antusiasme (h 367).
Demokrasi Barat yang matang perlu berhenti mencari negara lain untuk memberi tahu mereka apa yang akan terjadi: Brasil bukan Yunani baru. Kita tidak bisa hidup secara orang lain hidup, sama seperti halnya kita tidak dapat mati sebagaimana orang lain mati. Kita harus melalui demokrasi sendiri.
Sejarah demokrasi tidak akan memiliki satu titik akhir, kecuali semua kehidupan manusia. Masih akan ada kisah sukses, terutama di tempat-tempat di mana demokrasi mampu mempertahankan janjinya. Akan ada juga malapetaka – beberapa negara demokrasi cenderung runtuh seperti yang terjadi di masa lalu. Demokrasi Brasil tampak sangat rentan. Hampir setengah dari semua warga Brazil dalam jajak pendapat baru-baru ini menyatakan dukungan untuk gagasan intervensi militer sementara untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik negara itu saat ini. Kudeta masih akan terjadi, meskipun akan semakin langka. Seorang ilmuwan politik dari Australian National University, Thomas P. Power bahkan memaparkan temuan penelitiannya yang mengindikasikan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia dan kecenderungan pemerintahan otoriter di bawah rezim Presiden Joko Widodo. Baca: Thomas P. Power (2018) Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54:3, 307-338.
Ian Wilson, seorang pengajar Ilmu Politik dan Studi Keamanan, Research Fellow dari Asian Research Center, Murdoch University, Australia menyebutnya deeply authoritarian ketika memberi komentar atas ditahannya Ahmad Dhani karena isi cuitannya. Padahal banyak cuitan lebih brutal dari itu yang dibiarkan meski sudah dilaporkan oleh pihak oposisi.
Apakah ini merupakan gejala tamatnya demokrasi? Atau gejala akan lahir jenis demokrasi yang berbeda yang kita belum tahu bentuknya seperti apa.
“This is not, after all, the end of democracy. But this is how democracy ends.” Ini bukan akhir dari demokrasi. Tapi begitulah demokrasi berakhir.
Pelajaran penting bagi kita di Indonesia adalah pentingnya mengembangkan politik yang penuh imajinasi, politik yang terbuka. Membuka pikiran untuk menemukan dan memperbincangkan sistem politik yang lebih baik. Sistem demokrasi bukan sistem yang abadi, yang sakral, yang keramat. Ia juga bisa tamat, mati. Ia bisa kita perdebatkan. Ia bisa kita campakkan. Tidak perlu kita jadikan berhala yang disembah-sembah seolah sesuatu yang paling sempurna. Ia perlu kita kritisi. Sistem demokrasi adalah alat bantu yang bisa kapanpun kita ubah jika tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan kondisi masyarakat.
Mengapa tidak?