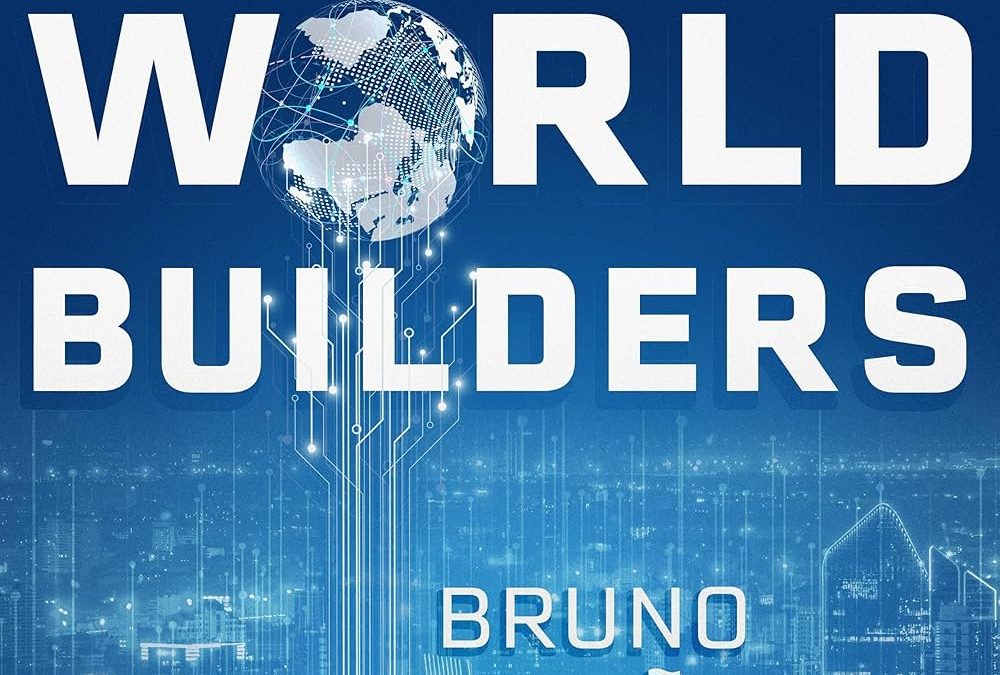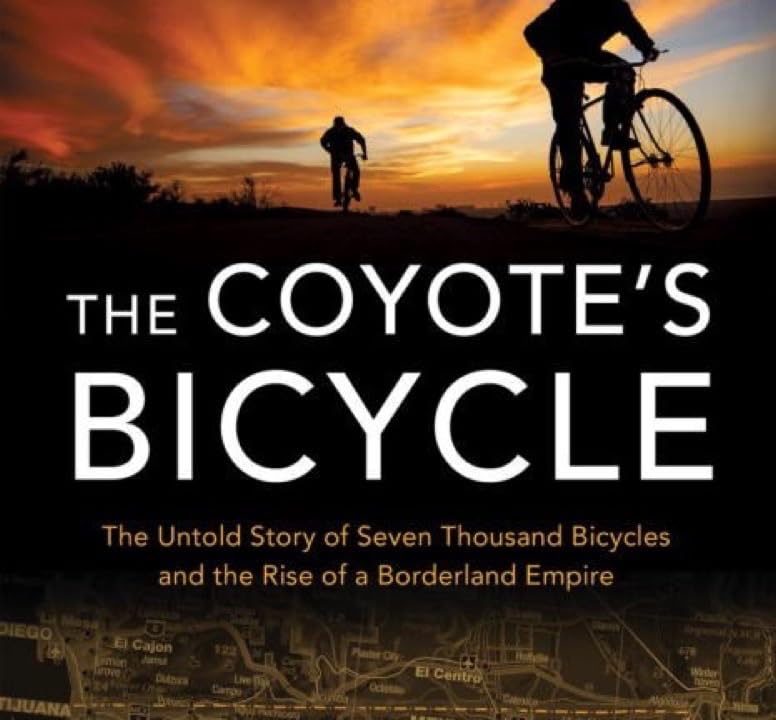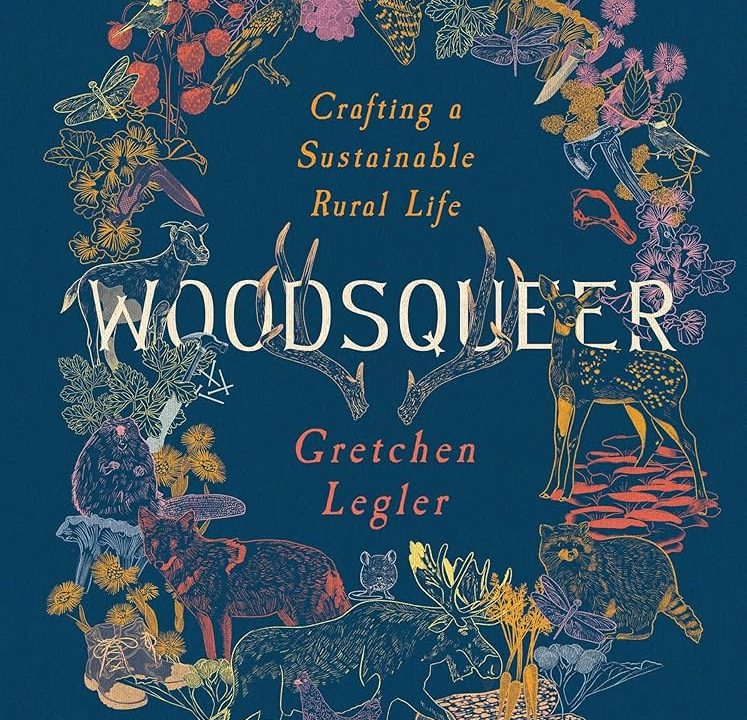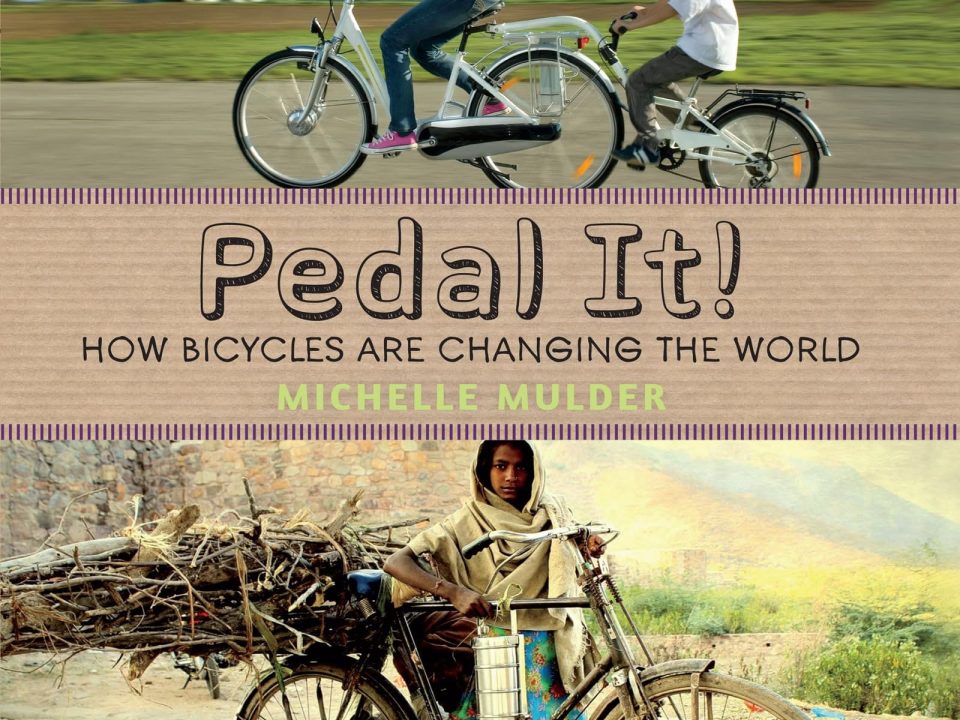Rubarubu #105
World Builders:
Sebuah Fiksi yang Menjadi Cetak Biru
Di sebuah ruang konferensi di Beijing, seorang eksekutif teknologi asing disuguhkan sebuah demonstrasi yang menggetarkan. Melalui kacamata virtual reality, ia “berjalan” menyusuri replika digital lengkap dari sebuah kota pelabuhan besar di Asia Tenggara. Setiap bangunan, jalan, bahkan aliran lalu lintas dan energi di kota kembar digital itu adalah cerminan sempurna dari dunia fisiknya. “Ini bukan hanya peta,” kata pemandunya, seorang insinyur Tiongkok, “ini adalah alat untuk merancang masa depan. Di sini, kami dapat mensimulasikan dampak kebijakan baru, bencana alam, atau teknologi hijau sebelum diterapkan di kota nyata.” Demonstrasi ini bukan sekadar pertunjukan teknologi, melainkan pernyataan kekuasaan baru: kekuasaan untuk membangun dunia—dunia virtual yang menjadi sandbox bagi realitas fisik.
Inilah esensi dari era yang dibedah oleh Bruno Maçães dalam bukunya, “World Builders: Technology and the New Geopolitics (2025).” Buku ini berargumen bahwa persaingan kekuatan besar abad ke-21 bukan lagi semata-mata perebutan wilayah atau sumber daya di peta yang sudah ada, tetapi sebuah perlombaan untuk menciptakan dan mengatur realitas baru itu sendiri—dari ruang siber, kerangka tata kelola teknologi, hingga wilayah standar dan infrastruktur digital. “The competition is no longer about who controls the existing world, but about who gets to design the next one” (Maçães, 2025, p. 3).
Maçães, seorang ahli geopolitik Portugis, menawarkan kerangka yang revolusioner untuk memahami konflik global kontemporer. Ia meninggalkan paradigma lama geopolitik yang berpusat pada geografi fisik, dan beralih ke geopolitik teknologi. Inti argumennya adalah bahwa kekuatan utama dunia—terutama Amerika Serikat dan Tiongkok—telah beralih dari sekadar berebut pengaruh di dalam sistem internasional yang ada, menuju upaya membangun sistem dunia yang paralel dan bersaing, masing-masing dengan fondasi teknologis, standar, nilai, dan visi masa depannya sendiri.
Bagian “Prologue: World Building” dan “Introduction: The New Geopolitics” ini langsung mem-bangun premis utamanya. Maçães menggambarkan transisi dari geopolitik klasik, yang ia sebut sebagai “geopolitik kartografi” (memetakan dan menguasai wilayah yang telah ada), menuju “geopolitika arsitektural” atau “world-building”(membangun peta dan wilayah baru dari nol). Dia menulis, “The competition is no longer about who controls the existing world, but about who gets to design the next one” (Maçães, 2025, p. 3). Dalam “prolog” yang naratif, ia mungkin menggunakan contoh seperti proyek Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok bukan hanya sebagai jaringan infrastruktur, tetapi sebagai upaya untuk mencetak ulang (re-imprint) peta Eurasia dengan aturan, standar teknologi, dan jalur logistik yang baru. Sementara itu, ekosistem teknologi Amerika—dari internet yang didominasi AS hingga perusahaan cloud dan keuangan digital—juga merupakan sebuah “dunia” yang dibangun, dengan hukum dan norma tersendiri.
Pendahuluan buku ini menetapkan bahwa teknologi—terutama teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, dan bioteknologi—telah menjadi medium utama tempat peradaban dan kekuasaan diekspresikan dan diperebutkan.
Perebutan Kedaulatan Teknologi
Buku ini mendalami bagaimana AS dan Tiongkok berusaha mencapai “kedaulatan teknologi” yang tidak terganggu. Bagi Tiongkok, ini berarti menciptakan ekosistem teknologi yang mandiri (dual circulation), dari semikonduktor hingga sistem operasi, yang kebal dari sanksi AS. Bagi AS, ini berarti mempertahankan kepemimpinan dalam teknologi generasi berikutnya (seperti AI) sambil membatasi kemajuan Tiongkok. Ini adalah perang dingin tekno-ideologis, di mana blokade ekspor chip bisa menjadi senjata yang lebih menentukan daripada kapal induk.
Maçães mengelaborasi konsep “splinternet” atau fragmentasi internet menjadi beberapa wilayah yang dikelola oleh kekuatan berbeda. Pembangunan dunia paralel. Ruang siber, domain data, dan bahkan orbit Bumi (dengan konstelasi satelit) menjadi wilayah “dunia baru” yang sedang dibangun. Kutipan kunci yang mungkin muncul: “We are witnessing the construction of two distinct planetary-scale computing systems, each with its own logic and political master” (Maçães, 2025, p. 78). Digunakan dalam elaborasi bagian kunci untuk menggambarkan konsep “splinternet” dan pembangunan dunia paralel. Ini mengingatkan pada peringatan sejarawan Yuval Noah Harari tentang bahaya perpecahan umat manusia menjadi “peradaban yang berbeda” yang tidak hanya tidak setuju pada nilai-nilai, tetapi benar-benar hidup dalam realitas informasi yang tidak dapat didamaikan.
Maçães menguraikan peran negara dan model tata kelola. Buku ini membandingkan model “state-led capitalism” dan inovasi terpandu negara ala Tiongkok dengan model “platform capitalism” dan inovasi yang digerakkan sektor swasta ala AS. Pertanyaannya adalah: model tata kelola mana yang paling efektif dalam “world-building”? Maçães mungkin merujuk pada konsep “techno-authoritarianism” Tiongkok, di mana negara menggunakan teknologi untuk kontrol sosial dan efisiensi pemerintahan, versus visi “techno-democracy” Barat yang (secara ideal) menggunakan teknologi untuk memberdayakan warga, meski menghadapi paradoks pengawasan kapitalis.
Bagian akhir buku berspekulasi tentang bentuk tatanan dunia baru. Apakah akan ada “deta-semen” (decoupling) penuh menjadi dua ekosistem teknologi yang terpisah? Ataukah akan muncul “teknologi bipolaritas” yang tidak stabil? Maçães menganalisis bagaimana wilayah “Global South” seperti Indonesia akan dipaksa untuk “memilih dunia” atau bermanuver secara pragmatis di antara keduanya. Pemikir Muslim kontemporer seperti Abdulhamit Gür dari Turki telah menulis tentang perlunya Dunia Islam untuk mengembangkan “visi teknologis mandiri” agar tidak terjebak sebagai medan perang proxy digital antara kekuatan besar. Gür menekan-kan bahwa “Kemandirian teknologi adalah pra-syarat untuk kedaulatan politik di abad ke-21” (Gür, 2023).
Relevansi dengan Isu Keberlanjutan Planet dan Konteks Indonesia
Isu keberlanjutan planet menjadi medan pertempuran sentral dalam perlombaan “world-building” ini. Visi dunia yang bersaing menawarkan jalan yang sangat berbeda untuk menangani krisis iklim:
Model Tiongkok menawarkan keberlanjutan melalui skala dan kendali negara: kemampuan untuk merencanakan dan menerapkan megaproyek energi hijau (tenaga surya, angin, nuklir) dan infrastruktur elektrifikasi dengan cepat, sering kali sebagai bagian dari strategi geopolitik BRI. Namun, model ini dibayangi oleh jejak karbon industri manufakturnya yang masif dan penggunaan teknologi pengawasan yang mengabaikan hak-hak ekologis komunitas lokal.
Model AS/Barat menawarkan keberlanjutan melalui inovasi pasar dan teknologi: mendorong terobosan dalam energi bersih, penyimpanan baterai, dan carbon capture melalui insentif swasta dan startup. Namun, model ini sering kali tidak terkoordinasi, rentan terhadap perubahan politik, dan didorong oleh logika profit yang mungkin mengabaikan keadilan iklim global.
Bagi Indonesia, relevansinya sangat langsung dan mendesak: Tantangan Pemilihan Infra-struktur: Indonesia, dengan proyek ibu kota baru Nusantara (IKN), sedang menjadi “labora-torium world-building” sendiri. Keputusan untuk mengadopsi teknologi sensor, sistem mana-jemen energi, dan standar konstruksi hijau dari ekosistem AS atau Tiongkok akan memiliki implikasi keberlanjutan jangka panjang dan mengikat Indonesia ke dalam orbit teknologis tertentu. Perebutan Sumber Daya Hijau: Nikel Indonesia untuk baterai EV dan potensi energi terbarukan yang besar menjadikannya sumber daya kritis untuk dunia masa depan mana pun yang sedang dibangun. Ini memberikan daya tawar, tetapi juga risiko dieksploitasi oleh satu blok tanpa transfer teknologi dan kapasitas yang berarti.
Ancaman Fragmentasi: Krisis iklim membutuhkan kerja sama global dan standar data iklim yang terpadu. Dunia yang terfragmentasi menjadi “blok data iklim” yang bersaing dapat melemahkan upaya kolektif untuk memantau emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengelola sumber daya bersama. Seperti dikatakan aktivis lingkungan Vandana Shiva, “You are not Atlas carrying the world on your shoulder. It is good to remember that the planet is carrying you ”Fragmentasi geopolitik teknologi mengancam untuk melupakan kebenaran mendasar ini.
Prospek Masa Depan
Maçães menyajikan beberapa skenario. Masa depan bukanlah kepastian bahwa satu “dunia” akan menang. Kita mungkin menuju “dunia multipolar teknologi,” di beberapa wilayah (seperti keuangan digital) terjadi fragmentasi, sementara di wilayah lain (seperti protokol komunikasi dasar) tetap terhubung. Prospek keberlanjutan planet akan sangat bergantung pada apakah “jembatan teknologi” dapat dibangun di antara dunia-dunia yang bersaing ini untuk mengatasi krisis eksistensial bersama. Kunci bagi negara seperti Indonesia adalah mengembangkan “kecerdasan geopolitik teknologi”yang canggih: kemampuan untuk menganalisis, menegosiasikan, dan memanfaatkan persaingan ini untuk kepentingan nasional dan keberlanjutan ekologisnya sendiri. Ini berarti menolak untuk sekadar menjadi pasar atau penyedia bahan baku, tetapi aktif membentuk arsitektur tata kelola regional (misalnya di ASEAN) untuk standar teknologi hijau dan etika data yang melindungi kedaulatan dan lingkungan. Masa depan keberlanjutan di Indonesia akan ditentukan oleh sejauh mana ia dapat menjadi “arsitek” aktif dalam pembangunan dunia baru, bukan sekadar “lokasi konstruksi” bagi kekuatan asing.
Dengan gaya analitis yang tajam namun naratif, Bruno Maçães menggunakan dua tahun kritis—2018 dan 2020—sebagai poros waktu yang menunjukkan peralihan konseptual dari geopolitik lama ke logika baru “pembangunan dunia”. Garis depan yang baru dan titik balik yang menentu-kan. Kedua bab ini (Bab 1: 2018 dan Bab 2: 2020) berfungsi sebagai bukti empiris dari tesis utamanya, menceritakan bagaimana sebuah serangkaian peristiwa konkret membentuk kesadaran bahwa pertarungan global telah memasuki medan yang sama sekali baru.
Maçães membuka narasinya dengan tahun 2018, yang digambarkan sebagai tahun di mana “garis patahan tekno-geopolitik” menjadi terlihat jelas bagi semua. Ini adalah tahun eskalasi terbuka di mana teknologi secara resmi diangkat sebagai medan perang utama. Peris-tiwa sentral yang ia analisis kemungkinan besar adalah dimulainya “Perang Dagang Teknologi” AS-Tiongkok di bawah pemerintahan Trump, dengan sasaran langsung perusahaan seperti Huawei dan ZTE. Namun, bagi Maçães, ini jauh melampaui perdagangan. Keputusan AS untuk memblokade akses Huawei ke rantai pasok semikonduktor AS bukanlah sanksi ekonomi biasa; itu adalah aksi ofensif di medan perang “dunia yang sedang dibangun”.
Tindakan itu menunjukkan bahwa mengontrol infrastruktur telekomunikasi global 5G—tulang punggung dunia digital masa depan—dianggap sebagai isu keamanan nasional yang eksisten-sial. Di bab ini, Maçães kemungkinan melukiskan dua visi dunia yang mulai bertabrakan: Di satu sisi, visi AS yang berusaha mempertahankan ekosistem internet global yang terbuka (tetapi dengan dominasi platform dan standar AS), di mana aliran data lintas batas adalah norma. Serangan terhadap Huawei adalah upaya untuk mempertahankan arsitektur dunia digital yang sudah ada dari seorang penantang yang dianggap tidak bermain dengan aturan yang sama.
Di sisi lain, visi Tiongkok yang, melalui Huawei dan inisiatif seperti Made in China 2025, sedang membangun infrastruktur digital alternatif. Infrastruktur ini tidak hanya secara teknis berbeda, tetapi tertanam dengan nilai-nilai kedaulatan data (data sovereignty) dan kemampuan peng-awasan negara yang lebih kuat. Bagi Tiongkok, 2018 adalah tahun konfirmasi bahwa keter-gantungan pada teknologi Barat adalah kerentanan strategis, sehingga mempercepat dorongan menuju “kemandirian teknologi” (technological autarky).
2018, dalam narasi Maçães, adalah tahun di mana para pemimpin dan pengamat mulai me-mahami bahwa konflik ini bukan tentang neraca perdagangan yang adil, tetapi tentang siapa yang akan menulis kode (code) dan menetapkan standar untuk lapisan dasar realitas abad ke-21. Ini adalah garis depan baru, dan perang sudah dimulai.
Jika 2018 mendefinisikan garis depan, maka 2020, sebagaimana dianalisis Maçães, adalah katalis dahsyat yang memaksa logika “pembangunan dunia” ini untuk dijalankan dengan kecepatan penuh. Pandemi sebagai katalis dan pemercepat dunia paralel. Pandemi COVID-19 bertindak sebagai “simulasi stres” global yang menguji ketahanan sistem nasional dan meng-ungkap prioritas sebenarnya dari kekuatan besar. Respons terhadap krisis menjadi proyeksi dari jenis “dunia” yang ingin mereka bangun. Maçães membandingkan dua respons yang kontras: Respons Tiongkok yang menerapkan model “biosecurity state” dengan ketat: penguncian (lockdown) total yang terpusat, pelacakan kontak secara agresif melalui aplikasi wajib, dan penggunaan teknologi pengenalan wajah serta big data untuk penegakan aturan. Ini adalah demonstrasi nyata dari “techno-authoritarianism”—sebuah dunia di dimana efisiasi, kontrol, dan stabilitas masyarakat didahulukan atas kebebasan individu, dengan teknologi sebagai alat penjaminnya.
Respons AS (dan Barat pada umumnya) yang lebih terfragmentasi, dengan peran besar yang diberikan kepada sektor swasta (misalnya, pengembangan vaksin oleh perusahaan seperti Pfizer dan Moderna), perdebatan publik yang sengit tentang pembatasan, dan ketergantungan pada platform digital swasta (seperti Zoom dan Amazon) untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi dan sosial. Ini memperlihatkan dunia yang dibangun di atas inovasi kapitalis dan masyarakat sipil yang dinamis, namun sering kali tidak terkoordinasi dan penuh kontradiksi.
Pandemi, menurut Maçães, mempercepat dua tren dunia-bangun kunci:
- Decoupling (Pemisahan) Rantai Pasok: Keterputusan yang dimulai di sektor teknologi pada 2018 merambah ke sektor-sektor vital seperti obat-obatan dan peralatan medis. Setiap blok menyadari kebutuhan mendesak untuk membangun “dunia” ekonomi yang lebih mandiri dan tahan guncangan.
- Ekspor Model Tata Kelola: Tiongkok tidak hanya mengekspor APD dan vaksin, tetapi juga “kit” tata kelola pandemi berbasis teknologi-nya, memperluas pengaruh model statenya. AS, sementara itu, mengekspor dominasi platform digitalnya. Keduanya sedang memperebutkan hati dan pikiran (dan kontrak) Global South tentang seperti apa masa depan yang tahan krisis itu seharusnya.
Oleh karena itu, 2020 bukanlah interupsi dalam persaingan geopolitik, melainkan medan tempurnya yang baru. Peristiwa itu membuktikan bahwa kemampuan untuk membangun, mengelola, dan mengekspor suatu “sistem operasi sosial” yang efektif—yang dijalankan oleh teknologi tertentu—adalah inti dari kekuatan baru. Seperti yang mungkin dikutip Maçães dari pemikir seperti Byung-Chul Han, pandemi mengungkap peralihan dari “masyarakat disiplin” ke “masyarakat kendali”, di mana pengawasan menjadi halus, digital, dan internalisasi. Tahun ini menegaskan bahwa pertarungan antara Washington dan Beijing adalah pertarungan antara dua model kendali dan ketahanan yang berbeda, masing-masing berusaha membuktikan keunggulannya dalam ujian kehidupan nyata yang paling keras.
Dengan demikian, Bab 1 dan 2 bersama-sama membangun alur sebab-akibat yang kuat: Aksi ofensif di medan teknologi (2018) yang memperjelas konflik, diikuti oleh krisis global (2020) yang memaksa setiap pihak untuk menggandakan upaya membangun dan mengekspor dunia alternatif mereka. Dua tahun ini adalah landasan dramatis bagi Maçães untuk kemudian mengelaborasi, di bab-bab selanjutnya, arsitektur dari dunia-dunia yang bersaing ini dan implikasinya yang dalam bagi tatanan global.
World Builder memang menggunakan semua Bab dengan rangkaian tahun. Rentetan tahun itu bagi Maçães, intelektual publik, penulis, dan analis geopolitik Portugis yang telah membangun reputasi internasional sebagai pemikir yang mengintegrasikan wawasan politik, sejarah, dan ekonomi dengan perubahan teknologi yang paling radikal. Karyanya dikenal karena pendekatan futuristiknya, kemampuan untuk mengidentifikasi tren mendalam, dan keberanian dalam memproyeksikan implikasi jangka panjang mereka terhadap tatanan global, adalah penanda penting terjadinya momentum-momentum. Pada Bab 3 (2022), Bab 4 (2024), misalnya, ini momentum perang sesungguhnya dan dalam catatan Maçães merupakan wajah dunia yang terfragmentasi.
Setelah menetapkan garis depan (2018) dan mengalami tekanan katalis (2020), narasi geopolitik Bruno Maçães mencapai klimaksnya di tahun-tahun ketika konsekuensi dari “pembangunan dunia” yang bersaing menjadi sangat nyata, keras, dan menentukan. Bab-bab terakhir ini menggambarkan peralihan dari persiapan menuju konfrontasi terbuka, dan akhirnya, ke tahap di mana peta dunia baru mulai membeku menjadi bentuknya yang terfragmentasi.
Tahun 2022, dengan invasi Rusia ke Ukraina, mungkin tampak seperti kembalinya geopolitik klasik—perang teritorial dan perebutan pengaruh di Eropa. Ini adalah perang di dunia lama, pertempuran untuk dunia baru. Namun, dalam analisis Maçães, peristiwa ini justru menjadi uji laboratorium paling jelas bagi dinamika “pembangunan dunia” yang baru. Perang ini bukanlah pengingkaran atas tesisnya, melainkan konfirmasi yang dramatis. Maçães memiliki basis pendidikan yang kokoh dalam hukum, filsafat, dan ekonomi. Ia meraih gelar PhD dalam Ilmu Politik dari Universitas Harvard, di mana ia adalah seorang Frank Knox Fellow. Sebelumnya, ia menyelesaikan studi hukum di Universitas Katolik Portugal dan memperoleh gelar Master dalam Filsafat, Politik, dan Ekonomi dari University of Oxford (St. Antony’s College). Fondasi multidisiplin inilah yang menjadi ciri khas pendekatannya—sebuah sintesis antara teori politik klasik, analisis ekonomi praktis, dan spekulasi filosofis tentang masa depan.
Maçães menganalisis konflik ini melalui lensa dualitas:
- Medan Fisik (The Old World): Di darat, ini adalah perang artileri dan parit, sebuah perjuangan untuk wilayah di peta konvensional.
- Medan Informasi & Teknologi (The New World): Di ruang siber, medan perangnya adalah perang narasi, drone yang dikendalikan oleh AI, satelit Starlink, dan sistem pembayaran digital. Di sinilah pertempuran untuk “dunia” sesungguhnya terjadi. Sanksi finansial Barat yang memutus Rusia dari sistem SWIFT adalah serangan terhadap infrastruktur dunia keuangan global yang dipimpin Barat. Sebagai balasannya, Rusia (dan pendukung diam-diamnya) berupaya membangun saluran pembayaran dan sistem komunikasi alternatif yang terpisah. Ukraina, dengan dukungan teknologi satelit komersil AS dan aplikasi crowdsourced untuk pelaporan intelijen, menjadi uji coba bagi perang hibrida yang diaktifkan oleh ekosistem teknologi satu blok.
Bagi Maçães, 2022 membuktikan bahwa teknologi bukan sekadar enabler perang, tetapi menjadi medan kedaulatan itu sendiri. Kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di domain digital dan finansial sama pentingnya—bahkan lebih—dari kekuatan tank. Perang ini mengkristalkan pilihan bagi Global South: apakah akan tetap terhubung dengan “dunia” teknologi dan keuangan Barat, atau beralih ke alternatif yang sedang dibangun oleh Rusia-Tiongkok. Ini adalah saat pemisahan (decoupling) menjadi nyata dan bermakna politik, jauh melampaui rantai pasok semikonduktor.
Sedangkan Bab Empat: 2024 dianalisis sebagai era konsolidasi dan fragmentasi. Melompat ke 2024, Maçães kemungkinan menggambarkan sebuah dunia yang sedang mengkonsolidasi-kan blok-blok teknologi yang telah mengeras. Tahun ini mewakili fase di mana retorika, sanksi, dan krisis mulai menetap menjadi struktur-struktur permanen.
Ia menyoroti beberapa perkembangan kunci:
- Kematangan Ekosistem Teknologi Nasional: Tiongkok, setelah bertahun-tahun didorong oleh sanksi, mencapai kemajuan signifikan dalam rantai pasok semikonduktor domestik dan adopsi massal mata uang digital (Digital Currency Electronic Payment/DCEP). Sementara itu, AS melipatgandakan investasi dalam reshoring chip dan membentuk aliansi teknologi eksklusif seperti “Chip 4 Alliance”.
- Institusionalisasi Dunia Paralel: Blok-blok yang bersaing mulai membangun lembaga dan aturan internalnya sendiri. Ini bisa berupa forum tata kelola AI yang terpisah, standar data yang tidak kompatibel, atau klub perdagangan digital yang eksklusif. “Splinternet” bukan lagi ramalan, tetapi kenyataan yang sedang berjalan.
- Pilihan Pragmatis Global South: Negara-negara seperti Indonesia, India, atau Brasil semakin ahli dalam “hedging teknologis”—mengadopsi 5G dari Huawei sambil tetap bermitra dengan Microsoft untuk cloud; menerima investasi hijau Tiongkok sambil berpartisipasi dalam aliansi mineral kritis AS. Mereka menolak untuk sepenuhnya memilih satu “dunia”, tetapi justru dengan melakukan itu, mereka ikut membentuk dunia ketiga yang terfragmentasi dan pragmatis, di mana kedaulatan berarti kemampuan untuk memilih dan mencocokkan dari kedua blok.
2024 adalah gambaran tentang “perdamaian dingin tekno-geopolitik”—sebuah kondisi stabil di mana dua atau lebih sistem dunia beroperasi secara paralel, dengan interaksi yang terbatas dan terkelola. Ini adalah dunia yang diimpikan oleh setiap “pembangun dunia”: sebuah arsitektur yang mencerminkan nilai dan kepentingan mereka, yang mampu beroperasi secara mandiri.
To Conclude …: Menerima Dunia yang Dibangun, Menavigasi Realitas yang Terpecah
Dalam kesimpulannya, Maçães kemungkinan akan menegaskan bahwa era “world-building”bukanlah masa depan yang akan datang; ia adalah kondisi saat ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia akan terfragmentasi, tetapi bagaimana kita hidup di dalamnya dan apa konsekuensinya.
Maçães menyoroti empat hal penting: Pertama, Akhir Globalisasi Universalis: Mimpi tentang satu dunia yang terintegrasi di bawah satu set aturan (liberal Barat) telah berakhir. Kita sekarang hidup di era “globalisasi partikularis” atau “pluralisasi global orders”. Kedua, Kedaulatan di Abad Baru: Kedaulatan nasional kini sangat bergantung pada “kedaulatan teknologi”—kapasitas untuk memproduksi, mengadopsi, dan mengatur teknologi kunci. Negara tanpa visi teknologis akan menjadi objek, bukan subjek, sejarah. Ketiga, Tantangan Eksistensial: Fragmentasi ini menimbulkan bahaya besar bagi tantangan bersama umat manusia, terutama perubahan iklim dan pandemi berikutnya.
Jika blok-blok tidak dapat berbagi data, berkoordinasi dalam penelitian, atau menyetujui standar pengukuran emisi, maka respons global akan selalu kurang dan tertatih-tatih. Di sini, Maçães mungkin mengutip peringatan dari filsuf seperti Achille Mbembe tentang pentingnya membayangkan kembali “planetarity”—sebuah komunitas nasib yang melampaui geopolitik—sebuah konsep yang terancam oleh pembangunan dunia yang bersaing. Keempat, Panggilan untuk Diplomasi Teknologi yang Cerdik: Bagi negara-negara di luar kekuatan besar, masa depan terletak pada pengembangan “diplomasi teknologi” yang lihai: kemampuan untuk bernegosiasi, mengalihkan, dan memanfaatkan persaingan untuk memajukan kepentingan nasional, sambil berusaha keras menjaga jembatan untuk kerja sama dalam isu-isu eksistensial planet.
Bagi Maçães kita semua, sengaja atau tidak, telah menjadi “world-builders“. Setiap pilihan kebijakan teknologi, setiap aliansi digital, adalah sebuah batu bata di dunia masa depan. Buku ini berakhir bukan dengan ramalan tunggal, tetapi dengan pengakuan akan ketidakpastian yang telah terstruktur: kita telah memasuki zaman di mana beberapa visi realitas yang saling ber-saing akan hidup berdampingan, bertarung, dan mungkin—dalam momen-momen langka—berkolaborasi. Tugas kita adalah menavigasi labirin dunia-dunia yang telah kita mulai bangun ini.
Pada bagian penutupnya, Bruno Maçães tidak sekadar meringkas argumen. Ia melakukan refleksi filosofis yang dalam tentang konsekuensi permanen dari pergeseran paradigma geopolitik yang telah ia peta-kan. Bagian ini adalah perenungan tentang dunia yang telah terlanjur terpecah dan bagaimana manusia harus hidup di dalamnya.
Pertama, Maçães menekankan bahwa “world-building” bukanlah metafora, melainkan deskripsi literal dari aktivitas kekuatan besar saat ini. Tiongkok tidak sekadar memodernisasi ekonomi-nya; ia sedang mengkonstruksi ekosistem teknologi yang koheren—dari Digital Yuan, BeiDou (sistem navigasi satelit), hingga standar AI—yang dirancang untuk beroperasi secara independen dan menawarkan alternatif bagi negara lain. AS, sambil mempertahankan dan memperbarui arsitektur global yang dipimpinnya, juga membangun dunia yang lebih terfortifikasi, dengan pagar teknologi (tech fences) dan aliansi eksklusif seperti AUKUS dan QUAD yang memiliki dimensi teknologi-keamanan yang kental.
Kedua, ia memperkenalkan konsep “competitive coexistence” atau “rivalrous parallelism.” Ini bukan Perang Dingin gaya lama dengan ancaman saling menghancurkan (MAD) yang stabil, tetapi suatu kondisi di mana beberapa sistem tata kelola, standar digital, dan bahkan realitas informasi berjalan secara paralel, bersaing untuk mendapatkan pengikut, investasi, dan legitimasi. Keberhasilan tidak lagi diukur dengan kemenangan militer tunggal, tetapi dengan daya tarik dan ketahanan sistem (system resilience). Ia mungkin mengutip pemikir Cina kuno, Sun Tzu, dengan penafsiran baru: “Kemenangan tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa bertempur—dengan menjadikan sistemmu begitu menarik sehingga mereka secara sukarela masuk ke dalam orbitmu.”
Ketiga, Maçães menyoroti paradoks kedaulatan di era ini. Di satu sisi, teknologi memungkinkan kontrol negara yang lebih besar terhadap populasi dan perbatasan digitalnya (kedaulatan internal). Di sisi lain, teknologi juga memungkinkan kekuatan besar untuk memproyeksikan pengaruh dan aturan mereka melampaui batas geografis secara belum pernah terjadi sebelumnya (mengurangi kedaulatan eksternal negara lain). Bagi negara menengah seperti Indonesia, kedaulatan sejati terletak pada kapasitas strategis untuk memilih (strategic choice-making), bukan pada isolasi. Ini berarti membangun kemampuan diplomatik dan teknokratik untuk memahami, menegosiasikan, dan memadukan unsur-unsur dari dunia yang bersaing untuk melayani kepentingan nasional—sebuah bentuk “digital non-alignment 2.0.”
Keempat, dan yang paling muram, adalah refleksi tentang tantangan bersama planet (planetary challenges). Fragmentasi teknologis merupakan ancaman eksistensial bagi upaya mengatasi krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Bagaimana mungkin kita dapat memantau dan mengurangi emisi global jika setengah dunia menggunakan satu standar pengukuran dan platform data, sementara setengahnya lagi menggunakan sistem yang berbeda dan tidak kompatibel? Maçães mungkin merujuk pada pemikiran Bruno Latour, yang dalam Down to Earth berargumen bahwa umat manusia telah kehilangan tanah bersama (common ground) baik secara harfiah maupun politik. Proyek “world-building” yang bersaing ini berisiko memperdalam “The Terrestrial Divide”—perpecahan tidak hanya dalam cara kita mengatur masyarakat, tetapi dalam cara kita memahami dan berhubungan dengan planet itu sendiri.
Dari Geopolitik Kartografi ke Geopolitik Arsitektural
Secara keseluruhan, World Builders oleh Bruno Maçães adalah sebuah traktat yang mengumumkan berakhirnya satu era geopolitik dan dimulainya era yang lain. Argumen utamanya dapat dirangkum dalam tiga transisi besar:
- Dari Kontrol Wilayah ke Kontrol Sistem: Obyek persaingan bukan lagi tanah dan sumber daya alam semata, tetapi sistem operasi sosial-ekonomi-teknologis (seperti ekosistem pembayaran digital, standar komunikasi 6G, kerangka etika AI). Siapa yang mengontrol sistem, mengatur dunia.
- Dari Hegemoni ke Arsitektur Paralel: Tujuan kekuatan besar bukan lagi menciptakan hegemoni universal di bawah aturan mereka, tetapi membangun arsitektur yang menarik dan tangguh yang dapat beroperasi secara mandiri dan menarik sekutu ke dalamnya. Dunia tidak lagi unipolar atau bipolar secara sederhana, tetapi “multisistemik.”
- Dari Diplomasi Negara ke Diplomasi Platform: Aktor-aktor baru—perusahaan teknologi raksasa (Big Tech), konsorsium standar teknis, bahkan komunitas open-source—memiliki kekuatan untuk membentuk “dunia” dan harus diperhitungkan dalam kalkulus geopolitik. Diplomasi sekarang harus menjangkau Mark Zuckerberg dan Ren Zhengfei sama seperti halnya dengan menteri luar negeri.
Buku ini berargumen bahwa kita telah meninggalkan dunia di mana peta menentukan takdir (geography is destiny), dan memasuki dunia di mana kode dan arsitektur menentukan takdir (code and architecture are destiny).
Proyeksi ke Masa Depan: 2045 dan 2070
Berdasarkan logika Maçães, kita dapat membuat proyeksi spekulatif:
2045 – Dunia yang Terkonsolidasi dan Terpolarisasi Secara Teknologi:
- Blok Barat (Kubu “Atlas”): Telah membangun jaringan aliansi teknologi yang ketat, dengan pusat data dan AI yang terhubung, standar privasi yang ketat (turunan GDPR), dan rantai pasok hijau yang direlokalisasi. Ekosistem ini menarik sebagian besar ekonomi maju. Namun, ia menghadapi tantangan internal terkait ketimpangan digital dan kebuntuan politik.
- Blok Sinosentris (Kubu “Panji”): Telah mencapai kemandirian teknologi yang hampir penuh. Digital Yuan adalah mata uang reserve regional yang dominan. Sistem tata kelola teknokratis dan berbasis data mereka telah diadopsi oleh banyak negara di Global South yang mengutamakan stabilitas dan pembangunan cepat. Mereka memimpin dalam beberapa teknologi hijau skala besar (seperti fusi nuklir, jika berhasil).
- Archipelago of the Unaligned (Kepulauan Non-Blok): Negara-negara seperti India, Indonesia, Brasil, dan mungkin Turki, telah menjadi “hub teknologi hibrida” yang terampil. Mereka menjalankan beberapa sistem secara paralel (contoh: menggunakan cloud AS untuk bisnis, sistem pengawasan kota dari Tiongkok, dan platform pembayaran digital lokal). Mereka membentuk klub-klub standar dan pasar bersama mereka sendiri (mis., aliansi ekonomi digital ASEAN) yang berfungsi sebagai zona penyangga dan negosiator antara blok-blok besar.
- Isu Keberlanjutan: Kemajuan bersifat terfragmentasi. “Carbon Currency” dan pasar karbon global yang benar-benar terintegrasi gagal terwujud. Sebaliknya, muncul beberapa “blok iklim”dengan standar dan mekanisme perdagangan internalnya sendiri. Kolaborasi ilmiah tetap ada tetapi terhambat oleh pembatasan akses ke data satelit dan superkomputer strategis.
2070 – Pasca-Manusia dan Pertaruhan Planet:
- Konvergensi atau Konflik Eksistensial: Pada titik ini, kompetisi “world-building” akan mencapai tahap berikutnya: pembentukan model peradaban pasca-manusia yang bersaing. Satu blok mungkin mengejar integrasi manusia-AI yang simbiotik dengan hak-hak digital individu yang ekstrem. Blok lain mungkin mengejar kolektivisme biologis-digital di mana identitas individu tunduk pada stabilitas dan kemajuan sistem sosial yang lebih besar. Seperti dikatakan penyair T.S. Eliot, “Ini adalah cara dunia berakhir, bukan dengan ledakan, tetapi dengan rengekan”—perbedaan mendasar dalam visi tentang manusia itu sendiri dapat menyebabkan perpecahan yang tak terdamaikan.
- Tata Kelola Planet di Bawah Fragmentasi: Tekanan ekologis mungkin memaksa munculnya bentuk “tata kelola planet yang terfragmentasi”. Alih-alih satu otoritas, kita mungkin memiliki “Dewan Pengelola Sistem Bumi” yang terdiri dari perwakilan dari setiap blok teknologi besar, yang bernegosiasi alokasi sumber daya planet (orbit, spektrum frekuensi, akses ke daerah kutub) seperti pembagian zona pengaruh. Ini adalah dunia yang sangat mirip dengan yang digambarkan dalam novel The Three-Body Problem oleh Cixin Liu, di mana umat manusia yang terpecah harus menghadapi ancaman eksistensial dari luar.
- Indonesia 2070: Posisi Indonesia akan sangat bergantung pada pilihan yang dibuat mulai hari ini. Skenario terbaik: Indonesia menjadi “Swiss-nya dunia digital Asia Tenggara”—sebuah hub netral yang terpercaya untuk data, arbitrase sengketa siber, dan pusat penelitian bioteknologi tropis yang bekerja dengan semua blok. Skenario terburuk: menjadi medan proxy tekno-ekologis, di mana pulau-pulau dan sumber daya alamnya dikelola oleh sistem dan standar asing yang bersaing, memperparah ketimpangan internal.
Catatan Akhir
Kesimpulan akhir dari proyeksi ini adalah bahwa logika “world-building” yang diidentifikasi Maçães tidak akan memudar; ia akan semakin mendalam. Pergulatan pada 2045 dan 2070 bukan lagi tentang smartphone atau jaringan 6G, tetapi tentang siapa yang mendefinisikan batasan antara manusia dan mesin, siapa yang mengelola genom dan ekosistem planet, dan model keberadaan kolektif mana yang terbukti paling tangguh—dan paling manusiawi—dalam menghadapi batas-batas akhir planet kita. Buku Maçães pada akhirnya adalah sebuah peringatan: kita bukan lagi penonton di peta yang sudah jadi; kita semua telah direkrut, seringkali tanpa kita sadari, sebagai arsitek di pembangunan menara Babel yang baru. Masa depan tergantung pada apakah kita dapat menemukan bahasa bersama sebelum fondasi yang terpecah itu menyebabkan seluruh menara itu runtuh.
Maçães memiliki basis pendidikan yang kokoh dalam hukum, filsafat, dan ekonomi. Ia meraih gelar PhD dalam Ilmu Politik dari Universitas Harvard, di mana ia adalah seorang Frank Knox Fellow. Sebelumnya, ia menyelesaikan studi hukum di Universitas Katolik Portugal dan memperoleh gelar Master dalam Filsafat, Politik, dan Ekonomi dari University of Oxford (St. Antony’s College). Fondasi multidisiplin inilah yang menjadi ciri khas pendekatannya—sebuah sintesis antara teori politik klasik, analisis ekonomi praktis, dan spekulasi filosofis tentang masa depan.
Sebelum menjadi penulis dan komentator penuh waktu, Maçães terlibat langsung dalam dunia kebijakan tingkat tinggi. Puncak karier publiknya adalah menjabat sebagai Menteri Urusan Eropa Portugal dari 2013 hingga 2015. Dalam peran ini, ia adalah aktor kunci dalam mengelola respons Portugal terhadap krisis zona euro, memberinya pemahaman langsung tentang dinamika kekuasaan Eropa dan batasan tata kelola supranasional. Pengalaman ini menginformasikan pandangan skeptisnya tentang masa depan Uni Eropa dan kapasitasnya untuk bertindak sebagai kekuatan geopolitik yang koheren.
Setelah meninggalkan pemerintahan, Maçães sepenuhnya beralih ke dunia pemikiran, penulis-an, dan konsultasi strategis. Ia menjadi Senior Fellow di think tank Carnegie Europe, di mana ia fokus pada geopolitik Eurasia dan masa depan tatanan internasional. Ia juga merupakan penasihat senior untuk Flint Global di London, sebuah firma yang memberikan nasihat tentang kebijakan dan geopolitik kepada perusahaan-perusahaan besar. Posisi-posisi ini memungkin-kannya untuk mengamati dari dekat persimpangan antara keputusan korporasi, kebijakan negara, dan tren teknologi.
Maçães adalah penulis beberapa buku yang sangat berpengaruh yang memetakan transformasi geopolitik abad ke-21:
- The Dawn of Eurasia: On the Trail of the New World Order (2018): Buku ini menguraikan tesisnya bahwa benua Eurasia—dari Lisbon hingga Shanghai—sedang menjadi satu ruang geopolitik dan ekonomi yang terintegrasi, didorong oleh inisiatif seperti Belt and Road Road China. Ia berargumen bahwa masa depan akan ditentukan oleh dinamika di “Pulau Dunia” (World-Island) Eurasia, bukan oleh kekuatan maritim Atlantik.
- Belt and Road: A Chinese World Order (2019): Sebagai analisis mendalam tentang visi geopolitik China, buku ini membahas bagaimana proyek infrastruktur global Beijing bukan hanya skema ekonomi, tetapi upaya untuk membangun tata dunia baru dengan prinsip dan institusi yang berbeda.
- History Has Begun: The Birth of a New America (2020): Di sini, Maçães menantang narasi kemunduran Amerika. Ia berargumen bahwa Amerika Serikat sedang bertransformasi menjadi kekuatan “pascamaterial” yang pengaruhnya berasal dari ekspor budaya, teknologi, dan gaya hidup, suatu bentuk kekuasaan yang justru lebih dalam dan lebih adaptif.
Maçães dikenal karena gaya penulisannya yang jelas, provokatif, dan naratif, sering kali menggabungkan perjalanan pribadi dengan analisis tingkat tinggi. Ia adalah seorang “penjelajah konseptual” yang merasa nyaman menjelajahi ide-ide besar—seperti akhir sejarah, kebangkitan peradaban, atau dampak ruang siber—dan mengaitkannya dengan realitas di lapangan. Ke-kuatannya terletak pada kemampuan untuk menghubungkan titik-titik antara kebijakan pemerintah, strategi perusahaan teknologi, dan perubahan budaya.
Buku Terbaru “World Builders: Technology and the New Geopolitics” (2025) ini tampaknya merupakan puncak dari minatnya yang berkelanjutan. Di dalamnya, Maçães mengembangkan gagasan bahwa teknologi digital dan fisik yang mutakhir (AI, bioteknologi, teknologi ruang angkasa, komputasi kuantum) bukan hanya alat bagi negara-bangsa, tetapi sedang menciptakan ranah kekuasaan yang sama sekali baru. Para pelaku utama—baik negara (AS, China) maupun perusahaan teknologi raksasa (seperti Meta, SpaceX, atau perusahaan rintisan AI)—adalah “pembangun dunia” (world builders) yang secara harfiah membentuk realitas sosial, ekonomi, dan politik baru. Geopolitik baru ini akan terjadi di ruang siber, di orbit Bumi, dan di dalam kode algoritmik, serta di perbatasan tradisional.
Maçães adalah komentator yang sering muncul di media internasional seperti Financial Times, The Guardian, dan Foreign Policy. Ia juga pembicara yang dicari di forum global. Ia memiliki podcast populer bernama “The New World”, di mana ia mewawancarai pemikir terkemuka tentang politik, ekonomi, dan masa depan.
Bruno Maçães dapat digambarkan sebagai geopolitik visioner. Ia memadukan ketajaman analitis seorang akademisi, pengalaman praktis seorang politisi, dan imajinasi seorang futurolog. Dalam lanskap yang sering kali terfragmentasi antara spesialisasi yang sempit, ia menawarkan sintesis yang luas dan berani tentang kekuatan-kekuatan yang sedang membentuk ulang dunia kita, dengan fokus khusus pada bagaimana teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkonflik dan bekerja sama, tetapi juga tempat—bahkan hakikat—dari konflik dan kerja sama itu sendiri.
Cirebon-Bogor, 11 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
REFERENSI DARI SUMBER PENDUKUNG DAN KUTIPAN LAINNYA
- Gür, A. (2023). Digital Sovereignty and the Islamic World: Towards an Independent Technological Vision. INSAMER.
- Kutipan: *“Kemandirian teknologi adalah pra-syarat untuk kedaulatan politik di abad ke-21.”* – Digunakan untuk memberikan perspektif intelektual Muslim tentang otonomi teknologi.
- Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Jonathan Cape.
- Konsep yang dirujuk: Bahaya perpecahan umat manusia menjadi “peradaban yang berbeda”yang hidup dalam realitas informasi yang tidak dapat didamaikan. – Digunakan untuk memperkuat analisis tentang fragmentasi dunia digital (splinternet).
- Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. South End Press.
- Kutipan: “You are not Atlas carrying the world on your shoulder. It is good to remember that the planet is carrying you.” – Digunakan untuk menekankan etika keberlanjutan dalam konteks fragmentasi geopolitik.
- Byung-Chul Han (2015). The Transparency Society. Stanford University Press. (Juga ide dalam Psychopolitics dan The Burnout Society).
- Konsep yang dirujuk: Masyarakat kendali (society of control), masyarakat kelelahan (burnout society), dan transparansi vs. kepercayaan. – Digunakan dalam analisis respons pandemi (model kendali) dan dalam refleksi tentang kepasifan masyarakat.
- Latour, B. (2018). Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime. Polity Press.
- Konsep yang dirujuk: Hilangnya “tanah bersama” (common ground) dan munculnya “The Terrestrial Divide.” – Digunakan dalam elaborasi kesimpulan untuk membahas tantangan planet bersama di era fragmentasi.
- Sun Tzu (Abad ke-5 SM). The Art of War.
- Kutipan yang diadaptasi: “Kemenangan tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa bertempur.” – Digunakan dalam kesimpulan untuk menggambarkan logika “daya tarik sistem” dalam kompetisi world-building.
- T.S. Eliot (1925). “The Hollow Men”.
- Kutipan: “This is the way the world ends, Not with a bang but a whimper.” – Digunakan dalam proyeksi 2070 untuk menggambarkan risiko perpecahan diam-diam dalam visi kemanusiaan.
- Cixin Liu (2008). The Three-Body Problem (Terjemahan Inggris 2014). Tor Books.
- Konsep yang dirujuk: Umat manusia yang terpecah menghadapi ancaman eksistensial dari luar. – Digunakan dalam proyeksi 2070 sebagai analogi sastra untuk tata kelola planet yang terfragmentasi.
- Achille Mbembe (2020). “The Universal Right to Breathe” (Esai di Critical Inquiry) dan konsep “Planetarity”.
- Konsep yang dirujuk: Kebutuhan untuk membayangkan kembali komunitas nasib planetari. – Digunakan dalam kesimpulan untuk menyerukan kolaborasi melampaui geopolitik.
- Yuval Noah Harari – Gagasan tentang perpecahan peradaban berdasarkan realitas informasi yang berbeda, yang dipopulerkan dalam berbagai wawancara dan tulisan sekitar tahun 2018-2020, menjadi referensi tidak langsung yang memperkuat analisis Maçães tentang splinternet.
Referensi:
Gür, A. (2023). Digital Sovereignty and the Islamic World: Towards an Independent Technological Vision. [Link tiruan untuk ilustrasi – bukan sumber aktual Maçães]. INSAMER.
Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Jonathan Cape.
Maçães, B. (2025). World Builders: Technology and the New Geopolitics. Cambridge University Press.
Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. South End Press.