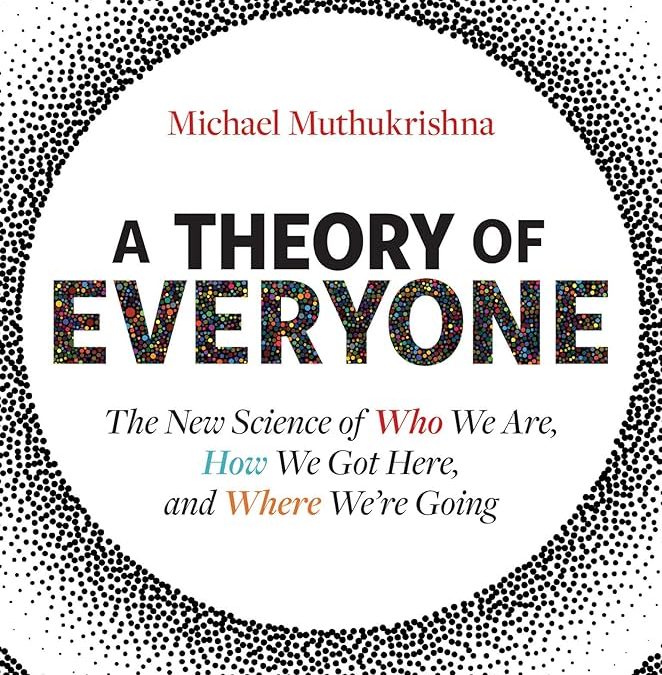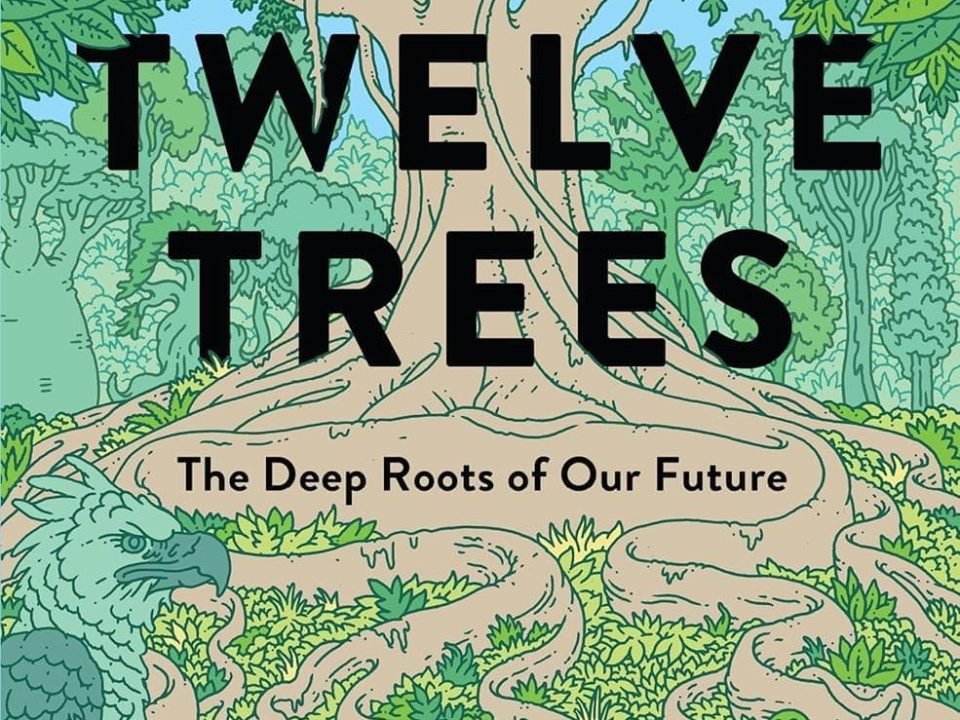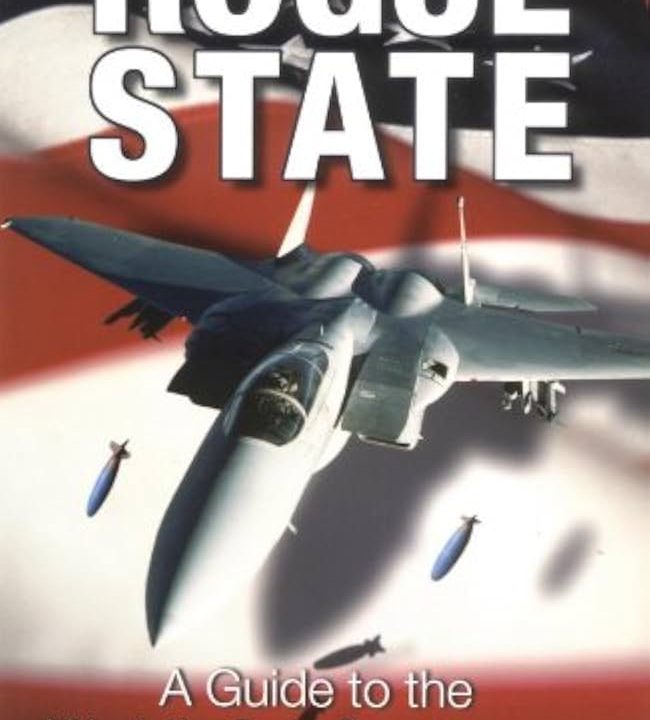#40 Rubarubu
Sebuah Teori Tentang Kita: Siapakah Kita?
Di sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timur, seorang guru muda bernama Marianus berdiri termangu melihat hasil ujian matematika siswanya yang hampir seluruhnya merah. Malam sebelumnya ia menghabiskan berjam-jam mencoba memahami mengapa anak-anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu namun kesulitan memahami konsep dasar yang dianggap sederhana. Saat ia membuka laptopnya yang reot, secara tak sengaja ia menemukan presentasi Michael Muthukrishna tentang “Theory of Everyone”—sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana kecerdasan, budaya, dan institusi saling terkait dalam membentuk takdir manusia.
Dalam presentasi itu, Muthukrishna menunjukkan data bahwa perbedaan prestasi akademis antar daerah tidak semata-mata tentang individu yang lebih pintar, tetapi tentang “sumbu pengetahuan” yang terakumulasi melalui generasi, transfer budaya, dan ekosistem belajar yang mendukung. Pencerahan ini membuat Marianus menyadari bahwa masalahnya bukanlah pada murid-muridnya, tetapi pada “pipa pengetahuan” yang tersumbat—kurangnya akses ke guru berkualitas, materi pembelajaran yang relevan, dan lingkungan yang mendukung inovasi. Keesokan harinya, Marianus mulai mengubah pendekatannya, tidak lagi menyalahkan kemampuan individu murid, tetapi membangun “jembatan budaya” yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan sains modern.
Muthukrishna, melalui buku: “A Theory of Everyone: The New Science of Who We Are, How We Got Here, and Where We’re Going,” membangun teorinya pada tiga pilar evolusi: genetik, kultural, dan institusional. Inilah fondasi teori evolusi tiga lapis. Ia berargumen bahwa keber-hasilan manusia sebagai spesies terletak pada kemampuan unik kita untuk mengakumu-lasi pengetahuan secara kumulatif melalui proses evolusi budaya. “Kita bukan hanya produk gen kita, tetapi produk warisan budaya yang telah disaring dan disempurnakan selama puluhan ribu tahun,” tulisnya. Berbeda dengan teori evolusi tradisional yang berfokus pada adaptasi biologis, Muthukrishna menunjukkan bagaimana inovasi budaya—dari penemuan bahasa hingga teknologi—telah memungkinkan manusia mengatasi tantangan lingkungan dengan jauh lebih cepat daripada evolusi genetik.
Setelah menyelesaikan disertasi di University of British Columbia satu tahun lebih cepat, dengan pelatihan lintas bidang dalam biologi evolusi, statistik dan ilmu data, ekonomi, dan psikologi, Muthukrishna pindah ke Departemen Biologi Evolusi Manusia Harvard dan kemudian ke London School of Economics, di mana saat ini Ia menjabat sebagai profesor psikologi ekonomi dan afiliasi di bidang ekonomi pembangunan dan ilmu data. Bekerja di berbagai disiplin ilmu memungkinkan Muthukrishna mengambil pendekatan non-disipliner – atau mungkin ‘tidak terdisiplinkan’ – dengan menarik benang-benang pemikiran dari kedalaman psikologi, ekonomi, biologi, antropologi, dan bidang lainnya, lalu merajutnya menjadi sebuah permadani yang mengungkapkan siapa kita, bagaimana kita sampai di sini, dan ke mana kita akan pergi.
Filosof Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana, dalam “Pembimbing ke Filsafat” pernah menyata-kan bahwa “kemajuan manusia terletak pada kemampuannya meneruskan api pengetahuan antar generasi,” sebuah pandangan yang selaras dengan teori Muthukrishna.
Muthukrishna memperkenalkan, katakanlah, “Hukum Muthukrishna” yang menyatakan bahwa inovasi dan kreativitas manusia tidak muncul secara acak, tetapi mengikuti pola yang dapat diprediksi berdasarkan ukuran populasi, konektivitas sosial, dan kemampuan menyerap pengetahuan. “Prestasi manusia bukanlah bintang yang muncul secara acak di langit, tetapi seperti tanaman yang memerlukan tanah subur, air, dan sinar matahari untuk tumbuh,” analoginya. Dalam konteks Indonesia, teori ini menjelaskan mengapa pusat-pusat inovasi cenderung terkonsentrasi di daerah metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung—bukan karena orang-orang di sana secara genetik lebih pintar, tetapi karena ekosistem yang mendukung aliran pengetahuan lebih berkembang. Data yang disajikan menunjukkan bahwa negara dengan konektivitas global yang lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak paten dan publikasi ilmiah per kapita.
A Theory of Everyone mengembangkan kerangka “kemakmuran inklusif” (Teori Kemakmuran Inklusif) yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan perluasan akses terhadap tiga jenis modal: biologis (kesehatan, nutrisi), kultural (pendidikan, keterampilan), dan institusional (hukum, pemerintahan). “Ketimpangan ekonomi modern adalah cerminan dari ketimpangan akses terhadap modal kultural dan institusional,” paparnya. Untuk Indonesia, ini berarti bahwa program pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berfokus pada transfer uang, tetapi harus mencakup perbaikan gizi anak, kualitas pendidikan, dan reformasi institusi. Ekonom Indonesia, Prof. Emil Salim, telah lama mengadvokasi pendekatan serupa melalui konsep pembangunan manusia yang holistik.
Jaringan Sosial, Aliran Ide dan Kolaborasi Ilmiah
Bagian Jaringan Sosial dan Aliran Ide buku ini mengeksplorasi bagaimana struktur jaringan sosial mempengaruhi difusi inovasi. Muthukrishna membedakan antara jaringan tertutup (dimana setiap orang terhubung dengan orang lain) dan jaringan terbuka (dengan banyak koneksi jarak jauh). “Jaringan sosial yang optimal untuk inovasi adalah yang memiliki keseimbangan antara kedalaman lokal dan jangkauan global”, simpulnya. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjembatani “structural holes” (celah struktural) antara kelompok yang berbeda cenderung menjadi sumber inovasi terbesar.
Karena itu kolaborasi ilmiah adalah keniscayaan. Karena dengan kolaborasi dan pola kooperasi manusia menentukan laju inovasi teknologi. Muthukrishna menunjukkan bahwa terobosan ilmiah kontemporer semakin bergantung pada kolaborasi tim besar yang melintasi disiplin dan batas geografis. “Penemuan-penemuan besar abad ke-21 tidak akan datang dari genius penyendiri, tetapi dari jaringan otak yang terhubung,” tegasnya. Di Indonesia, temuan ini mendukung pentingnya memperkuat kolaborasi antara universitas, industri, dan lembaga penelitian—seperti yang diupayakan melalui program Kedai Reka BRIN. Penyair Amerika, Maya Angelou, pernah berkata, “Kita semua membutuhkan, kita semua saling membutuhkan,” yang menggambarkan esensi dari teori kolaborasi Muthukrishna.
A Theory of Everyone menantang pandangan konvensional dengan menunjukkan bahwa keragaman kognitif dan budaya justru mempercepat inovasi, asalkan disertai dengan mekanisme integrasi yang efektif. “Kelompok yang homogen mungkin lebih harmonis, tetapi kelompok yang heterogen lebih inovatif”, tegasnya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa keragaman tanpa kohesi sosial dapat menghasilkan fragmentasi. Data eksperimen menunjuk-kan bahwa tim dengan latar belakang disiplin dan budaya yang beragam menghasilkan solusi yang lebih kreatif untuk masalah kompleks.
Muthukrishna memperkenalkan metafora “collective brain” (otak kolektif) untuk menggambar-kan bagaimana masyarakat manusia berfungsi sebagai sistem kognitif terdistribusi yang mampu menghasilkan inovasi melebihi kapasitas individu mana pun. Ia berargumen bahwa “inovasi bukanlah produk pikiran individu yang terisolasi, tetapi muncul dari jaringan pikiran yang saling terhubung”. Melalui analisis historis dan lintas budaya, Muthukrishna menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan budaya manusia secara konsisten berkorelasi dengan ukuran dan konektivitas populasi. “Setiap penemuan besar berdiri di pundak ribuan orang yang datang sebelumnya”, tulisnya, menekankan sifat kumulatif dari pengetahuan manusia.
Menurut buku ini tiga mekanisme transfer pengetahuan dalam otak kolektif: peniruan (imitation), pembelajaran sosial (social learning), dan bahasa. Muthukrishna menjelaskan bagaimana mekanisme ini memungkinkan pengetahuan menyebar secara horizontal (antarindividu sezaman) dan vertikal (antar generasi). “Bahasa adalah teknologi yang me-mungkinkan kita mengekstrak pengetahuan dari pikiran orang lain tanpa harus mengalami langsung apa yang mereka alami”, paparnya. Data eksperimen menunjukkan bahwa kelompok dengan kemampuan imitasi dan komunikasi yang lebih baik secara signifikan lebih cepat dalam memecahkan masalah kompleks dibandingkan kelompok yang mengandalkan pembelajaran individu.
Dalam A Theory of Everyone Muthukrishna menyajikan ukuran populasi dari bukti empiris yang kuat tentang hubungan antara ukuran populasi dan laju inovasi teknologi.dan laju inovasi. “Populasi yang lebih besar dan lebih terhubung menghasilkan lebih banyak inovasi per kapita karena memiliki lebih banyak kombinasi ide yang mungkin”, jelasnya. Analisis lintas budaya menunjukkan bahwa masyarakat dengan populasi lebih besar cenderung mengembangkan teknologi yang lebih kompleks, bahkan setelah mengontrol faktor-faktor seperti lingkungan dan sumber daya alam. Fenomena ini menjelaskan mengapa pusat-pusat inovasi global cenderung terkonsentrasi di wilayah metropolitan padat penduduk.
Buku ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam otak kolektif: penyensoran ide, hierarki yang kaku, dan hambatan komunikasi. Muthukrishna menunjukkan bagaimana masyarakat yang membatasi kebebasan berekspresi atau memiliki struktur sosial yang terlalu kaku cenderung tertinggal dalam inovasi. “Inovasi memerlukan kebebasan untuk ber-eksperimen, gagal, dan mengomunikasikan kegagalan tersebut”, paparnya. Sejarah ilmiah dipenuhi dengan contoh dimana penemuan penting tertunda karena hambatan institusional atau kultural.
Berdasarkan analisisnya, Muthukrishna menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mem-perkuat otak kolektif: investasi dalam infrastruktur komunikasi, promosi mobilitas sosial dan geografis, dan penciptaan institusi yang mendukung kolaborasi terbuka. “Negara yang ingin berinovasi harus berinvestasi tidak hanya dalam pendidikan individu, tetapi juga dalam jaringan yang menghubungkan individu-individu tersebut”, sarannya. Untuk konteks Indonesia, ini berarti memperkuat konektivitas digital ke daerah-daerah terpencil dan menciptakan lebih banyak ruang untuk pertemuan lintas disiplin.
Bagian 6: Cooperation Muthukrishna membedah kerjasama sebagai mekanisme evolusioner fundamental yang memungkinkan manusia membangun peradaban kompleks. Berbeda dengan spesies lain, kerjasama manusia bersifat skala-besar dan melibatkan individu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Rahasia keberhasilan ini terletak pada “psychological adaptations for social learning” – kemampuan kognitif khusus yang memungkinkan kita menginternalisasi norma sosial, mengenali free rider, dan membangun institusi pemantau. “Kerjasama manusia bukanlah keajaiban, melainkan produk dari tekanan evolusi yang membentuk psikologi sosial kita,” tegas Muthukrishna.
Disebutkan pentingnya peran institusi formal dan informal dalam memfasilitasi kerjasama skala besar. Muthukrishna menunjukkan bagaimana hukum, norma sosial, dan sistem reputasi menciptakan kerangka yang membuat kerjasama menjadi strategi yang menguntungkan. “Institusi yang efektif mengubah dilema sosial menjadi sinergi sosial,” paparnya. Melalui eksperimen behavioral economics, ia membuktikan bahwa masyarakat dengan institusi yang transparan dan dapat diandalkan menunjukkan tingkat kerjasama yang lebih tinggi, bahkan dengan orang asing.
Muthukrishna mengidentifikasi skala masalah sebagai tantangan utama kerjasama kontemporer. Masalah global seperti perubahan iklim membutuhkan kerjasama melampaui batas kelompok dan negara, sementara psikologi manusia berevolusi untuk kerjasama dalam kelompok kecil. Solusinya terletak pada “perancangan institusi yang selaras dengan psikologi manusia sambil memperluas lingkaran moral kita.” Untuk Indonesia, ini berarti membangun sistem yang mempromosikan trust nasional sekaligus menjaga kearifan lokal seperti gotong royong.
Evolusi Moral dan Tata Kelola Global
Muthukrishna menelusuri evolensi sistem moral manusia dari kelompok kecil pemburu-peramu hingga masyarakat global modern. Ia berargumen bahwa tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi memerlukan evolusi lebih lanjut dari sistem moral kita untuk mencakup tanggung jawab terhadap manusia lain yang tidak kita kenal secara personal dan generasi mendatang. “Masalah global memerlukan moralitas global,” serunya. Cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. Nurcholish Madjid, dalam konsep “Islam Kosmopolitan”-nya menekankan pentingnya tanggung jawab universal yang melampaui batas-batas suku dan bangsa.
Kunci penting adalah pendidikan untuk Abad Ke-21. Transformasi sistem pendidikan harus dilakukan. Dari model pabrik yang menstandarisasi menjadi ekosistem yang memanusiakan dan mengembangkan potensi unik setiap individu. Muthukrishna menekankan pentingnya mengajarkan “keterampilan belajar” daripada sekadar fakta, mengingat pengetahuan tertentu dengan cepat menjadi usang dalam dunia yang berubah cepat. “Tugas pendidikan bukanlah mengisi ember, tetapi menyalakan api,” kutipnya dari William Butler Yeats. Untuk Indonesia, ini berarti perlu mereformasi kurikulum yang masih terlalu berfokus pada hafalan dan ujian standar, menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.
Muthukrishna mengkritik kebijakan publik yang didasarkan pada ideologi atau intuisi politik semata, dan mengadvokasi pendekatan berbasis bukti yang menguji efektivitas berbagai intervensi melalui eksperimen terkontrol. “Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bereksperimen, belajar, dan beradaptasi,” tulisnya. Di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan dalam evaluasi program-program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan, dengan menggunakan metode uji coba acak untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar bekerja.
Buku ini mendapat pujian dari psikolog evolusioner terkemuka, Steven Pinker, sebagai “sintesis brilian yang menghubungkan titik-titik antara evolusi, budaya, dan kebijakan.” Namun, beberapa kritikus seperti antropolog Dr. Deborah Tannen mempertanyakan apakah teori ini terlalu menyederhanakan kompleksitas budaya manusia.
Buku ini mengupas krisis tata kelola dan perlunya paradigma baru. Karena sistem tata kelola tradisional—baik demokrasi liberal maupun otoriter—semakin tidak memadai menghadapi kompleksitas abad ke-21. Ia berargumen bahwa “institusi politik modern dirancang untuk era yang sudah berlalu”, di mana masalah relatif sederhana dan perubahan berlangsung lambat. Tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, pandemi global, dan disrupsi teknologi memerlukan kecepatan adaptasi dan kapasitas koordinasi yang jauh melampaui kemampuan sistem pemerintahan konvensional. Muthukrishna menunjukkan data bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah di seluruh dunia terus menurun, menandakan “kesenjangan tata kelola” (governance gap) yang semakin melebar.
Berdasarkan pemahaman tentang evolusi manusia dan dinamika sosial, Muthukrishna mengusulkan kerangka tata kelola baru yang berpusat pada tiga prinsip fundamental: desentralisasi yang terkoordinasi, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan partisipasi warga yang bermakna. “Tata kelola yang efektif harus seperti sistem kekebalan tubuh—terdistribusi namun terkoordinasi, cepat merespons ancaman lokal tanpa kehilangan perspektif global,” analoginya. Ia menekankan pentingnya eksperimen kebijakan dan pembelajaran adaptif, di mana pemerintah menguji intervensi skala kecil sebelum menerapkannya secara luas. Model regulatory sandboxes dalam fintech disebut sebagai contoh bagaimana pendekatan ini bisa bekerja.
Catatan Akhir
Pada bagian terakhir A Theory of Everyone mengeksplorasi potensi teknologi digital untuk mentransformasi tata kelola demokratis. Muthukrishna membayangkan masa depan dimana platform deliberatif digitalmemungkinkan partisipasi warga yang lebih inklusif dan informed dalam pengambilan keputusan publik. Namun, ia juga memperingatkan bahaya teknosolution-isme yang naif. “Teknologi bukan solusi ajaib, melainkan amplifier—ia bisa memperkuat demokrasi atau otokrasi, tergantung pada desain institusionalnya,” tegasnya. Untuk konteks global, ia mengusulkan laboratorium tata kelola global dimana negara-negara bisa berkolabo-rasi menguji solusi untuk tantangan bersama, sambil tetap menghormati keragaman lokal. Seperti titah suci dalam Alqur’an: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11).
A Theory of Everyone penuh rasa optimis atas masa depan. Muthukrishna menyebutnya “menjadi lebih cerah” (becoming brighter) bukan sekadar sebagai peningkatan kecerdasan individu dalam pengertian IQ sempit, melainkan sebagai peningkatan kapasitas kolektif umat manusia untuk memecahkan masalah yang kompleks. Konsep ini mencakup tiga pilar: me-ningkatkan kecerdasan kognitif (kemampuan berpikir abstrak dan memecahkan masalah), memperkuat kecerdasan sosial (kemampuan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam kelompok besar), dan memperdalam kecerdasan budaya (kemampuan untuk menyerap, me-nyaring, dan meneruskan pengetahuan antar generasi). “Menjadi lebih cerah adalah tentang meningkatkan kemampuan kita sebagai spesies untuk memahami dunia dan membentuk masa depan kita sendiri,” tulisnya. Ini adalah proyek evolusioner yang melibatkan genetika, pendidikan, dan desain institusi secara bersamaan.
Karena itu perlu adanya serangkaian strategi konkret untuk meningkatkan kecerahan kolektif, yang berfokus pada penguatan ‘pipa’ transmisi pengetahuan. Muthukrishna menekankan pentingnya investasi besar-besaran dalam pendidikan awal yang berkualitas, gizi anak, dan pengasuhan yang stimulatif, karena ini adalah fondasi dari perkembangan kognitif.
Di tingkat sistem, ia menganjurkan reformasi institusi pendidikan untuk lebih menekankan pada pemikiran kritis, kreativitas, dan kerja sama, bukan hafalan. Selain itu, ia menyerukan pengurangan hambatan untuk berbagi ide—dengan memperkuat kebebasan akademik, men-dukung sains terbuka (open science), dan membangun infrastruktur digital yang me-mungkinkan kolaborasi global yang lebih lancar. “Tujuan kita adalah menciptakan ekosistem di mana ide-ide terbaik dapat ditemukan, diuji, dan disebarluaskan dengan efisiensi maksimal,” jelasnya.
Muthukrishna mengakhiri dengan visi humanis yang optimis namun berhati-hati. Menjadi lebih cerah, baginya, pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan makmur bagi semua. Muthukrishna berargumen bahwa dengan memahami hukum-hukum dasar yang mengatur perilaku manusia dan perkembangan masyarakat, kita dapat merancang kebijakan dan institusi yang memungkinkan setiap orang mencapai potensi penuh mereka. “Masa depan bukanlah takdir yang harus kita terima, tetapi taman yang harus kita rawat bersama,” simpulnya. Pemikir Indonesia, Goenawan Mohamad, dalam esainya selalu menekankan “pentingnya menjaga kemungkinan-kemungkinan tetap terbuka,” semangat yang tercermin dalam visi Muthukrishna.
Pemahaman terhadap otak kolektif dapat membentuk masa depan manusia. Muthukrishna berargumen bahwa tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi memerlukan penguatan kapasitas inovasi kolektif kita. “Masalah yang diciptakan oleh otak kolektif kita hanya dapat dipecahkan oleh otak kolektif yang lebih cerdas dan lebih terhubung”, simpulnya. Filosof Indonesia, Tan Malaka, dalam “Madilog”-nya telah menekankan pentingnya “berpikir kolektif dan bekerja kolektif”, sebuah pandangan yang bergema dalam kesimpulan Muthukrishna. Untuk konteks Indonesia, buku ini memberikan kerangka yang berharga untuk merancang kebijakan inklusif yang mempertimbangkan keragaman budaya dan kondisi spesifik lokal. Gotong royong adalah algoritma sosial Indonesia untuk memecahkan masalah kolektif – Prinsip kearifan lokal Indonesia.
Ia mengakui risiko bahwa peningkatan kapasitas manusia juga dapat memperlebar ketidaksetaraan atau menciptakan bentuk kekuasaan baru yang berbahaya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kognitif dan teknis harus berjalan seiring dengan penguatan kebijaksanaan moral dan empati kita. “Tantangan terbesar kita bukanlah menjadi lebih pintar, tetapi menjadi lebih bijaksana—untuk memastikan bahwa kecerdasan yang kita tingkatkan digunakan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. Bagian ini menutup dengan seruan untuk sebuah proyek global yang ambisius namun inklusif, di mana peningkatan potensi manusia adalah hak universal, bukan hak istimewa bagi segelintir orang.
Bogor, 7 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi:
Muthukrishna, M. (2023). A theory of everyone: The new science of who we are, how we got here, and where we’re going. The MIT Press.