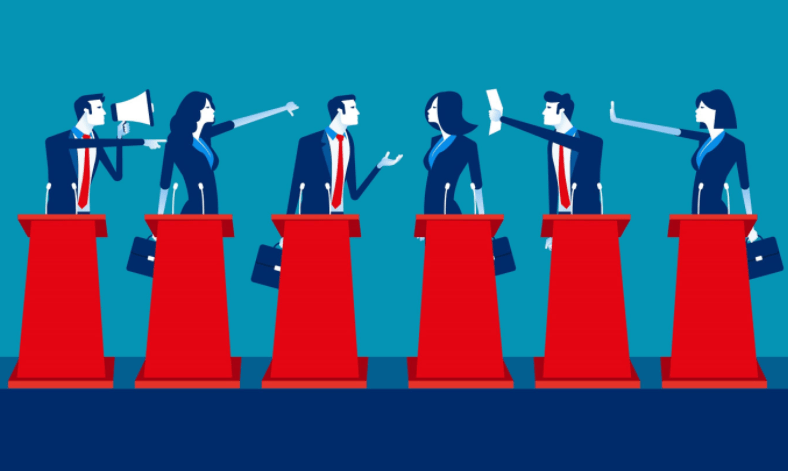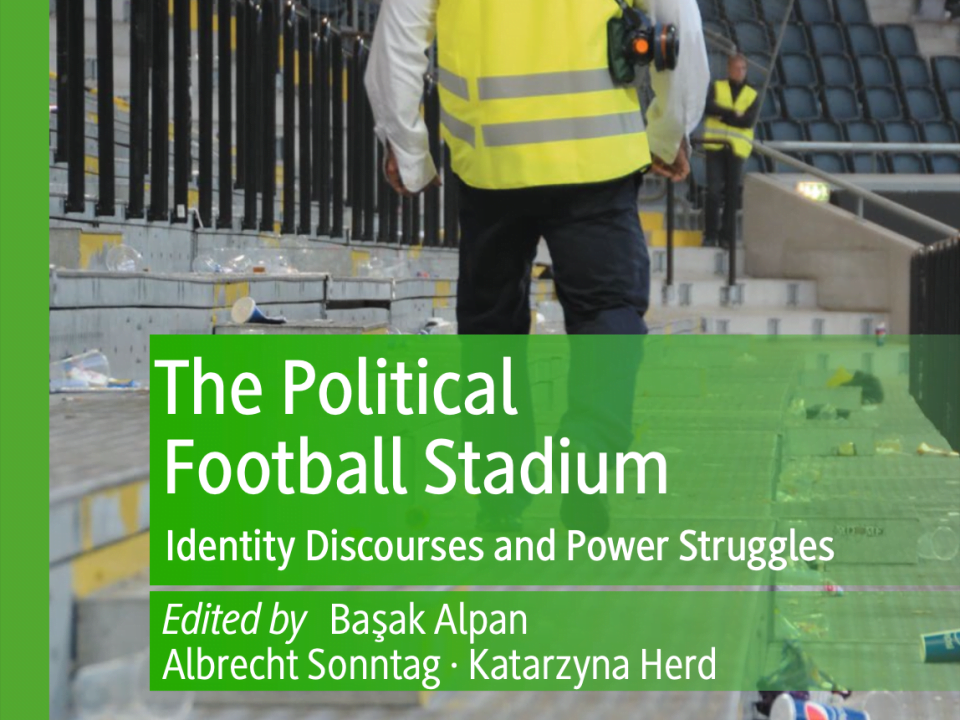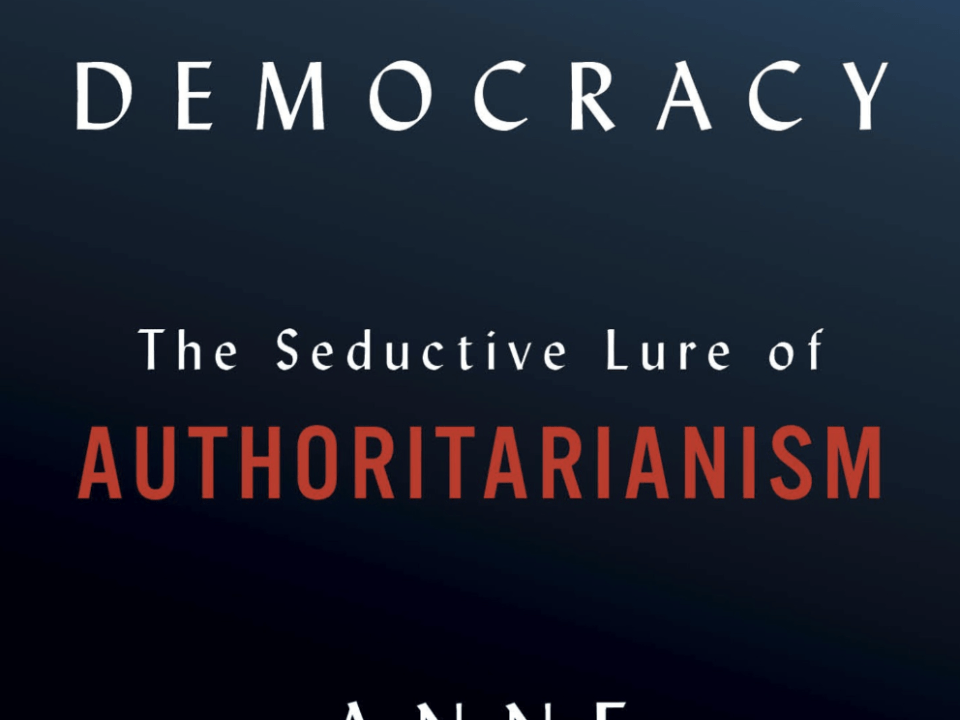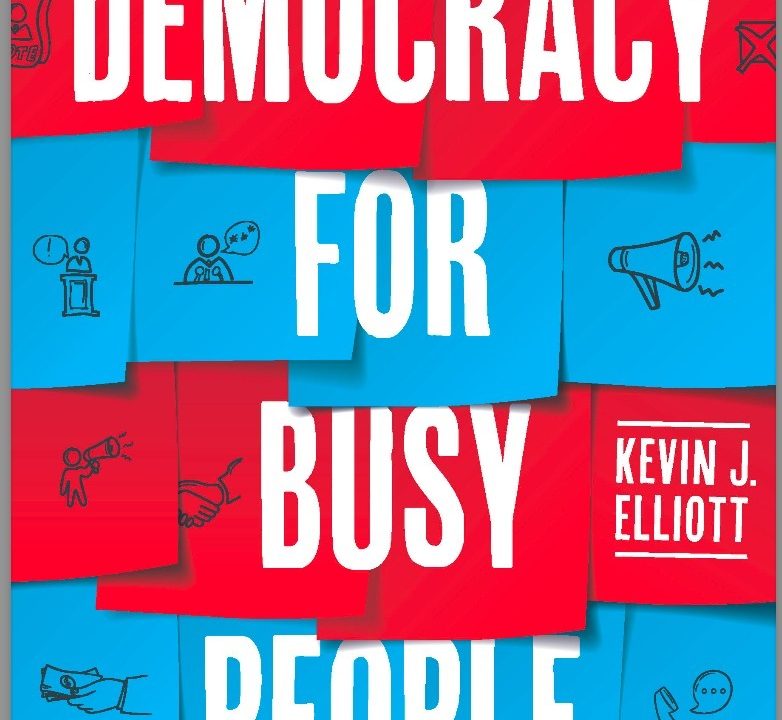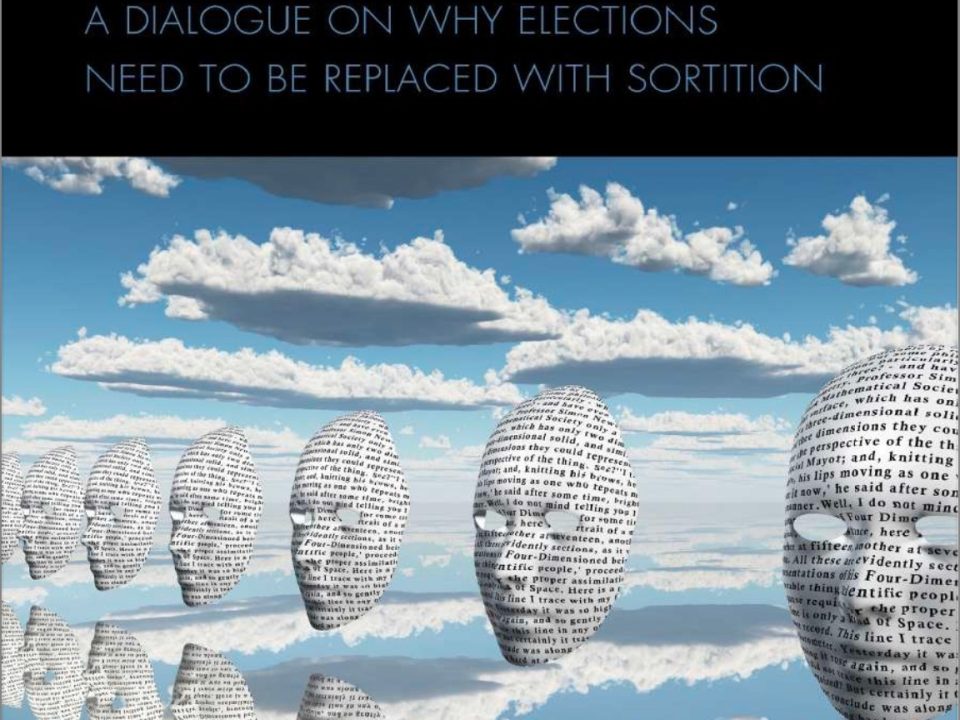Mengapa Bangsa-bangsa Gagal dan Runtuh?
“It’s the politics, stupid!
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor-Bandung-Cirebon, 19122018
#BincangBuku #19
“I met a traveler from an antique land Who said: “Two vast and trunkless legs of stone Stand in the desert. Near them, on the sand, Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, And wrinkled lip and sneer of cold command, Tell that its sculptor well those passions read, Which yet survive, stampt on these lifeless things, The hand that mockt them and the heart that fed: And on the pedestal these words appear: ‘My name is Ozymandias, king of kings: Look on my works, ye Mighty, and despair!’ Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare The lone and level sands stretch far away.”
“Ozymandias,” by Percy Bysshe Shelley (1817)” (Diamond, Jared. Collapse: how societies choose to fail or succeed, 2011)
“It’s the politics, stupid! That is Acemoglu and Robinson’s simple yet compelling explanation for why so many countries fail to develop. From the absolutism of the Stuarts to the antebellum South, from Sierra Leone to Colombia, this magisterial work shows how powerful elites rig the rules to benefit themselves at the expense of the many. Charting a careful course between the pessimists and optimists, the authors demonstrate history and geography need not be destiny. But they also document how sensible economic ideas and policies often achieve little in the absence of fundamental political change.”
—Dani Rodrik, Kennedy School of Government, Harvard University”
“Nations fail when they have extractive economic institutions, supported by extractive political institutions that impede and even block economic growth.”
(Daron Acemoglu. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. 2012)
Jared Diamond, penulis buku Collapse itu, membuat ilustrasi perbandingan dua kawasan sapi perah kecil di sebuah desa di Amerika dan di Greenland (saya kutip dari h.14-19). Dua tempat itu dia kunjungi. Huls Farm dan Gardar Farm. Dua peternakan itu, yang meskipun terletak ribuan mil terpisah, mempunyai kemiripan dalam kekuatan dan kerentanan mereka. Keduanya merupakan pertanian terbesar, paling makmur, paling maju secara teknologi di masing-masing lokasi. Secara khusus, masing-masing menjadi pusat kecanggihan memerah susu sapi. Kedua peternakan itu membiarkan sapi-sapinya merumput di padang rumput yang subur selama musim panas, menghasilkan jerami sendiri untuk dipanen pada akhir musim panas untuk memberi pakan sapi selama musim dingin, dan meningkatkan produksi pakan ternak musim panas dan jerami musim dingin dengan mengairi ladang mereka. Kedua peternakan serupa dalam ukuran kandang. Kandang Huls menampung sapi agak lebih banyak dari kandang Gardar (masing-masing 200 vs 165 sapi). Pemilik kedua peternakan dipandang sebagai pemimpin masyarakat. Kedua pemilik sangat religius.
Itulah keunggulan dua peternakan tersebut. Namun mereka juga mempunyai kerentanan yang sama. Keduanya berada di distrik yang secara ekonomi marjinal untuk pekerjaan menghasilkan susu. Karena letak geografis yang mempunyai iklim yang rentan, tidak stabil. Kedua peternakan rentan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim. Kedua distrik itu juga terletak jauh dari pusat memasarkan produk mereka, sehingga biaya transportasi tinggi. Mereka berada pada “competitive disadvantage” dibanding peternak lain pada distrik yang berbeda. Nilai ekonomi kedua peternakan tersebut disandera oleh kekuatan di luar kendali pemiliknya, seperti perubahan kemakmuran dan selera pelanggan dan tetangga mereka. Dalam skala yang lebih besar, ekonomi negara-negara di mana kedua pertanian itu berada naik dan turun dengan meningkatnya ancaman dari masyarakat musuh yang jauh.
Perbedaan terbesar antara Huls Farm dan Gardar Farm adalah dalam status mereka saat ini. Huls Farm, sebuah perusahaan keluarga yang dimiliki oleh lima saudara kandung dan pasangan mereka di Lembah Bitterroot di negara bagian Montana sebelah barat AS, saat ini makmur. Sementara Ravalli County tempat Huls Farm berada menawarkan salah satu tingkat pertumbuhan populasi tertinggi di negara bagian Amerika. Tidak dapat dibayangkan bahwa Amerika Serikat pada umumnya, dan Huls Farm pada khususnya, akan runtuh di masa mendatang.
Namun Gardar Farm, bekas pertanian bangsawan uskup Norse di barat daya Greenland, telah ditinggalkan lebih dari 500 tahun yang lalu. Masyarakat Greenland Norse runtuh total: ribuan penduduknya kelaparan sampai mati, terbunuh dalam kerusuhan sipil atau dalam perang melawan musuh, atau beremigrasi, sampai tidak ada yang bertahan hidup. Sementara tembok-tembok batu yang dibangun di kandang Gardar dan dekat Gardar Cathedral masih berdiri. Namun ketika Gardar Farm dan Norse Greenland berada di puncaknya, penurunan mereka tampaknya tak terbayangkan seperti halnya penurunan Huls Farm dan AS hari ini.
Norse Greenland hanyalah salah satu dari banyak masyarakat masa lalu yang runtuh atau lenyap, meninggalkan reruntuhan yang monumental seperti yang dibayangkan Shelley dalam puisinya “Ozymandias.” Keruntuhan/collapse yang dimaksud Diamond adalah penurunan drastis dalam populasi manusia dan/atau kompleksitas politik/ekonomi/sosial, dalam area yang luas, untuk waktu yang lama.
Fenomena keruntuhan ini merupakan bentuk ekstrem dari beberapa jenis penurunan yang lebih kecil. Masyarakat atau bangsa itu sendirilah yang bisa menentukan seberapa drastis penurunan kemampuan masyarakat sebelum terjerambab dicap sebagai keruntuhan, masyarakat atau bangsa yang gagal.
Beberapa jenis penurunan yang lebih ringan termasuk naik dan turunnya kekayaan normal, dan restrukturisasi politik/ekonomi/sosial kecil, dari setiap masyarakat individu; penaklukan satu masyarakat oleh tetangga dekat, atau keterpurukan satu bangsa/masyarakat terkait dengan kebangkitan tetangga, tanpa mengubah populasi total atau kompleksitas seluruh wilayah; dan penggantian atau penggulingan satu elite yang berkuasa oleh yang lain.
Dengan standar-standar itu, kebanyakan orang akan menganggap masyarakat masa lalu berikut ini telah menjadi korban keruntuhan yang dimulai dari hanya kemerosotan kecil: Anasazi dan Cahokia di AS, kota-kota Maya di Amerika Tengah, Moche dan Masyarakat Tiwanaku di Amerika Selatan, Yunani Mycenean dan Kreta Minoa di Eropa, Zimbabwe Besar di Afrika, Angkor Wat dan kota-kota Lembah Harappan Indus di Asia, dan Pulau Paskah di Samudra Pasifik.
Ketika Capres Prabowo Subianto memaparkan kecemasannya soal potensi punahnya Indonesia dengan mengutip novel Ghost Fleet debutan P.W Singer, sebagian orang gaduh bukan kepayang. Komentar mewarnai pidato itu seperti hujan meteor di tengah malam. Indonesia akan punah tahun 2030 tahun yang hanya tinggal kurang 12 tahun dari sekarang. Mungkinkah?
Ketika Capres Prabowo Subianto memprihatinkan tingkat kemiskinan—kemudian membandingkannya dengan negara-negara Afrika, termasuk Haiti (silakan cari sendiri ya, Haiti itu dimana dan berapa tingkat kemiskinannya), sebagian orang ramai membincangkannya (umumnya mengritik dan melecehkan. Ini tahun politik Bung!). Apa pentingnya kemiskinan bagi kelangsungan sebuah bangsa?
Apa sebetulnya yang menjadi soal, baik dari pemaparan Jared Diamond atau dari kutipan-kutipan gagasan yang dilontarkan Prabowo Subianto?
Mari kita berselancar dalam buku Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Sebuah buku yang ditulis oleh dua ekonom handal, Daron Acemoglu and James A. Robinson (2012). Daron Acemoglu seorang ekonom Turki-Amerika Serikat dari Institut Teknologi Massachusetts dan James A. Robinson ilmuwan politik dari Universitas Harvard.
Berbeda dengan pandangan Diamond, Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa sebuah bangsa akan berkembang atau gagal bukanlah seperti yang dikatakan oleh para penulis lain termasuk Diamond itu – kebijakan ekonomi, geografi, budaya, atau sistem nilai – tetapi lebih pada institusi politik. Acemoglu dan Robinson berteori bahwa ada dua jenis kelembagaan yang menjadi sebabnya: Lembaga ekstraktif (extractive institutions) dan lembaga inklusif (inclusive institutions). Lembaga ekstraktif ini memungkinkan sekelompok “kecil” individu melakukan yang terbaik untuk mengeksploitasi khalayak atau kepentingan umum untuk kepentingan individual atau kelompoknya. Sedangkan lembaga inklusif adalah sebaliknya di mana publik terlibat dalam menentukan proses-proses pemerintahan. Kata Acemoglu and Robinson — “extractive” institutions in which a “small” group of individuals do their best to exploit the rest of the population, and “inclusive” institutions in which “many” people are included in the process of governing.
Itulah pikiran sentral dari buku Why Nations Fail ini. Untuk memperkuat pandangan itu kedua ahli ekonomi ini menyajikan banyak sekali contoh kasus dari catatan sejarah sebagai menu yang memabukkan.
Dengan pisau analisis kelembagaan “ekstraktif” dan “inklusif” ini Acemoglu dan Robinson menemukan bahwa Romawi, Uni Sovyet, Kerajaan Spanyol, Venesia, Korea Selatan, Taiwan, Chili, China, Kore Utara, Zimbabwe, Inca dan Maya di Amerika Selatan dan sejumlah contoh lain maju atau gagal karena kegagalan atau keberhasilan bangsa-bangsa itu mengembangkan institusi yang inklusif atau ekstraktif.
Roma dan Venesia tumbuh karena institusi inklusif. Tetapi kemudian runtuh karena institusi inklusif yang baik diganti dalam kudeta oleh institusi ekstraktif yang buruk. Roma tumbuh dan berkembang selama berabad-abad di bawah lembaga ekstraktif kekaisaran, dan pada akhirnya gagal.
Disebutkan Korea Selatan, Taiwan, Chili, dan China yang semuanya memiliki hasil ekonomi yang baik di bawah lembaga-lembaga politik non-inklusif. Dengan pengecualian Cina, semua proses kepemerintahan berkembang menjadi lembaga inklusif.
Kita lihat kota lain yang menjadi teladan gagal atau tidaknya sebuah sistem politik mempengaruhi kehidupan, kemakmuran sebuah masyarakat: Kota Nogales. Nogales adalah sebuah kota yang terpisah oleh pagar. Sebelah utara pagar adalah Kota Nogales, Arizona, Amerika Serikat. Sebelah Selatan adalah Kota Nogales, Sonora, Meksiko. Dua kota ini tidak ada perbedaan apapun dari segi etnik, budaya, sistem nilai masyarakatnya, geografi, iklim. Penduduk Nogales, Arizona, dan Nogales, Sonora, memiliki leluhur yang sama, menikmati makanan yang sama dan musik yang sama, dan, memiliki budaya yang sama. Mereka adalah orang-orang Meksiko. Karena beragam proses politik maka Kota Nogales terbelah menjadi dua.
Dan kedua kota itu berkembang menjadi dua kota yang sangat jauh berbeda. Masyarakat Kota Nogales, Arizona berpenghasilan rata-rata sekitar $ 30.000 per tahun (2011). Sebagian besar remaja bersekolah, dan mayoritas orang dewasa adalah lulusan sekolah menengah. Masyarakat relatif sehat, dengan harapan hidup yang tinggi menurut standar global. Semua fasilitas publik tersedia dengan baik, jalan, listrik, urusan sampah. Dan yang tidak kalah pentingnya, hukum dan ketertiban terjamin. Orang-orang di Nogales, Arizona, dapat melakukan kegiatan sehari-hari mereka tanpa rasa takut akan nyawa atau keselamatan. Tidak takut akan pencurian, penyitaan, atau hal-hal lain yang dapat membahayakan investasi mereka dalam bisnis dan rumah mereka. Mereka dapat memilih untuk menggantikan walikota, anggota kongres, dan senator mereka; mereka memberikan suara dalam pemilihan presiden yang menentukan siapa menjadi pemimpin negara mereka. Demokrasi adalah kehidupan penting mereka.
Hal yang sebaliknya terjadi di Kota Nogales, Sonora, selatan pagar. Meskipun penduduk Nogales, Sonora, tinggal di bagian yang relatif lebih makmur di Meksiko, pendapatan rumah tangga rata-rata hanya sekitar sepertiga di Nogales, Arizona. Sebagian besar orang dewasa tidak memiliki gelar sekolah menengah atas, dan banyak remaja yang tidak bersekolah. Ibu selalu khawatir tentang tingginya angka kematian bayi. Kondisi kesehatan masyarakat yang buruk membuat harapan hidup tidak selama tetangga utara mereka. Mereka juga tidak memiliki akses ke banyak fasilitas publik. Jalanan dalam kondisi buruk. Hukum dan ketertiban berada dalam kondisi yang lebih buruk. Kejahatan tinggi. Membuka bisnis adalah kegiatan yang berisiko. Anda tidak hanya mengambil risiko perampokan, tetapi mendapatkan semua izin bukanlah upaya yang mudah. Penduduk Nogales, Sonora, hidup dengan korupsi dan ketidakmampuan politisi setiap hari.
Jauh melintasi Samudra Atlantik, di kawasan Asia: Korea Selatan dan Korea Utara. Pada sebuah musim panas 1945, ketika Perang Dunia Kedua hampir berakhir, koloni Jepang di Korea mulai runtuh. Dalam detik-detik penyerahan tanpa syarat Jepang pada 15 Agustus, Korea dibagi pada paralel ke-38 menjadi dua wilayah dengan dua pengaruh. Selatan dikelola oleh Amerika Serikat. Utara oleh Rusia. Kedamaian perang dingin bubar pada Juni 1950 ketika tentara Korea Utara menyerbu Selatan. Meskipun pada awalnya orang Korea Utara membuat terobosan besar, merebut ibukota, Seoul, pada musim gugur, mereka mundur sepenuhnya. Kehidupan kedua negara itu jauh berbeda.
Korea Utara dan Korea Selatan berbeda karena institusi ekstraktif di Korea Utara. Tetapi Italia Utara dan Selatan sama-sama memiliki lembaga formal yang sama, namun Korea Utara adalah ekonomi yang berkembang sangat terbatas institusi yang ekstraktif. Korea Selatan merupakan tempat yang baik secara ekonomi karena berkembang menuju institusi politik yang inklusif.
Menurut Acemoglu dan Robinson perbedaan yang mencolok antara dua Korea bukan hal yang kuno. Bahkan, mereka tidak ada sebelum akhir Perang Dunia Kedua. Tetapi setelah 1945, berbagai pemerintah di Utara dan Selatan mengadopsi cara yang sangat berbeda dalam mengatur ekonomi mereka. Korea Selatan dipimpin, dan institusi-institusi ekonomi dan politik awalnya dibentuk, oleh Syngman Rhee yang anti-komunis, berpendidikan tinggi Harvard dan Princeton yang berpendidikan mantap, dengan dukungan signifikan dari Amerika Serikat. Rhee terpilih sebagai presiden pada tahun 1948. Ditempa di tengah-tengah Perang Korea dan melawan ancaman komunisme yang menyebar ke selatan paralel ke-38, Korea Selatan bukan negara demokrasi. Baik Rhee dan penggantinya yang juga terkenal, Jenderal Park Chung-Hee, mengamankan tempat mereka dalam sejarah sebagai presiden yang otoriter. Namun keduanya mengatur ekonomi di mana properti swasta diakui, dan setelah 1961, Park secara efektif melemparkan beban negara di belakang pertumbuhan ekonomi yang cepat, menyalurkan kredit dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil.
Pada akhir 1990-an, hanya sekitar setengah abad, pertumbuhan Korea Selatan dan stagnasi Korea Utara menyebabkan kesenjangan sepuluh kali lipat antara dua bagian dari negara yang pernah bersatu ini — bayangkan perbedaan yang dapat dibuat dalam beberapa abad. Bencana ekonomi Korea Utara, yang menyebabkan kelaparan jutaan orang, jika dibandingkan dengan keberhasilan ekonomi Korea Selatan, sangat mencolok: baik budaya, geografi, atau ketidaktahuan dapat menjelaskan jalur yang berbeda antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Lembaga ekonomi inklusif, seperti yang ada di Korea Selatan atau di Amerika Serikat, adalah lembaga yang memungkinkan dan mendorong partisipasi banyak orang dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan bakat dan keterampilan mereka dengan sebaik-baiknya dan yang memungkinkan individu untuk membuat pilihan. Agar inklusif, lembaga-lembaga ekonomi harus memiliki properti pribadi yang aman, sistem hukum yang tidak memihak, dan penyediaan layanan publik yang menyediakan lapangan permainan yang setara di mana orang dapat bertukar dan membuat kontrak; itu izin masuknya bisnis baru juga terbuka dan memungkinkan orang untuk memilih karier mereka. Inilah kelembagaan inklusif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena makin banyak orang yang terlibat dan mengembangkan imajinasinya untuk mengelola peluang dan sumber-sumber ekonomi.
KONTRAS antara Korea Selatan dan Utara, dan Amerika Serikat dan Amerika Latin, menggambarkan prinsip umum. Lembaga ekonomi yang inklusif mendorong kegiatan ekonomi, pertumbuhan produktivitas, dan kemakmuran ekonomi. Dengan bukti-bukti sejarah yang beragam dan rentang waktu yang lama itulah Acemoglu dan Robinson percaya bahwa bangsa-bangsa juga berpeluang gagal ketika mereka memiliki institusi ekonomi ekstraktif, yang didukung oleh institusi politik ekstraktif yang menghambat dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dan perubahan teknologi akan selalu disertai oleh apa yang disebut oleh ekonom hebat Joseph Schumpeter sebagai penghancuran kreatif (creative destruction). Mereka mengganti yang lama dengan yang baru. Sektor-sektor baru menarik sumber daya dari yang lama. Perusahaan baru mengambil bisnis dari yang sudah ada. Teknologi baru membuat keterampilan dan mesin yang ada menjadi usang.
Proses pertumbuhan ekonomi dan institusi inklusif yang menjadi basisnya membuat para pecundang dan pemenang di arena politik dan di pasar ekonomi diselimuti kekhawatiran yang mencekam. Ketakutan akan kehancuran kreatif seringkali merupakan akar dari oposisi terhadap institusi ekonomi dan politik yang inklusif.
Apakah inilah juga yang menjadi momok bagi perjalanan Bangsa Indonesia ke depan? Apakah kegagalan reformasi melakukan perubahan radikal karena masih bercokol kuatnya kepentingan-kepentingan yang akan hancur jika kelembagaan ekonomi inklusif dan kelembagaan politik yang inklusif menggantikan ekstraktif?
Seperti yang diuraikan dengan cermat dalam buku ini. Keberhasilan dan kegagalan kelompok-kelompok tertentu, satu pelajaran jelas: kelompok-kelompok kuat sering kali menentang kemajuan ekonomi dan melawan mesin-mesin kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya proses mesin yang lebih banyak dan lebih baik, dan semakin banyak orang yang berpendidikan, tetapi juga proses transformatif dan destabilisasi yang terkait dengan penghancuran kreatif yang meluas. Pertumbuhan dengan demikian bergerak maju hanya jika tidak diblokir oleh pecundang ekonomi yang mengantisipasi bahwa hak ekonomi mereka akan hilang dan oleh pecundang politik yang takut bahwa kekuatan politik mereka akan terkikis.
Konflik atas sumber daya yang langka, pendapatan dan kekuasaan, diterjemahkan ke dalam konflik atas aturan main, institusi ekonomi, yang akan menentukan kegiatan ekonomi dan siapa yang akan mendapat manfaat darinya. Ketika ada konflik, keinginan semua pihak tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Beberapa akan dikalahkan dan frustrasi. Sementara yang lain akan berhasil dalam mengamankan hasil yang mereka sukai. Siapa pemenang konflik ini memiliki implikasi mendasar terhadap lintasan ekonomi suatu negara. Jika kelompok-kelompok yang menentang pertumbuhan adalah pemenang, mereka dapat dengan sukses memblokir pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi akan mandek.
Logika mengapa yang kuat belum tentu ingin mendirikan lembaga ekonomi yang mempromosikan keberhasilan ekonomi meluas maka kita perlu melihat dan mencermati pilihan lembaga politik. Dalam rezim absolut, beberapa elit dapat menggunakan kekuasaan untuk mendirikan lembaga ekonomi yang mereka sukai. Apakah mereka tertarik untuk berubah? Belum tentu. Sepanjang kondisi kelembagaan ekonomi status quo telah memberi keuntungan yang disukai maka jangan berharap ada perubahan.
Apakah institusi politik membuat mereka lebih pluralistik? Secara umum tidak, karena ini hanya akan melemahkan kekuatan politik mereka, membuatnya lebih sulit, mungkin mustahil, bagi mereka untuk menyusun institusi ekonomi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Di sini kita melihat sumber konflik yang matang, siap meledak. Orang-orang yang menderita dari institusi ekonomi ekstraktif tidak dapat berharap penguasa absolut untuk secara sukarela mengubah institusi politik dan mendistribusikan kembali kekuasaan dalam masyarakat. Satu-satunya cara untuk mengubah institusi-institusi politik ini adalah dengan memaksa elit untuk menciptakan institusi yang lebih pluralistik.
Sejumlah contoh kasus disajikan dengan lengkap dan menarik untuk dibaca. Memang salah satu hal yang memikat dari Acemoglu dan Robinson adalah padangannya pada apa yang terjadi di dalam negara, bukan di antara negara. Alasan terpenting mengapa bangsa gagal adalah karena mereka dihancurkan oleh tetangga mereka. Kartago jatuh bukan karena kegagalan “kehancuran kreatif” (creative destruction) tetapi lebih karena kehancuran tentara Romawi yang tidak begitu kreatif. Acemoglu dan Robinson mendokumentasikan banyak peradaban – dari Hindia Timur, Hindia Barat, hingga seluruh Amerika Utara dan Selatan, hingga Afrika – musnah oleh keunggulan militer Eropa Barat.
Tentu tidak semua orang setuju dengan pandangan Acemoglu dan Robinson. Misalnya Michele Boldrin, Salvatore Modica and David K. Levine (review pada Huffpost, 24 Jan 2014) tidak sepenuhnya setuju. Karena transisi dari institusi kolonial ekstraktif jika tidak mengarah pada peningkatan kesejahteraan yang dramatis – misalnya di Zimbabwe, malah menyebabkan kehancuran ekonomi yang besar, dan India merana secara ekonomi selama beberapa dekade bahkan ketika demokrasi berkembang.
Juga Warren Bass seorang ilmuwan politik senior dari the RAND Corporation dan mantan penasihat U.S. ambassador untuk PBB, Susan Rice. “Why Nations Fail” tidaklah sempurna, katanya. Dibutuhkan beberapa batalyon spesialis regional untuk memeriksa ulang sejarah dan analisis mereka. Sementara gambaran keseluruhannya terperinci dan meyakinkan, para penulis harus memiliki kemampuan manusia super untuk mendapatkan setiap nuansa yang tepat tentang situasi yang digambarkan dari kasus-kasus yang dituliskan, begitu sindiran Warren Bass dalam review buku itu yang dimuat Washington Post, 20 April 2012.
Tidak ada yang mudah dan sempurna untuk menulis sebuah buku yang menganalisis berdasarkan himpunan cacatan sejarah. Tesis sentral dari buku ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dikaitkan dengan lembaga ekonomi dan politik yang inklusif, sedangkan lembaga ekstraktif biasanya mengarah pada stagnasi dan kemiskinan. Tetapi ini tidak berarti bahwa lembaga ekstraktif tidak pernah dapat menghasilkan pertumbuhan atau bahwa semua lembaga ekstraktif diciptakan sama. Acemoglu dan Robinson memaparkan alasan-alasan dan bukti catatan yang cukup lengkap.
Hal yang menarik disampaikan oleh penulis buku ini adalah ketika pertumbuhan berada di bawah lembaga politik ekstraktif tetapi di mana lembaga ekonomi memiliki aspek inklusif, seperti yang mereka lakukan di Korea Selatan, selalu ada bahaya bahwa lembaga ekonomi menjadi lebih ekstraktif dan pertumbuhan berhenti. Mereka yang mengendalikan kekuatan politik pada akhirnya akan merasa lebih bermanfaat menggunakan kekuatan mereka untuk membatasi persaingan, meningkatkan porsi kue mereka, atau bahkan mencuri dan menjarah orang lain daripada mendukung kemajuan ekonomi.
“Kemampuan untuk menggunakan kekuasaan pada akhirnya akan merusak fondasi kemakmuran ekonomi, kecuali jika lembaga-lembaga politik diubah dari ekstraktif menjadi inklusif.” (h. 161). Sekali lagi ditekankan bahwa bangsa gagal secara ekonomi karena lembaga ekstraktif. Lembaga-lembaga ini membuat negara-negara miskin tetap miskin dan mencegah mereka menempuh jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi hari ini di Afrika, di tempat-tempat seperti Zimbabwe dan Sierra Leone; di Amerika Selatan, di negara-negara seperti Kolombia dan Argentina; di Asia, di negara-negara seperti Korea Utara dan Uzbekistan; dan di Timur Tengah, di negara-negara seperti Mesir. Ada perbedaan mencolok di antara negara-negara ini. Beberapa negara tropika, beberapa di garis lintang sedang. Beberapa adalah koloni Inggris; lainnya, dari Jepang, Spanyol, dan Rusia. Mereka memiliki sejarah, bahasa, dan budaya yang sangat berbeda. Yang mereka semua sama adalah lembaga ekstraktif. Dalam semua kasus ini, dasar lembaga-lembaga ini adalah elit yang merancang lembaga-lembaga ekonomi untuk memperkaya diri sendiri dan melanggengkan kekuasaan mereka dengan mengorbankan sebagian besar orang di masyarakat. Perbedaan sejarah dan struktur sosial dari negara-negara tersebut menyebabkan perbedaan dalam sifat elit dan rincian dari institusi ekstraktif. Tapi alasan mengapa institusi ekstraktif ini bertahan selalu terkait dengan lingkaran setan, dan implikasi dari institusi ini dalam hal memiskinkan warga mereka (h. 695).
Bagaimana dengan Cina?
Dalam kasus Cina, demikian tulis Acemoglu dan Robinson, proses pertumbuhan yang selalu membuntuti, impor teknologi asing, dan ekspor produk manufaktur kelas bawah kemungkinan akan berlanjut untuk sementara waktu. Namun demikian, pertumbuhan Tiongkok juga kemungkinan akan berakhir, terutama setelah Cina mencapai standar tingkat kehidupan negara berpenghasilan menengah. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah Partai Komunis Tiongkok dan elit ekonomi Tiongkok yang semakin kuat berhasil mempertahankan cengkeraman kekuasaan mereka yang sangat ketat dalam beberapa dekade mendatang.
Dalam hal ini, sejarah dan teori Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa pertumbuhan dengan penghancuran kreatif dan inovasi sejati tidak akan tiba, dan tingkat pertumbuhan yang spektakuler di Cina perlahan-lahan akan menguap. Tetapi hasil ini masih jauh dari yang ditentukan sebelumnya; ini dapat dihindari jika Tiongkok transisi ke lembaga politik inklusif sebelum pertumbuhannya di bawah lembaga ekstraktif mencapai batasnya. Namun demikian, ada sedikit alasan untuk berharap bahwa transisi di Tiongkok menuju lembaga-lembaga politik yang lebih inklusif mungkin terjadi atau akan terjadi secara otomatis dan tanpa rasa sakit. Bahkan beberapa suara di dalam Partai Komunis Tiongkok mengakui bahaya membentang di jalan di depan dan melemparkan gagasan bahwa reformasi politik – yaitu, transisi ke lembaga-lembaga politik yang lebih inklusif, untuk menggunakan terminologi kami – diperlukan (h. 724).
Bagaimana dengan Indonesia?
Karena konstelasi sejarah kolonialisasi global, maka tentu saja Indonesia tak akan dilupakan. Indonesia secara khusus dibahas pada Bab 9 (h. 422) yang menguraikan situasi perdagangan rempah dan kegagalan institusi ekonomi dan politik yang dibangun kaum penjajah.
Pada halaman 427 Acemoglu dan Robinson menuliskan dengan pedih penjajahan dan genosida di Banda, tempat tumbuh suburnya pala. Rencana awal mereka untuk mendirikan monopoli pala dan pala hancur, gubernur Belanda di Belanda, Jan Pieterszoon Coen, datang dengan rencana alternatif. Coen mendirikan Batavia, di pulau Jawa, sebagai ibukota baru Perusahaan Hindia Timur Belanda pada 1618. Pada 1621 ia berlayar ke Banda dengan armada dan melanjutkan untuk membantai hampir seluruh populasi pulau itu, mungkin sekitar lima belas ribu orang. Semua pemimpin mereka dieksekusi bersama dengan yang lain, dan hanya beberapa yang dibiarkan hidup, cukup untuk melestarikan pengetahuan yang diperlukan untuk produksi biji-bijian dan pala.
Setelah genosida ini selesai, Coen kemudian melanjutkan untuk menciptakan struktur politik dan ekonomi yang diperlukan untuk rencananya: a plantation society, masyarakat perkebunan. Pulau-pulau itu dibagi menjadi enam puluh delapan bidang, yang diberikan kepada enam puluh delapan orang Belanda, sebagian besar mantan dan saat ini karyawan Perusahaan Hindia Timur Belanda. Para pemilik perkebunan baru ini diajari cara memproduksi rempah-rempah oleh segelintir orang Banda yang masih hidup dan dapat membeli budak dari East India Company untuk mengisi pulau-pulau yang sekarang kosong dan untuk memproduksi rempah-rempah, yang harus dijual dengan harga tetap kembali ke perusahaan.
Lembaga ekstraktif yang dibuat oleh Belanda di Kepulauan Rempah-rempah memiliki efek yang diinginkan, meskipun, di Banda ini mengorbankan 15.000 jiwa tak berdosa dan pembentukan seperangkat lembaga ekonomi dan politik yang akan mengutuk pulau-pulau itu menjadi terbelakang. Pada akhir abad ketujuh belas, Belanda telah mengurangi pasokan rempah-rempah dunia sekitar 60 persen dan harga pala meningkat dua kali lipat. Penjajah Belanda menciptakan kelembagaan ekstraktif ekonomi dan politik untuk menjamin kemewahan dan kehidupannya sendiri. Kekuasaan Belanda di Hindia Belanda runtuh, kemudian.
Buku yang terdiri dari 15 bab dan dalam 845 halaman ini memberi pelajaran penting bagi kita menjelang pemilihan kepemimpinan nasional. Gagasan-gagasan yang memberi ruang yang luas untuk tumbuh dan kembangnya kelembagaan yang inklusif baik di sektor ekonomi maupun politik akan menentukan perjalana bangsa ke depan. Kemiskinan, ketidakadilan dan penguasaan sumberdaya pada segelintir elit penguasa dan pengusaha disebabkan dari bercokolnya kelembagaan politik yang ekstraktif.
Apakah Indonesia akan punah pada tahun 2030 ketika McKinsey Global Institute menempatkan Indonesia pada posisi ke 7 negara dengan ekonomi terhebat pada tahun itu? Atau akan menjadi negara gagal pada tahun 2050 ketika PriceWaterhouse Cooper (PwC) memperkirakan Indonesia adalah negara peringkat ke 4 yang mempunyai kekuatan ekonomi global pada tahun itu?
Kita sebagai warga negara harus waspada. “It’s the politics, stupid!”