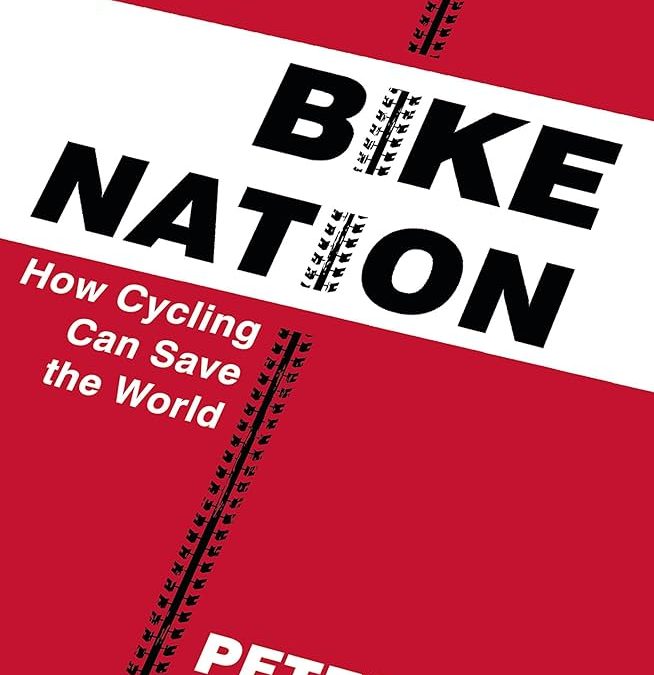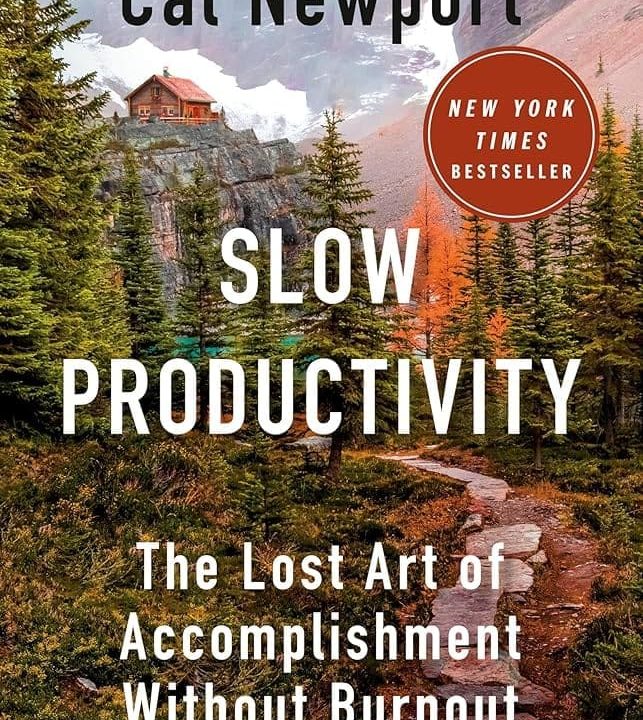Rubarubu #58
Bike Nation:
Sepeda Sebagai Penegakan Peradaban
Sepeda dan Dunia yang Hampir Runtuh
Peter Walker membuka Bike Nation dari sebuah paradoks yang sangat modern: kita tahu kota-kota kita rusak oleh mobil, tetapi kita terus membangunnya untuk mobil. Polusi udara mem-bunuh jutaan orang setiap tahun, kemacetan mencuri waktu hidup, perubahan iklim dipercepat oleh transportasi berbasis fosil—namun solusi yang murah, terbukti, dan manusiawi justru dipinggirkan. Sepeda, dalam narasi Walker, adalah teknologi yang terlalu sederhana untuk dunia yang terobsesi dengan kompleksitas, tetapi justru karena kesederhanaannya ia menjadi radikal.
Walker—seorang jurnalis transportasi dan lingkungan—tidak menulis buku ini dari menara gading. Ia memulainya dari jalanan London, dari pengalaman sehari-hari bersepeda di kota yang secara struktural masih memihak mobil. Ia menggambarkan bagaimana bersepeda sering kali diperlakukan bukan sebagai hak, melainkan sebagai aktivitas menyimpang—sebuah anomali dalam tata kota modern. Dari pengalaman personal ini, Walker membawa pembaca ke panggung global: Belanda, Denmark, Amerika Serikat, Kolombia, hingga Inggris sendiri. Sepeda, bagi Walker, bukan nostalgia masa lalu, tetapi masa depan yang ditunda.
Bike Nation: How Cycling Can Save the World karya Peter Walker (Yellow Jersey, 2017) me-norehkan sebuah kalimat yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengguncang asumsi paling dasar tentang bersepeda: tidak semua orang yang mengendarai sepeda adalah “pesepeda”. Kalimat ini bukan permainan kata, melainkan pintu masuk menuju kritik mendalam atas cara masyarakat modern—khususnya kota-kota Barat—memahami mobilitas, identitas, dan kelas sosial.
Walker mengajak pembaca membedakan antara cycling as an activity dan cycling as an identity. Di banyak negara, terutama Inggris dan Amerika Serikat, bersepeda telah direduksi menjadi identitas subkultural: hobi, gaya hidup, atau bahkan ideologi. “Pesepeda” dibayangkan sebagai figur tertentu—sering kali laki-laki, mengenakan pakaian teknis, agresif di jalan, dan dianggap menyimpang dari arus utama. Akibatnya, bersepeda tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang normal, melainkan sebagai pilihan eksentrik.
Padahal, Walker menunjukkan bahwa secara global, sebagian besar orang yang naik sepeda tidak pernah menyebut dirinya pesepeda. Mereka adalah ibu yang mengantar anak ke sekolah di Belanda, pekerja migran di Asia Tenggara, pelajar di Tiongkok, atau petani di Afrika. Mereka tidak “bersepeda”; mereka pergi ke suatu tempat. Sepeda hanyalah alat, bukan identitas. Inilah tesis awal Walker: krisis bersepeda di negara-negara maju bukan soal minat atau budaya, melainkan soal bagaimana sepeda disingkirkan dari kategori “normal.”
Walker kemudian membawa pembaca ke statistik yang sering diabaikan dalam perdebatan publik. Di Belanda, lebih dari 25% seluruh perjalanan dilakukan dengan sepeda; di Kopenhagen, angka itu mencapai hampir 50% untuk perjalanan kerja dan sekolah. Namun yang menarik, survei menunjukkan bahwa mayoritas pengguna sepeda di kota-kota ini tidak menganggap diri mereka “cyclists”. Mereka tidak merasa sedang melakukan tindakan politik atau olahraga; mereka sekadar menjalani hidup sehari-hari.
Kontras ini menjadi semakin tajam ketika Walker kembali ke Inggris. Ia menceritakan pengalam-an pribadinya bersepeda di London, di mana ia sering diperlakukan seolah sedang melakukan tindakan berisiko atau bahkan provokatif. Media Inggris, menurut Walker, memainkan peran besar dalam membentuk citra negatif pesepeda—dari stereotip “road warrior” hingga narasi konflik antara mobil dan sepeda yang seolah tak terhindarkan. Bersepeda diperlakukan sebagai pilihan individu yang harus “dipertanggungjawabkan”, bukan sebagai hak warga kota.
Walker menegaskan bahwa bahasa sangat menentukan politik. Ketika sepeda dibingkai sebagai “gaya hidup”, maka kegagalannya menjadi arus utama dapat disalahkan pada individu: kurang berani, kurang disiplin, kurang sporty. Namun ketika sepeda dipahami sebagai moda trans-portasi, pertanyaannya berubah menjadi struktural: apakah kota ini aman? apakah infra-strukturnya adil? apakah hukum melindungi yang rentan?
Dalam bagian pengantar ini, Walker juga mengkritik obsesinya banyak pemerintah terhadap kampanye perubahan perilaku. Ia menunjukkan bahwa selama puluhan tahun, Inggris meng-habiskan dana besar untuk “mendorong orang bersepeda” melalui iklan dan edukasi, semen-tara investasi infrastruktur tetap minim. Data yang ia kutip menunjukkan bahwa orang tidak takut bersepeda; mereka takut ditabrak mobil. Di negara-negara dengan tingkat keselamatan tinggi, hampir semua kelompok usia dan gender bersepeda. Di negara yang tidak aman, pe-sepeda didominasi kelompok muda dan laki-laki—bukan karena preferensi, tetapi karena seleksi risiko.
Walker mengaitkan hal ini dengan ketimpangan sosial. Mereka yang “berani” bersepeda di kota berbahaya sering kali adalah mereka yang tidak punya pilihan lain. Dengan demikian, citra pesepeda sebagai minoritas eksentrik justru menutupi fakta bahwa bahaya jalan raya adalah bentuk ketidakadilan struktural.
Lebih jauh, Walker memperlihatkan bagaimana mobilitas telah menjadi alat eksklusi. Ketika sepeda dipinggirkan, mereka yang tidak bisa atau tidak ingin mengemudi kehilangan akses ke kota: pekerjaan, pendidikan, dan ruang sosial. Dalam bahasa yang sangat jelas, Walker menyatakan bahwa transportasi adalah kebijakan sosial yang paling menentukan, karena ia mengatur siapa yang boleh bergerak dengan aman dan siapa yang harus mengambil risiko.
Pengantar ini ditutup dengan ajakan implisit yang sangat kuat: jika kita ingin kota yang adil, sehat, dan berkelanjutan, kita harus berhenti bertanya bagaimana “membuat orang menjadi pesepeda”, dan mulai bertanya bagaimana membuat bersepeda menjadi hal biasa. Bukan dengan moralizing, bukan dengan heroisme, tetapi dengan desain kota, hukum, dan politik yang berpihak pada kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks yang lebih luas, pengantar Bike Nation ini sejalan dengan pemikiran Ivan Illich tentang “alat yang ramah manusia”, serta dengan wacana degrowth yang menolak teknologi raksasa yang memaksa manusia menyesuaikan diri. Sepeda, dalam pembacaan Walker, bukan simbol kesederhanaan romantik, melainkan indikator kesehatan demokrasi perkotaan. Kota yang membuat sepeda menjadi normal adalah kota yang mengakui bahwa tidak semua orang ingin, mampu, atau perlu hidup di balik setir mobil.
Dengan demikian, kalimat pembuka buku ini bukan sekadar provokasi linguistik. Ia adalah undangan untuk membongkar cara kita berpikir tentang kemajuan. Tidak semua orang di atas sepeda adalah pesepeda—dan justru di situlah harapan perubahan berada.
Sepeda, Keadilan Sosial, dan Kelas
Salah satu kontribusi terpenting Bike Nation adalah pembongkaran mitos bahwa sistem transportasi bersifat netral dan teknis. Walker menunjukkan bahwa setiap jalan, setiap trotoar, setiap lampu lalu lintas adalah hasil keputusan politik. Mobil mendominasi kota bukan karena ia “alami” atau “lebih efisien”, tetapi karena puluhan tahun kebijakan publik yang secara sadar meminggirkan pejalan kaki dan pesepeda.
Walker mengutip sejarah Inggris dan Amerika Serikat, di mana pada awal abad ke-20 jalan-jalan kota justru adalah ruang sosial: anak-anak bermain, pedagang berjualan, warga bercakap. Mobil kemudian “merebut” jalan melalui kombinasi hukum, propaganda, dan kriminalisasi pengguna jalan non-motor. Konsep “jaywalking” misalnya, bukan muncul dari kebutuhan keselamatan, tetapi dari kampanye industri otomotif untuk menyalahkan pejalan kaki atas kecelakaan yang disebabkan mobil.
Dalam konteks ini, sepeda menjadi alat pembuka kedok: ia memperlihatkan bahwa kota bisa berfungsi dengan logika lain—logika pelan, dekat, dan manusiawi.
Walker dengan hati-hati menghindari romantisasi sepeda. Ia menegaskan bahwa sepeda tidak akan “menyelamatkan dunia” dengan sendirinya. Yang menyelamatkan dunia adalah perubahan struktur: hukum, desain kota, dan nilai sosial. Di sinilah ia membedakan antara kota yang “punya jalur sepeda” dan kota yang benar-benar “ramah sepeda.” Kota sepeda sebagai proyek sosial, bukan infrastruktur semata.
Melalui studi kasus Belanda dan Denmark, Walker menunjukkan bahwa keberhasilan bersepeda massal bukan hasil budaya bawaan, tetapi hasil perjuangan politik sejak 1970-an. Gerakan warga, protes terhadap kematian anak akibat mobil, krisis minyak, dan keberanian pemerintah untuk membatasi mobil menjadi fondasi transformasi tersebut.
Ia menekankan bahwa kota sepeda adalah kota yang:
- memprioritaskan keselamatan daripada kecepatan,
- menganggap mobil sebagai tamu, bukan tuan,
- dan memahami bahwa ruang publik adalah sumber daya terbatas yang harus dibagi secara adil.
Walker mengutip data yang menunjukkan bahwa kota dengan tingkat bersepeda tinggi memiliki kualitas udara lebih baik, kesehatan publik lebih tinggi, dan bahkan ekonomi lokal yang lebih hidup—karena pesepeda lebih sering berhenti, berbelanja, dan berinteraksi.
Salah satu bab terkuat dalam Bike Nation membahas sepeda sebagai isu keadilan sosial. Walker menolak anggapan bahwa bersepeda adalah hobi kelas menengah urban yang “punya waktu”. Justru sebaliknya, di banyak kota, mereka yang paling bergantung pada sepeda adalah kelompok berpenghasilan rendah—tetapi mereka juga yang paling rentan terhadap bahaya lalu lintas.
Walker mengkritik kebijakan transportasi yang menginvestasikan miliaran pada infrastruktur mobil dan kereta cepat, tetapi mengabaikan kebutuhan perjalanan jarak pendek yang dilakukan jutaan orang setiap hari. Ia menunjukkan bahwa bersepeda adalah moda transportasi paling inklusif—jika negara mau melindunginya.
Dalam konteks ini, sepeda menjadi alat pembebasan: dari biaya bahan bakar, dari ketergantungan kredit kendaraan, dari waktu yang hilang di kemacetan. Walker menggemakan argumen yang sejalan dengan Elly Blue (Bikenomics) dan Jason Henderson (Street Fights in Copenhagen): transportasi adalah bentuk distribusi kekuasaan.
Iklim, Kesehatan, dan Masa Depan yang Masuk Akal
Walker sangat jelas dalam argumen ekologisnya. Transportasi adalah salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, dan elektrifikasi mobil saja tidak cukup. Produksi mobil listrik tetap membutuhkan energi besar, ruang besar, dan tetap menciptakan kemacetan. Sepeda, sebaliknya, hampir nol emisi sepanjang siklus hidupnya. Ia mengutip penelitian kesehatan publik yang menunjukkan bahwa manfaat bersepeda—dari penurunan penyakit jantung hingga kesehatan mental—jauh melampaui risiko kecelakaan, bahkan di kota yang belum sepenuhnya aman. Dalam istilah filsuf Hans Jonas, sepeda memenuhi prinsip tanggung jawab: teknologi yang manfaat jangka panjangnya tidak menghancurkan masa depan.
Ia juga mengaitkan sepeda dengan kebahagiaan sehari-hari—bukan sebagai hedonisme, tetapi sebagai bentuk kesejahteraan yang sederhana dan berkelanjutan.
Menurut Peter Walker kita hidup dalam sebuah paradoks modern: di satu sisi, negara-negara maju menghabiskan miliaran untuk sistem kesehatan, obat-obatan, dan kampanye hidup sehat; di sisi lain, mereka secara sistematis membangun kota yang membuat gerak tubuh sehari-hari menjadi hampir mustahil tanpa mesin. Dalam konteks inilah Walker menyebut sepeda sebagai miracle pill—obat ajaib yang murah, tersedia luas, tanpa paten, dan hampir tanpa efek samping, tetapi justru diabaikan oleh kebijakan publik.
Walker mengutip berbagai studi epidemiologi yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik moderat yang terintegrasi dalam rutinitas harian—seperti bersepeda ke tempat kerja—jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibanding olahraga rekreasional yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia merujuk pada penelitian besar di Inggris dan Denmark yang menunjukkan bahwa orang yang rutin bersepeda untuk transportasi memiliki risiko kematian dini hingga 40% lebih rendah dibanding mereka yang tidak aktif secara fisik, bahkan setelah dikontrol dengan faktor usia, kelas sosial, dan kebiasaan merokok.
Yang penting bagi Walker bukan hanya manfaat individual, tetapi dampak sistemik. Ia menunjukkan bahwa kota-kota dengan tingkat bersepeda tinggi memiliki beban biaya kesehatan publik yang lebih rendah, tingkat penyakit kardiovaskular yang lebih kecil, dan kualitas hidup yang lebih baik secara umum. Namun ironisnya, kebijakan kesehatan jarang sekali terhubung dengan kebijakan transportasi. Sepeda dipromosikan sebagai “pilihan gaya hidup sehat”, bukan sebagai infrastruktur kesehatan publik.
Walker juga mengkritik retorika “tanggung jawab individu” dalam kesehatan. Menurutnya, menyuruh orang berolahraga di kota yang berbahaya dan tidak ramah sepeda sama absurdnya dengan menyarankan diet sehat di lingkungan tanpa akses makanan segar. Kesehatan, dalam kerangka Walker, adalah hasil desain sosial—dan sepeda adalah salah satu desain paling sederhana namun paling efektif yang pernah ditemukan manusia. Sepeda adalah “The miracle pill. Bikes make everyone more healthy,” tulis Walker.
Jika sepeda begitu sehat dan murah, mengapa begitu banyak orang enggan menggunakannya? Bab ini menjawab pertanyaan itu dengan satu kata kunci: takut. Walker menekankan bahwa hambatan utama bersepeda bukanlah hujan, jarak, atau kemalasan, melainkan rasa tidak aman yang sangat rasional.
Penulis yang juga koresponden berita the Guardian” ini membawa pembaca pada pengalaman sehari-hari pesepeda di kota-kota yang didominasi mobil: bunyi klakson, kendaraan melintas terlalu dekat, “near misses” yang tidak tercatat sebagai kecelakaan tetapi meninggalkan trauma psikologis. Ia menegaskan bahwa statistik kecelakaan sering gagal menangkap kenyataan emosional di jalan. Banyak orang berhenti bersepeda bukan karena pernah ditabrak, tetapi karena hampir ditabrak—berulang kali.
Dengan merujuk pada riset transportasi di Inggris, Walker menunjukkan bahwa persepsi risiko sering kali lebih menentukan perilaku dibanding risiko aktual. Namun ia segera membalik argumen ini: persepsi tersebut bukan ilusi, melainkan refleksi dari desain jalan yang memang memprioritaskan kecepatan mobil. Di negara-negara dengan infrastruktur terpisah—Belanda, Denmark, sebagian Jerman—ketakutan itu hampir menghilang, dan bersepeda menjadi aktivitas lintas usia dan gender.
Walker menyoroti perbedaan demografis yang tajam: di kota-kota yang tidak aman, pesepeda didominasi laki-laki muda; di kota yang aman, perempuan, anak-anak, dan lansia mendominasi. Bagi Walker, ini adalah indikator politik yang sangat jelas: keselamatan jalan bukan soal keberanian, tetapi keadilan.
Walker yang pada tahun 2009 mendirikan Guardian Bike Blog ini mengkritik narasi yang menyalahkan pesepeda atas keselamatan mereka sendiri—memakai helm, lampu, rompi reflektif—sementara struktur bahaya tetap utuh. Walker tidak menentang keselamatan individual, tetapi menolak gagasan bahwa solusi utama ada pada perilaku korban, bukan pada sistem yang menciptakan risiko.
Di Bab 3 (Bikes Are More Equal Than Cars: Social Justice on Two Wheels) Walker membawa argumen bersepeda ke wilayah yang jarang dibahas secara terbuka: keadilan sosial dan ekonomi. Ia menyatakan secara tegas bahwa mobil bukan hanya alat transportasi, melainkan mesin ketimpangan.
Walker menunjukkan bagaimana ketergantungan pada mobil menciptakan biaya tersembunyi yang sangat regresif. Mereka yang berpenghasilan rendah menghabiskan proporsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk transportasi, sering kali demi akses ke pekerjaan yang letaknya semakin jauh akibat perencanaan kota berbasis mobil. Sepeda, sebaliknya, memiliki biaya awal dan operasional yang sangat rendah, serta membuka akses mobilitas bagi kelompok yang secara sistematis dikecualikan dari sistem berbasis mobil.
Ia yang pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 orang paling berpengaruh dalam dunia bersepeda di Inggris, mengutip contoh kota-kota yang berinvestasi pada sepeda dan melihat dampak langsung pada inklusi sosial. Akses ke pekerjaan meningkat, pengeluaran rumah tangga menurun, dan kualitas hidup membaik, terutama bagi perempuan, anak muda, dan kelompok minoritas. Ia juga menyoroti bahwa infrastruktur sepeda yang baik mengurangi ketergantungan pada subsidi bahan bakar fosil—yang sering kali lebih menguntungkan kelas menengah atas.
Bab ini juga membongkar mitos bahwa sepeda adalah simbol kemiskinan. Di banyak kota Eropa, justru kelompok berpendidikan dan berpenghasilan tinggi yang memilih bersepeda karena rasionalitas waktu, kesehatan, dan kenyamanan. Walker menekankan bahwa ketika sepeda menjadi normal, ia berhenti menjadi simbol status—dan justru di situlah kekuatannya.
Di banyak tempat di dunia, meski sepeda telah menjadi moda trasnportasi rakyat yang paling murah tetapi selalu diabaikan dalam kebijakan transoprtasi. Sepeda menghadapi salah satu argumen paling sering digunakan untuk menolak kebijakan pro-sepeda: bahwa ia merugikan ekonomi dan bisnis. Walker membongkar klaim ini dengan data, studi kasus, dan ironi yang tajam.
Ia menunjukkan bahwa kota-kota yang mengurangi ruang mobil dan memperluas infrastruktur sepeda—seperti Amsterdam, Copenhagen, Paris, dan bahkan sebagian London—justru mengalami peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Toko-toko kecil mendapatkan lebih banyak pelanggan karena pesepeda dan pejalan kaki lebih sering berhenti, berbelanja, dan berinteraksi dibanding pengendara mobil yang sekadar lewat.
Walker mengutip studi yang menunjukkan bahwa pesepeda, meski berbelanja lebih sedikit per kunjungan, berbelanja lebih sering dan secara total menghabiskan uang yang setara atau lebih besar dibanding pengendara mobil. Selain itu, infrastruktur sepeda membutuhkan investasi yang jauh lebih kecil dibanding jalan raya, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi yang berlipat.
Menariknya, Walker mencatat bahwa banyak perusahaan besar mulai mendukung kebijakan bersepeda bukan karena idealisme, tetapi karena pragmatisme. Kota yang ramah sepeda lebih menarik bagi pekerja terampil, memiliki tingkat absensi lebih rendah, dan citra merek yang lebih positif. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, kualitas hidup menjadi faktor produksi—dan sepeda memainkan peran kunci.
Bike Nation membalikkan logika pertumbuhan. Walker menyatakan bahwa sepeda tidak menghambat kemakmuran; ia mendefinisikan ulang apa itu kemakmuran. Bukan kecepatan dan volume, tetapi kesehatan, waktu, hubungan sosial, dan keberlanjutan.
Bike Nation ini membangun fondasi argumen yang konsisten: sepeda bukan solusi teknis semata, melainkan kritik sistemik terhadap cara kita membangun kota, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Ia adalah teknologi sederhana yang membuka pertanyaan paling radikal: untuk siapa kota ini dibangun, dan kehidupan macam apa yang ingin kita hidupi bersama.
Peter Walker membuka Bab 5 (Build It, and They Will Come) dengan sebuah pengamatan yang berulang kali terbukti di berbagai kota dunia, tetapi tetap diperdebatkan secara ideologis: orang akan bersepeda jika infrastrukturnya aman, nyaman, dan masuk akal. Pernyataan ini terdengar sederhana, namun ia menabrak salah satu dogma paling keras dalam politik transportasi—bahwa perilaku individu harus berubah lebih dulu sebelum negara berinvestasi.
Walker menunjukkan bagaimana skeptisisme terhadap infrastruktur sepeda sering berangkat dari logika terbalik. Pemerintah menunggu “permintaan” sebelum membangun jalur sepeda, padahal permintaan itu sendiri ditekan oleh rasa takut dan ketidaknyamanan. Ia menyamakan hal ini dengan membangun jembatan hanya setelah orang berani berenang menyeberangi sungai.
Contoh paling kuat datang dari kota-kota yang mengambil risiko politik. Di Seville, Spanyol, pembangunan jaringan jalur sepeda yang terhubung secara cepat—sekitar 120 kilometer dalam waktu kurang dari lima tahun—menghasilkan lonjakan pengguna sepeda hingga lebih dari 400%. Ini bukan hasil kampanye moral atau perubahan budaya perlahan, melainkan akibat langsung dari perubahan fisik ruang kota. Walker mengutip data pemerintah kota yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna baru adalah orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan bersepeda.
Walker juga mengulas fenomena induced demand, konsep yang biasanya dipakai untuk menjelaskan mengapa menambah jalan mobil justru menambah kemacetan. Ia membalik logika ini: jalur sepeda yang baik menciptakan permintaan bersepeda, tetapi dengan dampak sosial yang positif—lebih sedikit polusi, lebih sedikit kecelakaan, dan ruang publik yang lebih hidup.
Bab ini menegaskan bahwa infrastruktur adalah pernyataan nilai. Kota yang membangun jalur sepeda mengatakan kepada warganya: “Kalian penting, bahkan ketika kalian tidak berada di dalam mobil.” Dalam pandangan Walker, ini adalah bentuk kebijakan publik yang paling nyata dan paling jujur.
Jika Bab 5 berbicara tentang harapan, Walker juga tak lupa membawa pembaca ke wilayah yang lebih gelap: kebencian terhadap pesepeda. Walker menulis dengan nada tajam dan personal, membongkar mengapa pesepeda sering menjadi sasaran kemarahan yang tampak tidak proporsional.
Ia menegaskan bahwa kebencian ini bukan soal perilaku pesepeda semata, meskipun media sering menyoroti pelanggaran kecil sebagai bukti “ketidaksopanan”. Walker menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pengendara mobil jauh lebih sering dan lebih mematikan, tetapi jarang dibingkai sebagai masalah moral kolektif.
Menurut penulis buku yang masuk dalam nominasi penghargaan Cycling Media Awards ini, kebencian terhadap pesepeda berakar pada ancaman simbolik. Sepeda menantang dominasi mobil atas ruang jalan—ruang yang selama puluhan tahun diperlakukan seolah-olah milik eksklusif kendaraan bermotor. Kehadiran pesepeda memaksa pengendara mobil untuk melambat, berbagi, dan menyadari keberadaan orang lain. Dalam masyarakat yang dibentuk oleh kecepatan dan individualisme, ini dirasakan sebagai gangguan.
Walker juga membahas peran media dalam membentuk narasi. Ia mengutip headline dan kolom opini yang menggambarkan pesepeda sebagai elit, sok suci, atau anti-kemajuan. Narasi ini sering kali mengabaikan fakta bahwa pesepeda berasal dari semua lapisan sosial, dan bahwa bersepeda sering kali merupakan pilihan rasional, bukan ideologis.
Walker menyentuh dimensi psikologis yang dalam. Walker mengaitkan kebencian terhadap pesepeda dengan apa yang disebut para peneliti sebagai dehumanization: pesepeda dilihat bukan sebagai manusia utuh, tetapi sebagai objek pengganggu. Ini menjelaskan mengapa agresi terhadap pesepeda—dari umpatan hingga kekerasan fisik—sering dianggap remeh.
Bagian yang sangat menarik dan menantang dari Bike Nation adalah pemaparan dan analisis menuju aksi. Di sini, Walker menulis tentang momen-momen ketika bersepeda berhenti menjadi pilihan individual dan berubah menjadi gerakan politik.
Ia mengisahkan sejarah aksi die-in, di mana aktivis berbaring di jalan untuk merepresentasikan korban kecelakaan lalu lintas. Aksi ini, yang sering dianggap mengganggu atau ekstrem, dipahami Walker sebagai respons terhadap kekerasan struktural yang jauh lebih besar—ribuan kematian setiap tahun akibat kebijakan transportasi yang memprioritaskan kecepatan di atas keselamatan.
Walker mengaitkan keberanian politik ini dengan tradisi panjang perlawanan sipil non-kekerasan. Ia menekankan bahwa banyak kemajuan dalam kebijakan sepeda tidak datang dari konsensus yang tenang, tetapi dari konflik terbuka. Di London, New York, dan Paris, perubahan signifikan sering kali didahului oleh protes, tekanan publik, dan figur-figur politik yang bersedia mengambil risiko elektoral.
Pada bagian activism ini Bike Nation membahas bagaimana aktivisme sepeda berhasil membingkai ulang isu transportasi sebagai isu kesehatan, iklim, dan keadilan sosial. Walker menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan ini bukan hanya karena tuntutannya masuk akal, tetapi karena ia mampu menghubungkan pengalaman sehari-hari—rasa takut di jalan, kemacetan, udara kotor—dengan struktur kekuasaan yang lebih besar.
Walker menutup bagian ini dengan refleksi tentang keberanian. Dalam dunia politik yang sering terjebak pada kehati-hatian dan kompromi, kebijakan pro-sepeda membutuhkan pemimpin yang berani tidak populer dalam jangka pendek demi manfaat jangka panjang. Ia menegaskan bahwa sejarah kota-kota ramah sepeda adalah sejarah tentang keputusan sulit yang diambil sebelum mayoritas siap menerimanya.
Bike Nation memperlihatkan bahwa bersepeda bukan sekadar soal transportasi, tetapi medan konflik tentang ruang, kekuasaan, dan masa depan kota. Infrastruktur menciptakan kemungkinan, kebencian mengungkap ketegangan, dan aktivisme membuka jalan bagi perubahan. Bersama-sama, ketiganya membentuk narasi tentang bagaimana teknologi sederhana bernama sepeda mampu mengguncang tatanan sosial yang tampak mapan.
Berikut adalah elaborasi naratif–deskriptif yang mendalam untuk Bab 8, Bab 9, dan Epilog dari Bike Nation: How Cycling Can Save the World karya Peter Walker. Teks ini ditulis mengalir tanpa pointer, dengan penjelasan contoh konkret, data yang lazim dirujuk Walker, serta analisis kebijakan dan budaya yang menjadi penutup argumen besar buku ini.
“If Bike Helmets Are the Answer, You’re Asking the Wrong Question,” tulis Wlakter (Bab 8). Bab ini merupakan salah satu bagian paling provokatif dalam Bike Nation, karena Walker secara sengaja menantang asumsi yang selama ini dianggap “akal sehat”: bahwa keselamatan pesepeda terutama ditentukan oleh penggunaan helm. Ia tidak menolak helm sebagai alat pelindung individual, tetapi membongkar bagaimana fokus obsesif pada helm justru mengaburkan persoalan yang jauh lebih mendasar—mengapa jalan raya dibuat berbahaya sejak awal.
Walker membuka dengan ironi kebijakan. Di banyak negara berbahasa Inggris, setiap diskusi tentang keselamatan bersepeda hampir selalu berakhir pada pertanyaan: “Apakah dia memakai helm?” Pertanyaan ini, menurut Walker, secara halus memindahkan tanggung jawab dari sistem ke individu. Jika terjadi kecelakaan, kesalahan seolah berada pada kepala pesepeda, bukan pada desain jalan, kecepatan kendaraan, atau prioritas transportasi. Ia mengontraskan pendekatan ini dengan Belanda dan Denmark, dua negara dengan tingkat keselamatan pesepeda tertinggi di dunia. Di sana, penggunaan helm relatif rendah dibandingkan negara seperti Australia atau Inggris, tetapi angka kematian pesepeda jauh lebih kecil. Walker mengutip data keselamatan lalu lintas yang menunjukkan bahwa risiko kematian per kilometer bersepeda di Belanda berkali-kali lebih rendah dibandingkan negara yang justru sangat menekankan helm. Perbedaannya bukan pada perilaku individu, melainkan pada infrastruktur yang memisahkan konflik, menurunkan kecepatan, dan memanusiakan jalan.
Walker juga mengulas riset yang menunjukkan bahwa kewajiban helm dapat menurunkan jumlah orang yang mau bersepeda. Di Australia, setelah penerapan hukum wajib helm, jumlah pesepeda menurun signifikan, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Dampak ini menciptakan paradoks: kebijakan yang dimaksudkan untuk keselamatan justru mengurangi manfaat kesehatan populasi secara keseluruhan, karena lebih sedikit orang bergerak aktif.
Lebih jauh, Walker membahas konsep risk compensation—gagasan bahwa pengendara mobil cenderung berkendara lebih agresif ketika melihat pesepeda berhelm, seolah perlindungan itu memberi izin tak sadar untuk mengambil jarak lebih dekat. Ia tidak mengklaim efek ini tunggal atau mutlak, tetapi menggunakannya untuk menunjukkan betapa rumitnya keselamatan jika hanya dipahami sebagai perlengkapan, bukan relasi kuasa di jalan.
Ini adalah kritik terhadap cara berpikir yang teknokratis dan moralistik. Walker menulis dengan tegas bahwa jalan yang aman tidak diciptakan oleh busa dan plastik, melainkan oleh politik ruang, desain kota, dan keberanian untuk menantang dominasi mobil. Helm mungkin melindungi kepala, tetapi tidak akan pernah menyembuhkan sistem yang sakit.
Walker juga megundang pembaca untuk refleksi yang lebih filosofis tentang sepeda sebagai teknologi. Ia menolak melihat sepeda sebagai alat kuno atau sekadar alternatif murah dari mobil. Sebaliknya, ia menyebut sepeda sebagai salah satu teknologi paling canggih yang pernah diciptakan manusia—bukan karena kompleksitasnya, melainkan karena kesempurnaan fungsionalnya.
Walker menelusuri sejarah sepeda sebagai teknologi yang hampir tidak memerlukan “pembaruan disruptif”. Desain dasarnya telah stabil selama lebih dari satu abad, namun tetap relevan di dunia modern. Ia mengutip studi teknik yang menunjukkan bahwa sepeda adalah alat transportasi paling efisien secara energi: dengan satu kalori tenaga manusia, sepeda dapat membawa tubuh sejauh beberapa kali lipat dibandingkan berjalan kaki, dan jauh melampaui kendaraan bermotor jika dihitung per unit energi.
Ia juga menempatkan sepeda dalam konteks krisis global—perubahan iklim, polusi udara, dan kota yang kehabisan ruang. Walker menunjukkan bahwa sepeda bukanlah solusi masa depan yang belum datang, melainkan solusi yang sudah ada tetapi diabaikan. Di kota-kota yang berinvestasi serius, sepeda mampu menggantikan perjalanan mobil jarak pendek dalam skala besar, mengurangi emisi, dan meningkatkan kualitas hidup secara nyata. Ia juga membahas teknologi pendukung: sepeda listrik, sistem berbagi sepeda, dan navigasi digital. Walker tidak memuja teknologi baru secara naif, tetapi melihatnya sebagai perpanjangan dari prinsip dasar sepeda—memperluas akses tanpa mengorbankan kesederhanaan. Sepeda listrik, misalnya, memungkinkan lansia, pekerja jarak jauh, dan mereka yang tinggal di kota berbukit untuk bersepeda tanpa mengubah karakter ruang kota.
Yang paling penting, Walker menegaskan bahwa sepeda adalah teknologi yang bersahabat dengan tubuh manusia, bukan memisahkannya. Tidak seperti mobil yang mengisolasi penggunanya, sepeda menempatkan tubuh dalam dialog dengan kota—dengan cuaca, suara, bau, dan kehadiran orang lain. Dalam pengertian ini, sepeda bukan hanya alat transportasi, tetapi juga medium pengalaman.
Dalam epilog, Walker menolak narasi futuristik yang selalu menunda perubahan. Ia menulis bahwa masa depan yang lebih adil, sehat, dan manusiawi tidak menunggu inovasi spektakuler, karena ia sudah hadir dalam bentuk yang paling sederhana: orang-orang yang bersepeda hari ini. “The Future Is Here,” tulis dengan penuh optimisme.
Walker menutup buku dengan refleksi tentang kota-kota yang telah berubah. Ia mengingatkan pembaca bahwa keberhasilan Kopenhagen, Amsterdam, atau Paris pasca-reformasi transportasi bukan hasil kebetulan budaya, melainkan keputusan politik yang konkret. Jalur sepeda, pembatasan mobil, dan keberanian untuk menghadapi kemarahan jangka pendek telah membuahkan kota yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih demokratis. Ia juga menekankan bahwa bersepeda bukan utopia bebas konflik. Akan selalu ada resistensi, ejekan, dan ketakutan. Namun, Walker menulis dengan keyakinan bahwa setiap jalur sepeda baru, setiap anak yang bersepeda ke sekolah, dan setiap jalan yang diperlambat adalah bukti bahwa perubahan itu nyata dan terukur.
Epilog yang ditulis tidak menawarkan akhir yang romantis, melainkan ajakan yang tenang namun tegas: masa depan tidak perlu ditemukan—ia perlu dipilih. Sepeda, dalam pandangan Walker, adalah salah satu pilihan paling jelas yang pernah kita miliki. Ia tidak menjanjikan kesempurnaan, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih berharga: kota yang kembali berskala manusia, dan teknologi yang melayani kehidupan, bukan sebaliknya. Dengan demikian, Bike Nation berakhir bukan sebagai manifesto yang berteriak, melainkan sebagai kesaksian bahwa dunia yang lebih masuk akal sudah ada di depan mata—dan sering kali, ia melaju perlahan di atas dua roda.
Sepeda, Degrowth Mobility, dan Masa Depan Kota Indonesia
Peter Walker menulis Bike Nation dengan keyakinan sederhana namun radikal: sepeda bukan sekadar alat transportasi, melainkan pilihan politik tentang bagaimana sebuah masyarakat mengatur hidup bersama. Ketika buku ini dibaca dari Jakarta atau Bandung, maknanya tidak melemah—justru menjadi lebih mendesak. Kota-kota Indonesia hari ini berada pada persimpangan yang sama dengan kota-kota Barat pada dekade 1960–70-an: apakah terus mengejar mobilitas berbasis pertumbuhan tanpa batas, atau berani menggeser paradigma menuju degrowth mobility—mobilitas yang mengurangi kecepatan, volume, dan ekstraksi, demi kualitas hidup.
Jakarta: Kota yang Terlalu Cepat untuk Warganya
Jakarta adalah contoh ekstrem dari apa yang oleh Walker sebut sebagai kota yang “dirancang untuk kendaraan, bukan manusia”. Jalan-jalan lebar, flyover berlapis, dan proyek infrastruktur raksasa mencerminkan logika lama: semakin cepat dan semakin banyak kendaraan, semakin maju kota itu. Namun realitas Jakarta justru sebaliknya. Kemacetan kronis, polusi udara yang berulang kali menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, serta hilangnya ruang hidup pejalan kaki menunjukkan kegagalan logika pertumbuhan mobilitas.
Dalam kacamata Bike Nation, persoalan Jakarta bukan kekurangan teknologi, melainkan kelebihan mobil. Degrowth mobility di Jakarta berarti berani mengakui bahwa solusi tidak terletak pada menambah jalan atau kendaraan listrik semata, tetapi pada mengurangi dominasi mobil pribadi. Jalur sepeda permanen yang sempat tumbuh selama pandemi COVID-19 adalah eksperimen penting: ketika ruang jalan dikembalikan ke tubuh manusia, kota menjadi lebih lambat, lebih terbaca, dan lebih adil.
Walker menekankan bahwa keselamatan pesepeda bukan soal helm, melainkan desain sistem. Jakarta sering gagal di titik ini. Jalur sepeda yang terputus-putus dan mudah dihapus menunjukkan bahwa sepeda masih dianggap “tamu sementara”, bukan warga kota yang sah. Degrowth mobility menuntut pembalikan logika: mobil adalah tamu, sepeda dan pejalan kaki adalah tuan rumah.
Bandung: Antara Imajinasi Progresif dan Realitas Topografi Sosial
Bandung sering dipuji sebagai kota kreatif, progresif, dan eksperimental. Secara budaya, Bandung lebih dekat pada ethos bersepeda yang dibayangkan Walker: komunitas sepeda tumbuh, jarak relatif pendek, dan iklim sosial yang lebih cair. Namun Bandung juga memperlihatkan paradoks khas kota Indonesia menengah—kota yang ingin modern, tetapi terjebak dalam imitasi mobilitas kota besar.
Topografi Bandung yang berbukit sering dijadikan alasan mengapa sepeda “tidak realistis”. Bike Nation justru membantah asumsi ini. Walker menunjukkan bagaimana kota-kota berbukit di Eropa berhasil mengintegrasikan sepeda melalui e-bike, jalur aman, dan pembatasan kecepatan mobil. Di Bandung, tantangan sebenarnya bukan kontur tanah, melainkan kontur kekuasaan ruang: siapa yang berhak atas jalan, dan untuk kepentingan siapa kota dibangun.
Degrowth mobility di Bandung berarti mengakui bahwa kota ini tidak perlu “mengejar Jakarta”. Bandung tidak perlu lebih cepat, lebih besar, atau lebih padat kendaraan. Justru kekuatannya terletak pada skala manusia—kampung kota, jalan kecil, dan ritme hidup yang bisa dilambatkan. Sepeda di Bandung bukan simbol efisiensi semata, melainkan alat untuk merawat kedekatan sosial dan ekologis.
Kota-Kota Indonesia Lain: Sepeda sebagai Mobilitas Cukup
Di luar Jakarta dan Bandung, banyak kota Indonesia—Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Malang, Mataram—secara struktural sebenarnya lebih “siap” untuk degrowth mobility. Jarak pendek, kepadatan sedang, dan budaya jalan yang masih cair memungkinkan sepeda menjadi moda utama, bukan alternatif. Namun justru di kota-kota ini, mimpi modernitas sering diwujudkan dalam bentuk motor dan mobil murah.
Walker menulis bahwa kebencian terhadap pesepeda sering muncul ketika sepeda mengganggu tatanan lama. Di Indonesia, sepeda sering dianggap simbol kemiskinan masa lalu atau hobi kelas menengah perkotaan, bukan alat mobilitas warga. Degrowth mobility menantang stigma ini dengan mengembalikan sepeda ke fungsi dasarnya: alat hidup sehari-hari yang cukup, murah, dan adil.
Di kota-kota kecil, degrowth mobility berarti mencegah kesalahan Jakarta terulang. Artinya bukan menunggu macet dulu baru membangun jalur sepeda, tetapi menata kota sejak awal untuk kecepatan rendah dan interaksi tinggi.
Kita perlu mendorong sepeda sebagai kritik pertumbuhan di indonesia. Bike Nation bukan hanya buku tentang sepeda, tetapi tentang kritik terhadap ide bahwa kemajuan selalu berarti lebih cepat, lebih jauh, dan lebih banyak. Dalam konteks Indonesia, kritik ini sangat relevan. Pertumbuhan ekonomi sering diukur melalui penjualan kendaraan, pembangunan jalan tol, dan konsumsi energi. Sepeda, dalam logika ini, tampak “tidak produktif”.
Namun degrowth mobility mengajukan ukuran lain: kesehatan publik, waktu luang, udara bersih, dan keadilan ruang. Sepeda menghasilkan nilai tanpa ekstraksi berlebihan. Ia menciptakan kerja lokal (bengkel, perawatan, manufaktur kecil), mengurangi biaya kesehatan, dan memperkuat ekonomi sehari-hari—sebuah economy of enough.
Dalam tradisi Nusantara sendiri, mobilitas tidak pernah dipahami sebagai kecepatan maksimum. Jalan kampung, lorong, dan pasar dirancang untuk perjumpaan, bukan pelarian. Sepeda, dalam pengertian ini, bukan teknologi asing, melainkan kelanjutan modern dari etika bergerak Nusantara.
Catatan Akhir: Satu Sepeda, Enam Cara Membaca Dunia
Berikut ini adalah ringkasan dari enam buku yang membincangkan tentang sepeda. Pertama adalah buku yang jadi pembahasan utama dalam tulisan ini: Bike Nation (Peter Walker). Buku mempunya nada utama: jurnalisme investigatif + advokasi kebijakan. Walker menulis Bike Nation sebagai argumen publik. Sepeda diperlakukan sebagai “pil ajaib” kebijakan: murah, efektif, berdampak sistemik. Fokusnya bukan pada pesepeda sebagai identitas, tetapi pada sepeda sebagai infrastruktur sosial. Walker menelusuri data kesehatan, ekonomi, keselamatan, hingga politik kebencian terhadap pesepeda. → Jika sepeda adalah solusi, maka masalahnya adalah struktur kota berbasis mobil.
Kedua Bikenomics (Elly Blue) yang fokus pada ekonomi feminis + keadilan sosial. Jika Bike Nation bertanya mengapa sepeda masuk akal, Bikenomics bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Blue membongkar mitos “free rider” dan menunjukkan bahwa mobil disubsidi besar-besaran, sementara sepeda justru menanggung biaya eksternal paling kecil. → Sepeda di sini adalah alat redistribusi keadilan ekonomi, bukan sekadar gaya hidup hijau.
Ketiga, Two Wheels Good (Jody Rosen) yang mengupas sejarah kultural + esai reflektif. Rosen membawa sepeda ke wilayah imajinasi, budaya, dan filosofi. Ia menulis tentang sepeda sebagai mesin emansipasi perempuan, simbol modernitas awal, hingga alat perlawanan. Tidak fokus pada kebijakan, tetapi pada makna eksistensial dan sejarah panjang sepeda. → Jika Walker dan Blue bicara solusi, Rosen bicara makna. Keempat, In the City of Bikes / The Story of the Amsterdam Cyclist (Pete Jordan). Jordan menulis buku ini dengan pendekatan etnografi personal + sejarah kota. Jordan menulis Amsterdam dari bawah: dari pengalaman tubuh, kebiasaan harian, dan budaya bersepeda yang tampak biasa namun politis. Sepeda tidak dirayakan sebagai ideologi, melainkan sebagai kenormalan sosial. → Buku ini menunjukkan hasil akhir dari politik sepeda: ketika sepeda tidak perlu dibela lagi.
Kelima, On Bicycles (Evan Friss) yang menceritakan sejarah urban + politik ruang. Friss membaca sepeda sebagai penanda konflik kelas, ras, dan ruang publik di New York selama dua abad. Dari sepeda elit abad ke-19 hingga kurir dan pekerja migran, sepeda selalu hadir dalam pertarungan “siapa berhak atas jalan”. → Sepeda adalah arsip konflik kota. Keenam, Street Fights in Copenhagen (Henderson & Gulsrud) yang membahas politik perencanaan + konflik kebijakan. Buku ini membongkar mitos Kopenhagen sebagai “kota sepeda alami”. Justru sebaliknya: kota itu dibentuk oleh pertarungan keras—tentang parkir, jalan tol, terowongan, dan metro. → Sepeda tidak pernah netral; ia menang karena politik yang gigih.
Enam buku, satu alur besar. Jika dibaca sebagai satu kesatuan, keenam buku ini membentuk alur logis:
- Rosen memberi kita sejarah makna
- Friss memberi kita sejarah konflik
- Jordan menunjukkan kehidupan setelah konflik
- Henderson & Gulsrud membongkar politik di balik keberhasilan
- Blue menjelaskan keadilan ekonomi sepeda
- Walker menyusun argumen kebijakan untuk masa depan
Bersama-sama, mereka menyatakan satu hal: Sepeda bukan teknologi kecil, melainkan koreksi radikal terhadap kota kapitalistik.
Tabel Perbandingan Enam Buku Kunci tentang Sepeda
| Buku | Fokus Utama | Pendekatan | Skala Analisis | Kontribusi Kunci | Kekuatan Unik |
| Bike Nation (Walker) | Kebijakan publik & kesehatan | Jurnalisme data & advokasi | Nasional & global | Sepeda sebagai solusi sistemik | Argumentatif, berbasis bukti |
| Bikenomics (Blue) | Ekonomi & keadilan sosial | Ekonomi politik feminis | Kota & komunitas | Membongkar subsidi mobil | Perspektif kelas & gender |
| Two Wheels Good (Rosen) | Sejarah & budaya | Esai sejarah naratif | Global-historis | Makna sepeda dalam modernitas | Kedalaman filosofis |
| In the City of Bikes (Jordan) | Budaya bersepeda | Etnografi personal | Kota (Amsterdam) | Normalisasi sepeda | Kehidupan sehari-hari |
| On Bicycles (Friss) | Sejarah urban | Arsip & sejarah sosial | Kota (NYC) | Sepeda sebagai konflik ruang | Analisis historis tajam |
| Street Fights in Copenhagen | Politik perencanaan | Studi kebijakan kritis | Kota (Kopenhagen) | Mengungkap mitos kota sepeda | Realisme politik |
Membaca Bike Nation dari Indonesia membawa kita pada kesimpulan yang sederhana namun menantang: masa depan kota tidak akan diselamatkan oleh kendaraan yang lebih cepat atau lebih canggih, tetapi oleh keberanian untuk melambat. Jakarta, Bandung, dan kota-kota Indonesia lainnya tidak perlu menjadi “Bike Nation” versi Eropa, tetapi bisa menjadi Bike Nusantara—kota-kota yang memilih kecukupan daripada kelebihan.
Degrowth mobility bukan anti-kemajuan. Ia adalah keberanian untuk bertanya: cukup bagi siapa, dan terlalu banyak untuk siapa? Sepeda, dalam konteks ini, bukan solusi tunggal, tetapi simbol pilihan peradaban—pilihan untuk membangun kota yang layak hidup, bukan sekadar layak dilewati.
Di balik semua data dan kebijakan, Bike Nation adalah buku tentang imajinasi moral. Sepeda sebagai Imajinasi moral. Walker bertanya: kota seperti apa yang kita anggap normal? Apakah normal bahwa anak-anak tidak bisa bermain di jalan? Bahwa perjalanan 5 km memerlukan mesin satu ton? Bahwa udara kotor dianggap harga kemajuan?
Di titik ini, sepeda muncul sebagai simbol perlawanan yang tenang. Seperti yang ditulis Ivan Illich, teknologi yang baik adalah teknologi yang memperluas kebebasan tanpa menciptakan dominasi. Walker, dengan bahasa jurnalistik yang jernih, menunjukkan bahwa sepeda adalah contoh nyata prinsip itu.
Ia juga sejalan dengan pemikir Muslim seperti Fazlur Rahman dan Seyyed Hossein Nasr, yang mengkritik modernitas karena memutus hubungan etika antara manusia, alam, dan teknologi. Sepeda, dalam pembacaan ini, adalah alat yang masih menjaga amanah—tidak merusak lebih dari yang ia berikan.
Bike Nation tidak menawarkan utopia. Dunia bisa dikayuh. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berani: contoh nyata bahwa dunia lain bukan hanya mungkin, tetapi sudah ada—di kota-kota yang memilih melindungi pesepeda, membatasi mobil, dan mengembalikan jalan kepada manusia.
Sepeda tidak menyelamatkan dunia karena ia sempurna, tetapi karena ia masuk akal. Dalam dunia yang dibangun terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu mahal, sepeda mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati sering kali berarti melakukan lebih sedikit, tetapi dengan lebih bijaksana.
Bogor, 24 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Walker, P. (2017). Bike Nation: How Cycling Can Save the World. London: Yellow Jersey.
Illich, I. (1973). Tools for Conviviality. New York: Harper & Row.
Henderson, J., & Gulsrud, N. M. (2019). Street Fights in Copenhagen: Bicycle and Car Politics in a Green Mobility City. Routledge.
Blue, E. (2016). Bikenomics: How Bicycling Can Save the Economy. Microcosm Publishing.
WHO. (2014). Health economic assessment tools (HEAT) for walking and cycling. World Health Organization.
https://www.who.int/tools/heat-for-walking-and-cycling
Nasr, S. H. (1996). Religion and the Order of Nature. Oxford University Press.