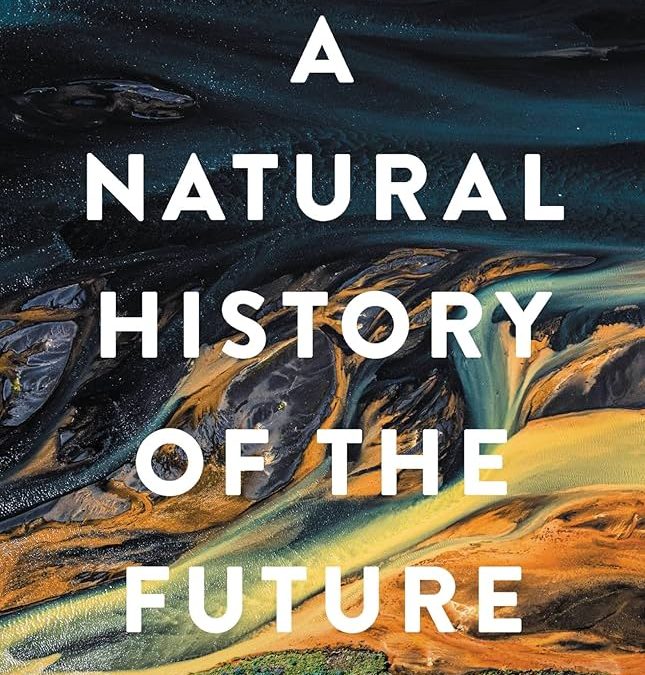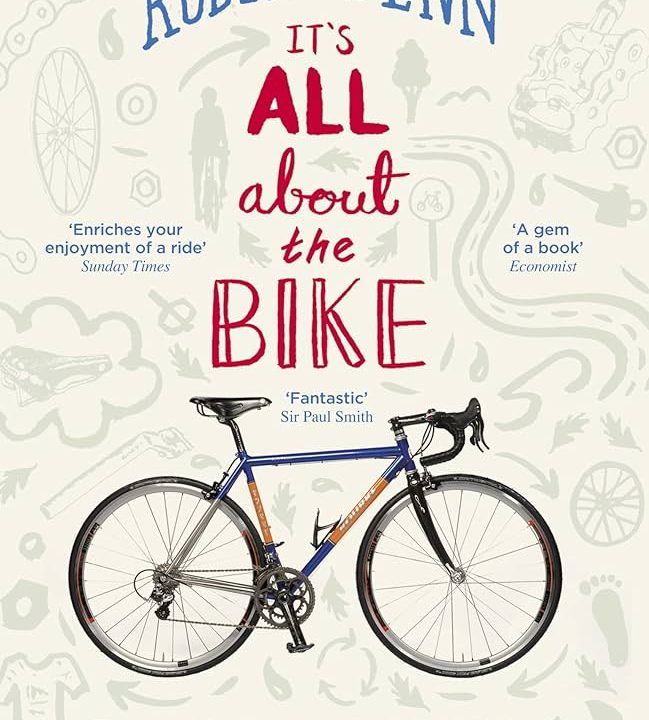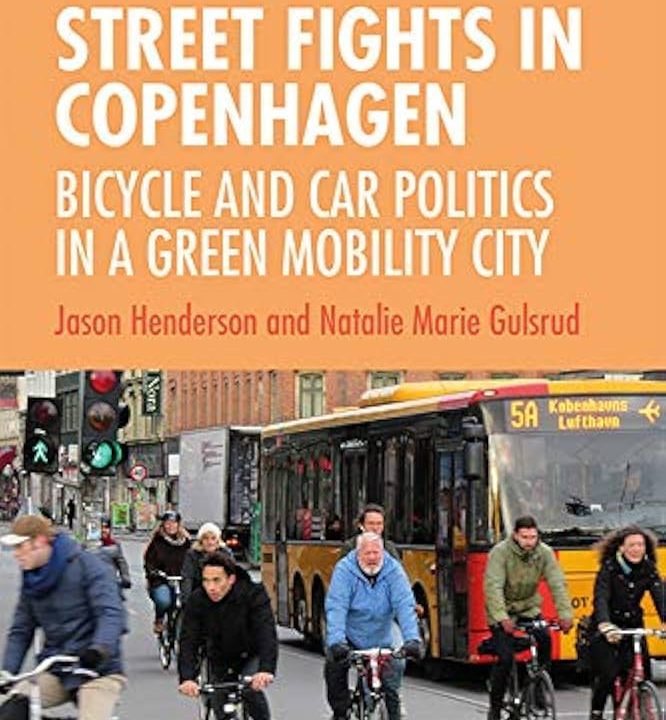Rubarubu #90
A Natural History of the Future:
Pelajaran dari Sejarah Alam dan Hukum Biologi
Kisah Banjir di Mississippi dan Hukum Alam yang Tak Terbantahkan
Bayangkan sebuah kota kecil di tepi sungai Mississippi. Hujan turun tanpa henti selama beberapa minggu, air naik, menelan rumah dan ladang, membanjiri jalanan, dan melumpuhkan kehidupan. Para insinyur kemudian datang dan mencoba menaklukkan sungai itu—meluruskan alur, memaksakan pipa dan bendungan, meyakini bahwa manusia bisa “mengatur” sungai sesuai kehendaknya. Namun pada suatu pagi, sungai itu tetap berdetak sesuai irama sendiri: ia meluap, mencari jalur baru, dan buang air ke dataran rendah. Meski manusia telah mencoba menata dunia, alam memiliki hukum-hukum sendiri yang tidak bisa kita tulis ulang. Itulah cerita yang mengiringi Rob Dunn saat ia menulis A Natural History of the Future: What the Laws of Biology Tell Us About the Destiny of the Human Species (Basic Books, 2021): bahwa entah kita menyadarinya atau tidak, masa depan manusia bukan ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh hukum biologi yang tak terhapus oleh perangkat apa pun. PublishersWeekly.com+1
Dalam Introduction, Dunn membuka dengan refleksi tentang bagaimana manusia modern telah begitu sibuk “mengendalikan” alam melalui teknologi, pertanian masif, dan pembangunan perkotaan sehingga kita mengabaikan apa yang sebenarnya membuat kehidupan bertahan dan berubah selama jutaan tahun. Ia menantang narasi futurisme yang berpusat pada teknologi—robot, AI, bioengineering sebagai penyelamat—dan justru mengarahkan perhatian pada hukum-hukum dasar biologi seperti seleksi alam, area-spesies (species-area law), dan hubungan antara spesies dan habitatnya. PublishersWeekly.com
Dunn memperkenalkan ide bahwa kehidupan adalah sistem yang dinamis dan berlapis, di mana setiap komponen—mikroba, tanaman, hewan, bahkan virus—berinteraksi dan berevolusi dalam pola yang dapat dipahami melalui hukum evolusi dan ekologi. Alih-alih sekadar memprediksi masa depan dengan model teknologi, kita perlu memahami masa depan melalui hukum-hukum yang telah membentuk kehidupan selama jutaan tahun. Dunn menunjukkan bahwa manusia sering lupa bahwa kita bukan penguasa alam, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang lebih luas. Kirkus Reviews
Ia juga menegaskan bahwa kita hidup dalam dunia yang lebih dominan oleh manusia daripada oleh kehidupan alami: angka dari kajian ekologi menunjukkan bahwa vertebrata liar kini hanya sekitar 3% dari biomassa vertebrata, sementara hewan domestik mencapai 65% dan manusia sisanya — gambaran dramatis tentang bagaimana kita telah merubah struktur kehidupan di planet ini. Kirkus Reviews
Hukum Biologi sebagai Lampu Panduan
Dunn menegaskan bahwa seleksi alam bukan prinsip masa lalu, melainkan kekuatan aktif yang terus membentuk kehidupan, termasuk kita sendiri dan organisme yang hidup berdampingan dengan kita. Hukum seleksi alam dan evolusi yang terus berlangsung. Dari bakteri yang cepat berevolusi menjadi resistensi antibiotik hingga serangga yang berkembang di kota, hukum ini menunjukkan bahwa biologi selalu bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Kirkus Reviews
Kisah-kisah seperti evolusi kecerdasan tertentu pada gelatik kota atau mikroba yang hidup di sistem transportasi bawah tanah seperti London Underground mengilustrasikan bahwa kehidupan akan terus beradaptasi sekalipun terhadap lingkungan buatan manusia. Kirkus Reviews Cerita ini mirip dengan ungkapan pemikir seperti Edward O. Wilson bahwa kita harus belajar menghormati batas biologi karena “kita hidup pada istilah alam, bukan istilah kita sendiri.” (secara tematik dirangkum dari ulasan editorial buku) Barnes & Noble
Dunn membahas konsep niche—tempat suatu organisme dapat hidup dan berperan dalam ekosistem. Semua saling terhubung antara habitat, niche, dan ketergantungan biologis. Ketika manusia mendesain kota, perkebunan, dan wilayah industri, kita sering mengabaikan bahwa setiap spesies memiliki kebutuhan ekologis yang spesifik. Upaya kita untuk menciptakan “lingkungan tanpa masalah” sering melahirkan konsekuensi tak terduga karena hukum alam terus berlaku; misalnya, spesies menjadi invasif atau wabah penyakit muncul dari adaptasi yang tidak terduga. ICPL Search
Kesalahan manusia sering bersumber dari antropocentrisme—keyakinan bahwa dunia hanya berputar di sekitar kebutuhan manusia. Padahal, dari jutaan mikroba dalam tanah hingga sejumlah besar spesies serangga yang belum diberi nama, kehidupan jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang kita pelajari atau kendalikan. NHBS
Karena itulah masa depan tidak bisa dipisahkan dari biologi. Dunn tidak sekadar menulis tentang hubungan manusia dan alam secara teoritis. Ia menjelaskan secara konkret bagaimana masa depan kehidupan di Bumi—termasuk kehidupan manusia—pasti mengikuti hukum biologi. Apapun usaha kita untuk memodifikasi atau mengatasi alam melalui teknologi, alam akan tetap merespons menurut prinsip evolusi dan ekologi yang tidak berubah. PublishersWeekly.com
Sebagai contoh, ia memperlihatkan bahwa manusia mungkin bisa memanipulasi gens tertentu, tetapi tidak mungkin sepenuhnya menghentikan evolusi atau mutasi organisme lain. Begitu juga ketika kita membangun pertanian modern, spesies beradaptasi, serangga menjadi resisten terhadap pestisida, dan bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Hukum-hukum ini bukan sekadar konsep akademik, tetapi pedoman hidup nyata yang menentukan keberlangsungan kita sendiri.
Gagasan Dunn sangat relevan dengan persoalan sustainability global saat ini. Dalam konteks Perubahan Iklim, A Natural History of the Future menunjukkan bahwa mitigasi dampak iklim tidak cukup hanya dengan teknologi rendah emisi atau teknologi bersih; kita perlu memahami dan menghormati hukum biologi yang mengatur sistem hidup besar dan kecil. Ketika kita me-lihat fenomena seperti Holocene extinction—di mana tingkat kepunahan spesies meningkat jauh di atas laju alami—kita menyaksikan hukum evolusi sekaligus akibat dari aktivitas manusia yang melampaui batas ekologis. Wikipedia
Secara global, gagasan ini mendorong pendekatan keberlanjutan yang memadukan kebijakan ilmiah dan penghormatan terhadap sistem alami. Di Indonesia, tantangan seperti deforestasi hutan hujan tropis, hilangnya keanekaragaman hayati (misalnya orangutan dan badak Jawa), serta degradasi lahan pertanian adalah contoh nyata bagaimana manusia sering mencoba “menata” alam tanpa memahami niche ekologis dan hukum ketergantungan antarspesies. Dunn menegaskan bahwa kita tidak bisa merencanakan masa depan kota, pertanian, atau kawasan industri tanpa mempertimbangkan hukum biologi yang tak kita kendalikan. Kirkus Reviews
Buku ini juga menekankan pentingnya memandang mikroorganisme—yang sering tidak terlihat namun sangat menentukan kesehatan manusia, tanah, dan sistem pertanian. Dunn mencatat bahwa microbiome (mikrobiota usus dan lainnya) adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem global, dan hubungan kita dengan mikrobiota memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. ICPL Search
Sebulan terakhir, hujan turun tanpa jeda di Aceh dan Sumatera Utara. Sungai-sungai yang selama bertahun-tahun dipersempit, ditebangi hulunya, dan dibebani tambang serta per-kebunan monokultur, kembali mengambil haknya. Air bah datang di malam hari, menenggelam-kan rumah, sawah, sekolah, dan jalan desa; membawa lumpur, batang kayu, bahkan ternak. Di beberapa tempat, warga hanya sempat menyelamatkan diri dengan pakaian yang melekat di badan. Narasi resmi sering menyebutnya sebagai “bencana alam,” seolah-olah alam adalah pelaku tunggal. Namun bagi siapa pun yang tinggal di sana, banjir ini terasa seperti ingatan ekologis yang bangkit—sebuah pengingat keras bahwa hutan yang hilang, sungai yang diluruskan, dan tanah yang diperas melampaui daya dukungnya akan selalu mencari jalan pulang. Dalam lanskap inilah A Natural History of the Future karya Rob Dunn menjadi sangat relevan bagi Indonesia: bukan sebagai buku ramalan, melainkan sebagai cermin.
Dunn mengajak kita memahami bahwa apa yang kita sebut “bencana” sering kali adalah konsekuensi dari hukum biologi dan ekologi yang kita abaikan, hukum-hukum yang tidak bisa dinegosiasikan oleh kebijakan jangka pendek atau teknologi yang lupa pada batas. Dari Aceh hingga Mississippi, kisahnya serupa: air, tanah, mikroba, dan makhluk hidup lain terus bergerak mengikuti hukum kehidupan—entah kita siap atau tidak.
Banjir besar yang berulang di Aceh dan Sumatra Utara dalam beberapa tahun terakhir—dan memuncak dalam sebulan terakhir—bukan peristiwa tunggal, melainkan gejala dari sebuah proses panjang yang bekerja perlahan, diam-diam, dan konsisten: penyusutan ruang hidup ekologis. Aceh–Sumatra Utara jelas mengingatkan ketika hukum biologi kembali menagih. Rob Dunn, dalam A Natural History of the Future, mengingatkan bahwa alam tidak “marah” dan tidak “menghukum”; ia hanya menjalankan hukum-hukumnya sendiri. Salah satu hukum paling sederhana namun paling sering diabaikan adalah species–area law—hukum hubungan antara luas habitat dan jumlah spesies yang dapat bertahan di dalamnya.
Dalam bahasa Dunn yang jernih, hukum ini menyatakan bahwa semakin kecil suatu wilayah alami, semakin sedikit spesies yang bisa hidup stabil di dalamnya. Kehilangan habitat tidak langsung memusnahkan semua kehidupan, tetapi menciptakan apa yang disebutnya sebagai extinction debt: kepunahan yang tertunda. Di Aceh dan Sumatra Utara, hutang ini telah lama menumpuk.
Species–Area Law di Hutan Leuser dan Sekitarnya
Ekosistem Leuser—yang membentang dari Aceh hingga Sumatra Utara—pernah menjadi salah satu bentang alam hutan hujan tropis paling utuh di Asia Tenggara. Ia bukan hanya “rumah” bagi orangutan, harimau, badak, dan gajah, tetapi juga bagi ribuan spesies mikroba tanah, jamur, serangga, dan tumbuhan kecil yang tidak pernah masuk headline berita.
Namun seperti yang dijelaskan Dunn, yang paling menentukan masa depan bukan hanya spesies besar, tetapi spesies kecil yang menopang sistem. Ketika konsesi perkebunan, tambang, dan jalan memotong hutan menjadi fragmen-fragmen terisolasi, luas efektif habitat menyusut drastis. Bukan hanya jumlah pohon yang berkurang, tetapi jejaring biologis yang runtuh: mikroba tanah yang mengatur penyerapan air, jamur mikoriza yang menjaga struktur tanah, dan serangga yang menghubungkan rantai nutrisi.
Dalam kerangka species–area law, hutan yang terfragmentasi tidak lagi mampu menampung keragaman biologis yang sama. Kehilangan spesies ini tidak selalu terlihat—namun dampaknya terasa saat hujan datang: tanah kehilangan kemampuan menyerap air, lereng menjadi rapuh, dan sungai kehilangan “ingatan ekologis”-nya untuk mengalir perlahan.
Rob Dunn berulang kali menantang ilusi manusia modern bahwa teknologi memberi kita kendali atas alam. Aceh–Sumut adalah contoh telanjang dari ilusi ini: Deforestasi dan Ilusi Kendali. Kanal-kanal dibuat untuk mengalirkan air lebih cepat, sungai diluruskan agar “efisien,” dan hutan diganti dengan sistem produksi tunggal. Namun, seperti yang ditekankan Dunn, biologi tidak mengenal efisiensi manusia; ia hanya mengenal keseimbangan jangka panjang.
Deforestasi tidak hanya mengurangi jumlah pohon, tetapi juga mengubah komposisi spesies. Spesies yang tersisa cenderung adalah mereka yang tahan gangguan—sering kali spesies oportunistik—sementara spesies yang menjaga stabilitas hidrologi justru hilang. Ini persis dengan prediksi Dunn: ekosistem yang disederhanakan menjadi lebih rapuh, bukan lebih kuat.
Ketika hujan ekstrem—yang kini makin sering akibat perubahan iklim—turun, sistem yang telah kehilangan kompleksitas biologisnya tidak mampu lagi menahan beban. Banjir pun terjadi, bukan sebagai kejadian luar biasa, tetapi sebagai konsekuensi logis dari hukum ekologi yang dilanggar.
Kunci penting yang perlu kita camkan adalah Resiliensi Ekosistem: Pelajaran dari Masa Depan.
Dalam A Natural History of the Future, Dunn menegaskan bahwa resiliensi tidak lahir dari dominasi satu spesies—termasuk manusia—tetapi dari keberagaman dan redundansi biologis. Sistem yang resilien adalah sistem yang memiliki banyak “cadangan”: banyak spesies dengan fungsi serupa, banyak jalur aliran air, banyak lapisan kehidupan.
Aceh dan Sumatra Utara masih memiliki peluang, karena sebagian hutang kepunahan belum “jatuh tempo.” Tetapi peluang itu hanya ada jika pendekatan pembangunan bergeser dari logika eksploitasi ke logika koeksistensi biologis. Rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan hulu, dan pengakuan terhadap praktik lokal masyarakat adat bukan sekadar isu moral—menurut Dunn, itu adalah strategi bertahan hidup spesies manusia.
Dalam kerangka Dunn, masa depan manusia bukan ditentukan oleh seberapa canggih teknologi kita, melainkan oleh seberapa patuh kita pada hukum biologi. Aceh–Sumut memberi contoh konkret: ketika hukum itu diabaikan, air akan mengingatkan kita; ketika dihormati, hutan akan kembali mengajari kita cara hidup bersama.
Banjir Aceh–Sumatra Utara bukan hanya berita lokal; ia adalah catatan kaki dari sejarah alam masa depan yang ditulis Rob Dunn. Ia mengajarkan bahwa masa depan bukan sesuatu yang menunggu kita, melainkan sesuatu yang sedang kita bangun—atau runtuhkan—hari ini. Dalam bahasa biologi, tidak ada hukuman, hanya akibat. Dan dalam konteks Indonesia, pilihan masih terbuka: membayar hutang ekologis dengan penderitaan, atau menegosiasikannya kembali dengan pemulihan dan kerendahan hati ekologis.
Ketika Kehidupan Menyergap: Dari Keterkejutan hingga Ceruk Manusia
Buku ini dibuka dengan sebuah kesadaran yang mengganggu: kehidupan sering kali menyergap manusia dari arah yang tidak kita duga. Dalam bab awal yang diberi judul Blindsided by Life, Rob Dunn mengajak pembaca menengok kembali momen-momen ketika spesies—termasuk manusia—gagal membaca tanda-tanda biologis yang sudah ada di depan mata. Pandemi, spesies invasif, runtuhnya sistem pangan, dan kolaps ekosistem bukanlah kejadian acak; semuanya merupakan konsekuensi dari hukum-hukum kehidupan yang telah lama bekerja. Manusia, dalam kisah ini, bukan makhluk yang berdiri di atas alam, melainkan spesies yang terlalu sering lupa bahwa ia juga tunduk pada seleksi, keterbatasan, dan ketergantungan ekologis. Kita terkejut bukan karena alam berubah tiba-tiba, melainkan karena kita menolak melihat pola-pola lama yang berulang.
Dari keterkejutan itu, Dunn membawa kita masuk ke lanskap yang paling kita kenal namun paling jarang kita pahami sebagai ekosistem: kota. Dalam Urban Galápagos, kota diperlakukan bukan sebagai anomali ekologis, melainkan sebagai laboratorium evolusi yang hidup. Seperti Kepulauan Galápagos yang melahirkan eksperimen alamiah Darwin, kota-kota modern—dari New York hingga Jakarta—menjadi tempat di mana spesies beradaptasi dengan cepat: tikus, kecoa, burung, mikroba, bahkan manusia sendiri. Dunn menunjukkan bahwa urbanisasi tidak menghentikan evolusi; ia justru mempercepatnya. Namun percepatan ini bersifat selektif dan brutal: hanya organisme yang mampu hidup berdampingan dengan limbah, kebisingan, dan fragmentasi yang bertahan. Kota, dalam narasi Dunn, adalah cermin masa depan: dunia yang dipenuhi ceruk-ceruk buatan manusia, tempat kehidupan terus berubah—sering kali dengan cara yang tidak kita rencanakan.
Namun kisah ini tidak hanya tentang spesies yang kalah. Dalam The Inadvertent Ark, Dunn memperlihatkan ironi besar zaman modern: ketika manusia menghancurkan habitat alami, kita secara tidak sengaja menciptakan bahtera-bahtera kehidupan baru. Taman kota, kebun rumah, laboratorium, bank benih, kebun binatang, hingga halaman belakang menjadi tempat per-lindungan terakhir bagi banyak spesies. Bahtera ini tidak sempurna, sering kali rapuh, dan kadang bersifat sementara. Tetapi ia menunjukkan satu hal penting: masa depan kehidupan tidak sepenuhnya gelap. Namun Dunn juga memperingatkan bahwa bahtera yang tidak di-sengaja ini sering kali menyelamatkan sebagian kecil kehidupan sambil membiarkan jejaring ekologis yang lebih luas runtuh. Menyelamatkan spesies tanpa menyelamatkan relasinya adalah kemenangan semu.
Ketegangan antara harapan dan keterbatasan mencapai puncaknya dalam The Last Escape. Di sini, Dunn menantang fantasi manusia tentang pelarian terakhir—baik melalui teknologi ekstrem, kolonisasi planet lain, atau manipulasi genetika tanpa batas. Dengan tenang namun tegas, ia mengingatkan bahwa tidak ada pelarian dari hukum biologi. Tidak ada planet cadangan yang siap menampung manusia tanpa ekosistem penopang. Bahkan teknologi paling canggih pun tetap bergantung pada mikroba, tanah, air, dan stabilitas iklim. Bab ini terasa seperti penarikan tirai: gagasan bahwa manusia bisa “kabur” dari kerusakan yang ia ciptakan adalah ilusi yang berbahaya, karena ia menunda tanggung jawab di bumi yang satu-satunya ini.
Semua alur ini kemudian disatukan dalam The Human Niche, sebuah refleksi tentang ceruk ekologis manusia. Dunn menolak dua ekstrem: manusia sebagai penguasa mutlak alam, dan manusia sebagai spesies tak berdaya. Ia mengusulkan pandangan yang lebih jujur dan lebih menuntut: manusia adalah spesies dengan kekuatan luar biasa untuk mengubah lingkungan, tetapi kekuatan itu datang dengan biaya biologis. Ceruk manusia di masa depan tidak bisa lagi dibangun di atas penaklukan, melainkan harus dirancang sebagai koeksistensi sadar—dengan mikroba, tumbuhan, hewan, dan sistem kehidupan yang memungkinkan kita bernapas, makan, dan bertahan.
Dalam alur lima bab ini, Dunn tidak sedang meramalkan kiamat atau menjanjikan utopia. Ia sedang melakukan sesuatu yang lebih sulit: mengembalikan manusia ke dalam sejarah alam, bukan sebagai epilog, tetapi sebagai salah satu bab yang masih bisa ditulis ulang. Masa depan, dalam pengertian Dunn, bukanlah garis lurus menuju kehancuran atau keselamatan, melainkan percabangan biologis—dan pilihan manusia hari ini akan menentukan cabang mana yang menjadi rumah kita.
Menurut Dunn kita perlu belajar dari pikiran yang bukan milik kita: kecerdasan, keberagaman, dan ketergantungan. Setelah menempatkan manusia kembali ke dalam sejarah alam, Dunn menggeser lensa ke sesuatu yang sering kita anggap istimewa milik kita sendiri: kecerdasan. Dalam kisah tentang gagak—burung hitam yang kerap diremehkan—ia menunjukkan bahwa kecerdasan bukanlah mahkota eksklusif manusia, melainkan strategi bertahan hidup yang muncul berulang kali dalam evolusi. Gagak mampu memecahkan masalah, menggunakan alat, mengingat wajah manusia, bahkan “mewariskan” pengetahuan lintas generasi. Bagi Dunn, ini bukan anekdot menarik, melainkan pelajaran penting: masa depan tidak akan dimenangkan oleh satu jenis kecerdasan saja. Alam selalu memihak pada kecerdasan yang kontekstual, lentur, dan terdistribusi, bukan yang terpusat dan angkuh.
Dari sini, narasi bergerak ke gagasan yang lebih luas tentang keberagaman sebagai penye-imbang risiko. Dunn mengajak kita melihat dunia biologis sebagai sistem portofolio: ekosistem yang beragam bekerja seperti investasi yang tersebar—ketika satu komponen gagal, yang lain masih bisa menopang keseluruhan. Dalam sejarah kehidupan, monokultur—baik di ladang pertanian maupun dalam sistem sosial—selalu membawa kerentanan. Penyakit, perubahan iklim, atau gangguan kecil dapat menjalar cepat ketika semua elemen seragam. Sebaliknya, keberagaman menciptakan penyangga, redundansi, dan jalan alternatif. Dunn menekankan bahwa ini bukan sekadar nilai moral tentang “merayakan perbedaan,” melainkan aturan biologis tentang cara mengurangi risiko kepunahan.
Di titik ini, pembaca mulai melihat pola besar: kecerdasan yang tersebar dan keberagaman yang dirawat bukanlah hiasan, melainkan syarat stabilitas. Namun Dunn tidak berhenti pada optimis-me tentang variasi. Ia menutup rangkaian ini dengan pengingat paling mendasar—dan paling sulit diterima oleh manusia modern—tentang hukum ketergantungan. Tidak ada spesies yang berdiri sendiri. Tidak ada teknologi yang benar-benar mandiri. Manusia bergantung pada jaringan kehidupan yang tak terlihat: mikroba di tanah yang memungkinkan pertanian, bakteri di tubuh yang menjaga kesehatan, jamur yang menghubungkan akar-akar pohon, dan serangga penyerbuk yang memastikan siklus pangan terus berputar.
Dalam The Law of Dependence, Dunn menanggalkan mitos kemandirian manusia. Semakin kita mencoba memutus ketergantungan—melalui sterilisasi berlebihan, penyederhanaan ekosistem, atau kontrol total—semakin rapuh posisi kita. Ketergantungan bukan kelemahan; ia adalah kondisi dasar kehidupan. Masa depan yang layak huni, menurut Dunn, bukan masa depan yang memutus relasi, melainkan yang mengelola ketergantungan dengan sadar dan rendah hati.
Jika pada bab-bab awal Dunn mengguncang kepercayaan diri manusia, maka pada bagian ini ia menawarkan arah yang lebih tenang namun menuntut: belajarlah dari kecerdasan makhluk lain, rawat keberagaman sebagai asuransi kehidupan, dan akui ketergantungan sebagai fondasi etika baru. Masa depan tidak akan diselamatkan oleh satu spesies paling pintar, tetapi oleh jaringan kecerdasan, perbedaan, dan relasi yang kita pilih untuk pertahankan.
Ketika Segalanya Retak: Dari Lebah Robot hingga Dunia yang Terus Berevolusi
Pada tahap akhir bukunya, Rob Dunn membawa pembaca ke wilayah yang terasa hampir surealis, namun sepenuhnya nyata. Ia memulai dengan metafora yang rapuh dan akrab: Humpty Dumpty—telur yang jatuh dan tak bisa disatukan kembali. Dalam Humpty-Dumpty and the Robotic Sex Bees, Dunn mengajak kita menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua sistem kehidupan yang rusak dapat dipulihkan ke kondisi semula. Kepunahan penyerbuk, misalnya, mendorong manusia membayangkan solusi teknologi ekstrem: lebah robot, penyer-bukan buatan, dan rekayasa mekanis terhadap fungsi-fungsi alam. Namun Dunn dengan tenang membedah ilusi ini. Masalahnya bukan sekadar mengganti satu fungsi dengan alat baru; alam adalah jejaring relasi, bukan kumpulan komponen yang bisa dicopot dan dipasang ulang sesuka hati.
Dalam narasi ini, Dunn tidak menolak teknologi, tetapi ia menolak arogansi teknologis—keyakinan bahwa kita dapat memperbaiki dunia tanpa memahami kompleksitas biologinya. Lebah bukan hanya pembawa serbuk sari; ia adalah simpul dalam jaringan evolusi yang melibatkan bunga, mikroba, iklim, dan waktu yang sangat panjang. Ketika simpul itu hilang, dunia tidak “rusak” secara mekanis—ia berubah secara evolusioner, sering kali ke arah yang lebih miskin dan lebih rapuh.
Dari titik keretakan ini, Dunn mengajak pembaca melangkah ke pemahaman yang lebih dewasa tentang masa depan dalam Living with Evolution. Inilah jantung filosofis buku ini. Evolusi, tegas Dunn, bukan peristiwa masa lalu yang selesai jutaan tahun lalu; ia adalah proses yang sedang berlangsung, dan manusia kini menjadi salah satu kekuatan evolusioner terbesar di planet ini. Antibiotik mengubah mikroba. Urbanisasi mengubah burung dan serangga. Perubahan iklim mengubah hampir semua spesies sekaligus. Pertanyaannya bukan apakah evolusi akan terus berjalan—ia pasti akan berjalan—melainkan apakah kita mau hidup dengan konsekuensinya secara sadar.
Hidup dengan evolusi berarti melepaskan fantasi tentang stabilitas abadi. Dunn mengajak kita berdamai dengan kenyataan bahwa tidak ada “keseimbangan alam” yang statis. Yang ada hanyalah ketidakseimbangan yang terus dinegosiasikan. Dalam konteks ini, keberlanjutan bukan berarti membekukan dunia pada satu titik ideal, melainkan menciptakan kondisi di mana perubahan tidak berujung pada kehancuran massal. Ini menuntut kerendahan hati biologis: memahami bahwa setiap intervensi manusia—sebesar apa pun niat baiknya—akan memicu respons evolusioner yang tak sepenuhnya bisa kita kendalikan.
Pemikiran ini mencapai kedalaman reflektif dalam Not the End of Nature. Dunn menolak narasi apokaliptik yang menyatakan bahwa alam akan “berakhir.” Alam, katanya, tidak akan berakhir —yang bisa berakhir adalah versi alam yang ramah bagi manusia. Setelah kepunahan massal sebelumnya, kehidupan selalu bangkit kembali, sering kali dalam bentuk yang asing dan tidak bersahabat bagi spesies yang dominan sebelumnya. Dengan kata lain, bumi tidak membutuh-kan manusia untuk bertahan; manusialah yang membutuhkan kondisi tertentu dari bumi.
Bab ini terasa seperti cermin keras bagi antroposentrisme modern. Ia menggeser pertanyaan dari “bagaimana menyelamatkan alam?” menjadi “bagaimana manusia tetap relevan dalam alam yang berubah?”. Dunn menekankan bahwa masa depan bukan tentang menyelamatkan planet sebagai objek moral, tetapi tentang memahami posisi kita dalam drama biologis yang jauh lebih besar dan lebih tua dari peradaban manusia.
Semua ini kemudian bermuara pada penutup yang dingin namun jujur: No Longer Among the Living. Judul ini bukan sekadar tentang kepunahan spesies lain, tetapi tentang kemungkinan bahwa manusia—dalam bentuknya yang sekarang—bisa menjadi catatan kaki sejarah alam. Dunn tidak menuliskannya sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat. Sepanjang sejarah bumi, banyak spesies yang dominan pernah merasa aman, hanya untuk kemudian menghilang. Yang membedakan manusia hanyalah satu hal: kita memiliki kesadaran akan proses ini. Ke-sadaran itulah, bagi Dunn, satu-satunya peluang etis yang kita miliki. Kita bisa memilih untuk bertindak seolah-olah hukum biologi tidak berlaku bagi kita—dan mengulang kisah Humpty Dumpty. Atau kita bisa menerima bahwa masa depan adalah ruang koeksistensi yang rapuh, penuh ketergantungan, dan terus berubah—namun masih bisa dihuni jika kita belajar hidup bersama evolusi, bukan melawannya.
Pada akhirnya, A Natural History of the Future bukan buku tentang kiamat, melainkan tentang kedewasaan spesies. Dunn tidak menawarkan keselamatan instan atau solusi teknokratik. Ia menawarkan sesuatu yang lebih menantang: cara berpikir biologis tentang masa depan. Masa depan, dalam pengertian ini, bukan hak istimewa manusia, melainkan kemungkinan yang harus dinegosiasikan dengan seluruh kehidupan lain di bumi. Jika kita gagal, alam akan tetap berjalan. Jika kita berhasil, itu bukan karena kita menaklukkan hukum biologi—melainkan karena kita akhirnya belajar hidup di dalamnya.
Catatan Akhir: Masa Depan sebagai Sejarah Alam yang Masih Ditulis
A Natural History of the Future mengajukan satu koreksi mendasar terhadap cara manusia modern membayangkan masa depan. Masa depan, kata Rob Dunn, bukanlah wilayah kosong yang akan kita isi dengan teknologi, kebijakan, dan ambisi. Ia adalah kelanjutan dari sejarah alam, dan manusia—betapapun canggihnya—tetaplah satu spesies di dalamnya, terikat oleh hukum yang sama yang mengatur mikroba, burung gagak, jamur tanah, dan hutan hujan.
Di tingkat global, buku ini memperlihatkan pola yang konsisten: ketika manusia mempersempit ruang hidup makhluk lain, menyederhanakan ekosistem, dan mengandalkan solusi tunggal, kita menciptakan dunia yang tampak efisien tetapi sebenarnya rapuh. Kota-kota menjadi Galápagos baru, teknologi menjadi bahtera yang tidak sengaja, dan harapan sering kali dibebankan pada inovasi yang lupa pada jejaring kehidupan yang menopangnya. Evolusi tidak berhenti karena niat baik manusia; ia terus berjalan, menyesuaikan diri dengan dunia yang kita ubah—sering kali dengan cara yang merugikan kita sendiri.
Namun Dunn tidak menutup bukunya dengan keputusasaan. Ia menolak narasi “akhir alam.” Alam akan tetap ada. Yang dipertaruhkan adalah apakah manusia masih memiliki ceruk ekologis yang layak huni. Masa depan, dalam pengertian Dunn, adalah pertanyaan tentang relasi: apakah manusia memilih untuk hidup bersama hukum biologi, atau terus berpura-pura berada di atasnya.
Dalam konteks Indonesia–sebagai Miniatur Dunia, pesan Dunn terasa hampir terlalu relevan. Dari hutan Leuser hingga mangrove pesisir, dari kota-kota padat hingga desa-desa yang ber-gantung pada sungai dan tanah, Indonesia adalah contoh nyata bagaimana species–area law, hukum ketergantungan, dan dinamika evolusi bekerja di depan mata. Deforestasi dan frag-mentasi habitat telah menyusutkan ruang hidup ribuan spesies—termasuk manusia—menciptakan hutang kepunahan yang belum seluruhnya jatuh tempo. Banjir di Aceh dan Sumatra Utara, krisis pangan lokal, penyakit zoonotik, dan kerentanan kota pesisir bukan sekadar kegagalan manajemen; ia adalah konsekuensi biologis dari dunia yang disederhanakan secara paksa.
Namun Indonesia juga menyimpan pelajaran harapan. Praktik adat yang menjaga hutan, sistem pertanian beragam, kebun campur, dan relasi spiritual dengan alam menunjukkan bahwa koeksistensi bukan utopia, melainkan pengetahuan yang telah lama ada—meski sering dising-kirkan oleh logika ekstraksi modern. Dalam bahasa Dunn, inilah bentuk ceruk manusia yang lebih selaras dengan hukum kehidupan.
Secara ilmiah, buku ini mengajarkan kerendahan hati. Evolusi, ketergantungan, dan keberagam-an bukan teori abstrak, melainkan realitas yang menentukan apakah suatu sistem bertahan atau runtuh. Sains di sini tidak berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi sebagai cara membaca batas. Secara filosofis, Dunn menggemakan kritik terhadap antroposentrisme. Manusia bukan pusat kosmos, melainkan simpul dalam jaringan yang lebih luas. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran filsuf seperti Hans Jonas tentang tanggung jawab antargenerasi, atau Bruno Latour tentang dunia sebagai kumpulan aktor yang saling memengaruhi—manusia hanyalah salah satunya.
Secara spiritual, terutama jika dibaca dari konteks Indonesia dan tradisi Islam, buku ini beresonansi dengan konsep amanah dan mīzān. Alam bukan milik manusia, melainkan titipan dengan keseimbangan yang harus dijaga. Ketika keseimbangan itu dirusak—fasād—akibatnya kembali kepada manusia sendiri. Dunn, meski menulis sebagai biolog, pada akhirnya mengajak pada sikap yang sangat spiritual: menerima keterbatasan dan hidup dengan kesadaran relasional.
Kesimpulan besar A Natural History of the Future bukanlah prediksi, melainkan undangan etis. Masa depan tidak akan diselamatkan oleh lebah robot, kota pintar, atau teknologi tunggal apa pun jika ia mengabaikan hukum kehidupan. Sebaliknya, masa depan yang layak huni hanya mungkin jika manusia: mengakui ketergantungannya, merawat keberagaman sebagai penyangga risiko, dan hidup berdampingan dengan evolusi yang tak pernah berhenti.
Di tingkat global maupun di Indonesia, pilihan itu masih terbuka—tetapi waktunya terbatas. Alam tidak menunggu kesadaran manusia. Ia terus berjalan. Pertanyaannya sederhana namun berat: apakah kita memilih berjalan bersamanya, atau menjadi catatan kaki berikutnya dalam sejarah alam?
Narasi Dunn selaras dengan pandangan filosofis yang jauh lebih tua. Baruch Spinoza berbicara tentang manusia sebagai bagian dari natura naturans—alam aktif yang menciptakan dirinya sendiri—dan bukan entitas di luar atau di atasnya. Perspektif ini menghilangkan keterpisahan antara manusia dan alam, suatu ide yang juga digugah Dunn ketika ia menegaskan bahwa masa depan manusia hanya dapat dipahami jika kita menempatkan diri di dalam hukum kehidupan yang sama. Mencermati hukum biologi berarti menghormati bahwa kita hidup berjejal dengan jutaan spesies lain, bukan berkuasa atas mereka.
A Natural History of the Future bukan sekadar buku ekologi. Ia adalah teguran epistemologis: kita perlu mengubah cara berpikir tentang masa depan dari narasi teknologi dominan menjadi narasi biologis. Dunn tidak berkata bahwa teknologi tidak penting; ia menegaskan bahwa kita tidak bisa mengabaikan hukum biologi ketika merencanakan masa depan. Ketika kita terus memandang dunia sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki tanpa memahami hukum-hukum yang telah membentuk kehidupan selama miliaran tahun, kita akan terus menemui kegagalan.
Ini adalah buku yang kaya wawasan, memadukan biologi, evolusi, ekologi, budaya, dan refleksi masa depan — sebuah peta intelektual tentang bagaimana kita harus berpikir ulang tentang keberlanjutan, pembangunan, dan hubungan kita dengan alam. Ke depannya, gagasan Dunn bisa menjadi salah satu fondasi pemikir bagi kebijakan lingkungan global dan lokal, termasuk di Indonesia, agar kita tidak lagi mencoba menaklukkan alam, melainkan belajar hidup bersama hukum-hukum kehidupan yang tidak dapat diubah. PublishersWeekly.com
Cirebon, 10 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Dunn, R. (2021). A Natural History of the Future: What the Laws of Biology Tell Us About the Destiny of the Human Species. Basic Books. PublishersWeekly.com
Anthropocene. (n.d.). Wikipedia. Wikipedia
Holocene extinction. (n.d.). Wikipedia. Wikipedia
Review databases: Kirkus and Publisher’s Weekly. Kirkus Reviews