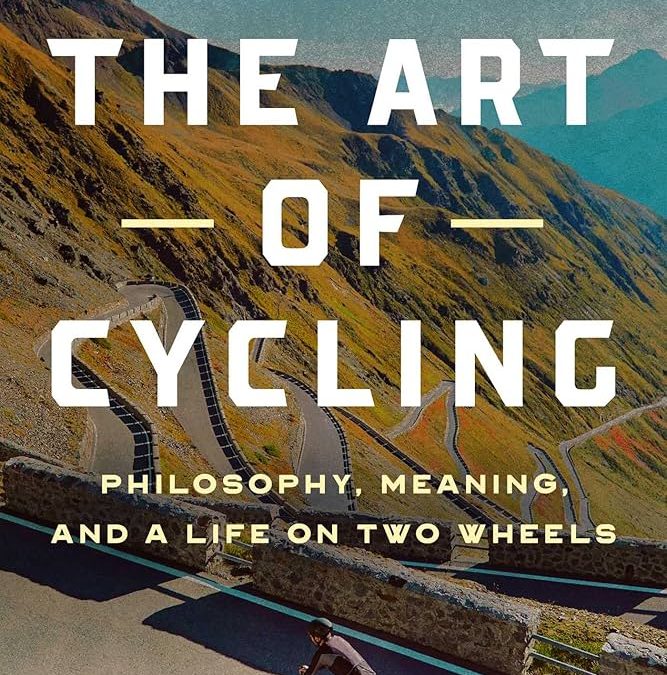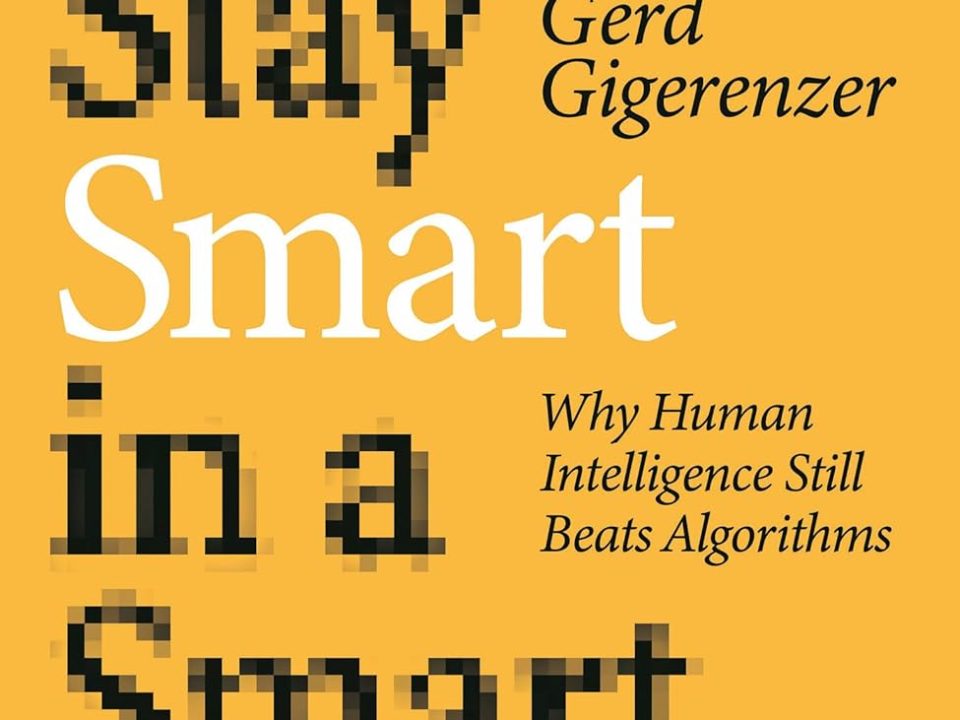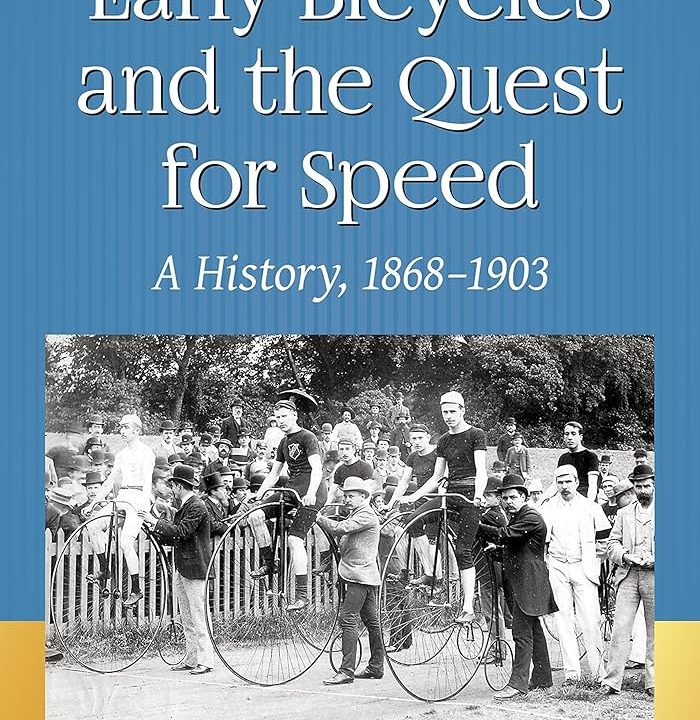Rubarubu #83
The Art of Cycling:
Sepeda sebagai Seni Hidup
Pada suatu pagi yang tenang, James Hibbard menggambarkan dirinya mengayuh sendirian di jalan yang hampir kosong—bukan untuk mencetak waktu, bukan pula untuk menaklukkan jarak. Ia mengayuh untuk merasakan. Dalam momen inilah, Hibbard menegaskan tesis utama bukunya: bersepeda bukan sekadar aktivitas fisik atau olahraga, melainkan sebuah seni hidup—sebuah praktik eksistensial yang memadukan tubuh, pikiran, waktu, dan dunia. James Hibbard adalah seorang penulis, editor, dan pemikir dengan latar belakang yang unik, menggabungkan dunia sastra, filsafat, dan olahraga ketahanan. Lahir di Bristol, Inggris, pada 1969, ia kemudian dibesarkan di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang memberinya perspektif lintas budaya sejak dini.
Hibbard membuka bukunya dengan sebuah penolakan yang tenang namun tegas terhadap dogma modern yang telah lama kita terima tanpa perlawanan: bahwa manusia adalah otak yang kebetulan memiliki tubuh. You are not your brain: on cycling and the transcendent. Anda bukanlah otak Anda: tentang bersepeda dan keagungan, tulisnya. Dalam pengantar ini, ia mengisahkan pengalaman bersepeda yang tampak sepele—sebuah perjalanan panjang sendirian, di mana pikiran yang semula riuh oleh kecemasan dan daftar tugas perlahan menghilang, bukan karena dipaksa diam, melainkan karena tubuh mengambil alih kepemimpinan kesadaran.
Di atas sepeda, Hibbard menulis, tidak ada jarak antara niat dan tindakan. Pikiran tidak memerintah tubuh seperti seorang jenderal; ia mengikuti irama napas, denyut jantung, dan tekanan pedal. Kesadaran tidak lagi berada “di kepala”, tetapi menyebar ke seluruh tubuh—ke paha yang terbakar, ke telapak tangan yang menggenggam setang, ke punggung yang menerima angin pagi. Inilah pengalaman transenden yang tidak mistis, tetapi sangat jasmani.
Hibbard mengaitkan pengalaman ini dengan kritik terhadap neurosentrisme—pandangan bahwa segala makna, identitas, dan kesadaran berakar semata-mata pada aktivitas otak. Bersepeda, baginya, adalah bantahan hidup terhadap reduksi itu. Ia menggemakan pemikiran Merleau-Ponty bahwa kesadaran adalah embodied, dan dalam pengalaman bersepeda, kita tidak “menggunakan” tubuh, melainkan menjadi tubuh.
Transendensi yang dimaksud Hibbard bukanlah pelarian dari dunia, tetapi justru peneng-gelaman yang total ke dalamnya. Di saat-saat tertentu—ketika jalan menanjak panjang, ketika rasa sakit mencapai ambang tertentu—ego yang biasa mengatur narasi diri larut. Yang tersisa hanyalah gerak. Dan dalam gerak itu, muncul keheningan yang tidak bisa diproduksi oleh meditasi yang dipaksakan. Sepeda, dengan demikian, menjadi medium sekuler bagi pengalaman yang dahulu diasosiasikan dengan doa atau ritual. Minatnya yang mendalam pada filsafat membawanya ke Reed College di Portland, Oregon, salah satu institusi seni liberal paling bergengsi di AS, yang dikenal karena pendekatannya yang intens terhadap humaniora. Di sanalah ia mendalami pemikiran para filsuf besar, sebuah fondasi yang kelak sangat mempengaruhi tulisannya. Setelah lulus, karier profesionalnya berawal di dunia penerbitan di New York City, di mana ia bekerja sebagai editor untuk Simon & Schuster dan penerbit lainnya, mengasah keahliannya dalam menyusun narasi.
Dalam bab ini, Hibbard menoleh ke asal-usul sepeda—bukan hanya sebagai artefak teknologi, tetapi sebagai jawaban kultural terhadap kebutuhan manusia untuk bergerak dengan martabat (Bab 1: On Purposes And Origins). Ia menceritakan bagaimana sepeda lahir bukan dari obsesi pada kecepatan ekstrem, melainkan dari pencarian efisiensi yang selaras dengan tubuh manusia. Tidak seperti mesin lain yang menuntut tubuh menyesuaikan diri, sepeda justru dibentuk mengikuti anatomi manusia.
Hibbard menyelipkan kisah pribadi tentang pertama kali ia menyadari bahwa tujuan bersepeda tidak selalu berada di ujung perjalanan. Ia mengenang masa muda ketika bersepeda berarti mencapai tempat tertentu secepat mungkin, dan bagaimana pemahaman itu runtuh seiring waktu. Pada suatu perjalanan tanpa tujuan jelas, ia menyadari bahwa asal-usul makna bersepeda justru terletak pada ketidakbergunaan praktisnya. Mengayuh tanpa alasan produktif membuka ruang bagi refleksi, perhatian, dan permainan—hal-hal yang kerap disingkirkan dalam kehidupan dewasa.
Ia membaca sejarah sepeda sebagai sejarah resistensi sunyi terhadap logika industrial: alat yang cukup cepat untuk memperluas dunia seseorang, tetapi cukup lambat untuk tetap memelihara hubungan dengannya. Dalam hal ini, Hibbard sejalan dengan Ivan Illich, yang melihat sepeda sebagai teknologi ambang—cukup kuat untuk membebaskan, namun tidak cukup kuat untuk mendominasi. Tujuan bersepeda, menurut Hibbard, bukanlah efisiensi maksimal, melainkan koherensi antara niat, gerak, dan dunia. Di situlah letak keindahannya: sepeda mengembalikan tujuan pada skala manusia.
Buku James Hibbard (2023). The Art of Cycling: Philosophy, Meaning, and a Life on Two Wheels. Pegasus Books, New York–London bukan manual teknik bersepeda, juga bukan sejarah sepeda dalam arti konvensional. Ia adalah esai filosofis panjang—kadang personal, kadang reflektif, kadang dialogis—yang memandang sepeda sebagai medium untuk memahami makna hidup modern. Seperti seni lukis atau musik, bersepeda bagi Hibbard adalah praktik yang menuntut kehadiran penuh (presence), kepekaan terhadap ritme, dan kesediaan untuk bergerak bersama dunia, bukan melawannya.
Salah satu benang merah terkuat dalam buku ini adalah gagasan bahwa bersepeda melatih manusia untuk hadir sepenuhnya di dalam tubuh dan ruang. Bersepeda adalah seni kehadiran.
Tidak seperti mengemudi mobil yang menciptakan jarak antara manusia dan lanskap, sepeda menghapus sekat itu. Tubuh menjadi alat ukur dunia: tanjakan terasa di otot, angin terasa di dada, waktu terasa di napas. Hibbard mengaitkan pengalaman ini dengan tradisi filsafat fenomenologi—terutama pemikiran Maurice Merleau-Ponty tentang tubuh sebagai cara utama manusia “berada di dunia”. Bersepeda, dalam kerangka ini, bukan aktivitas tambahan, melainkan cara mengetahui dunia melalui tubuh. Dunia tidak lagi sekadar pemandangan, tetapi pengalaman langsung yang berdenyut bersama gerak.
“On a bicycle, the world does not pass you by. You pass through it, slowly enough to feel its texture, quickly enough to feel alive.” —James Hibbard (2023)
Buku ini juga merupakan kritik halus namun mendalam terhadap budaya modern yang terobsesi pada kecepatan, efisiensi, dan produktivitas. Hibbard menempatkan bersepeda sebagai praktik ritmis—bukan lambat demi kelambatan, tetapi tepat demi keberlanjutan. Bersepeda berarti menyeimbangkan antara ritme, waktu, dan kritik atas kecepatan modern.
Dalam kayuhan sepeda, waktu tidak diukur oleh jam atau target, melainkan oleh denyut jantung, perubahan cahaya, dan jarak yang dilalui dengan usaha. Di sini, Hibbard bersinggungan dengan pemikiran Ivan Illich tentang convivial tools, serta kritik Hartmut Rosa tentang akselerasi sosial. Sepeda menjadi teknologi yang tidak tunduk sepenuhnya pada logika percepatan kapitalisme.
Bersepeda mengajarkan bahwa makna sering muncul bukan dari pencapaian akhir, melainkan dari proses—dari being on the way. Dalam dunia yang ingin segalanya instan, sepeda mengembalikan nilai perjalanan itu sendiri.
Hibbard juga membaca bersepeda sebagai praktik etis. Sepeda adalah teknologi yang sederhana, nyaris rendah hati. Ia tidak mendominasi ruang, tidak mengklaim kecepatan mutlak, dan tidak menuntut sumber daya berlebih. Dalam pengertian ini, bersepeda adalah latihan moral—sebuah cara hidup yang mengajarkan batas (limits), kesederhanaan, dan respek terhadap dunia. Etika, Kerendahan Hati, dan Relasi dengan Alam adalah bagian penting dari bersepeda.
Ia mengaitkan pengalaman ini dengan etika lingkungan dan filsafat kebajikan Aristotelian. Bersepeda melatih phronesis—kebijaksanaan praktis—karena setiap perjalanan menuntut penilaian situasional: kapan memacu, kapan menahan, kapan berhenti. Alam tidak ditaklukkan, tetapi diajak bernegosiasi.
Di sini, resonansi dengan pemikiran Timur—termasuk Zen dan tasawuf—juga terasa. Kayuhan yang berulang, napas yang teratur, dan perhatian yang fokus menjadikan bersepeda sebagai semacam meditasi bergerak. Seperti dikatakan Jalaluddin Rumi, “Where there is ruin, there is hope for a treasure”—dan dalam kelelahan bersepeda, sering muncul kejernihan batin.
Identitas, Kebebasan, dan Diri yang Bergerak
Berbeda dari olahraga kompetitif yang berorientasi pada prestasi, Hibbard menekankan bahwa makna terdalam bersepeda sering kali muncul dalam kesendirian. Di jalan yang sepi, seseorang tidak hanya bergerak melintasi ruang, tetapi juga melintasi lapisan-lapisan dirinya sendiri.
Bersepeda menjadi cara untuk menegosiasikan identitas: antara kontrol dan pelepasan, antara tujuan dan keterbukaan. Dalam hal ini, Hibbard dekat dengan pemikiran eksistensialis seperti Albert Camus—bahwa makna hidup tidak ditemukan di luar, melainkan diciptakan melalui tindakan sadar yang diulang setiap hari.
Sepeda tidak menjanjikan kebebasan absolut, tetapi menawarkan kebebasan yang bersyarat—bebas sejauh manusia mau menerima keterbatasan tubuh dan dunia. Justru dalam batas itulah, kebahagiaan yang lebih dewasa muncul.
Sepeda sebagai Seni, Bukan Sekadar Alat
Judul buku ini menemukan puncaknya dalam gagasan bahwa bersepeda adalah art—bukan dalam arti estetika permukaan, tetapi sebagai praktik kreatif yang membentuk cara hidup. Seperti seni, bersepeda menuntut latihan, kesabaran, dan keterbukaan terhadap kegagalan. Tidak semua perjalanan indah; ada hujan, angin, rasa sakit. Namun justru dari ketidaksempurnaan itu, makna tumbuh.
Hibbard menolak romantisasi berlebihan, tetapi juga menolak reduksi sepeda menjadi sekadar alat transportasi. Ia adalah medium relasional—menghubungkan manusia dengan tubuhnya, dengan kota, dengan alam, dan dengan waktu.
Barangkali Bab On Bodies And Pain (Bab 4) adalah salah satu bagian paling jujur dan paling fisikal dalam buku. Hibbard menulis tentang rasa sakit tanpa romantisasi, tetapi juga tanpa penolakan. Ia menceritakan perjalanan panjang di mana tubuhnya mencapai batas—lutut nyeri, punggung kaku, napas terengah. Namun alih-alih memandang rasa sakit sebagai musuh, ia mulai memahaminya sebagai bahasa tubuh yang menuntut didengarkan.
Rasa sakit dalam bersepeda, tulis Hibbard, bersifat dialogis. Ia bukan sinyal untuk berhenti secara otomatis, melainkan undangan untuk menyesuaikan diri: mengubah irama, posisi, ekspektasi. Di sinilah perbedaan antara penderitaan yang bermakna dan penderitaan yang sia-sia. Bersepeda mengajarkan bahwa tidak semua rasa sakit harus dieliminasi; sebagian perlu dinegosiasikan.
Hibbard mengaitkan pengalaman ini dengan filsafat Stoik dan Aristotelian, di mana kebajikan tumbuh bukan dari kenyamanan, tetapi dari hubungan yang bijak dengan ketidaknyamanan. Tubuh pesepeda menjadi laboratorium etika: kapan bertahan, kapan menyerah, kapan mengubah tujuan. Ia juga menyentuh data fisiologis—tentang adaptasi tubuh terhadap stres berulang, tentang bagaimana rasa sakit yang terukur dapat meningkatkan kapasitas fisik dan mental. Namun yang terpenting, ia menekankan bahwa bersepeda membebaskan rasa sakit dari makna patologis semata. Rasa sakit menjadi bagian dari narasi diri, bukan gangguan terhadapnya.
Dalam On The World, Self, And Other (Bab 6), Hibbard meluaskan cakrawala refleksinya dari tubuh ke relasi. Ia menulis tentang bagaimana bersepeda mengubah cara seseorang hadir di dunia dan bertemu dengan orang lain. Tidak seperti mobil yang memisahkan individu dalam kapsul privat, sepeda menempatkan manusia dalam kerentanan yang terbuka—terlihat, terdengar, dan terasa.
Ia mengisahkan pertemuan-pertemuan singkat di jalan: sapaan pesepeda asing, tatapan pejalan kaki, bahkan konflik kecil dengan pengendara lain. Semua itu, tulisnya, adalah latihan etis dalam koeksistensi. Bersepeda memaksa seseorang untuk mengakui keberadaan orang lain secara langsung, bukan sebagai abstraksi.
Hibbard, selain sebagai penulis, juga dikenal sebagai kolumnis untuk berbagai majalah bersepeda terkemuka. Ia terus menulis, bersepeda, dan tinggal di Los Angeles, di mana ia menjalani kehidupan yang menyelaraskan pikiran dan tubuh melalui disiplin di atas dua roda,
juga merefleksikan bagaimana identitas diri menjadi lebih cair di atas sepeda. Status sosial, profesi, dan simbol-simbol kekuasaan kehilangan daya. Yang tersisa adalah tubuh yang bergerak di ruang publik, tunduk pada hukum yang sama: angin, hujan, tanjakan.
Dalam momen-momen tertentu, ia merasakan apa yang ia sebut sebagai expanded self—diri yang tidak berakhir di batas kulit, tetapi meluas ke jalan, ke lanskap, ke orang-orang yang dilalui. Ini bukan penghapusan individualitas, melainkan pelembutannya. Diri tidak lenyap, tetapi menjadi lebih berpori.
Bab ini berakhir dengan refleksi sunyi: bahwa bersepeda, pada akhirnya, adalah cara untuk belajar hidup bersama dunia tanpa ilusi kontrol total. Ia mengajarkan kerendahan hati, perhatian, dan keterhubungan—nilai-nilai yang semakin langka di era hiper-individualisme.
Di Atas Sadle, Di Luar Pikiran
Sebagai pembaca filsafat Hibbard juga mengembangkan gagasan filsafat sepeda dan kesadaran yang membebaskan. Ada sebuah titik dalam sebuah pendakian yang curam, ketika napas men-jadi kasar seperti kertas ampelas dan denyut jantung menggema di pelipis, di mana seluruh narasi tentang “diri” mulai luruh. Sang pesepeda—yang sebelumnya adalah sebuah ego dengan rencana, kekhawatiran, dan cerita—pelan-pelan melebur menjadi hanya sebuah ritme: tarikan napas, putaran pedal, tatapan pada aspal di depan roda. Inilah pintu gerbang menuju ruang yang dibahas dalam tiga bab akhir perjalanan James Hibbard. Ini bukan lagi sekadar tentang bersepeda; ini adalah meditasi bergerak tentang hakikat menjadi, melihat, dan ada.
Meski Hibbard sekolah di jurusan filsafat, namun, jalan hidupnya mengambil belokan yang signifikan ketika ia pindah ke Los Angeles untuk mengejar karier akting. Di situlah, sebagai respons terhadap tekanan dan ketidakpastian industri hiburan, ia menemukan kembali ber-sepeda—sebuah aktivitas masa kecilnya—sebagai bentuk pelarian, meditasi, dan penemuan diri. Bersepeda tidak lagi sekadar hobi, tetapi berkembang menjadi gaya hidup dan jalan filosofis. Ia menjadi atlet ketahanan yang serius, menaklukkan rute-rute epik seperti Passo dello Stelvio di Alpen Italia dan berpartisipasi dalam lomba sepeda gran fondo yang melelahkan.
Pengalaman inilah yang akhirnya menyatukan dua benang hidupnya: kedalaman filsafat dan kesederhanaan yang sublim dari mengayuh sepeda. Pada 2023, ia merilis karya utamanya, “The Art of Cycling: Philosophy, Meaning, and a Life on Two Wheels” (diterbitkan oleh Pegasus Books). Buku ini bukan manual teknik bersepeda, melainkan sebuah esai filosofis yang mendalam yang menggunakan bersepeda sebagai lensa untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan besar tentang identitas, kesadaran, kebebasan, makna, dan bagaimana menjalani hidup yang baik. Hibbard menarik dari pemikiran para filsuf seperti Plato, Nietzsche, Kierkegaard, dan Sartre, serta pengalaman pribadinya di atas sadel, untuk berargumentasi bahwa bersepeda adalah praktik yang dapat mengarahkan kita pada kondisi “transendensi”—melampaui obrolan pikiran yang terus-menerus dan menyentuh inti keberadaan kita.
Perjalanan dimulai dengan keheningan yang membanjiri. Setelah berjam-jam mengayuh, percakapan batin yang tak putus-putusnya—tentang jarak yang tersisa, rasa sakit di kaki, agenda besok—akhirnya kehabisan tenaga. Ia diam. Dan dalam diam itu, sesuatu yang lain yang selalu ada tapi tertutupi oleh kebisingan, mulai terungkap. Buku ini mengupas tentang Kehampaan dan dunia di balik kata-kata, nothingness and the world beyond words (Bab 10).
Ini adalah “dunia di balik kata-kata.” Kata-kata adalah peta, tetapi pengalaman bersepeda adalah wilayahnya sendiri yang liar dan langsung. Kata “lelah” tidak akan pernah menangkap sensasi panas yang membakar di otot paha. Kata “pemandangan indah” mengkhianati ledakan kesadaran hijau, biru, dan emas saat meluncur di tepi jurang. Hibbard, melalui pengalaman bersepeda, membawa kita ke tepi linguistik. Di sana, kita menemukan Kehampaan (Nothingness)—bukan sebagai kekosongan yang mengerikan, tetapi sebagai ruang kemungkin-an yang jernih. Seperti seorang praktisi Zen yang duduk dalam zazen, pesepeda yang lelah menemukan bahwa ketika pikiran konseptual lelah, yang tersisa adalah kehadiran murni. Dunia tidak lagi diberi label; dunia dialami. Bunyi rantai yang berputar bukan “rantai,” melainkan sebuah simfoni logam yang ritmis. Angin yang menerpa bukan “angin,” melainkan sentuhan dingin yang tanpa nama yang membentuk diri. Dalam kehampaan ini, kita dibebaskan dari tirani narasi. Kita berhenti “membaca” perjalanan dan mulai “menjadi” perjalanan itu sendiri.
Bayangkan kisah seorang randonneur (pesepeda ketahanan jarak jauh) dalam event Paris-Brest-Paris. Setelah 600 kilometer dan tanpa tidur, ia melaporkan sebuah fenomena yang dikenal sebagai “the third state”—sebuah kondisi di mana rasa sakit dan waktu menghilang, digantikan oleh sebuah kesadaran otomatis yang tenang. Data fisiologis akan menunjukkan detak jantung yang stabil meski tubuh dalam tekanan ekstrem, sebuah paradoks yang hanya bisa dijelaskan dengan masuknya pikiran ke dalam keadaan flow atau meditatif yang melampaui kata-kata. Kehampaan menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan.
Dari ruang kehampaan yang jernih itu, sebuah realisasi muncul: identitas yang kita pegang erat—”Aku adalah seorang pengendara sepeda,” “Aku adalah tubuh yang lelah ini,” “Aku adalah si pemikir”—hanyalah lapisan permukaan. Bab ini adalah eksplorasi tentang diri yang terdiferensiasi. Engkau Bukan Hanya Ini, You’re Not Merely This (Bab 11).
Saat mengayuh, ada tubuh yang merasakan, ada napas yang mengalir, ada pemandangan yang dilihat, dan ada kesadaran yang menyaksikan semuanya. Mana yang “aku”? Hibbard mengajak kita melihat bahwa kita adalah medan pengalaman itu sendiri, bukan salah satu objek di dalamnya. Saat tanjakan terasa mustahil dan suara di kepala berkata, “Aku tidak bisa,” kita bisa belajar untuk mengenali: itu hanyalah sebuah pikiran yang lewat, sebuah sensasi di tubuh. “Kamu” adalah ruang kesadaran tempat pikiran dan sensasi itu muncul dan menghilang. Ini adalah kebijaksanaan yang ditemukan di persimpangan antara filsafat Barat (seperti gagasan David Hume tentang ketiadaan diri yang substansial) dan tradisi Timur (seperti ajaran Anatta atau ‘bukan-diri’ dalam Buddhisme).
Di atas sepeda, realisasi ini membebaskan. Rasa sakit tidak lagi berarti “Aku menderita,” melainkan “Ada sensasi yang intens di wilayah kaki.” Kegagalan tidak lagi berarti “Aku seorang pecundang,” meliarikan “Sebuah usaha belum membuahkan hasil yang diinginkan.” Identifikasi yang longgar ini mengubah dinamika daya tahan. Kita bukan lagi seorang korban dari kelelahan; kita adalah saksisekaligus partisipan dalam sebuah drama fisik yang besar.
Renungkan kisah atlet sepeda yang pulih dari cedera parah. Sebelumnya, identitasnya melekat erat pada “menjadi seorang atlit.” Saat cedera, ia mengalami penderitaan eksistensial—”jika aku bukan pesepeda, lalu siapa aku?” Proses penyembuhan sering kali melibatkan perluasan identitas: “Aku adalah kesadaran yang mengalami cedera, yang merasakan frustrasi, yang belajar kesabaran, dan yang suatu hari nanti mungkin akan bersepeda lagi.” Analisis psikologis akan menunjukkan bahwa atlet dengan self-concept yang lebih fleksibel dan kurang rigid cenderung lebih tangguh dalam menghadapi kemunduran. Bab ini adalah panduan untuk menemukan fleksibilitas itu di atas dua roda.
Buku ini betul-betul adalah pelajaran filsafat dari atas pelana. Setiap bagian-bagiannya tak lepas dari pemikiran filosofis seperti ketika para filosof Yunani berbicara dari kerumunan dan kesunyian. Segala Sesuatu Hanya Ada, Things Merely Are (Bab 12). Puncak dari perjalanan filosofis ini adalah sebuah penerimaan yang radikal dan penuh keajaiban. Setelah kata-kata diredam dan identitas dilihat sebagai sebuah permainan sementara, dunia muncul kembali dalam kemuliaannya yang paling sederhana dan paling menakjubkan: apa adanya.
“Things Merely Are.” Pepohonan, gunung, aspal yang berkilau oleh hujan, bahkan rasa sakit di lutut—semuanya tidak membutuhkan penilaian, interpretasi, atau cerita tambahan. Mereka ada dengan hakikatnya sendiri. Sebuah tanjakan bukan lagi “musuh yang harus dikalahkan,” melainkan sebuah bentuk geometris di permukaan bumi, sebuah kesempatan bagi tubuh untuk mengekspresikan potensi geraknya. Sebuah rasa sesak di dada bukan lagi “kecemasan,” melainkan sekumpulan sensasi energi yang berdenyut. Pandangan ini adalah intisari dari kesadaran non-dualistik—melihat tanpa memisahkan si penglihat dari yang dilihat.
Ini adalah keindahan yang membekukan dari olahraga ketahanan. Di saat-saat paling ekstrem, ketika semua drama manusiawi terkikis, yang tersisa hanyalah fakta telanjang dari keberadaan: ada kaki yang mendorong pedal, ada roda yang berputar, ada bumi yang berputar. Dan dalam kesederhanaan yang luar biasa ini, terkandung sebuah kedamaian yang mendalam. Bersepeda menjadi sebuah bentuk zikir yang bergerak, sebuah pengulangan fisik yang mengungkapkan kesucian dari momen sekarang. Kita tidak lagi bersepeda ke suatu tempat; kita bersepeda sebagaibagian dari tempat itu sendiri. Setiap putaran pedal adalah konfirmasi: Aku ada, ini ada, dan itu sudah lebih dari cukup.
Bayangkan seorang pesepeda yang telah menyelesaikan perjalanan epik, duduk di tepi jalan, melihat matahari terbenam. Tidak ada euforia yang heboh, hanya kelegaan yang sunyi dan lapang. Pikiran tidak lagi menceritakan kisah kemenangan. Ia hanya merefleksikan: “Langit itu merah. Keringat ini asin. Aku bernapas.” Inilah pencapaian tanpa pencapaian, tujuan tanpa tujuan. Dalam literatur eksplorasi diri, kondisi ini sering disebut sebagai “Pure Being”—dan sepeda hanyalah sebuah kendaraan yang luar biasa efektif untuk sampai ke sana.
Filsafat yang Dihidupi
James Hibbard, dalam tiga bab penutupnya, tidak menawarkan teori untuk dihafal, melainkan sebuah jalan untuk dialami. Sepeda adalah alatnya, tubuh adalah laboratoriumnya, dan jalanan terbuka adalah kanvasnya. “Nothingness,” “Not Merely This,” dan “Things Merely Are” bukanlah konsep abstrak; mereka adalah stasiun-stasiun dalam sebuah perjalanan transformatif yang dapat diakses oleh siapa saja yang bersedia mendorong pedal melampaui batas kebiasaan, baik fisik maupun mental.
Ini adalah seni sejati dari bersepeda: menggunakan gerakan yang repetitif dan keras untuk mengasah kesadaran hingga ia menjadi begitu jernih, sehingga akhirnya mampu merefleksikan hakikat terdalam dari realitas itu sendiri—sebuah realitas yang diam-diam menunggu untuk ditemukan di setiap tikungan jalan, di setiap tarikan napas dalam, di setiap keheningan yang muncul di antara detak jantung.
Bersepeda sebagai Spiritualitas
Di dunia modern yang telah kehilangan banyak ritual bersama, bersepeda muncul sebagai sebuah praktik yang ganjil sekaligus mendalam: ia tidak menjanjikan keselamatan, tidak menawarkan doktrin, dan tidak menuntut keyakinan metafisik apa pun. Namun justru karena itulah, bersepeda mampu berfungsi sebagai praktik spiritual sekuler—sebuah laku yang menumbuhkan perhatian, kerendahan hati, dan keterhubungan, tanpa perlu mengklaim kebenaran transenden di luar pengalaman itu sendiri.
James Hibbard, dalam The Art of Cycling, tidak pernah menyebut sepeda sebagai “agama”. Tetapi seluruh argumennya bergerak ke arah itu: bahwa bersepeda adalah latihan eksistensial yang mengajarkan bagaimana hidup secara utuh di dalam tubuh, di dalam dunia, dan bersama orang lain. Spiritualitas yang dimaksud di sini bukanlah pelarian dari dunia, melainkan pendalaman ke dalamnya.
Tubuh sebagai Jalan Pengetahuan
Etika bersepeda Hibbard bermula dari pembongkaran ilusi modern bahwa diri manusia bersemayam di otak. Ketika seseorang mengayuh, kesadaran tidak lagi terpusat pada pikiran abstrak, tetapi menyebar ke seluruh tubuh. Napas, detak jantung, tekanan pedal, dan arah angin menjadi sumber pengetahuan yang setara dengan rasio. Di atas sepeda, tubuh bukan alat, melainkan subjek yang mengetahui. Ini adalah koreksi radikal terhadap budaya produktivitas yang memandang tubuh sebagai mesin yang harus dioptimal-kan. Bersepeda mengajarkan bahwa memahami dunia tidak selalu berarti menguasainya; kadang, ia berarti merasakannya dengan penuh perhatian. Dalam konteks ini, etika bersepeda menuntut penghormatan terhadap tubuh—bukan dalam bentuk pemujaan kesehatan semata, tetapi dalam kesediaan mendengarkan batas, ritme, dan sinyal rasa sakit. Rasa sakit tidak dipuja, tetapi diterima sebagai bagian dari dialog antara niat dan kenyataan. Di sinilah muncul kebijaksanaan jasmani: mengetahui kapan bertahan, kapan melambat, dan kapan berhenti.
Gerak Tanpa Tujuan sebagai Kebajikan
Berbeda dengan perjalanan modern yang selalu diarahkan pada hasil, bersepeda menawarkan kemungkinan langka: bergerak tanpa alasan produktif. Etika bersepeda Hibbard menolak anggapan bahwa setiap gerak harus dibenarkan oleh efisiensi atau keuntungan. Dalam perjalanan tanpa tujuan jelas, muncul ruang kontemplatif yang tidak bisa dipaksakan. Pikiran melambat karena tubuh sibuk; ego mereda karena perhatian terserap oleh jalan. Ini bukan kemalasan, melainkan latihan kebebasan dari tirani tujuan. Sebagai praktik spiritual sekuler, bersepeda mengajarkan bahwa makna tidak selalu berada di ujung perjalanan. Kadang, makna justru muncul ketika kita berhenti bertanya “untuk apa” dan mulai bertanya “bagaimana aku hadir di sini”.
Kerentanan sebagai Etika Relasional
Bersepeda menempatkan manusia dalam posisi yang terbuka—tanpa pelindung baja, tanpa jarak teknologi yang memisahkan diri dari dunia. Kerentanan ini bukan kelemahan, melainkan fondasi etika. Di jalan, pesepeda harus membaca gerak orang lain, mengantisipasi, bernegosiasi, dan berbagi ruang. Tidak ada ilusi kedaulatan mutlak. Setiap pertemuan—dengan pejalan kaki, pengendara lain, atau bahkan konflik kecil—menjadi latihan etika mikro tentang hidup bersama.
Etika bersepeda, dalam pengertian ini, adalah etika koeksistensi. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa kebebasan pribadi selalu terikat pada kehadiran orang lain. Tidak ada keselamatan individual yang terpisah dari keselamatan bersama.
Waktu yang Melambat sebagai Bentuk Perlawanan
Sebagai praktik spiritual sekuler, bersepeda juga bersifat politis—bukan dalam arti ideologis sempit, tetapi sebagai perlawanan terhadap rezim percepatan. Sepeda bergerak cukup cepat untuk melampaui keterbatasan tubuh, tetapi cukup lambat untuk mempertahankan hubungan dengan lanskap dan manusia. Dalam ritme kayuhan, waktu kembali terasa berlapis: ada waktu napas, waktu tanjakan, waktu menunggu lampu lalu lintas. Ini adalah waktu yang dialami, bukan waktu yang diukur semata. Etika bersepeda mengajarkan bahwa melambat bukan kegagalan moral, melainkan pilihan eksistensial.
Transendensi Tanpa Dunia Lain
Transendensi dalam bersepeda, sebagaimana digambarkan Hibbard, tidak mengarah ke dunia lain. Ia muncul ketika batas antara diri dan dunia melembut: ketika tubuh, sepeda, jalan, dan lanskap menyatu dalam satu aliran gerak. Ini adalah pengalaman yang dikenal dalam banyak tradisi spiritual—tetapi di sini dicapai tanpa ritual sakral, tanpa doktrin, tanpa janji keselamatan. Transendensi ini bersifat sementara, rapuh, dan justru karena itu bermakna. Ia tidak dimiliki; ia dialami.
Etika Bersepeda sebagai Cara Hidup
Disintesis dari seluruh refleksi Hibbard, etika bersepeda sebagai praktik spiritual sekuler dapat dipahami sebagai laku hidup yang menekankan: hadir sepenuhnya dalam tubuh, bergerak dengan kesadaran, menerima keterbatasan tanpa sinisme, dan hidup bersama dunia tanpa ilusi dominasi. Bersepeda tidak menjadikan seseorang lebih suci. Tetapi ia dapat menjadikan seseorang lebih perhatian, lebih sabar, dan lebih sadar akan keterhubungan yang rapuh antara diri, orang lain, dan dunia.
Di era di mana spiritualitas sering diperdagangkan dan keheningan harus dibeli, sepeda menawarkan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih jujur: sebuah jalan sempit, dua roda, dan kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi manusia—tanpa harus percaya pada apa pun selain gerak itu sendiri.
Catatan Akhir: Etika Bersepeda sebagai Praktik Spiritual
Bersepeda, dalam pembacaan James Hibbard, adalah sebuah praktik yang bekerja diam-diam di wilayah yang selama ini diklaim agama dan filsafat: pertanyaan tentang tubuh, tujuan hidup, penderitaan, relasi dengan sesama, dan makna keberadaan. Namun ia melakukannya tanpa simbol sakral, tanpa dogma, dan tanpa janji keselamatan. Di sinilah bersepeda dapat dipahami sebagai spiritualitas sekuler—sebuah laku yang membentuk etika hidup melalui pengalaman jasmani yang sadar.
1. Tubuh sebagai Subjek Moral dan Epistemik
Etika bersepeda dimulai dari kritik terhadap pandangan modern bahwa manusia adalah “otak yang membawa tubuh”. Di atas sepeda, kesadaran tidak berpusat pada pikiran abstrak, melainkan menyebar ke seluruh tubuh: napas, otot, keseimbangan, dan kelelahan. Tubuh bukan instrumen, melainkan sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, bersepeda melatih etika perhatian terhadap tubuh—bukan sebagai proyek optimasi, tetapi sebagai dialog terus-menerus dengan batas. Rasa sakit tidak dimuliakan, tetapi diterima sebagai pesan; kelelahan tidak ditaklukkan secara heroik, melainkan dinegosiasikan. Etika ini menolak kekerasan terhadap diri sendiri yang sering disamarkan sebagai disiplin.
2. Tujuan yang Dilembutkan oleh Proses
Bersepeda mengajarkan bahwa tidak semua gerak harus dibenarkan oleh hasil. Dalam perjalan-an yang tidak sepenuhnya instrumental, tujuan kehilangan sifat tiraniknya. Yang muncul adalah nilai proses—ritme kayuhan, perubahan lanskap, dan kehadiran penuh di saat kini.
Sebagai praktik spiritual sekuler, bersepeda membentuk etika non-teleologis: hidup tidak selalu harus “menuju” sesuatu. Ada kebajikan dalam bergerak tanpa klaim produktivitas. Ini adalah koreksi terhadap moralitas kapitalistik yang mengukur nilai hidup dari output semata.
3. Kerentanan sebagai Dasar Etika Sosial
Di jalan, pesepeda berada dalam keadaan terbuka. Tidak ada selubung baja, tidak ada jarak teknologi yang mengaburkan konsekuensi. Kerentanan ini membentuk etika relasional yang khas: membaca situasi, mengantisipasi orang lain, dan berbagi ruang. Etika bersepeda dengan demikian adalah etika ko-eksistensi. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa kebebasan pribadi selalu dinegosiasikan dengan keselamatan bersama. Tidak ada kedaulatan absolut; yang ada adalah keterhubungan rapuh yang harus dirawat setiap saat.
4. Penderitaan sebagai Guru, Bukan Tujuan
Hibbard menolak romantisasi penderitaan. Dalam bersepeda, penderitaan tidak dicari demi makna, tetapi sering kali tak terelakkan. Etika yang lahir darinya adalah kemampuan untuk. hadir di dalam ketidaknyamanan tanpa melarikan diri dan tanpa memutlakkan rasa sakit. Ini mendekati latihan asketik dalam tradisi spiritual, tetapi tanpa kerangka penebusan. Penderitaan menjadi guru karena ia membongkar ilusi kontrol dan memaksa kejujuran terhadap diri sendiri.
5. Dunia sebagai Mitra, Bukan Objek
Bersepeda mengubah relasi dengan dunia. Jalan, cuaca, tanjakan, dan angin tidak ditaklukkan, melainkan dihadapi sebagai mitra dialog. Etika ini menolak sikap dominatif terhadap alam dan kota. Dalam pengertian ini, bersepeda menumbuhkan kerendahan hati ekologis. Dunia tidak hadir untuk dilalui secepat mungkin, tetapi untuk dialami secara bermakna.
6. Transendensi yang Imanen
Pengalaman “melampaui diri” dalam bersepeda tidak mengarah ke dunia lain. Ia muncul ketika batas antara diri, sepeda, dan lingkungan melebur dalam satu aliran gerak. Transendensi ini bersifat sementara, rapuh, dan tidak dapat dimiliki. Justru karena tidak dilembagakan, peng-alaman ini tetap jujur. Ia tidak menjadi klaim moral atas orang lain, melainkan pengingat akan keterbatasan dan keterhubungan.
7. Waktu yang Melambat sebagai Etika Perlawanan
Bersepeda menempatkan tubuh dalam waktu yang dialami, bukan sekadar diukur. Ritme kayuhan menciptakan jeda dalam budaya percepatan. Etika bersepeda di sini adalah etika perlambatan—bukan nostalgia, tetapi sikap kritis terhadap dunia yang terus memaksa percepatan sebagai nilai moral.
Sebagai praktik spiritual, bersepeda membentuk etika hidup yang berporos pada: kehadiran tubuh, kerendahan hati terhadap batas, penerimaan penderitaan tanpa glorifikasi, relasi yang saling memperhitungkan, dan keterhubungan dengan dunia yang tidak ingin ditaklukkan.
Ia tidak menawarkan keselamatan, tetapi kejelasan. Tidak menjanjikan kebahagiaan abadi, tetapi ketenangan sementara yang jujur. Menyadari dan bertindak dengan cara berada di dunia yang lebih beradab. Dalam dunia yang haus makna, bersepeda mengajarkan bahwa spiritualitas tidak selalu membutuhkan iman—kadang, ia hanya membutuhkan dua roda, jalan terbuka, dan kesediaan untuk mengayuh dengan penuh kesadaran.
Kode Etik Bersepeda: Sepuluh Prinsip
Berikut adalah Kode Etik Bersepeda (10 Prinsip) yang disintesis dari The Art of Cycling (James Hibbard) dan dirumuskan sebagai praktik spiritual—bisa dibaca sebagai panduan etis personal, sosial, dan ekologis bagi pesepeda modern.
1. Prinsip Kehadiran Tubuh
Bersepedalah dengan kesadaran penuh akan tubuh. Tubuh bukan alat yang harus dipaksa, melainkan subjek yang harus didengarkan. Napas, kelelahan, dan rasa sakit adalah bahasa—bukan musuh. Etika bersepeda dimulai dari perhatian, bukan penaklukan.
2. Prinsip Keselarasan Tujuan dan Proses
Jangan korbankan proses demi tujuan. Kecepatan, jarak, dan pencapaian tidak membenarkan pengabaian pengalaman. Nilai bersepeda terletak pada perjalanan itu sendiri, bukan semata hasil akhirnya.
3. Prinsip Kerentanan yang Bertanggung Jawab
Sadari kerentananmu, dan rawat kerentanan orang lain. Di jalan, pesepeda hidup dalam keterbukaan. Kesadaran akan rapuhnya diri melahirkan kewaspadaan, empati, dan tanggung jawab sosial.
4. Prinsip Non-Kekerasan terhadap Diri
Jangan menyamarkan kekerasan sebagai disiplin. Latihan dan ketekunan tidak berarti menolak batas tubuh. Bersepeda yang etis menghormati waktu pemulihan, usia, dan kondisi—bukan memuja penderitaan.
5. Prinsip Penderitaan sebagai Guru
Terimalah ketidaknyamanan tanpa memuliakannya. Tanjakan, angin, dan jarak mengajarkan kesabaran dan kerendahan hati. Penderitaan bukan tujuan, tetapi ruang pembelajaran tentang batas dan ketabahan.
6. Prinsip Ko-eksistensi di Ruang Publik
Berbagilah ruang dengan adil dan sadar. Jalan adalah milik bersama. Etika bersepeda menuntut kesediaan membaca situasi, memberi jalan, dan menghormati keberadaan pejalan kaki serta pengguna jalan lain.
7. Prinsip Kerendahan Hati Ekologis
Hadapi alam dan kota sebagai mitra, bukan objek. Cuaca, medan, dan lanskap bukan hambatan yang harus ditaklukkan, melainkan kondisi yang harus dipahami dan dihormati. Bersepeda adalah dialog dengan lingkungan.
8. Prinsip Perlambatan yang Bermakna
Hormati ritme manusiawi. Menolak percepatan yang tidak perlu adalah tindakan etis. Bersepeda mengajarkan bahwa hidup yang layak tidak selalu yang tercepat.
9. Prinsip Kesederhanaan Teknologis
Gunakan teknologi untuk mendukung kesadaran, bukan menggantikannya. Peralatan dan data boleh membantu, tetapi jangan sampai mengaburkan hubungan langsung antara tubuh, sepeda, dan dunia.
10. Prinsip Transendensi yang Imanen
Biarkan makna muncul, jangan dipaksakan. Momen-momen hening, mengalir, dan menyatu dengan gerak tidak dapat direkayasa. Etika bersepeda menghormati pengalaman tersebut tanpa mengklaimnya sebagai keunggulan moral.
Kode etik ini tidak dimaksudkan sebagai aturan kaku, melainkan kompas batin. Ia tidak menilai siapa yang “paling benar”, tetapi mengingatkan bagaimana bersepeda dapat menjadi cara hidup yang lebih sadar, adil, dan beradab—di jalan, di kota, dan di dalam diri.
Sebagai hikmah rasanya kta perlu mempertimbangkan sebuah Manifesto Komunitas Sepeda yang disusun dari Kode Etik Bersepeda sebagai praktik spiritual—ditulis sebagai nilai bersama komunitas sepeda.
MANIFESTO KOMUNITAS SEPEDA
Bersepeda sebagai Cara Hidup yang Beradab
Kami bersepeda bukan semata untuk bergerak,
tetapi untuk hadir.
Bukan hanya untuk tiba,
tetapi untuk mengalami.
Di atas dua roda, kami belajar bahwa tubuh bukan mesin,
jalan bukan milik satu golongan,
dan kecepatan bukan ukuran nilai manusia.
Maka kami menyatakan komitmen bersama ini.
1. Kami Menghormati Tubuh
Kami bersepeda dengan kesadaran penuh.
Kami mendengarkan napas, kelelahan, dan rasa sakit sebagai pengetahuan, bukan kelemahan.
Kami menolak budaya memaksa tubuh demi prestise.
2. Kami Menghargai Proses, Bukan Hanya Tujuan
Kami tidak mengorbankan pengalaman demi angka, waktu, atau gengsi.
Setiap kayuhan adalah bagian dari makna, bukan sekadar alat mencapai hasil.
3. Kami Mengakui Kerentanan
Kami sadar bahwa bersepeda membuat kami terbuka dan rapuh.
Kesadaran ini menumbuhkan empati, kewaspadaan, dan kepedulian pada sesama pengguna jalan.
4. Kami Menolak Kekerasan Terselubung
Kami tidak memuja penderitaan.
Disiplin kami bukan penyangkalan diri, melainkan perawatan diri yang berkelanjutan.
5. Kami Belajar dari Ketidaknyamanan
Tanjakan, panas, hujan, dan angin adalah guru.
Kami menghadapinya dengan sabar, rendah hati, dan tanpa kesombongan.
6. Kami Berbagi Ruang Publik
Kami bersepeda dengan hormat kepada pejalan kaki, pesepeda lain, dan pengguna jalan lainnya.
Kami percaya jalan adalah ruang bersama, bukan arena dominasi.
7. Kami Hidup Selaras dengan Lingkungan
Kami melihat kota dan alam sebagai mitra, bukan objek penaklukan.
Kami bersepeda dengan kesadaran ekologis dan tanggung jawab terhadap bumi.
8. Kami Memilih Perlambatan yang Bermakna
Kami menolak percepatan yang menghilangkan makna hidup.
Dalam perlambatan, kami menemukan ritme manusiawi.
9. Kami Menggunakan Teknologi Secara Bijak
Kami memakai teknologi untuk membantu kesadaran, bukan menggantikannya.
Kami tidak membiarkan data memutus hubungan antara tubuh, sepeda, dan dunia.
10. Kami Terbuka pada Makna yang Muncul
Kami tidak memaksakan pengalaman puncak.
Kami membiarkan momen hening, aliran, dan kebersamaan tumbuh secara alami.
Janji Bersama
Kami bersepeda bukan untuk menjadi yang tercepat,
tetapi untuk menjadi lebih manusia.
Kami percaya bahwa dari kayuhan yang sederhana
dapat lahir kota yang lebih adil,
tubuh yang lebih waras,
dan hidup yang lebih bermakna.
Di jalan, kami belajar hidup bersama.
Di atas sepeda, kami belajar menjadi utuh.
Sepeda dan Kehidupan yang Layak Dihidupi
Pada akhirnya, The Art of Cycling adalah undangan: untuk melihat kembali bagaimana kita bergerak di dunia, dan apa yang kita anggap sebagai hidup yang baik. Dalam era krisis iklim, kelelahan mental, dan fragmentasi sosial, Hibbard menawarkan sepeda sebagai praktik kecil dengan implikasi besar.
Bersepeda tidak akan menyelesaikan semua masalah dunia. Namun ia bisa mengajarkan cara hidup yang lebih penuh perhatian, lebih berkelanjutan, dan lebih bermakna. Sebuah seni hidup yang sederhana, namun radikal.
Bogor, 30 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Hibbard, J. (2023). The art of cycling: Philosophy, meaning, and a life on two wheels. New York & London: Pegasus Books.
Illich, I. (1974). Energy and equity. London: Calder & Boyars.
Merleau-Ponty, M. (2012). Phenomenology of perception (D. A. Landes, Trans.). Routledge. (Original work published 1945)
Rosa, H. (2013). Social acceleration: A new theory of modernity. Columbia University Press.
Thoreau, H. D. (1854/2004). Walden. Princeton University Press.