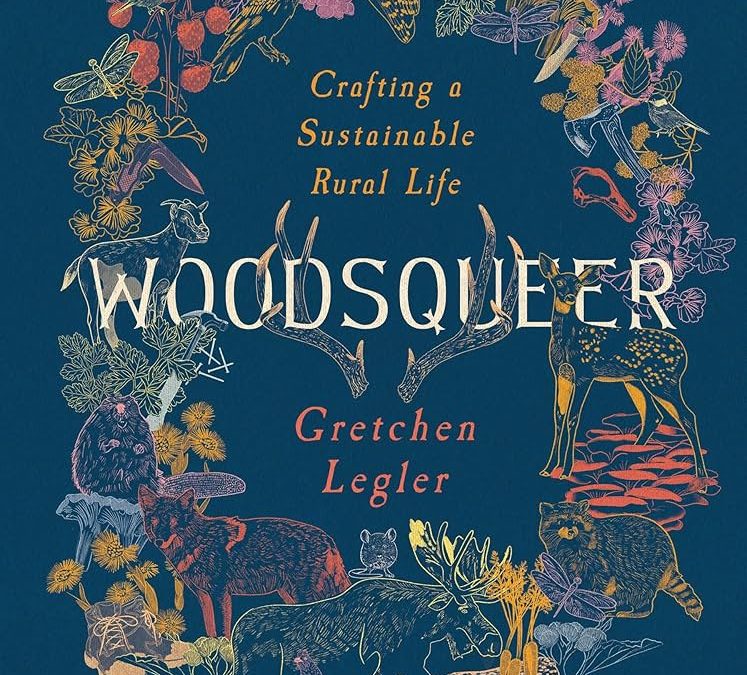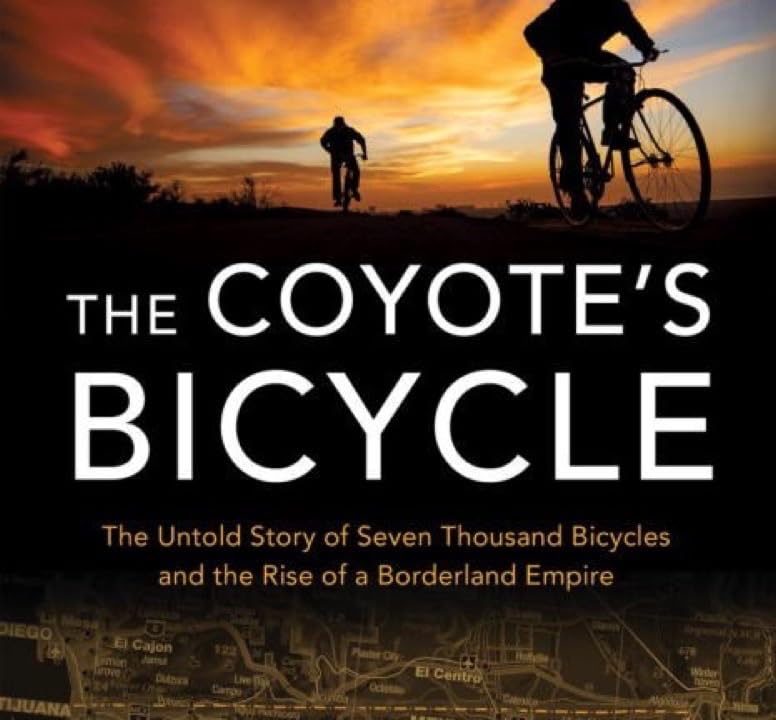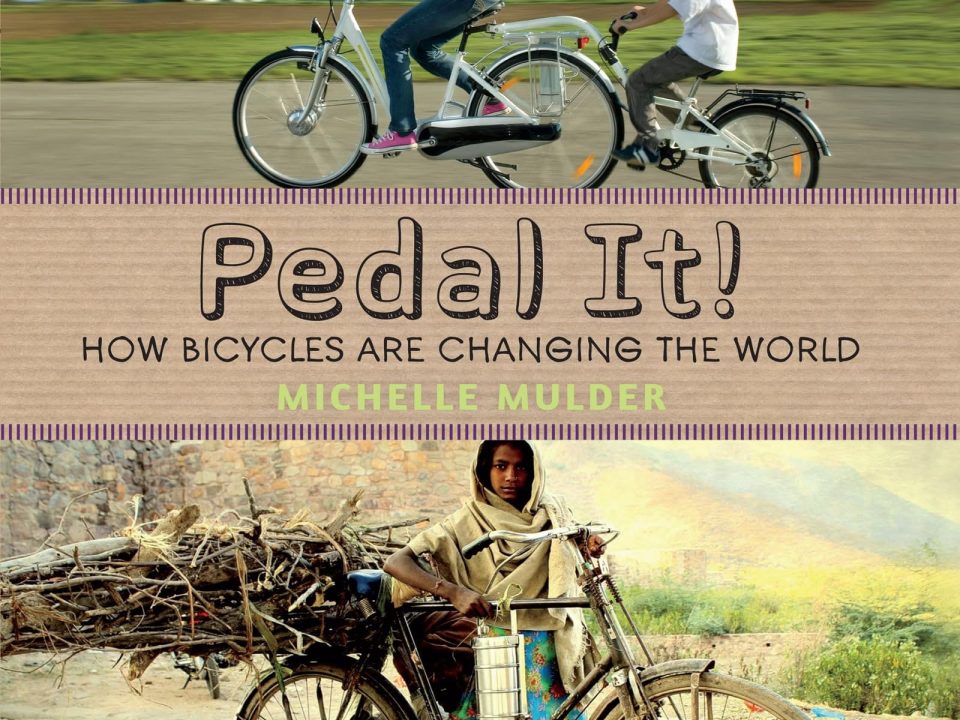Rubarubu #104
Woodsqueer:
Mendengar Bisikan Kayu dan Musim Dingin
Di sebuah pondok kayu tanpa listrik atau air ledeng di hutan Maine, seorang perempuan berdiri di tengah salju yang menggunung. Tangannya yang beku membelah kayu bakar, bukan sebagai latihan ketahanan diri yang romantis, tetapi sebagai kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup dalam suhu -20°C. Gretchen Legler, seorang profesor penulisan yang terbiasa dengan dunia akademis, memilih untuk menjalani satu tahun penuh di tempat terpencil bersama pasangannya, Ruth. Di sinilah, di antara cahaya lilin dan desau angin melalui pepohonan pinus, lahir kata “Woodsqueer”—sebuah istilah yang mereka ciptakan untuk menggambarkan sensasi aneh, indah, dan terkadang menakutkan dari menjadi “miring” atau “tidak waras” karena terlalu larut dalam kesendirian dan kesunyian alam. Woodsqueer: Crafting a Sustainable Rural Life (2021) bukanlah sekadar memoar tentang “kembali ke alam”; ini adalah catatan yang jujur dan reflektif tentang upaya membangun kehidupan yang berkelanjutan dan penuh arti, yang dirajut dari keterampilan tangan, perhatian penuh terhadap musim, dan cinta yang mendalam—baik kepada manusia maupun kepada tanah tempat mereka berpijak.
Bagian pembuka buku ini tidak ditulis sebagai manifesto keberlanjutan, melainkan sebagai undangan yang intim ke dalam sebuah pengalaman. Legler langsung membawa pembaca ke dalam kesunyian dan kejernihan dunia barunya, menggambarkan transisi dari kehidupan profesor yang sibuk menjadi kehidupan seorang penghuni hutan yang sehari-harinya diukur dengan tumpukan kayu bakar dan persediaan makanan di gudang bawah tanah. Kata “Woodsqueer” didefinisikan bukan sebagai kegilaan, tetapi sebagai transformasi persepsi—sebuah cara melihat di mana batas antara diri dan hutan menjadi kabur, di mana manusia tidak lagi menjadi pusat, melainkan bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang luas dan saling terhubung. Seperti yang diungkapkannya, kehidupan di pondok itu adalah tentang “belajar memperhatikan dengan cara baru” (Legler, 2021, p. 5). Pengantar ini menetapkan nada bahwa keberlanjutan yang ia cari bukanlah soal sistem teknologi, tetapi soal kehidupan sehari-hari yang dijalani dengan sengaja, penuh rasa syukur, dan tanggung jawab.
Intisari dan Elaborasi Bagian-Bagian Buku
Buku ini dibangun seperti sebuah journal musiman, dirajut dari esai-esai yang menangkap esensi hidup di pedesaan. Legler mendokumentasikan dengan puitis dan tajam ritme kerja fisik yang membentuk hari-harinya: memotong, membelah, dan menumpuk kayu; berkebun dan mengawetkan makanan untuk musim dingin; memanen sirup maple; dan merawat tanah serta bangunan. Setiap tugas bukan beban, tetapi meditasi dan bentuk pengetahuan. Seperti kata filosof petani Wendell Berry, “Makan adalah tindakan pertanian.” Legler menghidupi prinsip ini dengan menunjukkan bagaimana setiap gigitan makanan di musim dingin adalah hasil dari kerja, rencana, dan hubungannya dengan tanah di musim panas.
Namun, Woodsqueer jauh lebih dalam dari sekadar panduan hidup sederhana. Buku ini juga merupakan perjalanan emosional dan spiritual yang mendalam. Legler dengan jujur mengeksplorasi kesepian, ketakutan (terhadap kegelapan, binatang buas, ketidakcukupan), dan kerentanan yang menyertai pilihannya. Ia juga merayakan kegembiraan yang ditemukan dalam kesederhanaan, kedekatan dengan pasangannya Ruth, dan kebahagiaan spiritual yang ditemukan dalam keheningan alam. Hidup berkelanjutan di sini adalah soal keutuhan—menyatukan kerja tubuh dengan kedamaian pikiran, dan kepedulian terhadap lingkungan dengan kesehatan hubungan manusia. Dalam hal ini, pemikiran ekofeminis Muslim seperti Dr. Laily Fitria yang menekankan “ekologi kasih sayang” (rahmatan lil ‘alamin) menemukan resonansinya. Keberlanjutan bukan penguasaan atas alam, melainkan pengasuhan (ri’ayah) terhadap sebuah hubungan timbal balik yang penuh rahmat.
Salah satu sumbangan terbesar buku ini adalah cara Legler meruntuhkan dikotomi antara manusia dan alam. Ia tidak melihat hutan sebagai “sumber daya” atau “pemandangan”, tetapi sebagai tetangga, guru, dan bagian dari identitasnya sendiri. Saat menggambarkan seekor rusa yang mati, perubahan warna daun, atau kicauan burung tertentu, ia mengajak pembaca untuk mengembangkan etika perhatian dan kediaman. Penyair besar Persia Jalaluddin Rumi berkata, “Dengarkan bisikan bambu, dan di dalamnya temukan rahasia kehilangan dan cinta.” Legler mendengarkan bisikan hutan Maine, dan di dalamnya menemukan rahasia tentang hidup, mati, ketahanan, dan cinta—baik kepada Ruth maupun kepada dunia itu sendiri.
Di era krisis iklim, kecemasan ekologis, dan kehidupan digital yang serba cepat serta terputus, Woodsqueer menawarkan sebuah penawar yang mendalam. Buku ini relevan bukan karena mendorong semua orang untuk pindah ke hutan, tetapi karena ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting: Apa yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup yang baik? Bagaimana kita dapat hidup lebih selaras dengan ritme alam? Bagaimana kita membangun ketahanan—baik material maupun emosional—dalam dunia yang tidak pasti?
Buku ini memberikan sebuah model mental untuk keberlanjutan yang manusiawi dan ter-hubung. Ia menunjukkan bahwa transisi ke masa depan yang lebih berkelanjutan harus mencakup dimensi spiritual, emosional, dan komunal, bukan hanya teknis dan politis. “Crafting” atau “merajut” dalam judul buku bukan hanya tentang kerajinan tangan, tetapi tentang aktifitas membangun kehidupan dengan sengaja, jahitan demi jahitan, pilihan demi pilihan.
Prospek masa depan yang digambarkan Legler adalah dunia di mana kita memulihkan hubung-an kita yang rusak—dengan tanah, dengan makanan, dengan kerja tangan, dan dengan satu sama lain. Ia membayangkan sebuah masa depan di mana kita tidak takut pada kesunyian, di mana kita menemukan kekayaan dalam kecukupan, dan di mana keberlanjutan adalah sebuah praktik cinta sehari-hari. Di tengah narasi besar tentang ekonomi hijau dan teknologi bersih, suara Legler mengingatkan kita pada akar kata “ekologi” itu sendiri: oikos, yang berarti rumah. Masa depan yang berkelanjutan harus terasa seperti rumah—sebuah tempat dirawat, dipahami, dan dicintai.
Woodsqueer: Mendiami Batas, Malam, dan Cinta
Woodsqueer bukanlah sebuah analisis, melainkan serangkaian momen yang dipertajam—sebuah kumpulan vignette yang menangkap esensi dari apa artinya menjadi “woodsqueer”. Di sini, Gretchen Legler tidak lagi hanya menggambarkan kerja dan musim; ia menyelami geografi batin yang dibentuk oleh isolasi, keintiman dengan yang non-manusia, dan pengakuan men-dalam akan ikatan cinta yang menopang kehidupannya. Bagian ini adalah sebuah eksplorasi tentang menghuni batas-batas—antara peradaban dan alam liar, antara ketakutan dan ketenangan, antara identitas individu dan komitmen bersama.
Bagian ini dibuka dengan esai judul “Woodsqueer I”, di mana Legler mendefinisikan kondisi ini secara lebih mendalam. Menjadi woodsqueer adalah mengalami “sensasi miring” (tilted), di mana persepsi normal terganggu oleh kesendirian dan kedekatan yang ekstrem dengan alam. Ini bukanlah penyakit, tetapi sebuah transformasi cara mengetahui. Dunia tidak lagi dibaca melalui teks atau layar, tetapi melalui suara angin, jejak binatang di salju, dan kualitas kehe-ningan itu sendiri. Legler (2021) menulis bahwa ini adalah keadaan di mana “pikiranmu mulai mengikuti logika lain, logika yang lebih tua dan lebih lambat” (p. 135). Ini mengingatkan pada konsep filsuf Prancis Gaston Bachelard tentang “imajinasi materi”, di mana kesendirian yang mendalam memungkinkan imajinasi untuk berdialog secara langsung dengan elemen-elemen material dunia—kayu, es, kegelapan.
Kemudian, dalam “Minding the Fence“, perhatian dialihkan ke tugas yang tampaknya prosaik: memperbaiki pagar. Namun, di tangan Legler, ini menjadi meditasi yang mendalam tentang pemeliharaan dan batas. Pagar bukanlah simbol penolakan, tetapi sebuah struktur yang men-definisikan hubungan—menjaga kebun dari rusa, menandai wilayah, dan menciptakan rasa aman yang diperlukan untuk kehidupan berkelanjutan. “Merawat pagar,” tulisnya, “adalah cara merawat rumah, merawat hubungan kita dengan tanah ini” (Legler, 2021, p. 142). Ini adalah tindakan rendah hati yang melambangkan etos keseluruhan hidupnya: keberlanjutan sebagai sebuah praktik perawatan yang berulang dan penuh perhatian, bukan pencapaian yang sekali jadi. Seperti diungkapkan pemikir ekologi Muslim Seyyed Hossein Nasr, manusia sebagai khalifah bertugas memelihara (istikhlaf) keseimbangan alam, sebuah tugas yang dimulai dari tindakan merawat pagar di kebunnya sendiri.
Ketenangan tersebut diselingi oleh kehadiran tak terduga dalam “The Three O’clock Cat“. Seekor kucing liar (atau mungkin bukan kucing sepenuhnya) mulai muncul secara teratur di jendela mereka pada jam tiga pagi. Makhluk nokturnal ini menjadi simbol dari misteri dan “liar”-nya yang tidak sepenuhnya bisa dijinakkan. Legler tidak mencoba memilikinya, tetapi menghormati kunjungannya, mengakui bahwa mereka berbagi ruang dengan makhluk lain yang memiliki agendanya sendiri. Esai kecil ini menegaskan bahwa hidup di hutan berarti hidup dalam komunitas multi-spesies, di mana manusia bukanlah pusat, melainkan bagian dari jaringan pengamatan dan kehadiran yang saling silang.
Suasana berubah gelap dan lebih reflektif dalam “Acquainted with the Night“. Di sini, Legler menghadapi jantung dari pengalaman woodsqueer: ketakutan dan keindahan yang tak terpisah-kan dari kesendirian di malam hari. Ia mengakui rasa takut yang primitif—terhadap apa yang mungkin bersembunyi di balik kegelapan. Namun, seiring waktu, ia menjadi “berkenalan” dengan malam. Ia belajar menavigasinya, mendengarkan bahasanya, dan bahkan menemukan kedamaian di dalamnya. “Malam mengajari kita untuk melihat dengan telinga, dan mendengar dengan kulit kita,” katanya (Legler, 2021, p. 155). Perjalanan dari ketakutan menuju keakraban ini adalah metafora yang kuat untuk menghadapi semua hal yang asing dan menakutkan dalam hidup, termasuk bagian-bagian terdalam dari diri sendiri.
Penyair Rumi pernah menulis, “Bukan dengan melarikan diri dari ketakutan, tetapi dengan melaluinya, kita menemukan diri kita yang sebenarnya.” Legler hidup dalam kata-kata ini, melangkah ke dalam ketakutan malam hutan dan muncul dengan pemahaman yang lebih dalam.
Esai “Woodsqueer II” bertindak sebagai refleksi lanjutan, menganyam pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi pemahaman yang lebih padat. Ia menyadari bahwa menjadi woodsqueer juga berarti menerima ketergantungan yang radikal—pada kayu bakar, pada persediaan makanan, pada Ruth, dan pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini adalah keadaan kerendahan hati.
Bagian ini mencapai puncak emosional dan naratifnya dalam “Lesbian Wedding I”. Di sini, semua benang—pekerjaan, keterampilan, perhatian, cinta, dan komitmen pada sebuah tempat—menyatu. Legler menggambarkan persiapan pernikahan mereka di pondok, sebuah perayaan yang dirajut dari kerja tangan mereka sendiri (membuat roti, menghias dengan bunga liar) dan dihadiri oleh komunitas kecil yang mereka bangun. Pernikahan ini bukanlah adegan romantis yang kabur, tetapi manifestasi politik dan spiritual dari kehidupan berkelanjutan yang mereka pilih. Ini adalah pernyataan bahwa cinta mereka, seperti kehidupan mereka di tanah itu, adalah tentang ketekunan, perawatan, dan kehadiran penuh. Cinta dan keberlanjutan menjadi tak terpisahkan. Seperti kata penulis aktivis adrienne maree brown dalam Emergent Strategy, “Apa yang kita praktikkan menjadi lebih kuat.” Legler dan Ruth mempraktikkan cinta sebagai tindakan sehari-hari bertahan hidup dan berkembang bersama, di tanah yang sama, dan dalam praktik itu, mereka mengukuhkan baik identitas mereka maupun komitmen mereka pada kehidupan yang berakar.
Secara keseluruhan, Bagian ini adalah inti dari buku ini. Di sini, Legler menunjukkan bahwa “merajut kehidupan pedesaan yang berkelanjutan” pada akhirnya adalah proyek batin yang sama mendesaknya dengan proyek fisik. Ini adalah tentang menjadi cukup akrab dengan ketakutan malam sehingga kita bisa mendengar nyanyiannya; tentang menemukan makna sakral dalam memperbaiki pagar; tentang melihat kunjungan kucing liar sebagai anugerah; dan tentang memahami bahwa cinta adalah pondasi paling kuat untuk segala bentuk ketahan-an. Keberlanjutan, dalam bagian ini, terungkap bukan sebagai sebuah set kebajikan, tetapi sebagai keadaan keberadaan yang terlahir dari perhatian yang mendalam dan cinta yang berani.
Dengan Hewan-Hewan: Etika Kedekatan dan Kematian
Bagian lain dari Woodsqueer ini membawa kita ke dalam pusat dari hubungan manusia dengan alam yang paling kuno, paling mendasar, dan paling ambivalen: hubungan kita dengan hewan lain. Judulnya, “Dengan Hewan-Hewan” (With the Animals), bukanlah pengamatan pasif, melainkan sebuah deklarasi kediaman—Legler hidup bersama mereka, dalam sebuah komuni-tas yang kompleks yang terdiri dari perhatian, ketakutan, ketergantungan, dan kemati-an. Bagian ini mengungkap bahwa membangun kehidupan berkelanjutan di pedesaan pada akhirnya berarti merundingkan kembali etika kedekatan dengan makhluk hidup lain, yang seringkali melibatkan kontak langsung dengan realitas keras kehidupan dan kematian.
Perjalanan dimulai dalam “The Barn at Midnight“, sebuah esai yang membenamkan kita dalam keheningan magis dan sedikit menakutkan dari sebuah struktur tua di tengah malam. Barn (lumbung) ini bukan sekadar bangunan; ia adalah arsip dari kehidupan yang telah berlalu, menyimpan aroma jerami dan kotoran hewan, gema dari kerja dan kelahiran masa lalu. Di sini, Legler mendengarkan dan merasakan sejarah tempat itu melalui tubuhnya sendiri. Pengalaman ini mengajarkan bahwa keberlanjutan juga tentang menghuni ingatan sebuah lanskap, tentang menjadi sadar akan lapisan-lapisan kehidupan yang telah membentuk tempat yang kini kita sebut rumah. Ia menjadi medium untuk suara-suara yang telah pergi. Filsuf Gaston Bachelard, dalam The Poetics of Space, menulis tentang bagaimana lumbung dan gudang menyimpan “kenangan yang diimpikan”. Legler mengalami ini secara langsung—barn di tengah malam adalah ruang di mana imajinasi bertemu dengan sejarah material.
Esai “With the Animals” yang memberi judul bagian ini, kemudian mengajak kita ke dalam komunitas hidup yang nyata. Legler menggambarkan kehadiran konstan hewan-hewan lain—mulai dari tikus di loteng hingga rusa di pinggir hutan, dari burung-burung hingga serangga. Hidup berkelanjutan berarti berbagi ruang, dan berbagi ruang selalu melibatkan konflik dan negosiasi. Dia tidak meromantisasi hewan-hewan ini sebagai tokoh kartun; mereka adalah tetangga yang mencuri benih kebun, meninggalkan jejak, dan mengingatkannya bahwa dunia ini bukan milik manusia semata. Ini adalah praktik “keberpihakan yang luas” (wide allegiance), sebuah konsep ekologi yang mengenali bahwa kita terikat pada seluruh jaring kehidupan, bukan hanya pada spesies kita sendiri. Dalam tradisi Islam, konsep “ummah” sering diperluas oleh pemikir sufi untuk mencakup semua makhluk (kawn), menekankan bahwa semua ciptaan memuji Penciptanya dan layak mendapat penghormatan.
Pemahaman ini diuji dan diperdalam dalam bab-bab berikutnya. “Woodlot” (Tanah Hutan) adalah meditasi tentang hubungan langsung dengan sumber daya yang paling vital: kayu. Bekerja di woodlot adalah dialog fisik dengan pohon. Memilih, menebang, dan membelah kayu bukanlah tindakan penghancuran semata, tetapi bagian dari siklus pengelolaan yang menghormati. Legler memahami bahwa mengambil kehidupan pohon adalah untuk mempertahankan kehidupannya sendiri—sebuah transaksi yang sakral dan serius. Di sini, etika kedekatan menjadi etika penggunaan yang sadar dan penuh terima kasih.
Kemudian, realitas yang lebih keras muncul dalam “Can of Stones” dan terutama “Skinning the Beaver” (Menguliti Berang-berang). “Can of Stones” mungkin merujuk pada koleksi benda-benda dari alam—batu, tulang, bulu—yang menjadi artefak hubungannya dengan dunia non-manusia. Ini adalah museum pribadi dari perjumpaan. Namun, “Skinning the Beaver” membawa kita ke momen yang paling menantang. Legler dengan detail sensoris yang tajam namun tidak sensasional, menggambarkan proses menguliti bangkai berang-berang yang ditemukan mati. Ini adalah tindakan yang sangat intim dengan kematian, sebuah upaya untuk menghormati hewan itu dengan menggunakan setiap bagiannya, mengubahnya dari bangkai menjadi sumber daya (daging, bulu) dan sekaligus menjadi pelajaran mendalam. Di sini, keberlanjutan bukan lagi konsep abstrak, tetapi praktik tubuh yang mentransformasi kematian menjadi kelangsungan hidup, dan penghormatan menjadi tindakan utilitarian. Ia menghadapi paradoks moral yang diungkapkan oleh penulis pemburu Barry Lopez: bahwa kita mungkin harus membunuh (atau dalam hal ini, memanfaatkan kematian) untuk benar-benar mencintai dan memahami sesuatu. Ini juga mengingatkan pada konsep “halalan thayyiban” dalam Islam—bahwa apa yang dikonsumsi harus tidak hanya halal (diperbolehkan), tetapi juga thayyib (baik, bersih, diperoleh dengan cara yang layak). Legler berusaha sekuat tenaga untuk membuat penggunaan berang-berang itu menjadi thayyib, sebuah tindakan penuh perhatian dan tanpa pemborosan.
Bagian ini ditutup dengan “Tracks” (Jejak). Setelah semua perjumpaan langsung—dengan arwah lumbung, dengan tetangga hewan, dengan pohon, dan dengan bangkai—pandangan Legler kini terlatih untuk membaca cerita-cerita yang tertulis di tanah. Jejak rusa, cakar rakun, lorong tikus di salju, semuanya menjadi teks yang hidup. Melacak jejak adalah bentuk melek huruf yang paling kuno; itu adalah cara membaca kisah-kisah komunitas yang ia tinggali tanpa pernah melihat para aktornya. Ini melambangkan tingkat kesadaran ekologis yang telah dicapainya: sebuah kepekaan untuk mengenali kehadiran dan narasi non-manusia di sekitarnya. Penyair Mary Oliver, yang dikutip Legler di tempat lain, mungkin berkata, “Jalan di hutan adalah doa yang dijawab dunia.”
Secara keseluruhan, bagian “With the Animals” ini adalah sebuah perjalanan menuju kedewasa-an ekologis yang mendalam. Dari keheningan magis lumbung tengah malam hingga keintiman darah dan bulu saat menguliti, Legler menunjukkan bahwa keberlanjutan yang sejati tumbuh dari kedekatan yang berani dengan realitas kehidupan alam—dalam segala keindah-an, kekejaman, dan utilitasnya. Ini bukan etika yang steril yang menjauhkan kita dari alam, melainkan etika yang memasukkan kita ke dalamnya, dengan semua tanggung jawab, ketidaknyamanan, dan kekaguman yang menyertainya. Untuk merajut kehidupan berkelanjut-an, kita harus belajar membaca jejak-jejak, mendengar lumbung, dan menghadapi, dengan tangan kita sendiri, biaya sebenarnya dari kelangsungan hidup kita—selalu dengan tujuan untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penghormatan. Inilah etika woodsqueer yang sesungguhnya.
Kekuatan, Kelembutan, dan Kekayaan yang Diredefinisi
Woodsqueer ini juga merajut tema-tema yang tampaknya berlawanan—kekuasaan (tyranny) dan kelembutan (tenderness), hukum dan organik, kekurangan dan kelimpahan—ke dalam sebuah refleksi yang kohesif tentang apa artinya memiliki kekuasaan, menciptakan keadilan, dan menemukan kekayaan sejati dalam kehidupan berkelanjutan. Di sini, Gretchen Legler bergerak melampaui pengamatan pribadi menuju komentar sosial dan politik yang halus namun tajam, yang selalu berakar pada realitas konkret hidup di tanahnya.
Bagian ini dibuka dan diikat oleh esai berulang “The Tyrant and the Apple Tree“, yang bertindak sebagai bingkai filosofis. Di sini, Legler menggunakan metafora yang kuat: sebuah pohon apel tua yang menghasilkan buah yang pahit dan tidak bisa dimakan. Tiran adalah kecenderungan dalam dirinya—dan dalam budaya kita—untuk memaksakan kehendak, mengontrol, dan mengekstraksi, bahkan dari alam. Ia merenungkan apakah harus “mem-perbaiki” pohon itu dengan mencangkokkan tunas yang manis, sehingga memaksakan produktivitasnya, atau membiarkannya menjadi apa adanya, sebuah monumen bagi ketahanan yang liar dan tidak berguna. Esai ini menanyakan inti dari etika ekologis: Apakah hubungan kita dengan alam adalah hubungan dominasi atau penerimaan? Bisakah kita merawat tanpa mengontrol? Ini adalah pertanyaan yang bergema dengan tulisan Aldo Leopold tentang “Etika Tanah,” yang menyerukan perubahan peran manusia dari penakluk menjadi anggota biasa dari komunitas biotik. Legler (2021) memihak pada keanggotaan biasa itu, mempertanyakan haknya untuk “mencangkokkan kehendaknya” pada pohon apel.
Rangkaian esai di antaranya mengisi bingkai ini dengan cerita konkret. “Telling Her” membahas komunikasi dan keintiman dengan pasangannya, Ruth. Dalam konteks isolasi, komunikasi menjadi jalur hidup, tetapi juga medan di mana tyrant bisa muncul—dalam asumsi, ketidak-patuhan, atau ketidaksabaran. Keberlanjutan sebuah hubungan, seperti keberlanjutan ekologis, bergantung pada mendengarkan yang dalam dan merespons dengan lembut. “North Woods Law” membawa unsur eksternal: aturan dan penegakan hukum di hutan belantara Maine. Di sini, Legler menghadapi “tiran” dalam bentuk struktur kekuasaan manusia—hukum kepemilik-an, peraturan perburuan, batas-batas yang diterapkan negara bagian.
Dia mengamati bagaimana hukum ini, meski dimaksudkan untuk melindungi, juga bisa menjadi alat pemisah dan kontrol. Hidup berkelanjutan berarti menavigasi hukum-hukum ini, meng-hormatinya tetapi juga mempertanyakannya ketika mereka bertentangan dengan pengetahuan lokal atau etika perawatan yang lebih dalam. Ini adalah pengakuan bahwa kebebasan di tanah liar selalu dibingkai oleh kontrak sosial.
“A Chicken in Every Pot” adalah kilas balik ke masa kecil dan komentar tentang gagasan Amerika tentang kelimpahan. Frase yang berasal dari kampanye Herbert Hoover ini menjanjikan kemak-muran material bagi semua. Legler membandingkannya dengan realitas hidupnya sekarang: kelimpahan yang diukur bukan oleh konsumsi massal, tetapi oleh swasembada dan pemenuh-an. Memiliki ayam sendiri yang menyediakan telur adalah bentuk kekayaan yang berbeda secara kualitatif dari memiliki ayam di setiap panci melalui sistem industri. Esai ini menolak tirani dari gagasan kelimpahan yang homogen dan ekstraktif, dan menggantikannya dengan kelimpahan yang terhubung, bertanggung jawab, dan lokal.
Setelah rangkaian ini, “Her Tenderness” muncul sebagai penangkal langsung bagi semua kekuatan tiran—baik di dalam diri, dalam hubungan, dalam hukum, atau dalam ekonomi.
Kelembutan di sini bukan kelemahan, melainkan kekuatan formatif. Itu adalah kelembutan yang merawat bibit, menghibur di saat ketakutan, dengan sabar memperbaiki pagar, dan dengan lembut memegang tubuh hewan yang mati. Inilah etika yang memandu tindakannya ketika etika kontrol gagal. Kelembutan adalah praktik perhatian yang memungkinkan sesuatu menjadi dirinya sendiri—baik itu pohon apel yang pahit, pasangan, atau lanskap. Filsuf feminis Carol Gilligan menulis tentang “etika kepedulian” (ethics of care) yang berpusat pada hubungan dan tanggapan. Legler menghidupkan etika ini di tanahnya, di mana kelembutan adalah disiplin dan sumber ketahanan.
Bagian ini ditutup dengan esai singkat namun kuat, “Wealthy”. Di sini, Legler mendefinisikan ulang kekayaan sama sekali. Kekayaan bukanlah akumulasi finansial, tetapi kelimpahan pengalaman, hubungan, dan kemandirian yang telah dia gambarkan: kayu bakar yang ditumpuk rapi, selai yang diawetkan di rak, pengetahuan tentang jejak, kehadiran Ruth, dan bahkan keberadaan pohon apel tua yang keras kepala. Kekayaan adalah kapasitas untuk melihat dan menghargai jaringan kehidupan yang menopangnya. Penyair Wendell Berry menulis, “Kekayaan sejati adalah memiliki semua yang Anda butuhkan.” Legler mencapai kekayaan ini bukan melalui kepemilikan, tetapi melalui perhatian dan partisipasi yang mendalam dalam kehidupan tempatnya. Dalam tradisi Islam, konsep “ghina al-nafs” (kekayaan jiwa) mengacu pada keadaan di mana jiwa merasa cukup dan kaya terlepas dari keadaan material, sebuah kondisi yang dicapai melalui syukur (shukr) dan kesadaran akan berkah Allah. Legler, dalam caranya sendiri yang sekuler dan terhubung dengan bumi, mencapai ghina al-nafs melalui praktik perhatiannya.
Secara keseluruhan, bagian ini adalah sebuah argumentasi yang elegan dan personal untuk sebuah revolusi nilai. Legler menunjukkan bahwa proyek membangun kehidupan berkelanjutan tak terhindarkan adalah proyek politik dan etika. Itu mengharuskan kita untuk menggulingkan tiran di dalam diri kita dan masyarakat kita—tiran yang ingin mengontrol, mengekstraksi, mengonsumsi, dan mendefinisikan kekayaan secara sempit. Sebagai gantinya, kita harus membina “kelembutan” sebagai kekuatan politik dan ekologis, dan menemukan kembali “kekayaan” sebagai keterikatan dan perhatian yang mendalam. Keberlanjutan, dalam bagian ini yang paling jelas, adalah jalan menuju pembebasan—dari kekuatan yang menghancurkan, dari keinginan yang tak terpuaskan, dan dari isolasi yang terputus. Itu adalah jalan untuk menjadi benar-benar kaya dengan menjadi benar-benar terhubung dan lembut.
Kemenangan, Kehilangan, dan Kelahiran Kembali di Kebun
Bagian terakhir dari Woodsqueer ini adalah sebuah simfoni yang merangkul siklus kehidupan sepenuhnya—dari bibit yang tumbuh hingga ayam jago yang mati, dari sperma yang membuahi hingga lagu duka yang tak sempat dinyanyikan. Berpusat pada metafora “Victory Garden” (Kebun Kemenangan) yang muncul berulang, bagian ini mengeksplorasi kemenangan seperti apa yang sesungguhnya diraih dalam kehidupan berkelanjutan. Bukan kemenangan atas alam atau musuh, melainkan kemenangan yang rapuh dan sementara atas kelupaan, keputusasaan, dan keterputusan—kemenangan untuk terus menanam, merawat, dan terhubung di tengah kepastian kehilangan.
Bagian ini dibuka dan diinterupsi oleh dua esai berjudul “Victory Garden”. Di sini, Legler merebut kembali istilah perang dunia itu untuk konteks damainya sendiri. Kebun kemenangan-nya bukan untuk mendukung upaya militer, tetapi untuk mempertahankan kemandirian, kesehatan, dan sukacita. Setiap baris sayuran yang ditanam adalah sebuah tindakan harapan, sebuah pernyataan bahwa masa depan ada dan akan dipupuk dengan tangan sendiri. Namun, kebun ini juga rentan—terhadap cuaca, hama, dan kelelahan. Kemenangannya adalah kemenangan yang setiap hari harus diperjuangkan kembali. Ini adalah praktik ketahanan yang rendah hati, sebagaimana diungkapkan oleh petani-filsuf Masando Fukuoka: “Tujuan dari pertanian bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi kesempurnaan dan pemuliaan manusia.”
Namun, di tengah upaya memupuk kehidupan, kematian tiba-tiba dengan kejam dalam “Death Comes for the Red Rooster”. Ayam jago merah, karakter yang mungkin penuh warna dalam kehidupan sehari-hari mereka, dibunuh oleh predator. Kehilangan ini bukan sekadar kehilangan ternak; ia adalah perjumpaan langsung dengan kekerasan yang mendasari rantai makanan dan kerentanan dari segala sesuatu yang dicintai. Legler tidak mendramatisir, tetapi ia mengakui duka itu. Kematian ayam jago menjadi peringatan bahwa kehidupan berkelanjutan bukanlah sebuah firdaus yang terlindungi, melainkan sebuah partisipasi penuh dalam drama kehidupan dan kematian alam.
Esai “The Gardener” mungkin merujuk pada Ruth atau pada dirinya sendiri dalam peran itu. Sang tukang kebun adalah sosok yang sabar, tekun, dan visioner—seseorang yang mampu melihat potensi dalam biji dan membayangkan kelimpahan di masa depan di tengah lumpur dan kerja keras masa kini. Sang tukang kebun mewujudkan etika perawatan yang berkelanjutan, yang diperlukan baik untuk tanaman maupun untuk hubungan manusia. Ini adalah kualitas yang dikagumi oleh penyair Maya Angelou: “Kita semua harus bertahan hidup di kebun. Beberapa dari kita adalah bunga, beberapa dari kita adalah duri, beberapa dari kita adalah tukang kebun.”
Kemudian, dalam sebuah esai yang judulnya mengejutkan dan penuh daya hidup, “The Sperm at the Door”, Legler memperkenalkan elemen kehidupan yang paling mendasar dan biologis. Apakah ini merujuk pada upaya pembuahan, pada kehadiran hewan, atau pada fakta mentah kesuburan itu sendiri, esai ini menegaskan bahwa kehidupan berkelanjutan itu bersifat jasmani dan reproduktif. Ini adalah tentang menciptakan dan mempertahankan kehidupan, dalam segala bentuknya yang berlumpur dan ajaib. Ini adalah pengingat bahwa semua proyek kita yang lebih tinggi—kebun kemenangan, rumah tangga—berakar pada realitas biologis yang sederhana dan perkasa.
Setelah kematian ayam jago, muncul esai yang penuh penyesalan dan empati yang mendalam: “I Wish I Had Been the One to Sing to Him“. Di sini, Legler merenungkan apakah ayam jago itu merasa ketakutan atau kesepian di saat-saat terakhirnya. Keinginannya untuk menyanyikan lagu penenang adalah ungkapan dari etika kepedulian yang paling radikal—keinginan untuk menghibur makhluk lain, bahkan yang sering dianggap rendah, dalam momen transisi yang paling menakutkan. Ini adalah perluasan dari komunitas moralnya yang melampaui manusia, mencerminkan pandangan filsuf Lynn White Jr. yang, meski mengkritik agama, juga menyeru-kan sebuah etika ekologis yang melihat manusia sebagai bagian dari komunitas alam yang lebih luas, di mana semua makhluk memiliki nilai intrinsik.
Bagian ini ditutup dengan “Foragers” (Para Pencari Makanan). Di sini, Legler membayangkan dirinya dan Ruth bukan hanya sebagai penanam, tetapi juga sebagai pengumpul—orang-orang yang dengan terampil membaca lanskap untuk menemukan hadiahnya yang liar: jamur, beri, tanaman liar. Mencari makan adalah bentuk pengetahuan yang mendalam, sebuah dialog dengan ekosistem yang mengakui kelimpahan di luar kebun yang kita kontrol. Ini adalah pengakuan bahwa keberlanjutan juga berarti menerima pemberian (grace) dari dunia liar, bukan hanya memetik hasil dari kerja kita sendiri. Dalam tradisi banyak budaya Pribumi, seperti yang tercermin dalam tulisan Robin Wall Kimmerer, mencari makan adalah praktik timbal balik dan rasa syukur. Ini adalah cara untuk menjadi “pribumi” terhadap sebuah tempat, sebuah jalan untuk menjadi woodsqueer yang sejati.
Secara keseluruhan, bagian ini adalah penutup yang sempurna untuk perjalanan Legler. Bagian ini menyatukan tema-tema utama buku: kerja, cinta, kehilangan, dan ketahanan. “Kebun Kemenangan” adalah metafora untuk seluruh proyeknya—sebuah upaya yang rapuh namun gigih untuk menumbuhkan kehidupan yang baik di sepetak tanah, di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah komunitas makhluk hidup. Kemenangan sejati, yang disarankan bagian ini, terletak bukan pada hasil panen yang melimpah atau kemandirian total, tetapi pada kapasitas untuk terus hadir—dengan penuh perhatian, kelembutan, dan keberanian—dalam pusaran kehidupan dan kematian yang tak henti-hentinya. Ini adalah kemenangan untuk tetap manusiawi dan terhubung di dunia yang lebih luas dari diri kita sendiri. Seperti sebuah kebun, kehidupan berkelanjutan tidak pernah benar-benar “selesai”; ia selalu menjadi pekerjaan yang sedang berlangsung, sebuah praktik harian menabur, merawat, kehilangan, meratapi, dan memanen—lagi dan lagi.
Pertimbangkanlah Biji Ek: Kelimpahan, Kematian, dan Kecukupan
Bagian penutup Woodsqueer ini adalah meditasi yang tenang dan mendalam tentang asal-usul, keinginan, pengorbanan, dan kesempurnaan yang ditemukan dalam ketidaksempurnaan. Berpusat pada gambar “Consider the Acorn” (Pertimbangkanlah Biji Ek) yang muncul dua kali, bagian ini mengundang kita untuk melihat potensi tak terbatas yang terkandung dalam hal-hal yang kecil dan tampaknya biasa. Seperti biji ek yang mengandung keseluruhan pohon ek raksasa, pengalaman sederhana dalam kehidupan berkelanjutan ini mengandung kebenaran yang lebih besar tentang kecukupan, siklus, dan makna.
Bagian ini dibuka dan dijalin oleh esai berulang “Consider the Acorn“. Di sini, Legler memusat-kan perhatiannya pada objek yang paling rendah hati: sebuah biji ek yang jatuh. Ini adalah latihan perhatian yang mendalam. Dia merenungkan potensinya yang luar biasa—energi yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi raksasa hutan, jaringan kehidupan yang akan didukungnya, kayunya yang akan menghangatkan rumah suatu hari nanti. Biji ek menjadi metafora untuk hidup berkelanjutan itu sendiri: sebuah investasi kecil di masa kini yang imbalannya hanya akan dipetik oleh generasi mendatang. Ini adalah tindakan iman dan kesabaran. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf stoik Marcus Aurelius dalam Meditations: “Pertimbangkanlah asal-usul segala sesuatu… dari perubahan inilah keindahan tercipta.” Legler menemukan keindahan dan pelajaran kosmik dalam biji kecil itu.
Esai “God Gives Us Our Desires” mengeksplorasi sumber dari dorongan batin yang membawa-nya ke kehidupan hutan ini. Apakah keinginan untuk hidup sederhana, terhubung dengan tanah, dan mencintai Ruth adalah sebuah panggilan? Legler merenungkan keinginan bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai kompas menuju pemenuhan. Dalam konteksnya, Tuhan mungkin bukan persona teistik, tetapi kekuatan hidup itu sendiri yang menanamkan keinginan untuk hidup selaras. Ini menggemakan pemikiran Sufi seperti Ibnu Arabi, yang berbicara tentang al-hubb (cinta) sebagai kekuatan penggerak kosmik dan manusiawi yang menarik kita menuju penyatuan. Keinginan Legler untuk hidup di kayu adalah bentuk cinta ini—tarikan menuju keutuhan dengan alam dan pasangannya.
Kemudian, dalam “Hunters”, Legler memasuki ranah ambivalensi moral lainnya. Pemburu (mungkin termasuk dirinya atau tetangganya) adalah bagian dari lanskap. Dia tidak menyema-tkan label moral, tetapi mengamati mereka sebagai partisipan dalam siklus kuno mengambil kehidupan untuk mempertahankan kehidupan. Ini melengkapi esai sebelumnya tentang menguliti berang-berang. Pemburu menghadapi paradoks itu secara langsung. Esai ini mengakui bahwa kehidupan berkelanjutan di pedesaan bukanlah vegetarianisme pastoral, tetapi melibatkan kontak yang sulit dengan kematian hewan. Keberlanjutan berarti mengakui tempat kita dalam rantai makanan, bukan menyangkalnya.
Kembali ke “Consider the Acorn”, pengulangan ini memperdalam meditasi. Sekarang biji ek juga menjadi simbol kerendahan hati dan ketahanan. Itu tahan terhadap musim dingin, menunggu kondisi yang tepat, dan tidak terburu-buru. Ini adalah kualitas yang diperlukan untuk hidup di hutan.
Puncak naratif dan emosional bagian ini mungkin ada di “Lesbian Wedding II”. Jika pernikahan pertama adalah tentang persiapan dan perayaan, pernikahan kedua ini kemungkinan adalah refleksi yang lebih dalam tentang makna dan komitmen itu sendiri. Di tengah semua kerja dan ketahanan fisik, esai ini menegaskan bahwa fondasi dari seluruh proyek keberlanjutan ini adalah cinta antara dua wanita. Pernikahan mereka adalah tindakan politik dan pribadi yang mengukuhkan bahwa kehidupan yang baik yang mereka bangun adalah juga kehidupan yang autentik secara seksual dan emosional. Ini adalah kemenangan atas keterasingan.
Esai “Perfect” (Sempurna) kemungkinan besar adalah sebuah ironi yang lembut. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan kerja keras, apa artinya “sempurna”? Legler mungkin berargumen bahwa kesempurnaan ditemukan bukan dalam kekurangan, tetapi dalam kecocokan yang tepat, dalam adaptasi, dalam kepenuhan pengalam-an yang nyata. Sebuah hari di mana kayu terbakar dengan baik, kebun disirami, dan cinta dirasakan adalah hari yang “sempurna”. Ini adalah kesempurnaan yang fana, duniawi, dan cukup. Hal ini mengingatkan pada konsep Jepang “wabi-sabi”—menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, kesementaraan, dan kesederhanaan.
Bagian ini, dan mungkin seluruh buku, ditutup dengan “Nima’s Death”. Kematian Nima (seekor hewan peliharaan? Seekor ternak? Seorang teman?) membawa siklus penuh. Setelah mere-nungkan biji ek (awal), keinginan, perburuan, dan kesempurnaan, kita tiba pada akhir yang tak terhindarkan. Kematian Nima adalah kehilangan yang personal dan nyata, sebuah duka yang membumikan semua filosofi. Legler menggambarkannya dengan kelembutan dan kejujuran yang sama seperti kematian ayam jago merah. Esai ini mengingatkan bahwa hidup berkelanjut-an berarti mengalami seluruh siklus, bukan hanya bagian yang produktif atau menyenangkan. Itu berarti menghadapi duka sebagai bagian integral dari cinta dan perhatian. Seperti kata penyair Kahlil Gibran dalam The Prophet: “Semakin dalam duka mengukir keberadaanmu, semakin banyak sukacita yang dapat kamu tampung.” Duka atas Nima adalah ukiran di hati Legler, yang memperdalam kapasitasnya untuk sukacita di kebun, di hutan, dan di rumahnya.
Secara keseluruhan, bagian penutup ini adalah sebuah kesimpulan yang bijaksana dan penuh kedamaian. Ini menegaskan bahwa crafting a sustainable rural life pada akhirnya adalah tentang mengolah perhatian. Memperhatikan biji ek, keinginan hati, pemburu di kejauhan, pasangan di samping kita, ketidaksempurnaan yang sempurna dari sebuah hari, dan duka yang datang dengan cinta. Dalam perhatian yang mendalam ini, Legler menemukan bahwa dia telah memiliki segala yang dia butuhkan. Kehidupan berkelanjutan bukanlah tentang mencapai sebuah keadaan akhir, tetapi tentang terus-menerus mempertimbangkan, merawat, dan menghargai—mulai dari hal terkecil seperti biji ek, hingga ikatan terbesar seperti cinta dan kehilangan. Buku ini ditutup bukan dengan sebuah deklarasi kemenangan, tetapi dengan sebuah penerimaan yang tenang dan dalam terhadap kelimpahan yang selalu hadir, jika saja kita mau memperhatikannya.
“Madu, Sayangku, Kekasih” – Keberlanjutan sebagai Praktik Tubuh dan Kelembutan
Bagian kecil namun padat ini dari Woodsqueer menembus inti dari apa yang sering kali hilang dalam wacana keberlanjutan: keberlanjutan sebagai pengalaman tubuh yang hidup dan sebagai ekspresi cinta sehari-hari yang lembut. Judul yang berulang, “Honey, Sweetheart, Darling” (Madu, Sayangku, Kekasih), bukanlah sekadar panggilan mesra, tetapi menjadi kerangka untuk memahami bagaimana kehidupan yang selaras dengan alam pada akhirnya dijalani melalui badan yang merasakan dan dalam hubungan yang dipupuk dengan kata-kata yang penuh kasih.
Bagian ini diapit oleh dua esai dengan judul yang sama, “Honey, Sweetheart, Darling“, menciptakan sebuah pembungkus kelembutan. Dalam esai ini, Legler kemungkinan besar menangkap momen-momen kecil percakapan dan panggilan sayang antara dirinya dan Ruth. Kata-kata ini adalah ritual hubungan, benang yang merajut kehidupan sehari-hari mereka bersama di tengah kesulitan dan kesunyian. Dalam konteks hidup di hutan yang menuntut ketangguhan fisik, panggilan sayang ini adalah pelumas sosial dan sumber kelembutan yang vital. Mereka mengubah rumah kayu yang sederhana menjadi sebuah rumah—sebuah tempat di mana kasih sayang diucapkan dan didengar. Ini mengingatkan pada konsep filsuf Iris Murdoch yang melihat perhatian (attention) sebagai bentuk cinta moral tertinggi; dengan memanggil satu sama lain dengan nama sayang, mereka mempraktikkan perhatian yang terus-menerus dan penuh kasih. Dalam tradisi tasawuf Islam, panggilan mesra juga dilihat sebagai cerminan dari sifat Al-Wadud (Maha Pengasih) Tuhan, yang memanifestasikan kasih sayang-Nya di antara makhluk-Nya.
Di jantung bagian ini terletak esai sentral: “Being in a Body” (Menjadi Sebuah Badan). Di sinilah Legler melakukan eksplorasi filosofis yang paling gamblang tentang pengalamannya. Kehidupan berkelanjutan di pedesaan bukanlah ide abstrak; ia adalah sebuah realitas yang dialami melalui kulit, otot, tulang, dan indra. Legler merinci bagaimana tubuhnya—yang dulu mungkin terbiasa dengan kenyamanan perkotaan dan kehidupan akademis—bertransformasi. Tubuh yang membelah kayu, menggali tanah, merasakan dingin yang menusuk, mencium aroma tanah basah dan kayu pinus, mendengar setiap derit rumah di malam hari.
Esai ini menyatakan bahwa keberlanjutan adalah sebuah praktik somatik. Kita tidak “menerap-kan” keberlanjutan dari luar; kita menghidupinya melalui tubuh kita. Dengan membawa air, memanen sayuran, atau merasakan kelelahan setelah seharian kerja, kita mengalami secara langsung ketergantungan kita pada energi, makanan, dan tempat tinggal. Legler (2021) menegaskan bahwa dalam tindakan-tindakan fisik inilah kita memahami, secara paling mendasar, apa artinya “cukup” dan apa artinya “bekerja.” Tubuh menjadi alat pengetahuan dan sekaligus ukuran etis. Pemikiran ini selaras dengan tradisi fenomenologi, seperti pemikir-an Maurice Merleau-Ponty, yang berpendapat bahwa kita memahami dunia pertama-tama dan terutama melalui “tubuh yang hidup” (le corps vécu). Keberlanjutan, bagi Legler, adalah feno-menologi yang dihayati—pengetahuan yang muncul dari melakukan, dari merasakan, dari menjadi sebuah badan di dalam sebuah lanskap.
Ketika kita kembali ke “Honey, Sweetheart, Darling” yang kedua, maknanya kini lebih dalam. Panggilan sayang itu tidak hanya mengungkapkan cinta, tetapi juga mengakui tubuh yang lelah, merayakan tubuh yang kuat, dan menghibur tubuh yang rentan dari pasangannya. Kata “Madu” mungkin merujuk pada kehangatan dan kemanisan yang mereka ciptakan bersama; “Sayangku” mungkin merujuk pada harga diri dan nilai masing-masing; “Kekasih” merujuk pada hasrat dan komitmen yang mendalam. Dalam konteks “Being in a Body,” kata-kata ini menjadi bahasa yang merawat tubuh yang lain. Mereka adalah suara yang menghangatkan ketika tubuh kedinginan, yang menenangkan ketika tubuh takut, yang menguatkan ketika tubuh lelah.
Sintesis Keseluruhan Bagian:
Bagian ini, meski singkat, menawarkan pandangan yang sangat penting. Ia menyatakan bahwa fondasi dari kehidupan berkelanjutan yang autentik adalah hubungan yang penuh kasih dengan tubuh kita sendiri dan tubuh orang lain. Sebelum kita bisa merawat bumi dengan benar, kita harus belajar merawat dan mendengarkan tubuh kita—sensasinya, batasannya, kebutuhannya. Dan kita harus memupuk hubungan yang mengatakan “Honey, Sweetheart, Darling” karena ketahanan emosional adalah prasyarat untuk ketahanan ekologis.
Keberlanjutan, dalam bagian ini, didefinisikan ulang. Bukan lagi hanya soal jejak karbon atau teknik berkebun organik, tetapi tentang bagaimana kita menghuni tubuh kita di dalam sebuah tempat, dan bagaimana kita menawarkan kelembutan kepada tubuh lain yang menghuni tempat itu bersama kita. Ini adalah etika yang sangat manusiawi dan membumi. Seperti yang mungkin dikatakan oleh penyair Mary Oliver, “Bukankah tubuh juga memiliki sesuatu untuk dikatakan?” Legler mendengarkan tubuhnya, dan melalui tubuh itu, dia mendengarkan bumi. Dan dari mulutnya, keluar kata-kata sayang yang merajut jaringan kehidupan kecil mereka menjadi sesuatu yang kuat, manis, dan berharga—seperti madu.
Dengan demikian, bagian ini adalah mikro-kosmos dari seluruh proyek Woodsqueer. Keber-lanjutan dimulai dan diakhiri dengan kelembutan—kelembutan terhadap tanah, terhadap hewan, terhadap kayu bakar, terhadap pasangan, dan terhadap diri sendiri yang berupa tubuh yang fana namun mampu merasakan begitu banyak hal. “Madu, Sayangku, Kekasih” adalah mantra untuk etika baru ini.
Catatan Akhir : Sebuah Peta Menuju Desa Masa Depan yang Manusiawi
Di tengah gemuruh krisis iklim dan teriknya kehidupan urban yang terfragmentasi, suara Gretchen Legler dalam Woodsqueer bagai embun di daun pagi—sunyi, jernih, dan menghidupkan. Buku ini bukan sekadar memoar perempuan kota yang “kembali ke alam”, melainkan sebuah catatan etnografis yang intim tentang bagaimana menjadi manusia kembali. Ia menawarkan bukan sekadar nostalgia romantis untuk pedesaan, melainkan sebuah prototipe hidup yang radikal: bahwa keberlanjutan ekologis harus berjalan seiring dengan keberlanjutan relasional dan spiritual. Dalam setiap bab tentang memotong kayu, merawat pagar, atau memanggil “Sayang”, terselip pertanyaan besar: bagaimana kita membangun kembali dunia dari skala yang manusiawi?
Pertama, tentang Lingkungan: Dari Kelangkaan ke Kelimpahan yang Diperhatikan.
Buku ini mengajak kita melihat lingkungan bukan sebagai “sumber daya” yang perlu dikelola dengan cemas—seperti yang dibongkar dalam Scarcity in the Modern World—tetapi sebagai jaringan kehidupan yang kita huni dan kita rawat. Kunci keberlanjutan bukanlah teknologi hijau termutakhir semata, melainkan perhatian mendalam (deep attention). Seperti Legler yang belajar “membaca” hutan melalui jejak dan suara, kita pun diajak untuk mengenali kembali pola mata angin di kampung halaman, siklus air di sungai dekat rumah, atau nama-nama burung yang bersarang di pepohonan kota. Keberlanjutan dimulai ketika kita berhenti menjadi turis di bumi sendiri dan menjadi penghuni yang peka. Dalam konteks Indonesia, ini berarti menghidupkan kembali kearifan lokal seperti sasi di Maluku atau hutan larangan di Sumatera, bukan sebagai folklor, tetapi sebagai sistem pengetahuan yang valid untuk mengelola kelimpahan tanpa merusak.
Kedua, tentang Desa: Dari Pencitraan ke Penghidupan yang Autentik.
Woodsqueer menghancurkan fantasi “hidup di desa” yang sering dieksploitasi dalam iklan pariwisata. Hidup di desa bagi Legler adalah kerja fisik yang melelahkan, kesepian yang mendalam, tetapi juga kepuasan menumbuhkan sesuatu dengan tangan sendiri. Inilah pelajaran penting: pembangunan desa tidak boleh terjebak pada proyek fisik semata (jalan, homestay, plang selfie), tetapi harus memulihkan “ekonomi penghidupan” yang utuh. Desa masa depan harus menjadi tempat di mana orang bisa menghidupi hidupnya, bukan sekadar mencari hidup. Ini berarti mendukung pertanian regeneratif yang menghasilkan pangan sekaligus memulihkan tanah, merangkum kerajinan tangan bukan sebagai cendera mata, tetapi sebagai jalur kemandirian, dan yang terpenting, menciptakan ruang bagi komunitas untuk bercerita, berduka, dan merayakan bersama—seperti pernikahan lesbian Legler yang sederhana namun penuh makna. Desa harus menjadi benteng terhadap individualisme, tempat di mana kata “gotong royong” kembali berdenyut sebagai darah kehidupan, bukan sekadar slogan program pemerintah.
Ketiga, tentang Hidup yang Manusiawi: Dari Efisiensi ke Kelembutan.
Inilah mungkin sumbangan terbesar Woodsqueer. Di dunia yang memuja efisiensi, produk-tivitas, dan kecepatan, Legler menawarkan etika kelembutan (ethics of tenderness) sebagai fondasi hidup manusiawi. Kelembutan itu terwujud dalam cara dia menguliti berang-berang dengan hormat, memanggil Ruth dengan kata-kata sayang, atau menerima pohon apel liar yang tak menghasilkan buah manis. Kelembutan adalah keberanian untuk peduli, merawat, dan tidak mengontrol. Dalam skala masyarakat, ini diterjemahkan sebagai keberpihakan pada yang rentan: petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan alam itu sendiri. Hidup yang manusiawi adalah hidup yang mengakui bahwa kita bagian dari jaringan yang saling tergantung, dan kewajiban moral terbesar kita adalah menjaga jaringan itu tetap utuh. Filsuf Indonesia, Mochtar Lubis, pernah menyerukan “Manusia Indonesia yang Utuh.” Woodsqueer memberi kita gambaran: manusia utuh itu adalah yang tidak terpisah antara pikiran dan tangan, antara diri dan komunitas, antara manusia dan alam.
Lalu, Apa yang Harus Kita Lakukan? Sebuah Seruan untuk Bertindak dari Skala Tubuh hingga Komunitas:
- Mulai dari Badan yang Menghuni: Seperti Legler yang “Being in a Body”, kita harus menyadari kembali tubuh kita sebagai alat untuk terhubung dengan dunia. Berjalan tanpa alas kaki di tanah, menanam sesuatu—pandannya di pot pun jadi—memasak dengan bahan lokal. Keberlanjutan adalah sensasi fisik sebelum menjadi konsep politik.
- Membangun “Kebun Kemenangan” di Mana Saja: “Victory Garden” Legler adalah metafora untuk oase kemandirian dan harapan. Di balkon kota, di pekarangan desa, atau di lahan komunitas, menanam pangan adalah aksi revolusioner. Ia memutus ketergantungan, mengembalikan pengetahuan tentang musim, dan menciptakan keamanan pangan yang nyata.
- Merawat Pagar, Membangun Jembatan: “Minding the Fence” mengajarkan bahwa batas (fisik, sosial, ekologis) perlu dirawat dengan jelas, tetapi bukan untuk mengisolasi. Di tingkat desa, ini berarti memperkuat kedaulatan atas wilayah adat dan sumber daya, sambil membangun aliansi dengan desa lain dan aktor urban untuk saling mendukung. Gerakan Slow Food atau Community Supported Agriculture (CSA) adalah contoh jembatan ini.
- Bercerita dengan Baru: Narasi dominan tentang kemajuan sering kali merendahkan kehidupan pedesaan dan sederhana. Kita perlu menulis, membuat film, dan mencipta seni yang merayakan kerumitan dan keindahan hidup yang terhubung dengan alam, seperti yang dilakukan Legler. Kisah-kisah ini adalah benih untuk imajinasi kolektif yang baru.
- Menerima Kematian sebagai Guru: “Death Comes for the Red Rooster” dan “Nima’s Death” mengingatkan bahwa hidup yang utuh menerima kematian sebagai bagian dari siklus. Dalam konteks ekologi, ini berarti berhenti menyangkal kematian sistem ekstraktif kita (polusi, kepunahan) dan berani “mengubur” model itu untuk memberi ruang bagi kehidupan baru yang regeneratif.
Menuju Keberlimpahan yang Woodsqueer
Masa depan yang kita butuhkan mungkin tidak harus persis seperti pondok kayu Legler di Maine. Tetapi semangat woodsqueer—keberanian untuk menjadi “miring” di mata dunia yang serba cepat demi hidup yang lebih dalam, lebih lambat, dan lebih penuh cinta—adalah kompas universal. Masa depan lingkungan, desa, dan kemanusiaan terletak pada kemampuan kita untuk memulihkan keintiman: keintiman dengan tanah, keintiman dengan komunitas, dan keintiman dengan diri sendiri yang fana.
Hikmah akhir dari buku ini adalah sebuah undangan: Marilah kita menjadi penghuni, bukan pengeksploitasi; perawat, bukan pengontrol; dan pencerita, bukan penghitung semata. Di tengau krisis yang membayang, jawabannya mungkin justru terletak pada keheningan untuk mendengar bisikan biji ek, pada kekuatan untuk membelah kayu bakar sendiri, dan pada kelembutan untuk memanggil sesama kita, “Honey, Sweetheart, Darling.” Karena dari sanalah, dari skala yang paling manusiawi, kita akan merajut kembali dunia yang retak.
Woodsqueer: Crafting a Sustainable Rural Life adalah sebuah hadiah bagi jiwa yang haus akan keaslian dan kedalaman. Ini adalah buku tentang menjadi manusia dengan segala kerumitannya di hadapan alam yang agung. Melalui prosa yang indah dan refleksi yang tajam, Gretchen Legler tidak memberikan panduan mudah, tetapi sebuah kesaksian yang hidup bahwa jalan menuju keberlanjutan adalah jalan menuju diri sendiri dan komunitas kehidupan yang lebih luas. Ia mengajak kita untuk, dalam kata-kata penyair Mary Oliver, “memasuki kengerian, tetap di situ, dan memberi nama pada semua burung hantu.” Di hutan Maine, Legler memberi nama pada ketakutan dan keindahannya, dan dalam proses itu, ia menemukan—dan membagikan—sebuah cetak biru untuk hidup yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga bermakna dan dijalani dengan penuh kesadaran.
Bandung, 16 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Daftar Pustaka
Angelou, M. (1993). Wouldn’t take nothing for my journey now. Random House.
Aurelius, M. (c. 161–180 AD). Meditations.
Bachelard, G. (1958). The poetics of space (The Orion Press, Trans.).
Berry, W. (1987). Home economics. North Point Press.
Berry, W. (2010). What are people for?: Essays. Counterpoint Press.
Fitria, L. (2020). Eco-theology in Islam: Conceptualizing rahmatan lil ‘alamin for environmental ethics [Artikel Konferensi]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/344434257_Eco-Theology_in_Islam_Conceptualizing_Rahmatan_lil_‘Alamin_for_Environmental_Ethics
Fukuoka, M. (1975). The one-straw revolution. New York Review Books.
Gibran, K. (1923). The prophet. Alfred A. Knopf.
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Harvard University Press.
Ibn ‘Arabi. (c. 13th Century). The bezels of wisdom (Fusus al-Hikam).
Kimmerer, R. W. (2013). Braiding sweetgrass: Indigenous wisdom, scientific knowledge and the teachings of plants. Milkweed Editions.
Legler, G. (2021). Woodsqueer: Crafting a sustainable rural life. Trinity University Press.
Leopold, A. (1949). A sand county almanac. Oxford University Press.
Lopez, B. H. (1978). Of wolves and men. Charles Scribner’s Sons.
Merleau-Ponty, M. (1945). Phenomenology of perception (C. Smith, Trans.). Routledge & Kegan Paul.
Murdoch, I. (1970). The sovereignty of good. Routledge & Kegan Paul.
Oliver, M. (1986). Dream work. Atlantic Monthly Press.
Oliver, M. (1992). New and selected poems. Beacon Press.
Rumi, J. a.-D. (Terj. oleh Barks, C.). (2004). The essential Rumi. HarperOne.
White Jr., L. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. Science, 155(3767), 1203–1207.