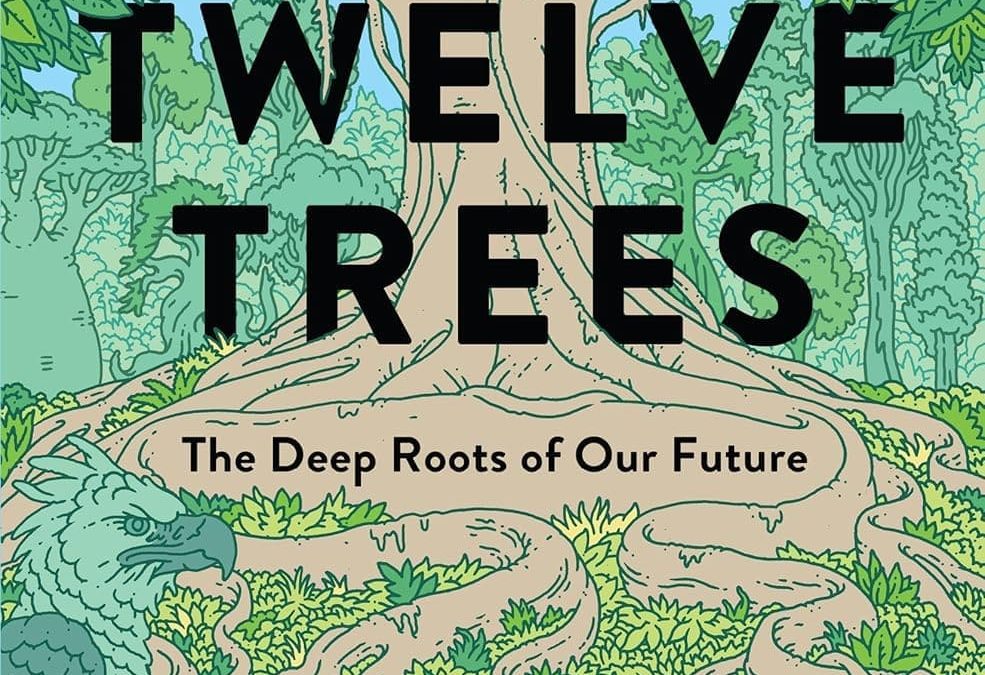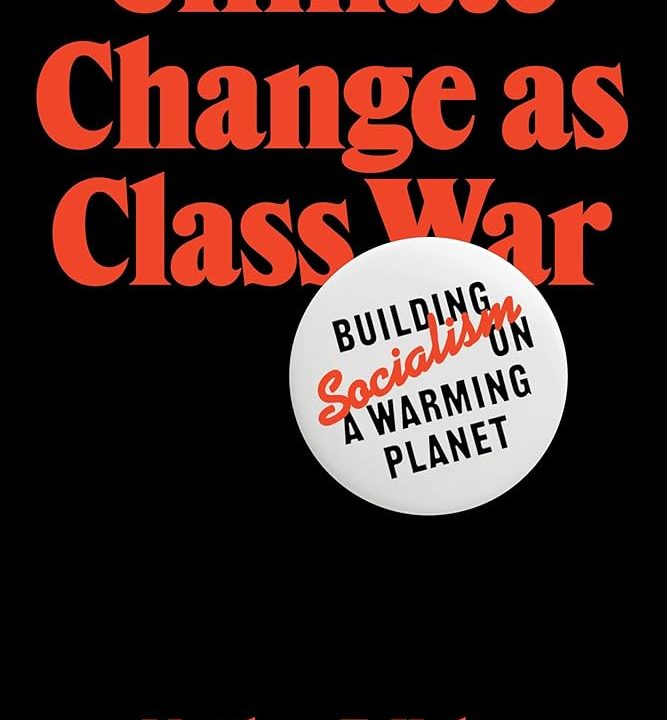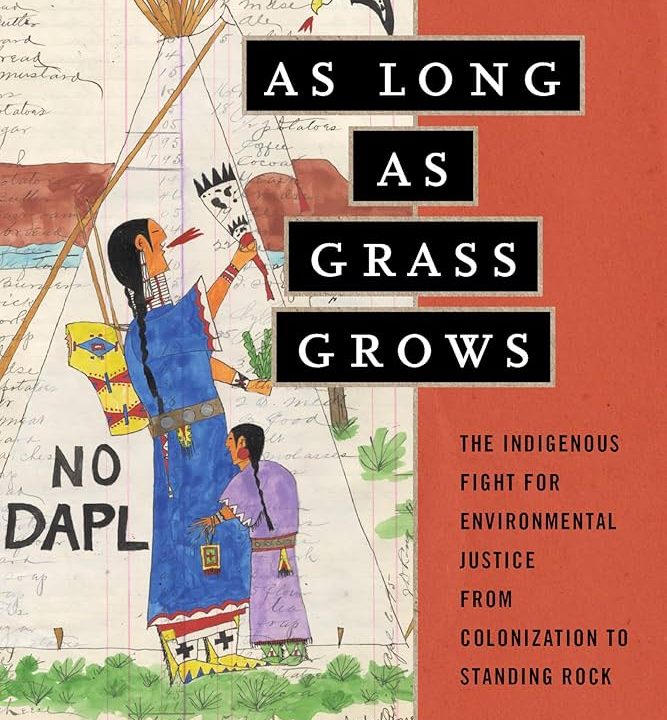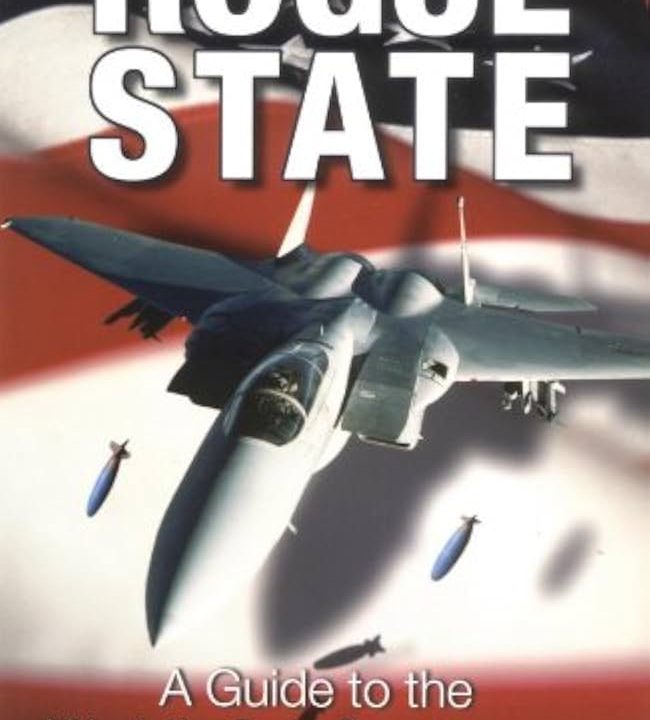Rubarubu #77
Twelve Trees:
Pohon-pohon yang Menyimpan Kisah
Tak ada buku tentang pohon yang ditulis dengan menarik daripada Twelve Trees: The Deep Roots of Our Future yang ditulis Daniel Lewis (2024). Buku ini mengisahkan duabelas pohon yang dijabarkan dengan menawan dalam 12 bab. Setiap bab menceritakan satu jenis pohon, ilmu di baliknya, tokoh/narasionalisasi seperti cerita pohon bristlecone, teknik ilmiah yang dipakai (dendrokronologi), ancaman kontemporer, dimensi etis-kultural, dan implikasi konservasi — semuanya disambungkan kembali ke tema besar buku: pohon sebagai arsip hidup dan barometer masa depan. “I think it is hard to miss the sensory elements of trees if you just take a moment to pay attention,” kata penulis pada suatu kesempatan. WLRN
Inilah dua belas pohon & kisah mereka. Buku ini menampilkan pohon-pohon seperti: Sequoia raksasa sebagai saksi waktu geologis dan simbol konservasi Amerika; Pohon Kauri Selandia Baru dan sejarah ekstraksi serta konflik dengan Māori; Pohon Baobab Afrika dan perannya dalam ekologi, budaya, dan ancaman perubahan iklim; Pohon Ara dan hubungan ko-evolusinya dengan tawon, sebagai cerita tentang saling ketergantungan ekologis; Pohon Eboni dan sejarah perdagangan kayu mewah yang gelap; Pohon Bristlecone Pine sebagai arsip iklim tertua di Bumi.
Lewis menggabungkan narasi sejarah sains yang ketat, reportase perjalanan yang hidup (mengunjungi hutan-hutan tua, berbicara dengan peneliti), dan refleksi filosofis tentang apa yang dapat kita pelajari dari ketahanan dan kerentanan pohon-pohon ini. Gayanya dapat diakses namun kaya, menghubungkan titik-titik antara biologi molekuler dan politik global.
Bagi Lewis yang Dosen dan Peneliti Senior di bidang Sejarah Sains di The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens di San Marino, California, salah satu lembaga penelitian dan kebun raya terkemuka di dunia, ini adalah sebuah petualangan yang diimpikan: “This arboreal adventure … the dozen species chronicled show how much the lives of trees are entwined with people and culture.” Bookshop Setiap pohon mempunyai peran penting dalam kehidupan di bumi: “A well-informed, staunch defense of trees’ capacity to multiply biodiversity and support life on Earth.” Kirkus Reviews
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kurator untuk Sejarah Sains dan Teknologi di The Smithsonian Institution’s National Museum of American History. Latar belakang kuratorial ini sangat membentuk karyanya: ia adalah seorang “arkeolog ide” yang terampil, yang menggali arsip, spesimen museum, dan catatan lapangan untuk menyusun kisah-kisah yang lebih besar.
Lewis menggambarkan pohon bristlecone pine sebagai “arsip hidup”— setiap cincin pertum-buhan menyimpan rekaman perubahan iklim ribuan tahun, menyatukan sains dan sejarah alam dalam satu tubuh kayu. Ia menekankan bahwa umur ribuan tahun bukan berarti kebal; kondisi ekstrem dan perubahan antropogenik tetap menimbulkan risiko bagi spesies yang tampak tangguh ini. Menarik perhatian pada dilema ilmiah-etis: ketika pohon sangat tua menjadi objek studi (contoh: Prometheus), pertanyaan muncul tentang hak pohon itu sendiri, akses penelitian, dan perlindungan spesimen bersejarah. Ia menegaskan bahwa konservasi harus memper-timbangkan waktu panjang (centuries, milenia) — pendekatan jangka pendek tidak cukup ketika menghadapi makhluk yang telah berusia jauh lebih lama daripada umat manusia modern.
Pada suatu sore yang dingin di punggung pegunungan Great Basin, seorang penjelajah berdiri di depan sebuah pohon; kulitnya seperti kertas tua, rantingnya seperti ukiran yang dibuat oleh ribuan musim dingin. Pohon itu — sebatang bristlecone pine — telah melihat lebih banyak abad daripada kebanyakan bangsa manusia, dan berdiri sebagai buku hidup tebal yang mencatat kisah iklim, api, dan ketekunan. Daniel Lewis membuka Twelve Trees dengan pengalaman semacam ini — perjumpaan intim dengan pohon-pohon yang bertahan, yang masing-masing menjadi fokus bab tersendiri. Gaya Lewis sering berupa kombinasi perjalanan lapang, catatan sejarah alam, dan refleksi pribadi: ia menulis bukan hanya untuk menerangkan dimensi biologis pohon-pohon itu, tetapi juga untuk menautkannya ke budaya, ekonomi, dan masa depan kolektif kita. Ringkasan ini mengikuti jejaknya: pohon sebagai subjek ilmiah sekaligus simbol moral. Perlego Bagi Lewis “Trees are our … custodians, forecasters, and predictors in an era of changing climates.” International Tree Foundation Kutipan tentang pohon sebagai “custodians … predictors” menggarisbawahi perspektif Lewis bahwa pohon bukan hanya objek alam, melainkan agen ekologis dan temporal yang memberikan sinyal tentang masa lalu dan masa depan iklim.
Secara keseluruhan buku dibagi menjadi dua nada utama: (a) kekaguman ilmiah — bagaimana pohon bekerja (air, karbon, umur panjang, simbiosis mikroba), dan (b) kisah antropologis-politik — bagaimana manusia telah membentuk nasib spesies melalui penebangan, perdagangan, ritual, dan konservasi. Lewis memilih 12 spesies yang mewakili rentang ekologi dan persoalan: dari Great Basin bristlecone pine (pohon yang sangat tua), coast redwood(raksasa karbon), Sophora toromiro di Rapa Nui yang nyaris hilang dari alam liar, hingga Central African forest ebony, sandalwood, longleaf pine, olive, baobab, dan penutupnya dengan ceiba yang megah. “The lifestyles of 12 magnificent trees conveyed through science and history.” Kirkus Reviews
Setiap bab memadukan sejarah alam, wawancara dengan ilmuwan dan penjaga hutan, serta diskusi tentang strategi konservasi modern (eksitu, pemuliaan, restorasi habitat). Struktur ini membuat buku bisa dibaca sebagai atlas biologi sekaligus manifesto etis untuk merawat pohon. Perlego+1 Melalui buku ini Lewis ingin menunjukkan bahwa “Trees … need to have their own rights, and be accorded their own dignity.” The Guardian Frasa “need to have their own rights … dignity” membawa dimensi etis: bahwa hubungan manusia dengan pohon perlu berubah dari eksploitasi menuju pengakuan nilai intrinsik — sejalan dengan gerakan “rights of nature” yang makin populer. Parafrase dari bab menunjukkan bahwa ilmu alam, sejarah, etika, dan konservasi saling terkait—memberi kerangka bagi pembaca untuk mengapresiasi bukan hanya keindahan pohon, tetapi urgensi melindungi mereka dalam konteks perubahan cepat.
Bab pertama dibuka seperti sebuah perjumpaan sakral: penulis berdiri di tengah lereng dingin Great Basin, menatap pohon-pohon yang tampak seperti arca kayu—kulitnya bercelah, tubuh-nya seperti menahan waktu sendiri. Lewis menggunakan bristlecone pine (Pinus longaeva) sebagai pembuka karena ia adalah contoh paling ekstrem dari apa arti “umur panjang” dalam dunia tumbuhan: beberapa individu hidup selama ribuan tahun, menyaksikan periode iklim, kebudayaan manusia dan kepunahan lokal. Lewis sadar bahwa “Every species of tree offers lessons to the world.” PublishersWeekly.com
Dengan gaya puitis namun faktual, Lewis mengajak pembaca membayangkan pohon sebagai buku, setiap cincin tahunan adalah huruf yang merekam musim, banjir, kemarau, serangan serangga, dan kadang trauma manusia (misalnya kebakaran atau penebangan). Ini bukan metafora kosong: ada metode ilmiah (dendrokronologi) yang benar-benar membaca “huruf” itu untuk merekonstruksi sejarah iklim jauh sebelum termometer modern. The Huntington+1
Filosofi Daniel Lewis berakar pada keyakinan bahwa sejarah alam dan sejarah manusia tidak dapat dipisahkan. Dia berargumen bahwa untuk membayangkan masa depan yang layak dihuni, kita harus memahami “akar yang dalam”—baik secara harfiah (sistem akar pohon) maupun metaforis (sejarah panjang interaksi kita dengan spesies lain). Dengan memusatkan perhatian pada individu pohon dan spesiesnya, dia menawarkan lensa yang kuat untuk memahami konsep abstrak seperti keanekaragaman hayati, keadilan lingkungan, dan waktu geologis. Lewis percaya “Trees are the heartbeat of the world.” Bookshop+1
Lewis menjelaskan lingkungan ekstrem tempat bristlecone hidup: ketinggian tinggi (biasanya di atas ~1.700 m), tanah nipis berlubang (dolomitic limestone), musim pendek dan angin kuat. Dalam kondisi itu pohon tumbuh sangat lambat—kadang diameter bertambah hanya sedikit dalam seabad—yang justru menjadi rahasianya: pertumbuhan lambat berarti jaringan kayu lebih padat, jamur perusak kurang efektif, dan cincin tahunan menjadi jejak perubahan iklim yang sangat jelas. Lewis memaparkan bagaimana ekosistem yang keras ini mengurangi kompetisi tanaman lain, memungkinkan beberapa pohon bertahan tunggal di lanskap terbuka; bentuknya yang memutar dan gnarled adalah adaptasi terhadap stress kronis, bukan tanda “kelemahan.” Ini bab tentang bagaimana ketahanan ekologis bekerja secara fisik dan simbolik. The Huntington+1
Dari sisi sains, bab ini adalah pengantar ringkas namun kuat tentang dendrokronologi — ilmu membaca cincin pohon untuk menafsirkan kondisi masa lalu. Lewis menjelaskan proses: cincin terang (earlywood) dan gelap (latewood) merekam kecepatan pertumbuhan setiap tahun; variasi ketebalan dan densitas dapat menunjukkan musim basah/kering, suhu musim panas, bahkan kejadian seperti kebakaran atau wabah hama. Peneliti memotong sampel inti menguna-kan bor khusus (increment borer) untuk mengambil inti tanpa membunuh pohon, lalu me-nyusun kurva kronologi panjang dengan menyesuaikan pola antar pohon. Di sini Lewis menekankan dua hal penting: pertama, bristlecone menyimpan catatan ribuan tahun yang berharga untuk memahami fluktuasi iklim pra-industri; kedua, interpretasi ilmiah adalah kerja hati-hati yang menggabungkan laboratorium, lapangan, dan arsip sejarah. The Huntington+1
Lewis tidak hanya bercerita tentang data — ia juga menyingkap intrik humanistik dalam cerita bristlecone: misalnya kontroversi seputar Prometheus (pohon tua yang dipotong pada 1960-an untuk penelitian, kemudian diketahui amat tua sehingga kasus itu menjadi skandal), dan ke-beradaan Methuselah (pohon yang sangat tua yang disimpan lokasi rahasianya untuk melin-dunginya dari vandalisme). Kisah-kisah ini menggarisbawahi dilema etis antara ilmu pengetahu-an (mendapat sampel untuk pengetahuan umum) dan konservasi (melindungi individu ber-sejarah itu sendiri). Lewis menggunakan contoh-contoh tersebut untuk menanya-kan: siapa yang berhak “membaca” arsip pohon, dan apa batas yang harus ditempat-kan pada praktik ilmiah agar tidak menghancurkan objek studi? Perdebatan Prometheus mengajarkan penting-nya transparansi ilmu dan pelibatan publik dalam keputusan konservasi. Wikipedia+1
Ancaman kontemporer menjadi fokus selanjutnya. Meski adaptif, bristlecone rentan terhadap beberapa ancaman baru dan tersamar: perubahan iklim (pergeseran batas elevasi, perubahan pola presipitasi), pencemaran udara (ozon, deposisi nitrogen), peningkatan kunjungan wisata (kerusakan trampling akar), serta kebijakan yang kurang sensitif terhadap pengelolaan api. Lewis menunjukkan paradoks: pohon yang telah melewati ribuan musim menghadapi ancaman yang berekskalasi dalam beberapa dekade — bukan karena mereka lemah, melainkan karena kondisi cepat berubah di skala global. Ia juga membahas bagaimana perubahan iklim dapat mengubah kompetisi spesies (spesies lain naik elevasi), memodifikasi kebakaran, dan membuka celah bagi patogen baru. Kesimpulan naratifnya: umur panjang pohon memberi kita konteks historis, tetapi bukan kekebalan. The Huntington+1
Lewis juga mengulas upaya-upaya konservasi khusus untuk pohon tua ini: perlindungan kawasan (mis. penetapan groves ke taman nasional atau cagar), kebijakan pembatasan kunjungan, serta teknik monitoring jangka panjang (sensor, fotografi repeat, dan survei ring sampling yang minim invasif). Bab ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berlapis: perlindungan habitat, manajemen rekreasi yang sensitif, pemantauan ilmiah, dan pendidikan publik. Lewis menyoroti contoh keberhasilan lokal di mana penjagaan komunitas, peneliti, dan pengelola taman bekerja sama untuk menjaga lokasi pohon-pohon berusia ribuan tahun sambil tetap memungkinkan pengalaman publik yang bertanggung jawab. Simon & Schuster+1
Pada dimensi budaya dan spiritual, bab pertama mengeksplorasi peran bristlecone sebagai simbol kontinuitas dan kesabaran—pokok percakapan tentang bagaimana manusia me-mandang waktu. Lewis mengaitkan pengalaman berdiri di samping pohon kuno dengan refleksi filosofis: pohon-pohon itu memaksa kita berpikir di luar kerangka hidup manusia singkat—mendorong etika intergenerasional. Di sini ia menyinggung pemikiran bahwa menjaga pohon tua adalah tindakan moral yang melampaui utilitarianisme: bukan sekadar menyimpan data atau kayu, melainkan merawat kenangan planet yang lebih tua dari bangsa manapun. Ia juga mengutip penulis dan pemikir alam yang menegaskan hubungan batin tersebut — gagasan bahwa hubungan manusia-pohon membuka potensi transformasi etika yang relevan di era krisis ekologi. The Huntington+1
Lewis menfokuskan dedikasinya pada sejarah Ilmu Pengetahuan Alam, Sejarah Lingkungan, Hubungan Manusia-Alam, Ilmu Pohon (Dendrologi), Komunikasi Sains. Buku ini ditulis dengan gaya prosa yang elegan dan jelas, narasi yang didorong oleh penelitian mendalam, kemampuan untuk menghubungkan detail ilmiah dengan tema humanis yang luas. Twelve Trees telah engukuhkan pentingnya perspektif sejarah dalam wacana lingkungan kontemporer dan men-ciptakan model baru untuk penulisan sains populer yang sekaligus mendalam secara ilmiah, naratif yang menarik, dan mendesak secara moral.
Terakhir, Lewis menarik garis ke depan: apa arti bab bristlecone bagi kebijakan konservasi dan bagi masyarakat yang bergulat dengan perubahan iklim? Pesannya ganda dan praktis: (1) pohon sebagai arsip menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pemantauan ilmiah jangka panjang—data historis adalah alat penting untuk adaptasi; (2) perlindungan pohon tua memerlukan kombinasi ilmu, hukum konservasi, dan etika publik—kita perlu kebijakan yang menghargai nilai intrinsik dan ilmiah; (3) pengalaman estetik dan spiritual dengan pohon-pohon tua bisa menjadi basis mobilisasi publik untuk perlindungan habitat. Bagi pembaca di negara tropis seperti Indonesia, pelajaran implisitnya adalah sama: hutan tua, mangrove purba, atau pohon sakral lokal adalah arsip—mereka mengandung informasi ekologis dan budaya yang tak ternilai; melindungi mereka menuntut kolaborasi ilmiah, lokal, dan kebijakan yang menyadari hubungan panjang waktu. The Huntington+1
Mari kita mulai penjelajahan pada sebagian pohon-pohon yang telah dituliskan dengan menawan oleh Lewis, seorang sejarawan sains, penulis sains populer, dan kurator Amerika yang karyanya berfokus pada persimpangan mendalam antara manusia, alam, dan ilmu pengetahu-an. Sebagai ahli waris tradisi penulis naturalis seperti John Muir dan Rachel Carson, serta sejarawan sains seperti Stephen Jay Gould, Lewis membawa kedalaman akademis dan prosa yang jernih untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman kita tentang alam membentuk masa depan kita. Reputasinya sebagai penulis yang menggugah pikiran diteguhkan dengan terbitnya buku “Twelve Trees: The Deep Roots of Our Future,” sebuah karya yang menempatkan pohon sebagai pusat narasi sejarah planet dan takdir manusia.
Bab pembuka (Chapter 1 — A Book Older Than God: The Great Basin Bristlecone Pine) berfungsi sebagai manifesto umur dan ketahanan. Lewis menjelaskan bagaimana Pinus longaeva hidup di lingkungan ekstrim: tanah tipis, sinar UV kuat, musim dingin panjang. Umurnya—beberapa individu berumur ribuan tahun—menjadikannya arsip biologis: cincin tahunannya menyimpan catatan iklim prasejarah. Lewis menggabungkan observasi lapang (gemerincing angin, tekstur kayu) dengan sains dendrokronologi untuk menunjukkan bahwa pohon-pohon ini bukan sekadar keajaiban; mereka adalah sumber data untuk memahami perubahan iklim lama dan modern. Namun, ujar Lewis, umur panjang bukan jaminan: perubah-an iklim, patogen, dan kegiatan manusia (rekreasi, pengelolaan api) menempatkan bahkan pohon-pohon purba ini dalam kondisi rapuh. Bab ini menanamkan pesan pusat buku: menghormati pohon berarti menghormati sejarah panjang planet ini. Perlego+1
Sementara itu Earth Work: The Nearly Lost Tree of Rapa Nui (Sophora toromiro)–Chapter 3 adalah salah satu bab paling memilukan: toromiro adalah pohon pulau (Easter Island) yang pada akhirnya punah di alam karena tekanan manusia (penggundulan, penggembalaan) — namun bertahan dalam koleksi botani di Eropa. Lewis menelusuri jejak botani dan etnohistory: bagaimana budaya Rapa Nui pernah hidup bersama pohon ini, dan bagaimana kehilangan vegetasi di pulau itu berkaitan erat dengan transformasi sosial-lingkungan. Bab ini meng-eksplorasi etika ex situ (menyimpan spesies di kebun raya) versus in situ (restorasi habitat) dan pertanyaan berat: apa arti “kehidupan” ketika sebuah spesies hidup hanya di dalam rumah kaca atau kebun raya? Lewis juga menyoroti proyek-proyek restorasi yang melibatkan keturunan lokal, dan bagaimana ingatan kolektif dan sains harus bersinergi jika ‘kebangkitan’ spesies di alam liar ingin berhasil. Bab ini menjadi pengingat keras bahwa kehilangan biologis sering terkait dengan kerusakan sosial. Perlego+1
Di bagian penutup naratif sebelum afterword, Lewis menaiki kanopi Amazon untuk menemu-kan Ceiba pentandra — pohon yang sering dianggap suci dalam tradisi Amerika Latin dan Karibia. Ceiba bukan hanya tinggi; ia menyokong komunitas ekologis: epifit, mamalia, burung, serangga. Di bab 12 — Tall Stories: The Mighty Ceiba Tree ini Lewis membahas fungsi ekologis (penyimpanan air, penyangga biodiversitas), peran budaya (ritual, mitos), dan ancaman (deforestasi komersial, perubahan iklim). Ia menggunakan kisah individu — mendaki ke dahan, mendengar suara hutan — untuk menjelaskan kenapa kehilangan pohon-pohon seperti ceiba berarti melemahkan struktur komunitas hutan yang lebih luas. Bab ini juga menyinggung proyek restorasi besar dan pendekatan lokal yang menggabungkan pengetahuan tradisional dengan sains modern. Perlego+1
Bab keenam Twelve Trees dibuka seperti sebuah ziarah pelan ke dalam aroma—aroma kayu cendana India Timur (Santalum album) yang telah berabad-abad melintasi tubuh manusia, ritual keagamaan, perdagangan global, dan imajinasi penyembuhan. Daniel Lewis tidak memperlakukan cendana sebagai sekadar spesies botani, melainkan sebagai makhluk lintas dunia: antara hutan dan kuil, antara pasar dan laboratorium, antara pengobatan rakyat dan sains modern.
Sejak awal, Lewis menempatkan cendana sebagai pohon yang hidup lebih lama dalam budaya manusia daripada dalam hutan alaminya sendiri. Kayunya telah dibakar sebagai dupa di kuil Hindu dan Buddha, dioleskan sebagai pasta suci di dahi para peziarah, direbus dalam ramuan Ayurveda, dan disuling menjadi minyak esensial yang dipercaya menenangkan pikiran, meredakan peradangan, dan membuka jalan menuju kejernihan batin. Dalam tradisi ini, penyembuhan tidak pernah semata-mata biologis; ia adalah peristiwa kosmologis—hubungan antara tubuh, roh, dan alam semesta. Lewis menulis seolah mengingatkan pembaca bahwa sebelum ada istilah “farmakologi,” manusia telah lama membaca pohon sebagai teks pengobatan.
Namun kisah cendana bukan hanya kisah kesakralan. Ia juga kisah eksploitasi. Karena aromanya yang tak tergantikan dan nilainya yang tinggi, cendana India Timur menjadi salah satu pohon paling diburu di dunia. Lewis menggambarkan bagaimana kolonialisme Inggris mempercepat ekstraksi tanpa batas, mengubah pohon yang tumbuh perlahan—bahkan parasitik, bergantung pada akar pohon lain—menjadi komoditas yang ditebang lebih cepat daripada kemampuannya untuk pulih. Hutan-hutan Karnataka dan Tamil Nadu menyusut, dan negara turun tangan, mengklaim kepemilikan atas setiap pohon cendana, bahkan yang tumbuh di tanah pribadi. Ironisnya, perlindungan negara justru melahirkan pasar gelap, pembalakan ilegal, dan kekerasan—menjadikan cendana pohon yang dijaga sekaligus dikejar.
Lewis dengan halus menunjukkan paradoks besar: semakin cendana disakralkan, semakin ia dirusak; semakin ia dicari untuk menyembuhkan, semakin ia mendekati kepunahan. Di titik inilah bab ini berbelok ke dunia sains modern. Kita diajak masuk ke laboratorium, tempat para ahli kimia, botanis, dan farmakolog berusaha menerjemahkan pengetahuan tradisional ke dalam bahasa molekul. Minyak cendana dianalisis, senyawa-senyawanya diisolasi, diuji terhadap bakteri, sel kanker, dan sistem saraf. Apa yang dahulu diyakini melalui pengalaman dan ritual kini dicoba dibuktikan melalui uji klinis dan statistik.
Namun Lewis tidak pernah menempatkan sains sebagai penakluk tradisi. Sebaliknya, ia memperlihatkan ketegangan yang rapuh dan produktif antara keduanya. Pengobatan rakyat bukan sekadar “pra-ilmiah,” melainkan arsip panjang observasi manusia terhadap alam. Sains modern, dalam versi terbaiknya, adalah upaya mendengarkan ulang arsip itu—dengan alat baru, dengan kerendahan hati baru. Di sini, cendana menjadi jembatan: antara dukun dan doktor, antara kitab kuno dan jurnal ilmiah, antara intuisi dan verifikasi.
Bab ini juga menyinggung upaya-upaya kontemporer untuk menyelamatkan cendana dari nasib yang ia ciptakan sendiri. Program budidaya, penanaman kembali, dan bahkan rekayasa genetika muncul sebagai jalan keluar yang ambigu—harapan sekaligus risiko. Lewis menulis tentang perkebunan cendana di Australia dan Pasifik, tentang klon-klon yang tumbuh lebih cepat, tentang minyak sintetis yang berusaha meniru aroma alam. Pertanyaannya menggantung: apakah kita sedang menyelamatkan cendana, atau hanya menyelamatkan aroma yang kita inginkan darinya?
Di balik semua itu, Making Folk Medicine Modern adalah meditasi tentang cara manusia memberi nilai. Cendana bernilai karena baunya, karena khasiatnya, karena kisah-kisah yang kita ceritakan tentangnya. Tetapi nilai itu juga yang membuatnya rapuh. Lewis seolah mengajak pembaca merenung: apa yang terjadi ketika pohon tidak lagi dihormati sebagai makhluk hidup, melainkan sebagai bahan aktif, komoditas, atau paten?
Bab ini berakhir bukan dengan kesimpulan tegas, melainkan dengan kesadaran yang sunyi. Bahwa masa depan cendana—seperti masa depan banyak pohon lain—bergantung pada kemampuan manusia untuk menjahit kembali yang telah terbelah: tradisi dan sains, ekonomi dan etika, penyembuhan dan keberlanjutan. Cendana, dengan pertumbuhannya yang lambat dan aromanya yang bertahan lama, mengajarkan kesabaran pada spesies yang serba tergesa. Ia mengingatkan bahwa tidak semua yang berharga dapat dipercepat, dan tidak semua penyembuhan datang tanpa merawat sumbernya.
Dalam tangan Daniel Lewis, cendana India Timur bukan sekadar contoh etnobotani. Ia menjadi simbol jalan panjang manusia dalam belajar—dan sering kali gagal—hidup berdampingan dengan pengetahuan yang lebih tua dari dirinya sendiri.
Anugerah dari Lembah Rapuh
“The olive tree is surely the richest gift of Heaven.”
—Thomas Jefferson, Papers of Thomas Jefferson.
Bab tentang pohon zaitun dalam Twelve Trees bergerak seperti cahaya sore di lereng Mediterania: tampak tenang, berkilau lembut, tetapi menyimpan sejarah panjang tentang ketahanan, konflik, dan ketergantungan manusia pada alam. Daniel Lewis membuka kisah ini dengan zaitun sebagai pohon yang hampir mustahil dipisahkan dari peradaban manusia. Ia bukan sekadar tanaman pertanian; ia adalah arsip hidup tentang bagaimana manusia belajar menetap, membangun budaya, dan mengubah lanskap demi kelangsungan hidup.
Zaitun tumbuh di tanah yang sulit—lereng berbatu, tanah kering, wilayah yang sering dianggap terlalu keras bagi pertanian lain. Meskipun Thomas Jefferson menyebutnya berkah dari surga. Di sinilah Lewis melihat metafora sentral bab ini: peradaban tumbuh di tempat yang rapuh, dan sering kali justru mempercepat kerapuhan itu. Pohon zaitun, dengan akarnya yang men-cengkeram tanah curam dan batangnya yang berlekuk seperti tubuh tua yang menyimpan ingatan, menjadi saksi ribuan tahun eksperimen manusia dalam bertahan hidup di batas kemampuan alam.
Lewis menelusuri sejarah zaitun dari domestikasi awalnya di Timur Tengah hingga penyebaran-nya ke seluruh Mediterania, mengikuti jalur perdagangan, penaklukan, dan agama. Minyak zaitun menjadi bahan bakar lampu, medium sakramen, simbol kemurnian, komoditas per-dagangan, dan dasar pola makan yang kini dipuji sebagai “diet Mediterania.” Dalam setiap fase sejarah, zaitun tidak pernah netral. Ia selalu terjalin dengan kekuasaan, dengan siapa yang memiliki tanah, siapa yang memeras buahnya, dan siapa yang menikmati hasilnya.
Namun inti bab ini bukanlah romantisasi. Slippery Slopes berbicara tentang kemiringan—secara harfiah dan kiasan. Lewis menggambarkan bagaimana penanaman zaitun secara masif di lereng -lereng curam, sering kali tanpa praktik konservasi tanah yang memadai, berkontribusi pada erosi yang parah. Teras-teras batu yang dahulu dibangun dengan kerja kolektif perlahan runtuh ketika pertanian beralih dari subsisten ke industri. Tanah yang selama berabad-abad ditahan oleh akar zaitun dan dinding batu mulai meluncur turun, membawa serta kesuburan yang tidak tergantikan.
Di sinilah paradoks zaitun muncul dengan tajam. Pohon yang dikenal sebagai simbol perdamai-an dan keberlanjutan justru menjadi bagian dari sistem pertanian yang, dalam skala industri, dapat merusak lanskap. Lewis menulis tentang kebun zaitun modern yang padat, dipanen dengan mesin, disiram secara intensif, dan dirancang untuk efisiensi jangka pendek. Minyak zaitun, yang dipasarkan sebagai produk alami dan sehat, lahir dari proses yang sering kali mengabaikan kesehatan tanah, air, dan keanekaragaman hayati.
Lewis juga membawa pembaca ke dalam dunia kimia dan sensorik minyak zaitun—tentang rasa pahit dan pedas yang menandakan polifenol, tentang oksidasi yang merusak kualitas, tentang perbedaan antara minyak segar dan minyak yang telah kehilangan hidupnya. Tetapi pengetahu-an ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan ekonomi global, dengan label dan sertifikasi, dengan pasar yang sering kali lebih menghargai citra daripada substansi. Seperti pohonnya, minyak zaitun hidup di persimpangan antara keaslian dan manipulasi.
Bab ini juga menyentuh dimensi politik zaitun, terutama di wilayah-wilayah konflik di Mediterania timur. Pohon zaitun menjadi penanda kepemilikan tanah, simbol identitas, dan sasaran kekerasan. Menebang atau merusak pohon zaitun bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga tindakan simbolik—upaya menghapus masa depan dengan menghancurkan sesuatu yang membutuhkan puluhan tahun untuk berbuah penuh. Dalam konteks ini, Lewis menunjuk-kan bagaimana pohon dapat menjadi korban langsung dari ketegangan manusia, sekaligus alat perlawanan yang sunyi.
Namun seperti bab-bab lain dalam Twelve Trees, Slippery Slopes tidak berhenti pada diagnosis. Lewis menulis tentang para petani, ilmuwan tanah, dan aktivis yang berusaha mengembalikan kebijaksanaan lama: terasering yang diperbaiki, penanaman campuran, penghormatan pada ritme pohon yang lambat. Ada pengakuan bahwa zaitun tidak bisa dipaksa mengikuti logika percepatan modern tanpa biaya ekologis yang besar. Pohon ini menuntut kesabaran—dan mungkin mengajarkan kembali apa arti kesabaran itu.
Pada akhirnya, pohon zaitun dalam bab ini berdiri sebagai cermin bagi peradaban. Ia me-nunjukkan bagaimana sesuatu yang tampak abadi sebenarnya bergantung pada pilihan-pilihan kecil yang diulang selama berabad-abad. Lereng yang licin bukan hanya fenomena geologis, tetapi juga moral: sejauh mana manusia bersedia mengorbankan masa depan demi kenyaman-an hari ini. Dalam gaya khasnya, Daniel Lewis meninggalkan pembaca dengan kesadaran bahwa zaitun akan terus tumbuh—jika diberi kesempatan. Pertanyaannya adalah apakah manusia bersedia belajar dari pohon yang telah menemani mereka sejak awal sejarah, atau terus meluncur di lereng yang mereka ciptakan sendiri.
“Aku menjelaskan kepada Pangeran Kecil bahwa baobab bukanlah semak kecil, melainkan—sebaliknya—pohon-pohon sebesar kastel; dan bahkan jika ia membawa pergi satu kawanan gajah sekalipun, kawanan itu tidak akan sanggup menghabiskan satu baobab pun.”
—Antoine de Saint-Exupéry, Pangeran Kecil.
Jika pohon-pohon lain dalam Twelve Trees berbicara dengan suara sejarah dan perdagangan, maka baobab Afrika berbicara dengan suara waktu itu sendiri. Dalam Elephantine, Daniel Lewis mendekati baobab bukan sebagai objek botani semata, melainkan sebagai makhluk raksasa yang hidup di ambang antara alam dan mitos—pohon yang ukurannya menantang imajinasi manusia dan usianya mengguncang cara kita memahami kehidupan.
Baobab muncul dalam lanskap Afrika seperti tubuh purba yang tertanam di bumi. Batangnya menggelembung, seolah menyimpan air, ingatan, dan cerita dalam satu rongga raksasa. Lewis menggambarkannya sebagai pohon yang tampak terbalik, dengan cabang-cabang yang me-nyerupai akar menjulur ke langit—sebuah citra yang dalam banyak kosmologi Afrika dianggap sebagai hasil hukuman para dewa atau keisengan kosmik. Tetapi bagi sains, bentuk itu adalah strategi bertahan hidup yang brilian: adaptasi terhadap iklim ekstrem, kekeringan panjang, dan ketidakpastian ekologis.
Lewis menelusuri baobab sebagai organisme yang menantang definisi usia. Tidak seperti pohon lain yang membentuk cincin tahunan yang rapi, baobab tumbuh dengan cara yang mem-bingungkan para dendrokronolog. Batangnya berongga, jaringan kayunya lunak, dan pertum-buhannya tidak mengikuti pola yang mudah dibaca. Untuk mengetahui umurnya, para ilmuwan harus menggunakan penanggalan radiokarbon, dan hasilnya mengejutkan: beberapa baobab berusia lebih dari seribu, bahkan dua ribu tahun. Mereka bukan saksi satu peradaban, tetapi banyak peradaban yang datang dan pergi.
Dalam bab ini, baobab hadir sebagai infrastruktur hidup. Lewis menulis tentang bagaimana pohon ini menyediakan air yang tersimpan dalam batangnya, buah yang kaya vitamin C, daun untuk sayuran, serat untuk tali, dan ruang berlindung bagi manusia dan hewan. Baobab adalah apotek, gudang, rumah, dan penanda geografis. Di banyak komunitas Afrika, pohon ini menjadi pusat kehidupan sosial—tempat musyawarah, ritual, dan cerita diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Namun Elephantine juga adalah kisah tentang kerentanan. Lewis dengan hati-hati menggeser nada dari kekaguman ke kecemasan ketika membahas kematian misterius baobab-baobab tertua di Afrika bagian selatan. Pohon-pohon yang telah bertahan selama ribuan tahun tiba-tiba roboh dalam beberapa dekade terakhir. Tidak ditebang, tidak dibakar—mereka runtuh dari dalam. Para ilmuwan menduga perubahan iklim sebagai penyebab utama: suhu yang meningkat, pola hujan yang berubah, tekanan air yang tidak lagi seimbang. Baobab, simbol ketahanan ekstrem, ternyata juga memiliki batas.
Lewis tidak memperlakukan runtuhnya baobab sebagai tragedi yang terisolasi. Ia menem-patkannya dalam konteks lebih luas tentang bagaimana perubahan iklim menguji organisme yang selama ini kita anggap hampir abadi. Ketika baobab tumbang, yang runtuh bukan hanya satu pohon, tetapi sebuah penanda waktu, sebuah arsip hidup tentang bagaimana bumi pernah bekerja. Kehilangan itu bersifat ekologis sekaligus kultural.
Dalam gaya reflektifnya, Lewis menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan baobab tidak pernah bersifat eksploitatif semata—tetapi kini berada dalam ketegangan baru. Komersialisasi buah baobab sebagai “superfood” global membawa peluang ekonomi, tetapi juga risiko baru: panen berlebihan, perubahan kepemilikan, dan tekanan pada ekosistem lokal. Pohon yang selama ini hidup dalam ritme komunitas kini ditarik ke dalam logika pasar global yang serba cepat.
Namun bab ini tidak ditutup dengan keputusasaan. Lewis menulis tentang pengetahuan lokal yang tetap bertahan, tentang rasa hormat yang masih diberikan pada baobab sebagai makhluk hidup yang lebih tua dari ingatan kolektif. Ada kesadaran bahwa pohon ini tidak bisa diperlakukan seperti komoditas biasa. Ia menuntut hubungan yang bersifat etis, jangka panjang, dan rendah hati—hubungan yang mengakui bahwa manusia adalah pendatang baru dalam dunia yang telah lama dihuni baobab.
Pada akhirnya, Elephantine menjadikan baobab sebagai guru yang diam. Pohon ini mengajarkan tentang skala—bahwa kehidupan tidak selalu bergerak cepat, bahwa makna bisa terkumpul perlahan selama ribuan tahun. Ia juga mengingatkan bahwa bahkan raksasa pun bisa jatuh ketika sistem pendukungnya terguncang. Dalam baobab, Daniel Lewis menemukan simbol paling kuat dalam bukunya: bahwa masa depan tidak akan diselamatkan oleh kekuatan, melainkan oleh pemahaman, kesabaran, dan kemampuan manusia untuk hidup selaras dengan waktu alam, bukan melawannya.
Mengakhiri petualangannya dengan pepohonan Lewis menulis afterword (kata penutup) dengan mengawalinya sebuah kutipan puisi:
Lalu sebuah suara—seperti angin yang
melolong jauh di dalam dedaunan
—berkata:
Aku akan menceritakan kepadamu
sebuah kisah tentang benih.
—Mary Oliver, “Banyan,” Poetry magazine, 1985
Pada tahun 1958, di puncak Mauna Kea, di Pulau Besar Hawai‘i, seorang ahli kimia lingkungan bernama Charles David Keeling mulai mencatat akumulasi karbon dioksida di atmosfer, Lewis membuka lembar penutupnya. Ketika data itu digambarkan dalam grafik, kurvanya bergerak naik ke kanan—bertangga, tegas, dan tak terbantahkan—memberikan untuk pertama kalinya bukti penting bagi dunia tentang meningkatnya karbon dioksida di udara yang kita hirup. Ia telah menemukan siklus napas Bumi.
Keeling memilih Mauna Kea, lanjutnya dalam epilog itu, karena keterpencilannya dari benua, serta karena ketiadaan vegetasi dan debu di sekitarnya yang dapat mencemari pengukuran. Ia bertahan, mencatat tanpa lelah. Ketika pendanaan habis pada pertengahan 1960-an, ia memindahkan operasi pencatatan ke gunung besar lainnya di pulau itu: Mauna Loa. Rekaman Kurva Keeling terus berlanjut hingga hari ini. Berkat kerja Keeling, NOAA mulai memberi perhatian serius pada emisi karbon dioksida dan memantaunya di seluruh planet. Banyak lokasi terpencil lain kini telah memantau gas rumah kaca ini selama bertahun-tahun, mengonfirmasi temuan Keeling—mengubahnya dari perkara teori menjadi perkara fakta.
Menurut Lewis kita mencatat agar kita dapat mengingat, merencanakan, bertindak, dan mengenang. Tanpa bukti, kita melupakan keberhasilan, kegagalan, dan gagasan-gagasan yang sedang bertunas. Ilmu pengetahuan adalah bentuk ingatan kolektif—namun bukan ingatan yang beku—sebab pengumpulan pengetahuanlah yang mendorong sains bergerak maju. Puluhan orang yang diceritakan dalam buku ini, Ia mengingatkan, mengenal pohon-pohon serta masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka terutama melalui praktik pencatatan.
Tradisi lisan kaya akan keindahan dan dapat menyimpan catatan penting dari masa lampau, tetapi catatan tertulis berbeda sifatnya. Barangkali Anda pernah memainkan permainan “bisik-bisik di sekitar api unggun”: sebuah kalimat pendek dibisikkan dari satu telinga ke telinga lain, hingga sampai pada orang terakhir—dan hasil akhirnya sering kali tak dapat dimengerti. Dokumen bersudut empat—dan kini padanan elektroniknya—memberi kita pijakan yang kokoh. Mereka memungkinkan nuansa sekaligus mendukung ketelitian, perenungan, dan kemampuan untuk kembali meninjau sebuah gagasan.
Gagasan tentang pentingnya mencatat juga muncul dalam karya penulis fiksi ilmiah Octavia Butler, khususnya dalam novelnya Parable of the Sower. Tokohnya, Lauren Oya Olamina, memelihara sebuah jurnal yang ia gunakan untuk mengembangkan seperangkat gagasan baru tentang rapuhnya Bumi, sekaligus menuliskan cara-cara baru memandang planet ini dan busana spiritualnya. Butler memahami arti pencatatan pada tingkat yang dalam dan naluriah. Tujuh ribu surat, jurnal, dan buku hariannya kini tersimpan di Huntington Library, sebagian ditulis dalam apa yang ia sebut commonplace books—sebuah istilah indah dan klasik yang memberi hormat pada tradisi pencatatan abad-abad sebelumnya. Ia mencatat daftar belanja, nomor telepon, sketsa cerita, tugas-tugas harian, dan gagasan-gagasan besar untuk bukunya. Tulisan kasarnya adalah jalan menuju teks-teks yang diterbitkan. Ia memahami bahwa pencatatan, lebih dari apa pun, adalah sebuah hubungan: antara dirinya, tulisannya, dan semesta.
“Benih menjadi pohon, pohon menjadi hutan;
hujan menjadi sungai, sungai menjadi laut;
ulat menjadi lebah, lebah menjadi kawanan.
Dari satu menjadi banyak; dari banyak menjadi satu;
selamanya menyatu, tumbuh, dan meluruh,”
tulisnya dalam Parable of the Sower.
Catatan menghubungkan kita, tetapi juga membuat kita bertanggung jawab. Ada beragam jenis rekaman, dan bermacam-macam pencatat. Ingatan adalah makhluk licin yang sukar ditangkap, dan bukti sering kali sulit ditemukan. Ada alasan mengapa pengadilan memiliki stenografer, mahasiswa mendapat nilai, dan agen rahasia mengenakan alat perekam. Jadilah pendoku-mentasi. Susun garis besar, tulis, buat draf, gambar, dan rangkai. Lacak dunia. Kisah-kisah planet ini selalu diceritakan secara terpotong-potong. Tinggalkan catatan bagi masa depan, sebagaimana para pendahulu kita telah melakukannya untuk kita. Pencatatan telah membawa kita sampai ke titik ini.
Kerja para mitra lapangan pohon—naturalis, pengambil sampel, pemanjat, dan penghitung—diimbangi oleh kemitraan lain yang melibatkan kerja sastra yang sering luput dari perhatian: menelaah tumpukan besar bahan tertulis, melakukan kajian ilmiah, dan akhirnya menerbitkan karya. Tanpa catatan tertulis, tak akan ada kabar tentang perubahan dalam sains, tak ada penemuan baru, tak ada klaim. Pujilah para penulis yang menelaah sejawat, merangkai artikel jurnal, menerbitkan monograf, dan mengisi halaman media populer. Dengan sedikit permainan paradoks, mari kita sebut mereka para pecinta pohon dalam ruang. Para ilmuwan dan lainnya telah menulis lebih dari enam puluh ribu artikel akademik dan puluhan buku tentang dua belas pohon ini hanya dalam empat tahun terakhir—dan laju itu belum melambat.
Memahami dan menafsirkan pohon-pohon, serta kehidupan internasional mereka yang saling dibandingkan, memerlukan sebuah desa keilmuan—lintas budaya, lintas bahasa—namun disatukan oleh argot sains. Sering kali, kerja di dalam ruang juga dilakukan oleh mereka yang bekerja di luar ruang, menciptakan lintasan dari lapangan hingga catatan kaki.
Kerja lapangan adalah disiplin yang berantakan, esensial, dan sering kali menggairahkan dalam ilmu alam, dan tulisan mendorong kerja itu masuk ke ruang publik. Namun ada aspek sekutu lain dari kerja sejarah alam yang menuntut bahu, lengan, dan tangan turut memutar roda: pekerjaan di perpustakaan dan koleksi studi museum sejarah alam untuk memverifikasi, memperkaya, mendukung, atau membantah temuan lapangan. Kerja koleksi adalah sepupu dekat pencatatan dan pelaporan.
Anda pun dapat menjadi relawan di ruang-ruang dalam ini, bergabung dengan kelompok yang oleh pengamat abad ke-19—tanpa maksud merendahkan—disebut “naturalis lemari.” Banyak tugas ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan pendeskripsian, lalu kerja komparatif: mengawetkan spesimen, kemudian menatanya di atas meja untuk menyingkap perbedaan dan persamaan. Mengenal suatu spesies dalam bentuk fisiknya berarti memahami sekutu biologisnya. Para pengelola koleksi adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam ilmu biologi, karena merekalah penjaga arsip kemungkinan. Dan penemuan masih menunggu—bukan hanya di lapangan, tetapi juga di koleksi museum, di mana spesimen, bahkan yang telah berusia puluhan tahun, dapat ditinjau kembali untuk mengungkap kebenaran baru, siap menempati tempatnya dalam jalinan pemahaman kita tentang evolusi dan keberlangsungan hidup.
Dan akhirnya: pencatatan dan riset tidak hanya memberi makan sains. Mempelajari nuansa gagasan-gagasan luas seperti identitas dan persahabatan memberi kita konteks. Ada kepuasan dalam terus mempelajari cara-cara baru dan mengunjungi lanskap-lanskap pemahaman yang belum dikenal. Lakukan penyelidikan. Upayakan pemahaman yang lebih dalam. Pergilah ke pinggiran dan tegakkan klaimmu. Carpamus diem—mari kita rebut hari ini bersama.
Dalam setiap konteks, hubunganlah yang menentukan. Banyak kerja kolektif yang perlu kita lakukan demi pohon bermula dari bertindak dengan rasa kekerabatan. Pekerjaan terbaik dan paling berguna bagi pohon adalah kemitraan. Jika kita tak mampu memelihara hubungan baik satu sama lain, kita tak akan mampu membangun jejaring terkuat untuk menyelamatkan pohon. Bekerjalah sama, jangan bertarung. Serahkan kompetisi pada dunia alam, sebab dalam tindakan evolusioner itu—yang berlangsung tanpa penilaian moral, tanpa niat buruk, dan tanpa kerapuhan manusia—tersimpan sebagian besar keselamatan pohon-pohon. Mereka dilahirkan untuk bertahan.
Catatan Akhir: Sebuah Penghargaan bagi Merekam, Melaporkan, Mengingat
Lewis menutup dengan refleksi metodologis: pentingnya mendokumentasikan pohon, koleksi herbarium, data genetika, citra satelit, dan narasi manusia sebagai alat untuk memahami dan merawat pohon. Afterword ini mempromosikan gagasan “arsip hidup”: kebun raya, bank gen, dan catatan lapang adalah jaring keselamatan—tetapi bukan pengganti habitat alami. Lewis mendesak publikasi data terbuka, kolaborasi lintas disiplin, dan pembelajaran sejarah yang jujur (termasuk pengakuan atas peran kolonialisme dalam perampasan tanaman dan pengetahuan lokal). Ia menutup dengan nada optimis-praktis: merekam adalah awal tindakan; melanjutkan tindakan memerlukan politik, pendanaan, dan komitmen jangka panjang. Perlego “We and the trees share the same future and must face our fate together,” kata Lewis. Simon & Schuster UK
Sebagai kurator di The Huntington, Lewis telah terlibat dalam pameran utama yang meng-hubungkan seni, sains, dan lingkungan. Dia adalah pembicara yang dicari di festival literasi, simposium sains, dan konferensi lingkungan, di mana dia mengartikulasikan pentingnya perspektif sejarah untuk memahami krisis ekologis saat ini. Tulisannya telah muncul di Los Angeles Times, The Guardian, dan berbagai jurnal ilmiah populer. Melalui karyanya, dia bertindak sebagai duta besar antara dunia akademis yang khusus dan publik yang lebih luas, menerjemahkan kompleksitas sains dan sejarah menjadi cerita yang mendesak dan relevan.
Buku Lewis menegaskan bahwa pohon-pohon bukan hanya penyimpan karbon atau sumber kayu; mereka adalah infrastruktur hidup yang menopang iklim lokal, ketahanan pangan, dan budaya. Secara global, pembacaan pohon sebagai arsip iklim dan jaringan kehidupan relevan dalam konteks krisis iklim dan kehilangan hutan. Di Indonesia, pelajaran Lewis bergema kuat: negara kita menghadapi tekanan besar terhadap hutan primer, lahan gambut, dan mangrove — akibat konversi lahan untuk kelapa sawit, kehutanan komersial, dan pertambangan — dengan implikasi bagi biodiversitas dan karbon. Data pemutakhiran deforestasi dan laporan organisasi lingkungan menunjukkan fluktuasi tapi masih tingginya tekanan terhadap hutan Indonesia; upaya restorasi dan perlindungan—serta keterlibatan masyarakat adat—sangat penting. Pelajaran praktis: pendekatan konservasi harus menggabungkan in situ (perlindungan habitat, pengelolaan lanskap) dan ex situ (kebun raya, bank benih) sambil memastikan partisipasi komunitas lokal yang memegang pengetahuan tradisional. Global Forest Watch+1
Kritik, apresiasi, dan kutipan relevan. Kritikus memuji Twelve Trees untuk kehangatan narasi dan perpaduan antara sains dan humaniora: Guardian menyebutnya “global arboreal odyssey” dan The Economist menempatkannya sebagai salah satu buku alam terbaik 2024 karena keseimbangan antara kekaguman dan analisis praktis. Library Journal dan Publishers Weekly memuji cara Lewis mengaitkan spesies individu ke isu konservasi besar. Kritik yang muncul umumnya menyentuh dua hal: beberapa pembaca ingin analisis kebijakan yang lebih tajam (mis. blueprint restorasi di tingkat negara), dan ada pembaca yang merasa bab-bab tertentu terlalu anekdotik sehingga detail lokal menutupi generalisasi ekologis. Secara estetis dan etis, buku ini juga mengundang refleksi spiritual: seperti John Muir yang menulis, “In every walk with nature one receives far more than he seeks,”—sebuah pengingat bahwa kontak dengan pohon mengubah nilai batin kita—dan Seyyed Hossein Nasr yang menyatakan bahwa krisis ekologis juga krisis spiritual; kedua kutipan ini memberi dimensi moral pada argumen Lewis bahwa menyelamatkan pohon adalah menyelamatkan hubungan manusia-alam. Google Books+4The Guardian+4The Economist+4
“The salvation of trees can be our salvation.” WJCT News 89.9
Bogor, 3 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Lewis, D. (2024). Twelve Trees: The Deep Roots of Our Future. Simon & Schuster. Simon & Schuster
Lewis, D. (2024). Twelve Trees: The Deep Roots of Our Future. Simon & Schuster. Perlego
“The Guardian” review. (2024). Twelve Trees by Daniel Lewis review — a global arboreal odyssey. The Guardian. The Guardian
The Economist. (2024). How “reading trees” can unlock many mysteries. The Economist. The Economist
Library Journal. (2024). Twelve Trees: The Deep Roots of Our Future — review. Library Journal. Library Journal
Global Forest Watch / WRI data on Indonesia deforestation. (2024–2025). Global Forest Watch+1
Huntington Library (essay excerpt). “A Book Older than God: The Great Basin Bristlecone Pine” (summary/excerpt online). The Huntington
Simon & Schuster (publisher page for Twelve Trees). Simon & Schuster
Prometheus / Methuselah references (historical cases of bristlecone ethics). Wikipedia entries for Prometheus (tree) and Methuselah (pine) (context on controversies and protection). Wikipedia+1
Daniel Lewis (intisari): pohon adalah “arsip hidup” — menyimpan cerita iklim dan budaya. Perlego
John Muir: “In every walk with Nature one receives far more than he seeks.” National Park Service
Seyyed Hossein Nasr: krisis ekologis adalah juga “krisis spiritual” yang menuntut perubahan etika. Google Books