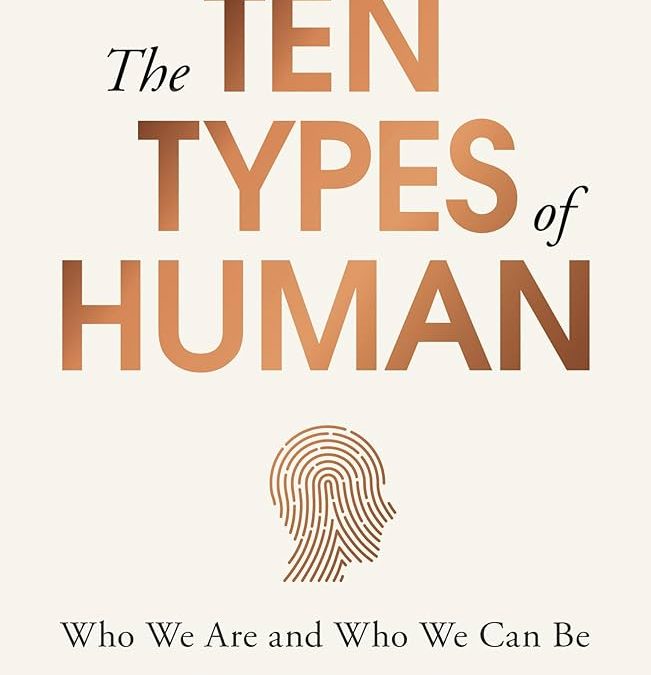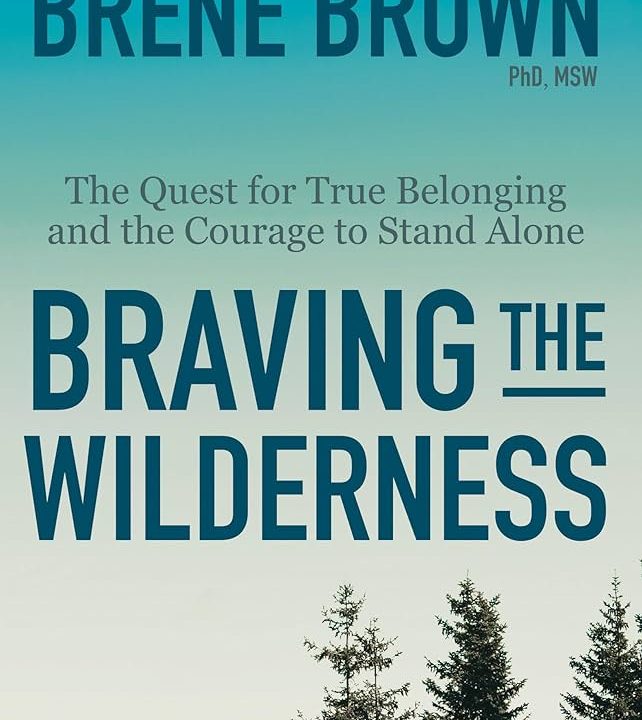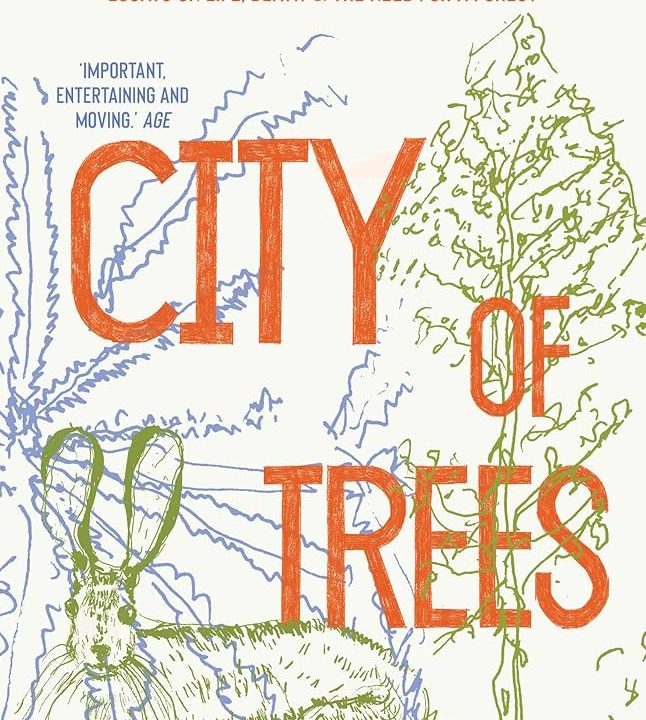Rubarubu #97
The Ten Types of Human:
Sepuluh Sifat dalam Satu Sosok
Pada tahun 2013, di sebuah desa di Bangladesh, seorang pria bernama Al Amin dituduh mencuri sepeda motor. Dia diringkus oleh warga, disiksa, dan akhirnya dibakar hidup-hidup di depan kerumunan yang menyaksikan. Insiden mob justice yang mengerikan ini menggetarkan hati pengacara hak asasi manusia Dexter Dias, yang kemudian menjadi salah satu titik tolak penulisan buku ini. Kisah ini mengajukan pertanyaan abadi: apa yang mendorong manusia biasa—tetangga, warga—untuk melakukan atau menyetujui kekejaman ekstrem terhadap sesamanya? Apakah dalam diri kita semua terdapat potensi untuk itu? Atau sebaliknya, apakah kita juga memiliki naluri untuk melindungi dan berempati? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk jantung dari The Ten Types of Human: A New Understanding of Who We Are and Who We Can Be oleh Dexter Dias (2017).
Buku ini bukan tentang mengklasifikasikan manusia ke dalam kotak-kotak kaku, melainkan eksplorasi mendalam terhadap sepuluh sistem atau “tipe” psikologis—model mental—yang berevolusi dalam diri kita untuk menghadapi dilema dan tekanan hidup yang paling mendasar. Dias berpendapat bahwa kita bukanlah satu diri yang tetap, tetapi sekumpulan “kita” yang berbeda, yang diaktifkan oleh keadaan yang berbeda. “We are not one self. We are many.” (Dias, 2017, p. 3) – Pernyataan sentral buku.
Dias membuka dengan konteks pribadi dan profesionalnya sebagai pengacara yang berhadapan dengan kasus-kasus kemanusiaan paling gelap di pengadilan Inggris dan internasional. Penga-lamannya ini membawanya pada pencarian ilmiah dan filosofis untuk memahami “mekanisme” di balik perilaku manusia. Prolog menetapkan nada buku: sebuah perjalanan yang menggabung-kan narasi kasus hukum yang memilukan, kisah korban dan pelaku dari berbagai penjuru dunia, dengan temuan mutakhir dari neurosains, psikologi evolusioner, antropologi, dan genetika. Ia menulis, “Ini adalah pencarian untuk memahami kekuatan-kekuatan yang membentuk hidup kita, yang membuat kita melakukan hal-hal yang kita lakukan” (Dias, 2017, p. 10).
“Tipe” pertama yang diperkenalkan adalah kemampuan mendasar kita untuk mengenali dan merespons penderitaan orang lain (Sang Penanggap Rasa Sakit (The Perceiver of Pain)). Ini adalah fondasi empati. Dias mengupasnya melalui kasus tragis Genie, seorang gadis California yang disekap dan disiksa selama bertahun-tahun oleh orang tuanya. Kisah Genie menjadi studi kasus tentang bagaimana isolasi sosial yang ekstrem dapat menghancurkan kapasitas untuk berbahasa dan berinteraksi manusiawi. Namun, buku ini juga menunjukkan sisi lain: respons para ilmuwan dan pekerja sosial yang berusaha menyelamatkannya. Di sini, Dias mengutip karya psikolog perkembangan seperti Harry Harlow (tentang pentingnya kontak dan kasih sayang pada primata) dan neurosaintis seperti Tania Singer (tentang jaringan saraf empati di otak). Ia berargumen bahwa menjadi “penanggap rasa sakit” bukanlah jaminan—kapasitas ini dapat ditekan, diputar, atau dimatikan oleh ideologi, tekanan kelompok, atau trauma. Filsuf Muslim abad ke-12, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam Ihya Ulum al-Din (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama), menekankan pentingnya rahmah (belas kasih) sebagai sifat Ilahi yang harus diteladani manusia, dan bahwa hati yang keras adalah penyakit spiritual. Perspektif ini selaras dengan tesis Dias bahwa empati adalah kapasitas alami yang perlu dipupuk dan dilindungi.
Sepuluh Tipe Manusia
Buku ini terbagi menjadi sepuluh bagian besar, “The Ten Types framework is a way of mapping the landscape of human behaviour, a guide to the forces that pull us in one direction or another.” (Dias, 2017, p. 12), masing-masing mendalami satu “tipe” atau model perilaku manusia:
- The Perceiver of Pain: Empati dan pengenalan akan penderitaan.
- The Ostraciser: Mekanisme pengucilan dan penolakan sosial.
- The Tamer of Terror: Cara kita mengatasi ketakutan akan kematian dan kekacauan.
- The Beholder: Persepsi kita tentang kecantikan dan daya tarik fisik.
- The Aggressor: Sifat agresi dan kekerasan.
- The Tribalist: Kecenderungan kelompok dan permusuhan terhadap luar kelompok.
- The Nurturer: Dorongan keibuan/pengasuhan dan pengorbanan untuk anak.
- The Romancer: Dinamika seksual, cinta, dan kecemburuan.
- The Rescuer: Dorongan untuk menolong orang asing yang membutuhkan.
- The Kinsman: Loyalitas dan pengorbanan untuk keluarga dan kerabat dekat.
Dias menjelaskan bahwa “tipe-tipe” ini bukan kotak yang eksklusif. Mereka adalah kecen-derungan atau program psikologis dalam otak kita yang telah berevolusi untuk menyelesaikan masalah spesifik nenek moyang kita di sabana Afrika. Kita bisa bergerak di antara mereka, dan konflik batin sering terjadi ketika beberapa “tipe” ini saling berbenturan (misalnya, The Tribalist yang mendorong kebencian pada kelompok lain berbenturan dengan The Perceiver of Pain yang mengingatkan kita bahwa mereka juga manusia). Buku ini dipenuhi dengan cerita-cerita yang menggugah: dari korban perdagangan manusia, veteran perang yang trauma, hingga ibu yang berjuang demi anaknya. Setiap cerita adalah jendela ke dalam salah satu “ruang” psikologis ini.
Hannah Arendt, dengan konsepnya tentang “banality of evil” (kehampaan dari kejahatan), sangat relevan dengan analisis Dias tentang bagaimana mekanisme seperti The Tribalist atau The Ostraciser dapat membuat orang biasa melakukan kejahatan tanpa berpikir kritis. Sedang-kan penyair Indonesia, Sapardi Djoko Damono, dalam puisinya yang terkenal “Pada Suatu Hari Nanti”, menulis: “pada suatu hari nanti / jasadku tak akan ada lagi / tapi dalam bait-bait sajak ini / kau takkan kurelakan sendiri”. Puisi ini menyentuh The Tamer of Terror—usaha manusia untuk mengatasi ketakutan akan kematian melalui warisan yang abadi (cinta, karya seni, keturunan). Sementara itu, aktivis HAM Muslim asal Iran, Shirin Ebadi (peraih Nobel Perdamaian), dalam perjuangannya, menampilkan perpaduan antara The Perceiver of Pain (empati pada korban) dan The Rescuer(dorongan menolong). Ia sering mengutip ayat Quran yang menekankan keadilan dan pembelaan pada yang tertindas (*QS. An-Nisa: 135*).
Secara global, buku ini adalah lensa yang sangat relevan untuk memahami polarisasi politik, konflik etnis, kekerasan massal, dan juga gerakan solidaritas kemanusiaan di abad ke-21. Fenomena seperti radikalisasi, xenophobia, dan “cancel culture” di media sosial dapat dianalisis melalui lensa The Tribalist dan The Ostraciser. Di sisi lain, gerakan sukarelawan global dalam bencana atau krisis pengungsi mencerminkan bangkitnya The Rescuer dan The Perceiver of Pain.
Di Indonesia, buku ini memberikan kerangka untuk merefleksikan berbagai persoalan kompleks:
- Konflik identitas (SARA): Kekuatan The Tribalist sangat kuat. Memahami bahwa ini adalah kecenderungan psikologis yang dalam, bukan takdir, adalah langkah pertama untuk mengelolanya dengan kebijakan yang inklusif dan pendidikan multikultural.
- Kekerasan massa dan intoleransi: Kasus-kasus penganiayaan terhadap kelompok minoritas mencerminkan kegagalan The Perceiver of Pain dan dominasi The Aggressor atau The Ostraciser yang dimobilisasi oleh narasi tertentu.
- Solidaritas dan gotong royong: Nilai gotong royong dan tepo seliro yang mengakar dalam budaya Jawa dan banyak budaya Nusantara adalah manifestasi lokal yang kuat dari The Nurturer, The Kinsman, dan The Rescuer. Buku ini membantu mengartikulasikan nilai-nilai luhur ini dalam bahasa sains kontemporer.
Dias tidak pesimis. Dengan memahami “sepuluh tipe” ini, kita dapat secara sadar membangun lingkungan sosial, sistem pendidikan, dan kebijakan publik yang mengaktifkan “tipe-tipe” terbaik kita (seperti The Perceiver of Pain, The Nurturer, The Rescuer) dan menahan “tipe-tipe” yang lebih destruktif. Masa depan kemanusiaan bergantung pada pilihan kita untuk merancang masyarakat yang memupuk empati, menghargai keindahan (The Beholder), dan memperluas lingkaran pengorbanan kita melampaui keluarga dan suku (The Kinsman, The Tribalist) menuju kemanusiaan universal. Buku ini adalah peta dan sekaligus seruan untuk kesadaran diri dan tanggung jawab kolektif.
Mari kita menyelami satu per satu dari sepuluh tipe manusia itu.
Sang Penanggap Rasa Sakit
Bagian pembuka buku ini, “The Perceiver of Pain”, bukan sekadar pengantar teori. Ini adalah sebuah perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam ke dalam salah satu fondasi kemanusiaan kita yang paling mendasar sekaligus paling rapuh: kemampuan untuk mengenali dan merespons penderitaan makhluk lain. Dexter Dias membawa pembaca melalui labirin psikologi manusia, dari ketinggian empati yang heroik hingga jurang ketidakpedulian yang mengerikan, dengan satu pertanyaan sentral: mengapa kita terkadang dengan mudahnya mengabaikan rasa sakit orang lain?
Perjalanan ini dimulai bukan dengan abstraksi, tetapi dengan angka yang memilukan: “The 21,000”. Ini adalah jumlah anak, menurut UNICEF, yang meninggal setiap hari karena sebab-sebab yang dapat dicegah—kelaparan, penyakit, kemiskinan. Data “The 21,000” dan konsep compassion fatigue: Dias merujuk pada laporan UNICEF dan penelitian psikologi sosial kontemporer. Angka ini, tulis Dias, begitu besar hingga membuat kita mati rasa; ia mengalah-kan kapasitas empati kita. Di sinilah kita menemukan paradoks pertama: sistem yang membuat kita menjadi Perceivers of Pain juga memiliki mekanisme pembatas. Otak kita tidak dirancang untuk menanggung penderitaan dunia. Kognisi kita, seperti yang dielaborasi dalam “The Cognitive Cost of Compassion”, memiliki anggaran terbatas. Memberi perhatian dan empati memerlukan sumber daya mental dan emosional. Ketika dihadapkan pada skala penderitaan yang masif, kita sering kali melakukan “pemadaman psikologis”—kita mematikan perasaan agar bisa terus berfungsi. Ini adalah mekanisme pertahanan, tetapi juga celah berbahaya yang memungkinkan kekejaman terjadi dalam kesunyian.
Dias kemudian mengajak kita menyelami kasus-kasus ekstrem di mana kemampuan untuk “melihat” rasa sakit orang lain benar-benar terhapus. Ia membawa kita ke wilayah yang dalam peta kuno akan diberi label “Here Be Dragons”—wilayah gelap dan belum terpetakan dari jiwa manusia. Melalui kisah-kisah pengadilan, seperti pelaku kekerasan yang tampaknya sama sekali tidak memiliki belas kasihan, Dias memperkenalkan konsep “The Rule of Effective Invisibility”. Korban, bagi pelaku, menjadi tidak terlihat secara manusiawi. Mereka direduksi menjadi objek, hambatan, atau ancaman. Proses dehumanisasi ini adalah gerbang menuju kekejaman. Saat kita berhenti memandang seseorang sebagai manusia yang dapat merasakan sakit, penghalang moral untuk menyakiti mereka runtuh. Filosof seperti Emmanuel Levinas akan mengatakan bahwa etika dimulai dari “Wajah Orang Lain” yang menuntut tanggapan kita; aturan Effective Invisibility adalah pembunuhan terhadap wajah itu.
Puncak eksplorasi kegelapan ini adalah bab “A More Total Darkness” dan “The Blank Face of Oblivion”, di mana Dias membahas isolasi sensorik total. Ia mengutip eksperimen kontroversial dan kisah nyata tentang individu yang dirampas dari semua input sosial dan sensori. Dalam kegelapan yang lebih total dari kebutaan fisik ini, diri manusia dapat terfragmentasi. Tanpa cermin dari orang lain, tanpa umpan balik dari dunia, kapasitas untuk memahami diri sendiri dan, pada gilirannya, memahami penderitaan orang lain, dapat menguap. Ini mengingatkan pada peringatan Buya Hamka dalam Tasawuf Modern tentang bahaya “kegelapan hati” (zulmah al-qalb) yang lebih berbahaya daripada kegelapan mata, karena ia memutuskan hubungan dengan realitas dan sesama.
Namun, bagian ini bukan cerita tanpa harapan. Di tengah analisis tentang mekanisme ketidak-pedulian, Dias menyelipkan bab berjudul “The Promise”. Di sini, ia menunjukkan sisi lain dari koin yang sama. Kapasitas untuk merasakan sakit orang lain juga adalah sumber dari semua altruisme, kasih sayang, dan keadilan. “Janji” itu adalah potensi bawaan kita untuk peduli. “Once I Was Blind” adalah narasi tentang pembukaan mata—momen di mana seseorang tiba-tiba “melihat” penderitaan yang sebelumnya mereka abaikan. Ini adalah pengalaman transformatif, mirip dengan pencerahan spiritual. Seorang pemikir Muslim, Syed Muhammad Naquib al-Attas, mendefinisikan pendidikan (ta‘dīb) sebagai proses pengenalan dan penanaman adab, yang pada hakikatnya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap tempat yang tepat dari segala sesuatu, termasuk pengakuan terhadap hak dan martabat orang lain. Proses “Once I Was Blind” ini adalah inti dari ta‘dīb—sebuah pencerahan moral yang membuka mata hati.
Dias mensintesis argumennya dengan menunjukkan bahwa menjadi Perceiver of Pain bukanlah kondisi statis, melainkan sebuah pertempuran terus-menerus antara dua kekuatan: naluri bawaan kita untuk berempati dan berbagai tekanan—kognitif, sosial, ideologis—yang mendorong kita ke arah ketidakpedulian. Ancaman terbesar bukanlah dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kapasitas ini (yang secara psikopatologis jumlahnya kecil), tetapi dari bagaimana sistem sosial, tekanan kelompok, dan retorika politik dapat secara sistematis menidurkan atau mengalihkan kapasitas ini dalam diri kita semua.
Oleh karena itu, “The Perceiver of Pain” lebih dari sekatalog kemampuan psikologis. Ia adalah panggilan untuk kewaspadaan. Ia mengajak kita untuk memeriksa diri: dalam kondisi apa kita membiarkan “Aturan Efektif Ketidakterlihatan” berlaku? Kapan kita memilih untuk membayar “Biaya Kognitif Kasih Sayang”, dan kapan kita menolaknya? Bagian ini menyiapkan panggung untuk seluruh buku dengan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk belas kasih yang mendalam, tetapi potensi itu hidup dalam medan pertempuran psikologis yang konstan. Masa depan kemanusiaan kita, sebagaimana akan dijelajahi dalam tipe-tipe selanjutnya, bergantung pada pertempuran memenangkan dan memperluas wilayah The Perceiver of Paindalam diri kita masing-masing dan dalam masyarakat kita.
Pengalaman tipe ini bisa ditemukan pada lagu-lagu ini: ‘A Real Hero’ – College & Electric Youth: Lagu ini, dengan nuansa synthwave yang melankolis namun penuh harapan, menangkap inti dari tipe ini: kepekaan terhadap penderitaan dan potensi untuk menjadi pahlawan dalam keheningan, dalam tindakan empati sehari-hari. ‘Poor Wayfaring Stranger’ – Natalie Merchant : Versi Merchant yang haunting tentang lagu spiritual tradisional ini adalah lagu untuk mereka yang terluka, yang berjuang, dan untuk empati yang mengenali penderitaan dalam perjalanan setiap orang. Ia adalah suara dari The Perceiveritu sendiri.
Sang Pengucil dan Sang Penjinak Teror
Setelah menelusuri medan belas kasih yang rapuh, Dexter Dias mengajak kita memasuki dua wilayah gelap sekaligus vital dari kondisi manusia: naluri untuk mengucilkan dan kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketakutan kita yang paling dalam. Bagian “The Ostraciser” dan “The Tamer of Terror“ adalah dua sisi dari koin yang sama: upaya psikologis kita untuk mengatur dunia sosial dan eksistensial dengan menciptakan ketertiban, batas, dan makna—seringkali dengan mengorbankan orang lain atau melalui ilusi.
Sang Pengucil (The Ostraciser)
Bagian ini dibuka dengan sebuah perintah kuno dan kejam: “Take Elpinice and go“. Elpinice adalah seorang perempuan dalam sejarah Yunani yang dikutuk menjadi pengasingan. Dari sini, Dias menunjukkan bahwa pengucilan bukanlah fenomena modern, melainkan alat sosial purba yang tertanam dalam psikologi kita. “The Wounded City” kemudian mengajak kita melihat lanskap internal seseorang yang mengalami ostracisme. Menggunakan penelitian neurosains mutakhir (seperti karya Naomi Eisenberger yang menunjukkan bahwa rasa sakit sosial di otak memanfaatkan jalur saraf yang sama dengan rasa sakit fisik), Dias berargumen bahwa dikucilkan sakit secara harfiah. Otak kita mengalami penolakan sosial sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup, memicu penderitaan yang mendalam dan nyata. Pada bagian The Ostraciser, ia menulis: “Exclusion is a form of killing. It is a social death.” (Dias, 2017, p. 95), menggemakan konsep “social death” yang banyak dibahas dalam sosiologi.
Kekuatan bagian ini terletak pada bagaimana Dias menggali mekanisme yang memungkinkan kita, sebagai pelaku pengucilan, untuk melakukan hal ini tanpa merasa bersalah. “Do Not Read This“adalah metafora yang kuat tentang bagaimana kita secara kognitif “menutup mata” terhadap penderitaan yang kita sebabkan. Kita membangun dinding psikologis, membenarkan tindakan kita dengan narasi bahwa “mereka” (yang dikucilkan) pantas mendapatkannya, atau bahwa tindakan itu diperlukan untuk kebaikan kelompok. Inilah jantung dari “The Circle and the Suffering”. Dias menggambarkan bagaimana kita menggambar “lingkaran” moral di sekitar kelompok kita sendiri (in-group), sementara mereka yang di luar lingkaran itu—out-group—menjadi kurang layak mendapat empati dan perlindungan penuh. Mereka yang menderita di luar lingkaran seringkali tak terlihat, atau penderitaannya dibenarkan. Fenomena ini mengingat-kan pada konsep “the suffering of others“ yang dikritik oleh Susan Sontag, di mana kita menjadi penonton pasif atas penderitaan yang jauh, terpisah oleh batas geografis dan psikologis. Seorang pemikir Muslim seperti Ali Syariati dalam Ummah dan Imamah-nya juga memperingatkan tentang fanatisme kesukuan (asabiyyah) yang sempit, yang mengutamakan loyalitas kelompok di atas keadilan universal, sebuah bentuk pengucilan berdasarkan identitas.
Simfoni lagu-lagu ini adalah cermin tipe THE OSTRACISER (Sang Pengucil): ‘Beyond the Sea’ – Bobby Darin / Kathryn Williams: Di satu sisi, lagu ini bernostalgia tentang kerinduan dan tempat yang tak terjangkau. Di sisi lain, ia bisa menjadi metafora pahit tentang mereka yang “di seberang lautan” sosial, yang dikucilkan dan tidak dapat dijangkau oleh rasa solidaritas kita.
‘Paid My Dues’ – Anastacia: Dipilih oleh seorang aktivis (Kathy Bolkovac), lagu ini adalah nyanyian perlawanan dari mereka yang telah dikucilkan dan diperlakukan tidak adil, tetapi menolak untuk diam. Ini adalah suara dari pihak yang di-Ostracise yang berbalik melawan.
Sang Penjinak Teror (The Tamer of Terror)
Jika Sang Pengucil mengatur ancaman sosial, maka Sang Penjinak Teror adalah mekanisme pertahanan kita terhadap ancaman eksistensial terbesar: kesadaran akan kematian kita sendiri. Dias memulai dengan pernyataan yang menggema, “The Time Has Come“, mengisyaratkan bahwa konfrontasi dengan ketakadaan adalah tak terhindarkan.
Melalui “The Broken Circuit”, Dias memperkenalkan teori manajemen teror (Terror Management Theory) yang dikembangkan oleh Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, dan Tom Pyszczynski. Inti teori ini adalah bahwa konflik antara naluri untuk hidup dan kesadaran bahwa kita akan mati menciptakan kecemburuan eksistensial yang mendalam. Untuk mengatasinya, budaya dan keyakinan kita berfungsi sebagai “The Ice Age“—sebuah sistem pertahanan psikologis yang membekukan teror kita. Kita menciptakan dan memeluk struktur makna—agama, nasionalisme, ideologi, bahkan proyek pribadi—yang memberi kita rasa simbolis akan keabadian dan nilai hidup.
Namun, pertahanan ini rapuh. “The Case of Schwarzenegger’s Farm“ (sebuah metafora untuk upaya manusia menciptakan dunia yang terkendali dan perkasa) menunjukkan betapa mudahnya sistem makna kita terguncang. Ketika keyakinan kita ditantang, ketika kita diingatkan akan kematian kita secara tidak langsung (A H N T – kata kematian yang dipecah, mungkin “A Hint”), “The Broken Circuit” itu menyala kembali, dan teror muncul. Respons kita, seperti yang digambarkan dalam “Facing into the Sun” dan “Locked Out”, seringkali adalah berpegang lebih kuat pada keyakinan kelompok kita (memperkuat The Tribalist) dan menjadi lebih bermusuhan terhadap mereka yang di luar keyakinan itu (mengaktifkan The Ostraciser). Inilah hubungan simbiosis antara dua “tipe” ini: ketakutan akan kematian (Tamer of Terror) dapat mendorong kita untuk mengucilkan mereka yang dianggap mengancam pandangan dunia kita (The Ostraciser).
Dias mengilustrasikan ini dengan kekuatan naratif, menunjukkan bagaimana retorika politik sering kali memanfaatkan ketakutan eksistensial untuk menggalang dukungan dan mengarah-kan kemarahan pada kelompok kambing hitam. Dalam konteks ini, filsuf eksistensialis Albert Camusdalam The Myth of Sisyphus berargumen bahwa menghadapi absurditas dan ketakutan akan kematian tanpa ilusi adalah tindakan pemberontakan yang sejati. Sementara itu, tradisi Sufisme dalam Islam, seperti ajaran Jalaluddin Rumi, menawarkan jalan lain untuk “menjinak-kan teror”: dengan meleburkan diri dalam cinta Ilahi (fana), yang mengubah perspektif tentang kematian dari akhir yang menakutkan menjadi penyatuan dengan Yang Abadi.
Alur naratif dari kedua bagian ini mengalir dari rasa sakit sosial menuju kecemasan eksistensial. Dias menunjukkan bahwa tindakan mengucilkan sering kali bukan sekadar kekejaman yang dingin, tetapi dapat menjadi gejala dari ketakutan yang mendalam—ketakutan akan konta-minasi, ketidakmurnian kelompok, atau ancaman terhadap sistem makna yang melindungi kita dari kengerian ketiadaan. “The Wounded City” di dalam diri korban pengucilan adalah bayang-an cermin dari “The Broken Circuit” di dalam diri pelakunya; keduanya adalah respons terhadap ancaman yang dirasakan, nyata atau simbolis.
Kesimpulan mendalam dari kedua bagian ini adalah peringatan: naluri untuk bertahan dan menciptakan keteraturan—baik secara sosial melalui pengucilan maupun secara psikologis melalui penciptaan makna—dapat dengan mudah berbelok menjadi kekuatan yang merusak. Mereka menjelaskan mengapa permusuhan antar kelompok begitu mudah tersulut, mengapa dialog menjadi mustahil ketika identitas dan keyakinan dasar merasa terancam, dan mengapa kita begitu sering mencari “orang lain” untuk dipersalahkan ketika dunia terasa kacau atau menakutkan. Memahami “The Ostraciser” dan “The Tamer of Terror” adalah langkah penting untuk mengenali dinamika ini dalam diri kita sendiri dan dalam masyarakat, sehingga kita dapat—dengan kesadaran—memilih untuk tidak membiarkan ketakutan kita menguasai dan mengarahkan kita untuk mengucilkan sesama manusia.
Lagu-lagu ini menyingkap tipe THE TAMER OF TERROR (Penjinak Teror): ‘Forever Autumn’ – Jeff Wayne (feat. Richard Burton): Dipilih oleh seorang yang menghadapi tantangan kesehatan berat (Dawn Faizey Webster), lagu ini menghadapi kehilangan dan kesementaraan dengan keindahan yang tragis. Ini adalah upaya The Tamer untuk menemukan makna dan keindahan bahkan di tengah musim gugur yang abadi—konfrontasi dengan kematian. ‘Mad World’ – Tears For Fears/Gary Jules: Lagu ini menangkap absurditas dan kecemasan eksistensial yang mencoba dijinakkan oleh tipe ini. Dunia yang “gila” inilah yang membuat kita mencari sistem kepercaya-an, ritual, dan makna untuk bertahan.
Sang Penatap dan Sang Penyerang
Setelah menjelajahi dinamika sosial dan eksistensial, Dexter Dias membawa kita ke dalam dua domain yang tampak berlawanan namun sama-sama fundamental: daya tarik fisik yang meng-giurkan dan agresi yang menghancurkan. Bagian “The Beholder“ dan “The Aggressor” meng-eksplorasi bagaimana evolusi telah membentuk persepsi kita tentang keindahan dan ke-mampuan kita untuk melakukan kekerasan—dua kekuatan yang secara mengejutkan memiliki akar yang dalam dan saling terkait dalam arsitektur psikologis manusia.
Sang Penatap (The Beholder)
Bagian ini dimulai dengan pernyataan yang menyayat hati dari seorang korban serangan asam: “All They Saw Was My Face“. Kisah ini menjadi pintu masuk yang tragis ke dalam salah satu bias paling purba dan paling kuat dalam persepsi manusia: bagaimana kita melihat dan menilai orang lain berdasarkan penampilan fisik mereka. Dias mengungkapkan bahwa kemampuan kita sebagai Beholder—penatap keindahan—tidak netral atau murni estetis. Ia adalah sistem penilaian evolusioner yang bekerja dengan cepat dan sering kali di luar kesadaran kita.
Melalui bab “Penalising Plainness“, Dias, dengan merujuk pada banyak penelitian psikologi evolusioner dan sosial, menunjukkan bagaimana wajah-wajah yang dinilai kurang menarik atau simetris secara tidak sadar mendapatkan hukuman sosial. Mereka dianggap kurang dapat dipercaya, kurang cerdas, dan kurang kompeten. “The Pool of Fire“ adalah metafora untuk pengalaman hidup yang menghanguskan akibat stigma ini—dikucilkan, diejek, atau direduksi menjadi penampilan semata. Sementara itu, “The Water Is Rising” menggambarkan tekanan yang terus meningkat dari budaya yang semakin terobsesi pada citra dan standar kecantikan yang tidak realistis, yang diperkuat oleh media dan iklan. Seseorang mungkin teringat pada kritik filsuf Jean Baudrillard tentang simulacra dan masyarakat konsumsi, di mana citra yang direkayasa menggantikan realitas, dan nilai manusia direduksi menjadi tanda-tanda penampilan.
Namun, Dias juga menunjukkan sisi adaptif dari The Beholder. Persepsi kita terhadap simetri, proporsi wajah tertentu, atau tanda-tanda kesehatan, pada masa lalu evolusi kita, dapat menjadi petunjuk cepat tentang kesesuaian pasangan atau status kesehatan. Masalahnya muncul ketika kecenderungan purba ini bertabrakan dengan kompleksitas masyarakat modern, menghasilkan ketidakadilan yang mendalam dan penderitaan psikologis. Seorang pemikir Muslim seperti Syed Hussein Alatas dalam The Myth of the Lazy Native secara tidak langsung menyentuh persoalan ini, menunjukkan bagaimana penjajah membangun stereotip negatif tentang penampilan dan karakter penduduk pribumi untuk membenarkan dominasi mereka—sebuah bentuk politisasi persepsi yang merusak.
THE BEHOLDER (Sang Penatap) jika diekspresikan dalam simfoni maka akan dirasakan dalam alunan ini: Piano Sonata No. 30, Op. 109 – Beethoven: Gerakan Andante yang dalam dan reflektif ini merepresentasikan kontemplasi mendalam tentang keindahan murni dan bentuk. Ini adalah sisi Beholder yang tinggi, yang mengagumi keindahan abstrak dan proporsi sempurna. ‘I Am Not Alone’ – Kari Jobe: Dipilih oleh seorang penyintas (Hanifa Nakiryowa), lagu ini menunjukkan sisi lain Beholder: bagaimana kepercayaan spiritual atau cinta dapat membuat seseorang merasa “terlihat” dan bernilai, melawan stigma atas penampilan fisik.
Sang Penyerang (The Aggressor)
Dari ranah persepsi, kita dibawa masuk ke dalam pusaran kegelapan yang lebih dalam: “The Aggressor”. Bagian ini dibuka dengan sebuah peraturan yang mengerikan, “Ordinance 72.058”, yang mungkin merujuk pada dekrit atau hukum yang mengesahkan kekerasan sistematis. Dari sini, Dias memulai penyelidikannya yang mendalam terhadap mekanisme psikologis yang memungkinkan manusia biasa—bukan monster—untuk melakukan, menyaksikan, atau membenarkan kekerasan yang luar biasa kejamnya.
Perjalanan ini melintasi berbagai medan kekejaman. “The Golden Box” bisa menjadi metafora untuk ilusi atau pembenaran berharga yang kita bungkus di sekitar tindakan agresif. “Like a Torch” dan “With Open Eyes” mungkin menggambarkan bagaimana kekerasan dapat menyala dengan cepat dan dilakukan dalam keadaan sadar penuh, bukan dalam amukan buta. Dias menyelidiki dinamika ini dengan merujuk pada psikologi kekuasaan, eksperimen klasik seperti Milgram dan Zimbardo, serta penelitian tentang dehumanisasi. “How Similar Are You to Small Insects?” adalah pertanyaan yang mengerikan, yang merujuk pada proses di mana korban direndahkan ke status sub-manusia, sehingga menyakiti mereka menjadi lebih mudah secara psikologis.
Dias kemudian memperluas analisisnya dari kekerasan interpersonal ke kekerasan kolektif dan perang modern. “4GW” (Fourth Generation Warfare) dan “The Burning Country” membawa pembaca ke konflik-konflik kontemporer yang kabur batasnya, di mana kekerasan menjadi kompleks dan melibatkan aktor non-negara. “A Man of Business” dan “Diamonds” meng-ungkap sisi ekonomi dan oportunistik dari agresi—bagaimana kekerasan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Puncak dari penjelajahan ini mungkin terletak pada bab-bab seperti “The Vortex”, “17 Days”, “The Great Desert”, dan “The Cave of Hands”. Di sini, Dias menggunakan narasi yang kuat dan metafora yang dalam untuk menggambarkan pengalaman terjebak dalam siklus kekerasan, ketahanan atau kehancuran korban, kekosongan spiritual yang ditinggalkan oleh konflik, dan jejak manusia yang tertinggal—baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. “The Cave of Hands” khususnya, dapat menjadi gambaran tentang jejak abadi dari trauma kolektif atau simbol harapan yang rapuh di tengah kegelapan.
Dalam menjelajahi The Aggressor, Dias bukan hanya berbicara tentang psikopat. Dia berbicara tentang “kita”. Dia menunjukkan, seperti yang pernah dikemukakan oleh filsuf Hannah Arendt, bagaimana kejahatan dapat bersifat birokratis dan dangkal. Dia juga menggemakan peringatan Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth tentang bagaimana kekerasan kolonial melahirkan kekerasan balasan, menciptakan lingkaran setan. Dari perspektif Islam, konsep zulm (kezaliman) didefinisikan tidak hanya sebagai tindakan agresi, tetapi sebagai “meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya”—sebuah ketidakseimbangan yang merusak tatanan alam dan sosial. Agresi, dalam pandangan ini, adalah puncak dari zulm.
Alur naratif dari kedua bagian ini menciptakan kontras yang tajam namun saling berhubung-an. The Beholder adalah tentang penarikan, daya tarik, dan preferensi. The Aggressor adalah tentang penolakan, penolakan, dan penghancuran. Namun, keduanya adalah alat seleksi yang kuat. Keduanya melibatkan penilaian cepat terhadap orang lain—satu berdasarkan potensi manfaat atau kesenangan, yang lainnya berdasarkan ancaman atau hambatan.
Yang lebih mengganggu, Dias menunjukkan bagaimana kedua kecenderungan ini dapat saling memicu. Persepsi negatif atau stereotip yang dibentuk oleh The Beholder (misalnya, melihat kelompok lain sebagai “jelek”, “asing”, atau “inferior”) dapat menjadi bahan bakar yang mudah untuk The Aggressor, terutama ketika dikombinasikan dengan mekanisme seperti The Ostraciser dan ketakutan eksistensial dari The Tamer of Terror. Standar kecantikan yang sempit (The Beholder) dapat menjadi bentuk kekerasan psikologis, sementara agresi fisik sering kali bertujuan untuk menghancurkan atau menguasai apa yang dianggap berharga atau indah.
Kesimpulan mendalam dari penjelajahan ini adalah pengakuan bahwa baik kemampuan kita untuk mengagumi keindahan maupun kapasitas kita untuk melakukan kekerasan adalah bagian dari warisan evolusi kita. Mereka bukanlah kekuatan moral yang netral; mereka dapat diguna-kan untuk membangun atau menghancurkan. Memahami The Beholder mengajarkan kita untuk sadar akan bias mendalam yang membentuk interaksi sosial kita dan untuk melawan ketidak-adilan yang ditimbulkannya. Memahami The Aggressor adalah langkah penting untuk mengakui potensi kekerasan dalam diri kita sendiri, untuk mengidentifikasi kondisi sosial yang memicu-nya, dan untuk membangun sistem—hukum, pendidikan, norma budaya—yang dapat menahan dan mengalihkan energi destruktif ini. Keduanya mengajak kita untuk tidak menjadi pasif terhadap keindahan yang menindas atau terhadap kekerasan yang dibungkus pembenar-an, melainkan untuk secara aktif membentuk dunia di mana nilai manusia diakui melampaui penampilan dan di mana konflik dapat diselesaikan tanpa jatuh ke dalam jurang The Aggressor yang paling gelap.
Tipe THE AGGRESSOR (Sang Penyerang) bisa didengarkan lewat alunan lagu ini: ‘I’m Gonna Be (500 Miles)’ – The Proclaimers: Di balik melodi ceria, tekad obsesif dalam liriknya mencermin-kan sisi fokus tunggal dan kegigihan yang tak kenal lelah dari The Aggressor. Ini adalah energi yang sama, yang bisa digunakan untuk mengejar cinta atau untuk menghancurkan. ‘Shine Bright Like a Diamond’ – Julie Anna: Versi yang mungkin lebih keras atau ironis dari lagu Rihanna ini bisa melambangkan kekerasan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan sesuatu yang berkilau—kekayaan, kekuasaan, status—atau ketangguhan ilusif yang diproyeksikan oleh seorang Aggressor.
Kesukuan dan Keibuan—Dua Kutub Ikatan Manusia
Perjalanan kita dalam memahami sepuluh tipe manusia kini mencapai inti dari dua kekuatan yang paling mendasar dalam membentuk kehidupan sosial dan personal: naluri untuk berkelompok dan naluri untuk mengasuh. Dalam “The Tribalist“ dan “The Nurturer“, Dexter Dias mengungkap dua sisi dari kebutuhan manusia yang sama: untuk terhubung dan melindungi, yang pada ekstremnya dapat melahirkan konflik terbesar sekaligus pengorbanan teragung.
Si Kesukuan (The Tribalist)
Bagian ini dibuka dengan sebuah kutipan yang menggema dari The Tempest karya Shakespeare: “The Isle Is Full of Noises”. Suara-suara itu adalah suara identitas kelompok, yang nyaring, saling bersahutan, dan terkadang mengganggu. Dias membawa kita ke “The Pier”, tempat simbolis di mana kita berdiri untuk melihat “yang lain”. Dari sanalah kita meng-amati “The Dogs”—metafora yang mungkin mengacu pada cara kelompok lain digambarkan sebagai ancaman yang liar, tidak rasional, dan berbahaya.
Melalui “Like Peeling Fruit”, Dias mengupas lapisan-lapisan psikologis dari tribalisasi. Dengan merujuk pada teori identitas sosial (Henri Tajfel) dan penelitian psikologi evolusioner, ia menunjukkan betapa cepat dan mudahnya otak manusia membagi dunia menjadi “kita” (in-group) dan “mereka” (out-group). Bahkan pembagian yang sewenang-wenang—seperti berdasarkan warna kaos—dapat langsung memunculkan loyalitas dan bias kelompok. Ini bukanlah kesalahan berpikir, melainkan strategi evolusioner yang mendalam. Dalam lingkungan nenek moyang kita, identifikasi cepat dengan kelompok sendiri dan kewaspadaan terhadap kelompok lain adalah masalah hidup dan mati.
Namun, The Tribalist modern sering kali beroperasi dengan logika yang sama tetapi dengan konsekuensi yang jauh lebih kompleks. Ia menjelaskan polarisasi politik, sentimen nasionalis ekstrem, konflik etnis, dan bahkan rivalitas sepak bola. Dias menunjukkan bahwa kekuatan The Tribalist terletak pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan psikologis akan rasa memiliki, makna, dan keamanan (yang terkait dengan The Tamer of Terror). Namun, energi yang sama ini dapat dengan mudah dialirkan ke dalam “The Dogs”—kebencian terhadap kelompok luar yang didehumanisasi, seperti yang dijelaskan dalam bagian The Ostraciser dan The Aggressor. Filsuf Kwame Anthony Appiah dalam Cosmopolitanism mengkritik cengkeraman paradigma kesukuan ini dan mengadvokasi etika global yang mengakui kemanusiaan bersama. Sementara itu, pemikir Muslim Abdolkarim Soroush berbicara tentang pentingnya membeda-kan antara “agama kebenaran” dan “agama identitas”; yang terakhir sering kali terjebak dalam tribalisasi yang menjadikan keyakinan sebagai bendera kelompok, bukan pencarian spiritual universal.
Pengalaman tipe THE TRIBALIST (Sang Kesukuan) ada dalam nyanyian ini: ‘America’ – dari West Side Story: Lagu ini sempurna menggambarkan konflik Tribalist antara kelompok (gangs Jets dan Sharks), yang penuh dengan semangat, identitas kelompok, dan ironi tentang mimpi yang bertabrakan dengan realitas kesukuan yang keras. ‘Wicked Game’ – Chris Isaak: Nuansa lasunya yang sensual dan lirik tentang tarik-menarik yang berbahaya dapat merepresentasikan daya tarik mematikan dari loyalitas kesukuan, bagaimana kita terjerat dalam permainan “kita vs mereka” meski tahu konsekuensinya.
Sang Pengasuh (The Nurturer)
Dari medan pertempuran kelompok, kita dibawa masuk ke ruang yang paling intim dan universal: ikatan antara pengasuh dan anak. “The Nurturer” dimulai dengan pilihan yang menyakitkan: “Left, Right”. Ini mungkin merujuk pada dilema tragis seorang ibu yang harus memilih anak mana yang akan diselamatkan dalam situasi yang tidak mungkin, menggambarkan sisi gelap dari pengasuhan.
Melalui “The Ruthlessness of Rearing” dan “Cases Like Mine”, Dias, dengan mengutip penelitian psikologi perkembangan dan ilmu saraf, mengeksplorasi intensitas dan komitmen tanpa kompromi dari naluri keibuan/pengasuhan. Ini bukan sekadar perasaan lembut, tetapi suatu kekuatan biologis dan psikologis yang sangat kuat, terkadang “kejam” dalam prioritas mutlaknya untuk melindungi keturunannya sendiri. “The Surface of Civilisation” adalah metafora yang brilian: Dias berargumen bahwa lapisan tipis peradaban kita sepenuhnya bergantung pada lautan pengasuhan yang tak terlihat di bawahnya. Tanpa pengasuhan yang konstan dan rela berkorban sejak bayi, tidak ada budaya, bahasa, atau masyarakat yang dapat bertahan.
Bab-bab seperti “The Surrendering” dan “The Rose” menggambarkan kelembutan, kerentanan, dan keindahan dalam pengasuhan. Namun, Dias tidak romantis. “Life’s Longing” menyentuh dorongan evolusioner yang mendalam untuk meneruskan gen dan merawat kehidupan. Pengasuhan, dalam pandangan ini, adalah cara kita melampaui kematian individu (Tamer of Terror) melalui kelangsungan hidup anak-anak kita. Kisah “All the Annas”—mungkin merujuk pada banyaknya anak atau ibu dengan nama yang sama yang menghadapi tantangan serupa—menegaskan universalitas pengalaman ini sekaligus keragamannya.
Tarik-Menarik antara Kelompok dan Kasih Sayang
Hubungan antara The Tribalist dan The Nurturer adalah jantung dari narasi bagian ini. Keduanya adalah tentang ikatan dan perlindungan. The Tribalist memperluas lingkaran pengasuhan dan loyalitas melampaui keluarga inti ke kelompok yang lebih besar (suku, bangsa, agama). Ia me-nawarkan rasa aman kolektif dan identitas yang diperluas. Namun, di sinilah konflik muncul.
The Nurturer seringkali tidak memihak dan berfokus pada yang terdekat dan paling rentan. The Tribalist, sebaliknya, sangat memihak dan dapat menuntut pengorbanan individu untuk kelompok, atau bahkan kekerasan terhadap kelompok luar. Bab “The Ruthlessness of Rearing“ bisa dibaca sebagai cermin dari “The Dogs”; yang satu adalah kekuatan protektif yang terfokus pada keluarga, yang lainnya adalah kekuatan protektif yang terdistorsi menjadi agresi terhadap kelompok luar. Naluri untuk melindungi “milik kita” dapat dengan mudah dialihkan dari anak kita sendiri ke ideologi atau kelompok kita, dengan logika yang sama tentang prioritas dan kesetiaan mutlak.
Dias menunjukkan bahwa peradaban berada di persimpangan dua kekuatan ini. Di satu sisi, kita membutuhkan The Tribalist dalam bentuknya yang positif—sebagai rasa kebersamaan, kooperasi, dan solidaritas sosial yang memperluas rasa saling memiliki. Di sisi lain, kita mem-butuhkan etika universal yang dapat melampaui batas-batas kesukuan. Di sinilah The Nurturer menawarkan pelajaran penting: kemampuannya untuk melihat kerentanan mutlak dan mem-berikan kasih sayang tanpa syarat. Jika etika The Nurturer—perhatian terhadap yang paling rentan—dapat diperluas melampaui ikatan darah atau kelompok, itulah dasar dari kemanusiaan universal.
Seperti yang dikemukakan oleh filosof Nel Noddings dalam etika care-nya, tanggapan terhadap kebutuhan orang lain adalah fondasi moral. Sementara itu, ajaran Islam menekankan “rahmatan lil ‘alamin” (menjadi rahmat bagi seluruh alam), sebuah konsep yang memperluas lingkaran kepedulian dan pengasuhan (rahmah) hingga mencakup semua ciptaan, melampaui batas suku, bangsa, atau agama.
Kesimpulan mendalam dari kedua bagian ini adalah pengakuan bahwa masa depan manusia bergantung pada kemampuan kita untuk memperluas lingkaran The Nurturer sambil melunakkan bias sempit The Tribalist. Kita harus belajar untuk melihat kerentanan dan kemanusiaan dalam “wajah” anggota kelompok lain, untuk merespons mereka bukan sebagai “The Dogs” melainkan sebagai “All the Annas”—individu yang membutuhkan pengakuan dan perlindungan. Dengan kata lain, kita harus merawat bukan hanya anak-anak kita sendiri, tetapi juga “anak-anak” dari peradaban global yang rapuh ini. Hanya dengan merangkul tegangan kreatif antara ikatan kelompok dan kasih sayang universal, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif dan manusiawi.
Inilah lagu untuk THE NURTURER (Sang Pengasuh): ‘Time After Time’ – Cyndi Lauper: Lagu ini adalah janji pengasuhan yang tak goyah: “Jika terjatuh, aku akan menangkapmu.” Ia mewakili kesetiaan, kesabaran, dan kehadiran konstan yang menjadi ciri The Nurturer. ‘Reach Out, I’ll Be There’ – Four Tops: Ini adalah seruan langsung dari The Nurturer: penawaran dukungan tanpa syarat. Dalam kegembiraan Motown-nya, terdapat kekuatan besar dari pengasuhan yang proaktif dan siap siaga.
Romansa dan Penyelamatan—Dua Dorongan Menuju Keterhubungan yang Luar Biasa
Setelah menjelajahi ikatan sosial dan pengasuhan, Dexter Dias membawa kita ke dalam dua ranah yang mendorong manusia melampaui batas-batas dirinya: daya tarik erotis yang kompleks dan dorongan heroik untuk menyelamatkan orang asing. Dalam “The Romancer” dan “The Rescuer”, kita menyelami motivasi yang dapat mengobarkan hati dengan cinta atau membakarnya dengan keberanian moral, keduanya adalah kekuatan yang mendefinisikan sekaligus mengangkat kondisi manusia.
Sang Perebut Hati (The Romancer)
Bagian ini dibuka dengan “The Gift”—sebuah metafora untuk daya tarik seksual dan romantis, sebuah pemberian evolusioner yang memastikan kelangsungan reproduksi tetapi telah ber-kembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dalam budaya manusia. Namun, hadiah ini datang dengan “The Lie”. Di sini, Dias, dengan merujuk pada psikologi evolusioner (seperti karya David Buss dan Geoffrey Miller), mengeksplorasi ilusi dan strategi yang melekat dalam permainan percintaan: pameran status, sinyal kesiapan berkomitmen, dan penipuan diri sendiri. “Carriages and White Horses” melambangkan fantasi romantis, gambaran ideal yang kita proyeksikan pada orang lain, sering kali jauh dari kenyataan mereka yang sebenarnya.
Namun, Dias tidak sinis. Dalam “Something Beyond All That”, ia mengakui bahwa romansa dan cinta seksual memiliki dimensi transendental. Ini bukan hanya tentang gen atau status, tetapi tentang pencarian makna, keindahan, dan penyatuan dengan yang lain. “The Fever” meng-gambarkan intensitas obsesif dari ketertarikan romantis, keadaan pikiran yang terhipnotis yang dapat mengabaikan logika dan konsekuensi. Filsuf Roland Barthes dalam A Lover’s Discourse membedah bahasa cinta sebagai sebuah sistem tanda yang penuh dengan kekosongan dan kerinduan. Sementara itu, penyair sufi Jalaluddin Rumi melihat cinta erotis sebagai metafora dan jalan menuju cinta Ilahi—”The Gift” yang tertinggi adalah kemampuan untuk mencintai itu sendiri, sebuah kekuatan yang membebaskan jiwa dari keterasingan.
THE ROMANCER (Sang Perebut Hati) dapat dinikmati dalam alunan nyanyian ini: ‘Bang Bang (My Baby Shot Me Down)’ – Déborrah Morgane: Lagu ini menangkap sisi tragis dan intens dari romansa—cinta sebagai kekuatan yang menghancurkan, gairah yang berakhir dengan luka. Ini adalah The Romancer yang terluka. Mazurka in A Minor, Op. 68, No. 2 – Chopin: Potongan piano melankolis nan intim ini mewakili kerinduan, kerapuhan, dan keindahan yang mendalam dari cinta yang tidak terucapkan atau yang telah berlalu. ‘Do You Love Me’ – The Contours: Disarankan oleh seorang untuk orang lain, lagu yang penuh energi dan keraguan ini menangkap kegelisahan, kerentanan, dan kebutuhan akan pengakuan yang menjadi inti dari The Romancer.
Sang Penyelamat (The Rescuer)
Dari ranah intim romansa, kita dibawa ke medan luas tanggung jawabi moral. “The Rescuer” dibuka dengan referensi Shakespeare yang dalam: “He to Hecuba”. Ini merujuk pada monolog Hamlet yang mempertanyakan bagaimana seorang aktor dapat menangisi ratu mitos, semen-tara dia sendiri tidak tergerak oleh penderitaan nyata. Inilah teka-teki inti: mengapa kita bisa menangis untuk karakter fiksi tetapi acuh tak acuh terhadap penderitaan nyata di depan kita? Ini adalah kisah orang-orang yang menyelamatkan Yahudi selama Holocaust, merujuk pada konsep “altruisme heroik”.
Jika dicerminkan dalam sebuah nyanyian maka lagu-lagu inilah yang menggambarkan THE RESCUER (Sang Penyelamat): ‘I Wanna Be Your Dog’ – The Stooges: Pilihan yang provokatif. Bisa jadi ini mewakili kerendahan hati total dari The Rescuer—keinginan untuk menjadi alat, pelayan, bagi mereka yang membutuhkan, menanggalkan ego sepenuhnya. ‘Weather With You’ – Crowded House: Metafora yang sempurna: seorang Rescuer membawa “cuacanya” sendiri—harapan, ketahanan, perlindungan—ke dalam situasi yang paling gelap. Ini tentang membawa cahaya ke dalam penderitaan orang lain.
Melalui “The Naming of Parts” (mungkin merujuk pada proses mengidentifikasi korban atau masalah), “The Cairo”, dan “The Other Side of the Mountain”, Dias membawa kita pada perjalanan konkret para penyelamat—mereka yang menyelundupkan orang keluar dari rezim opresif, membantu korban perdagangan manusia, atau mengambil risiko pribadi yang besar untuk orang asing. “The Road” dan “The Line to Almaty” melambangkan jalan berbahaya yang ditempuh oleh para penyelamat dan mereka yang diselamatkan.
Dias menggali psikologi di balik tindakan heroik ini. “The Problem of Us” membahas dilema mendasar: mengapa kita sering kali membantu “kita” (in-group) tetapi mengabaikan “mereka” (out-group)? “All the Elaines” (menggemakan “All the Annas” dari bagian The Nurturer) adalah upaya untuk memanusiakan korban, melihat wajah individu dalam massa penderitaan. Penyelamat-an sering kali dimulai ketika orang asing yang menderita berhenti menjadi statistik dan menjadi seseorang—seorang “Elaine”.
Bab-bab seperti “A Place of Myth and Legend”, “How It Happens”, “The Turning”, dan “A Year in the Life” menelusuri momen-momen transformatif yang mengubah orang biasa menjadi penyelamat. Ini sering kali bukan tentang keberanian yang luar biasa sejak lahir, tetapi tentang pilihan bertahap, kesadaran yang tiba-tiba, atau ketidakmampuan untuk berpaling setelah menyadari suatu kebenaran. “The Choice” adalah intinya: momen di mana seseorang me-mutuskan untuk bertindak meskipun ada risiko. Filsuf Emmanuel Levinas akan menyebutnya sebagai tanggapan etis terhadap “Wajah Orang Lain” yang menuntut pertanggungjawaban mutlak dari kita. Dalam tradisi Islam, konsep “al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar” (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) bukan hanya kewajiban kolektif, tetapi panggilan individu untuk bertindak demi keadilan, bahkan—seperti diingatkan oleh banyak hadis—”dengan tangan, atau lidah, atau (setidaknya) dengan hati”.
Namun, Dias juga jujur. “Outliers” mengakui bahwa para penyelamat sering kali adalah orang-orang yang tidak biasa, dengan kombinasi empati (Perceiver of Pain), keberanian, dan jaringan dukungan tertentu. Dan “Take the Weather with You” mungkin merujuk pada beban psikologis yang dibawa oleh para penyelamat—trauma sekunder, kelelahan, dan rasa tanggung jawab yang tak pernah usai.
Dari Daya Tarik Pribadi ke Tanggung Jawab Universal
Hubungan antara The Romancer dan The Rescuer terletak pada konsep “Something Beyond All That”. Keduanya adalah dorongan yang menarik kita keluar dari diri sendiri menuju orang lain. The Romancer melakukannya melalui daya tarik dan keinginan, sering kali terfokus pada satu orang yang dipandang istimewa. The Rescuer melakukannya melalui belas kasih dan tanggung jawab, yang dapat diperluas kepada banyak orang asing.
Namun, terdapat ketegangan yang dalam. The Romancer sering kali egois (mencari kebahagiaan atau pemenuhan diri), sementara The Rescuer pada dasarnya altruistik (mengutamakan ke-sejahteraan orang lain). The Romancer dihalangi oleh “The Lie” dan fantasi, sedangkan The Rescuer harus menghadapi kebenaran yang keras dan tidak menyenangkan dari penderitaan manusia. Namun, keduanya membutuhkan imajinasi: The Romancer membayangkan kehidupan bersama yang indah, The Rescuer membayangkan dunia di mana penderitaan orang itu dapat diringankan.
Kesimpulan mendalam dari kedua bagian ini adalah bahwa manusia memiliki kapasitas ganda untuk keterhubungan yang mendalam. Kita dapat terhubung melalui keintiman erotis dan romantis, yang memberikan makna dan sukacita pada kehidupan individu. Tetapi kita juga dapat—dan dalam pandangan etis, kita harus—terhubung melalui solidaritas dan tindakan penyelamatan, yang memberikan makna dan martabat pada kehidupan kolektif kita. Masa depan kemanusiaan mungkin bergantung pada kemampuan kita untuk memperluas energi dan komitmen yang kita investasikan dalam The Romancer—pengabdian, perhatian, keinginan untuk melihat yang terbaik dalam diri seseorang—ke dalam wilayah The Rescuer. Ini berarti mengubah cinta yang terfokus menjadi tanggung jawab yang diperluas. Seperti yang diungkap-kan oleh penyair W. H. Auden, kita harus “mencintai satu sama lain atau mati.” Tetapi cinta di sini bukan hanya romansa; itu adalah agape, cinta kasih yang aktif dan berkorban untuk sesama.
Dalam konteks global dan Indonesia khususnya, memahami The Rescuer sangat penting untuk membangun masyarakat yang peduli, yang tidak hanya fokus pada kelompoknya sendiri (The Tribalist) tetapi juga pada kaum marginal, pengungsi, dan mereka yang terpinggirkan. Mema-hami The Romancer mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan manusia, jauh di balik label-label sosial, dan kebutuhan akan keintiman yang otentik di dunia yang semakin terfragmentasi.
Dengan kata lain, kedua “tipe” ini mengajak kita untuk hidup dengan lebih penuh: untuk men-cintai lebih dalam dan lebih luas, untuk melihat bukan hanya kecantikan yang kita idamkan tetapi juga penderitaan yang membutuhkan respons kita. Mereka adalah panggilan ganda dari jiwa manusia: untuk terhubung dan untuk menyelamatkan.
Lagi-lagi Datang Sang Kerabat—Siklus dan Simfoni Akhir Kemanusiaan
Bagian penutup dari eksplorasi sepuluh tipe manusia ini bukanlah akhir yang linear, melainkan sebuah pengembalian—sebuah da capo dalam simfoni kompleks kondisi manusia. Judulnya, “Again Came the Kinsman”, adalah petunjuk kunci. Setelah perjalanan panjang melalui belas kasih, pengucilan, teror, keindahan, agresi, kesukuan, pengasuhan, romansa, dan penyelamat-an, kita kembali lagi ke titik awal yang paling purba dan paling fundamental: ikatan darah dan keluarga. Tetapi, setelah semua yang telah kita jelajahi, kita kembali dengan pemahaman yang baru, lebih dalam, dan lebih bernuansa.
Lagi-lagi Datang Sang Kerabat (Again Came the Kinsman)
Bagian ini dibuka dengan gambaran yang primitif dan mengancam: “The Wolves”. Metafora ini bekerja dalam beberapa lapisan. Pada satu sisi, ia mewakili ancaman eksternal dari dunia liar—bahaya yang dihadapi nenek moyang kita yang membentuk kebutuhan akan kelompok keluarga yang kohesif untuk bertahan hidup. Di sisi lain, “serigala” bisa juga melambangkan naluri-naluri buas di dalam diri kita sendiri—The Aggressor, ketakutan akan kelaparan, atau dorongan egois yang harus dijinakkan oleh ikatan kekeluargaan. Dari ancaman inilah muncul “The Storm”, sebuah kekacauan yang menguji hingga ke batas kekuatan ikatan-ikatan itu.
Melalui “Silent Flight”, Dias mungkin menceritakan kisah pelarian atau pengasingan—seorang individu yang harus meninggalkan keluarganya, atau sebaliknya, sebuah keluarga yang diam-diam melarikan diri dari ancaman. Ini adalah momen di mana ikatan keluarga direnggangkan hingga hampir putus oleh tekanan eksternal yang besar. Namun, bagian yang paling mengharu-kan dan mendalam kemungkinan terletak pada “For 16 Years”. Ini adalah rentang waktu yang panjang, mungkin mengacu pada sebuah pengorbanan tanpa henti, penantian yang tak kunjung usai, atau komitmen seorang kerabat (seorang ibu, ayah, saudara) yang bertahan melampaui batas-batas rasional. Di sini, Dias menunjukkan bahwa The Kinsman bukan sekadar naluri biologis yang sederhana. Ia adalah sebuah proyek seumur hidup, sebuah pilihan yang diperbarui setiap hari, sebuah ketekunan yang membentuk identitas.
Lagu untuk tipe AGAIN CAME THE KINSMAN (Lagi-lagi Sang Kerabat): ‘Fix You’ – Coldplay: Dipilih oleh seorang untuk saudaranya, ini adalah lagu The Kinsman yang sejati. Ini tentang kehadiran yang tak tergoyahkan, upaya untuk menyembuhkan, dan janji untuk berdiri di samping keluarga meski dalam kegagalan. ‘I’m Sticking With You’ – Velvet Underground/The Decemberists: Lagu sederhana dan langsung ini adalah deklarasi kesetiaan keluarga yang paling murni. Ini adalah suara The Kinsman dalam bentuknya yang paling polos dan paling kuat: komitmen tanpa syarat.
Akhirnya, kita tiba pada frasa penutup yang sederhana namun dahsyat: “Always In”. Ini adalah pernyataan final tentang sifat ikatan kekeluargaan. Ia selalu ada, selalu aktif, selalu menjadi bagian dari kita. Bukan berarti ikatan ini selalu harmonis atau positif—konflik keluarga bisa menjadi yang paling pahit—tetapi ia tak terhapuskan. Ia adalah “latar belakang default” psikologis kita, kerangka acuan pertama dari mana kita memahami dunia dan menempatkan diri kita di dalamnya. Seperti yang ditunjukkan oleh antropolog evolusioner seperti Robin Dunbar dengan “Angka Dunbar”-nya, kapasitas kognitif kita untuk hubungan sosial yang bermakna secara evolusioner berlapis, dengan keluarga inti berada di inti terdalam. Psikolog perkembangan seperti John Bowlby dengan teori kelekatan (attachment theory)-nya juga menunjukkan bagaimana pola ikatan awal dengan pengasuh (biasanya keluarga) membentuk peta hubungan kita sepanjang hidup.
Lingkaran yang Kembali ke Titik Awal, Namun dengan Arti Baru
Alur naratif bagian ini adalah alur siklus. Kita mulai dan mengakhiri dengan keluarga. Namun, perjalanan melalui sembilan “tipe” sebelumnya telah mengubah makna dari The Kinsman ini.
- The Kinsman dan The Nurturer: The Kinsman adalah ekstensi dari The Nurturer. Jika The Nurturer berfokus pada pengasuhan anak, The Kinsman memperluas lingkaran pengorbanan dan loyalitas itu kepada orang tua, saudara kandung, sepupu, dan kerabat dekat lainnya. “For 16 Years” bisa menjadi kisah seorang saudara merawat saudaranya yang sakit, atau orang tua yang tak kenal lelah mencari anaknya yang hilang—sebuah manifestasi dari The Nurturer yang telah melampaui masa kanak-kanak.
- The Kinsman dan The Tribalist: The Kinsman adalah bentuk paling dasar dari The Tribalist. Kesetiaan kesukuan dan nasionalisme adalah perluasan metaforis dari loyalitas keluarga. “The Wolves” yang mengancam keluarga bisa, dalam skala yang lebih besar, menjadi “musuh” yang mengancam bangsa, memobilisasi The Tribalist dengan menggunakan logika dan emosi yang sama dengan The Kinsman.
- The Kinsman dan The Rescuer: Seringkali, dorongan untuk menyelamatkan bermula dari dalam lingkaran keluarga sebelum dapat diperluas kepada orang asing. “Silent Flight” bisa jadi adalah tindakan penyelamatan seorang kerabat. Kisah-kisah heroik dalam The Rescuer sering kali didorong oleh narasi bahwa korban adalah “seperti keluarga kita”.
- Konflik dengan “Tipe” Lain: Namun, The Kinsman juga bisa berbenturan dengan tipe lain. Ia bisa berbenturan dengan The Romancer (misalnya, ketika keluarga menentang pilihan pasangan), dengan The Perceiver of Pain (ketika loyalitas keluarga membuat kita mengabaikan penderitaan yang disebabkan oleh anggota keluarga kita sendiri), atau bahkan dengan The Ostraciser (ketika kita mengucilkan seseorang dari keluarga).
Filsuf Konfusianisme, Mengzi (Mencius), berargumen bahwa rasa kemanusiaan (ren) bermula dari kasih sayang terhadap keluarga, dan dari sana berkembang secara bertahap untuk men-cakup semua orang. Ini adalah visi optimis tentang perluasan The Kinsman. Namun, filsuf seperti Friedrich Nietzsche mungkin akan memperingatkan bahwa moralitas yang berpusat pada keluarga (“moralitas kawanan”) dapat membatasi kemauan individu yang kuat. Dalam tradisi Islam, konsep “silaturrahim” (menyambung tali kekeluargaan) adalah kewajiban agama yang utama, tetapi juga diseimbangkan dengan konsep keadilan universal (‘adl) yang men-syaratkan bahwa ikatan keluarga tidak boleh mengalahkan kebenaran dan keadilan (QS. An-Nisa’: 135).
Dengan mengakhiri bukunya pada The Kinsman, Dias menyimpulkan bahwa sepuluh tipe manusia itu bukanlah hierarki, melainkan sebuah ekologi psikologis yang dinamis. The Kinsman adalah fondasi—tanah subur tempat naluri-naluri lain tumbuh. Ia adalah sumber keamanan pertama kita dan sekolah pertama kita untuk belajar tentang cinta, konflik, pengorbanan, dan loyalitas. Ia adalah alasan pertama kita untuk bertahan hidup dan berjuang (“The Storm”).
Namun, “kembalinya” sang kerabat di akhir perjalanan ini adalah sebuah pengingat yang sobering. Sebagian besar konflik manusia yang besar—perang suku, balas dendam keluarga, nepotisme, etnosentrisme—berasal dari kecenderungan ini ketika ia berubah menjadi favoritisme buta atau permusuhan terhadap kelompok lain. Masa depan kemanusiaan yang lebih damai bergantung pada kemampuan kita untuk menghormati kekuatan The Kinsman tanpa menjadi tawanannya. Kita harus mengakui ikatan khusus ini sebagai bagian dari diri kita yang “Always In”, sementara juga secara aktif memupuk The Perceiver of Pain dan The Rescuer dalam diri kita untuk memperluas lingkaran kepedulian kita melampaui batas-batas gen dan nama keluarga.
Pada akhirnya, The Ten Types of Human adalah sebuah peta untuk navigasi diri. Dengan mengenali sepuluh “kita” yang berbeda dalam diri kita ini—dari The Kinsman yang paling dasar hingga The Rescuer yang paling luhur—kita memiliki pilihan. Kita dapat memahami apa yang mendorong kita, apa yang menakuti kita, dan apa yang menginspirasi kita. Dan dengan pemahaman itu, kita mungkin, seperti yang diharapkan Dias, dapat memilih dengan lebih bijak jenis manusia seperti apa yang kita ingin menjadi, baik secara individu maupun kolektif.
Catatan Akhir: Suara Buku—Gema, Tanggung Jawab, dan Panggilan untuk Bertindak
Epilog The Ten Types of Human, yang diberi judul puitis “The Sound of the Book”, bukanlah sekadar penutup. Ia adalah sebuah resonansi. Setelah perjalanan epik melalui sepuluh lanskap psikologis manusia—dari kedalaman belas kasih hingga puncak kekejaman, dari keintiman keluarga hingga heroisme untuk orang asing—Dexter Dias tidak meninggalkan kita dengan sebuah kesimpulan akademis yang dingin. Sebaliknya, dia meninggalkan kita dengan sebuah gema: suara dari semua kisah yang telah diceritakan, suara dari ilmu pengetahuan yang telah dijelajahi, dan yang paling penting, suara dari sebuah pertanyaan yang mendesak yang sekarang bergema dalam diri pembaca.
Judul epilog ini adalah sebuah metafora yang brilian. Sebuah buku, setelah dibaca, tidak benar-benar diam. Ia terus berbunyi dalam pikiran dan hati pembacanya. “Suara” yang dimaksud Dias adalah suara penderitaan yang telah didokumentasikan, suara keberanian yang telah dikisahkan, dan suara dari mekanisme psikologis yang sekarang telah terungkap. Setelah kita memahami bahwa kita bukanlah satu diri yang tetap, melainkan sebuah “kumpulan kemungkinan” yang diaktifkan oleh keadaan, maka kita tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Pengetahuan itu sendiri menimbulkan tanggung jawab.
Epilog ini berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman dan tindakan. Dias menyatukan benang merah dari seluruh penjelajahannya: bahwa kesepuluh “tipe” itu—The Perceiver of Pain, The Ostraciser, The Tamer of Terror, The Beholder, The Aggressor, The Tribalist, The Nurturer, The Romancer, The Rescuer, dan The Kinsman—semuanya ada dalam diri kita masing-masing. Mereka bukan label untuk orang lain, tetapi potensi dalam diri kita sendiri. Pertanyaan yang menentukan, seperti yang mungkin digaungkan dalam epilog, adalah: potensi mana yang akan kita beri makan? Suara mana yang akan kita perdengarkan?
Dias menegaskan bahwa struktur psikologis kita bukanlah takdir. Memahami bahwa The Ostraciser dan The Tribalist dapat dengan mudah diaktifkan oleh ketakutan (The Tamer of Terror) justru memberi kita kekuatan untuk melawannya. Memahami “The Cognitive Cost of Compassion” (biaya kognitif dari belas kasih) dari Bagian I bukanlah pembenaran untuk ketidakpedulian, melainkan penjelasan mengapa kita harus secara sengaja dan aktif melatih The Perceiver of Pain dan The Rescuer kita. Ilmu pengetahuan di sini bukan untuk determinisme, tetapi untuk pembebasan—alat untuk mengenali perangkap pikiran kita sehingga kita dapat menghindarinya.
Epilog ini pasti menyentuh kembali kisah-kisah pembuka yang memilukan—seperti kisah Al Amin yang dibakar hidup-hidup atau kasus-kasus kekejaman lainnya yang menandai perjalanan Dias sebagai pengacara hak asasi manusia. Dengan kerangka sepuluh tipe, kita sekarang dapat melihat peristiwa-peristiwa itu bukan sebagai monster yang tak dapat dipahami, tetapi sebagai hasil dari kombinasi beracun dari The Tribalist yang menyala-nyala, The Ostraciser yang menguat, The Perceiver of Pain yang dimatikan, dan The Aggressor yang dilepaskan. Pemahaman ini membuat kejahatan itu, dalam kata-kata Hannah Arendt, semakin “biasa” (banal), dan karena itu semakin dapat dicegah melalui kewaspadaan sosial dan desain institusi yang cermat.
Dias, melalui “suara buku”-nya, kemungkinan besar mengutip atau merujuk pada pemikir yang melihat manusia sebagai proyek yang belum selesai. Filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre meng-atakan bahwa “manusia dikutuk untuk bebas”. Setelah membaca buku ini, kita dikutuk dengan kebebasan yang lebih sadar: kebebasan untuk memilih “tipe” manusia seperti apa yang akan kita wujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Apakah kita akan memilih untuk memperluas lingkaran The Kinsman dan The Nurturer kita menjadi The Rescuer yang universal? Atau apakah kita akan membiarkan ketakutan dan prasangka mempersempitnya? Dalam konteks Islam, epilog ini beresonansi dengan konsep “khalifah” (wakil Tuhan) di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dibekali dengan potensi (fitrah) untuk mengenali yang baik dan yang buruk, dan dibebani dengan tanggung jawab untuk memilih yang baik. The Ten Types dapat dilihat sebagai penjelasan psikologis dari berbagai kecenderungan (fitrah) itu, dan panggilan dalam epilog adalah panggilan untuk memenuhi amanah sebagai khalifah dengan memilih jalan yang membawa rahmat.
Bagi Dias buku bisa berfungsi sebagai alat dan senjata. Epilog “The Sound of the Book” pada akhirnya adalah sebuah panggilan untuk kesadaran dan komitmen. Buku ini, bagi Dias, bukan hanya sebuah eksplorasi intelektual; ia adalah sebuah alat—dan bahkan senjata—dalam pertarungan untuk menentukan masa depan kemanusiaan. Suaranya adalah pengingat bahwa dalam setiap situasi sosial, politik, atau personal, kita memiliki pilihan untuk mengaktifkan satu “diri” di atas yang lain.
Masa depan tidak ditentukan oleh “tipe” mana yang paling kuat, tetapi oleh “tipe” mana yang paling gigih kita pelihara dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sistem pendidikan kita, dan dalam norma-norma masyarakat kita. Apakah kita akan membangun masyarakat yang memicu The Aggressor dan The Ostraciser, atau yang memupuk The Perceiver of Pain dan The Rescuer?
Dengan demikian, epilog ini menolak untuk mengakhiri cerita. Ia justru memulai sebuah cerita baru—cerita di mana pembaca menjadi aktornya. “Suara buku” itu sekarang adalah suara Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengan pemahaman ini? Bagaimana Anda akan merespons penderitaan yang kini Anda pahami mekanisme pengabaiannya? Kepada siapa Anda akan memperluas lingkaran pengasuhan dan kesetiaan Anda? Dalam kata-kata penyair Derek Walcott yang mungkin digemakan oleh semangat epilog ini: “Either I’m nobody, or I’m a nation.” Setelah membaca The Ten Types of Human, kita menyadari bahwa kita memang adalah sebuah “bangsa”—bangsa dari berbagai kemungkinan diri. Dan kedaulatan atas bangsa internal itu sepenuhnya ada di tangan kita. Tugas kita adalah memerintahnya dengan bijaksana, dengan penuh belas kasih, dan dengan keberanian untuk bertindak. Bunyinya mungkin telah berakhir, tetapi gaungnya—dan tanggung jawab yang dibawanya—baru saja dimulai.
Dexter Dias tidak hanya menulis sebuah buku; dia mengkurasi sebuah simfoni pengalaman manusia. Lampiran musik dalam “The Sound of the Book” bukan sekadar daftar lagu, melainkan partitur emosional yang memberikan kedalaman dan resonansi baru pada Sepuluh Tipe, mengubah teori psikologis menjadi sebuah perjalanan puitis yang dapat dirasakan. Ekspresi Sepuluh Tipe itu bisa kita temukan di dalam lagu-lagu yang dihimpun Dias tersebut.
Dengan kurasi musik ini, Dias menunjukkan bahwa Sepuluh Tipe bukanlah kategori kering, tetapi melodi hidup yang terus bergema dalam pengalaman kita. Simfoni manusia yang utuh
Setiap lagu adalah jendela ke dalam salah satu ruang jiwa manusia, mengingatkan kita bahwa psikologi adalah sebuah seni, dan pemahaman tentang diri sendiri adalah sebuah simfoni yang belum selesai—dimulai dengan rasa sakit orang asing, dijalani melalui ikatan dan konflik, dan diakhiri dengan sebuah ode untuk sukacita dan kerinduan akan kebebasan yang lebih besar. Buku ini, seperti daftar putarnya, mengajak kita bukan hanya untuk memahami, tetapi untuk merasakan kompleksitas yang luar biasa itu, dan mungkin, untuk memilih melodi mana yang akan kita nyanyikan bersama dalam kehidupan kita.
Manusia selalu ada sisi kekuatan harapan, sebuah Koda penuh harapan yang jika diekspresikan dalam simfoni maka ia ada dalam simfoni ini:
- ‘Here Comes the Sun’ – The Beatles: Setelah perjalanan melalui kegelapan dan terang kemanusiaan, lagu ini adalah kebangkitan, harapan, dan kehangatan. Ia menandakan pemahaman (The Perceiver of Pain yang baru) dan kemungkinan baru.
- Symphony No. 9 ‘Ode to Joy’ – Beethoven: Simfoni universal tentang persaudaraan manusia. Ini adalah aspirasi tertinggi dari buku ini—ketika semua tipe bekerja bersama menuju sukacita kolektif, mengatasi pengucilan dan agresi.
- ‘I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free’ – Nina Simone: Disarankan oleh seorang individu (Ubah), lagu ini adalah titik temu antara penderitaan, pengucilan, dan harapan. Ini adalah suara dari setiap tipe yang tertindas, dan juga seruan akhir buku: pemahaman (The Ten Types) adalah langkah pertama menuju kebebasan itu—kebebasan untuk memilih manusia seperti apa kita akan menjadi.
Cirebon, 9 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Daftar Pustaka
Alatas, S. H. (1977). The myth of the lazy native: A study of the image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th century and its function in the ideology of colonial capitalism. Frank Cass.
Al-Attas, S. M. N. (1980). The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education. Muslim Youth Movement of Malaysia.
Appiah, K. A. (2006). Cosmopolitanism: Ethics in a world of strangers. W. W. Norton & Company.
Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil. Viking Press.
Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3
Barthes, R. (1978). A lover’s discourse: Fragments (R. Howard, Trans.). Hill and Wang.
Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation (S. F. Glaser, Trans.). University of Michigan Press.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Hogarth Press.
Buss, D. M. (1994). The evolution of desire: Strategies of human mating. Basic Books.
Camus, A. (1955). The myth of Sisyphus and other essays (J. O’Brien, Trans.). Knopf. (Original work published 1942)
Damono, S. D. (1989). Pada suatu hari nanti. Pustaka Jaya.
Dias, D. (2017). The ten types of human: A new understanding of who we are and who we can be. William Heinemann.
Dunbar, R. I. M. (1992). Neocortex size as a constraint on group size in primates. Journal of Human Evolution, 22(6), 469–493. https://doi.org/10.1016/0047-2484(92)90081-J
Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2004). Why rejection hurts: A common neural alarm system for physical and social pain. Trends in Cognitive Sciences, 8(7), 294–300. https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.05.010
Fanon, F. (1963). The wretched of the earth (C. Farrington, Trans.). Grove Press.
Ghazali, A. H. (n.d.). Ihya ulum al-din [The revival of the religious sciences].
Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. I & II. Journal of Theoretical Biology, 7(1), 1–52. https://doi.org/10.1016/0022-5193(64)90038-4
Hamka. (1939). Tasawuf modern. Pustaka Panjimas.
Harlow, H. F. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13(12), 673–685. https://doi.org/10.1037/h0047884
Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychology Review, 10(3), 252–264. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1003_4
Levinas, E. (1969). Totality and infinity: An essay on exteriority (A. Lingis, Trans.). Duquesne University Press. (Original work published 1961)
Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view. Harper & Row.
Noddings, N. (1984). Caring: A feminine approach to ethics and moral education. University of California Press.
Oliner, S. P., & Oliner, P. M. (1988). The altruistic personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe. Free Press.
Patterson, O. (1982). Slavery and social death: A comparative study. Harvard University Press.
Sartre, J.-P. (2007). Existentialism is a humanism (C. Macomber, Trans.). Yale University Press. (Original work published 1946)
Singer, T., Seymour, B., O’Doherty, J., Kaube, H., Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2004). Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain. Science, 303(5661), 1157–1162. https://doi.org/10.1126/science.1093535
Slovic, P. (2007). “If I look at the mass I will never act”: Psychic numbing and genocide. Judgment and Decision Making, 2(2), 79–95.
Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (1991). A terror management theory of social behavior: The psychological functions of self-esteem and cultural worldviews. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 24, pp. 93–159). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60328-7
Sontag, S. (2003). Regarding the pain of others. Farrar, Straus and Giroux.
Soroush, A. (2000). Reason, freedom, and democracy in Islam: Essential writings of Abdolkarim Soroush (M. Sadri & A. Sadri, Trans.). Oxford University Press.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Brooks/Cole.
Zimbardo, P. G. (2007). The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil. Random House.
Catatan untuk Sumber-Sumber Khusus:
- Al-Qur’an dan Hadis: Tidak dimasukkan dalam daftar referensi menurut APA, tetapi dikutip dalam teks dengan menyebutkan Surah dan ayat (e.g., QS. Al-Baqarah: 30) atau perawi hadis.
- Karya Klasik (Tanpa Tanggal Penerbitan Asli): Untuk karya seperti Rumi’s Mathnawi atau teks klasik lainnya, hanya disebutkan nama penulis dan judul dalam teks, atau dimasukkan dalam daftar pustaka seperti contoh Al-Ghazali di atas jika dianggap penting untuk dirujuk.
- Karya dalam Bahasa Indonesia (Contoh: Sapardi Djoko Damono): Tetap dimasukkan dalam daftar dengan judul asli dan format sesuai APA.