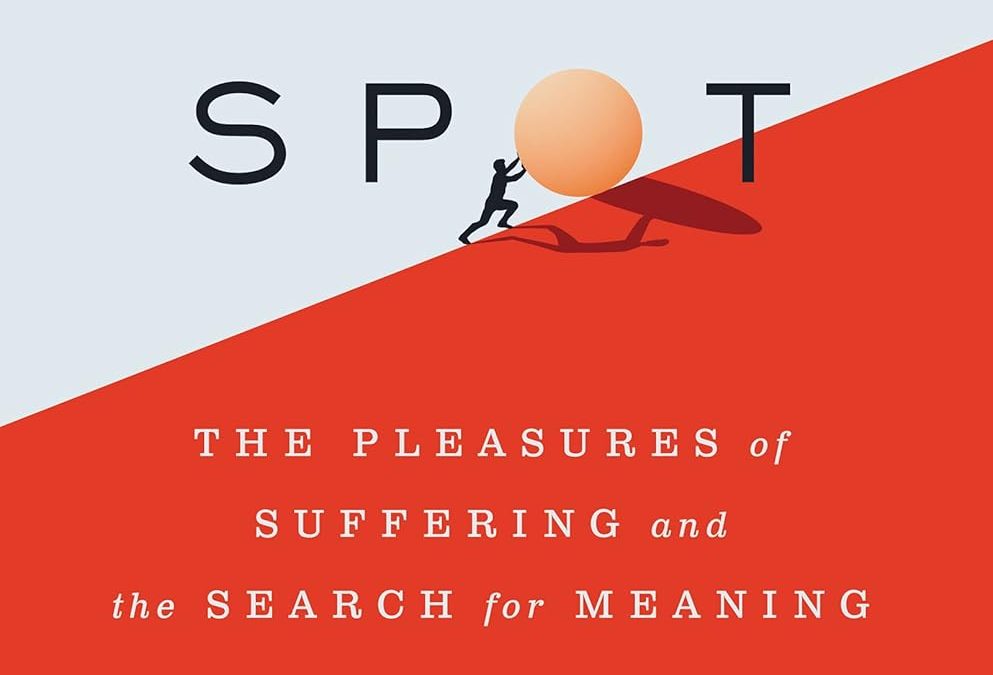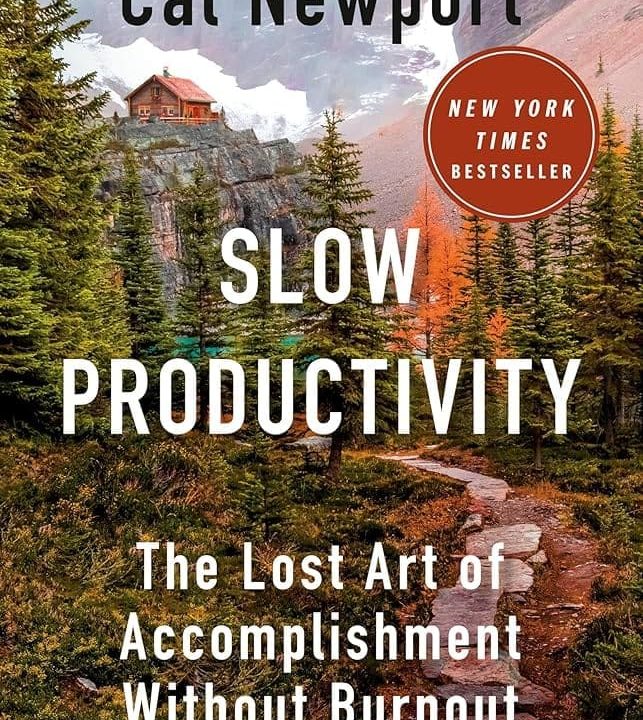Rubarubu #60
The Sweet Spot:
Rasa Sakit Kebahagiaan
The Good Life
Bloom membuka bukunya dengan pertanyaan sederhana namun menjebak: apa itu hidup yang baik? Ia menolak gagasan klasik bahwa hidup terbaik adalah hidup tanpa rasa sakit. Dalam pengantarnya, ia menceritakan berbagai contoh kehidupan nyata: seseorang yang baru me-nyelesaikan maraton dan menangis haru; seorang ayah yang terjaga semalaman mengurus bayi, merasa lelah tetapi juga penuh rasa cinta; seorang relawan di daerah bencana yang bekerja dalam tekanan dan ketakutan tetapi mengakui bahwa masa-masa itulah yang membuat hidupnya bermakna.
Bloom menyebut bahwa manusia merupakan makhluk yang secara misterius tidak senang jika hidupnya terlalu mudah. Kita menginginkan kenyamanan, tetapi kita juga mendambakan tantangan, usaha, bahkan penderitaan terukur. Dalam preface ini, ia menetapkan tesis dasar: hidup yang baik tidak identik dengan hidup yang menyenangkan. Hidup yang baik adalah hidup yang memiliki makna, dan makna hampir selalu menagih harga—usaha, rasa sakit, dan pengorbanan.
Dengan nada personal, Bloom menceritakan bahwa buku ini bukan ajakan untuk memuja penderitaan, tetapi ajakan untuk memahami kapan dan mengapa penderitaan tertentu justru kita cari sendiri, dan bagaimana hal itu membentuk pengalaman hidup yang dipenuhi rasa tujuan.
“If you suffer for something that gives delight, soon the suffering itself can give joy.” — Paul Bloom, The Sweet Spot: The Pleasures of Suffering and the Search for Meaning (2021). Inilah yang dipercaya Bloom. Kutipan ini merangkum aneka cerita yang membentuk napas buku Bloom: pendaki yang merasakan euforia setelah hari-hari berjam-jam menahan dingin dan kelelahan; atlet yang menikmati rasa sakit otot sebagai bukti usaha; pembaca yang memilih menyaksikan film horor untuk ‘merasakan’ keterlibatan emosi; atau relawan yang menjalani pesta amal dengan berjalan berpuluh kilometer sambil merasakan letih sebagai validasi moral.
Professor of Psychology di University of Toronto dan Brooks and Suzanne Ragen Professor Emeritus of Psychology di Yale University ini menegaskan: bukan semua penderitaan sama—beberapa diderita dengan pilihan, tujuan, dan batas yang memberi makna, dan dari sanalah muncul kenikmatan khusus yang bukan sekadar hedonisme kosong. Goodreads+1
Baginya ada ‘sweet spot’ antara pleasure dan suffering. Penulis yang menerima berbagai penghargaan, termasuk Klaus J. Jacobs Research Prize senilai satu juta dolar ini, menempatkan posisinya melawan gagasan hedonistik sederhana (bahwa tujuan utama hidup adalah meng-hindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan). Ia memperkenalkan gagasan motivational pluralism: manusia termotivasi oleh berbagai dorongan—kenikmatan, kebaikan moral, dan pencarian makna—yang seringkali saling tarik-menarik. Dari riset psikologi, sejarah budaya, dan cerita kehidupan nyata, Bloom menyusun argumen bahwa kehidupan yang kaya makna biasa-nya menuntut unsur kesulitan: usaha, pengorbanan, dan kadang penderitaan yang dapat dilihat sebagai “bahan bakar” makna. Namun ia juga memperingatkan terhadap romantisisme penderitaan yang membenarkan semua kesengsaraan sebagai bernilai—penderitaan yang tak dipilih, traumatik, atau acak jarang memberi kebaikan yang sama. HarperCollins+1
Buku ini terasa mengedor-gedor kita dengan pertanyaan: Mengapa kita mengejar penderitaan yang disengaja? Bloom membuka dengan contoh-contoh sehari-hari: dari olahraga berat, permainan teka-teki yang sulit, sampai praktik erotik seperti BDSM—oleh banyak orang dipilih karena memberi “rasa hidup” dan fokus perhatian. Ia membahas mekanisme psikologis: usaha meningkatkan nilai subjek (IKEA effect), ketegangan-pelepasan (relief after strain), dan bagai-mana rasa kesulitan memusatkan perhatian sehingga aktivitas terasa lebih “hidup”. Bloom menautkan bukti eksperimen dan survei untuk menunjukkan fenomena ini. The New Yorker+1. Seperti kata Viktor E. Frankl (psikiater, pencetus logoterapi): “When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.” — Man’s Search for Meaning. Frankl menegaskan bahwa makna sering kali ditemukan dalam bagaimana seseorang me-nanggapi penderitaan yang tak terhindarkan—ide yang bersinggungan dengan argumen Bloom tentang makna sebagai respons, bukan pembenaran penderitaan. Antilogicalism+1
Bloom memakai analogi Goldilocks: terlalu sedikit tantangan = kebosanan dan kehampaan; terlalu banyak = stres dan kehancuran. “Sweet spot” adalah titik dimana tantangan cukup untuk memberi rasa pencapaian dan makna tanpa menyebabkan kerusakan. Di bagian ini ia menyaji-kan studi tentang aliran (flow), gamifikasi, dan praktik sehari-hari yang menambahkan “friksi bermakna” (mis. memasak dari nol, bukan membeli jadi) untuk menggenjot rasa kepuasan. Google Books+1
Penulis yang telah menulis untuk jurnal ilmiah seperti Nature dan Science, serta untuk The New York Times, The New Yorker, dan The Atlantic ini menyelidiki bagaimana tradisi keagamaan menggunakan puasa, ziarah, pengorbanan, dan ritus sebagai sarana mengikat nilai moral dengan pengorbanan fisik/emosional—memberi bukti komitmen. Ia kritis terhadap klaim bahwa semua penderitaan memiliki nilai spiritual inheren: konteks, niat, batasan, dan hasil morallah yang menentukan apakah penderitaan itu membentuk kebajikan atau sekadar siksaan. HarperCollins Bloom menunjuk pada peran narasi: menonton tragedi yang dikendali-kan (fiksi) memberi kesempatan untuk merasakan intensitas emosional tanpa risiko nyata—ini adalah «suffering yang aman» yang memuaskan kebutuhan makna dan rasa terlibat. Platform streaming memberi akses tak terbatas pada kisah-kisah itu sehingga manusia bisa memilih tingkat penderitaan emosional yang ingin mereka alami. The New Yorker
Sebagai penyeimbang, Bloom menekankan bahwa penderitaan acak, traumatis, atau yang disebabkan oleh ketidakadilan struktural jarang memberi makna. Ia mengingatkan agar pembaca tidak menormalisasi atau memuliakan penderitaan kelompok yang rentan. Konteks sosial dan politik, serta kemampuan untuk memilih, memainkan peran kunci dalam apakah penderitaan bisa dibingkai ulang menjadi makna. The New Yorker
The Sweet Spot membahas gagasan-gagasan yang berkaitan dengan derita. Bab pertama, misalnya, tentang Suffer. Ini adalah pintu masuk konseptual: mengapa kita merasakan pen-deritaan? Bloom menguraikan bahwa rasa sakit memiliki fungsi evolusioner—melindungi, memperingatkan, dan memaksa kita berhenti sebelum cedera parah. Namun ia melangkah lebih jauh: selain penderitaan fisik dan emosional yang tidak diinginkan, manusia juga mem-punyai kemampuan unik untuk merasionalisasi serta memaknai penderitaan. Ia menyaji-kan beberapa contoh: orang yang menaiki gunung tinggi meski tahu akan kelelahan; seseorang yang melakukan diet ketat dengan penuh disiplin; penggemar film horor yang merasakan ketegangan sebagai bagian dari kenikmatan. Bloom menyebut bahwa penderitaan dapat menjadi instrumen pembentuk identitas, sesuatu yang membuat kita merasa telah mengerahkan diri sepenuhnya. Penderitaan bukan hanya sensasi, melainkan cerita—dan manusia hidup dari cerita tentang dirinya.
Di bab ini, Bloom membedakan penderitaan terpilih dan tidak terpilih. Yang pertama sering menghasilkan kepuasan; yang kedua lebih rumit dan cenderung traumatik. Namun bahkan penderitaan tak terhindarkan dapat diberi makna ketika seseorang memahami konteks dan tujuannya.
Pada bagian berikutnya Ia menguraikan soal Benign Masochism. ini adalah istilah populer dalam psikologi: benign masochism, yaitu kecenderungan kita menikmati rasa sakit atau ketidaknyamanan “aman”. Contoh utamanya adalah memakan makanan pedas, menonton horor, menaiki roller coaster, atau mengerjakan teka-teki sulit. Kita “merasakan sakit” tetapi tahu itu tidak benar-benar mengancam. Bloom menceritakan bahwa rasa sakit semacam ini memberi kesempatan bagi kita untuk bermain dengan batas sensasi. Ada dimensi neurologis: tubuh melepaskan hormon tertentu (endorfin, dopamin) sebagai respons terhadap ancaman ringan, yang menciptakan kombinasi unik antara stres dan kenikmatan. Ia mengutip penelitian Paul Rozin yang menunjukkan bahwa orang mencari pengalaman ini karena mereka merasakan kontrol terhadap ketakutan.
Melalui kisah para penggemar adrenalin, Bloom menegaskan bahwa kita sering kali mengejar rasa sakit bukan untuk sensasinya saja, tetapi untuk rasa kemenangan atas diri sendiri—sebuah bentuk permainan eksistensial yang hanya mungkin dilakukan oleh makhluk sadar seperti manusia.
Bab An Unaccountable Pleasure memeriksa kenikmatan yang sulit dijelaskan melalui teori hedonis klasik. Mengapa seseorang menikmati meditasi yang menyakitkan? Mengapa orang merasa nikmat saat bekerja keras menyelesaikan esai, merawat tanaman, atau mendaki bukit sendirian? Bloom yang menulis atau menyunting lebih dari delapan buku, termasuk Just Babies, How Pleasure Works, Descartes’ Baby, dan, yang terbaru, Against Empathy” ini me-nyodorkan gagasan bahwa kenikmatan manusia tidak sepenuhnya bergantung pada sensasi fisik. Ada dimensi evaluatif: kita menikmati sesuatu karena kita menilai itu bermakna atau bernilai. Maka muncul kenikmatan yang tampaknya paradoks: rasa lelah di akhir hari, rasa sakit pada otot, ketegangan emosional dari cerita sedih.
Dalam bab ini ia menampilkan penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa kesulitan justru meningkatkan nilai suatu aktivitas (IKEA effect). Kita menghargai apa yang kita usahakan. Bloom berkata bahwa jika hidup penuh kemudahan, banyak kenikmatan yang hilang maknanya. Dalam narasi Bloom, kenikmatan sering merupakan “hadiah sekunder” dari perjuangan, bukan tujuan itu sendiri.
Bloom menyebut bab Struggle sebagai jantung argumen buku: perjuangan adalah bahan baku rasa hidup. Ia mengisahkan atlet, pemusik, pendaki gunung, koki profesional, hingga mahasiswa yang mengerjakan disertasi dalam rasa putus asa namun terus bergerak. Perjuangan mencipta-kan fokus dan struktur: ia membuat hidup terasa penuh arah. Bloom juga merujuk pada konsep flow dari Mihaly Csikszentmihalyi—keadaan tenggelam dalam tugas yang cukup sulit tetapi masih dapat dikuasai. Ini adalah bentuk perjuangan yang optimal: tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Dari sinilah muncul “sweet spot” awal—kisaran perjuangan yang membuat kita merasa hidup, terlibat, dan berkembang.
Struggle memberi rasa identitas: kita menjadi orang yang berjuang untuk sesuatu. Ia juga memberi rasa moral: pengorbanan memberi bobot pada tindakan. Di akhir bab, Bloom me-nekankan bahwa perjuangan yang dipilih jauh lebih bermakna daripada perjuangan yang dipaksakan.
The Sweet Spot merupakan tema yang jarang disadari betapa pentingnya kita memahami aspek penderitaan ini dalam kehidupan dan pergaulan hidup. Bloom juga membahas tentang Meaning, sesuatu sering kita lupakan dalam dunia yang serbagegas. Kita tak lagi sempat me-renungkan dan menggali langkah, pandangan dan segala sesuatu dalam pengertian yang dalam. Padahal seperti diuraikan Bloom, bab ini adalah landasan eksistensial: makna hidup tidak steril—ia hampir selalu menyertakan penderitaan.
Ia menyinggung Viktor Frankl, yang mengajar bahwa makna muncul bukan dari apa yang kita dapatkan tetapi bagaimana kita merespons apa yang tak terhindarkan. Bloom, yang lebih skeptis, tetap mengakui kekuatan gagasan itu: penderitaan yang diberi kerangka moral atau naratif dapat berubah menjadi sumber ketangguhan. The Sweet Spot menunjukkan bahwa “meaning-making” adalah kapasitas psikologis manusia: kita merangkai cerita, dan cerita itu memberi bobot pada penderitaan. Orang menjadi relawan bencana meski harus menghadapi bahaya; orang merawat keluarga sakit meski kelelahan; seseorang memilih menjadi seniman meski harus hidup serba kekurangan. Makna, bagi Bloom, bukanlah kenyamanan emosional melainkan struktur naratif yang mengikat usaha, pengorbanan, dan tujuan menjadi satu.
Dalam sejumlah penderitaan itu barangkali Bab Sacrifice yang bisa kita ingat sebagai sebuah ritual purba. Berbagai peradaban kuno menempatkan Pengorbanan sebagai ritual penting keberlangsungan komunitas atau kehidupan seseorang. Bab ini menyelidiki mengapa peng-orbanan terasa mulia, dan mengapa manusia sering menilai sesuatu bernilai justru karena kita bersedia mengorbankan sesuatu untuknya. Bloom menghubungkan pengorbanan dengan mekanisme sosial: pengorbanan adalah sinyal komitmen. Dalam agama, ritual pengorbanan menunjukkan dedikasi; dalam komunitas, pengorbanan demi kelompok memupuk rasa percaya. Bloom mengulas fenomena “costly signaling”—semakin besar harga yang dibayar, semakin kuat pesan kesetiaan atau ketulusan seseorang.
Ia juga menyelami dimensi interpersonal: orang tua yang mengorbankan tidur, waktu, uang, dan tenaga, menemukan jati diri baru dalam peran itu. Pengorbanan, yang secara fisik dan emosional menyakitkan, memperdalam ikatan. Bloom menyebut pengorbanan sebagai bentuk cinta dan sebagai “pembentuk nilai”: kita menghargai apa yang menuntut usaha dari kita.
Namun Bloom memperingatkan bahaya: tidak semua pengorbanan layak. Pengorbanan dapat dipaksakan oleh struktur sosial yang tidak adil. Tidak setiap penderitaan harus dirayakan.
Bab terakhir, Sweet Poison, ini adalah refleksi moral dan peringatan. Bloom menyebut “sweet poison” sebagai penderitaan yang terlihat bermakna atau memuaskan, tetapi sebenarnya berbahaya atau menjerumuskan. Contohnya termasuk obsesi kerja yang membuat seseorang merasa “produktif” tetapi merusak kesehatan dan relasi; kecanduan rasa sakit emosional dalam hubungan toksik; idealisasi berlebihan terhadap kerja keras; hingga ekstremisme yang meng-gunakan penderitaan sebagai simbol kesucian atau pembenaran radikalisasi. Bloom menunjuk-kan bahwa penderitaan memang bisa menjadi sarana makna, tetapi ia juga bisa menjadi candu—memberi ilusi tujuan, moralitas, atau kejernihan padahal menghancurkan fondasi hidup. Bloom mengajak pembaca untuk membedakan antara penderitaan yang membangun dan penderitaan yang memakan korban, antara tantangan yang kita pilih untuk tumbuh dengan kesengsaraan yang kita romantisasi tanpa sadar.
Ia menutup buku dengan nada bijak: tujuan hidup bukanlah mengejar rasa sakit, melainkan mengejar hidup yang berarti. Dan makna kadang membutuhkan rasa sakit—tetapi hanya ketika kita memilihnya secara sadar, dengan batas, dengan tujuan, dan dengan integritas moral.
Sweet Poison Pandangan Filosofis
Sweet Poison menarik untuk dipaparkan lebih mendalam. Sweet Poison membawa pembaca memasuki wilayah paling gelap namun paling jujur dalam psikologi manusia: bahwa penderita-an tertentu—meskipun merusak—dapat terasa seperti madu, sesuatu yang justru kita dekati, bahkan kita peluk, meski sadar bahwa ia dapat menelan kita bulat-bulat. Bloom menyebut-nya sweet poison, racun manis yang menggoda, racun yang terasa sebagai pemenuh makna, namun pada akhirnya mengikis apa yang membuat hidup layak untuk dijalani. Untuk membuka suasana batin ini, Bloom menghadirkan kembali kata-kata penyair John Keats kepada kekasih-nya, Fanny Brawne—sebuah surat yang memadukan eros, keputusasaan, dan fantasi tentang kehancuran yang memikat:
“Aku memiliki dua kemewahan untuk direnungkan dalam setiap langkahku, kecantikanmu dan detik kematianku. Oh, andai aku dapat memiliki keduanya pada menit yang sama. Aku membenci dunia ini: dunia ini terlalu sering memukuli sayap kehendakku, dan alangkah bahagianya bila aku dapat meneguk racun manis dari bibirmu untuk mengantarku keluar dari dunia ini. Dari bibir mana pun selain milikmulah aku takkan pernah mengambilnya.” —John Keats, surat kepada Fanny Brawne, Juli 1819
Bloom menggunakan kutipan ini bukan untuk merayakan kehancuran romantis, tetapi untuk memperlihatkan paradoks mendasar dalam diri manusia: kadang kita justru menginginkan sesuatu yang dapat menghancurkan kita, sepanjang kehancuran itu terasa indah, mulia, atau memberikan rasa absolut. Kita tergoda oleh penderitaan yang memberi kita ilusi makna, sekalipun ia memperpendek atau memperburuk hidup kita.
Racun manis: penderitaan yang terasa seperti tujuan. Bloom menekankan bahwa sweet poison tidak sama dengan penderitaan terpilih seperti berolahraga, berkarya keras, atau berpuasa untuk disiplin diri. Racun manis adalah penderitaan yang tidak lagi menjadi sarana menuju sesuatu yang baik—sebaliknya, ia menjadi tujuan itu sendiri.
Contoh utamanya:
- Pekerja yang terobsesi pada kerja keras sampai mengorbankan kesehatan dan relasi, merasa “salah” jika tidak menderita.
- Aktivis atau pemikir yang merasa semakin menderita berarti semakin benar atau suci.
- Hubungan romantis toksik yang menawarkan intensitas emosional alih-alih kedamaian.
- Pola pikir martir: bahwa nilai hidup hanya muncul dari pengorbanan ekstrem.
Bagi Bloom, bentuk-bentuk ini adalah cermin dari kebutuhan manusia akan makna—tetapi kebutuhan itu bisa tersesat, menjadi pemujaan terhadap rasa sakit, seolah-olah sakit itu sendiri adalah bukti kebenaran.
Racun manis dan evolusi: mengapa kita begitu mudah tertarik pada ekstrem. Untuk memahami mengapa manusia mudah jatuh pada racun manis, Bloom membawa argumen yang elegan: kita adalah produk dari rangkaian kemenangan evolusi yang mengagumkan sekaligus ironis. Ia mengutip Richard Dawkins dalam Unweaving the Rainbow:
“Kita akan mati, dan itu membuat kita menjadi yang beruntung,” tulis Richard Dawkins. Setelah semua, kitalah yang berkesempatan untuk ada.
Kita berutang pada seluruh leluhur kita: selama 3,8 miliar tahun, setiap dari mereka “cukup menarik untuk menemukan pasangan, cukup sehat untuk bereproduksi, dan cukup beruntung untuk hidup sampai berhasil melakukannya.” Untuk sampai di titik ini, kita haruslah makhluk yang luar biasa—meski kita juga harus rendah hati karena setiap makhluk di bumi, dari tikus hingga nyamuk, berbagi kemenangan yang sama: semuanya adalah penyintas kompetisi miliaran tahun.
Bloom mengambil refleksi Dawkins ini untuk menegaskan: karena kita adalah survivors dalam permainan besar kehidupan, kita dilengkapi mekanisme yang membuat kita sangat responsif terhadap bahaya, tantangan, dan sensasi ekstrem. Manusia, seperti hewan lain, dirancang untuk mengetahui kebenaran tentang dunia: “Seperti makhluk lainnya, kita dibentuk untuk mengetahui hal-hal yang benar tentang dunia. Hewan yang mempercayai hal-hal yang benar cenderung bertahan lebih baik dibandingkan mereka yang tidak…
Tetapi tidak seperti hewan lain, manusia juga memiliki rasa moral. Kita memiliki kapasitas untuk kebaikan, rasa keadilan—bersama sisi gelap seperti kemarahan, kebencian, hingga nafsu membalas dendam. Kapasitas moral ini memungkinkan kelompok besar manusia yang tidak saling terkait untuk bekerja sama dan menahan dorongan destruktif mereka demi manfaat bersama.”
Bloom memanfaatkan analisis evolusioner ini untuk menjelaskan dua hal:
- Mengapa manusia mencari intensitas: karena otak kita dirancang untuk memperhatikan ancaman dan kemenangan melawan ancaman itu. Penderitaan ekstrem bisa memberikan perasaan “realness”, keaslian, atau signifikansi.
- Mengapa moralitas dapat berubah menjadi racun: karena kapasitas moral yang evolusioner ini juga dapat memicu romantisasi pengorbanan, kecanduan pada kemarahan moral, atau pencarian makna melalui konflik dan rasa sakit.
Di sinilah racun manis bekerja: ia menyamar sebagai sesuatu yang bermoral, penting, atau penuh tujuan.
Racun yang terasa seperti kebajikan. Bloom menguraikan bagaimana penderitaan dapat menjadi identitas. Orang dapat merasa bahwa semakin besar penderitaan yang mereka pikul, semakin berarti hidup mereka. Ini bukan sekadar spiritualitas; ini bisa menjadi ideologi.
Racun manis bisa datang dari:
- Kerja ekstrem (workaholism) yang dilihat sebagai prestasi moral.
- Kultus produktivitas, yang menjadikan rasa lelah sebagai simbol kehormatan.
- Fetisisasi “ketegaran”—keyakinan bahwa meminta bantuan adalah kelemahan.
- Pengorbanan demi komunitas yang sebenarnya merusak individu.
- Amarah moral dan balas dendam, yang memberi ekstasi tersendiri.
Bloom memperlihatkan bahwa penderitaan dapat menciptakan “high moral”, seolah-olah rasa sakit adalah bukti kesucian. Namun ia mengingatkan bahwa ini adalah mekanisme yang sama yang membuat seseorang:
- rela hancur dalam hubungan yang salah,
- rela dibakar oleh beban kerja,
- rela hidup dalam konflik karena merasa itu membuktikan keberpihakan moral.
Di sini racun itu manis karena ia menipu: ia memberi kita perasaan bahwa kita sedang benar, kuat, atau penting.
Mengapa racun manis sulit dilepaskan. Bloom mengatakan bahwa racun manis jauh lebih sulit dilepas daripada penderitaan biasa. Alasannya: Ia memberi identitas: kita merasa “inilah aku”; Ia memberi makna: rasa sakit menjadi narasi heroik; Ia memberi pembenaran moral: penderita-an dianggap sebagai bukti nilai; Ia memberi intensitas emosional yang sulit ditiru oleh kehidupan biasa.
Dengan kata lain, racun manis memuaskan bagian paling dalam dari diri kita—bagian yang ingin merasa signifikan. Bloom mengajak pembaca untuk memeriksa motif mereka: apakah keter-tarikan pada penderitaan ini benar-benar tentang kebaikan, ataukah hanya ketagihan terhadap drama, intensitas, dan rasa menjadi “istimewa” melalui sakit?
Pelajaran dari racun manis: kesadaran sebagai jalan keluar. Bloom tidak menyarankan agar manusia menghindari semua rasa sakit. Ia justru mengatakan bahwa rasa sakit tertentu adalah bagian dari hidup yang kaya. Namun ia memperingatkan bahwa:
- penderitaan yang dipilih harus mengarah pada pertumbuhan,
- penderitaan harus memiliki batas,
- dan penderitaan tidak boleh menjadi pusat identitas.
Ia menyimpulkan bahwa sweet poison adalah versi terdistorsi dari pencarian makna. Kita perlu membedakan antara: penderitaan yang dipilih untuk membangun, dan penderitaan yang dipelihara karena memabukkan.
Bloom menutup buku dengan nada yang tegas namun manusiawi: hidup yang berarti membutuhkan usaha, bahkan rasa sakit—tetapi tidak membutuhkan kehancuran. Racun manis harus dikenali sebelum ia menggantikan seluruh definisi hidup kita.
Bab “Sweet Poison” adalah simpul intelektual paling penting dari keseluruhan buku. Di sini Bloom membawa dua ide besar: bahwa penderitaan memiliki daya tarik, bahkan pesona yang manusia cari secara aktif; dan bahwa kematian, kefanaan, dan tragedi justru memberi struktur bagi nilai dan makna hidup.
Pada tingkat filosofis, Bloom berada di wilayah yang dipijak Friedrich Nietzsche, Simone Weil, Hannah Arendt, Albert Camus, Kierkegaard, Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, dan bahkan psiko-analisis Freud—pemikir yang percaya bahwa manusia bukan sekadar pencari kenikmatan, tetapi pencari intensitas pengalaman, termasuk pengalaman yang menyakitkan.
Kutipan John Keats yang disalin Bloom: “Aku punya dua kemewahan untuk direnungi ketika berjalan: kecantikanmu dan jam kematianku… Andai aku bisa mengambil racun manis dari bibirmu untuk mengantar kepergianku dari dunia ini” adalah ekspresi sebuah ketegangan eksistensial yang sangat manusiawi: kita mencintai kehidupan, namun kehidupan itu sendiri selalu membawa bayangan kematian. Bloom menggunakan kutipan ini bukan untuk meroman-tisasi kematian, melainkan untuk menunjukkan bagaimana manusia mencampur dua pengalam-an ekstrem—keindahan dan kehancuran—ke dalam satu tarikan napas yang sama.
Ini adalah wilayah Eros (dorongan hidup) dan Thanatos (dorongan kematian), yang dalam psikoanalisis Freud dianggap sebagai dua kekuatan dasar yang membentuk manusia. Bloom tidak menyebut Freud secara eksplisit, namun analisisnya sejalan: manusia terkadang meng-inginkan “racun manis”—pengalaman yang menyakitkan tetapi memikat, pengalaman yang mengandung risiko tetapi memperkaya makna.
Nietzsche menyebut fenomena ini sebagai: “kegembiraan tragis” (die tragische Lust)—kesenangan yang muncul dari menghadapi realitas keras dan tetap berkata “ya” pada kehidupan.
Bloom menulis bahwa kita “beruntung” karena kita hidup—mengutip Richard Dawkins:
“Kita akan mati, dan itu membuat kita menjadi yang beruntung—karena kita yang sempat hidup.” Kalimat ini membawa pembacaan etis: keberadaan itu sendiri adalah hadiah. Dari perspektif evolusi, Bloom menunjukkan bahwa keberadaan kita adalah hasil dari garis keturun-an yang tak pernah sekali pun gagal dalam 3,8 miliar tahun. Setiap leluhur kita “cukup sehat untuk bertahan, cukup menarik untuk berpasangan, dan cukup beruntung untuk hidup sampai menghasilkan keturunan.”
Dalam istilah Camus: “Kesadaran atas absurditas justru menuntun pada pemberontakan untuk hidup.” Bloom tidak memberikan moralitas absolut; ia tidak memerintahkan apa yang harus kita lakukan. Namun ia membangun sebuah etika naturalistik: jika hidup adalah keberuntungan statistik, maka menjalani hidup dengan perhatian, keberanian, dan rasa syukur menjadi sikap moral yang sangat wajar.
Dalam tradisi Islam klasik, Ibn ‘Arabi menyatakan: “Keberadaan adalah pemberian paling besar. Wujud itu sendiri adalah rahmat.” (Futuhat al-Makkiyya). Bravo—konvergensi pemikiran antara sains evolusi dan metafisika spiritual ini luar biasa.
Sweet Poison sebagai Sumber Makna
Bloom menunjukkan bahwa walaupun kita berusaha menghindari sensasi tidak menyenangkan, kita secara aktifmemasukkan elemen penderitaan ke dalam hidup: olahraga ekstrem, novel tragedi, film horor, puisi sedih, hubungan emosional yang kompleks. Ia menyebut fenomena ini sebagai pencarian sengaja terhadap pengalaman emosional negatif yang “benign”—atau tidak berbahaya—namun memperkaya hidup. Atau kalau dalam tradisi sufi Rumi, “The wound is the place where the Light enters you.” Kutipan mistik ini memberi warna spiritual bahwa luka/ derita bisa menjadi pintu transformasi—sebuah resonansi estetis dengan argumen Bloom, tetapi dari ranah spiritual dan sufistik. littlethingsaboutmeeh
Dari sudut pandang etika, ini menunjukkan:
a) Makna memerlukan ketegangan
Tanpa risiko, kehilangan, dan waktu yang terbatas, nilai kehidupan akan menguap. Dalam bahasa Kierkegaard: “Kecemasan adalah pusingnya kebebasan.” Artinya, ketidakpastian dan penderitaan bukan musuh manusia—mereka adalah syarat kedalaman dan pilihan moral.
b) Kematian memberi bentuk pada nilai moral
Seandainya manusia abadi, keputusan moral menjadi tak berarti. Bloom tidak menarik kesimpulan eskatologis; fokusnya tetap pada struktur pengalaman manusiawi. Namun analisisnya sejalan dengan Arendt dan Levinas:
- kefanaan membuat tanggung jawab menjadi nyata,
- kesementaraan membuat kasih sayang menjadi berharga,
- kerapuhan membuka pintu bagi empati.
The Sweet Poison pada dasarnya menggugat hedonisme klasik. Hedonisme mengasumsikan manusia mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit. Bloom menunjukkan bahwa itu tidak cukup untuk menjelaskan manusia.
Secara etis, ini berhubungan dengan perbedaan antara:
- Hedonia = kenikmatan langsung
- Eudaimonia = hidup yang bermakna, berbudi, dan utuh
Aristoteles mengatakan: “Kita mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah hidup dengan tujuan.” Bloom menggemakan argumen ini: manusia tidak hanya ingin bahagia—manusia ingin hidup yang bernilai. Dan nilai membutuhkan pergulatan, pengorbanan, dan bahkan luka.
Dalam tradisi Islam, Rumi menulis: “Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu.”
Bloom tidak religius, tetapi konsep “racun manis” menunjukkan intuisi yang sama: rasa sakit dapat menjadi pintu ke transformasi eksistensial.
Secara etis, bagian “Sweet Poison” membuka pertanyaan sulit:
a) Apakah wajar menikmati rasa sakit tertentu?
Bloom menjawab: ya, dalam batas tertentu, dan sepanjang rasa sakit itu: tidak merusak orang lain; tidak menghancurkan diri sendiri; tidak memupuk ketergantungan destruktif. Ini mirip dengan etika Aristoteles soal “mesotes” (keutamaan berada pada titik tengah): keberanian adalah titik tengah antara keputusasaan dan kenekatan.
b) Apakah rasa sakit selalu bernilai?
Tidak. Bloom jelas: bukan semua penderitaan itu mulia. Penderitaan yang dipaksakan, dihasil-kan kekerasan, ketidakadilan, atau penindasan tidak memiliki kualitas “sweet poison”. Itu adalah racun sungguhan tanpa manisnya. Di titik ini Bloom sejalan dengan pemikiran etika Islam (Al-Ghazali, Al-Farabi) dan pemikir humanis modern: Derita yang memberi makna adalah derita yang dipilih, bukan dipaksakan.
Jika bab-bab sebelumnya menjelaskan aspek psikologi penderitaan, maka “Sweet Poison” menjadi tesis ontologis: Penderitaan bukan sekadar sesuatu yang kita alami—ia adalah bagian dari struktur keberadaan kita sebagai makhluk yang mencari makna.
Bloom menyatakan bahwa manusia adalah spesies unik:
- Kita sadar akan kematian.
- Kita memiliki moralitas.
- Kita memahami waktu.
- Kita sadar akan pilihan dan konsekuensinya.
Kesadaran seperti ini tak terhindarkan membawa kecemasan. Tetapi kecemasan itu justru menciptakan kedalaman. Manusia bukan sekadar makhluk yang ingin hidup tanpa rasa sakit, tetapi makhluk yang ingin hidup secara penuh. Dalam kata-kata Albert Camus: “Tujuan bukan untuk menghapus penderitaan, tetapi untuk membuat penderitaan itu bermakna.”
Catatan Akhir
Bloom menawarkan panduan pragmatis: carilah “penderitaan yang dipilih, dibatasi, dan ber-makna.” Para pengkritik (dan Bloom sendiri hati-hati) menunjukkan risiko: ada kecenderung-an budaya untuk memuliakan penderitaan (toxic stoicism), atau menyalahkan korban yang me-ngalami penderitaan tak terpilih. Bloom mencoba jembatan—mengakui nilai penderitaan yang bermakna tanpa mengabaikan etika dan keadilan sosial. The Guardian+1
Di akhir, Bloom mengajak pembaca untuk merancang hidup dengan sadar: tambahkan gesekan yang bermakna (proyek kreatif, latihan fisik, ritual sosial) dan carilah tujuan yang membuat pengorbanan menjadi bukti dan sumber nilai. Bukan semua rasa sakit layak dicari; tapi memilih tujuan yang menuntut usaha —dan merasa hidup melalui usaha itu—adalah salah satu jalan menuju hidup yang terasa penuh. HarperCollins+1
Bab “Sweet Poison” adalah argumentasi bahwa: Penderitaan yang dipilih secara sadar dapat menjadi sumber makna dan keindahan; Kematian memberi isi pada hidup, bukan mengosong-kannya; Manusia lebih dari pencari kenikmatan—kita adalah pencipta makna; Etika penderitaan menuntut kita membedakan antara derita yang memperkaya dan derita yang menghancurkan;
Makna tertinggi sering lahir dari ketegangan antara cinta dan kehilangan, keberanian dan kerapuhan, hidup dan kematian.
Dalam bahasa Keats, penderitaan bisa menjadi “racun manis”— dan dalam bahasa Bloom,
manusia memilih racun itu karena di dalamnya terdapat rasa hidup yang paling intens.
Bogor, 12 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Bloom, P. — The Sweet Spot: The Pleasures of Suffering and the Search for Meaning (publisher page). HarperCollins
https://www.harpercollins.com/products/the-sweet-spot-paul-bloom (lihat laman penerbit) - Frankl, V. E. (1959/2006). Man’s search for meaning. Beacon Press. (lihat edisi dan terjemahan yang relevan). https://antilogicalism.com/wp-content/uploads/2017/07/mans-search-for-meaning.pdf
- Nietzsche, F. W. (1889). Twilight of the Idols (G. T. transl.). Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/files/52263/52263-h/52263-h.htm
- Rumi, J. al-D. (terj. Coleman Barks). The Essential Rumi. (edisi terjemahan populer). Contoh koleksi dan terjemahan: https://littlethingsaboutmeeh.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/coleman-barks-the-essential-rumi.pdf
- Cowart, L. (2021, November). Are There Hidden Advantages to Pain and Suffering? The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2021/11/15/are-there-hidden-advantages-to-pain-and-suffering-hurts-so-good-leigh-cowart-the-sweet-spot-paul-bloom
- Ritchie, S. (2021, Nov 24). The Sweet Spot by Paul Bloom review – the pleasure of pain. The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2021/nov/24/the-sweet-spot-by-paul-bloom-review-the-pleasure-of-pain
- Vox Conversations. (2021, Dec 13). Paul Bloom on the importance of suffering. https://www.vox.com/vox-conversations-podcast/2021/12/13/22811994/paul-bloom-the-sweet-spot
- Kutipan & koleksi kutipan dari buku Bloom (contoh kutipan yang digunakan): Goodreads — The Sweet Spotquotes. Goodreads
https://www.goodreads.com/work/quotes/87070767-the-sweet-spot-the-pleasures-of-suffering-and-the-search-for-meaning - Ulasan panjang & konteks budaya: Leigh Cowart / New Yorker review — “Are There Hidden Advantages to Pain and Suffering?” (membahas The Sweet Spot). The New Yorker
https://www.newyorker.com/magazine/2021/11/15/are-there-hidden-advantages-to-pain-and-suffering-hurts-so-good-leigh-cowart-the-sweet-spot-paul-bloom - Ulasan kritik: The Guardian review (Stuart Ritchie) tentang The Sweet Spot. The Guardian
- Viktor E. Frankl — Man’s Search for Meaning (PDF/edisi Beacon Press; kutipan “When we are no longer able to change a situation…”). Antilogicalism
- Friedrich Nietzsche — Twilight of the Idols (Project Gutenberg). Project Gutenberg
- Rumi — baris terjemahan populer (“The wound is the place where the Light enters you”) sering dikaitkan dengan terjemahan Coleman Barks / kumpulan The Essential Rumi. (contoh sumber terjemahan tersedia online). littlethingsaboutmeeh
- Wawancara/video diskusi Bloom (Vox): “A good life is painful” (wawancara/percakapan tentang tema buku). Vox