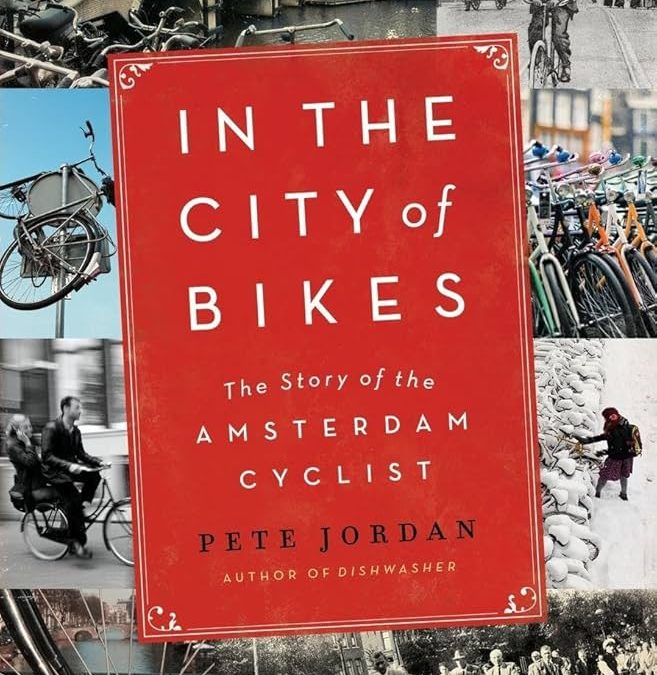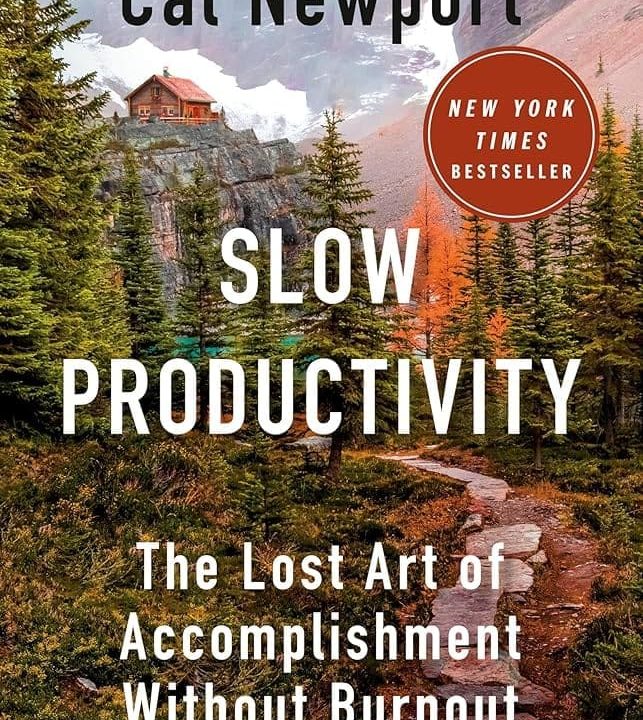Rubarubu #57
The Story of the Amsterdam Cyclist:
Mozaik Kisah Kota Sepeda
Ketika Pete Jordan tiba di Amsterdam sebagai “seorang pria dari Amerika”, ia membawa serta warisan mental yang tak terucap: kota adalah ruang bagi mobil, dan sepeda adalah pengecualian—entah sebagai alat rekreasi, olahraga, atau simbol subkultur tertentu. Namun sejak hari-hari pertamanya, kota ini segera memperlihatkan sesuatu yang ganjil bagi matanya. Bukan karena sepeda tampak luar biasa, tetapi justru karena sepeda sama sekali tidak tampak istimewa. Tidak ada aura heroik, tidak ada selebrasi gaya hidup. Orang-orang bersepeda sambil mengenakan pakaian kerja biasa, membawa anak, mengangkut belanjaan, berhenti di lampu lalu lintas dengan ekspresi datar. Jordan menyadari dengan cepat bahwa di Amsterdam, sepeda bukan identitas—ia adalah kondisi eksistensial kota.
Sebagai orang Amerika, Jordan merasa seolah-olah ia dapat “melihat beberapa hal” yang justru tak lagi terlihat oleh warga lokal karena telah menjadi terlalu normal. Perspektif orang luar ini menjadi lensa penting buku ini. Ia menangkap sesuatu yang sering luput dari diskursus global tentang “kota sepeda”: bahwa Amsterdam bukan kota sepeda karena warganya idealis atau ekologis, melainkan karena kota ini menyusun dirinya agar sepeda masuk akal secara total. Bahkan bagi seorang pendatang dari negeri mobil paling fanatik, logika itu begitu gamblang hingga hampir tak terbantahkan.
Namun kisah ini tidak dimulai di abad ke-21. Jordan membawa kita mundur ke akhir abad ke-19, ke masa yang ia sebut sebagai keberuntungan sejarah—the lucky few. Pada 1890-an, sepeda muncul sebagai teknologi modern yang menjanjikan kebebasan personal, terutama bagi kelas menengah perkotaan. Di Amsterdam, sepeda dengan cepat menjadi alat mobilitas yang cocok dengan struktur kota yang padat, relatif datar, dan berjarak dekat. Jalan-jalan yang sempit dan kanal-kanal yang membelah kota tidak menuntut mesin besar; mereka menuntut kelincahan dan kesederhanaan.
Pada masa itu, sepeda bukan milik semua orang. Ia adalah simbol kemajuan, bahkan status sosial tertentu. Namun berbeda dengan mobil di kemudian hari, sepeda tidak pernah sepenuhnya memisahkan penggunanya dari pejalan kaki atau dari ruang publik. Ia tidak menciptakan hierarki kekuasaan yang kasar. Sepeda tetap berada dalam skala manusia. Dalam istilah Lewis Mumford, sepeda adalah teknologi yang “organik” terhadap kota, bukan teknologi yang menaklukkannya.
Memasuki dekade 1920-an, lanskap kota Barat berubah drastis. Di banyak tempat, mobil mulai menuntut supremasi. Jalan-jalan direkayasa ulang, trotoar dipersempit, dan ruang publik diserahkan pada kecepatan dan mesin. Di sinilah Jordan memperkenalkan gambaran “King of the Street”. Mobil, di banyak kota dunia, naik takhta sebagai penguasa tunggal jalanan. Ia tidak sekadar alat transportasi, tetapi simbol modernitas, kebebasan, dan kekuasaan individual.
Amsterdam pun sempat tergoda. Mobil masuk, parkir memenuhi ruang, dan janji kecepatan menggoda imajinasi elite kota. Namun berbeda dengan banyak kota lain, dominasi ini tidak pernah sepenuhnya tak terbantahkan. Sepeda tidak tersingkir total. Ia bertahan—kadang terdesak, kadang diremehkan—tetapi tidak pernah punah dari keseharian kota. Ada semacam memori kolektif yang tetap hidup: bahwa jalan bukan hanya milik mesin tercepat, melainkan milik semua tubuh yang bergerak di dalamnya.
Di titik inilah Jordan mengajukan perbandingan yang tajam dan reflektif: the land of the automobile versus the land of the bicycle. Perbandingan ini bukan sekadar geografis, melainkan perbandingan ontologis tentang cara manusia memahami kebebasan dan individualitas. Di “tanah mobil”, individualitas diekspresikan melalui kepemilikan, kecepatan, dan isolasi. Mobil menjadi ruang privat yang bergerak, memisahkan pengemudi dari kota dan dari sesamanya. Di “tanah sepeda”, ekspresi individual justru terjadi dalam keterhubungan—tubuh yang terbuka terhadap cuaca, terhadap orang lain, terhadap ritme kota.
Jordan menunjukkan bahwa di Amsterdam, sepeda tidak pernah diperlakukan sebagai pernyataan gaya hidup yang eksentrik. Ia tidak dimaknai sebagai simbol moral atau politik. Justru karena itu, sepeda menjadi medium ekspresi individual yang paling jujur: seseorang bisa memilih sepeda tua yang reyot, sepeda kargo besar, sepeda elegan, atau sepeda biasa tanpa perlu menjelaskan diri. Identitas tidak dipaksakan oleh teknologi.
Dalam kontras ini, Amerika—dan banyak kota modern lainnya—tampak sebagai ruang di mana pilihan mobilitas dibingkai sebagai ekspresi kebebasan, padahal sesungguhnya pilihan itu sangat sempit. Kebebasan yang ditawarkan mobil adalah kebebasan yang mahal, boros energi, dan sering kali memenjarakan kota dalam kemacetan dan polusi. Amsterdam, sebagaimana digambarkan Jordan, justru menawarkan kebebasan yang lebih sunyi: kebebasan untuk bergerak tanpa dominasi, tanpa spektakel, tanpa harus menjadi istimewa.
Bagian awal buku ini, dengan demikian, bukan sekadar pengantar sejarah. Ia adalah undangan untuk mempertanyakan asumsi terdalam kita tentang kemajuan. Dengan mata seorang pendatang, Jordan memperlihatkan bahwa apa yang kita anggap “alami” dalam kota modern—mobil, jalan lebar, kecepatan—sebenarnya adalah hasil pilihan politik dan kultural yang sangat spesifik. Dan jika pilihan itu bisa dibuat, maka pilihan lain pun selalu mungkin.
Amsterdam, Sepeda, dan Sebuah Kesalah pahaman Global
Pete Jordan membuka bukunya bukan dengan data atau kebijakan, melainkan dengan keterkejutan personal. Sebagai orang Amerika yang pindah ke Amsterdam, ia membawa satu prasangka umum: bahwa kota sepeda ini adalah hasil dari perencanaan progresif, kesadaran ekologis, dan kebijakan hijau yang visioner. Namun semakin lama ia tinggal, mengamati, dan mewawancarai warga Amsterdam, semakin runtuh asumsi itu. Amsterdam bukan kota sepeda karena warganya lebih “hijau” atau lebih “bermoral” dibanding kota lain. Justru sebaliknya, seperti yang berulang kali ditekankan Jordan, orang Amsterdam bersepeda karena itu paling masuk akal—paling efisien, paling murah, paling praktis, dan paling sesuai dengan ritme hidup sehari-hari. Sepeda di sini bukan simbol ideologi, melainkan infrastruktur budaya yang banal, begitu biasa hingga nyaris tak terlihat. Dalam satu refleksi yang menjadi roh buku ini, Jordan mencatat bahwa di Amsterdam, sepeda tidak pernah dimaknai sebagai alat perjuangan. Ia hanyalah bagian dari kehidupan, seperti sendok atau tangga. Dan justru karena itulah ia berhasil.
Amsterdam adalah kota yang dibentuk oleh kebiasaan, bukan heroisme. Buku The Story of the Amsterdam Cyclist: In the City of Bikes karya Pete Jordan (2013) ini disusun sebagai mozaik kisah: percakapan dengan pekerja, ibu rumah tangga, pengantar barang, arsitek, pengrajin, aktivis, hingga anak-anak sekolah. Jordan tidak mencari figur heroik atau pionir. Ia justru tertarik pada yang biasa, pada “ordinary cyclist”—orang-orang yang tidak pernah menyebut diri mereka pesepeda, tetapi bersepeda setiap hari.
Dari kisah-kisah ini, muncul satu benang merah penting: Amsterdam tidak membangun budaya sepeda dengan mempromosikan sepeda; kota ini membangun kota yang cocok untuk sepeda.
Lebar jalan, jarak antar fungsi kota, kepadatan permukiman, kebijakan parkir yang ketat untuk mobil, serta desain jalan yang secara halus namun tegas memprioritaskan pengguna paling rentan—semua ini menciptakan kondisi di mana bersepeda menjadi pilihan default. Seperti dicatat Jordan, banyak warga Amsterdam bahkan tidak menganggap diri mereka sedang “memilih” sepeda. Mereka sekadar menjalani hidup.
Di sinilah buku ini menjadi kritik implisit terhadap banyak kota global—termasuk kota-kota di Asia dan Amerika—yang mencoba “mengimpor” sepeda tanpa mengubah struktur ruang, ekonomi, dan imajinasi kota.
Sepeda, di kota ini adalah sebagai anti-spektakel modernitas. Salah satu kekuatan buku ini adalah kemampuannya membaca sepeda secara kultural dan filosofis, tanpa menggurui. Jordan menunjukkan bahwa sepeda Amsterdam bukanlah sepeda mahal atau modis. Banyak yang tua, berkarat, berat, bahkan tampak “jelek”. Tapi justru di situlah maknanya. Sepeda Amsterdam tidak dirancang untuk kecepatan, gaya, atau performa. Ia dirancang untuk ketahanan, keseharian, dan ketidakmenonjolan. Dalam istilah Ivan Illich, sepeda di Amsterdam adalah contoh klasik dari convivial tool—alat yang memperluas kemampuan manusia tanpa mendominasi hidupnya (Illich, 1973).
Jordan secara halus memperlihatkan bagaimana kota ini menolak spektakel teknologi. Tidak ada fetish kecepatan, tidak ada glorifikasi inovasi disruptif. Yang ada adalah kesetiaan pada yang cukup. Dalam konteks ini, Amsterdam menjadi antitesis dari kota kapitalis modern yang selalu mengejar “lebih cepat, lebih besar, lebih baru”.
Menariknya, buku ini juga membongkar mitos bahwa Amsterdam selalu ramah sepeda sejak awal. Jordan mengingatkan bahwa pada 1950–1960-an, kota ini hampir tenggelam oleh mobil, sama seperti kota-kota lain di Eropa dan Amerika Utara. Perubahan terjadi melalui konflik, protes, dan negosiasi panjang—termasuk gerakan warga yang menuntut keselamatan anak-anak dari dominasi mobil. Namun yang membedakan Amsterdam adalah apa yang terjadi setelah kemenangan politik itu: politik sepeda menghilang ke dalam keseharian. Ia tidak lagi menjadi isu, slogan, atau identitas. Ia menjadi kebiasaan. Seperti politik yang lenyap ke dalam normalitas. Dalam perspektif Hannah Arendt, ini adalah bentuk keberhasilan politik tertinggi: ketika tindakan kolektif berhasil membangun dunia bersama yang stabil, sehingga tidak lagi membutuhkan heroisme (Arendt, 1958).
Buku ini yang merekam perjalanan panjang sebuah kota dengan penghormatan pada sepeda menjadi sebuah pelajaran untuk kota-kota dunia. Jordan tidak menawarkan Amsterdam sebagai model yang bisa ditiru secara mentah. Ia justru memperingatkan bahaya romantisasi. Yang bisa dipelajari bukanlah jalur sepedanya, melainkan logika sosialnya: kota yang dirancang untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk arus modal dan kendaraan. Dalam konteks krisis iklim dan wacana degrowth, buku ini sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa transisi ekologis yang paling radikal sering kali tampak paling membosankan. Tidak heroik, tidak futuristik, tetapi efektif.
Pemikir degrowth seperti Giorgos Kallis menegaskan bahwa masa depan berkelanjutan tidak terletak pada teknologi hijau spektakuler, melainkan pada pengaturan ulang kebutuhan dan kebiasaan (Kallis, 2018). Amsterdam, sebagaimana dituturkan Jordan, adalah contoh hidup dari tesis ini.
Menarik untuk membaca buku ini berdampingan dengan pemikiran etika dari tradisi lain. Dalam Islam, konsep wasatiyyah (keseimbangan) dan larangan israf (berlebih-lebihan) menemukan ekspresi ruangnya dalam kota seperti Amsterdam—bukan sebagai kota religius, tetapi sebagai kota yang menolak pemborosan energi, ruang, dan perhatian. Seperti dikatakan dalam Al-Qur’an: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31). Sepeda juga bisa memberikan resonansi etis dan spiritual.
Sepeda Amsterdam adalah praktik etis yang tidak berkhotbah. Ia bekerja dalam diam.
Sepeda dan Arsip Hidup Kota
Ketika pendudukan Nazi dimulai di Belanda pada awal 1940-an, kehidupan kota Amsterdam mengalami pembalikan makna yang brutal. Namun justru dalam kondisi keterbatasan ekstrem itulah sepeda menemukan peran yang tak terduga. Jordan menggambarkan dua tahun pertama pendudukan sebagai masa “true libertines”—sebuah frasa ironis sekaligus getir. Kebebasan politik telah dirampas, tetapi kebebasan bergerak dalam arti paling dasar justru bergantung pada sepeda. Bahan bakar langka, kendaraan bermotor disita atau tak terpakai, dan sistem transportasi formal lumpuh. Di tengah kehancuran itu, sepeda menjadi satu-satunya alat yang relatif netral, tidak mencolok, dan dapat diandalkan.
Pada masa ini, bersepeda bukanlah pilihan ideologis, melainkan strategi bertahan hidup. Sepeda memungkinkan orang bekerja, menyelundupkan makanan, mengunjungi keluarga, dan mempertahankan sisa-sisa kehidupan sosial. Dalam kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan Jordan, sepeda menjadi semacam perpanjangan tubuh: ringan, senyap, dan tak mudah diawasi. Ia adalah teknologi rendah yang tidak menarik perhatian kekuasaan totaliter. Di sinilah sepeda mulai memperoleh makna politis yang paradoksal—bukan sebagai simbol perlawanan yang heroik, melainkan sebagai alat kehidupan sehari-hari yang menolak mati.
Namun seiring berjalannya waktu, pendudukan semakin menekan. Pada tahun-tahun terakhir, Jordan mencatat perubahan psikologis yang halus tetapi mendalam, tertangkap dalam ungkapan: “You no longer think, you just pedal.” Bersepeda menjadi aktivitas mekanis, repetitif, hampir seperti meditasi yang pahit. Pikiran dikosongkan bukan demi ketenangan, melainkan demi bertahan. Tubuh bergerak karena harus, bukan karena ingin. Dalam konteks ini, sepeda tidak lagi melambangkan kebebasan, tetapi ketekunan eksistensial—gerak tanpa ilusi.
Pengalaman ini meninggalkan jejak panjang dalam memori kolektif kota. Ketika perang berakhir dan dekade 1950-an dimulai, Amsterdam—seperti banyak kota Eropa lainnya—berada dalam fase rekonstruksi. Namun Jordan mencatat bahwa periode ini ditandai oleh perasaan ambivalen yang kuat. “It’s chaos with the bicycles,” demikian keluhan yang sering terdengar. Jalan-jalan penuh sepeda, bercampur dengan kendaraan bermotor yang mulai kembali. Tidak ada hierarki yang jelas. Ruang kota menjadi arena negosiasi kasar antara kebiasaan lama dan ambisi modern.
Pada titik ini, sepeda mulai dipersepsikan sebagai masalah, bukan solusi. Ia dianggap kuno, lambat, dan tidak cocok dengan visi kemajuan pascaperang yang menatap masa depan industri dan konsumsi. Mobil, dengan segala janji kemakmurannya, mulai kembali mengklaim ruang. Namun berbeda dengan banyak kota lain, kekacauan ini tidak segera diselesaikan dengan pengusiran sepeda. Amsterdam memilih—atau mungkin terpaksa—hidup dalam ketegangan ini untuk sementara waktu.
Masuk ke fase “A Bike Is Coming: The New Additions”, Jordan menunjukkan bagaimana sepeda beradaptasi dengan zaman. Model-model baru bermunculan, aksesori berkembang, dan fungsi sepeda meluas. Ia tidak lagi hanya alat transportasi tunggal, tetapi mulai menyerap kebutuhan kota yang berubah: membawa anak, barang, bahkan pekerjaan. Sepeda kargo, misalnya, bukan inovasi modern belaka, melainkan evolusi dari kebutuhan urban yang nyata. Di sini, sepeda menunjukkan kemampuannya untuk bertransformasi tanpa kehilangan esensinya.
Transformasi ini mencapai puncak simboliknya pada dekade 1960-an, yang oleh Jordan digambarkan dengan kalimat nyaris Zen: “A bike is something, yet almost nothing!” Ungkapan ini menangkap esensi sikap Amsterdam terhadap sepeda. Ia adalah sesuatu—nyata, penting, fungsional—tetapi juga hampir tidak ada dalam arti simbolik. Sepeda tidak dibebani makna moral, tidak dipuja sebagai ikon, tidak dijadikan fetish teknologi. Ia hadir, digunakan, lalu dilupakan.
Justru dalam “ketiadaan makna berlebihan” inilah sepeda menjadi begitu kuat. Di tengah gelombang modernisasi, konsumerisme, dan politik identitas tahun 1960-an, sepeda tetap rendah hati. Ia tidak menuntut ideologi. Ia hanya meminta jalan yang layak dan kota yang manusiawi. Jordan memperlihatkan bahwa keberhasilan Amsterdam bukanlah hasil dari cinta romantis terhadap sepeda, melainkan dari keengganan untuk membuangnya demi ilusi kemajuan.
Bagian-bagian ini, jika dibaca sebagai satu alur, menunjukkan bahwa sepeda di Amsterdam bukan sekadar artefak teknologi, melainkan arsip hidup tentang bagaimana kota menghadapi krisis—perang, kelangkaan, modernisasi, dan perubahan budaya. Ia bertahan bukan karena dilindungi sejak awal, tetapi karena terlalu berguna untuk dihilangkan. Ia tidak menang dengan berteriak, melainkan dengan terus bergerak.
Ketika Jordan memasuki kisah White Bicycles, ia sengaja tidak menuliskannya sebagai legenda heroik yang bersih dan rapi. “A Big Success: The Urban Myths of the White Bicycles” justru dibuka dengan ironi. Di banyak buku dan narasi populer, proyek Witte Fietsenplan dari gerakan Provo tahun 1960-an sering digambarkan sebagai cikal bakal bike-sharing modern: sepeda putih gratis untuk siapa saja, simbol perlawanan terhadap mobil dan kapitalisme. Namun Jordan membongkar mitos itu dengan hati-hati. Dalam praktiknya, sepeda-sepeda putih itu cepat hilang—dicuri, disita polisi, atau dirusak. Secara teknis, proyek ini gagal.
Namun kegagalannya justru menjadi keberhasilan kultural. White Bicycles hidup sebagai mitos urban yang membentuk imajinasi kolektif. Ia mengajarkan bahwa sepeda bisa menjadi alat kritik sosial, bukan hanya alat transportasi. Ide bahwa kota dapat dibayangkan ulang—lebih pelan, lebih egaliter, lebih manusiawi—menjadi jauh lebih penting daripada keberhasilan logistik proyek itu sendiri. Jordan menunjukkan bahwa dalam sejarah kota, gagasan sering kali lebih bertahan lama daripada kebijakan.
Dari mitos menuju praktik sehari-hari, Jordan lalu beralih ke salah satu karakter paling khas Amsterdam: bike fishermen. “A Typical Amsterdam Characteristic: The Bike Fishermen” adalah potret tentang orang-orang yang mencari nafkah dengan mengangkat sepeda dari kanal-kanal kota. Setiap tahun, ribuan sepeda berakhir di air—jatuh karena mabuk, vandalisme, kecelakaan, atau sekadar kecerobohan. Alih-alih melihat ini semata sebagai masalah, kota justru melahirkan profesi informal yang unik.
Para bike fishermen adalah metafora hidup tentang hubungan Amsterdam dengan sepedanya: akrab, ceroboh, tidak sentimental. Sepeda jatuh ke kanal bukan tragedi nasional. Ia diangkat, dibersihkan, dijual kembali, atau didaur ulang. Dalam logika ini, sepeda bukan benda sakral, melainkan bagian dari siklus kota—lahir, rusak, tenggelam, dan muncul kembali. Jordan dengan cerdas menunjukkan bahwa keberlanjutan kota sering kali tumbuh dari praktik-praktik informal yang nyaris tak terlihat.
Ketegangan lama antara sepeda dan mobil mencapai klimaksnya pada dekade berikutnya. “Death to the Car!: The 1970s” bukan sekadar slogan provokatif, melainkan ekspresi kemarahan yang lahir dari korban nyata. Pada awal 1970-an, meningkatnya kepemilikan mobil menyebabkan lonjakan kematian anak-anak di jalan. Gerakan Stop de Kindermoord (“Hentikan Pembunuhan Anak”) menjadi titik balik moral. Untuk pertama kalinya, mobil tidak lagi dilihat sebagai simbol kemajuan tak terbantahkan, melainkan sebagai ancaman terhadap kehidupan sehari-hari.
Jordan menggambarkan dekade ini sebagai masa politisasi ruang jalan. Protes, okupasi, eksperimen lalu lintas, dan perubahan kebijakan terjadi bersamaan. Sepeda kembali ke pusat perdebatan, bukan sebagai nostalgia masa lalu, tetapi sebagai jawaban masa depan. Di sinilah Amsterdam mulai secara sadar memilih jalur yang berbeda dari banyak kota lain: bukan menyerah pada dominasi mobil, melainkan menegosiasikannya, membatasinya, dan pada akhirnya menguranginya.
Hasil dari konflik panjang ini mulai terasa pada 1980-an dan seterusnya. “It’s a Joy to Be on a Bike Again!” menandai kembalinya rasa senang yang sempat hilang. Infrastruktur membaik, jalur sepeda diperluas, dan bersepeda kembali menjadi pengalaman yang aman dan menyenangkan. Namun Jordan menekankan bahwa kegembiraan ini bukan hadiah alamiah, melainkan buah dari perjuangan politik yang panjang. Tidak ada kota sepeda yang lahir secara kebetulan.
Pada fase ini, sepeda tidak lagi simbol perlawanan, tetapi bagian normal dari kehidupan kota. Anak-anak, orang tua, pekerja kantoran, seniman, imigran—semuanya berbagi jalan yang sama. Normalisasi inilah yang, menurut Jordan, sering disalahpahami oleh pengamat luar. Amsterdam bukan kota sepeda karena warganya “secara budaya” suka bersepeda, melainkan karena kebijakan, sejarah konflik, dan pilihan moral yang konsisten.
Buku ini ditutup dengan nada reflektif dalam “Let’s Ride: Looking Back and Looking Forward”. Jordan menolak penutup yang triumfalistik. Ia sadar bahwa Amsterdam bukan utopia. Ketegangan tetap ada: pariwisata massal, sepeda listrik, konflik pejalan kaki, dan komersialisasi ruang publik. Namun kekuatan Amsterdam terletak pada kemampuannya untuk terus bernegosiasi, bukan membekukan kota dalam satu model ideal.
Melihat ke belakang, sepeda muncul sebagai saksi setia perubahan zaman—perang, pendudukan, modernisasi, krisis energi, dan kebangkitan ekologis. Melihat ke depan, sepeda tetap relevan justru karena kesederhanaannya. Ia tidak menjanjikan kecepatan tanpa batas, tetapi menawarkan keberlanjutan, kedekatan, dan skala manusia.
Dalam kalimat-kalimat terakhirnya, Jordan seolah mengajak pembaca bukan sekadar mengagumi Amsterdam, tetapi belajar dari prosesnya. Kota sepeda bukanlah hasil dari cinta romantis terhadap dua roda, melainkan dari keberanian untuk bertanya: siapa kota ini sebenarnya untuk? Dan selama pertanyaan itu terus diajukan, sepeda akan selalu menemukan jalannya.
Kebangkitan Politik Sepeda sejak 1970-an
Pada awal 1970-an, sepeda kembali ke pusat panggung sejarah—bukan sebagai alat nostalgia atau hobi rekreasi, melainkan sebagai subjek politik. Kebangkitan ini tidak lahir dari romantisme, melainkan dari darah di jalanan, krisis energi global, dan kegagalan mendalam paradigma kota berbasis mobil. Di banyak kota Eropa dan Amerika Utara, jalanan yang semula dijanjikan sebagai simbol kemajuan justru berubah menjadi ruang ketakutan: anak-anak tewas, lingkungan tercemar, dan kehidupan kota terfragmentasi.
Di Belanda, momen ini memiliki nama yang sangat literal: Stop de Kindermoord—“Hentikan Pembunuhan Anak.” Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kematian anak akibat lalu lintas mobil. Yang penting dicatat: ini bukan gerakan “penggemar sepeda,” melainkan gerakan orang tua, warga, dan komunitas yang menolak menerima kematian sebagai harga kemajuan. Di sinilah sepeda menjadi simbol moral. Ia berdiri sebagai antitesis mobil: lambat melawan cepat, ringan melawan berat, manusia melawan mesin.
Secara bersamaan, krisis minyak 1973 mengguncang keyakinan terhadap energi fosil murah dan tak terbatas. Negara-negara industri tiba-tiba menyadari kerentanannya. Jalanan tanpa mobil pada hari Minggu di Belanda—yang kini sering dikenang dengan nostalgia—sebenarnya adalah eksperimen politik darurat. Namun dari situ, muncul pertanyaan yang lebih radikal: jika kota bisa hidup tanpa mobil untuk sementara, mengapa tidak secara permanen? Kebangkitan politik sepeda pada era ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia berkelindan dengan gerakan lingkungan, feminisme, gerakan hak anak, dan kritik terhadap modernisme teknokratis. Sepeda menjadi alat yang “tidak patuh” terhadap logika kapitalisme perkotaan. Ia sulit diprivatisasi secara penuh, tidak membutuhkan infrastruktur megah, dan tidak menjanjikan pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi tinggi. Dalam pengertian ini, sepeda adalah teknologi yang secara struktural subversif.
Namun kebangkitan ini bukan tanpa konflik. Pada 1970-an, kota-kota seperti Amsterdam, Copenhagen, dan Münster menjadi medan pertempuran ideologis. Aktivis menduduki jalan, memblokir pembangunan jalan tol, dan menuntut ruang aman bagi sepeda. Negara dan pemerintah kota awalnya menolak, menganggap tuntutan ini regresif dan anti-modern. Tetapi tekanan politik yang konsisten—ditopang oleh data keselamatan, krisis energi, dan legitimasi moral—perlahan memaksa perubahan kebijakan.
Yang membedakan kebangkitan politik sepeda pasca-1970-an dari fase sebelumnya adalah pergeseran dari gerakan ke institusi. Sepeda tidak lagi hanya simbol perlawanan, tetapi mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret: jalur sepeda terpisah, zona lalu lintas tenang, pembatasan parkir mobil, dan perencanaan kota berbasis jarak pendek. Inilah fase di mana sepeda menjadi bagian dari statecraft—bukan sekadar aktivisme jalanan.
Namun proses ini juga mengandung paradoks. Ketika sepeda dinormalisasi dan dilembagakan, ia kehilangan sebagian daya radikalnya. Di kota-kota yang “berhasil,” sepeda sering dipromosi-kan sebagai gaya hidup sehat atau strategi efisiensi, bukan lagi sebagai kritik struktural ter-hadap pertumbuhan tanpa batas. Meski demikian, jejak politik asalnya tidak pernah sepenuh-nya hilang. Setiap jalur sepeda adalah artefak konflik masa lalu. Memasuki abad ke-21, kebangkitan politik sepeda menemukan energi baru melalui krisis iklim. Jika pada 1970-an sepeda adalah jawaban atas krisis keselamatan dan energi, kini ia menjadi respons terhadap krisis eksistensial planet. Kota-kota di seluruh dunia—Paris, Bogotá, Barcelona, bahkan Jakarta dan Bandung—mulai kembali menengok sepeda bukan karena nostalgia Eropa, melainkan karena keterpaksaan ekologis.
Namun sejarah 1970-an memberi pelajaran penting: sepeda tidak akan “bangkit” hanya karena manfaat teknisnya jelas. Ia membutuhkan konflik, keberanian politik, dan perubahan nilai. Tanpa pembatasan mobil, sepeda akan selalu kalah. Tanpa keberpihakan pada keselamatan dan keadilan, sepeda akan direduksi menjadi aksesori kelas menengah.
Kebangkitan politik sepeda sejak 1970-an menunjukkan bahwa kota bukan sekadar hasil perencanaan teknis, melainkan medan moral. Sepeda bertahan bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia mengingatkan kita pada skala manusia—bahwa kemajuan sejati bukan soal seberapa cepat kita bergerak, melainkan bagaimana kita hidup bersama. Dalam dunia yang kembali menghadapi krisis energi, iklim, dan fragmentasi sosial, politik sepeda tidak pernah sekadar tentang dua roda. Ia adalah pertanyaan abadi tentang arah peradaban: apakah kota dibangun untuk mesin, atau untuk kehidupan.
Catatan Akhir: Kota Sepeda sebagai Kota yang Dewasa
The Story of the Amsterdam Cyclist pada akhirnya bukan buku tentang sepeda, melainkan tentang kedewasaan peradaban urban. Kota yang dewasa tidak perlu membuktikan kemajuan lewat kecepatan atau kemegahan. Ia cukup memastikan bahwa warganya bisa hidup dengan aman, tenang, dan bermartabat.
Pete Jordan mengajak kita melihat bahwa masa depan mobilitas bukanlah soal inovasi spektakuler, melainkan soal mengembalikan kota pada skala manusia. Dan dalam dunia yang terobsesi dengan pertumbuhan, itulah mungkin tindakan paling radikal.
Bogor, 23 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Arendt, H. (1958). The Human Condition. University of Chicago Press.
- Illich, I. (1973). Tools for Conviviality. Harper & Row.
- Jordan, P. (2013). The Story of the Amsterdam Cyclist: In the City of Bikes. HarperCollins.
https://www.harpercollins.com/products/the-story-of-the-amsterdam-cyclist-pete-jordan - Kallis, G. (2018). Degrowth. Agenda Publishing.
- UN-Habitat. (2013). Planning and Design for Sustainable Urban Mobility.
https://unhabitat.org/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility - Pucher, J., & Buehler, R. (2012). City Cycling. MIT Press.
https://mitpress.mit.edu/9780262017451/city-cycling/