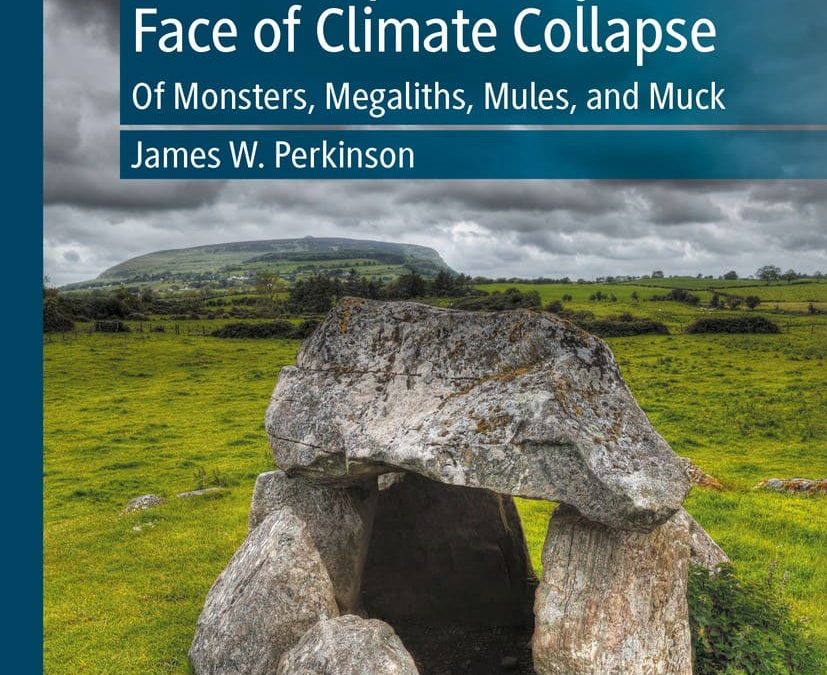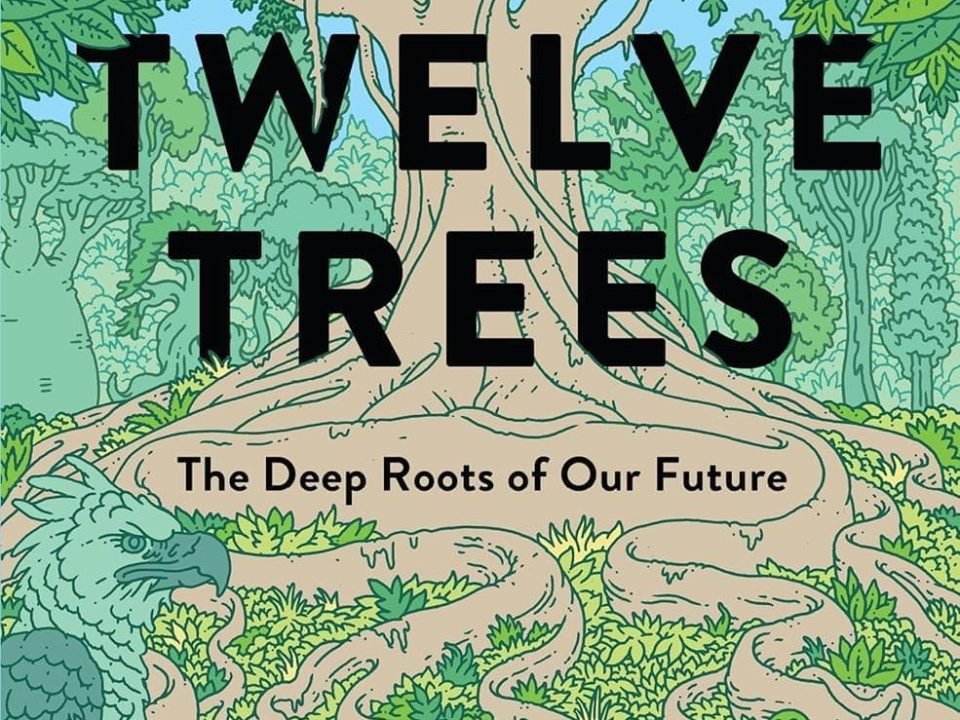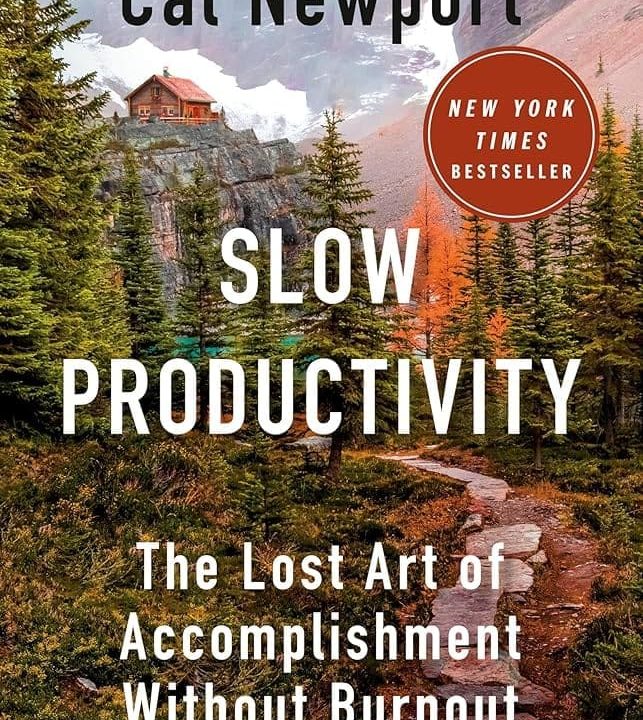Rubarubu #44
The Face of Climate Collapse:
Politik pada Wajah Keruntuhan Iklim
Pada suatu malam di kota pasca-industri yang genap tak lagi mengenal suara pabrik yang berdengung, seorang pemuda berjalan di trotoar berlubang. Di sampingnya berdiri tumpukan mesin tua, kabel terkelupas, dan bekas gudang yang dikalahkan oleh waktu — simbol sebuah ekonomi ekstraktif yang dulu menjanjikan kemakmuran, sekarang menyisakan bekas dan korosi. Dalam buku ini, Perkinson mengajak kita untuk melihat bahwa krisis iklim bukan hanya tentang kenaikan suhu atau kenaikan permukaan laut, melainkan tentang warisan struktur buka-tutup, monster industrial, megalit infrastruktur, keledai (mules) ekonomi yang memikul beban, dan lumpur (muck) peradaban yang tercemar. Ia menyebut buku ini sebagai tanggapan terhadap “a monstrosity of urbanization whose maw is now planetary-wide.” Ecumenical Theological Seminary Kisah pemuda dan kota itu jadi metafora untuk panggilan buku: bagaimana spiritualitas, politik, dan ekologi berkelindan dalam menghadapi keruntuhan yang sudah dalam proses.
Buku dibagi ke dalam beberapa bagian (kaum teoretis, historis, kultur, dan praktis) yang menjelajahi bagaimana spiritualitas politik dapat membantu kita memahami dan merespon kolaps sistemik iklim-sosial. Perkinson memadukan ekoteologi, studi kolonial, budaya urban, mitologi, dan narasi masyarakat adat untuk menolak dualisme tradisional antara manusia dan alam, dan antara spiritualitas dan politik. Ia menuntut agar kita mempertimbangkan “more-than-human” (lebih-dari-manusia) sekaligus relasi keadilan rasial, ekonomi, dan kolonial — agar tidak hanya menyikapi perubahan iklim sebagai tantangan teknis, tetapi sebagai transformasi struktural. Misalnya, ia menulis bahwa buku ini “hunts and gathers across different historical epochs and situations… to challenge the current crisis of sustainability from the perspective of indigenous communities and deep ancestry.” Ecumenical Theological Seminary+1
Salah satu bab yang sangat menarik dan makin terasa relevan adalah bab tentang “Meg a liths” (infrastruktur raksasa) — Perkinson menunjukkan bahwa bendungan, jalan tol, pertambangan besar, perkebunan monokultur adalah semacam megalit modern yang dibangun di atas logika ekstraksi dan dominasi, yang kini menjadi beban besar dalam krisis iklim. Ia menghubungkan infrastruktur tersebut dengan warisan kolonial-settler, dengan mobilisasi tenaga kerja murah dan penyingkiran masyarakat lokal. Dalam konteks spiritual, ia menegaskan bahwa megalit ini bukan hanya fisik, tetapi simbol kuasa, dominasi, dan alienasi alam-manusia. Dengan demikian, spiritualitas politik bukan hanya tentang doa atau ritual, tetapi tentang upaya mempertemukan kembali relasi manusia-alam yang pernah dirobek oleh proyek modernitas. Kritik terhadap buku ini memuji bab-megalit sebagai “a precise excavation of how infrastructure carries colonial history into our climate predicament.” Equinox Journal
Bab yang saya anggap paling relevan untuk dunia kita saat ini adalah bab tentang “Mules” — yaitu bagaimana ekonomi global memakai “keledai” kerja dan beban sosial untuk menanggung eksternalitas iklim. Perkinson memaparkan bahwa pekerja di industri pertambangan, perkebunan, dan konstruksi adalah bagian dari sistem yang menjaga mesin ekstraksi tetap berjalan, sementara dampak lingkungan dan kesehatan tertumpu pada komunitas yang tak memiliki suara politik. Ia kemudian mengaitkan ini dengan spiritualitas pembebasan: menggali jejak gerakan pekerja, komunitas adat, dan aktivisme yang menyebut bahwa relasi kerja-alam harus adil. Prinsip “just transition” diperkaya dengan dimensi spiritual bahwa pekerja bukan sekadar biaya produksi, melainkan manusia dengan martabat dan keterkaitan ekologis. Di Indonesia, misalnya pekerja tambang batu bara dan petani sawit bisa dilihat sebagai “mules” modern — beban sosial dari ekspansi industri yang mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan komunitas lokal.
Dalam bab “Monsters” Perkinson menjelaskan monster bukan hanya metafora untuk cuaca ekstrem atau kenaikan air laut, tetapi juga untuk sistem produksi yang menciptakan makhluk sosial-ekologis baru: limbah kimia, ubur-ubur di air hangat, hutan gundul, kota banjir. Ia menunjukkan bagaimana mitologi monster bisa menjadi alat spiritual untuk memahami kecemasan iklim: monster adalah manifestasi relasi yang rusak, ia mengundang ketakutan tetapi juga perubahan. Ia mengutip pemikir seperti Mary Shelley dalam Frankenstein, bahwa “the creature was not the monster; the maker was.” Buku ini pun mengaitkan mitos monster dengan tanggung jawab insan modern: bukan hanya korban tetapi pencipta. Kritik terhadap buku ini menghargai cara Perkinson membongkar narasi teknis dan mengubahnya menjadi narasi spiritual-politik: “He invites us to face the monster our civilization has become.” (review) Namun ada catatan bahwa bahasanya kadang terlalu metaforis untuk pembuat kebijakan yang mencari rekomendasi konkret.
Pada bagian praktis dan setelah refleksi teoritis, buku menyoroti dimensi “Muck” — lumpur sebagai simbol degradasi ekologi, metabolisme industri, dan liminalitas manusia-alam. Perkinson mendorong kita untuk tinggal di tempat (dwelling) bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai penjaga—menyentuh tanah, ikut dalam ritual lokal, belajar dari masyarakat adat yang melihat tanah sebagai relational. Ia memanggil istilah “political spirituality” sebagai praktik yang menghubungkan ritual, komunitas, dan aksi sosial dalam konteks perubahan iklim dan kolonialisme. Buku ini mengingatkan bahwa bukan cukup mengurangi emisi; kita harus mengubah cara kita hidup bersama Bumi, cara kita berhubungan dengan tanah, air, dan sesama. Dalam konteks Indonesia, ini relevan dengan upaya revitalisasi adat, moratorium sawit, pengakuan hak masyarakat lokal, dan strategi restorasi lanskap — semua membutuhkan rekontekstualisasi nilai, bukan sekadar regulasi teknis.
Political Spirituality in the Face of Climate Collapse karya James W. Perkinson (2024) tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga mengandung spirit of praxis, kita bisa mengekstraksi titik-aksi strategis (strategic action points) dari kerangka pemikiran Perkinson dan menerapkannya pada konteks Indonesia maupun global.
Berikut 10 titik-aksi strategis yang dielaborasi dalam bahasa yang bisa digunakan untuk korporasi, lembaga sosial, akademik, maupun komunitas ekologi:
1. Dekolonisasi Cara Pandang terhadap Alam
Makna strategis:
Perkinson menegaskan bahwa krisis iklim adalah warisan kolonial yang memisahkan manusia dari alam dan menjadikan alam sekadar objek ekonomi.
Tindakan konkret:
- Mengintegrasikan pengetahuan lokal dan adat dalam kebijakan lingkungan.
- Mengubah paradigma bisnis dari “extraction mindset” ke “regeneration mindset”.
- Di Indonesia, ini berarti memperkuat posisi masyarakat adat dalam tata kelola hutan, pesisir, dan lahan gambut.
“Coloniality is not only a history of conquest, but a cosmology of separation.”
2. Bangun Spiritualitas Ekologis
Makna strategis:
Perubahan iklim bukan sekadar isu teknis; ini juga krisis makna dan hubungan. Spiritualitas ekologis mengajarkan rasa hormat, keterhubungan, dan tanggung jawab moral terhadap bumi.
Tindakan konkret:
- Mengembangkan narasi publik yang menghubungkan keimanan, etika, dan ekologi (misalnya eco-theology dalam komunitas Muslim dan Kristiani).
- Memasukkan dimensi spiritual dalam pendidikan lingkungan. Mendorong ritual atau kegiatan reflektif di ruang kerja dan komunitas yang menumbuhkan empati ekologis.
Jalaluddin Rumi pernah menulis, “Bumi adalah kitab yang disusun dengan cinta; siapa yang membaca dengan hati akan menemukan Tuhan di tanah.”
3. Audit Infrastruktur Raksasa (Megaprojects)
Makna strategis:
Perkinson menyebut “megaliths” sebagai simbol dari ekonomi destruktif. Infrastruktur besar sering menindas masyarakat kecil dan merusak ekosistem.
Tindakan konkret:
- Lakukan audit keberlanjutan sosial dan spiritual dari setiap proyek infrastruktur besar.
- Dorong pembangunan yang berbasis human and ecological scale.
- Dalam konteks Indonesia: evaluasi proyek IKN, bendungan, dan tambang dengan kriteria “eco-justice”.
4. Keadilan bagi “Mules” – Pekerja dan Komunitas yang Menanggung Beban
Makna strategis:
“Mules” adalah metafora bagi tenaga kerja dan masyarakat yang menanggung beban eksternalitas industri.
Tindakan konkret:
- Dorong transisi energi yang adil (Just Transition) dengan memperhatikan hak pekerja tambang, petani sawit, nelayan, dan komunitas miskin kota.
- Integrasikan kesejahteraan sosial dalam kebijakan lingkungan dan transisi energi.
Kutipan Perkinson: “The mule carries civilization’s burden, but is rarely invited to the table of decision.”
5. Revolusi Epistemik dan Pendidikan
Makna strategis:
Krisis iklim juga adalah krisis pengetahuan. Perkinson menyerukan “political spirituality” sebagai pendidikan untuk membongkar sistem nilai lama.
Tindakan konkret:
- Reformasi kurikulum pendidikan agar tidak hanya menekankan STEM, tetapi juga ethical literacy dan ecological imagination.
- Mendorong pendidikan lintas ilmu: sains, teologi, dan budaya lokal.
Paulo Freire menyebut pendidikan sebagai “praktik kebebasan” — membebaskan kesadaran dari struktur opresif.
6. Hadapi “Monster” Modern: Industri, Data, dan Konsumerisme
Makna strategis:
Monster adalah simbol sistem yang menciptakan kerusakan global — industri, data, dan kapitalisme digital.
Tindakan konkret:
- Kurangi jejak karbon korporasi dengan audit rantai pasok.
- Kembangkan ekosistem bisnis berbasis sirkularitas dan etika digital hijau.
- Dorong gaya hidup sederhana dan konsumsi sadar (conscious consumption).
Kutipan dari Perkinson: “We must face the monster our civilization has become — without becoming monstrous ourselves.”
7. Regenerasi Komunitas dan Ekonomi Lokal
Makna strategis:
Perkinson mengajak kita untuk membangun kembali dari bawah: komunitas, tanah, dan relasi sosial.
Tindakan konkret:
- Fasilitasi ekonomi regeneratif: agroforestri, energi komunitas, ekowisata berbasis adat.
- Kembangkan koperasi hijau dan jaringan solidaritas ekonomi kecil.
- Di Indonesia, gerakan seperti “Desa Mandiri Energi” atau “Hutan Adat Lestari” adalah wujud nyata strategi ini.
8. Bangun “Spiritual Governance” — Politik Bernurani
Makna strategis:
Perkinson menggagas bahwa spiritualitas politik berarti memimpin dengan nurani ekologis, bukan sekadar efisiensi ekonomi.
Tindakan konkret:
- Dorong integritas ekologis di lembaga publik dan swasta.
- Libatkan tokoh lintas agama dalam kebijakan iklim.
- Tumbuhkan kepemimpinan yang sadar keterhubungan: manusia-alam-Tuhan.
Ali Syariati pernah menulis, “Spiritualitas tanpa politik adalah kemewahan; politik tanpa spiritualitas adalah kekerasan.”
9. Menghidupkan “Ritual Bumi” dan Seni Perubahan
Makna strategis:
Perubahan perilaku memerlukan bahasa budaya. Seni dan ritual menjadi sarana transformatif.
Tindakan konkret:
- Gunakan seni pertunjukan, musik, atau sastra untuk membangun kesadaran ekologis.
- Revitalisasi upacara adat yang mengajarkan keseimbangan.
- Kolaborasi antara seniman, ilmuwan, dan aktivis iklim.
Seperti kata penyair Afrika Ben Okri: “Stories are the secret reservoir of values; change the stories and you change the world.”
10. Ekologi Pertobatan dan Harapan
Makna strategis:
Perkinson menutup bukunya dengan refleksi: harapan bukan optimisme kosong, tapi pertobatan yang aktif — mengakui keterlibatan kita dalam krisis.
Tindakan konkret:
- Praktik “ecological repentance”: audit pribadi, komunitas, dan lembaga atas kontribusi pada degradasi.
- Menumbuhkan budaya pertanggungjawaban ekologis di ruang ibadah, sekolah, dan korporasi.
- Di Indonesia, ini bisa dihubungkan dengan nilai gotong royong dan “pemulihan bersama” (restorative justice).
Kutipan: “Hope is not escape from collapse, but courage to compost the ruins into renewal.”
Catatan Akhir
Relevansi global buku ini sangat kuat: di tengah polarisasi iklim, krisis keadilan sosial, dan keruntuhan institusi, Perkinson menawarkan perspektif yang menyatukan spiritualitas dan politik. Ia meminta agar gerakan iklim tidak hanya menuntut teknologi atau kebijakan, tetapi juga transformasi etis dan struktural—membongkar supremasi manusia-sentris, kolonialisme, dan ekonomi ekstraktif. Bagi Indonesia, konteksnya jelas: sebagai negara megadiversitas, produsen sawit dan batu bara, dan dengan banyak komunitas adat yang terdampak, buku ini mengajak kita untuk melihat bahwa transisi energi, restorasi hutan, atau pengelolaan lahan gambut bukan hanya soal target net-zero tetapi soal keadilan, hubungan manusia-alam, dan regenerasi budaya. Ia menjadi suara yang mendesak agar upaya iklim nasional memasukkan dimensi spiritual, lokal, dan historis.
Sebagai apresiasi dan kritik: ulasan dari jurnal JSRNC mengatakan bahwa “Perkinson navigates the monstrous scale of the Anthropocene with theological acuity and cultural sensitivity.” Equinox Journal Namun pengamat lain menyebut bahwa buku ini “could have benefited from more concrete policy pathways” — bahwa narasi spiritual-politiknya kuat, tetapi pembuat kebijakan yang mencari model implementasi praktis mungkin merasa kekurangan instrumen teknis langsung. Meskipun demikian, banyak yang memuji bahwa buku ini mengisi ruang yang jarang disentuh—yakni hubungan antara spiritualitas, dekolonisasi, dan perubahan iklim—dan memberi landasan pemikiran yang kaya untuk aktivis, pemimpin komunitas, dan pemikir lingkungan. Kutipan penutup yang menggugah: “Our hour on the planet is a time of comeuppance, of facing the monstrous effects our modern industrial conceit has unleashed on the biosphere.” Ecumenical Theological Seminary+1
Bogor, 18 Oktober 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Perkinson, J. W. (2024). Political Spirituality in the Face of Climate Collapse: Of Monsters, Megaliths, Mules, and Muck. Springer Nature Switzerland AG. iMusic
Perkinson, J. W. (2024). Review of Political Spirituality in the Face of Climate Collapse. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC). Equinox Journal