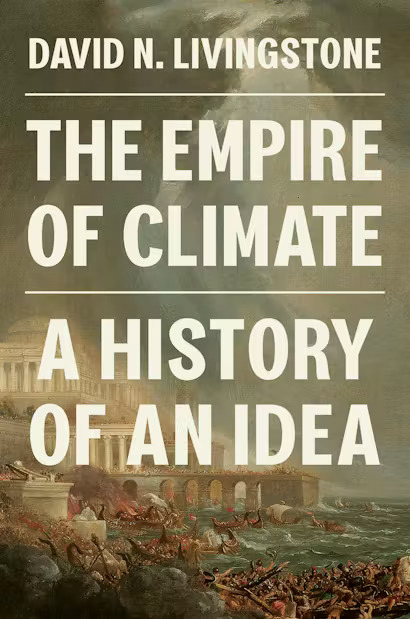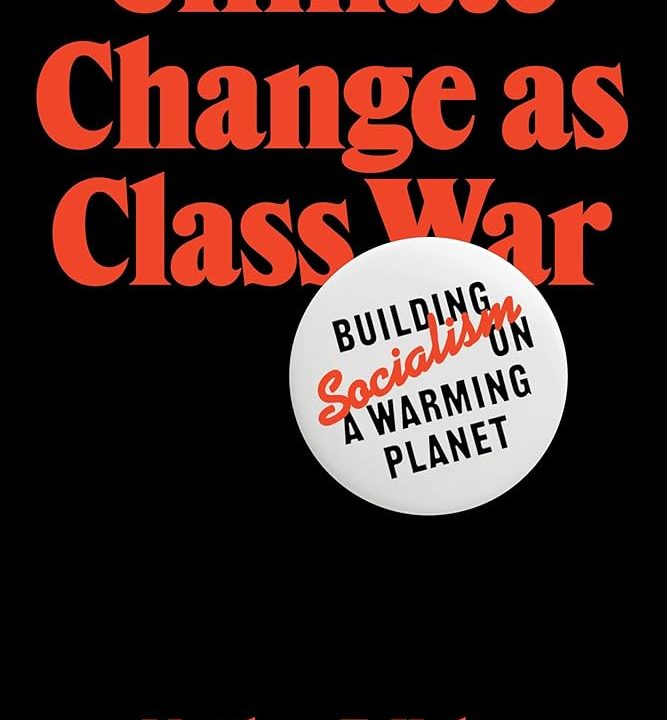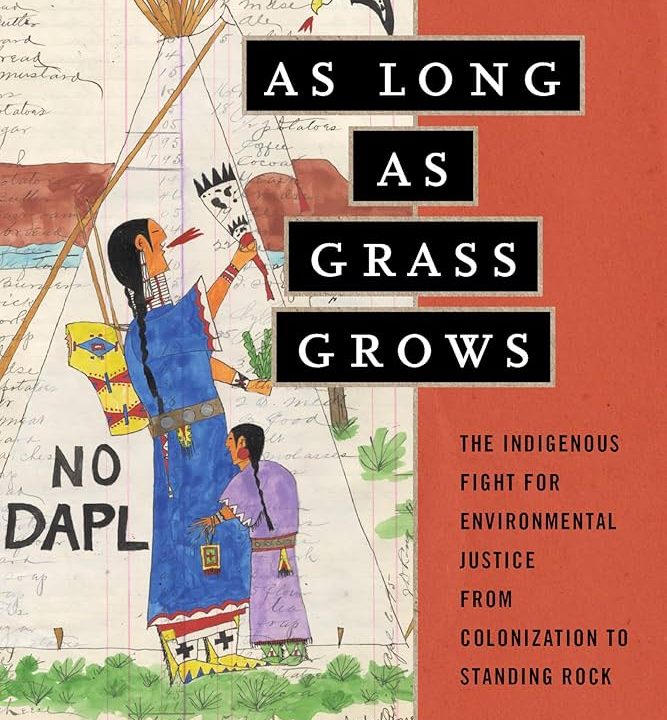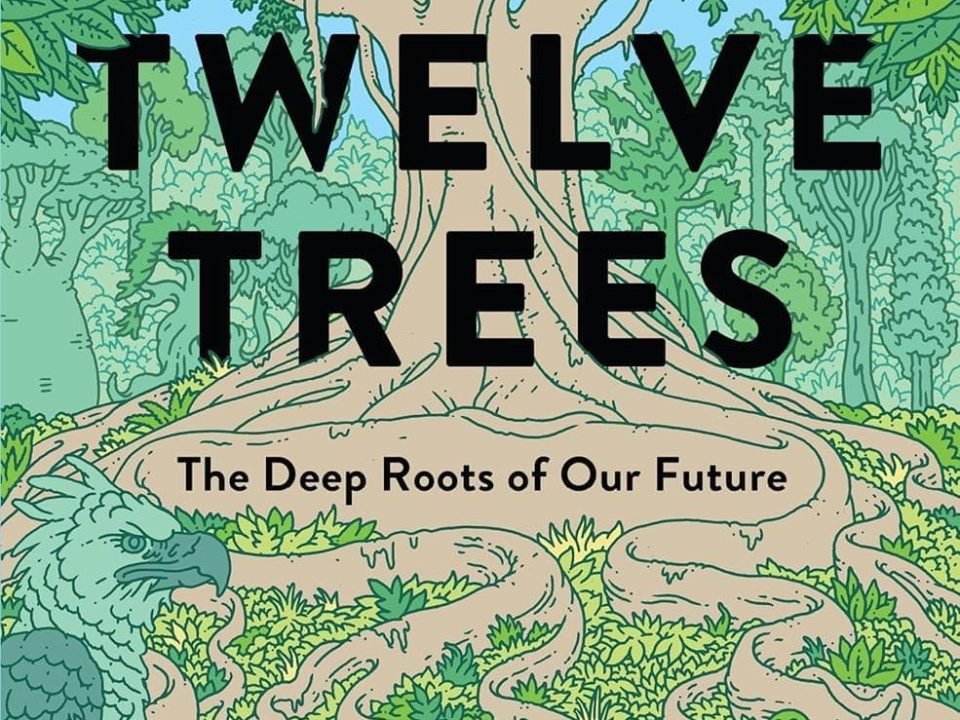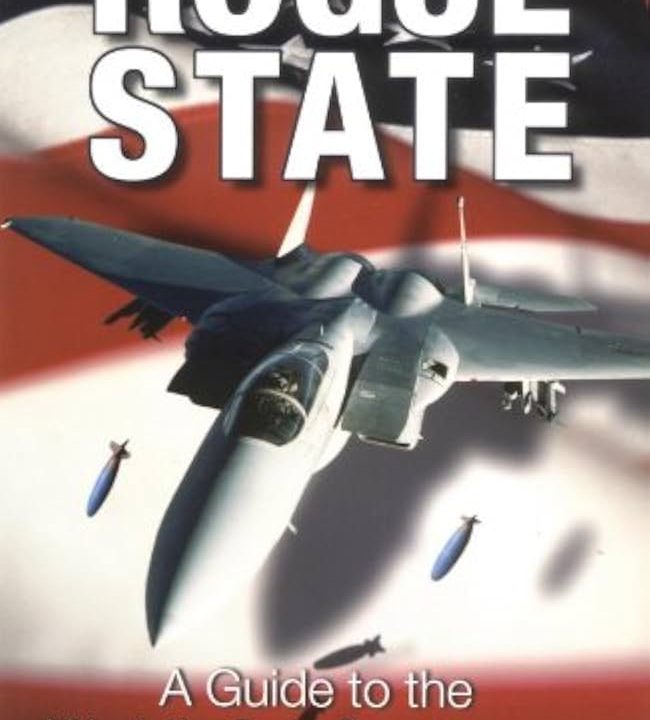Rubarubu #45
The Empire of Climate:
Penguasa di Atas Kekaisaran Manusia
Pada pagi berkabut di sebuah kota pelabuhan Inggris, seorang kuli bangunan mengintip ke arah laut. Ia merasakan udara dingin yang menusuk dan mendengar roda-pelabuhan yang berderak. Ia tahu bahwa cuaca buruk bukan sekadar gangguan kerja—melainkan bagian dari “aturan” yang menentukan nasib pelabuhan, kapasitas kapal, dan bahkan kebijakan perdagangan. Livingstone menggunakan citra semacam ini untuk membuka bukunya: bahwa iklim (climate) selama berabad-abad telah dianggap sebagai kekuatan yang mengatur peradaban membentuk karakter manusia, layout ekonomi, bahkan legitimasi imperium. Ia menulis bahwa “the empire of the climate is the first, the most powerful of all empires.” (hal. 3).
Dengan demikian buku ini bukan hanya tentang perubahan iklim modern, tetapi sejarah gagasan iklim sebagai kekuatan politik, budaya, dan epistemik.
Buku ini terstruktur ke dalam beberapa bagian historis: mulai dari pemikiran kuno (Hippocrates, Aristoteles) tentang udara dan kesehatan, pengembangan geografi medis dan determinisme iklim di Eropa, hingga munculnya pemikiran modern tentang iklim, ras, ekonomi, perang, dan keamanan lingkungan. Sebagai contoh, bab-dua “Heir of Hippocrates” mengeksplorasi bagaimana Hippocrates dalam On Airs, Waters, and Places mengaitkan kesehatan manusia dengan kondisi udara, air, dan tempat. Birmingham School of Law+1 Bab berikutnya, “Tropical Terrain: Moral and Medical”, mengeksplorasi bagaimana iklim tropis dipandang oleh Eropa sebagai wilayah yang “kurang produktif” atau “berbahaya”—yang membantu justifikasi kolonialisme. Livingstone memperlihatkan bahwa gagasan ini bukan hanya ilmiah tetapi ideologis, dan berpengaruh pada pengaturan kolonial. Birmingham School of Law+1
Salah satu bagian yang paling menarik adalah bagian ketiga buku yang membahas iklim dan ekonomi—bagaimana pemikir seperti Montesquieu atau Ibn Khaldūn mengaitkan kondisi iklim dengan kemakmuran, karakter bangsa, dan perkembangan ekonomi.
Montesquieu dan Kekaisaran Iklim
Livingston mengamati sebuah pemikiran lama. Sebuah pernyataan dari filsuf abad ke-18, Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, memberinya sebuah nama bagi wilayah konseptual yang dijelajahi dalam pengamatannya hingga dituangkan dalam buku ini. Dalam karya terkenalnya, The Spirit of the Laws, yang pertama kali terbit dalam bahasa Prancis pada tahun 1748, Montesquieu menyatakan bahwa “kekaisaran iklim adalah kekaisaran pertama dan paling kuat dari semua kekaisaran.” Pernyataan ini kontroversial. Pada awal 1750-an, Sorbonne —sebuah lembaga teologi di Universitas Paris yang, atas otoritas kerajaan, harus menyetujui setiap publikasi keagamaan—menyebut klaim tersebut sebagai salah satu bagian yang patut mendapat kecaman. Salah satu masalahnya adalah bahwa Montesquieu dianggap memberikan pengaruh yang terlalu besar kepada iklim dalam menjelaskan adat istiadat dan karakter moral suatu bangsa. Masalah lainnya muncul dari pengamatannya bahwa sistem keyakinan agama tidak dapat dipindahkan secara memadai dari satu rezim iklim ke rezim iklim yang lain—dan bahwa karena itu, iklim telah membatasi wilayah penyebaran baik Kekristenan maupun Islam. Jelaslah bahwa “kekaisaran iklim” yang dimaksud Montesquieu menjalankan kekuasaannya atas wilayah yang membentang begitu luas—sesuatu yang tentu saja membuat gelisah para otoritas keagamaan saat itu.
Sejak zaman Montesquieu, demikian pengamatan Livingston, kekaisaran iklim terus mem-perluas pengaruhnya atas semakin banyak wilayah dalam kehidupan dan kebudayaan manusia. Dan di tengah kekhawatiran global akan konsekuensi dari perubahan iklim yang cepat, kekuasa-an imperialnya tampak akan bertahan hingga masa depan yang tak dapat dipastikan. Di berbagai medan pengetahuan—penelitian teknis, akademia, sains populer, hingga jurnalisme iklim—dalam pengertian konvensionalnya, tampak jelas bagaimana iklim telah menjadi rujukan utama bagi kekuatan elementernya yang menjelaskan begitu banyak hal. Maka dari itu, dalam pembahasan di buku ini Livingstone bebas melintasi batas-batas kabur antara ranah budaya tersebut, sekaligus melanggar garis pemisah antara sains spesialis dan sains populer, antara kecendekiaan mendalam dan sentimen orang awam. Sebelum menelusuri perjalanan kita menjelajahi kekaisaran ini, akan berguna untuk memperlihatkan betapa kuatnya daya penjelasan iklim di tangan para sejarawan profesional, jurnalis sains, dan penulis populer—serta merenungkan beberapa persoalan konseptual yang akan terjalin sepanjang narasi yang mengikuti.”
Dalam bab “Weather, Wealth, and Zonal Economics” Livingstone menguraikan bahwa ide-zona iklim (misalnya iklim dingin menumbuhkan kerja keras, iklim tropis menumbuhkan kemalasan) telah memengaruhi kebijakan pembangunan dan migrasi. Birmingham School of Law+1 Ia memperingatkan bahwa walau tampak usang, pemikiran semacam itu tetap muncul dalam wacana modern—misalnya dalam argumen bahwa kawasan tropis “tertinggal” karena iklim. Kritik seperti yang dikemukakan oleh reviewer menyatakan: “A clear bias towards climate determinism, multiple misuses of causal relationships … suggesting that eastern despotism and subjugation of women are determined by climate.” Goodreads
Ini menjadi catatan penting bahwa Livingstone menunjukkan bagaimana gagasan iklim telah dipakai untuk mendukung ideologi rasial, kolonial, dan ekonomi.
Bagian yang sangat relevan untuk kondisi saat ini adalah bab yang membahas iklim dan konflik/keamanan—termasuk bab seperti “Climate Wars” dan “Securitizing Climate Change”. Livingstone menunjukkan bahwa narasi modern “perubahan iklim akan menyebabkan perang” memiliki akar panjang—sejak zaman kuno ketika iklim dianggap memengaruhi temperamen manusia dan kecenderungan terhadap kekerasan. Birmingham School of Law+1 Ia menulis: ketika kita mengatakan “iklim akan memaksa migrasi”, “iklim akan memicu konflik”, kita sedang memakai kerangka lama—inilah “empire of climate” yang memanfaatkan ketakutan iklim untuk tujuan politik. Seorang pengamat mencatat: “There are dark forces lurking within climate’s empire … These toxicities include climate’s role in the reproduction of racial ideology, the justification of slavery, the rationalising of conflict.” Mike Hulme
Dengan demikian bagian ini mengajak kita berhati-hati: narasi iklim dapat digunakan tidak hanya untuk aksi adil, tetapi juga untuk justifikasi yang tak adil.
Di bab pertama (A Matter of Degree), Livingstone memperkenalkan tema inti bukunya dengan mengutip pepatah Montesquieu, seperti diuraikan di atas, bahwa “kekaisaran iklim adalah yang pertama, paling kuat dari semua kekaisaran.” Pernyataan ini membuka kerangka konseptual untuk menyelidiki bagaimana gagasan iklim — bukan sekadar cuaca — telah dijadikan kekuatan penjelasan dalam ranah sosial, politik, dan intelektual sepanjang sejarah. Livingstone menggunakan konsep “empire of climate” (kekaisaran iklim) bukan secara harfiah, tetapi sebagai metafora untuk menandai pengaruh besar iklim terhadap cara manusia memahami dirinya dan dunia sekitarnya. pup-assets.imgix.net+2bsls.ac.uk+2
Bagi Livingstone wacana tentang iklim telah melintasi domain berbagai disiplin: dari sains teknis dan penelitian ilmiah hingga jurnalisme populer. Ia menekankan bahwa iklim berfungsi sebagai naratif dominan yang menjelaskan perubahan masa lalu sekaligus memperkirakan masa depan — bahkan, di era modern, banyak orang mengandalkan skenario “derajat panas” (seberapa banyak kenaikan suhu global) untuk meramalkan bencana ekologis dan sosial. Scribd
Sebagai contoh kontemporer, Livingstone menunjuk proyek-proyek media populer seperti pertunjukan “Six Degrees Could Change the World” dari National Geographic, di mana pemirsa diajak membayangkan masa depan bumi seiring kenaikan suhu satu derajat demi satu derajat. Pada titik tertentu, setiap kenaikan derajat disertai ramalan kehancuran: pulau-pulau kecil tenggelam, badai makin besar, hingga populasi pengungsi iklim yang sangat besar. Cara ini, menurut Livingstone, adalah realisasi modern dari gagasan lama bahwa iklim bukan hanya latar, tetapi aktor kultural dan historis yang menentukan nasib manusia. Scribd
Livingstone juga mengakui kata “empire” menantang: ia mengundang pembaca melewati batas antara sains murni dengan wacana populer, dan meneliti bagaimana ide determinasian iklim tak hanya muncul dari ilmuwan, melainkan juga dari jurnalis, penulis populer, dan pemikir publik. Dalam perjalanan intelektualnya, ia menunjukkan bagaimana iklim bertahan sebagai kerangka penjelasan — kadang sebagai metafora, kadang sebagai agen yang sangat nyata — dalam narasi kesehatan manusia, perang, ekonomi, dan perubahan sosial. bsls.ac.uk
Gagasan determinisme iklim, menurut Livingstone, tidak pernah hilang meskipun sains modern banyak mengoreksi atau menolak teori-teori lama. Sebaliknya, ide-ide tersebut terus muncul kembali dalam diskusi kontemporer, terutama dalam konteks perubahan iklim global: bagaimana kenaikan suhu, ekstrem cuaca, atau ketidakstabilan iklim dipahami dan digunakan sebagai lensa analitis oleh berbagai aktor publik dan ilmiah. whp-journals.co.uk
Dengan menyajikan bab pembuka ini, Livingstone mempersiapkan pembaca untuk perjalanan intelektual melalui empat tema besar — kesehatan, pikiran, kekayaan, dan perang — di mana determinisme iklim telah memainkan peran historis kuat. Ia mengajak pembaca untuk mempertanyakan: sejauh mana iklim, yang tampaknya natural, telah menjadi kekuatan budaya dan politik yang “mengais” kehidupan manusia dari masa ke masa.
Secara konseptual, Bab 1 berfungsi sebagai fondasi: Livingstone menetapkan bahwa iklim adalah ide, tidak hanya fenomena fisik. Ini penting karena membantu kita melihat bahwa pemikiran iklim membawa beban politik, sosial, dan etis — bukan sekadar data meteorologis.. Dalam konteks modern, framing “derajat perubahan” (misalnya, 1 °C, 2 °C, dan seterusnya) menjadi sangat dominan dalam diskursus iklim — dan Livingstone menunjukkan bahwa pola pikir ini memiliki akar intelektual yang dalam. Secara kritis, Bab ini mengingatkan bahwa narasi iklim bisa menjadi alat kekuasaan: bukan hanya menjelaskan, tetapi juga membentuk politik (siapa yang diprediksi menderita, siapa yang harus diselamatkan).
Bagi aktivisme iklim, pemahaman bahwa ide iklim tidak netral sangat penting: perubahan kebijakan iklim tidak bisa hanya didorong oleh data ilmiah, tetapi juga harus menyadari bagaimana gagasan iklim telah digunakan di masa lalu untuk menjustifikasi ketidakadilan (misalnya, rasial, kolonial).
Relevansi untuk dunia saat ini sangat besar. Kita hidup dalam era di mana perubahan iklim tidak hanya soal suhu naik, tetapi soal keadilan, geopolitik, ras, ekonomi—persis seperti tema buku ini. Livingstone mengajak kita memahami bahwa gagasan iklim bukanlah netral; ia dibentuk oleh kekuasaan, kolonialisme, dan ideologi. Untuk Indonesia, konteksnya panjang: sebagai negara tropis, bekas kolonial, dengan tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, migrasi internal, dan ketimpangan pembangunan. Buku ini membantu kita menyadari bahwa wacana pembangunan (“kita tertinggal karena iklim tropis”) bisa menjadi jebakan—kita harus membalik narasi dan memperkuat bahwa iklim tropis memiliki potensi besar. Misalnya, alih teknologi energi terbarukan di Indonesia harus disertai kesadaran bahwa tropis bukan kelemahan tetapi aset.
Secara metodologis dan teoritis, Livingstone melakukan kajian sejarah gagasan yang sangat ekstensif—lebih dari 550 halaman kajian lintas zaman dan wilayah. Pujian datang dari banyak pengamat: Publishers Weekly menyebutnya “sweeping chronicle … well worth the effort.” PublishersWeekly.com Namun ada kritik: salah satunya bahwa buku ini sangat luas hingga kadang terasa kurang mendalam pada kasus-tertentu, atau bahwa penulis bisa menekan lebih keras bahaya determinisme iklim kontemporer. Seperti ulasan oleh Hulme mengatakan:
“Livingstone could … have pressed home even more strongly the dangers of ‘climatic geography [being used to] choreograph humanity’s global drama’.” Mike Hulme Ini menunjukkan bahwa meskipun buku berharga, pembaca yang mencari panduan kebijakan spesifik mungkin merasa belum cukup.
Saya ingin mengutip juga dari pemikir lain yang menegaskan esensi relasi manusia-alam: misalnya Rachel Carson dalam Silent Spring menulis bahwa “in nature nothing exists alone.” Filosof Muslim seperti Fazlun Khalid menegaskan bahwa manusia adalah khalifah yang dipanggil menjaga alam, bukan menaklukkannya. Kutipan ini meneguhkan bahwa memahami iklim sebagai gagasan politik-budaya memerlukan etika relasi. Buku Livingstone menguatkan bahwa pemahaman iklim harus dibebaskan dari narasi dominasi dan kolonialisasi.
Sebagai kesimpulan, The Empire of Climate menawarkan kontribusi penting: ia membuka mata kita bahwa ide “iklim” telah lama menjadi medan kuasa—menentukan siapa berkuasa, siapa dinilai produktif, siapa dianggap rusak. Ia mengajak kita untuk memeriksa narasi pembangunan, kolonial, dan ekologi dengan lensa kritis. Bagi Indonesia dan banyak negara tropis, tantangan-nya adalah membalik relasi: mengubah iklim tropis dari argumen kelemahan menjadi kekuatan. Sebagai langkah praktis: kita bisa mereformasi pendidikan lingkungan, mengevaluasi kebijakan pembangunan dan perkotaan yang memakai narasi “iklim kita problem”, dan menguatkan suara masyarakat adat serta pengetahuan lokal. Buku ini bukan sekadar sejarah ide—ia adalah panggilan untuk bertindak dengan kesadaran historis dan politik. Sebagaimana Livingstone menulis: “To blame people’s behaviour on climate risks repeating the imperious and racist justifications for colonialism and slavery.” PublishersWeekly.com+1
Di Bab 5 — Climate, Cognition, and Human Evolution, Livingstone mengeksplorasi bagaimana gagasan iklim telah digunakan dalam sejarah pemikiran sebagai penjelasan atas evolusi manusia, terutama dalam perkembangan kognisi (daya pikir) dan ukuran otak. Dia membingkai ini sebagai bagian dari “kekaisaran iklim” — bahwa iklim bukan hanya latar bagi kehidupan manusia, tetapi agen aktif dalam membentuk sifat manusia itu sendiri.
Livingstone menelusuri akar pemikiran ini ke masa ilmuwan awal dan pemikir abad ke-19 dan ke-20, yang menghubungkan variasi iklim dengan perbedaan ras, kepintaran, dan “kesiapan evolusioner” manusia. Dalam konteks ini, iklim bukan lagi sekadar faktor lingkungan: ia diandaikan sebagai penyumbang pembentuk sifat manusia seperti daya berfikir, adaptabilitas, dan kreativitas.
Lebih jauh, Livingstone menunjukkan bahwa teori-teori semacam itu pernah digunakan untuk membenarkan ide eugenika dan hierarki rasial: populasi yang tinggal di “iklim keras” dianggap lebih tangguh dan lebih inovatif, sedangkan iklim tropis sering dikaitkan dengan kemalasan atau ketidakproduktifan. Gagasan-gagasan ini kemudian menembus wacana antropologi, biogeografi, dan teori sosial.
Namun bab ini tidak berhenti pada pemikiran kuno atau pseudoscience: Livingstone juga menyimak bagaimana ide iklim dan evolusi manusia telah muncul kembali dalam wacana ilmiah modern. Di era paleontologi dan paleoantropologi, ilmuwan mengeksplorasi apakah perubahan iklim di Pleistosen (zaman glasial dan interglasial) mungkin telah memengaruhi evolusi otak manusia, migrasi hominin, dan adaptasi perilaku. Ide bahwa variabilitas iklim telah mendorong seleksi untuk fleksibilitas kognitif dan inovasi menjadi pusat debat: apakah masa perubahan iklim besar-besaran adalah mesin evolusi bagi manusia.
Livingstone juga memberikan narasi bahwa gagasan semacam determinisme iklim dalam evolusi manusia tak sepenuhnya mati; ia terus hidup dalam bentuk — kadang implisit — dalam wacana populer dan ilmiah, terutama ketika perubahan iklim masa kini dihubungkan dengan risiko masa depan evolusi manusia, atau setidaknya tekanan selektif baru. Dengan demikian, dia menyajikan bab ini sebagai contoh bagaimana “ide iklim” telah menjadi jembatan antara pemikiran evolusioner, sains, dan diskursus publik.
The Empire of Climate menggarisbawahi ketegangan antara determinisme iklim — gagasan bahwa iklim memaksa manusia menjadi seperti apa mereka sekarang — dengan pengamatan ilmiah modern yang menunjukkan bahwa manusia sangat fleksibel. Ide lama yang berbahaya (misalnya rasialisme yang dibenarkan melalui iklim) menghadapi kritik dari sains kontemporer, tetapi akar pemikiran tersebut sulit hilang sepenuhnya (Determinisme vs Fleksibilitas).
Menurut Livingstone, tidak cukup hanya melihat iklim sebagai tantangan luar yang dihadapi manusia; dalam pemikiran historis, iklim sering dianggap memiliki agen sendiri — “kekuatan” yang membentuk otak manusia, kapasitas berpikir, dan pola migrasi. Ini adalah cara pemikiran metaforis yang memberi iklim tempat aktif dalam sejarah manusia (Iklim sebagai Agen Evolusi).
Ia juga memperlihatkan risiko ketika teori ilmiah (atau teoritis) disalahgunakan untuk justifikasi sosial: ide bahwa “beberapa ras lebih unggul secara kognitif karena iklim asal” pernah dipakai untuk mendukung eugenika, diskriminasi rasial, dan kolonialisme. Livingstone memperingatkan bahwa pemikiran semacam ini punya akar historis panjang dan bisa “hidup kembali” dalam wacana kontemporer, terutama saat orang berbicara tentang adaptasi iklim di masa depan (Penyalahgunaan Ilmiah).
Di zaman krisis iklim, gagasan bahwa manusia bisa “berselekusi” oleh perubahan iklim — atau bahwa adaptasi iklim bisa menjadi tekanan evolusioner — bukan sekadar spekulasi ilmiah, tetapi muncul di diskusi publik. Livingstone menegaskan bahwa narasi ini perlu dipahami dalam konteks sejarah gagasan iklim, agar tidak jatuh pada retorika deterministik yang merugikan (misalnya meremehkan kerentanan kelompok tertentu) sekaligus membuka refleksi etis dan filosofis tentang masa depan manusia.
Bab 7 — Weather, Wealth, and Zonal Economics menelusuri bagaimana cuaca dan iklim tidak hanya dilihat sebagai latar geografis, tetapi sebagai penjelasan terhadap kemajuan ekonomi, distribusi kekayaan, dan ketimpangan global yang berlangsung selama berabad-abad. David Livingstone menunjukkan bahwa sejak era kolonial hingga zaman modern, terdapat tradisi pemikiran yang meyakini bahwa ekonomi dunia dapat dijelaskan melalui garis lintang — seolah-olah kemiskinan dan kemajuan adalah produk dari suhu udara.
Pada Bab ini Livingstone membahas iklim sebagai penentu kekayaan dan ketimpangan global dengan argumentasi sebagai berikut:
1. Dari Geografi ke Ideologi
Livingstone mengulas bahwa sejak abad ke-18, berbagai ilmuwan, ekonom, dan administrator kolonial mulai membangun teori ekonomi berdasarkan zona iklim. Ide ini kemudian bergeser dari sekadar observasi geografis menjadi justifikasi moral dan politik.
Iklim tropis dianggap tidak kondusif untuk kerja keras, akumulasi modal, dan rasionalitas ekonomi — sedangkan iklim sedang (temperate climate) dianggap sebagai inkubator peradaban, kerja keras, dan disiplin.
Pemikiran semacam ini perlahan menjadi zonal economics, yaitu model pemetaan kekayaan berdasarkan iklim, yang sering digunakan dalam kebijakan kolonial dan pembangunan internasional. Zonal economics secara tidak langsung melahirkan pembenaran politis bahwa kemiskinan di wilayah selatan dunia (Global South) adalah akibat alamiah dari iklim mereka — bukan dari kolonialisme atau eksploitasi.
2. Weather as Economic Destiny
Livingstone menyoroti bagaimana pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, para ekonom dan ilmuwan sosial berusaha menjadikan cuaca sebagai variabel permanen dalam pertumbuhan ekonomi.
Misalnya, fluktuasi musim dingin disebut sebagai pendorong inovasi — karena manusia dipaksa berpikir lebih keras untuk bertahan. Sebaliknya, panas dan kelembaban tropis dikaitkan dengan kelambanan, penyakit, serta minimnya kapasitas menunda konsumsi demi investasi jangka panjang.
Dengan cara ini, iklim masuk ke “ekonomi moral” peradaban: cuaca menjadi karakter, karakter menjadi kebijakan. Teori ini menjalar ke dalam pendidikan kolonial, doktrin pembangunan, bahkan ke teori entrepreneurship dan psikologi ekonomi pada abad ke-20.
3. Kritik terhadap Determinisme Kesejahteraan
Livingstone dengan hati-hati mengkritik determinisme zonal ini. Ia menyingkap bahwa banyak konsep ekonomi berbasis iklim muncul sejalan dengan kepentingan kolonial. “Fakta ilmiah” seringkali bersandar pada asumsi budaya Eropa — bukan pada data objektif.
Lebih jauh, zonal economics sering menutupi realitas lain:
- Sejarah perbudakan dan ekstraksi sumber daya tropis demi akumulasi modal di Barat.
- Kebijakan perdagangan yang merugikan negara beriklim panas.
- Eksploitasi tenaga kerja dari selatan dunia untuk membangun ekonomi utara dunia.
Dalam konteks ini, iklim tidak lagi netral: ia menjadi alat untuk membangun narasi global tentang siapa yang “layak makmur” dan siapa yang “ditakdirkan miskin”.
4. Masa Kini: Iklim Masih Bicara di Pasar Global
Livingstone menunjukkan bahwa dalam ekonomi modern, cuaca tetap menjadi variabel fundamental — dari industri pertanian hingga high-frequency trading. Lonjakan ekonomi bisa dipicu oleh gelombang dingin, dan krisis bisa datang dari badai yang tidak terduga. Banyak perusahaan mulai membangun strategi finansial berbasis klimatologi; bahkan Bloomberg dan Goldman Sachs kini memiliki divisi weather risk analytics. Tetapi Livingstone juga memperingat-kan bahwa iklim dalam ekonomi saat ini bukan hanya risiko — ia kini menjadi komoditas. Data iklim dibeli dan dijual, carbon trading berkembang, bencana alam dikapitalisasi melalui asuransi. Cuaca bukan lagi takdir — ia sudah masuk neraca keuangan global.
Climate Wars
Livingstone membuka Bab Bab 10 — Climate Wars dengan memberi gambaran suram tentang masa depan: dunia di mana perubahan iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga pemicu konflik politik, perang sumber daya, migrasi massal, keamanan nasional, hingga penataan ulang peta kekuasaan global. Inilah situasi iklim ketika iklim menjadi pertempuran geopolitik. David Livingstone menelusuri bagaimana ide tentang “climate wars” bukan fiksi spekulatif, melainkan telah menjadi bagian dari narasi serius dalam militer, lembaga intelijen, pusat penelitian strategis, hingga kebijakan negara.
1. Dari Sains ke Strategi Militer
Livingstone menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-21, militer dan lembaga intelijen dunia — termasuk Pentagon dan NATO — mulai menggunakan istilah “threat multiplier” untuk menggambarkan iklim. Artinya, iklim tidak selalu menyebabkan perang… tetapi ia mempercepat dan memperparah konflik yang sudah ada: kemiskinan, kelangkaan air, migrasi, perebutan tanah, hingga instabilitas politik.
Laporan Pentagon tahun 2003 bahkan memperingatkan bahwa perubahan iklim ekstrem dapat menimbulkan “darurat keamanan global”—dengan konflik antarnegara yang mirip masa perang dingin, tetapi berbasis ekologi. Sejak itu, iklim masuk ke dalam dokumen intelijen, skenario simulasi militer, dan policy-making internasional. Iklim tak lagi dipandang sebagai cuaca; ia menjadi aktor politik.
2. Migrasi dan Perbatasan yang Memanas
Livingstone memperlihatkan bahwa “climate refugees”—pengungsi iklim—akan menjadi salah satu isu terbesar abad ke-21. Naiknya permukaan laut, gagal panen, kekeringan, dan bencana alam diprediksi mengusir jutaan manusia dari tempat tinggal mereka. Akibatnya, iklim langsung terkait isu perbatasan, kedaulatan negara, dan kebijakan imigrasi.
Dalam narasi geopolitik, migrasi iklim mulai dilihat sebagai ancaman. Politik perbatasan mengeras. Tembok digambar ulang. Batas negara bukan sekadar wilayah administratif — melainkan benteng pertahanan terhadap iklim.
Pada titik ini, Livingstone mengingatkan: ketika iklim dipolitisasi, kemanusiaan sering dikorbankan.
3. Perebutan Sumber Daya: Air, Makanan, dan Bahan Tambang
Bab ini menggambarkan masa depan konflik bukan lagi soal ideologi atau agama, melainkan akses terhadap sumber daya vital seperti air bersih, tanah subur, energi, dan mineral langka. Livingstone menulis bahwa banyak wilayah dunia — dari Timur Tengah hingga Afrika Sub-Sahara — sudah mengalami “perang tersembunyi” akibat iklim. Perubahan cuaca ekstrem membuat sumber daya makin langka, menyalakan kompetisi yang bisa berubah menjadi konflik terbuka.
Gagasan eco-nationalism mulai tumbuh: negara bertindak agresif demi melindungi sumber daya alamnya. Ketahanan pangan dan krisis energi jadi isu pertahanan negara. Iklim menjadi satu hal yang mendefinisikan strategi geopolitik.
4. Dari Krisis ke Otoritarianisme Hijau?
Livingstone secara kritis mewanti-wanti bahwa narasi “climate wars” bisa menjadi pembenaran untuk lahirnya bentuk baru otoritarianisme berbasis iklim — disebut sebagian pemikir sebagai “green authoritarianism”. Jika iklim dianggap ancaman eksistensial, maka keputusan politis mungkin akan dilegitimasi tanpa demokrasi: demi iklim, demokrasi bisa dipinggirkan; demi keamanan, kebebasan dapat dikorbankan. Bab ini mendorong kita menanyakan pertanyaan penting: Dalam dunia yang dilanda krisis iklim, siapa yang akan memegang kekuasaan — dan atas nama siapa mereka akan bertindak?
5. Peringatan Terakhir: Iklim Bisa Menyatukan atau Memecah
Livingstone menutup bab ini dengan refleksi: “Climate wars” bukan takdir. Itu adalah pilihan — hasil interaksi antara sains, politik, ekonomi, dan tafsir kita tentang ketidakpastian. Iklim bisa menjadi alasan untuk membangun tembok… tetapi juga bisa menjadi fondasi untuk solidaritas global.
Yang menentukan bukan hanya cuacanya. Tapi cara manusia membaca cuaca itu — dan atas nama siapa kebijakan dibuat.
Indonesia dan Global South dalam Wacana Iklim
Indonesia — negara kepulauan yang rawan banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut — adalah contoh nyata “frontline of climate wars”. Bukan perang militer terbuka, tetapi perebut-an lahan, migrasi desa-kota, konflik agraria, privatisasi air, dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan perlahan menciptakan arena konflik yang makin kompleks.
Dalam perspektif Livingstone, Indonesia harus berhati-hati: jangan sampai iklim menjadi alasan untuk kekuasaan yang terkonsentrasi, atau kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan korporasi dan investasi. Karena pada akhirnya, perang iklim bukan perang mela-wan alam — melainkan tentang cara kita hidup bersama, di tengah ketidakpastian yang sama.
Perubahan iklim bisa mendorong konflik di Indonesia, mengapa? Perubahan iklim memperkuat dua mekanisme utama yang memicu konflik. Pertama, meningkatkan kelangkaan (air, tanah subur, sumber ikan) sehingga bersaingnya kelompok atas sumber hidup makin tajam.
Kedua, mengganggu institusi penyelesaian konflik (negara/lokal yang lemah, birokrasi korup, lemahnya akses ke pengadilan), sehingga persaingan kecil mudah menyulut ketegangan lebih luas. Di Indonesia kedua mekanisme ini diperkaya oleh warisan koloni dan pembangunan ekstraktif: peraturan agraria yang tumpang tindih, konsesi besar untuk perusahaan tambang/sawit, serta relasi ekonomi-politik yang memberi insentif penguasaan sumber daya cepat.
Secara praktis, perubahan iklim membuat ranah konflik menjadi lebih “hibrid”: bukan sekadar tentara vs tentara, tetapi perebutan akses (air, lahan), pemindahan penduduk (migrasi internal), kriminalisasi perlawanan lokal, dan politisasi keamanan (penetapan wilayah sebagai “zona keamanan” untuk investasi). Ini adalah bentuk climate insecurity yang bersifat struktural.
2) Bentuk konflik yang muncul
a) Konflik agraria dan ekstraksi lahan
Perusahaan perkebunan sawit, tambang batu bara, dan pulp & paper memperluas areal di hutan—sering atas lahan adat yang belum diakui. Dalam situasi kekeringan, atau setelah ke-bakaran (seperti kejadian kebakaran lahan gambut Riau–Kalimantan), ketegangan meningkat: petani kehilangan ladang, pohon produktif mati, dan akses tradisional ke lahan dirusak. Konflik berujung pada pengusiran, kriminalisasi pemimpin komunitas, dan bentrokan antara masyara-kat dan aparat perusahaan/polisi. Di daerah seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Papua, pola ini sudah terlihat berulang.
b) Politik air dan privatiasi layanan
Kota-kota besar seperti Jakarta menghadapi penurunan muka tanah dan gangguan pasokan air bersih. Di wilayah pedesaan, sumur kering dan akses air menurun saat musim kemarau panjang. Tekanan ini memunculkan persaingan antara industri (pabrik sawit, tambang) dan masyarakat setempat; di beberapa kasus, perusahaan menguasai sumber air melalui izin atau pengeboran skala besar. Komersialisasi air, atau favoritisme perizinan, menimbulkan resistensi masyarakat dan kadang tindakan protes yang dipatahkan dengan kekerasan.
c) Migrasi internal dan konflik perkotaan
Kenaikan permukaan laut, abrasi pantai (mis. beberapa pulau kecil di Kepulauan Seribu, pesisir utara Jawa), dan hilangnya mata pencaharian nelayan mendorong migrasi ke kota. Gelombang migran ini menimbulkan tekanan pada layanan publik, lapangan kerja informal, dan ruang hunian, yang memicu gesekan sosial dan kriminalisasi migran internal. Di beberapa kota, kelompok lokal melihat pendatang sebagai “ancaman ekonomi” sehingga muncul diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan antar-komunitas.
d) Keamanan dan militerisasi ruang ekstraktif
Di wilayah seperti Papua, ketegangan antara masyarakat adat, perusahaan tambang, dan negara sering dibingkai sebagai masalah keamanan. Perubahan iklim yang mengganggu mata pencaharian menambah frustrasi. Pemerintah merespons sebagian dengan pendekatan keamanan (pengiriman aparat), yang sering memperburuk dinamika — menyebabkan siklus kekerasan, pelanggaran HAM, dan memperlemah peluang dialog.
3) Mengapa pola ini bisa menajam menjadi “climate wars” — faktor pemicu eskalasi
Beberapa faktor struktural berisiko mengubah konflik lokal menjadi konflik luas:
- Kelemahan pengakuan hak tanah adat dan lemahnya reforma agraria. Tanpa kepastian hukum, klaim rakyat mudah digusur demi investasi.
- Korelasi antara kekayaan sumber daya & patronase politik. Oligarki atau elite lokal yang menguasai izin menolak pembatasan, mempolitisasi konflik menjadi legitimasi keamanan.
- Institusi yang tidak adaptif. BPBD, dinas pertanian, atau lembaga penyelesaian sengketa yang tidak dilatih untuk konflik iklim akan gagal meredam ketegangan.
- Narasi securitizing (mengkaitkan pemanfaatan sumber daya dengan ancaman nasional). Framing ini memberi legitimasi penggunaan kekerasan.
- Krisis multi-lapisan (iklim + pandemi + krisis ekonomi). Ketika banyak tekanan bersamaan, fragmen sosial mudah runtuh.
4) Strategi pencegahan & respons (praktis, terprioritaskan)
Saya susun rekomendasi dalam jangka pendek (0–2 tahun), menengah (2–7 tahun), dan panjang (>7 tahun), dengan aktor utama yang disarankan.
A. Jangka Pendek — meredam ketegangan & lindungi warga rentan
- Pendekatan cepat berbasis konflik-sensitif: BNPB, dinas provinsi, dan lembaga donor harus mensyaratkan conflict sensitivity assessment pada respon darurat kebakaran/gangguan panen.
- Moratorium perizinan untuk areal rawan konflik: Sementara menunggu peta resmi konflik-iklim, moratorium menghalangi ekspansi tambang/sawit di wilayah yang rawan konflik (dilakukan oleh K/L terkait + moratorium daerah).
- Penguatan akses pelayanan dasar: Prioritaskan distribusi air bersih darurat, subsidi pupuk/benih tahan gagal panen, dan jaring pengaman sosial pada komunitas terdampak.
- Perlindungan pemimpin masyarakat dan jurnalis: mekanisme pengamanan cepat dan hotline untuk laporan intimidasi/kriminalisasi.
- Forum mediasi lokal: fasilitasi dialog antara perusahaan–masyarakat–pemerintah dipandu pihak netral (universitas, ormas), untuk kesepakatan sementara akses sumber air/lahan.
B. Jangka Menengah — tata kelola, hukum, dan alternatif ekonomi
- Penyelesaian reforma agraria yang nyata & pendaftaran tanah adat (recognition & registration): percepat pengakuan hak komunal (desa adat, Hutan Adat — sesuai UU). Gunakan dana APBN/APBD + bantuan donor untuk sertifikasi partisipatif.
- Persyaratan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang mengikat: perkuat regulasi agar investasi hanya boleh berjalan setelah FPIC autentik. Pengawasan independen (ombudsman agraria) wajib ada.
- Kebijakan air berbasis hak dan alokasi prioritas publik: perkuat regulasi penggunaan air, lisensi perusahaan, dan penaikan pajak konsumsi sumber daya untuk mendanai restorasi ekosistem.
- Transisi ekonomi wilayah ekstraktif: program diversifikasi ekonomi untuk wilayah tambang/kelapa sawit—pelatihan, investasi UMKM hijau, dan dana transisi untuk pekerja.
- Sistem insentif dan akuntabilitas korporasi: aturan keberlanjutan bagi korporasi (due diligence lingkungan-sosial) + sanksi efektif; tunjuk badan audit independen.
C. Jangka Panjang — transformasi struktural untuk mencegah “climate wars”
- Perubahan kerangka fiskal & investasi: alihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dan buat mekanisme transfer fiskal untuk mendukung daerah rawan iklim.
- Desentralisasi keadilan lingkungan & penguatan legislatif daerah: dorong DPRD untuk membuat peraturan daerah yang melindungi hak adat, dengan dukungan kapasitas teknis.
- Restorasi ekosistem skala besar: restorasi gambut (REDD+/program setara), reforestasi pesisir (mangrove), dan konservasi daerah penyangga air. Ini mengurangi risiko banjir/abrasi dan memulihkan mata pencaharian.
- Perencanaan ruang berbasis iklim (land-use planning): tata ruang yang realistis—hindari lokasi permukiman/pabrik di zona rawan banjir/gambut.
- Pendanaan jangka panjang untuk adaptasi komunitas: green bonds daerah, akses modal mikro adaptif, dan program insuransi mikro untuk petani.
5) Mekanisme pengawasan, indikator, dan early warning
Agar kebijakan efektif, butuh M&E (monitoring & evaluation) dan indikator konflik-iklim:
- Indikator awal: penurunan debit sumur >30% selama dua musim; peningkatan pengaduan tanah; lonjakan pengadaan izin di wilayah adat.
- Dashboard nasional: gabungkan data BMKG, BNPB, Kementan, KemenLHK, ATR/BPN untuk melihat overlap risiko iklim + izin + konflik.
- Mekanisme Ombudsman Agraria-Ikim: satu pintu pelaporan korporasi, pelepasan izin ilegal, kriminalisasi aktivis — hasil audit publik tiap tahun.
- Fund for Rapid Response: dana cadangan untuk dukung mediasi, subsidi, dan bantuan pangan pada titik konflik awal.
6) Peran aktor: siapa harus melakukan apa
- Pemerintah Pusat (KemenLHK, Kementan, ATR/BPN, BNPB, KemenESDM, KemenKo Perekonomian):kebijakan makro, moratorium, restorasi, dana transisi.
- Pemerintah Daerah: pendaftaran tanah adat, peraturan daerah pro-lingkungan, penegakan lokal.
- Perusahaan & Korporasi: due diligence, FPIC, benefit-sharing, mekanisme keluhan yang aksesibel.
- Masyarakat Adat & Komunitas Lokal: partisipasi di semua tahapan, pengelolaan tanah berbasis kearifan lokal.
- Masyarakat Sipil & Akademia: monitoring independen, kapasitas mediasi, litigasi strategis.
- Donor & Lembaga Internasional: dukungan teknis, insentif finansial untuk restorasi, garansi investasi hijau.
7) Risiko kebijakan yang harus dihindari
- Militarisasi sebagai solusi utama. Penempatan aparat besar tanpa dialog memperburuk siklus kekerasan.
- Papan hijau tanpa substansi (greenwashing). Izin baru untuk “energi hijau” yang menyingkirkan masyarakat asli akan memicu konflik baru.
- Sosialisasi tanpa akuntabilitas. Program yang tidak melibatkan pemilik lokal mengundang resistensi.
Catatan Akhir: keamanan iklim adalah masalah tata kelola dan keadilan
Buku ini mempunyai relevansi bagi dunia saat ini dalam setidaknya tiga hal: Pertama, Ilmu evolusi dan iklim: Dalam studi paleoantropologi modern, pertanyaan tentang seberapa besar variabilitas iklim di masa lampau memengaruhi evolusi manusia tetap relevan. Jika iklim pernah menjadi agen seleksi, bisa jadi tekanan iklim masa depan juga akan memberi dampak tidak hanya ekologis, tetapi biologi dan sosial. Kedua, Etika dan politik adaptasi iklim: Pemahaman historis bahwa iklim telah dipakai untuk justifikasi ideologi rasial memberi pelajaran penting dalam debat adaptasi dan migrasi iklim: kita harus berhati-hati agar kebijakan iklim masa depan tidak mengulang narasi lama yang menstigmatisasi kelompok rentan berdasarkan asal geografis atau “kemampuan adaptasi.” Ketiga, Diskursus publik dan sains: Karena ide iklim-evolusi ini bisa muncul kembali dalam wacana populer (misalnya dalam artikel populer, dokumenter, atau politik), penting untuk menyadari akar intelektualnya agar kita bisa membedakan antara sains murni, metafora, dan retorika ideologis.
“Climate wars” bukan sekadar soal cuaca — mereka adalah konsekuensi dari kegagalan tata kelola, pengakuan hak, dan politik pembangunan. Di Indonesia, risiko itu nyata: dari kebakaran gambut sampai pemindahan komunitas pesisir. Namun di sana juga terletak peluang: restorasi ekosistem, penguatan hak adat, dan transisi ekonomi yang inklusif dapat menjadi pencegah konflik paling efektif.
Praktik terbaik yang paling tahan lama bukan yang memaksakan solusi teknokrat, melainkan yang membangun kepercayaan antara negara, komunitas, dan bisnis. Tanpa itu, tekanan iklim manapun mudah menjadi pemantik konflik yang lebih besar. Dengan strategi terintegrasi (darurat–tata kelola–transformasi struktural), Indonesia dapat mengubah potensi perang iklim menjadi ruang rekonsiliasi dan ketahanan bersama.
Livingstone menegaskan bahwa interpretasi hubungan antara iklim dan kekayaan adalah soal politik pengetahuan. Pertanyaan pentingnya bukan hanya:
“Apakah iklim menentukan ekonomi?”
melainkan:
“Siapa yang mendapat keuntungan dari narasi bahwa iklim menentukan ekonomi?”
Dengan cara ini, bab ini menyarankan agar pembacaan iklim dalam ekonomi harus disertai kesadaran historis: bahwa apa yang disebut “global inequality” mungkin bukan bawaan alam — melainkan buatan sejarah.
Dalam konteks Indonesia — negara tropis yang kerap mendapat label “terhambat oleh iklim” — bab ini memberikan kerangka kritis. Ketergantungan terhadap ekspor sumber daya mentah, narasi “produktivitas rendah”, serta stigma birokrasi lamban sering dipetakan ke iklim tropis.
Namun Livingstone mengingatkan: penjelasan iklim kerap menutupi struktur sejarah ekonomi-politik, termasuk warisan kolonial dan sistem perdagangan dunia yang timpang.
Dengan demikian, bab ini mengajak pembaca bertanya:
Apakah kita membaca iklim sebagai fakta… atau sebagai narasi yang dibentuk kekuasaan ekonomi global? Bagi Livingstone: “Climate is not just a background condition. It is an actor, a historical agent, a sculptor of bodies and minds.”
Dalam buku ini, Livingstone tidak hanya bertanya bagaimana manusia bertahan dari iklim, tetapi juga: Bagaimana iklim membentuk kesadaran manusia? Kita biasanya memahami iklim sebagai data—temperatur, kecepatan angin, kelembaban. Namun Livingstone berargumen bahwa iklim harus dibaca bukan sekadar geofisika, melainkan filsafat sejarah, antropologi kognitif, dan bahkan penentu arah politik global. Iklim bukan ruang hampa. Ia adalah “aktor sejarah”.
Iklim sebagai Arsitek Kesadaran
Sejak masa prasejarah, manusia tidak hanya bertarung melawan cuaca—tetapi bernegosiasi dengannya secara mental. Manusia gurun mengembangkan orientasi spasial dan pengetahuan navigasi lintang—manusia kutub membangun ketahanan tubuh—manusia tropis mengembangkan strategi bertahan hidup berbasis komunitas dan jaringan sosial.
Livingstone menyebut ini sebagai “cognitive climatology”
→ iklim mengolah struktur berpikir manusia.
Pemikiran ini beresonansi dengan Heidegger, bahwa manusia selalu being-in-the-world, tetapi Livingstone memperluasnya menjadi being-in-the-weather.
| Pemikir | Gagasan | Hubungan dengan Livingstone |
| Heidegger | Being-in-the-world | Kesadaran manusia selalu dalam ruang atmosferik |
| Spinoza | Determinisme alam | Iklim mengarahkan kehendak manusia tanpa disadari |
| Ibn Khaldun | Asabiyyah gurun | Solidaritas muncul dari tekanan iklim ekstrem |
| Sloterdijk | Atmosfer sebagai ruang kuasa | Politik udara menentukan kekuasaan modern |
Manusia sebagai Pelancong Atmosfer
Livingstone memberi kita cara baru membaca dunia. Bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan ontologis dan politis. Selama ini kita bertanya:
“Bagaimana cuaca memengaruhi kita?”
Namun pertanyaan baru muncul: “Bagaimana cuaca membentuk siapa kita?”
Di sinilah muncul tugas filosofis baru: Membangun politik, etika, dan spiritualitas berdasarkan kesadaran atmosferik.
Karena jika iklim adalah “empire,” maka manusia adalah pelancong, yang selalu hidup…
di bawah langit yang berubah.
Livingstone memberi pesan yang tegas bahwa iklim adalah ide politik, moral, dan spiritual, bukan sekadar gejala atmosfer. Dalam konteks global maupun Indonesia—dari perdebatan tentang transisi energi hingga eksploitasi hutan tropis—pesan-pesan ini mengingatkan agar kita mengubah cara berpikir: dari “menguasai iklim” menjadi “berdamai dengan iklim”.
Evolusi Manusia: Sebuah Respons Atmosferik
Livingstone menunjukkan bahwa evolusi bukan sekadar seleksi genetik, tetapi respons terhadap tantangan iklim:
- Lompatan neurologis Homo sapiens terjadi saat terjadi perubahan iklim drastis Plestosen → memaksa manusia membangun strategi abstraksi.
- Peradaban laut muncul karena pola angin muson.
- Revolusi pertanian lahir dari stabilitas iklim jangka panjang — ketika cuaca dapat “dipercaya”.
Di sini, iklim menjelma menjadi “pemicu inovasi sekaligus sumber ketakutan kosmik.”
Bahkan mitologi dibentuk oleh iklim:
- Bangsa Nordik membayangkan Ragnarok: kehancuran oleh musim dingin.
- Indonesia memiliki mitos Nyai Roro Kidul: laut sebagai batas dunia manusia.
- Yunani kuno menyembah Zeus—dewa cuaca & langit—sebagai pengatur takdir.
Iklim dan Politik Global – Menuju Climate Realism
Livingstone mengingatkan bahwa konflik hari ini—perang air, migrasi iklim, perebutan lahan subur—akan mendefinisi geopolitik masa depan.
Inilah lahirnya era Climate Wars (Bab 10): “War on terror will be replaced by war for water.”
Di sini, filsafat iklim bertemu dengan realpolitik:
- Kebijakan imigrasi Eropa sangat dipengaruhi ketakutan terhadap migran iklim dari Afrika & Timur Tengah.
- Konflik Palestina–Israel dapat dibaca sebagai perebutan akses terhadap tanah dan air sejak era Mandat Inggris.
- Indonesia menghadapi masa depan serupa: banjir, kekeringan, kenaikan air laut, dan urbanisasi memicu bentuk “kolonialisme internal”.
Indonesia: Menjadi Negara Atmosferik
Dalam konteks Indonesia, filsafat iklim ini menjadi sangat penting:
- Iklim tropis membentuk budaya komunal, bukan individual.
- Kerentanan bencana (tsunami, banjir, gempa) memunculkan teologi bencana dan spiritualitas ekologi.
- IKN (Ibu Kota Nusantara) adalah eksperimen geopolitik atmosferik: pemindahan pusat kuasa berdasarkan kalkulasi iklim.
Livingstone memberi peringatan: “Who controls the weather controls the world — even when they don’t realize it.” Inilah yang membuat Livingstone relevan. Ia mengubah cara kita membaca masa depan manusia: bukan lewat ide, ekonomi, atau moralitas — tetapi cuaca.
Menuju Filsafat Iklim – Proposal Kerangka Pemikiran
| Pilar | Pertanyaan Kunci |
| Ontologi | Apakah manusia adalah makhluk atmosferik? |
| Epistemologi | Apakah pengetahuan lahir dari pengalaman geografis? |
| Etika | Siapa yang bertanggung jawab atas perubahan iklim? |
| Politik | Apakah masa depan adalah perang cuaca? |
| Evolusi | Apakah kecerdasan adalah respons terhadap iklim ekstrem? |
Filsafat iklim menggeser cara kita memahami diri: Manusia bukan hanya makhluk rasional — tetapi makhluk meteorologis.
Bogor, 18 Oktober 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Livingstone, D. N. (2024). The Empire of Climate: A History of an Idea. Princeton University Press.
Tosta, T. (2024, October 8). Review: David N. Livingstone, The Empire of Climate: A History of an Idea. British Society for Literature & Science. Retrieved from https://www.bsls.ac.uk/2024/10/livingstone-david-n-the-empire-of-climate-a-history-of-an-idea/
Hulme, M. (2025, June 17). Review of David Livingstone’s The Empire of Climate. Retrieved from https://mikehulme.org/review-of-david-livingstones-the-empire-of-climate-a-history-of-an-idea/
Kutipan Pendek dari Pemikir & Aktivis Lain (Resonansi Tematik)
- Rachel Carson — Silent Spring:
“In nature nothing exists alone.”
→ Sejalan dengan Livingstone bahwa segala relasi manusia-iklim bersifat interdependen. - Vandana Shiva — Staying Alive:
“The earth democracy is about sharing, not domination.”
→ Menggemakan kritik atas kolonialisme ekologis yang dibahas Livingstone. - Bruno Latour — Facing Gaia:
“We are not outside the climate; we are of it.”
→ Menegaskan posisi manusia bukan pengamat iklim, melainkan bagian darinya. - Fazlun Khalid (pemikir Muslim ekologis):
“The Earth is a trust, not a possession.”
→ Membawa dimensi spiritual tanggung jawab, bukan dominasi. - Jalaluddin Rumi (penyair sufistik):
“The garden of the world has no limits except in your mind.”
→ Menyiratkan bahwa keterbatasan ekologis sering lahir dari keserakahan pikiran manusia.