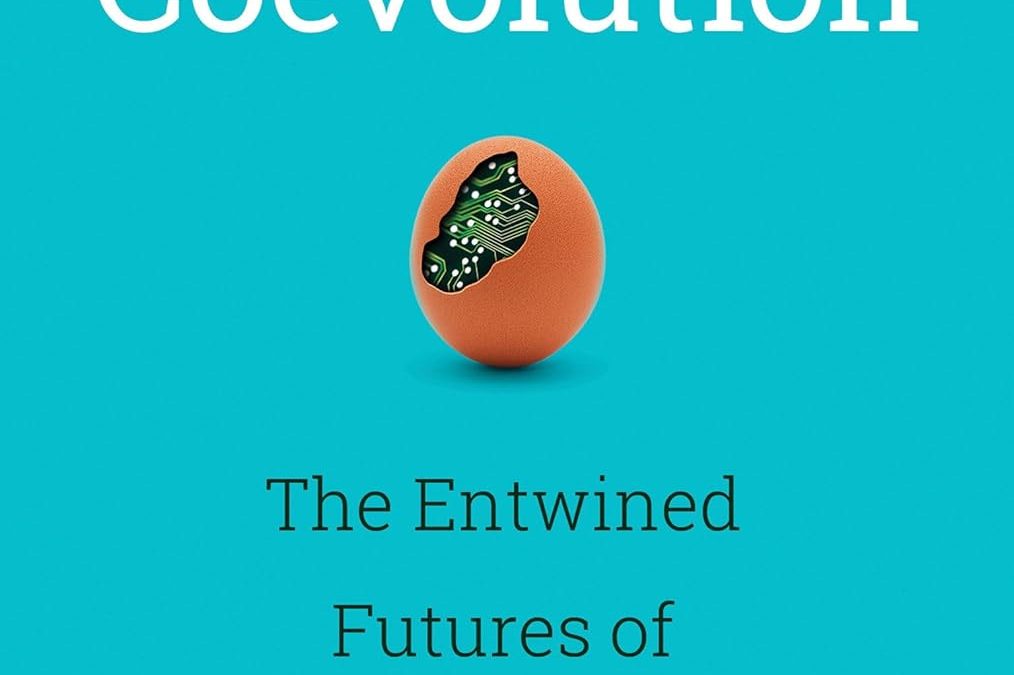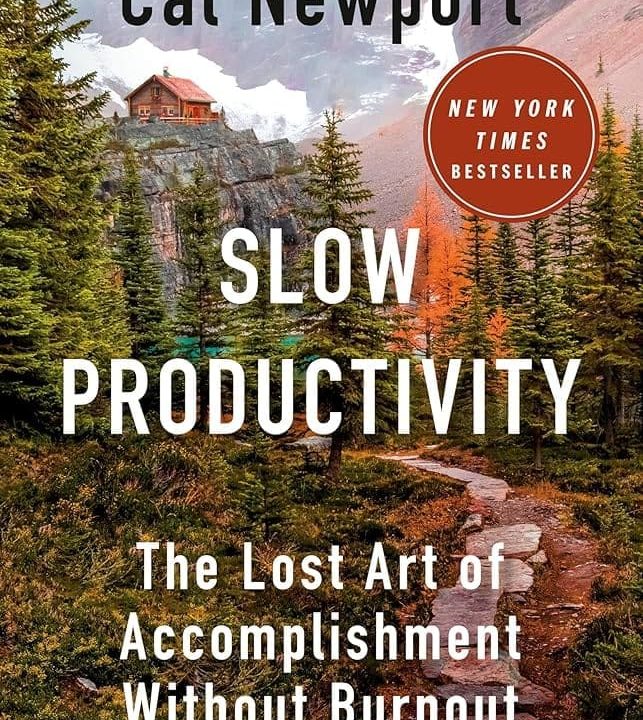Rubarubu #71
The Coevolution:
Kisah Masa Depan Ketergantungan Manusia–Mesin
Bayangkan seorang guru di Jakarta Utara yang pagi hari membuka aplikasi pembelajaran di tablet untuk mengajar muridnya secara daring. Ia menatap layar yang dipenuhi notifikasi, pesan dari orang tua murid, dan pembaruan sistem. Ia menyadari sesuatu yang aneh—bukan hanya dirinya yang bergantung pada alat itu, tetapi perangkat lunak, jaringan, dan algoritme belajar itu sendiri “memperhatikan” cara ia mengetik, menjawab, dan memilih materi. Guru ini tidak lagi sekadar menggunakan teknologi; dalam banyak hal, teknologi membentuk cara ia bekerja, berpikir, bahkan merasakan keterhubungan dengan muridnya. Ini bukan sekadar metafora. Menurut Edward Ashford Lee, di buku The Coevolution: The Entwined Futures of Humans and Machines oleh Edward Ashford Lee (MIT Press, 2020), inilah salah satu wajah paling nyata dari hubungan manusia dan teknologi: bukan dominasi mutlak manusia atas mesin, tetapi koevolusi yang saling membentuk di mana manusia dan mesin hidup saling terkait satu sama lain dalam ekosistem budaya dan teknologi yang semakin kompleks. mitpressbookstore
Melihat Kembali Narasi Kontrol Teknologi
Dalam bagian Preface, Lee, seorang ilmuwan komputer dan insinyur elektro asal Amerika Serikat, serta penulis yang dikenal luas karena gagasan-gagasannya tentang hubungan manusia–teknologi dan masa depan koevolusi antara manusia dan mesin, membuka dengan pertanyaan yang sama sederhana namun mengguncang: apakah manusia benar-benar me-ngendalikan jalannya teknologi, atau justru sebaliknya teknologi telah mendefinisikan ulang manusia? Ia menantang asumsi umum bahwa teknologi adalah hasil dari desain yang sepenuh-nya “terkendali” oleh pikiran manusia—gagasan yang sering disebutnya sebagai digital creationism. Lee menyarankan bahwa pandangan ini mengabaikan fakta bahwa teknologi, seperti organisme biologis, muncul melalui proses yang mirip dengan evolusi Darwin: tercipta, diuji, bermutasi, dan dipilih oleh konteks sosial dan budaya yang lebih besar daripada kehendak individu. SIGBED
Penulis yang sejak muda menunjukkan minat yang mendalam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini menggunakan metafora Richard Dawkins—di mana “sebuah ayam adalah telur yang mencari telur lain”—untuk menerangkan hubungan serupa antara manusia dan mesin. Ia bertanya retoris: apakah manusia mungkin adalah cara bagi komputer untuk “mereproduksi” komputer lain? Pertanyaan ini bukan sekadar retorik; ia menunjukkan hubungan simbiotik yang semakin nyata: teknologi membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, dan membuat keputusan. Teknologi bahkan ikut memengaruhi struktur institusi, ekonomi, dan politik—hal yang dulu dianggap sebagai domain eksklusif manusia. mitpressbookstore
Ia kemudian memperkenalkan gagasan utama buku ini: koevolusi manusia–mesin bukan berarti teknologi akan menggantikan manusia atau sebaliknya, melainkan kedua entitas ini terus berkembang bersama. Ia menegaskan bahwa lebih mungkin hubungan simbiotik itu berkem-bang daripada kepunahan umat manusia secara total atau fusi lengkap menjadi satu entitas hybrid—meskipun semua kemungkinan itu layak dibahas secara serius. mitpressbookstore
Apakah teknologi sebagai “Makhluk Digital”? tanya Lee penuh provokasi. Lee menyelami gagasan apakah teknologi digital bisa dilihat sebagai entitas hidup yang baru dalam ekosistem bumi. Teknologi, terutama algoritma, jaringan, dan sistem digital, berkembang sekilas mirip dengan organisme: mereka memiliki ketergantungan, replikasi, adaptasi, dan bahkan mutasi dalam pengembangan. Namun Lee juga berhati-hati menjelaskan bahwa manusia tidak boleh jatuh pada apa yang disebutnya sebagai dataism—percaya bahwa manusia hanyalah serangkai-an proses data atau bahwa otak manusia sepenuhnya dapat direduksi menjadi mesin. Menurut Lee, ini bukan hanya kesalahan filosofis tetapi juga sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, karena apa yang manusia lakukan dengan pikiran jauh lebih kompleks daripada sekadar komputasi digital semata. Baginya coevolution sebagai lensa pemahaman masa depan tak bisa dielakkan. mitpressbookstore
Dalam mencoba menjawab pertanyaan apakah mesin bisa hidup tanpa manusia, Lee menunjuk-kan bahwa saat ini teknologi digital sangat bergantung pada manusia—manusia memasok energi, konteks sosial, dan tujuan penggunaannya—sementara manusia pun semakin ber-gantung pada teknologi itu sendiri. Ini adalah hubungan simbiotik, bukan satu pihak yang mendominasi sepenuhnya. mitpressbookstore
Koevolusi: Simbiosis yang Berkelanjutan
Lebih jauh, Lee menggambarkan bagaimana coevolution (koevolusi) ini bekerja mirip dengan fenomena biologis: manusia menciptakan teknologi, tetapi teknologi itu kemudian mengubah cara manusia bertindak, berpikir, memutuskan, dan berinteraksi—dukungan yang kemudian kembali memengaruhi arah pengembangan teknologi. Fenomena ini mirip dengan bagaimana organisme dalam ekologi saling memengaruhi evolusi satu sama lain secara timbal-balik. Dalam konteks digital, algoritma yang dirancang untuk rekomendasi bahkan memengaruhi preferensi budaya, perilaku pasar, dan gaya hidup—bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai kekuatan pembentuk dalam kehidupan manusia. mitpressbookstore
Lee membedakan pandangan ini dari narasi “teknologi sebagai monster yang akan mengguling-kan umat manusia.” Ia menunjukkan bahwa lebih mungkin hubungan ini berkembang menuju simbiotik jangka panjang: teknologi tidak sepenuhnya independen, dan manusia tidak sepenuh-nya independen dari teknologi—bahkan dalam cara berpikirnya. Dengan kata lain, masa depan yang berkelanjutan adalah masa depan di mana coevolution manusia–teknologi dipahami, diarahkan, dan diatur untuk kebaikan bersama. mitpressbookstore
Apa relevansi gagasan coevolution ini terhadap sustainability baik global maupun Indonesia? Gagasan Lee beresonansi langsung dengan isu sustainability dunia, karena teknologi digital kini menjadi tulang punggung sistem energi, informasi, transportasi, dan produksi pangan—semua aspek penting keberlanjutan. Hubungan kita dengan teknologi menentukan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya, mengelola limbah, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Alih-alih memandang teknologi sebagai alat netral, Lee mengajak kita melihatnya sebagai bagian dari proses evolusi budaya dan ecotechnology—area di mana keputusan desain dan penggunaan teknologi punya dampak ekologis besar. Ini penting karena solusi sustainability tidak bisa disederhanakan menjadi “kurangi emisi” saja tanpa memikirkan bagaimana sistem digital berkontribusi pada produksi, konsumsi, dan pola perilaku yang luas.
Dalam wacana global seperti pencapaian UN Sustainable Development Goals (SDGs), integrasi teknologi digital sering dipandang sebagai kunci efisiensi dan pemantauan. Namun perspektif koevolusi memperingatkan bahwa efek samping—seperti ketergantungan energi, limbah elektronik, dan penguatan ketimpangan—bukan sekadar insiden, tetapi bagian dari jalur evolusi teknologi yang perlu ditinjau secara sadar. Pendekatan ini membuka ruang bagi kebijakan eco-technology governance yang mempertimbangkan evolusi panjang antara manusia dan mesin.
Di Indonesia, coevolution ini hadir melalui dampak nyata teknologi digital pada berbagai sektor: pendidikan daring di daerah terpencil, e-commerce yang mengubah pola perdagangan tra-disional, aplikasi pertanian presisi yang mengoptimalkan hasil panen, hingga sistem pem-bayaran digital yang mendesain ulang relasi ekonomi lokal. Tetapi ketergantungan ini juga menimbulkan risiko ekologi dan sosial—ketimpangan akses, limbah elektronik yang sulit terkelola, serta budaya konsumsi yang makin cepat dan boros sumber daya.
Relevansi buku Lee terhadap konteks Indonesia terletak pada pertanyaan: bagaimana kita mengarahkan koevolusi ini agar mendukung pembangunan berkelanjutan, bukan eksploitasi berkelanjutan? Misalnya, meskipun teknologi digital dapat mempercepat pertanian cerdas (smart farming), kita harus mempertimbangkan ekologi lokal, keanekaragaman hayati, dan pola pengetahuan lokal agar teknologi tidak mengikis modal sosial dan ekologis yang sudah ada.
Gagasan koevolusi Lee bergema dengan pemikiran beberapa tokoh:
- Marshall McLuhan menyatakan bahwa medium is the message—teknologi tidak hanya menyampaikan konten, tetapi mengubah struktur pengalaman manusia. Konsep ini selaras dengan koevolusi Lee.
- Bruno Latour dalam We Have Never Been Modern menolak sekat keras antara manusia dan teknologi, sebuah ide yang mendasari koeksistensi dan keterkaitan evolusioner.
- Filsafat Islam klasik, seperti pemikiran Al-Ghazali tentang keterkaitan manusia dengan alam semesta, menegaskan bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas—suatu sikap yang penting ketika teknologi menjadi bagian integral dari hidup.
Sebuah kutipan relevan dari Marshall McLuhan menyatakan: “We shape our tools and thereafter our tools shape us.” yang secara naratif selaras dengan tesis Lee bahwa teknologi bukan hanya akibat ciptaan manusia, tetapi juga pembentuk manusia itu sendiri.
Kisah tentang Manusia, Mesin, dan Makna
Buku The Coevolution dibuka dengan sebuah ketegangan mendasar: bagaimana mungkin makhluk yang sering merasa rapuh, terbatas, dan penuh kesalahan justru mampu menciptakan mesin yang tampak presisi, rasional, dan semakin otonom? Lee tidak memulai dari kecanggihan superkomputer, melainkan dari ketidaksempurnaan manusia itu sendiri—bahkan dari sesuatu yang ekstrem: setengah otak.
Ia mengisahkan kasus-kasus neurologis yang sudah lama menjadi bahan refleksi sains kognitif: manusia yang kehilangan sebagian besar jaringan otaknya, tetapi tetap mampu hidup relatif normal—berbicara, berelasi, bekerja. Dalam beberapa kasus hidrocephalus, pemindaian otak menunjukkan rongga kosong yang luas, namun individu tersebut tetap berfungsi sebagai manusia utuh. Kisah-kisah ini mengguncang asumsi populer bahwa kecerdasan adalah hasil perhitungan komputasional yang terlokalisasi dan mekanis. Jika manusia dapat hidup, berpikir, dan bermakna dengan “perangkat keras” yang sangat terbatas, maka kecerdasan jelas bukan sekadar soal jumlah neuron atau kapasitas komputasi.
Dari sini, Lee yang memimpin sejumlah pusat riset dan proyek besar, termasuk Industrial Cyber-Physical Systems Research Center (iCyPhy) dan proyek perangkat lunak sumber terbuka Ptolemy II, sebuah alat model-based design yang banyak dipakai untuk merancang sistem heterogen, membawa kita ke pertanyaan yang lebih radikal: apa sebenarnya yang kita maksud dengan “hidup”? Apakah hidup berarti mampu memproses informasi? Bereproduksi? Beradaptasi? Atau memiliki tujuan dan makna? Dalam dunia teknologi modern, istilah “hidup” semakin sering disematkan pada sistem digital: autonomous agents, self-healing systems, algoritma yang “belajar”, jaringan yang “berevolusi”. Namun Lee dengan hati-hati membongkar penyamaan ini. Ia menunjukkan bahwa kehidupan biologis bukan hanya proses, melainkan relasi—ketergantungan pada lingkungan, sejarah evolusioner, dan keterikatan dengan makhluk lain.
Di sinilah muncul salah satu ketegangan penting buku ini: komputer tampak semakin “hidup”, tetapi justru karena manusia memproyeksikan metafora kehidupan ke dalamnya. Lee menegas-kan bahwa teknologi tidak hidup dalam pengertian biologis, tetapi ia hidup bersama kita—dalam arti koevolusioner. Mesin digital tidak memiliki tujuan intrinsik; tujuan itu selalu disuntik-kan oleh manusia, oleh konteks sosial, oleh sistem ekonomi dan budaya yang melingkupinya.
Pertanyaan provokatif pun muncul: jika demikian, apakah komputer sebenarnya berguna? Atau—mengikuti pertanyaan klasik yang dikutip Lee—“Are computers useless?” Lee membawa pembaca ke sejarah awal komputasi, ketika komputer diciptakan untuk tujuan yang sangat spesifik: menghitung lintasan balistik, memecahkan persamaan diferensial, mengelola sistem tertutup. Komputer unggul dalam dunia yang stabil, terdefinisi dengan jelas, dan minim ambiguitas. Namun dunia manusia bukan dunia seperti itu.
Lee mengisahkan bagaimana banyak sistem komputasi gagal secara spektakuler ketika dipaksakan masuk ke wilayah yang sarat konteks manusia: sistem prediksi sosial yang bias, algoritma manajemen yang merusak organisasi, atau otomasi yang justru menciptakan kerentanan baru. Dari sini ia sampai pada kesimpulan yang tajam: komputer bukan tidak berguna, tetapi ia menjadi berbahaya ketika kita salah memahami apa yang bisa dan tidak bisa ia lakukan. Masalahnya bukan pada mesin, melainkan pada ekspektasi manusia yang keliru—pada kecenderungan kita memperlakukan model sebagai realitas.
Kesalahpahaman ini semakin jelas ketika Lee membahas bahasa dan makna. Dalam bagian yang mengalir dari refleksi sebelumnya, ia menunjukkan bahwa komputer bekerja pada simbol, sementara manusia hidup dalam makna. Kita bisa memerintahkan mesin dengan bahasa formal, tetapi bahasa manusia selalu berlapis—ambigu, emosional, historis. Kasus-kasus kegagalan sistem otomatis sering kali berakar pada perbedaan ini: mesin “melakukan apa yang diperintahkan”, tetapi bukan apa yang dimaksudkan. Lee menegaskan bahwa masalah ini bukan bug teknis, melainkan jurang ontologis antara simbol dan makna.
Dari sinilah narasi buku bergerak ke konsep yang menjadi fondasi koevolusi: umpan balik negatif (negative feedback). Lee menceritakan bagaimana sistem biologis—dari pengaturan suhu tubuh hingga keseimbangan ekosistem—bertahan bukan karena kontrol mutlak, melainkan karena mekanisme koreksi diri. Sistem yang sehat bukan sistem yang sempurna, melainkan sistem yang mampu mengoreksi kesalahan sebelum menjadi bencana. Dalam teknologi, prinsip ini sering diabaikan. Banyak sistem digital dirancang untuk optimasi maksimal, efisiensi tertinggi, kecepatan tercepat—tanpa mekanisme umpan balik yang cukup untuk menahan ekses. Lee mengaitkan ini dengan krisis yang lebih luas: dari runtuhnya sistem keuangan otomatis hingga algoritma media sosial yang memperkuat polarisasi. Semua ini, menurutnya, adalah contoh sistem tanpa umpan balik ekologis dan etis yang memadai.
Di titik ini, benang merah Bab 1–5 menjadi jelas. Manusia bukan makhluk rasional sempurna; kita adalah makhluk adaptif yang hidup dari ketidaksempurnaan, konteks, dan koreksi terus-menerus. Mesin, sebaliknya, unggul dalam dunia formal yang stabil, tetapi rapuh ketika dihadapkan pada kompleksitas kehidupan. Koevolusi terjadi ketika kita berhenti memaksakan mesin menjadi manusia, dan berhenti mereduksi manusia menjadi mesin.
Lee tidak menawarkan solusi teknis instan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih mendasar: kerendahan epistemik—kesadaran bahwa kecerdasan, kehidupan, dan makna tidak dapat direduksi menjadi algoritma. Dari setengah otak manusia hingga sistem umpan balik ekosistem, buku ini mengajak kita melihat masa depan bukan sebagai dominasi mesin atau romantisasi manusia, melainkan sebagai proses belajar bersama dalam keterbatasan bersama.
Menjelaskan yang Tak Terjelaskan
Setelah membawa pembaca pada keterbatasan manusia dan mesin, Edward Ashford Lee melangkah ke wilayah yang lebih gelap dan lebih gelisah: apa yang terjadi ketika kita menuntut penjelasan penuh dari sistem yang, pada dasarnya, tak lagi sepenuhnya kita pahami? Di sinilah bab tentang explaining the inexplicable menjadi semacam peringatan etis sekaligus epistemologis.
Lee membawa pembaca masuk ke kegelisahan terdalam zaman teknologi: kita hidup berdam-pingan dengan sistem yang bekerja dengan sangat efektif, namun tidak lagi sepenuhnya dapat dijelaskan—bahkan oleh penciptanya sendiri. Ia mencontohkan model pembelajaran mesin dan sistem kontrol kompleks yang menghasilkan keputusan penting tanpa narasi sebab-akibat yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Dalam bab ini, Lee menegaskan bahwa tuntut-an kita akan penjelasan total sering kali berangkat dari asumsi keliru: bahwa semua sistem harus transparan seperti mesin mekanik klasik.
Lee mengaitkan kondisi ini dengan biologi. Seperti tubuh manusia yang mampu menyembuhkan luka tanpa “menjelaskan” prosesnya, sistem kompleks—baik biologis maupun komputasional—berfungsi melalui interaksi banyak komponen yang tidak tunduk pada satu penjelasan linear. Dalam Explaining the Inexplicable, ia tidak merayakan ketertutupan ini, tetapi mengajak pembaca menerima kenyataan bahwa ketiadaan penjelasan bukan berarti ketiadaan makna atau nilai, sekaligus memperingatkan bahwa penggunaan sistem tak-terjelaskan menuntut kewaspadaan etis yang lebih besar, bukan lebih kecil. Edward Ashford Lee adalah sosok yang menggabungkan kedalaman intelektual dengan keahlian teknis, serta konsisten mengajak kita berpikir ulang tentang hubungan antara manusia dan teknologi, terutama bagaimana kita membentuk teknologi dan bagaimana teknologi itu kemudian membentuk kita sendiri. TU Wien Informatics
Selain karya teknisnya, Lee juga menulis beberapa buku untuk khalayak luas. Dua di antaranya ditujukan bukan hanya untuk pembaca teknis tetapi untuk pembaca umum: Plato and the Nerd: The Creative Partnership of Humans and Technology. Wikipedia Dan dalam buku Coevolution ini Lee juga mencermati fenomena yang kini akrab: sistem pembelajaran mesin yang menghasil-kan keputusan akurat tetapi tidak transparan. Model-model ini—khususnya jaringan saraf dalam—bekerja sebagai black box. Kita tahu input dan output, tetapi jalur di antaranya kabur bahkan bagi para perancangnya. Lee mengisahkan contoh-contoh di mana sistem semacam ini digunakan untuk keputusan medis, finansial, dan hukum—bidang-bidang yang menyentuh hidup manusia secara langsung. Ketika hasilnya salah, pertanyaan pun muncul: mengapa? Namun mesin tidak bisa menjawab dalam bahasa manusia; ia hanya bekerja sesuai statistik internalnya.
Lalu Lee mengajukan pertanyaan yang terasa sederhana tetapi radikal: apakah semua hal perlu—atau bahkan bisa—dijelaskan sepenuhnya? Ia mengingatkan bahwa dalam biologi, banyak proses vital berlangsung tanpa “penjelasan” tunggal. Evolusi tidak memiliki tujuan eksplisit, tubuh tidak “tahu” mengapa ia sembuh, dan ekosistem tidak membutuhkan narasi untuk berfungsi. Masalah muncul ketika manusia modern, dengan warisan rasionalisme dan kontrol, menuntut transparansi mutlak dari sistem yang justru dirancang menyerupai kompleksitas alam.
Dari sini, narasi bergerak ke refleksi tajam tentang the wrong stuff. Lee menunjukkan bahwa kesalahan besar dalam teknologi bukan semata-mata bug atau kegagalan teknis, melainkan pemilihan bahan konseptual yang keliru. Kita membangun sistem sosial dari metrik, efisiensi, dan optimasi—padahal kehidupan manusia tumbuh dari empati, improvisasi, dan ketidak-pastian. Ia mengisahkan bagaimana indikator kuantitatif sering menggantikan realitas: nilai ujian menggantikan pembelajaran, klik menggantikan makna, produktivitas menggantikan kesejahteraan.
Gagasan ini mengalir langsung ke Bab 7, “The Wrong Stuff,” di mana Lee menggeser fokus dari bagaimana sistem bekerja ke apa yang kita masukkan ke dalam sistem itu. Di sini ia berargumen bahwa kegagalan teknologi modern jarang disebabkan oleh algoritma yang salah semata, melainkan oleh nilai, asumsi, dan tujuan yang keliru sejak awal perancangan. Dalam bab ini, Lee mengulas bagaimana masyarakat modern cenderung menggantikan realitas yang kompleks dengan indikator yang mudah diukur: skor, peringkat, efisiensi, dan optimasi. Ia menunjukkan bahwa ketika sistem dibangun dari “bahan yang salah”—misalnya mengukur kesejahteraan dengan produktivitas semata—maka hasilnya adalah teknologi yang tampak berhasil namun secara perlahan merusak ekosistem sosial dan manusiawi. The Wrong Stuff menjadi kritik tajam terhadap keyakinan bahwa lebih banyak data selalu berarti keputusan yang lebih baik, padahal data hanya mencerminkan apa yang kita anggap penting.
Dalam dunia koevolusi manusia–mesin, “bahan yang salah” ini menciptakan sistem yang tampak berhasil tetapi secara perlahan menggerogoti fondasi sosial dan ekologis. Lee mengait-kan ini dengan analogi biologis: organisme yang terlalu terspesialisasi sering kali rapuh ketika lingkungannya berubah. Demikian pula sistem teknologi yang dioptimalkan secara sempit—ia unggul dalam kondisi tertentu, tetapi gagal menghadapi kompleksitas nyata.
Pertanyaan berikutnya muncul secara eksistensial dan personal: “Am I digital?” Lee tidak menanyakannya sebagai spekulasi futuristik tentang unggah kesadaran, melainkan sebagai refleksi tentang bagaimana kehidupan manusia telah dibentuk oleh logika digital. Kalender, ingatan, navigasi, bahkan relasi sosial kita kini dimediasi oleh sistem komputasi. Lee mengisah-kan momen-momen sehari-hari—ketergantungan pada GPS, notifikasi yang membentuk perhatian, algoritma yang menyaring dunia—untuk menunjukkan bahwa kita tidak menjadi digital dalam arti ontologis, tetapi kita hidup dalam ekologi digital.
Pertanyaan eksistensial ini menjadi inti “Am I Digital?” Lee tidak mengajukan spekulasi fiksi ilmiah tentang kesadaran yang diunggah ke komputer. Sebaliknya, ia menelusuri bagaimana kehidupan manusia sehari-hari—ingatan, perhatian, navigasi, dan relasi—semakin dibentuk oleh sistem digital. Dalam bab ini, Lee menegaskan bahwa manusia tidak berubah menjadi makhluk digital secara biologis, tetapi cara kita hidup, memilih, dan memahami dunia telah terkoevolusi dengan teknologi digital.
Ia menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem komputasi mengubah cara kita mempercayai pengetahuan dan otoritas. GPS menggantikan intuisi spasial, algoritma menggantikan penilaian sosial, dan notifikasi menggantikan ritme alami perhatian. Am I Digital? bukan ratapan nostalgia, melainkan refleksi kritis: bagaimana menjaga kemanusiaan ketika lingkungan tempat kita berevolusi kini adalah jaringan perangkat lunak dan sistem otomatis.
Di sini, Lee berhati-hati agar tidak jatuh pada determinisme teknologi. Ia menolak gagasan bahwa manusia “akan” menjadi mesin. Sebaliknya, ia menekankan bahwa identitas manusia tetap biologis, historis, dan relasional. Namun koevolusi berarti bahwa kebiasaan, persepsi, dan bahkan nilai kita dibentuk bersama oleh teknologi yang kita ciptakan. Kita bukan makhluk digital, tetapi kita belajar hidup seperti makhluk yang selalu terhubung, terukur, dan dipercepat.
Refleksi ini membawa Lee ke pembahasan tentang intelligences—dalam bentuk jamak. Ia dengan sengaja menghindari definisi tunggal kecerdasan. Kecerdasan manusia berbeda dari kecerdasan hewan, berbeda pula dari kecerdasan mesin. Ada kecerdasan kolektif dalam koloni semut, kecerdasan ekologis dalam hutan, dan kecerdasan sosial dalam komunitas manusia. Mesin menambahkan bentuk baru: kecerdasan statistik yang cepat, luas, tetapi dangkal dalam makna.
Lee mengisahkan bagaimana kekeliruan terbesar zaman ini adalah membandingkan kecerdasan mesin dan manusia seolah-olah mereka bersaing di medan yang sama. Padahal, masing-masing berkembang dalam ceruk evolusioner yang berbeda. Ketika manusia mencoba meniru dirinya sendiri melalui mesin, ia sering kali meniru aspek yang paling mudah diukur—kecepatan, memori, akurasi—dan mengabaikan aspek yang paling menentukan: kebijaksanaan, tanggung jawab, dan kemampuan hidup bersama ketidakpastian.
Refleksi ini diperdalam pada Bagian “Intelligences,” di mana Lee dengan sengaja menggunakan bentuk jamak. Ia menolak gagasan bahwa kecerdasan adalah satu kualitas tunggal yang dapat diukur dan dibandingkan secara universal. Dalam bab ini, Lee memperluas makna kecerdasan: dari kecerdasan ekologis dalam sistem alam, kecerdasan sosial dalam komunitas manusia, hingga kecerdasan statistik dalam mesin.
Lee mengingatkan bahwa kesalahan besar diskursus publik adalah memperlakukan kecerdasan mesin sebagai pesaing langsung kecerdasan manusia. Dalam Intelligences, ia menegaskan bahwa setiap bentuk kecerdasan berkembang dalam ceruk evolusionernya sendiri. Mesin unggul dalam kecepatan dan pengolahan pola, tetapi tidak memiliki tujuan intrinsik, nilai, atau tanggung jawab. Manusia, sebaliknya, hidup dalam dunia makna, sejarah, dan konsekuensi moral—wilayah yang tidak dapat direduksi menjadi komputasi.
Semua refleksi ini akhirnya bermuara pada satu kata yang menjadi poros etis buku ini: accountability. Jika mesin bukan makhluk bermakna, jika kecerdasan bersifat jamak, dan jika sistem kompleks tak sepenuhnya dapat dijelaskan, maka siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya? Lee dengan tegas menolak gagasan bahwa tanggung jawab dapat “dialihkan” ke algoritma. Mesin tidak pernah bertanggung jawab; tanggung jawab selalu berada pada manusia—perancang, pengguna, institusi, dan masyarakat yang mengizinkan sistem itu beroperasi.
Lee dengan tegas menyatakan bahwa dalam sistem manusia–mesin, tanggung jawab tidak pernah dapat dialihkan ke teknologi. Algoritma tidak bisa disalahkan, karena ia tidak memiliki kehendak atau kesadaran moral. Tanggung jawab selalu kembali pada manusia: perancang, pembuat kebijakan, institusi, dan masyarakat yang mengizinkan sistem tersebut beroperasi.
Ia mengkritik kecenderungan untuk menyembunyikan keputusan di balik kompleksitas teknis. Ia menegaskan bahwa semakin tidak terjelaskan sebuah sistem, semakin besar tuntutan akunta-bilitas manusia di sekitarnya. Accountability bukan sekadar prinsip hukum, melainkan sikap etis dalam menghadapi koevolusi—pengakuan bahwa kita tidak hanya hidup bersama mesin, tetapi bertanggung jawab atas dunia yang dibentuk oleh interaksi dengannya.
Bagi Lee Koevolusi bukan alasan untuk menyerah pada kompleksitas, melainkan panggilan untuk kedewasaan kolektif. Hidup bersama mesin berarti menerima keterbatasan pengetahu-an, memilih bahan nilai yang tepat, mengakui pluralitas kecerdasan, dan—yang terpenting—memegang tanggung jawab etis atas sistem yang kita lepaskan ke dunia. Di titik ini, The Coevolution semakin jelas bukan sekadar buku tentang teknologi, melainkan sebuah etika hidup di zaman sistem kompleks—zaman ketika menjelaskan segalanya tidak selalu mungkin, tetapi bertanggung jawab selalu wajib.
Membaca buku ini kita tahu bahwa pada akhirnya kita perlu berdamai dengan penerimaan atas ketakterjelasan (Explaining the Inexplicable), kritik atas nilai yang salah (The Wrong Stuff), kesadaran eksistensial manusia di dunia digital (Am I Digital?), pengakuan pluralitas kecerdasan (Intelligences), hingga penegasan etika tanggung jawab (Accountability). Keseluruhannya menegaskan bahwa The Coevolution bukan sekadar buku tentang masa depan teknologi, melainkan panduan moral untuk hidup di tengah sistem kompleks yang kita ciptakan sendiri.
Edward Ashford Lee mengajak pembaca mundur selangkah dari gejala yang tampak—kecelakaan sistem, bias algoritmik, kegagalan otomatisasi—untuk menanyakan pertanyaan yang lebih mendasar: apa sebenarnya sebabnya? Dalam bab ini, Lee mengkritik kecenderungan manusia modern untuk mengira bahwa sebab selalu bersifat lokal, linear, dan dapat ditunjuk dengan jari. Ia menunjukkan bahwa dalam sistem kompleks, sebab sering kali tersebar, berlapis, dan muncul dari interaksi banyak elemen yang tidak pernah dirancang untuk bekerja bersama.
Digunakan analogi dari biologi dan rekayasa: penyakit jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal, begitu pula kegagalan teknologi. Causes menekankan bahwa mencari kambing hitam—satu baris kode, satu kesalahan manusia—adalah cara berpikir lama yang tidak memadai untuk dunia koevolusioner. Sebab-sebab sejati sering tertanam dalam struktur, insentif, dan asumsi desain yang telah lama diterima tanpa dipertanyakan. Dengan kata lain, penyebab terbesar sering kali adalah cara kita membingkai masalah sejak awal.
Keahliannya menjembatani antara sains komputer, teknik, dan filsafat teknologi, menjadikan ia tidak hanya seorang insinyur, tetapi juga pemikir kritis tentang dampak teknologi terhadap masyarakat. Dalam buku ini Ia menjelaskan ketika hubungan lebih menentukan daripada komponen. Gagasan ini berkembang dalam “Interaction,” yang menjadi jantung konseptual bagi pemahaman sistem hidup dan sistem buatan. Lee menegaskan bahwa dalam dunia koevolusi, bukan komponen individual yang paling menentukan, melainkan cara mereka berinteraksi. Sebuah algoritma, sebuah institusi, atau seorang manusia mungkin tampak tidak berbahaya secara terpisah, tetapi ketika dipertemukan dalam jaringan interaksi tertentu, hasilnya bisa tak terduga.
Dalam Interaction, Lee kembali ke contoh-contoh biologis: ekosistem tidak runtuh karena satu spesies saja, melainkan karena perubahan relasi antarspesies. Ia lalu mengaitkannya dengan dunia teknologi—bagaimana sistem otomasi, pasar, dan kebijakan saling menguatkan atau saling melemahkan. Interaksi menciptakan umpan balik (feedback) yang dapat memperbaiki sistem atau justru mempercepat kerusakan. Bab ini memperjelas satu prinsip penting: dalam sistem kompleks, niat baik pada tingkat lokal tidak menjamin hasil baik pada tingkat global.
Dari interaksi yang keliru, Lee membawa pembaca ke Bab 13, “Pathologies,” sebuah bab yang paling gelap sekaligus paling jujur. Di sini ia memperlakukan sistem teknologi dan sosial seperti organisme hidup yang dapat jatuh sakit. Pathologies bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan pola disfungsional yang menetap—bias yang membeku, ketimpangan yang dipercepat, ketergantungan yang melumpuhkan kemampuan manusia untuk bertindak mandiri.
Lee menunjukkan bahwa patologi sistem sering kali tampak sebagai “normalitas baru.” Sistem yang merugikan sebagian besar orang bisa tetap stabil, bahkan dianggap sukses, selama ia memenuhi metrik tertentu. Dalam bab ini, Lee mengingatkan bahwa seperti penyakit kronis dalam tubuh, patologi sistemik tidak selalu spektakuler; ia bekerja perlahan, melalui kebiasaan, prosedur, dan rutinitas yang jarang dipertanyakan. Pathologies memperingatkan bahwa ketika manusia menyerahkan terlalu banyak keputusan kepada sistem yang tidak memahami nilai, maka yang sakit bukan hanya sistem itu sendiri, tetapi juga masyarakat yang bergantung padanya.
Koevolusi: Inti dari Segalanya
Semua jalur refleksi ini akhirnya bertemu dalam Bab 14, “Coevolution,” yang merupakan inti filosofis dan ilmiah buku ini. Di sinilah Lee merumuskan tesis besarnya secara paling utuh: manusia dan mesin tidak bergerak dalam hubungan penguasa–alat, melainkan dalam proses koevolusi yang saling membentuk. Kita membangun mesin, tetapi mesin itu kemudian mem-bentuk cara kita berpikir, bekerja, dan hidup; perubahan pada manusia memicu perubahan desain, dan perubahan desain kembali memengaruhi manusia.
Dalam Coevolution, Lee menolak dua ekstrem: optimisme naif bahwa teknologi akan me-nyelamatkan segalanya, dan pesimisme deterministik bahwa manusia akan digantikan oleh mesin. Sebaliknya, ia mengajukan pandangan biologis: koevolusi selalu menghasilkan peme-nang dan kerentanan baru secara bersamaan. Seperti spesies yang berevolusi bersama predator atau simbionnya, manusia yang berevolusi bersama mesin memperoleh kemampuan baru—kecepatan, jangkauan, koordinasi—namun juga kehilangan sebagian ketangguhan lama, seperti intuisi, keterampilan manual, dan ketahanan terhadap gangguan.
Lee menekankan bahwa koevolusi bukan proses netral. Ia dibentuk oleh pilihan: nilai apa yang kita masukkan, batas apa yang kita tetapkan, dan tanggung jawab apa yang kita ambil. Dalam bab ini, ia kembali menegaskan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh kecerdasan mesin semata, melainkan oleh kebijaksanaan manusia dalam mengelola hubungan koevolusioner tersebut. Tanpa etika, koevolusi dapat menjadi spiral patologi; dengan kesadaran, ia bisa menjadi simbiosis yang memperkaya.
Pada paruh bagian dari buku ini Lee menyempurnakan bangunan The Coevolution: dari pencari-an sebab yang melampaui gejala (Causes), pemahaman bahwa hubungan lebih penting dari-pada bagian (Interaction), kesadaran akan penyakit sistemik (Pathologies), hingga perumus-an koevolusi sebagai kenyataan dasar hidup manusia modern (Coevolution). Di titik ini, buku Lee tidak lagi berbicara tentang teknologi semata, melainkan tentang cara manusia belajar hidup secara dewasa dalam dunia yang ia bentuk bersama makhluk non-manusia ciptaannya sendiri.
Catatan Akhir: Menulis Masa Depan Bersama Teknologi
The Coevolution mengajarkan bahwa nasib manusia di masa depan tidak ditentukan oleh kemenangan mesin atas manusia, melainkan oleh cara manusia hidup bersama ciptaannya sendiri. Kita memasuki zaman ketika kecerdasan, keputusan, dan bahkan makna hidup tidak lagi sepenuhnya berada di tangan individu, tetapi tersebar di jaringan sistem teknis yang kompleks, cepat, dan sering kali tak terjelaskan. Di sinilah tantangan terbesar muncul: bukan soal apakah mesin akan menjadi “lebih pintar” dari manusia, tetapi apakah manusia akan tetap cukup bijak, bertanggung jawab, dan utuh untuk hidup di tengah koevolusi tersebut.
Buku ini menyingkap bahwa masa depan manusia bukanlah kelanjutan lurus dari kemajuan teknologi, melainkan medan rapuh di mana sebab-sebab tersembunyi, interaksi tak terduga, dan patologi sistemik dapat menentukan arah sejarah. Seperti organisme dalam ekosistem, manusia kini berevolusi bersama mesin—memperoleh kemampuan baru sekaligus kehilangan ketahanan lama. Ketika sistem menjadi semakin otonom, tuntutan etika justru semakin berat: manusia tidak dapat menyerahkan tanggung jawab pada algoritma, karena tanggung jawab adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diotomatisasi.
Nasib manusia, sebagaimana dirumuskan Lee, bukanlah punah atau digantikan, melainkan diuji. Diuji dalam kemampuannya memahami keterbatasan pengetahuan, memilih nilai yang tepat, dan merawat relasi—baik dengan sesama manusia, dengan mesin, maupun dengan dunia hidup yang lebih luas. Tantangan manusia masa depan adalah belajar hidup dalam kompleksitas tanpa kehilangan kemanusiaan; menerima ketakterjelasan tanpa menyerah pada ketidakpedulian; dan membentuk koevolusi bukan sebagai spiral kerusakan, melainkan sebagai simbiosis yang sadar dan bermakna.
Dalam pengertian ini, The Coevolution bukanlah buku tentang akhir manusia, melainkan tentang kedewasaan manusia—sebuah undangan untuk menjadi spesies yang mampu hidup dengan ciptaannya sendiri tanpa melupakan tanggung jawab moral, ekologis, dan eksistensial-nya.
The Coevolution bukan sekadar buku teknologi; ia adalah undangan untuk berpikir ulang tentang diri kita sendiri sebagai makhluk evolusioner—bukan hanya dalam konteks biologis, tetapi juga budaya dan teknologi. Lee menolak ilusi kontrol penuh atas teknologi, tetapi ia tidak mengajak pada fatalisme. Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa pemahaman koheren tentang hubungan manusia–mesin dapat membantu kita menyusun masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sadar konteks.
Dalam kata penutup, kita diajak melihat koeksistensi dengan teknologi bukan sebagai “pertarungan” antara manusia versus mesin, tetapi sebagai dialog evolusioner, di mana pilihan kita hari ini akan menentukan nasib generasi yang akan datang—anak, masyarakat, dan planet itu sendiri.
Bogor, 31 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi (APA)
Lee, E. A. (2020). The Coevolution: The Entwined Futures of Humans and Machines. MIT Press. MIT Press
Edward A. Lee. (n.d.). In Wikipedia. Wikipedia
Edward A. Lee | EECS at UC Berkeley. (n.d.). www2.eecs.berkeley.edu
About — Edward Ashford Lee. (n.d.). edwardalee.github.io
Edward A. Lee bio — Informatik Austria. (n.d.). informatikaustria.at
Press. mitpressbookstore
SIGBED Blog (2020, April 2). The Coevolution of Humans and Machines — Edward Lee. SIGBED
Wikipedia (2025). Edward A. Lee. Wikipedia