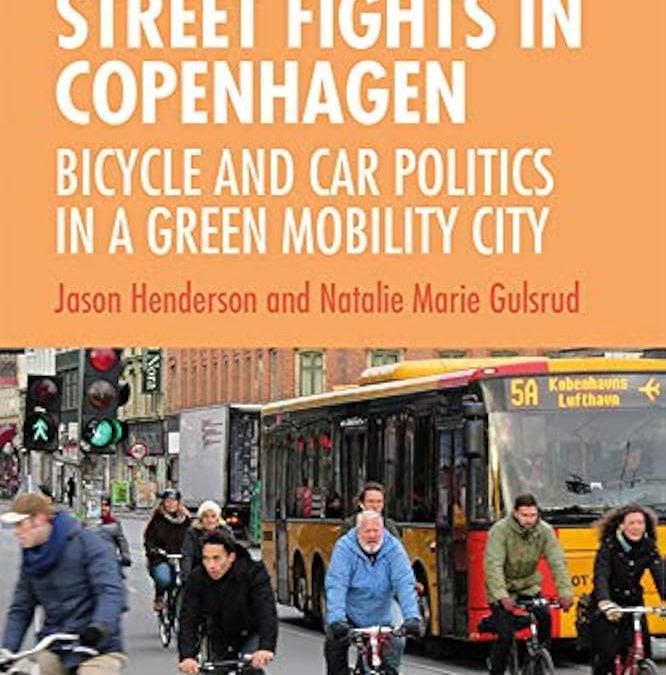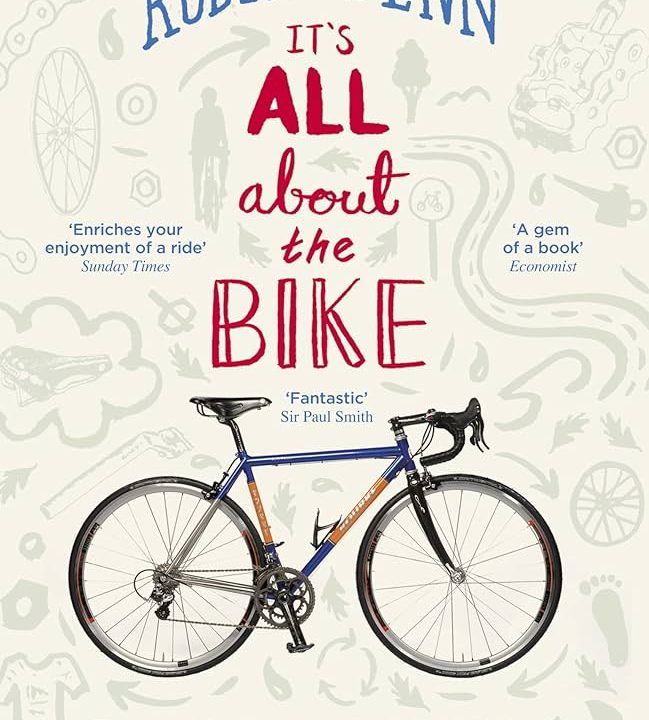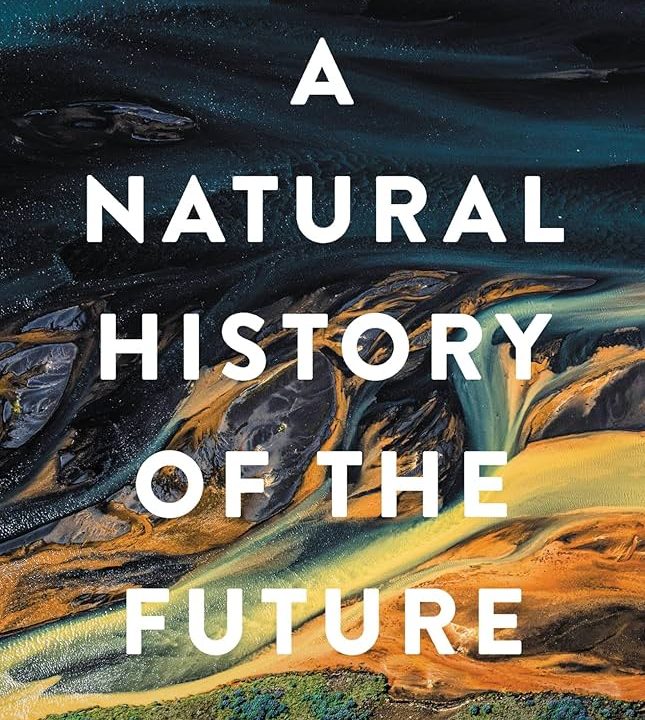Rubarubu #91
Street Fights in Copenhagen:
Merebut Kembali Ruang Jalanan
Kota Hijau yang Tidak Pernah Netral
Buku ini dibuka dengan sebuah paradoks yang tampak sederhana tetapi politis: mengapa di kota yang dikenal sebagai “surga sepeda dunia” seperti Kopenhagen, konflik antara mobil dan sepeda justru begitu tajam dan terus berulang? Henderson dan Gulsrud mengajak pembaca masuk ke jantung kota yang sering dipuja sebagai model global mobilitas berkelanjutan—bukan untuk merayakannya secara romantik, melainkan untuk membongkar lapisan konflik, kekuasa-an, dan negosiasi politik yang tersembunyi di balik citra “green city”.
Salah satu kisah nyata yang kerap muncul dalam buku ini adalah bagaimana pembangunan jalur sepeda di Kopenhagen hampir selalu diiringi perlawanan: dari pengusaha yang takut kehilangan parkir, dari pengemudi mobil yang merasa “dipinggirkan”, hingga dari politisi yang khawatir kehilangan dukungan kelas menengah suburban. Jalan, dalam pengertian ini, bukan sekadar ruang fisik, tetapi arena politik tempat visi tentang kota diperebutkan setiap hari.
Argumen sentral buku ini adalah bahwa mobilitas tidak pernah netral. Mobilitas merupakan politik kekuasaan. Pilihan kebijakan tentang siapa yang diberi ruang, kecepatan, keamanan, dan prioritas di jalan raya adalah pilihan politik yang mencerminkan relasi kekuasaan sosial, ekonomi, dan kultural.
Kota yang tidak pernah netral ini dibahas pada Bab 1: Copenhagen: Bicycle City yang membawa pembaca masuk ke jantung identitas Kopenhagen sebagai “bicycle city”, tetapi dengan cara yang sengaja tidak romantik. Alih-alih memulai dari jalur sepeda yang rapi dan statistik mengesankan, Henderson dan Gulsrud memulai dari jalan sebagai ruang sosial yang diperebutkan.
Di Kopenhagen, sepeda telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari: pekerja kantoran, pelajar, orang tua dengan anak di bakfiets, hingga politisi semuanya bersepeda. Namun normalisasi sepeda ini bukan hasil dari konsensus moral kolektif, melainkan dari serangkaian keputusan politik yang sering kontroversial. Setiap meter jalur sepeda berarti pengurangan ruang mobil, parkir, atau kecepatan lalu lintas—dan di situlah konflik dimulai. Bab ini me-nunjukkan bahwa “kota sepeda” bukanlah identitas statis, melainkan hasil sejarah panjang pasang-surut. Pada awal abad ke-20, sepeda adalah alat mobilitas utama kelas pekerja. Namun pasca-Perang Dunia II, Kopenhagen—seperti banyak kota Eropa—jatuh dalam euforia auto-mobilitas. Mobil dipandang sebagai simbol kemajuan, kebebasan, dan modernitas. Sepeda terpinggirkan, dianggap kuno dan inferior.
Kebangkitan sepeda pada 1970-an bukanlah nostalgia romantis, melainkan respons terhadap krisis energi, kecelakaan lalu lintas, dan tekanan aktivisme warga. Henderson dan Gulsrud menggambarkan bagaimana demonstrasi, kematian anak-anak di jalan raya, dan krisis minyak menciptakan momen politis yang memaksa pemerintah kota mempertimbangkan ulang prioritas mobil. Sepeda kembali ke jalan bukan sebagai simbol kemiskinan, tetapi sebagai praktik perlawanan sehari-hari terhadap dominasi mobil.
Namun, bab ini juga menekankan bahwa keberhasilan sepeda di Kopenhagen tidak menghapus hierarki. Pengguna sepeda di pusat kota sering lebih diuntungkan dibanding mereka yang tinggal di pinggiran. Infrastruktur sepeda yang baik sering kali mengikuti logika produktivitas ekonomi—menghubungkan kawasan kerja dan pusat kota—bukan semata logika keadilan sosial. Dengan demikian, bahkan kota sepeda pun tidak bebas dari bias kelas dan spasial.
Yang paling menarik dari bab ini adalah cara penulis memperlihatkan bahwa sepeda di Kopenhagen telah menjadi alat tata kelola kota (urban governance). Ia dipakai untuk mencapai berbagai tujuan: kesehatan publik, pengurangan emisi, citra global kota, hingga daya tarik investasi. Sepeda, dalam pengertian ini, bukan sekadar alat emansipasi, tetapi juga bisa menjadi instrumen manajemen neoliberal—dipromosikan karena efisien, murah, dan “rasional”.
Bab ini menolak pandangan bahwa sepeda adalah solusi teknis yang netral. Justru sebaliknya, sepeda adalah teknologi politik yang terus dinegosiasikan. Ia bisa menjadi simbol demokrasi jalanan, tetapi juga bisa dikooptasi menjadi bagian dari narasi kota kompetitif global.
Dari pengantar dan bab pertama ini, Henderson dan Gulsrud meletakkan fondasi penting: transisi mobilitas bukanlah perjalanan dari “buruk” ke “baik”, tetapi dari satu konfigurasi kekuasaan ke konfigurasi lain. Kopenhagen menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi paling “ideal”, sepeda tetap harus diperjuangkan, dipertahankan, dan diperdebatkan. Bagi pembaca di luar Eropa—termasuk Indonesia—bab-bab awal ini memberi peringatan keras: jangan pernah menganggap kota sepeda sebagai produk akhir. Ia selalu rapuh, selalu politis, dan selalu terancam oleh kembalinya logika lama mobilitas cepat, individual, dan berbasis konsumsi energi tinggi.
Henderson dan Gulsrud menunjukkan bahwa meskipun Kopenhagen sering dipandang sebagai kota yang “sudah selesai” dengan transisi sepeda, kenyataannya dominasi mobil tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya dinegosiasikan ulang, dibatasi, dan dilunakkan melalui kompromi politik. Setiap jalur sepeda yang dibangun adalah hasil dari “street fights”—pertarungan diskursif dan material antara berbagai aktor: pemerintah kota, asosiasi pengendara, kelompok pesepeda, media, dan warga biasa. Dalam kerangka ini, sepeda bukan sekadar alat transportasi ramah lingkungan, tetapi simbol politik: simbol kota yang lebih egaliter, lebih lambat, dan lebih berorientasi pada kehidupan sehari-hari manusia.
Buku Street Fights in Copenhagen: Bicycle and Car Politics in a Green Mobility City karya Jason Henderson dan Natalie Marie Gulsrud (Routledge, 2019) ini menelusuri sejarah panjang bagaimana Kopenhagen berubah dari kota yang sangat ramah sepeda pada awal abad ke-20, menjadi kota yang dikuasai mobil pasca-Perang Dunia II, lalu kembali “menemukan” sepeda sejak krisis minyak 1970-an. Perubahan ini tidak pernah linear atau damai. Kopenhagen adalah sebagai arena sejarah panjang konflik, termasuk tentang kehadiran sepeda di jalan-jalan kota.
Henderson dan Gulsrud dengan detail memperlihatkan bagaimana:
- Kebijakan pro-mobil pernah dianggap simbol modernitas dan kemajuan.
- Aktivisme warga pada 1970-an memaksa pemerintah kota mempertimbangkan ulang dominasi mobil.
- “Kota hijau” muncul bukan dari konsensus moral, tetapi dari krisis, konflik, dan tekanan politik.
Kopenhagen, dalam narasi ini, menjadi contoh bagaimana transisi ekologis selalu berakar pada sejarah sosial tertentu—bukan sekadar soal teknologi atau desain.
Politik Jalanan: Dari Infrastruktur ke Imajinasi Sosial
Salah satu kontribusi penting buku ini adalah penekanannya pada politik imajinasi. Henderson dan Gulsrud menunjukkan bahwa perdebatan tentang sepeda dan mobil bukan hanya tentang lebar jalan atau jumlah jalur, tetapi tentang visi hidup perkotaan: apakah kota adalah ruang untuk bergerak cepat atau untuk hidup bersama? Media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi ini. Pesepeda sering direpresentasikan sebagai “fanatik hijau” atau “pengganggu lalu lintas”, sementara mobil diperlakukan sebagai kebutuhan alami kehidupan modern. Buku ini membongkar bagaimana bahasa, framing media, dan narasi kebijakan membentuk siapa yang dianggap “rasional” dan siapa yang dianggap “ekstrem”. Di sinilah sepeda menjadi praktik yang secara halus subversif: ia mengganggu asumsi bahwa kecepatan dan kenyamanan individual harus selalu menjadi prioritas tertinggi.
Secara implisit, buku ini mengajukan pertanyaan etis yang mendalam: kota itu milik siapa? Inilah dimensi etis dan filosofis. Apakah jalan raya adalah hak istimewa kendaraan bermotor, atau ruang publik bersama yang harus mengutamakan keselamatan dan keadilan sosial? Henderson dan Gulsrud tidak menawarkan utopia. Mereka justru menegaskan bahwa kota hijau adalah kota yang terus berkonflik secara demokratis. Keadilan mobilitas tidak tercapai sekali untuk selamanya, tetapi harus terus diperjuangkan melalui kebijakan, aktivisme, dan perubahan budaya.
Dalam hal ini, buku ini sejalan dengan pemikiran Henri Lefebvre tentang right to the city, serta dengan kritik ekologis terhadap kapitalisme perkotaan yang menempatkan efisiensi ekonomi di atas kehidupan sosial.
Meskipun berfokus pada Kopenhagen, buku ini sangat relevan bagi kota-kota di luar Eropa—termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Yogyakarta. Henderson dan Gulsrud menunjukkan bahwa bahkan di kota paling “hijau” pun, sepeda harus terus diperjuangkan.
Bagi konteks Indonesia, buku ini memberi pelajaran penting:
- Bahwa membangun jalur sepeda bukan sekadar proyek teknis, tetapi proyek politik.
- Bahwa resistensi terhadap sepeda sering datang dari struktur kekuasaan lama yang mapan.
- Bahwa keberhasilan mobilitas berkelanjutan membutuhkan perubahan imajinasi kolektif, bukan hanya infrastruktur.
Mengapa Kopenhagen Menjadi Medan Pertarungan
Pertanyaan “mengapa Kopenhagen?” bukanlah pertanyaan geografis semata, melainkan pertanyaan politis dan epistemologis. Henderson dan Gulsrud membuka buku ini dengan kesadaran bahwa Kopenhagen telah lama dijadikan ikon global kota sepeda—sebuah model yang diekspor ke seluruh dunia melalui konferensi, laporan kebijakan, dan studi banding. Namun justru karena status simboliknya itulah, Kopenhagen menjadi tempat yang ideal untuk membongkar mitos tentang transisi hijau yang seolah-olah alami, rasional, dan bebas konflik.
Kopenhagen sering dipresentasikan sebagai kota yang “berhasil”: tingkat penggunaan sepeda tinggi, infrastruktur sepeda luas, dan citra globalnya hijau serta progresif. Tetapi para penulis mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: berhasil menurut siapa, dengan proses seperti apa, dan dengan konflik apa yang disembunyikan? Di balik statistik keberhasilan itu, terdapat sejarah panjang pertarungan politik tentang siapa yang berhak atas ruang jalan, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang diuntungkan.
Kopenhagen dipilih bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia terbuka secara politis. Di kota ini, konflik antara mobil dan sepeda tidak pernah benar-benar berakhir; ia terus muncul dalam rapat dewan kota, media lokal, proyek pembangunan, dan percakapan sehari-hari warga. Dengan kata lain, Kopenhagen adalah laboratorium tempat kita bisa melihat dengan jelas bahwa mobilitas adalah arena konflik kelas, budaya, dan ideologi, bukan sekadar soal desain teknis.
Henderson dan Gulsrud juga ingin menantang kecenderungan global untuk meniru Kopenhagen secara dangkal—mengambil infrastruktur tanpa memahami kondisi sosial dan politik yang melahirkannya. Mereka memperingatkan bahwa “menyalin” Kopenhagen tanpa memahami konflik internalnya justru berisiko melanggengkan ketidakadilan baru di kota-kota lain. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai manual teknokratis, melainkan sebagai kritik politik terhadap narasi kota hijau.
Kopenhagen: Sejarah Pendek yang Sarat Pertarungan
Sejarah sepeda dan mobil di Kopenhagen bukanlah kisah evolusi teknologi yang netral, melainkan drama politik tentang siapa yang berhak atas jalan. Henderson dan Gulsrud menulis sejarah ini sebagai rangkaian pergeseran kekuasaan, bukan sebagai garis kemajuan yang mulus.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sepeda tumbuh bersama industrialisasi. Ia menjadi alat mobilitas utama kelas pekerja dan menengah: murah, efisien, dan cocok dengan kota yang padat. Jalan-jalan Kopenhagen kala itu adalah ruang campuran—pejalan kaki, sepeda, trem, dan aktivitas sosial hidup berdampingan. Mobil belum mendominasi imajinasi urban.
Namun setelah Perang Dunia II, narasi modernitas berubah drastis. Mobil masuk sebagai simbol kebebasan individual, kemajuan teknologi, dan kemakmuran ekonomi. Negara kesejahteraan Denmark—yang sering dipandang progresif—tidak kebal terhadap imajinasi ini. Pemerintah kota dan nasional mulai mendesain ulang Kopenhagen agar “ramah mobil”: pelebaran jalan, pengurangan ruang sepeda, dan prioritas kecepatan lalu lintas.
Yang penting, para penulis menekankan bahwa dominasi mobil bukan kehendak rakyat semata, melainkan hasil koalisi antara industri otomotif, perencana kota modernis, dan elite politik yang percaya bahwa masa depan kota adalah kota yang mengalir cepat. Sepeda tidak dilarang secara eksplisit, tetapi secara perlahan “dipinggirkan”—dibuat tidak nyaman, tidak aman, dan tidak prestisius.
Kebangkitan sepeda pada 1970-an sering dipuja sebagai kisah heroik. Henderson dan Gulsrud tidak menolak narasi itu, tetapi memperumitnya. Mereka menunjukkan bahwa kebangkitan ini dipicu oleh krisis minyak, kematian anak-anak akibat kecelakaan lalu lintas, dan tekanan gerakan warga. Demonstrasi “Stop the Killing of Our Children” menjadi simbol bahwa politik jalan adalah politik kehidupan.
Sejak saat itu, Kopenhagen memasuki fase kompromi: sepeda diberi ruang kembali, tetapi mobil tidak pernah benar-benar tersingkir. Sejarah ini, bagi penulis, penting untuk menunjuk-kan bahwa kota sepeda lahir dari konflik dan trauma, bukan dari visi teknokratik yang tenang.
Judul bab ini: “Something Is Rotten in the State of Denmark” — Ketika Sepeda Berhenti Bertumbuh dan Mobil Kembali Naik (Bab 3)—meminjam Shakespeare—menandai momen refleksi kritis. Setelah puluhan tahun dipuji sebagai kota sepeda teladan dunia, Kopenhagen menghadapi kenyataan yang tidak nyaman: pertumbuhan penggunaan sepeda melambat, sementara kepemilikan mobil kembali meningkat.
Henderson dan Gulsrud mengajak pembaca meninggalkan euforia statistik. Mereka menunjuk-kan bahwa keberhasilan masa lalu justru menciptakan ilusi stabilitas. Banyak politisi dan perencana kota mulai menganggap sepeda sebagai “urusan selesai”, sehingga perhatian kebijakan bergeser ke isu lain—pertumbuhan ekonomi, pembangunan properti, dan daya saing global.
Dalam konteks ini, mobil kembali menemukan celah. Urban sprawl di wilayah metropolitan mendorong perjalanan jarak jauh yang sulit ditempuh dengan sepeda. Rumah semakin mahal di pusat kota, memaksa kelas pekerja pindah ke pinggiran yang infrastrukturnya masih berorientasi mobil. Sepeda tetap dominan di pusat kota, tetapi kehilangan daya jangkau sosialnya.
Bab ini juga mengungkap paradoks penting: kota sepeda bisa tetap eksklusif secara kelas. Pengguna sepeda yang paling diuntungkan sering adalah profesional perkotaan dengan akses ke pekerjaan fleksibel dan jarak tempuh pendek. Sementara itu, pekerja logistik, buruh, dan penduduk pinggiran semakin bergantung pada mobil—bukan karena pilihan ideologis, tetapi karena struktur kota. “Pembusukan” yang dimaksud penulis bukanlah kegagalan moral masyarakat Denmark, melainkan kegagalan struktural untuk melanjutkan perjuangan politik mobilitas. Sepeda dipertahankan sebagai simbol, tetapi tidak lagi diperjuangkan sebagai proyek transformasi sosial.
Bagaimanapun Jalan sebagai insfrastruktur sosial dan mobilitas adalah ruang politik. Pada Bab 4: The Politics of Mobility in Copenhagen — kita disugihi perbincangan tentang Jalan sebagai Arena Kekuasaan. Jika dua bab sebelumnya berbicara tentang sejarah dan gejala stagnasi, bab keempat adalah inti teoretis buku ini. Henderson dan Gulsrud secara eksplisit menyatakan: mobilitas adalah politik. Setiap keputusan tentang kecepatan, lebar jalan, parkir, atau lampu lalu lintas adalah keputusan tentang nilai—tentang siapa yang dianggap penting. Di Kopenhagen, politik mobilitas berlangsung dalam berbagai arena: dewan kota, birokrasi perencanaan, media, dan pengalaman harian warga. Sepeda sering dipromosikan sebagai solusi “win-win”: sehat, hijau, murah. Namun penulis memperingatkan bahwa bahasa win-win dapat mengaburkan konflik nyata. Ketika sepeda menang, selalu ada pihak yang merasa kehilangan—biasanya pengguna mobil yang terbiasa dengan privilese ruang dan waktu.
Bab ini menyoroti bagaimana kebijakan sepeda sering harus “dibingkai” secara strategis agar dapat diterima. Alih-alih berbicara tentang keadilan sosial atau krisis iklim, kebijakan sering dijustifikasi lewat efisiensi ekonomi, produktivitas, dan citra kota global. Dengan kata lain, sepeda diterima sejauh ia cocok dengan logika neoliberal kota kompetitif. Namun, Henderson dan Gulsrud tidak sepenuhnya pesimistis. Mereka menunjukkan bahwa politik mobilitas di Kopenhagen tetap terbuka. Konflik tidak disembunyikan, dan warga masih dapat mempengaruhi arah kebijakan. Justru di sinilah letak pelajaran penting: kota sepeda bukanlah kota tanpa konflik, melainkan kota yang bersedia mengelola konflik secara demokratis.
Perkembangan dan dinamika tentang sepeda sebagai sarana atau mode transportasi publik sangat baik menengok ke Kopenhagen: sebagai Cermin, Bukan Model. Melalui tiga bab ini, Street Fights in Copenhagen menegaskan satu pesan kuat: Kopenhagen bukanlah utopia mobilitas hijau, melainkan cermin tentang betapa rapuhnya transisi ekologis. Keberhasilan masa lalu tidak menjamin masa depan. Sepeda tidak akan bertahan hanya dengan infrastruktur; ia membutuhkan politik, imajinasi, dan keberanian untuk terus menantang dominasi mobil.
Ketika upaya publik untuk menyodorkan sepeda sebagai gagasan mode transportasi yang setara dengan mode lainnya, maka pertanyaan yang muncul adalah berapa mobil yang cukup di jalanan kota sehingga memberikan ruang yang cukup pula bagi pesepeda. “How Many Cars in the City?” tulis Henderson dan Gulsrud (Bab 5). Inilah perdebatan toll ring sebagai drama demokrasi perkotaan.
Bab ini berpusat pada satu pertanyaan yang tampak teknis, tetapi sebenarnya eksistensial: berapa banyak mobil yang “boleh” ada di kota? Henderson dan Gulsrud menunjukkan bahwa pertanyaan ini mengguncang fondasi politik Kopenhagen ketika gagasan toll ring—pengenaan biaya bagi mobil yang masuk ke pusat kota—mulai diperdebatkan secara serius.
Toll ring bukan sekadar alat manajemen lalu lintas. Ia adalah mekanisme yang secara eksplisit mengatakan bahwa ruang kota terbatas dan harus diperebutkan secara politik, bukan diberikan gratis kepada kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, mobil kehilangan statusnya sebagai hak alamiah warga dan berubah menjadi aktivitas yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial dan ekologis.
Perdebatan berlangsung panas. Pendukung toll ring—aktivis lingkungan, sebagian perencana kota, dan kelompok pengguna sepeda—membingkainya sebagai kebijakan rasional: mengurangi kemacetan, menurunkan emisi, dan mendanai transportasi publik. Namun penentang kebijakan ini—termasuk partai politik arus utama dan asosiasi pengendara—menggambarkannya sebagai ancaman terhadap kebebasan bergerak dan keadilan sosial.
Yang menarik, Henderson dan Gulsrud menunjukkan bahwa retorika keadilan sosial sering dipakai untuk mempertahankan status quo. Mobil dipresentasikan sebagai kebutuhan kaum pekerja, meskipun data menunjukkan bahwa kepemilikan mobil lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan menengah dan atas. Dalam praktiknya, toll ring ditolak bukan karena ia tidak adil, tetapi karena ia mengganggu normalitas budaya mobil.
Kegagalan penerapan toll ring menjadi momen penting dalam buku ini. Ia menandai batas dari konsensus sepeda Kopenhagen. Kota ini bisa membangun jalur sepeda terbaik di dunia, tetapi ketika harus secara langsung membatasi mobil, resistensi politik menjadi terlalu besar. Di sinilah kita melihat bahwa transisi hijau sering berhenti tepat sebelum menyentuh kepentingan yang paling dilindungi.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana soal parkir? Buku ini membahasnya pada Bab 6: Cycling Policy Is Parking Policy — Politik Parkir sebagai Politik Kekuasaan. Jika toll ring adalah pertempuran besar dan terbuka, maka parkir adalah medan perang yang sunyi namun menentukan. Bab ini mungkin yang paling tajam secara analitis, karena Henderson dan Gulsrud menunjukkan bahwa politik mobilitas tidak ditentukan oleh jalan, melainkan oleh tempat mobil berhenti.
Parkir mobil di Kopenhagen—seperti di banyak kota lain—lama diperlakukan sebagai fasilitas netral. Namun para penulis membongkar ilusi ini. Setiap tempat parkir di pusat kota adalah sebidang ruang publik yang disubsidi secara besar-besaran untuk kepentingan privat. Ketika parkir murah dan melimpah, mobil menjadi pilihan rasional, bahkan jika ada alternatif sepeda atau transportasi publik.
Kebijakan sepeda, dalam kerangka ini, tidak akan efektif tanpa reformasi parkir. Jalur sepeda bisa diperlebar, tetapi jika parkir tetap mudah dan murah, dominasi mobil akan bertahan. Henderson dan Gulsrud menggambarkan bagaimana upaya menaikkan tarif parkir atau mengurangi ruang parkir selalu memicu resistensi keras—bahkan lebih keras daripada kebijakan sepeda itu sendiri.
Parkir menjadi simbol hak istimewa yang jarang disadari. Warga yang tidak memiliki mobil tetap membayar biaya sosial dan ekologis dari ruang parkir: berkurangnya ruang hijau, trotoar yang sempit, dan kualitas udara yang lebih buruk. Namun karena parkir telah dinormalisasi, ketidakadilan ini jarang dibicarakan sebagai isu etika.
Bab ini mengajarkan satu pelajaran penting: sepeda bukan hanya soal mobilitas, tetapi soal distribusi ruang. Ketika kota berani mempersoalkan parkir, ia sedang mempersoalkan relasi kekuasaan paling mendasar dalam urbanisme modern.
Bab 7: From the Harbor Tunnel to the Metro City Ring — Membayangkan Kota yang Mana?
Bab terakhir dalam bagian ini membawa kita ke ranah imajinasi jangka panjang. Henderson dan Gulsrud membandingkan dua proyek infrastruktur besar: rencana terowongan pelabuhan untuk mobil dan pembangunan Metro City Ring. Kedua proyek ini menjadi metafora tentang dua visi kota yang saling bersaing.
Terowongan pelabuhan menjanjikan kelancaran lalu lintas dan efisiensi ekonomi. Namun di balik janji itu, ia mereproduksi logika lama: semakin banyak kapasitas jalan, semakin banyak mobil yang akan datang. Penulis menunjukkan bahwa proyek ini tidak netral—ia mengunci kota pada masa depan yang masih bergantung pada mobil, meskipun dibungkus dengan teknologi canggih.
Sebaliknya, Metro City Ring merepresentasikan visi kota yang lebih kolektif. Transportasi publik berkapasitas besar tidak hanya memindahkan orang, tetapi juga membentuk pola hidup: kepadatan yang lebih tinggi, penggunaan lahan yang lebih efisien, dan ketergantungan yang lebih rendah pada kendaraan pribadi. Namun Henderson dan Gulsrud tidak meromantisasi Metro. Mereka mengingatkan bahwa transportasi publik pun dapat melayani kepentingan kapital—misalnya dengan mendorong gentrifikasi dan spekulasi properti. Pertanyaannya bukan hanya alat apa yang dibangun, tetapi untuk siapa dan dengan nilai apa.
Bab ini menutup dengan pertanyaan filosofis yang menggantung: apakah Kopenhagen akan menjadi kota yang terus memperluas kapasitas mobilnya secara tersembunyi, atau kota yang secara sadar membatasi pertumbuhan lalu lintas demi kualitas hidup? Pertanyaan ini, menurut penulis, belum dijawab—dan justru itulah inti dari politik mobilitas.
Melalui tiga bab ini, Street Fights in Copenhagen memperjelas bahwa masa depan kota tidak ditentukan oleh niat baik atau reputasi global, melainkan oleh keputusan-keputusan sulit tentang pembatasan. Toll ring, parkir, dan infrastruktur besar bukan isu teknis; mereka adalah ekspresi nilai tentang kebebasan, keadilan, dan keberlanjutan.
Kopenhagen, sekali lagi, bukan teladan yang selesai, tetapi medan pertempuran yang jujur. Dan di situlah relevansinya bagi kota-kota lain—termasuk di Indonesia—yang sering ingin meniru “hasil akhir” tanpa bersedia menghadapi konflik yang menyertainya.
Dari Copenhagen ke Jakarta–Bandung
Buku Street Fights in Copenhagen berakhir dengan sebuah kesadaran yang tenang namun radikal: kota mobilitas hijau tidak lahir dari teknologi canggih atau konsensus teknokratik, melainkan dari konflik politik yang panjang, melelahkan, dan tak pernah benar-benar selesai. Kesadaran ini menjadi sangat relevan ketika kita mengalihkan pandangan ke Jakarta dan Bandung—dua kota yang hari ini berada di persimpangan antara krisis mobilitas, krisis iklim, dan krisis imajinasi tentang masa depan kota.
Seperti Copenhagen, Jakarta dan Bandung bukan sekadar ruang fisik, melainkan arena pertempuran nilai. Siapa yang berhak atas jalan? Untuk siapa kota dirancang? Mobilitas macam apa yang dianggap “normal,” “modern,” dan “bermartabat”? Di sinilah pelajaran utama buku ini menemukan relevansinya: mobilitas tidak pernah netral, dan kebijakan transportasi selalu merupakan politik distribusi ruang, waktu, dan risiko.
Jakarta dan Bandung adalah contoh ekstrem dari apa yang Henderson dan Gulsrud sebut sebagai dominasi logika mobil. Kota yang tercekik oleh pertumbuhan. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi—mobil dan motor—tidak hanya mencerminkan kebutuhan mobilitas, tetapi juga aspirasi kelas menengah, narasi pembangunan, dan janji kebebasan individual. Jalan tol dalam kota, flyover, underpass, dan pelebaran jalan adalah manifestasi dari imajinasi pertumbuhan: bahwa kemacetan dapat diatasi dengan menambah kapasitas, bukan dengan membatasi.
Namun seperti ditunjukkan dalam buku ini, pertumbuhan kapasitas selalu melahirkan permintaan baru. Jakarta adalah bukti paling telanjang dari paradoks tersebut. Setiap infra-struktur baru segera dipenuhi kendaraan, sementara kualitas hidup kota terus merosot—udara memburuk, waktu hilang, ruang publik menyusut. Dalam bahasa degrowth, ini adalah kota yang terjebak dalam treadmill of growth: bergerak cepat tanpa benar-benar maju. Bandung, meski lebih kecil, mengulang pola yang sama. Kota yang dahulu bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan sepeda kini macet oleh kendaraan dari dan ke kawasan metropolitan. Wisata, properti, dan konsumsi ruang menjadi justifikasi baru bagi ekspansi mobilitas bermotor. Sepeda dan pejalan kaki, seperti di Copenhagen pra-reformasi, kembali didorong ke pinggir—secara harfiah dan simbolik.
Dalam konteks ini, sepeda di Jakarta dan Bandung bukan sekadar alat transportasi alternatif. Ia adalah praktik degrowth dalam arti paling konkret. Bersepeda berarti bergerak lebih lambat, menggunakan lebih sedikit energi, mengambil lebih sedikit ruang, dan menerima batas-batas tubuh. Itulah sebabnya sepeda sering terasa “tidak cocok” dengan kota kapitalis: ia menolak logika kecepatan, efisiensi maksimum, dan akumulasi.
Buku ini membantu kita memahami mengapa kebijakan pro-sepeda di Jakarta—seperti jalur sepeda permanen—selalu memicu resistensi. Resistensi itu bukan semata soal teknis, melain-kan soal ancaman terhadap tatanan lama. Membatasi ruang mobil berarti mempertanyakan hierarki sosial yang selama ini dilekatkan pada kendaraan pribadi. Di sinilah sepeda menjadi politik, bukan hobi.
Copenhagen mengajarkan bahwa perubahan semacam ini tidak pernah linier. Ada kemajuan, stagnasi, bahkan kemunduran. Jakarta dan Bandung dan kota-kota lain di Nusantara tidak gagal hanya karena jalur sepeda dibongkar atau diperdebatkan. Kegagalan sesungguhnya adalah ketika konflik tersebut disangkal dan digantikan oleh retorika “keseimbangan” yang netral palsu.
Degrowth Mobility: Dari Efisiensi ke Pembatasan
Sintesis besar buku ini bagi wacana degrowth mobility adalah penegasan bahwa kota hijau tidak dibangun dengan membuat mobil lebih efisien, tetapi dengan membuat mobil kurang dominan. Ini adalah pergeseran etika: dari optimasi menuju pembatasan. Dari “bagaimana kita bergerak lebih cepat?” menuju “mengapa kita perlu bergerak sejauh dan secepat ini?” Dalam kerangka degrowth, mobilitas bukan lagi tentang memaksimalkan jarak tempuh, melainkan meminimal-kan kebutuhan perjalanan. Ini berarti kota yang lebih padat secara sosial, bukan secara kendaraan; kota yang memungkinkan hidup dekat dengan kerja, pasar, sekolah, dan ruang publik. Street Fights in Copenhagen menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini selalu menghadapi perlawanan, tetapi juga membuka kemungkinan solidaritas baru.
Jakarta dan Bandung memiliki potensi degrowth mobility yang besar: jaringan kampung, ekonomi lokal, budaya nongkrong, dan kehidupan jalanan yang sesungguhnya ramah bagi mobilitas lambat. Yang hilang bukanlah kapasitas, melainkan keberanian politik untuk membatasi.
Penutup buku ini menawarkan konsep yang sangat penting bagi kota-kota seperti Jakarta dan Bandung: politik harapan, politik harapan di kota Global Selatan. Harapan bukan janji bahwa kota akan menjadi “seperti Copenhagen,” melainkan keyakinan bahwa konflik itu sendiri adalah tanda kehidupan demokratis. Jalur sepeda yang diperdebatkan, parkir yang dikurangi, jalan yang dipedestrianisasi—semua itu bukan kegagalan tata kota, melainkan tanda bahwa kota sedang dinegosiasikan ulang.
Degrowth mobility tidak menjanjikan kota tanpa konflik. Ia menjanjikan kota yang jujur tentang batas-batasnya, dan berani memilih kehidupan daripada kecepatan. Dalam konteks krisis iklim, ketimpangan, dan kelelahan urban, inilah mungkin satu-satunya arah yang masuk akal.
Catatan Akhir: Kota sebagai Proyek Moral
Street Fights in Copenhagen pada akhirnya adalah buku tentang kota sebagai proyek moral, bukan proyek teknis. Ia mengingatkan kita bahwa masa depan mobilitas ditentukan bukan oleh algoritma atau mesin, tetapi oleh keberanian untuk bertanya: hidup macam apa yang ingin kita jalani bersama?
Dalam penutup buku ini, Henderson dan Gulsrud tidak menawarkan kesimpulan yang bersifat final atau kemenangan yang telah diraih. Sebaliknya, mereka mengajak pembaca memasuki wilayah yang lebih rapuh namun justru lebih penting: politik harapan. Setelah berlapis-lapis konflik, kegagalan kebijakan, kompromi politik, dan tarik-menarik kepentingan, mereka menegaskan bahwa kota mobilitas hijau tidak lahir dari konsensus yang rapi, melainkan dari perjuangan yang terus-menerus untuk mendefinisikan masa depan bersama.
Harapan, dalam pengertian yang digunakan penulis, bukan optimisme naif bahwa teknologi atau kebijakan akan otomatis menyelamatkan kota. Harapan adalah praktik politik—kemampuan warga, aktivis, perencana, dan pembuat kebijakan untuk terus memperjuangkan perubahan meskipun hasilnya parsial, tertunda, atau bahkan dibatalkan. Dalam konteks Kopenhagen, sepeda bukan simbol kemenangan mutlak, melainkan simbol kemungkinan yang terus diperjuangkan.
Penulis menekankan bahwa keberhasilan Kopenhagen sering disalahpahami secara global. Kota ini kerap dipresentasikan sebagai model ideal yang telah “selesai” melakukan transisi hijau. Padahal, buku ini menunjukkan sebaliknya: di balik jalur sepeda yang rapi dan statistik peng-gunaan sepeda yang mengesankan, terdapat konflik laten tentang mobil, ruang, kelas sosial, dan arah pembangunan. Kota hijau bukan keadaan stabil, melainkan arena konflik yang terus bergerak.
Dalam kerangka ini, politik mobilitas hijau tidak bisa dipisahkan dari politik demokrasi. Keputus-an tentang parkir, tol, infrastruktur, dan transportasi publik adalah keputusan tentang siapa yang diuntungkan, siapa yang dibatasi, dan nilai apa yang diprioritaskan. Henderson dan Gulsrud menolak gagasan bahwa kota hijau dapat dibangun hanya melalui keahlian teknis atau manajemen cerdas. Tanpa partisipasi publik dan konflik terbuka, “hijau” berisiko menjadi kosmetik—sekadar label yang menutupi keberlanjutan dominasi mobil dan logika pertumbuhan.
Yang menarik, penulis juga memperingatkan terhadap bahaya sinisme. Mengetahui bahwa transisi hijau penuh kontradiksi tidak boleh berujung pada sikap apatis. Justru di sinilah politik harapan menjadi penting: mengakui keterbatasan, tanpa menyerah pada status quo. Kopen-hagen, meskipun gagal dalam beberapa kebijakan kunci seperti toll ring, tetap menunjuk-kan bahwa perubahan mungkin terjadi melalui akumulasi langkah-langkah kecil, tekanan publik, dan pergeseran budaya jangka panjang.
Kota mobilitas hijau, dalam kesimpulan ini, didefinisikan bukan oleh absennya mobil, tetapi oleh keberanian untuk membatasi. Membatasi mobil bukan tindakan anti-kebebasan, melainkan upaya memperluas kebebasan kolektif—kebebasan untuk bernapas lebih bersih, bergerak lebih aman, dan hidup di ruang kota yang lebih adil. Di sini, sepeda berfungsi bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi sebagai praktik politik sehari-hari yang menantang normalitas lama.
Penutup buku ini juga membuka cakrawala ke luar Kopenhagen. Henderson dan Gulsrud menegaskan bahwa tidak ada model universal yang bisa diekspor begitu saja. Setiap kota harus menemukan jalannya sendiri, dengan sejarah, konflik, dan struktur kekuasaannya masing-masing. Namun, satu hal bersifat universal: tanpa konflik, tidak ada transisi; tanpa harapan, tidak ada politik hijau.
Dengan demikian, Street Fights in Copenhagen berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan undangan. Undangan untuk melihat kota sebagai proyek moral dan politik, bukan sekadar mesin efisiensi. Undangan untuk memahami mobilitas sebagai medan perjuangan nilai. Dalam Islam, prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dapat dibaca sebagai dasar etis bagi prioritas mobilitas publik dan non-motorized. Dan yang terpenting, undangan untuk terus berharap—bukan karena masa depan pasti lebih baik, tetapi karena masa depan hanya bisa diperjuangkan jika kita berani membayangkannya secara berbeda.
Bagi Jakarta dan Bandung, pertanyaan itu masih terbuka. Dan seperti ditunjukkan buku ini, keterbukaan itulah sumber harapan terbesar. Jika degrowth adalah tentang hidup cukup, maka degrowth mobility adalah tentang bergerak secukupnya—dan mungkin, untuk pertama kalinya, benar-benar sampai.
Street Fights in Copenhagen pada akhirnya adalah buku tentang demokrasi sehari-hari. Jalan sebagai arena demokrasi ekologis. Ia mengajak kita melihat jalan raya sebagai ruang tempat nilai-nilai sosial diuji: keadilan, keberlanjutan, keselamatan, dan solidaritas. Jane Jacobs, seorang arsitek dan pemerhati kota, mengingatkan bahwa kota yang sehat adalah kota dengan kehidupan jalanan yang kaya, bukan lalu lintas yang lancar semata.
Dalam dunia yang menghadapi krisis iklim, buku ini mengingatkan bahwa transisi hijau tidak akan pernah “halus” atau bebas konflik. Tetapi justru melalui konflik yang terbuka dan politis itulah, kota yang lebih manusiawi bisa dibangun.
Bogor, 24 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Henderson, J., & Gulsrud, N. M. (2019). Street fights in Copenhagen: Bicycle and car politics in a green mobility city. Routledge.
Illich, I. (1974). Energy and equity. Harper & Row.
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. Random House.
Lefebvre, H. (1996). Writings on cities. Blackwell.