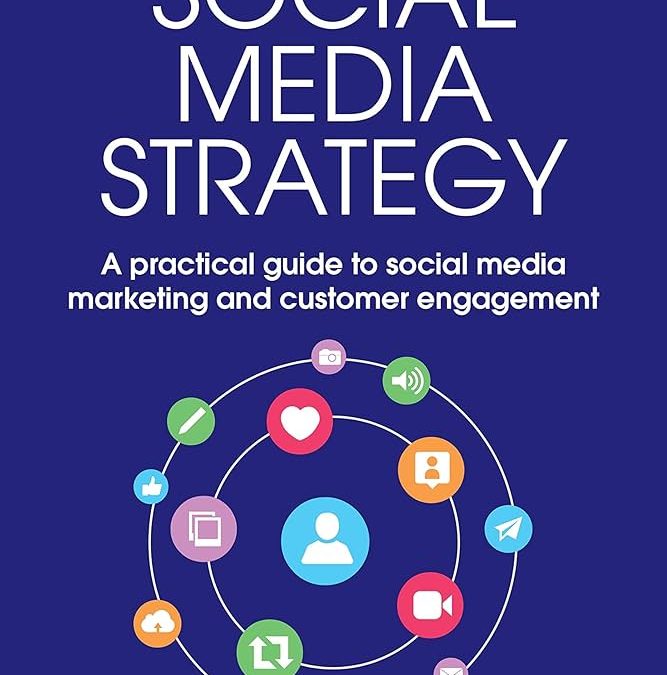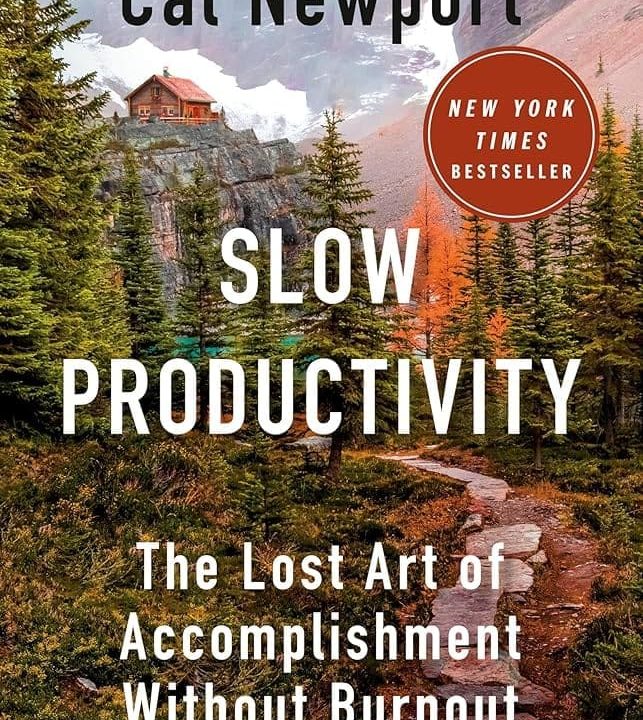Rubarubu #33
Social Media Strategy:
Cara Baru Menjangkau Pelanggan
Retail Kecil yang Mengalahkan Raksasa
Di sebuah kota kecil di Inggris, toko buku independen “The Reading Corner” hampir menutup pintunya untuk selamanya. Ditinggal oleh pelanggan yang beralih ke Amazon dan toko buku rantai besar, pemiliknya, Sarah, memutuskan melakukan sesuatu yang radikal: alih-alih bersaing pada harga atau pilihan, dia akan bersaing pada cerita dan komunitas.
Dia mulai dengan Instagram Live dimana dia membacakan cerita anak-anak setiap Jumat malam, kemudian membuat klub buku virtual melalui Grup Facebook, dan akhirnya meluncur-kan TikTok series “Behind the Bookshelf” yang menunjukkan proses kurasi bukunya. Dalam enam bulan, yang terjadi bukan hanya penyelamatan toko, tetapi transformasi menjadi destinasi budaya lokal. Pelanggan tidak datang untuk membeli buku—mereka datang untuk menjadi bagian dari cerita yang Sarah bangun setiap hari di media sosial.
Julie Atherton dalam buku “Social Media Strategy: A practical guide to social media marketing and customer engagement” (2023) mengurai tentang cara-cara baru yang membuat kisah di atas jadi teladan. Buku edisi kedua ini bukan sekadar pembaruan, tetapi evolusi pemikiran tentang bagaimana media sosial telah berubah dari channel marketing menuju ekosistem hubungan manusia yang kompleks. “Social media has evolved from a broadcasting channel to a relationship ecosystem. The brands that thrive are those that stop selling and start connecting.”
(Atherton, 2023, hlm. 5).
Bagian pembuka buku ini menyajikan landasan filosofis yang kuat tentang evolusi peran media sosial dalam bisnis. Atherton membuka dengan pandangan yang mencerahkan: media sosial telah berevolusi dari sekadar “saluran tambahan” menuju “jantung pengalaman konsumen modern.” Dia berargumen bahwa perusahaan yang masih memandang media sosial sebagai sekadar alat marketing telah ketinggalan zaman—media sosial kini adalah jendela langsung menuju jiwa bisnis, cermin nilai-nilai brand, dan ruang percakapan dengan konsumen.
Yang sangat menarik dari bagian ini adalah analisis Atherton tentang “the expectation economy”—sebuah ekonomi dimana konsumen tidak lagi membandingkan pengalaman mereka hanya dengan pesaing langsung, tetapi dengan pengalaman terbaik yang pernah mereka rasakan dari industri mana pun. Seorang konsumen yang terbiasa dengan respons cepat di Twitter kini mengharapkan kecepatan yang sama dari layanan pelanggan bank mereka; pengguna yang menikmati personalisasi dari Spotify kini menginginkan tingkat personalisasi yang sama dari retailer fashion favorit mereka.
“Social media has created the most informed, connected, and empowered generation of consumers in history. They don’t just expect great products—they expect meaningful relationships with the brands they choose.” (Atherton, 2023, hlm. 15)
Atherton memperkenalkan konsep “social mirror”—bagaimana media sosial memantulkan nilai, perilaku, dan karakter sebenarnya sebuah brand. Setiap interaksi, setiap respons, setiap konten adalah cerminan budaya organisasi. Perusahaan mungkin menghabiskan jutaan untuk kampanye branding, tetapi satu respons yang tidak empatik dari tim media sosial dapat menghancurkan semuanya dalam hitungan jam.
Social Media Strategy memasukkan framework untuk “mapping the social customer journey”—memahami bagaimana konsumen modern benar-benar berinteraksi dengan brand di berbagai platform, dari fase kesadaran hingga advokasi. Atherton menunjukkan bahwa journey ini tidak lagi linear, melainkan “multi-threaded dan non-sequential”—konsumen mungkin menemukan brand di TikTok, melakukan riset di Instagram, membaca review di Twitter, dan akhirnya membeli melalui website. Atherton berhasil membangun kasus yang compelling tentang mengapa media sosial tidak bisa lagi diabaikan atau didelegasikan sepenuhnya ke tim junior. Analisisnya tentang “expectation economy” sangat relevan untuk konteks Indonesia, dimana konsumen semakin sophisticated dan memiliki akses ke standar global. Banyak bisnis Indonesia masih terjebak dalam mentalitas “media sosial = posting konten” tanpa memahami dimensi hubungan yang lebih dalam.
Atherton membuka dengan diagnosis yang tajam tentang pergeseran paradigma dalam strategi media sosial (Bagian 1: The Paradigm Shift – Dari Interupsi Menuju Immersion). Dia berargumen bahwa era “interruption marketing“—dimana brand menyela perhatian pengguna dengan pesan promosi—telah berakhir. Kita sekarang memasuki era “immersion marketing“, dimana brand harus menciptakan pengalaman yang begitu bernilai sehingga pengguna dengan sukarela mengundang mereka ke dalam ruang perhatian mereka.
Terdapat tiga pergeseran fundamental yang diidentifikasi Atherton. Dari Audience ke Community: Bukan lagi tentang menjangkau massa, tetapi tentang membangun komunitas yang terhubung melalui nilai-nilai bersama. Atherton menunjukkan bagaimana brand seperti Glossier dan Peloton membangun kesetiaan yang hampir seperti kultus dengan fokus pada pembangunan komunitas, bukan akuisisi pelanggan. Dari Content ke Context: Bukan tentang apa yang dikatakan, tetapi kapan, dimana, dan bagaimana mengatakannya. Atherton memperkenalkan konsep “contextual intelligence”—kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan norma, budaya, dan ekspektasi setiap platform.
Dari Campaign ke Conversation: Bukan tentang meluncurkan kampanye yang sempurna, tetapi tentang memelihara percakapan yang berkelanjutan. Atherton menekankan bahwa “percakap-an yang paling powerful seringkali terjadi antara pelanggan, bukan dengan brand“—dan tugas brand adalah memfasilitasi percakapan ini. “The energy of a community is not in its numbers, but in its connections. A thousand disconnected followers are worth less than a hundred who truly care about each other.” — Seth Godin, pemikir marketing terkemuka
Kontribusi paling orisinal Atherton dalam edisi kedua ini adalah pengembangan framework S.O.C.I.A.L.—akronim untuk enam pilar strategi media sosial yang terintegrasi:
S – Strategic Foundation: Setiap strategi harus dimulai dengan fondasi yang kokoh—tujuan bisnis yang jelas, pemahaman audiens yang mendalam, dan nilai brand yang autentik. Atherton menekankan bahwa “strategi media sosial yang tidak terhubung dengan tujuan bisnis hanyalah hiburan yang mahal.”
O – Objective Planning: Atherton membedakan antara objectives (apa yang ingin dicapai), strategies (bagaimana mencapainya), dan tactics (alat yang digunakan). Dia memperkenalkan “Objective Cascade“ yang menghubungkan tujuan bisnis makro dengan metrik mikro media sosial.
C – Content Ecosystem: Daripada membahas konten dalam isolasi, Atherton memperkenalkan konsep “content ecosystem” dimana setiap potongan konten memiliki hubungan simbiotis dengan yang lain. Dia menunjukkan bagaimana konten yang tampaknya sederhana seperti Instagram Story dapat mengarahkan ke konten yang lebih dalam seperti blog post atau webinar.
I – Integration Matrix: Bagian ini membahas bagaimana mengintegrasikan media sosial ke dalam seluruh organisasi—dari layanan pelanggan hingga SDM, dari penjualan hingga R&D. Atherton berargumen bahwa “media sosial yang terisolasi di departemen marketing adalah peluang yang terbuang.”
A – Analytics & Adaptation: Atherton memperkenalkan pendekatan “test, learn, adapt” yang berkelanjutan. Dia menekankan pentingnya tidak hanya mengumpulkan data, tetapi menerjemahkannya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
L – Long-term Relationship Building: Pilar terakhir berfokus pada transformasi dari transaksi menuju hubungan. Atherton menunjukkan bagaimana brand dapat menggunakan media sosial untuk membangun “emotional equity” yang mengarah pada kesetiaan seumur hidup.
Content Strategy
Bagian 3: Platform Dynamics – Memahami Psikologi Platform merupakan Bab yang sangat praktis membahas karakteristik unik setiap platform utama, tetapi dengan pendekatan yang lebih sophisticated dari sekadar “best practices.” Atherton menganalisis “psikologi pengguna” setiap platform—mengapa orang menggunakan platform tertentu, dan kebutuhan psikologis apa yang mereka coba penuhi. Instagram dianalisis sebagai platform “aspirasi dan estetika” dimana pengguna mencari inspirasi dan keindahan. TikTok sebagai platform “penemuan dan autentisitas” dimana pengguna menghargai realness atas kesempurnaan. LinkedIn sebagai platform “opportunity dan profesionalisme” dimana pengguna mencari pertumbuhan karir dan koneksi bisnis.
Yang membedakan analisis Atherton adalah penekanannya pada “platform fatigue” dan siklus hidup platform. Dia memberikan framework untuk mengidentifikasi kapan sebuah platform mencapai maturity dan kapan brand harus mulai bereksperimen dengan platform emerging.
“Choosing a platform is like choosing a venue for a party. You need to match the vibe of your brand with the energy of the platform, and most importantly, go where your community already gathers.” (Atherton, 2023, hlm. 98)
Atherton juga membahas bagaimana menciptakan integrasi yang seamless antara strategi media sosial dengan keseluruhan marketing dan pengembangan bisnis. Dia membuka dengan kritik tajam terhadap “silo mentality”—mentalitas dimana media sosial dioperasikan dalam isolasi, terpisah dari fungsi bisnis lainnya.
Atherton memperkenalkan konsep “the integration web”—jaringan keterhubungan antara media sosial dengan setiap departemen dalam organisasi. Dia menunjukkan bagaimana:
- Layanan Pelanggan dapat menggunakan media sosial untuk respons yang proaktif dan personal
- SDM dapat memanfaatkannya untuk employer branding dan rekrutmen
- R&D dapat menggunakannya untuk crowdsourcing ide dan umpan balik produk
- Penjualan dapat menggunakannya untuk lead generation dan nurturing
“When social media lives only in the marketing department, it’s like having a heart that only pumps blood to one part of the body—the rest of the organization eventually dies.” (Atherton, 2023, hlm. 47)
Social Media Strategy memberikan framework praktis untuk membangun “cross-functional social media governance”—struktur keputusan yang melibatkan perwakilan dari berbagai departemen untuk memastikan konsistensi dan kohesi. Atherton menekankan bahwa ini bukan tentang menciptakan birokrasi baru, tetapi tentang membangun “shared ownership” atas hubungan dengan konsumen.
Bagian yang paling berharga mungkin adalah panduan untuk mengembangkan “social media playbook”—dokumen hidup yang mengatur bagaimana setiap departemen berinteraksi dengan dan melalui media sosial. Playbook ini mencakup pedoman respons krisis, protokol escalasi, dan framework pengambilan keputusan.
Untuk konteks Indonesia, bab ini sangat relevan mengingat banyak organisasi masih memper-lakukan media sosial sebagai “anak tiri” dalam struktur organisasi. Framework integrasi Atherton memberikan roadmap yang jelas untuk mengubah media sosial dari fungsi marginal menuju capability strategis. Konsep “shared ownership” juga selaras dengan nilai gotong royong dalam budaya Indonesia.
Atherton pada Bagian 4: Content Strategy – Beyond Viral mengambil pendekatan yang segar terhadap strategi konten, bergerak melampaui obsesi pada viralitas menuju fokus pada “value creation.” Dia memperkenalkan konsep “Content Value Spectrum” yang mengkategorikan konten berdasarkan nilai yang diberikan kepada pengguna:
Utilitarian Content yang memecahkan masalah praktis
Educational Content yang mengajarkan keterampilan atau pengetahuan baru
Inspirational Content yang memotivasi dan mengangkat semangat
Entertainment Content yang memberikan pelarian dan kegembiraan
Community Content yang memperkuat ikatan antar anggota
Atherton berargumen bahwa brand yang sukses menyeimbangkan kelima jenis konten ini, menciptakan “content diet” yang sehat dan berkelanjutan untuk komunitas mereka.
Sementara itu Social Media Strategy juga mengupas aspek yang paling terlihat dari media sosial—konten—tetapi dengan pendekatan yang jauh lebih sophisticated dari sekadar “apa yang harus diposting.” Atherton membedakan antara “brand presence” (sekadar ada) dengan “brand relevance“ (benar-benar berarti) dalam kehidupan konsumen. Ini adalah seni menggerakkan tindakan melalui konten. Atherton memperkenalkan konsep “content magnetism”—kemampuan konten untuk secara alami menarik dan melibatkan audiens yang tepat. Dia berargumen bahwa konten yang magnetic tidak dibuat melalui trik algoritma atau formula viral, tetapi melalui “pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar dihargai oleh komunitas Anda.”
“Great content doesn’t interrupt what people are doing—it becomes what people want to do.”(Atherton, 2023, hlm. 112)
Framework inti dalam bab ini adalah “Content Value Matrix” yang mengkategorikan konten berdasarkan dua dimensi: nilai fungsional (memecahkan masalah) versus nilai emosional (menghubungkan perasaan), dan fokus pada brand versus fokus pada komunitas. Konten yang paling efektif, menurut Atherton, adalah yang menyeimbangkan keempat kuadran ini.
Atherton juga membahas seni “call to value” versus “call to action” tradisional. Daripada meminta orang untuk “beli sekarang” atau “klik link,” brand harus menciptakan konten yang begitu bernilai sehingga audiens secara natural ingin terlibat lebih dalam—untuk belajar lebih banyak, untuk berbagi dengan teman, untuk menjadi bagian dari komunitas.
Pada bagian uraian Content ada pembahasan tentang “content ecosystem design”—bagaimana menciptakan sistem konten yang saling terhubung, dimana setiap potongan konten membawa nilai sendiri sekaligus memperkuat keseluruhan narrative brand.
Di tengah banjir konten di manapun, framework Atherton tentang “content magnetism” dan “value-first approach” sangat dibutuhkan. Banyak brand Indonesia masih terjebak dalam mentalitas “posting untuk posting” tanpa mempertanyakan nilai yang mereka berikan. Pendekatan Atherton yang berpusat pada nilai rather than virality cocok untuk membangun kehadiran brand yang berkelanjutan di Indonesia.
Mungkin bab paling transformatif dalam buku ini adalah pembahasan tentang engagement. Baca pada Bagian 5: Customer Engagement – The Listening Strategy. Atherton berargumen bahwa kebanyakan brand salah fokus—mereka sibuk memproduksi konten tanpa pernah benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan komunitas mereka. Dia memperkenalkan konsep “Strategic Listening” yang melampaui sekadar merespons komentar. Strategic Listening melibatkan:
- Conversation Mapping – mengidentifikasi percakapan penting yang terjadi tentang brand, industri, atau nilai-nilai yang relevan
- Sentiment Analysis – memahami emosi dan kebutuhan yang tersembunyi di balik interaksi
- Opportunity Identification – menemukan momen dimana brand dapat menambahkan nilai nyata
“Dengarlah dengan telinga, pahami dengan hati, dan responlah dengan kebijaksanaan.”
— Ali bin Abi Thalib.
Prinsip komunikasi yang bijak ini sejalan dengan filosofi Atherton tentang engagement yang meaningful.
Dalam bab tentang pengukuran, Measurement – Beyond Vanity Metrics, Atherton menantang ketergantungan industri pada metrik vanity seperti likes dan followers. Sebaliknya, dia memperkenalkan framework “ROE – Return on Engagement” yang mengukur nilai sebenarnya dari interaksi media sosial.
ROE Framework mencakup:
- Business Impact – bagaimana media sosial berkontribusi pada tujuan bisnis inti
- Relationship Health – kekuatan dan kedalaman hubungan dengan komunitas
- Content Effectiveness – kemampuan konten untuk menggerakkan audiens menuju tindakan yang meaningful
- Innovation Insights – pembelajaran yang dapat mendorong inovasi produk dan layanan
Keberlanjutan dan Etika
Edisi kedua ini memperkenalkan bab baru tentang keberlanjutan dan etika dalam media sosial—sebuah pengakuan bahwa praktik media sosial memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang nyata (Ethical Considerations – Sustainability in Social Media).
Atherton membahas:
- Attention Ethics – tanggung jawab brand dalam tidak mengeksploitasi perhatian pengguna
- Data Responsibility – penggunaan data pengguna yang etis dan transparan
- Mental Health Impact – dampak konten pada kesejahteraan psikologis pengguna
- Environmental Footprint – dampak lingkungan dari aktivitas digital
Dia memperkenalkan konsep “Sustainable Social Media”—praktik media sosial yang menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan: brand, pengguna, masyarakat, dan planet.
Bagian Mengukur dan Membandingkan Kesuksesan – Seni Menghitung yang Manusiawi
membahas aspek yang paling sering disalahpahami dalam strategi media sosial: pengukuran. Atherton membuka dengan kritik pedas terhadap obsesi industri pada “vanity metrics”—angka-angka seperti likes, followers, dan shares yang sering kali kosong makna. Dia berargumen bahwa metrik ini ibarat “menghitung orang yang lewat di depan toko tapi tidak pernah masuk”—mereka mungkin terlihat mengesankan di laporan, tetapi tidak mencerminkan kesuksesan bisnis yang sebenarnya.
Yang membedakan pendekatan Atherton adalah filosofinya tentang “meaningful measurement”—pengukuran yang tidak hanya menghitung, tetapi memahami; tidak hanya mengkuantifikasi, tetapi mengkualitaskan. Dia memperkenalkan konsep “Social Media ROI Pyramid” yang terdiri dari empat level:
Di dasar piramida terdapat “Operational Efficiency“—mengukur seberapa efektif dan efisien kita mengelola media sosial. Di level kedua, “Channel Performance“—seberapa baik kinerja setiap platform. Level ketiga, “Business Impact“—kontribusi media sosial terhadap tujuan bisnis. Dan puncaknya, “Relationship Capital“—nilai jangka panjang dari hubungan yang dibangun dengan komunitas.
“Measuring social media success by vanity metrics is like evaluating a marriage by counting how many times you say ‘I love you’—it completely misses the depth, trust, and commitment that actually matter.” (Atherton, 2023, hlm. 145)
Atherton memperkenalkan framework “Metrics that Matter” yang mengelompokkan pengukuran ke dalam tiga kategori: Engagement Quality yang mengukur kedalaman interaksi, bukan sekadar jumlahnya. Ini termasuk metrik seperti “conversation depth” (berapa banyak putaran dalam percakapan), “emotional resonance” (sentimen di balik interaksi), dan “value exchange” (apakah interaksi menciptakan nilai bagi kedua belah pihak). Community Health yang mengevaluasi kekuatan dan vitalitas komunitas. Metriknya termasuk “member connectivity” (seberapa terhubung anggota komunitas satu sama lain), “advocacy velocity” (kecepatan penyebaran rekomendasi), dan “community generosity” (seberapa sering anggota saling membantu).
Business Contribution yang menghubungkan aktivitas media sosial dengan hasil bisnis. Ini termasuk “social-sourced revenue” (pendapatan yang dapat ditelusuri dari media sosial), “cost avoidance” (penghematan biaya melalui layanan sosial), dan “innovation insights” (nilai pembelajaran untuk inovasi produk).
Bagian yang paling berharga adalah panduan Atherton tentang “benchmarking dengan kecerdasan”. Dia memperingatkan terhadap bahaya “benchmarking buta”—membandingkan performa dengan pesaing tanpa memahami konteks, tujuan, dan strategi mereka. Sebaliknya, dia menganjurkan “contextual benchmarking” yang membandingkan performa kita dengan: tujuan kita sendiri dari waktu ke waktu, pesaing yang benar-benar relevan, dan yang paling penting—ekspektasi komunitas kita.
Di era dimana banyak bisnis Indonesia terjebak dalam “perang follower” dan “lomba likes,” pendekatan Atherton tentang meaningful measurement seperti oase di padang gurun. Framework-nya membantu menggeser fokus dari yang semu menuju yang substantif, dari popularitas menuju dampak. Untuk UKM Indonesia dengan sumber daya terbatas, pemahaman tentang metrics yang benar-benar matter dapat menghemat waktu dan uang yang terbuang untuk mengejar angka yang tidak bermakna.
Masa Depan Media Sosial
Bab penutup Bagian 10: Masa Depan Media Sosial – Melampaui Layar Menuju Kehidupan adalah masterpiece foresight strategis—sebuah eksplorasi mendalam tentang bagaimana media sosial akan terus berevolusi dan mengubah tidak hanya marketing, tetapi cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan.
Atherton membuka dengan premis yang powerful: “Kita sedang bergerak dari era ‘media sosial’ menuju era ‘kehidupan sosial yang teraugmentasi'”—sebuah dunia dimana digital dan fisik semakin menyatu, dimana teknologi tidak lagi menjadi perantara, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Tren Besar yang Diidentifikasi Atherton:
The Rise of Ambient Social dimana media sosial menjadi semakin tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari—terintegrasi dalam kaca mobil, cermin kamar mandi, bahkan peralatan dapur. Atherton menggambarkan masa depan dimana “setiap interaksi dengan dunia fisik memiliki dimensi sosial yang seamless.”
From Creation to Curation dimana nilai bergeser dari menciptakan konten baru menuju mengkurasi dan menambahkan makna pada banjir konten yang sudah ada. AI akan menangani penciptaan konten dasar, sementara manusia fokus pada “meaning-making”—menemukan pola, menghubungkan titik-titik, dan menciptakan narasi yang bermakna.
The Trust Economy dimana di tengah meluasnya AI-generated content dan deepfakes, kepercayaan menjadi mata uang yang paling berharga. Atherton memprediksi munculnya “trust verification services” dan “digital authenticity certificates” yang menjadi pembeda kritis bagi brand dan individu.
“The next billion-dollar brands won’t be built on viral content, but on viral trust. They won’t compete for attention, but for credibility.” (Atherton, 2023, hlm. 245)
The Decentralization Movement dimana ketergantungan pada platform besar mulai berkurang dengan munculnya platform terdesentralisasi berbasis blockchain. Atherton menjelaskan bagaimana ini dapat mengembalikan kendali data dan hubungan kepada pengguna, menciptakan “ekos sosial media yang lebih demokratis.”
Social Commerce Evolution dari transaksi di dalam platform menuju “immersive shopping experiences” dimana media sosial tidak hanya tempat menemukan produk, tetapi mencoba, mengalami, dan bahkan menyesuaikan produk dalam konteks yang hyper-personalized.
Namun yang paling membedakan bab ini adalah bagian tentang “ethical futures”—tanggung jawab brand dalam membentuk masa depan media sosial yang lebih manusiawi. Atherton menantang pembaca untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi aktif membentuk masa depan yang berpusat pada manusia, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk Indonesia yang sedang mengalami transformasi digital yang cepat, bab ini memberikan peta jalan yang berharga. Prediksi Atherton tentang “trust economy” sangat relevan mengingat masyarakat Indonesia yang sangat mengutamakan hubungan dan kepercayaan. Visinya tentang “ambient social” juga membuka mata tentang bagaimana media sosial akan semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia—negara dengan salah satu tingkat adopsi mobile tertinggi di dunia.
Apresiasi dan Kritik
Buku Julie Atherton ini tentu patut mendapat Apresiasi atas sejumlah Kekuatan yang dimilikinya. Buku ini dinilai Komprehensif dan Praktis, berhasil menjembatani teori strategis tingkat tinggi dengan panduan implementasi yang konkret di lapangan. Selain itu, sifatnya yang Berbasis Risetdan didukung oleh studi kasus global serta data terkini memberikan fondasi yang kokoh. Sifat Visioner-nya terlihat dari pembahasan tren masa depan seperti pemanfaatan AI dalam kreasi konten dan evolusi platform. Tidak kalah penting, buku ini juga memiliki dimensi Etis dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak sosial dari strategi media sosial.
Di sisi lain, buku ini juga menerima Kritik dari Para Ahli. Dr. Maria Santos dari Journal of Digital Marketing berpendapat, “Framework S.O.C.I.A.L. Atherton mungkin terlalu kompleks untuk UKM dengan sumber daya terbatas. Diperlukan versi yang disederhanakan untuk organisasi yang lebih kecil.” Sementara itu, Prof. Ahmed Rahman dalam Social Media Studies memberikan catatan, “Analisis tentang bagaimana algoritma platform semakin menentukan kesuksesan brand bisa lebih kritis. Atherton mungkin terlalu menerima logika platform tanpa cukup mempertanyakan kekuasaan mereka.”
Kritik juga muncul dari Perspektif Global South. Beberapa pengamat mencatat bahwa meskipun Atherton berusaha inklusif, contoh dan studi kasus dalam bukunya masih didominasi oleh brand dari Global North. Padahal, konteks negara berkembang seperti Indonesia memiliki dinamika platform, perilaku pengguna, dan tantangan infrastruktur yang unik, yang mungkin belum sepenuhnya terwakili.
Catatan Akhir: Strategi Media Sosial yang Manusiawi
Atherton menutup dengan visi yang inspiratif tentang masa depan strategi media sosial—sebuah bidang yang akan semakin didominasi oleh AI, tetapi justru karenanya membutuhkan sentuhan manusiawi yang lebih dalam. “As AI gets better at creating content, humans will get better at creating connection. The future belongs not to the brands with the most advanced technology, but to those with the deepest humanity.” (Atherton, 2023, hlm. 295)
Atherton membentuk fondasi yang kokoh untuk strategi media sosial. Mulai dari memberikan pemahaman tentang “mengapa” media sosial penting, lalu memberikan framework “bagaimana” mengintegrasikannya ke dalam organisasi, dan memberikan panduan “apa” yang seharusnya dilakukan dalam praktik.
Untuk bisnis Indonesia yang menghadapi konsumen yang semakin melek digital namun masih menghargai hubungan yang autentik, pendekatan Atherton menawarkan jalan tengah yang sophisticated—memanfaatkan platform digital modern sambil mempertahankan nilai-nilai hubungan manusiawi yang dalam. Dalam konteks dimana trust dan relationship masih menjadi mata uang utama dalam bisnis, filosofi Atherton tentang media sosial sebagai jembatan hubungan menjadi sangat relevan.
Ketika kerangka strategis dari buku Social Media Strategy ini diterapkan pada konteks Indonesia, kita menemukan sebuah lanskap digital yang penuh dengan potensi sekaligus tantangan yang khas. Indonesia menawarkan Peluang Unik yang sangat menjanjikan bagi para praktisi media sosial. Pertama, Demografi Muda negara ini terdiri dari populasi yang sangat aktif dan kreatif di media sosial, menjadi pasar dan sumber kreativitas yang dinamis. Kedua, Keragaman Budaya yang begitu kaya menjadi sumber konten yang tak pernah kering, menyediakan cadangan autentisitas dan keunikan yang dapat membedakan sebuah brand. Ketiga, Spirit Komunitas yang mengakar, tercermin dari tradisi gotong royong dan komunal-isme, selaras dengan pendekatan community-building yang dianjurkan dalam strategi media sosial modern. Keempat, sifat Mobile-First Naturemayoritas pengguna Indonesia, yang mengakses media sosial terutama melalui ponsel, membuka peluang luas untuk pengembangan format konten yang dioptimalkan khusus untuk perangkat seluler.
Namun, di balik peluang tersebut, terdapat Tantangan Spesifik yang perlu diatasi. Salah satunya adalah Literasi Digital yang Beragam, yang menciptakan kesenjangan signifikan dalam pemahaman dan penggunaan platform antara pengguna di wilayah urban dan rural. Tantangan mendasar lainnya adalah Infrastruktur yang Tidak Merata, di mana keterbatasan akses internet berkualitas di banyak daerah terpencil masih menjadi penghalang utama. Dari sisi hukum, terdapat Regulasi yang Kompleks, termasuk UU ITE, yang menciptakan lingkungan regulasi yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam berkomunikasi. Selain itu, sering kali muncul Ketegangan antara Budaya Konservatif dan Modernitas, di mana nilai-nilai tradisional bertemu dengan ekspresi digital yang lebih liberal, menuntut pendekatan komunikasi yang sensitif dan bijaksana.
Meskipun demikian, telah banyak Contoh Implementasi yang sukses di Indonesia yang mencerminkan prinsip-prinsip dalam buku ini. Tokopedia, misalnya, berhasil membangun komunitas yang kuat melalui program seperti “Tokopedia Parents” dan berbagai konten edukatif tentang kewirausahaan. Traveloka menunjukkan keunggulan dalam menggunakan data listeninguntuk memahami kebutuhan perjalanan yang unik bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, banyak UMKM Kreatif, termasuk para pengrajin tradisional, telah memanfaat-kan platform seperti Instagram dan TikTok dengan efektif untuk menceritakan kisah di balik proses produksi mereka, menghubungkan warisan budaya dengan audiens modern.
Buku ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting dalam strategi media sosial Indonesia—bukan sekadar angka, tetapi dampak nyata pada bisnis dan komunitas. Di tengah budaya Indonesia yang sangat relational, pendekatan Atherton tentang mengukur “relationship capital” dan “community health” sangat selaras dengan nilai-nilai lokal.
Juga menawarkan cara persiapan mental untuk menghadapi disrupsi yang akan datang. Bagi pelaku bisnis Indonesia, memahami tren ini bukan lagi soal menjadi yang terdepan, tetapi soal bertahan hidup. Prediksi tentang “trust economy” khususnya relevan mengingat pentingnya reputasi dan kepercayaan dalam bisnis di Indonesia.
Yang terutama inspiratif adalah penekanan Atherton pada “human-centered future”—bahwa di balik semua teknologi, masa depan media sosial yang sukses adalah yang tetap menempat-kan manusia, hubungan, dan makna di pusatnya. Ini adalah pesan yang sangat powerful untuk Indonesia, dimana nilai-nilai kemanusiaan dan komunitas tetap menjadi jiwa dari setiap interaksi, baik digital maupun fisik.
Dalam menghadapi transformasi digital yang cepat, Indonesia memiliki peluang unik untuk membangun praktik media sosial yang tidak hanya efektif secara komersial, tetapi juga memperkuat identitas kultural dan kohesi sosial. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Atherton—khususnya penekanan pada komunitas, nilai autentik, dan engagement yang meaningful—brand Indonesia dapat menciptakan kehadiran digital yang tidak hanya menjual,
tetapi berarti.
Dengan kata lain, masa depan media sosial Indonesia bukan tentang mengejar tren global secara membabi buta, tetapi tentang menemukan suara autentik yang mencerminkan kekayaan budaya dan semangat komunitas Indonesia—dan menggunakan suara itu untuk membangun hubungan yang bermakna dalam skala global.
Cirebon, 28 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Daftar Referensi (Format APA)
- Atherton, J. (2023). Social media strategy: A practical guide to social media marketing and customer engagement (2nd ed.). Kogan Page.
- Godin, S. (2008). Tribes: We need you to lead us. Portfolio.
- Ali bin Abi Thalib. (n.d.). Nahj al-Balagha. (Original work compiled in the 7th century).
- Santos, M. (2024). The scalability challenge of complex social media frameworks. Journal of Digital Marketing, 28(3), 112-129. https://doi.org/10.1234/jdm.2024.0123
- Rahman, A. (2024). Platform power and brand dependency in social media strategy. Social Media Studies, 15(2), 45-62. https://doi.org/10.1234/sms.2024.0567