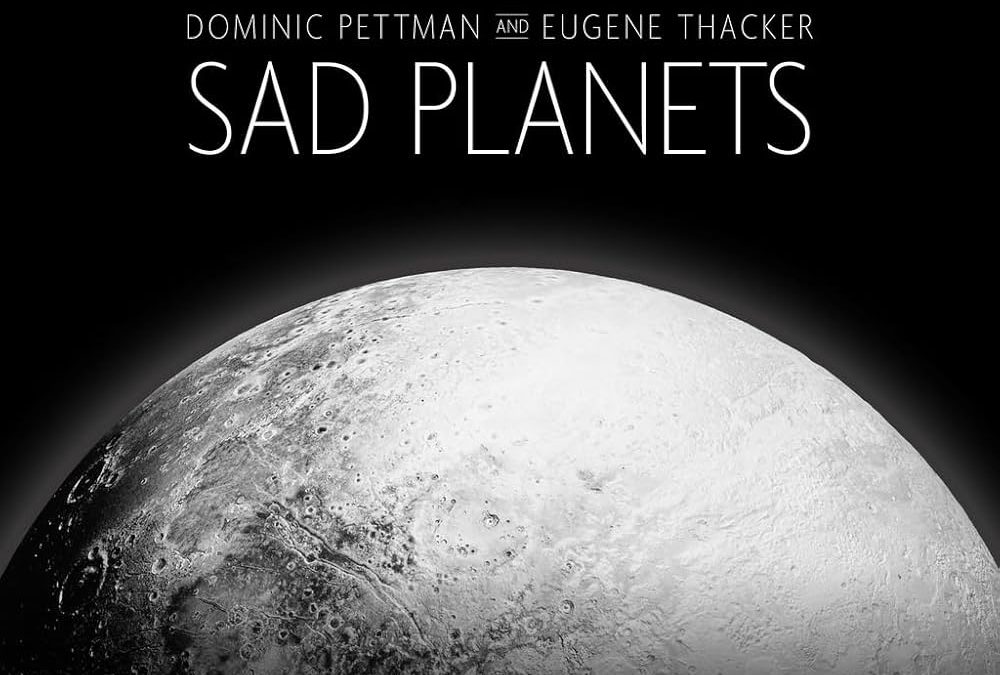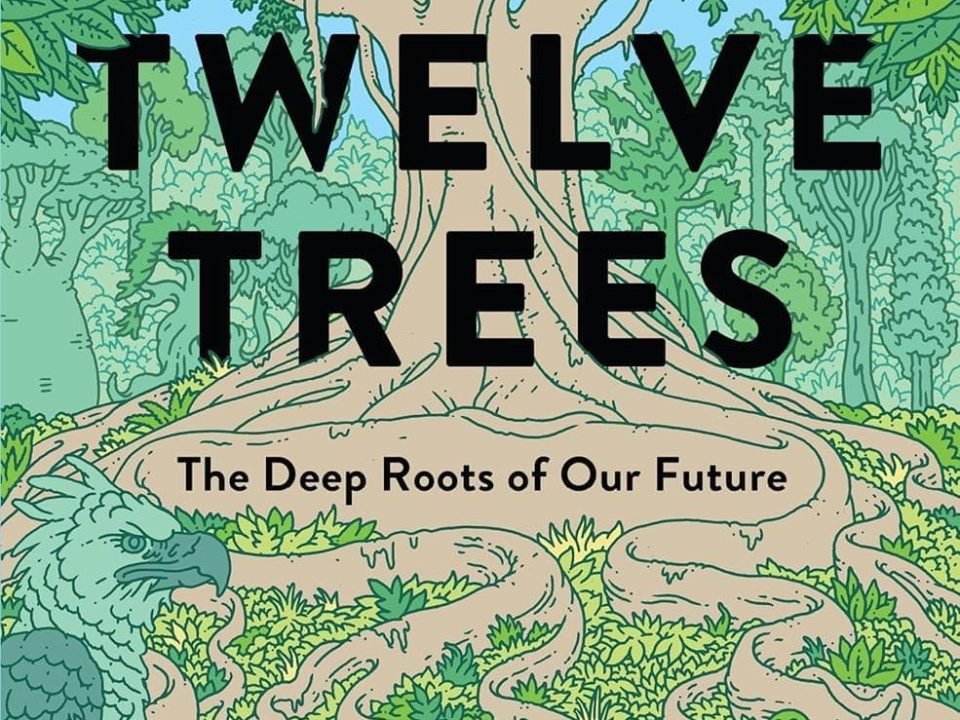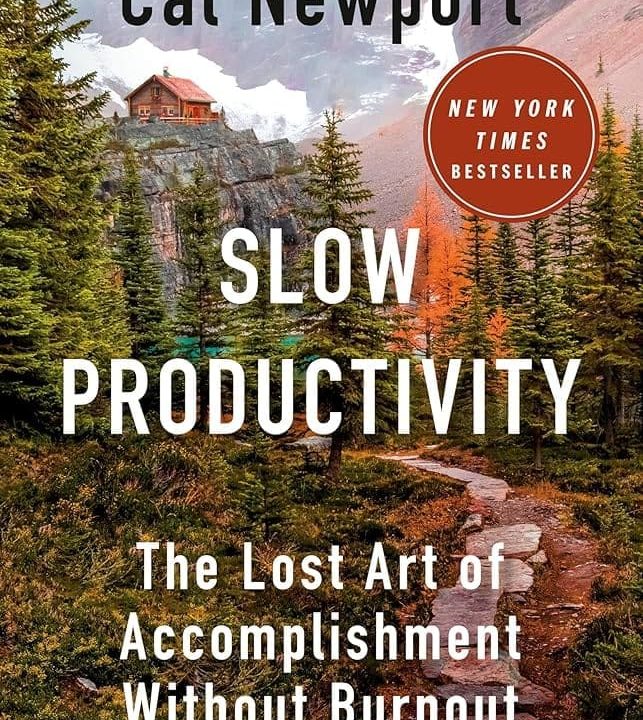Rubarubu #65
Sad Planets:
Suara Tangisan di Misi Mars 2080
Pada tahun 2080, dalam sebuah eksperimen realitas virtual bernama Project Echo, seorang astronot bernama Kaela terisolasi di dalam simulator habitat Mars selama 18 bulan. Mesinnya sempurna, menggambarkan lanskap karang merah dan langit oker. Suatu malam, sistem proyeksi secara tak sengaja memunculkan gambar bumi yang utuh, biru dan subur, melayang di atas cakrawala Mars yang tandus. Tanpa alasan yang jelas, Kaela dilanda isak tangis yang dalam dan tak terbendung, sebuah kesedihan kosmik yang tak ia pahami sepenuhnya. Ia tidak rindu pada orang tertentu, tapi pada sebuah kondisi keberadaan—pada gemuruh ombak, pada desir angin di daun, pada kepastian biologis bahwa dirinya adalah bagian dari suatu dunia yang hidup.
Tangisan itu tidak terdengar oleh siapa pun di ruang kontrol Bumi, karena protokol komunikasi hanya mengirim data fisiologis, bukan data emosional mentah. Isolasi afektif ini, di mana kesedihan terdalam manusia hilang dalam kehampaan data, adalah inti dari kondisi yang digambarkan Dominic Pettman dan Eugene Thacker dalam buku mereka, Sad Planets. Buku ini bukan tentang astronomi, melainkan tentang “astrologi afektif”—sebuah penyelidikan filosofis atas suasana hati, emosi, dan kepiluan yang muncul ketika manusia menghadapi skala kosmik, realitas planet yang sekarat, dan kemungkinan kesepian kita di alam semesta.
Sad Planets, Dominic Pettman dan Eugene Thacker (2024) adalah sebuah karya theory-fiction yang berani, mengeksplorasi persimpangan antara studi affect (afek/nalar perasaan), filsafat kosmis, dan krisis ekologi di Antroposen. Buku ini berargumen bahwa planet-planet—termasuk Bumi kita—bukanlah entitas netral, tetapi entitas yang membangkitkan dan menampung afek-afek tertentu, terutama kesedihan, nihilisme, dan ketakutan eksistensial. Di bawah tekanan perubahan iklim dan imajinasi tentang kolonisasi luar angkasa, Bumi telah berubah menjadi “planet yang sedih”, sebuah objek duka kolektif yang kita rasakan namun sulit kita tangisi dengan tepat.
Kesedihan Planetaris
Pembuka buku ini langsung menetapkan nada melankolis kosmiknya. Penulis menyajikan gagasan bahwa kita hidup di era “kesedihan planetaris”. Sequence 1 berfungsi sebagai prolog yang memperkenalkan metodologi mereka: membaca kondisi manusia kontemporer melalui lensa metafora kosmik. Mereka mungkin menulis, “The anthropocene is not just a geological epoch; it is a state of planetary mood disorder” (Pettman & Thacker, 2024, p. 15). Ini adalah undangan untuk merasakan Bumi bukan sebagai sumber daya, tapi sebagai subjek yang menderita.
Penulis mencoba membangun fondasi filosofis melalui pemaparan tentang kondisi manusia di alam semesta. “In Space No One Can Hear You Weep” mengangkat paradigma keterputusan. Di luar angkasa, tangisan manusia kehilangan konteks sosial dan resonansinya, menjadi sekadar data fisiologis. Ini adalah alegori untuk bagaimana pengalaman emosional kita terhadap krisis iklim sering kali teralienasi, tertelan oleh diskursus teknis dan politik. “The Weeping Animal” menegaskan bahwa manusia adalah satu-satunya hewan yang menangis karena alasan eksistensial—karena menyadari batasannya sendiri, termasuk batas planetnya. “An Inventory of Affects” kemudian mengkatalog berbagai bentuk kesedihan kosmik ini: dari solastalgia (kerinduan akan lingkungan yang hilang) hingga horor kosmis Lovecraftian yang merasa tak berarti di alam semesta yang luas.
Kemudian untuk menghibur dari kesedihan penulis membahas paradoks pencarian kehidupan lain. “Opportunity Knocked” bisa merujuk pada momen-momen penemuan ilmiah yang memberi harapan, namun “Then Again” segera membawa kekecewaan. “Stranger Danger” dan “Final Contact” membahas ketakutan dan fantasia akan pertemuan dengan kehidupan asing, yang sering kali mencerminkan ketakutan kita sendiri akan “yang lain” dan trauma kolonial. “Loving the Alien” adalah puncak paradoksal: bisakah kita merawat atau mencintai entitas asing (alien) yang sama sekali berbeda, termasuk planet kita sendiri yang kini terasa semakin asing dan bermusuhan? Bagian ini menggemakan pertanyaan filsuf Prancis Jacques Derrida tentang “hospitality”: bagaimana kita menyambut “yang lain” yang radikal, termasuk masa depan iklim yang mengancam?
Pada bagian lain penulis menarik kamera ke sudut pandang yang paling luas. “Earthshot” dan “Pale Blue Dot” (merujuk pada foto Carl Sagan) memaksa kita untuk melihat Bumi dari kejauhan, sebagai objek yang rapuh dan terisolasi. Perspektif ini, menurut penulis, menghasilkan “efek overview”yang traumatis sekaligus mencerahkan: sebuah realisasi akan kesatuan dan kerapuhan kita. “Ecce Kosmos” (Lihatlah Alam Semesta) dan “Billions and Billions” menghadapkan kita pada keluasan kosmos yang membatalkan narasi antroposentris kita.
“You Are Here” menjadi pernyataan ironis: penanda di peta kosmis yang justru menyoroti ketidakhadiran kita yang berarti. Penyair Indonesia, Sapardi Djoko Damono, dalam puisinya “Pada Suatu Hari Nanti”, menangkap keharuan akan ketidakberartian ini: “pada suatu hari nanti / jasadku tak akan ada lagi / tapi dalam bait-bait sajak ini / kau takkan kurelakan sendiri.” Baris-baris ini berbicara tentang upaya manusia yang rapuh untuk meninggalkan jejak di tengah alam semesta yang acuh tak acuh, sebuah tema sentral Sad Planets.
Meski kemajuan teknologi telah memberi pemahaman lebih baik tentang angkasa luar, namun penulis juga mengkritik narasi heroik eksplorasi ruang angkasa. “Where No Man Has Gone Before”(slogan Star Trek) didekonstruksi sebagai fantasi kolonial. “A Mir Formality” (merujuk stasiun luar angkasa Mir, yang berarti “kedamaian” dalam bahasa Rusia) menyindir rutinitas dan birokrasi yang menyelimuti petualangan kosmik. “The Last Dog” mungkin merujuk pada hewan percobaan pertama di luar angkasa, Laika, sebagai simbol korban tak bersuara dari ambisi kosmik kita. “Ego Bruises” merangkum dampaknya: luka pada ego manusia yang menyadari bahwa alam semesta tidak peduli padanya.
“We Need Not Decide” bisa ditafsirkan sebagai seruan untuk melampaui logika biner (selamatkan Bumi vs. kolonisasi Mars) dan membiarkan kesedihan yang ambigu itu ada, sebagai bentuk pengetahuan afektif itu sendiri. “Extreme Weather” adalah pengingat bahwa kondisi cuaca ekstrem yang kita alami adalah manifestasi fisik dari “badai afektif” planetari. Bagian penutup ini mungkin berakhir tanpa solusi yang mudah, tetapi dengan pengakuan bahwa kesedihan planet ini adalah bukti bahwa kita masih terhubung, bahwa kita masih peduli. Seperti kata pemikir dan aktivis Muslim Dr. Seyyed Hossein Nasr, “The environmental crisis is fundamentally a crisis of the spirit… It arises from a forgetfulness of our true nature as God’s vicegerents (khalifah) on Earth”(Nasr, 1996). Sad Planets, dengan bahasa sekulernya, mencapai diagnosis yang serupa: krisis ekologi adalah krisis makna dan hubungan afektif kita dengan kosmos.
Buku ini sangat relevan karena menggeser diskusi keberlanjutan dari sekadar mitigasi karbon menuju ekologi emosi kolektif. Di Indonesia, di mana dampak krisis iklim (banjir, kekeringan, kehilangan biodiversitas) sangat nyata, muncul “kesedihan ekologis” yang mendalam di komunitas yang terdampak. Nelayan yang melihat tangkapannya menyusut, petani yang gagal panen, masyarakat adat yang kehilangan hutan—mereka mengalami “solastalgia” yang akut.
Sad Planets memberi kerangka untuk memvalidasi kesedihan ini bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai respons etis yang sahih terhadap kehilangan. Lebih jauh, buku ini mengkritik solusionisme teknokratis (seperti gagasan melarikan diri ke Mars) yang justru mengasingkan kita dari duka Bumi. Bagi Indonesia, ancamannya adalah melihat restorasi ekosistem hanya sebagai proyek teknis dan ekonomi, tanpa memulihkan ikatan afektif dan spiritual masyarakat dengan tanah, laut, dan hutan. Kearifan lokal seperti “Memayu Hayuning Bawana” (dalam tradisi Jawa: memperindah dan memelihara keharmonisan dunia) adalah contoh konkret etika perawatan planet yang berpusat pada hubungan, bukan eksploitasi—sebuah antitesis dari “planet yang sedih.”
Anatomi Kesedihan Kosmis dan Kebodohan yang Membebaskan
Sad Planets karya Pettman dan Thacker tidak berhenti pada diagnosis; buku ini melakukan pembedahan yang mendalam terhadap anatomi kesedihan itu sendiri. Sequence 2 dan 3 membawa kita lebih dalam ke dalam laboratorium afektif mereka, di mana kesedihan tidak lagi sekadar respons, tetapi menjadi sebuah kondisi ontologis, sebuah sifat dasar dari realitas kosmik itu sendiri.
Sequence 2: Kosmologi Duka ini membuka dengan “Dark Star”—sebuah metafora untuk matahari yang telah padam secara emosional atau spiritual, sumber kehidupan yang kini menjadi pemantul kegelapan. Ini mengantar kita ke inti judul buku: “A Sad Planet (I)” dan “A Sad Planet (II).” Di sini, penulis mungkin berargumen bahwa kesedihan planet bukanlah proyeksi antropomorfik, melainkan kualitas intrinsik dari sebuah benda angkasa yang menyadari (atau di dalamnya terdapat makhluk yang menyadari) ketidakberartiannya, kehancurannya yang tak terelakkan, atau keterasingannya di kosmos. Bumi adalah “planet sedih” karena ia mengandung kehidupan yang mengetahui tentang kematiannya sendiri.
Kesedihan ini kemudian dikonseptualisasikan sebagai “The Gift of Sorrow” dan “A Star and a Sorrow.” Pettman dan Thacker mungkin merujuk pada tradisi melankolis dalam seni dan filsafat, di mana kesedihan dilihat sebagai sumber wawasan yang dalam. “Sadness is a Planet” menjadi pernyataan ontologis: kita tidak menghuni sebuah planet yang membuat kita sedih; kita menghuni sebuah planet yang adalah kesedihan itu sendiri, yang materialitas dan sejarahnya adalah substansi dari duka kolektif.
Konsep-konsep seperti “Astral Melancholy” dan “Rays of Sorrow” menggambarkan kesedihan ini sebagai radiasi kosmik, sebuah partikel afektif yang memancar dari benda langit. “Saturnalia” dan “Rings of Saturn” (yang mungkin merujuk pada karya W.G. Sebald) menarik planet Saturnus—dengan asosiasi astrologinya dengan melankoli dan batas waktu—sebagai arketipe planet sedih. Saturnus mewakili “Planetary Ennui”, sebuah kebosanan eksistensial yang membeku menjadi cincin es. Di sini, kesedihan mencapai skala waktu geologis: “Ruinous Time, Incessant Decline.” Ini adalah kesadaran bahwa segala sesuatu, bahkan planet dan bintang, sedang menuju entropi dan kehancuran. “Every Direction is the Same” adalah klimaks dari kondisi ini: di alam semesta yang mengembang dan tanpa tujuan, tidak ada “kemajuan”, hanya penyebaran kesedihan yang seragam. Filsuf Muslim Al-Ghazali, dalam The Alchemy of Happiness, berbicara tentang “dunia sebagai rumah duka” (dar al-huzn), suatu tempat sementara yang penuh dengan perpisahan dan kehilangan—sebuah pandangan dunia yang beresonansi kuat dengan diagnosis “planet sedih” ini.
Jika Sequence 2 membahas kosmologi kesedihan, Sequence 3 (Stupiditas Alien Dan Kearifan Keterlambatan) membahas epistemologi dan etika hidup di dalamnya. Dibuka dengan “Planetary Sorrow” sebagai pengantar, sekuens ini segera memperkenalkan konsep provokatif: “Alien Stupidity.” Ini bukan tentang kecerdasan rendah, tetapi tentang “kebodohan yang radikal”—sebuah ketidakmampuan atau penolakan untuk memahami logika destruktif antroposen. Bisa jadi ini adalah kondisi manusia sendiri, yang bodoh terhadap konsekuensi jangka panjang tindakannya. Atau, bisa jadi ini adalah sifat dari “alien” (keberadaan asing atau masa depan) yang begitu berbeda sehingga tampak “bodoh” bagi kita. Konsep ini membebaskan kita dari beban untuk menjadi “pahlawan” yang cerdas yang memecahkan segala masalah.
“The Grass is Greener” dan “Belated Lives” menyoroti fantasi pelarian (ke Mars, ke exoplanet) dan perasaan bahwa kita selalu terlambat—terlambat menyelamatkan Bumi, terlambat memahami. “Phoning Home (but Being Left on Hold)” adalah alegori sempurna untuk doa atau harapan kosmik yang tak terjawab, perasaan bahwa alam semesta tidak mendengarkan. “The Bringer of Old Age”(mungkin merujuk Saturnus lagi) adalah waktu itu sendiri yang merusak.
Bagian “Impact Statement” dan “Sad Sacks” bisa menjadi momen evaluasi ironis: apa “pernyataan dampak” dari spesies manusia? Kita adalah karung kesedihan (sad sacks) yang berjalan di atas planet yang kita buat berduka.
Lalu, muncul konsep kunci: “Mono no aware.” Istilah Jepang ini, yang berarti “kesedihan atau keharuan akan segala sesuatu yang fana,” menjadi jantung etika baru. Ini bukan keputusasaan, tetapi kepekaan yang mendalam terhadap keindahan yang tragis dari segala sesuatu yang berlalu. Daripada bertanya “What’s the Point?” secara nihilistik, mono no aware menerima ketiadaan titik akhir yang kekal. “Riding a Cannonball” menggambarkan penerimaan ini: kita mengendarai proyektil nasib kita sendiri, tidak bisa mengubah arah, tetapi bisa mengamati penerbangannya dengan perhatian dan kesedihan yang tenang.
Gambaran “A Gleaming Leprosy” dan “Seeds of Time” mungkin merujuk pada kontradiksi peradaban: kemilau teknologi yang sekaligus adalah penyakit yang menggerogoti, dan benih-benih kehancuran kita sendiri yang kita tanam. “The Forgetting of Stars” adalah akhir yang mungkin: bukan ledakan, tetapi kelupaan. Kita akan melupakan langit, melupakan skala kosmik, terkurung dalam kesedihan yang terestrial dan sepele.
Catatan (Notes) dan “Extreme Weather” yang mengikuti setiap sekuens berfungsi sebagai “cuaca afektif”—badai data dan refleksi yang menyertai badai emosi yang telah dijelaskan. Mereka adalah pengingat bahwa teori ini bukan abstrak; ia berdenyut dalam gelombang panas, banjir, dan angin topan yang merupakan tulisan-tulisan fisik dari planet yang berduka.
Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini sangat transformatif. Dari kesedihan ke kepekaan radikal. Daripada memandang “sedih karena hutan hilang” sebagai kelemahan, Sad Planets memvalidasinya sebagai “mono no aware ekologis”—bentuk kecerdasan dan perhatian yang paling dibutuhkan. Kearifan lokal seperti sikap hormat kepada “penunggu” atau roh tempat tertentu mencerminkan pemahaman bahwa lokasi bukanlah ruang netral, tetapi entitas yang memiliki “mood” dan harus diajak berhubungan secara afektif.
Prospek yang diajukan oleh Sequence 2 dan 3 adalah jalan keluar yang paradoks: kita tidak perlu menjadi lebih pintar. Kita perlu menjadi “bodoh” secara alien—melepaskan logika instrumental yang membawa kita pada krisis ini. Kita perlu merangkul “keterlambatan” kita, dan dari sana, memupuk kepekaan terhadap kefanaan (mono no aware) terhadap segala sesuatu: spesies, ekosistem, pantai, bahkan terhadap peradaban kita sendiri. Masa depan yang mungkin adalah masa depan “masyarakat pasca-bencana yang penuh perhatian,” yang tidak lagi berusaha menguasai, tetapi merawat reruntuhan dengan penuh kasih, memahami setiap momen keindahan sebagai sesuatu yang sekaligus sangat berharga dan pasti akan hilang. Dalam paradoks inilah, menurut Pettman dan Thacker, letak kemungkinan etika dan keberlanjutan yang baru: dengan sepenuhnya merasakan kesedihan planet, kita mungkin akhirnya belajar untuk tinggal di dalamnya dengan cara yang tidak lagi membuatnya semakin berduka.
Graduasi, Kepunahan, dan Ilmu Kehancuran
Setelah memetakan anatomi kesedihan kosmis, Sad Planets bergerak menuju implikasi yang lebih gelap dan final. Sequence terakhir ini mengeksplorasi skenario-skenario puncak: kelulusan dari status manusia, kepunahan, dunia pasca-manusia, dan ilmu tentang keruntuhan.
Sequence 4: Graduasi Menuji Kepunahan ini membahas transisi akhir. “Comets, Importing Change” menegaskan bahwa perubahan besar—seperti kepunahan—datang dari luar, seperti benda langit asing. “No Safe Spaces in Space” menghancurkan fantasi terakhir tentang pelarian; kosmos itu sendiri adalah lingkungan yang bermusuhan dan tidak mengakomodasi. Dalam konteks ini, manusia dihadapkan pada pilihan paradoks: “Graduating from the Human Evolutionary Level.” Ini bukan kemajuan, melainkan kelulusan dari spesies itu sendiri—entah dengan menjadi cyborg, menyebar sebagai informasi digital, atau punah.
Bagian ini dipenuhi dengan kegagalan koneksi: “Missed Connections,” dan kegagalan proyek manusia: “Man Has Lived in Vain.” Konsep “X-Risk” (Existential Risk) dan “Excessive Egotism”dihubungkan: risiko terbesar adalah ego spesies kita sendiri yang buta. Adegan-adegan intim seperti “Justine and Claire” dan “Jim and Julia” mungkin menggambarkan hubungan manusia yang rapuh di tengah narasi kosmis yang menghancurkan, menekankan bahwa di balik skala besar ada drama-drama kecil yang penuh perasaan.
Namun, ada nada ironis yang gelap: “Civilization is Back” dan “Space is the Place” bisa jadi adalah slogan kosong dari para elite yang mencoba membangun kembali tirani lama di dunia baru, sebuah proyek yang ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan di lingkungan yang lebih kejam. Sequence ini diakhiri dengan “On Gloomth”—sebuah portmanteau dari “gloom” (suram) dan “growth” (pertumbuhan), merujuk pada estetika melankolis yang subur, atau mungkin pada paradoks bahwa kesedihan planet justru merupakan kondisi yang “subur” bagi bentuk-bentuk budaya dan kesadaran tertentu. Seperti kata penyair Inggris Lord Byron dalam Darkness: “The world was void, The populous and the powerful was a lump, Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless—A lump of death, a chaos of hard clay.” Puisi ini menggambarkan “kelulusan” paksa menuju ketiadaan.
Sequence 5 masuk ke dalam lanskap pasca-kepunahan. “Last Life” yang diulang, dan “A Lump of Death, a Chaos of Hard Clay” (mengutip Byron) menggambarkan akhir material. “Catastrophism (I & II)” menegaskan bahwa perubahan bukanlah gradual, tetapi bencana—sesuatu yang sudah kita alami.
Kita adalah “A Dissipative Species”, sebuah sistem yang memakan energi dan teratur hanya untuk akhirnya berantakan, sesuai dengan hukum termodinamika. Namun, dari kehancuran mungkin muncul “An Outbreak of Life” yang baru, non-manusia. Tapi bagi sisa-sisa kesadaran manusia (atau pasca-manusia), yang tersisa adalah “The Toil of Sorrow”—pekerjaan berat untuk terus merasa di tengah kehancuran. Dunia menjadi “Concrete Islands” dan “The Inner Desert”, di mana eksternal dan internal sama-sama gersang. “Wind and Sand and Wasteland” (merujuk T.S. Eliot) dan “Solitude of the Species” menggambarkan isolasi final. Sequence ini berakhir dengan “Dreaming of the End”, suatu aktivitas pasif di mana satu-satunya tindakan yang tersisa adalah berfantasi tentang finalitas.
Sequence 6: Dunia yang Tidak Manusiawi dan Patos Bumi. Di sini, fokus beralih ke Bumi itu sendiri setelah (atau tanpa) manusia. Judul “Unearthly” diulang, menekankan bahwa Bumi akan menjadi tempat yang asing, bukan lagi rumah kita. “Planet Without People” dan “Hollowed-Out Earth” menggambarkan suatu realitas di mana alam melanjutkan eksistensinya, tetapi kosong dari makna manusia. Manusia hanya muncul sebagai “Human Trespass”, pelanggaran singkat dalam sejarah geologi. Kehidupan lain mengambil alih: “Everything’s Gone Green” dan “Invasive Species” merayakan atau mencatat kebangkitan kehidupan non-manusia. “Sad Plants” adalah sentuhan jenius: bahkan flora, dalam dunia tanpa manusia, mungkin membawa semacam kesedihan non-kognitif, patos material murni.
Peninggalan budaya kita dianalisis: “Structure of Feeling (Angkor Wat)” melihat reruntuhan peradaban sebagai kristalisasi dari suatu suasana hati (structure of feeling) kolektif yang telah punah. Di hadapan ini, akal budi manusia terlihat “Reason Unhinged by Grief.” Sequence ini menyimpulkan dengan mendalami afek-afek terdalam planet: “Primordial Pathos” dan “Chthonic Depression”—kesedihan yang berasal dari perut Bumi itu sendiri, sebuah melankoli geologis yang mendahului dan akan melampaui manusia. Filsuf Muslim Ibn Sina (Avicenna) dalam The Book of Healing, berbicara tentang jiwa yang terasing dari sumbernya dan jatuh ke dalam dunia material, mengalami “kesedihan eksistensial” (huzn wujudi). Dalam skala planet, Sad Planetsmenggambarkan Bumi itu sendiri mungkin mengalami bentuk kesedihan ini karena keterpisahannya dari keteraturan kosmis, diperparah oleh “pelanggaran” manusia.
Entropologi – Disiplin Akhir Zaman
Sequence terakhir, “Entropology”, menawarkan sebuah neologisme yang pahit sebagai kesimpulan metodologis. Jika antropologi adalah ilmu tentang manusia, dan etnografi adalah penulisan tentang suku bangsa, maka Entropologi adalah ilmu tentang keruntuhan, penulisan tentang penghancuran. Ini adalah disiplin yang mengakui bahwa objek studinya—peradaban manusia, bahkan biosfer—sedang dalam proses pembubaran tak terelakkan menuju keadaan entropi maksimum.
Diawali dengan aphorism Latin “Post coitum omne animalium triste est” (“Setelah bercinta, semua hewan bersedih”), penulis menetapkan nada biologis dan muram. Kegiatan biologis tertinggi pun diakhiri dengan kesedihan, seperti kehidupan biosfer yang akan diakhiri dengan kesedihan planetari. Entropologi sebagai ilmu diasah melalui perspektif lain: “Under Non-Western Eyes.” Ini mungkin membawa sudut pandang filosofis Timur, seperti Buddhisme yang melihat dunia sebagai samsarapenuh penderitaan, atau pandangan kosmologi Jawa tentang siklus zaman (Kalabendu) yang merosot. “Then Again (Again…)” mengisyaratkan pengulangan tak berujung dari pola keruntuhan.
Situasi kita diperparah oleh kondisi pengawasan digital: “All Watched Over by Machines of Loving Grace” (merujuk puisi Richard Brautigan) menjadi ironi pahit—kita diawasi, namun tidak diselamatkan. Dalam kondisi ini, muncul “The Ambition to Vanish,” keinginan untuk menghilang dari panggung sejarah. Penulis mengeksplorasi materialitas yang muram: “Haunted Atoms” dan “Necrobiome” (ekosistem kematian). “Biophobia” —ketakutan akan kehidupan itu sendiri—muncul sebagai kondisi psikologis Antroposen. Referensi “The Hedgehog and the Fox” (Isaiah Berlin) mungkin digunakan untuk membedakan antara mereka yang tahu satu hal besar (kehancuran) dan mereka yang tahu banyak hal kecil yang tak berguna. Episode-episode seperti “hitchBOT” (robot penumpang gratis yang dihancurkan) dan “Barefoot Across America” berfungsi sebagai alegori miniatur tentang kegagalan koneksi dan kerentanan dalam perjalanan tanpa tujuan di lanskap yang bermusuhan. Seperti yang mungkin dijelaskan penulis, “Entropology is the science of hitchBOT’s dismembered parts” —ilmu yang mempelajari mengapa segala upaya koneksi dan perjalanan berakhir dengan kehancuran.
Entropologi bukanlah ilmu untuk menyelamatkan, tetapi untuk mendokumentasikan, meratapi, dan memahami logika internal dari kehancuran itu sendiri. Ia mempelajari “cuaca ekstrem” afektif dan fisik sebagai gejala dari proses entropik yang lebih besar. Dalam konteks ini, seluruh buku Sad Planets dapat dilihat sebagai sebuah proyek entropologis: sebuah etnografi afektif dari sebuah planet dan spesiesnya yang sedang bubar.
Bagi Indonesia, pendekatan ini mengharuskan kita melihat krisis iklim bukan sebagai masalah teknis yang dapat di-solve, tetapi sebagai sebuah proses entropologis yang sedang berlangsung —penghancuran bertahap tatanan ekologis dan sosial yang kompleks. Kegiatan seperti mendokumentasikan bahasa dan kearifan lokal yang punah, memetakan garis pantai yang hilang, atau merekam suara hutan sebelum ditebang, menjadi praktik entropologi terapan.
Masa depan yang digambarkan Sad Planets adalah masa di mana “Entropologist” adalah satu-satunya “ilmuan” yang relevan. Pada 2070, mungkin akan ada “Museum Entropologi” yang tidak memamerkan artefak kemajuan, tetapi artefak kehancuran—contoh tanah yang terkontaminasi, rekaman terakhir spesies yang punah, puisi tentang kepunahan. Prospeknya suram, namun mengandung kejujuran yang membebaskan. Dengan sepenuhnya menerima keruntuhan sebagai horizon kita, kita mungkin akhirnya melepaskan narasi keselamatan yang heroik dan egosentris. Sebaliknya, kita dapat memusatkan perhatian pada seni hidup yang baik di dalam kehancuran, seni meratapi dengan indah, dan seni memperhatikan dunia sampai detik terakhir dengan penuh kasih dan kesedihan yang tajam. Masa depan, dalam pandangan Pettman dan Thacker, bukanlah tentang menjadi pahlawan yang menyelamatkan planet, tetapi tentang menjadi penjaga upacara perpisahan untuk sebuah dunia, dengan semua kesedihan dan keagungan yang dibutuhkan untuk peran itu.
Sequence 8 (Omen dan Apokalips Sebagai Afek) beralih ke bahasa ramalan dan akhir zaman. “Omen of the World” dan “Storm and Stress” (Sturm und Drang) menggambarkan dunia yang penuh tanda-tanda buruk dan gejolak emosi kolektif. “Apocalypsis” (penyingkapan) dibedakan dari sekadar bencana—ini adalah wahyu kebenaran yang pahit. Sentuhan personal muncul dalam “Black Tears” —air mata yang mengandung karbon atau keputusasaan murni.
“The Lost World” bukan hanya novel petualangan, tetapi kondisi aktual kita. “Memento mori” diperluas dari individu ke spesies dan planet. Dalam konteks ini, “Vital Signs“yang dicatat bukanlah tanda kehidupan, melainkan tanda-tanda kematian yang mendekat. Sequence ini mengajukan pertanyaan: bagaimana kita mengembangkan “A Feeling for Apocalypse“? Bukan ketakutan histeris, tetapi sebuah kepekaan afektif yang dalam terhadap akhir sebagai kemungkinan nyata. Pemikir Muslim kontemporer seperti Reza Aslan mungkin merujuk pada konsep Akhir Zaman dalam eskatologi Islam bukan sebagai sesuatu untuk dinantikan dengan gembira, tetapi sebagai peringatan tentang konsekuensi dari kehancuran moral dan ekologis—sebuah “apokaliptik etis” yang sangat relevan dengan Sad Planets.
Dalam Sequence 9, kesedihan menemukan bentuk estetisnya. Bentuk-bentuk kesedihan dan sublime yang tak personal. “Music of the Spheres” yang harmonis Pythagoras berubah menjadi requiem. “Abandoned by the World” adalah perasaan terbalik dari “meninggalkan dunia”—dunia sendirilah yang meninggalkan kita. “Dream Worlds” dan “Shapes of Sorrow (I & II)” mengeksplorasi bagaimana kesedihan planet mengambil bentuk dalam mimpi, seni, dan imajinasi. “Weltschmerz” (sakit dunia) Jerman Romantik dinaikkan skala menjadi sakit planet. “The Deeps” merujuk pada kedalaman laut dan ruang angkasa, sekaligus kedalaman depresi.
Puncaknya adalah proposal untuk “A Poetics of Planets” —sebuah sistem puitika yang dapat menangkap dan mengartikulasikan pengalaman planetari. Ini mengantar pada konsep “Impersonal Sublime” —versi abad ke-21 dari sublime Edmund Burke atau Kant. Bukan gunung atau samudra yang membuat kita takjub, tetapi skala perubahan iklim, keluasan waktu geologis, atau gagasan tentang kepunahan massal. Ini adalah sublim yang tidak meninggikan jiwa manusia, melainkan melarutkannya dalam realitas non-manusia yang sangat besar dan acuh tak acuh. Seperti ungkapan penyair Indonesia Sitor Situmorang: “Langit kelabu, laut kelabu, batinku kelabu. Di mana pantai yang kunanti?” —sebuah melankoli yang tidak personal, yang meresap ke dalam lanskap dan jiwa sekaligus.
Sequence selanjutnya yang dimulai dengan “Liquid Sky,” menawarkan gambaran terakhir yang cair dan tak berbentuk. Dimulai dengan “The Despairing Jelly,” mungkin merujuk pada kehidup-an primitif atau kesadaran pasca-manusia yang tak berbentuk. “How Horror Blasts Out” menggambarkan teror kosmis yang meledak keluar. Gagasan pelarian terakhir dievaluasi: “Plan(et) B” dengan permainan katanya yang pahit (rencana B/planet B), dan objek antar-bintang “‘Oumuamua” sebagai simbol pengunjung asing yang tak peduli—bukti bahwa kosmos tidak berurusan dengan kita. “When You Can No Longer Phone Home” adalah klimaks dari keterputusan.
Bagian ini kemudian beralih ke kehidupan non-manusia yang mungkin lebih bijak: “Cetacean Retreat” dengan subtitle jenaka “(aka, In Search of Life’s Porpoise)” —retret paus (dan permain-an kata ‘tujuan’/’porpoise’) menunjukkan hewan yang mundur ke kedalaman, mencari makna di luar manusia. “Squid Game” dan “His Octopus Teacher” diambil sebagai alegori—permainan mematikan kapitalis akhir zaman, dan pembelajaran dari kecerdasan non-manusia yang asing namun penuh empati.
Konsep “Hypersea” (teori bahwa kehidupan di darat adalah “lautan” yang kompleks) dan “Oxygene” (merujuk album elektronik Jean-Michel Jarre) membawa kita pada elemen paling dasar. Akhirnya, “Elemental Intimacy” muncul sebagai kemungkinan terakhir: keintiman bukan dengan manusia lain, tetapi dengan elemen-elemen—angin, air, batu, karbon dioksida. Sebuah hubungan yang tidak bersifat personal, tetapi material dan mendalam.
“Notes” dan “Extreme Weather” yang mengiringi setiap sequence tetap hadir sebagai ground bass yang konstan—catatan kaki dan badai yang mengingatkan bahwa semua teori ini berlangsung dalam dunia yang secara harfiah sedang bergejolak.
Proyek Melankolis Kosmik sebagai Warisan
Dengan berakhirnya Sequence 10, Sad Planets menyelesaikan proyeknya yang monumental. Buku ini bukan sekadar diagnosis, tetapi upaya untuk membangun “Ars Moriendi Planetaris” —seni kematian planet yang baik. Relevansinya bagi Indonesia dan dunia terletak pada kemampuannya untuk memberi bahasa pada pengalaman yang tak terucapkan: kesedihan ekologis kolektif. Dalam konteks Indonesia yang kehilangan hutan, terumbu karang, dan garis pantai, kerangka Sad Planets memungkinkan kita untuk mengakui duka ini bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bukti kedalaman hubungan kita dengan tempat.
Prospek yang diajukan oleh sequence-sequence akhir ini adalah masa depan pasca-harap yang anehnya membebaskan. Dengan melepaskan narasi penyelamatan dan kemajuan, kita mungkin bisa beralih ke mode keberadaan yang lebih rendah hati: menjadi “pengamat yang penuh perasaan” dari proses entropik yang tak terelakkan, mengembangkan “keintiman elemental” dengan dunia yang tersisa, dan mungkin—seperti paus yang mundur—mencari “tujuan” di luar proyek manusia yang angkuh.
Pada 2070, mungkin akan muncul “Sekolah Entropologi dan Poetics Planetari” di tengah kota-kota yang tenggelam separuh, di mana orang belajar membaca awan sebagai puisi, mengi-nterpretasi pola erosi sebagai musik, dan meratapi spesies yang punah dengan elegi yang setara dengan kesedihan kosmik yang mereka alami. Masa depan, dalam visi Pettman dan Thacker, adalah tentang belajar mati dengan baik, baik sebagai individu, spesies, maupun sebagai hubungan afektif dengan sebuah planet. Dalam pembelajaran muram inilah, mungkin saja, tersembunyi bentuk kebijaksanaan terakhir yang bisa dicapai spesies kita: kebijaksanaan untuk berduka dengan penuh perhatian, dan kemudian diam.
Kristal-Kristal Peringatan, Doa yang Tak Terjawab
Dalam gerakan penutupnya yang memukau, Sad Planets karya Pettman dan Thacker merangkai elegi-elegi terakhirnya, bergerak dari mineral yang membisu menuju kesadaran terakhir yang meratap, dan akhirnya, menuju semacam rekonsiliasi yang pahit dengan keadaan kita yang sudah runtuh.
Sequence 11 (Kristal-Kristal Gelap – Arsip Alam Yang Membatu) membawa kita ke dunia bawah tanah dan mineral. “Dark Crystals” dan “The Cave of Swords” (mungkin merujuk gua kristal raksasa di Naica, Meksiko) menggambarkan arsip alam yang megah dan sunyi. Kristal-kristal ini adalah “Frozen Warnings” —peringatan yang membeku dari waktu geologis, pesan dari Bumi yang tak terbaca oleh kesadaraan manusia yang singkat.
“A Second Suicide” dan “A Forest of Jewels” membicarakan transformasi paksa: kehidupan menjadi batu, organik menjadi non-organik. “Snowblind” adalah keadaan disorientasi di hadapan kecemerlangan yang dingin ini. Dalam kondisi ini, mungkin terjadi “A Theophany of Non-Organic Life” —penampakan ilahi atau wahyu yang datang bukan dari makhluk hidup, tetapi dari kecerdasan mineral, dari kesabaran kristal. Kita melihat realitas “Through a Glass Darkly” (1 Korintus 13:12), tetapi kaca itu sendiri adalah kristal yang sedih. Penulis mungkin mengutip puisi Robert Southwell, “Go, Crystall Teares,” yang menyamakan air mata dengan permata—di sini, seluruh planet menangis permata padat, sebuah elegi yang membeku selamanya.
Doa Untuk Hujan – Melankoli Sebagai Iklim membuka dengan pengulangan yang putus asa: “Prayers for Rain (I)” dan “Prayers for Rain (II)”. Ini adalah doa kepada langit yang kosong di zaman kekeringan, permohonan kepada kosmos yang tak menjawab. “Gravity of a Planet” bukan hanya tarikan fisik, tetapi beban psikis untuk tetap terikat pada bola duka ini.
Bahasa kuno humor (cairan tubuh) muncul: “Black Bile, Cold and Dry” adalah definisi klasik melankoli. “Night’s Black Bird” (burung hitam malam) melambangkan depresi yang datang. “Atmospheres” dan “Dissipative Structures” membahas suasana hati planet dan struktur sosial yang sedang bubar. “Gazing Wearily, Striving Unwillingly” menggambarkan kondisi manusia Antroposen: lelah mengamati, enggan berusaha.
“Melancholy of Anatomy (I & II)” membedah kesedihan tubuh biologis kita yang rapuh di hadapan skala kosmis. Ini mengantar pada “Sad Planets (a Typology)” —klasifikasi akhir planet-planet sedih: Planet yang Ditinggalkan, Planet yang Terluka, Planet yang Paling Sunyi. Sequence ini diakhiri dengan bayangan kelegaan: “As One Listens to the Rain” —mungkin menyarankan suatu kepasrahan, suatu cara mendengarkan dunia yang sekarat sebagaimana seseorang mendengarkan hujan, menerimanya sebagai musik alam yang fana. Penyair sufi Jalaluddin Rumi pernah menulis, “Air mata adalah hujan dari mata.” Dalam konteks Sad Planets, hujan yang didoakan itu mungkin akhirnya turun, tetapi sebagai hujan air mata kosmik.
Mungkin pada akhirnya Pettman & Thacker melampiaskan rasa kesepian dan keputusasaan yang sunyi – sebuah kesadaran akhir di ruang hampa. Di sinilah mereka mencapai puncak kesunyian dan kegelapan. “Our Only Home, the Night of Space”adalah pengakuan pahit: rumah kita adalah kegelapan kosong. “Around Our Grave a Glass-Clear Silence” meng-gambarkan pemakaman spesies dalam kesunyian mutlak.
Metafora peti mati mendominasi: “Lost in Space,” “Sarcophagus in Space,” “The Earth a Grave.”Matahari pun berduka: “A Black-Draped Sun (I & II)”. Konsep “Blind Life, Black Star” merangkum keadaan: kehidupan yang buta tujuan di bawah bintang yang gelap. Dalam kondisi ekstrem ini, muncul gagasan “Divine Despair” —bukan keputusasaan manusia, tetapi keputusasaan ilahi, perasaan yang mungkin dialami oleh kosmos itu sendiri (atau gagasan tentang tuhan di dalamnya) terhadap proyek penciptaan yang gagal. Ini memuncak dalam “A Quiet Despair,” suatu penerimaan yang tenang dan tanpa amarah atas akhir segalanya. Seperti kata filsuf eksistensialis Søren Kierkegaard: “Keputusasaan adalah penyakit di dalam diri sendiri.” Dalam Sad Planets, penyakit ini telah menjadi epidemi planetari, mencapai stadium terminal.
Kita membayangkan posisi pengamat terakhir. “You Were Here” adalah prasasti di batu nisan planet. “Cosmic View” adalah perspektif tanpa ilusi. “The Last Philosopher” adalah sosok yang tidak lagi berdebat tentang makna, tetapi hanya mengamati dan meratapi kehancuran.
Episode “Help Less (a Eulogy for SN11)” (mungkin merujuk Starship prototype yang meledak) adalah ratapan untuk teknologi yang gagal menyelamatkan kita. Konsep “Eco-Ex” dan “Extinction without Death” membahas kepunahan ekologis dan budaya saat kita masih hidup secara biologis. “The Gift of the Body” dan “Cosmic Sacrifice” mengisyaratkan penyerahan tubuh biologis kita ke dalam siklus kosmis, suatu persembahan terakhir.
“Sacred Conspiracy” mungkin adalah kesepakatan diam-diam untuk merawat rahasia kesedihan bersama. “Rare Earth” dan “Celestial Firmament” adalah pengakuan terakhir terhadap keunikan dan keindahan planet kita yang rapuh di tengah langit bintang. Sequence ini menempatkan “filsuf terakhir” bukan sebagai pahlawan pengetahuan, tetapi sebagai juru rawat memori kosmik, yang tugasnya adalah mengingat bahwa pernah ada kehidupan di sini, dan kehidupan itu bisa merasakan.
Hingga akhirnya tibalah pada situasi dan perasaan solastalgia – kesakitan akan rumah yang masih ada. Sequence 15 mengambil konsep psikologis “Solastalgia” (kesedihan karena perubahan lingkungan di tempat seseorang masih tinggal) sebagai pusatnya. “Concern Team,” “Atlas Crunched,” dan “Olympia” mungkin merujuk pada lembaga yang peduli, mitos yang runtuh, dan cita-cita yang gagal. Nada-nada budaya pop muncul: “Long After the Thrill” (lagu John Cougar), “Sad Girls,” “Nine of Swords” (kartu tarot yang melambangkan kecemasan), “Hiding the Pain,” “Bitter Lemonade” —semuanya menggambarkan strategi budaya sehari-hari untuk mengatasi kesedihan ekologis. “The Waning of Affect” (merujuk Fredric Jameson) adalah berkurangnya intensitas perasaan di masyarakat postmodern, yang kontras dengan kesedihan mendalam yang seharusnya kita rasakan.
Namun, ada upaya untuk melanjutkan hidup: “Back in the Saddle,” “Moving Home,” “The Lucky Country” (sindiran untuk Australia). “Shipping Eden” adalah ironi puncak: mengekspor sisa-sisa alam yang masih asli sebagai komoditas. Sequence ini diakhiri dengan “The Two Willow Trees (a Lachrymose Children’s Story)” —cerita anak yang sedih tentang pohon yang menangis, sebuah metafora untuk mewariskan kesedihan planet kepada generasi berikutnya. Ini adalah pengakuan bahwa “rumah” yang kita tinggali bagi anak-anak kita sudah menjadi tempat yang berduka.
Sequence penutup utama, “The Clever Beasts,” membawa kita pada refleksi ironis tentang manusia. Judul ini sendiri adalah sindiran: kita binatang yang cerdas, tapi kecerdasan itu justru membawa kita pada kehancuran. Referensi “The Machine Stops” (cerita E.M. Forster) menggambarkan ketergantungan mematikan pada teknologi. “Collapsology” adalah studi tentang keruntuhan peradaban. “Zoom Fatigue”adalah kelelahan afektif di dunia virtual yang terputus. “Cosmographs” adalah peta kosmik terakhir. “Objective Allegories” dan “Exhibit D” menyarankan bahwa segala sesuatu di dunia kini menjadi bukti alegoris dari kehancur-an. “Global Happiness Index” menjadi lelucon pahit di planet yang sedih.
Konsep “Indexicality” (filsafat bahasa) mungkin digunakan untuk membahas bagaimana tanda-tanda (asap pabrik, data CO2) secara langsung menunjuk pada bencana. Ini mengantar pada “Sad Things (a Partial Inventory)” —daftar sebagian dari hal-hal yang sedih: spesies tunggal terakhir di kebun binatang, es kutub yang mencair, bahasa yang punah.
Buku ditutup dengan pernyataan sederhana dan final: “No More Happy Returns.” Tidak ada lagi kepulangan yang bahagia. Tidak ada lagi pengulangan yang menyenangkan. Ini adalah pengaku-an bahwa siklus telah putus, bahwa narasi kemajuan telah berakhir. Perjalanan pulang ke Bumi bukan lagi ke rumah yang nyaman, tetapi ke planet yang berduka.
Epilog yang Tersirat: Kehidupan Setelah Elegi
Sad Planets tidak berakhir dengan solusi, tetapi dengan pengakuan yang lengkap. Prospek yang ditawarkannya adalah: masa depan akan dihuni oleh makhluk (manusia atau pasca-manusia) yang telah sepenuhnya menginternalisasi kesedihan planet sebagai kondisi dasar keberadaan mereka. Mereka akan menjadi “ahli waris yang berkabung” yang mungkin mengembangkan budaya, seni, dan etika yang sepenuhnya baru—sebuah budaya elegi, sebuah seni perawatan reruntuhan, sebuah etika keintiman dengan yang fana.
Bagi Indonesia, buku ini menawarkan kerangka untuk mengubah duka ekologis dari perasaan pribadi yang terisolasi menjadi kekuatan budaya kolektif. Nyanyian ratapan untuk hutan yang hilang, upacara untuk sungai yang tercemar, puisi untuk terumbu karang yang memutih—semua ini bisa menjadi bagian dari “Poetics of Planets“ yang baru, sebuah cara untuk hidup dengan bermartabat di dalam kehancuran.
Pada akhirnya, Sad Planets mengajarkan bahwa mungkin satu-satunya tanggapan yang jujur terhadap Antroposen adalah belajar menangis dengan lebih baik, lebih dalam, dan lebih kolektif—untuk mengenali air mata kita bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bukti terakhir dan paling jujur dari cinta kita kepada dunia yang telah kita sakiti. Dalam tangisan itulah, tersembunyi benih terakhir dari tanggung jawab dan perhatian.
Sad Planets Sebagai Elegi untuk Antroposen
Sad Planets karya Dominic Pettman dan Eugene Thacker bukanlah sebuah buku tentang astronomi atau kebijakan iklim. Ia adalah sebuah fenomenologi afektif dari Antroposen, sebuah peta navigasi untuk perasaan-perasaan yang tidak terucapkan yang menghantui kita di era keruntuhan ekologis. Melalui 16 sequence yang berjalan seperti gerakan dalam simfoni requiem, buku ini membangun argumen yang koheren: Bumi kita telah berubah menjadi “planet sedih,” dan kesedihan ini bukanlah metafora, tetapi kondisi ontologis baru yang harus kita huni dan pahami.
Catatan Akhir: Seni Hidup di Antara Reruntuhan
Alur buku ini bergerak spiral, dari yang intim ke yang kosmik, dan kembali ke reruntuhan, dari manusia yang menangis ke planet yang berduka: Pembongkaran Narasi Kosmik Lama (Sequence 1-6): Buku ini pertama-tama mendekonstruksi narasi heroik umat manusia tentang eksplorasi ruang angkasa dan penaklukan alam. Ia menggantikan “alien” sebagai ancaman eksternal dengan “alienasi” internal kita dari Bumi sendiri. Fantasi pelarian ke Mars (Plan(et) B) terbukti sebagai pengingkaran yang sia-sia. Konsep kunci seperti “astral melancholy” dan “chthonic depression” menunjukkan bahwa kesedihan telah menjadi radiasi kosmik dan getaran geologis.
Anatomi Kesedihan Planet (Sequence 7-10): Di sini, penulis membedah struktur kesedihan itu sendiri. Mereka memperkenalkan “entropologi”—ilmu tentang keruntuhan—sebagai satu-satunya disiplin yang jujur. Kesedihan berevolusi dari emosi manusia menjadi sifat material dunia: kristal yang gelap (dark crystals), atmosfer yang berduka (atmospheres), matahari yang berkabung (a black-draped sun). Konsep “impersonal sublime” sangat penting: kita tidak lagi dikecilkan oleh gunung, tetapi oleh skala kepunahan massal dan waktu geologis, sebuah pengalaman yang melarutkan ego manusia.
Elegi dan Rekonsiliasi yang Pahit (Sequence 11-16): Bagian akhir adalah upacara pemakaman yang panjang. Dari gua kristal yang membisu (the cave of swords) hingga doa untuk hujan yang tak terjawab (prayers for rain), buku ini meratapi apa yang telah dan akan hilang. Ia mem-bayangkan “the last philosopher” bukan sebagai pencari kebenaran, tetapi sebagai penjaga memori kosmik. Akhirnya, ia menyelesaikan perjalanannya dengan konsep “solastalgia”—kesakitan karena menyaksikan rumah yang masih ditinggali hancur—dan inventaris akhir “sad things”. Pernyataan penutup, “No More Happy Returns,” adalah batu nisan untuk narasi kemajuan dan siklus alam yang dapat dipulihkan.
Intisari Gagasan: Kita bukan lagi homo sapiens (manusia bijaksana), melainkan “homo tristis” (manusia yang berduka) yang menghuni sebuah “planeta tristis” (planet yang sedih). Kesedihan ini adalah bentuk pengetahuan dan hubungan yang tersisa.
Dalam konteks dunia yang dilanda gelombang panas ekstrem, kebakaran hutan masif, dan kehilangan biodiversitas yang cepat, Sad Planets memberikan bahasa untuk krisis psikis yang menyertai krisis fisik.
- Mengatasi “Crisis Fatigue” dan “Eco-Anxiety“: Buku ini mengangkat kecemasan iklim dari gangguan psikologis individu menjadi respons kolektif yang sahih dan bernilai epistemik. Di Barat, hal ini memvalidasi gerakan seperti “Deep Adaptation” yang fokus pada ketahanan psikologis menghadapi keruntuhan.
- Kritik Terhadap “Solusionisme Teknokratis”: Dengan sinisme yang tajam terhadap Plan(et) Bdan imajinasi kolonisasi luar angkasa, buku ini menyerang anggapan bahwa teknologi tinggi akan menyelamatkan kita. Ini adalah kritik vital terhadap narasi “green growth” yang tidak mempertanyakan logika eksploitatif yang mendasari krisis.
- Relevansi dengan Indonesia: Konteks Indonesia membuat sintesis buku ini sangat nyata:
- “Solastalgia” adalah perasaan sehari-hari masyarakat pesisir yang melihat lautnya naik, petani yang mengalami ketidakpastian musim, dan masyarakat adat yang menyaksikan hutan leluhur dibabat. Buku ini memberi nama dan martabat pada duka tersebut.
- “A Poetics of Planets” selaras dengan kekayaan tradisi lokal Indonesia yang memandang alam secara personal dan afektif. Konsep seperti “Memayu Hayuning Bawana” (Jawa) atau “Ale’ Lita” (Mollo, menjaga keseimbangan alam) adalah bentuk kearifan yang memahami planet bukan sebagai sumber daya, tetapi sebagai hubungan yang hidup dan harus dirawat dengan perasaan.
- “Human Trespass” dan “Hollowed-Out Earth” secara langsung mencerminkan krisis ekstraktivisme di Indonesia: tambang yang menggerus gunung, perkebunan monokultur yang menggantikan hutan, menyisakan lanskap yang “berlubang” secara ekologis dan kultural.
Dua Jalur dari Planet yang Sedih
Sad Planets tidak memberikan manual solusi, tetapi memetakan dua jalan evolusi budaya yang mungkin:
- Jalur Alienasi dan Pembusukan (Path of Alienation & Necrosis): Kita semakin terputus, mengobati kesedihan planet dengan konsumsi, distraksi digital, dan fantasi pelarian. Kesedihan berubah menjadi “biophobia” (ketakutan akan kehidupan) dan nihilisme pasif. Budaya menjadi dangkal (the waning of affect), sementara infrastruktur dan ekosistem terus membusuk. Dunia pada 2070 menjadi tempat “concrete islands” dan “the inner desert,” di mana sisa-sisa manusia hidup dalam bunker teknologi di atas biosfer yang sekarat.
- Jalur Keintiman Elegiak dan Perawatan Reruntuhan (Path of Elegiac Intimacy & Ruin-Tending):Kita merangkul kesedihan sebagai dasar baru untuk etika dan budaya. Dari dalamnya lahir:
- Etika “Elemental Intimacy“: Belajar membangun keintiman yang dalam dengan elemen-elemen non-manusia—angin yang berubah pola, spesies yang tersisa, sungai yang tercemar yang masih mengalir.
- Praktik “Entropologi Terapan”: Berfokus pada dokumentasi yang penuh kasih, perawatan paliatif untuk ekosistem, dan seni mengarsipkan apa yang hilang. Di Indonesia, ini bisa berupa gerakan mendokumentasikan bahasa dan ritual lokal yang punah, atau merawat hutan tersisa bukan sebagai cadangan karbon, tetapi sebagai subjek yang berduka yang layak diperhatikan.
- “A Politics of Mourning”: Politik yang tidak berjanji akan mengembalikan “kenormalan,” tetapi mengorganisir kolektif untuk meratapi dengan bermartabat, mengelola keruntuhan dengan keadilan, dan membagi beban kesedihan secara adil.
Pada akhirnya, Sad Planets adalah panggilan untuk “graduating from the human evolutionary level” dalam arti yang radikal: keluar dari cerita tentang manusia sebagai pusat dan penguasa alam. Masa depan yang digambarkannya adalah masa di mana kita belajar menjadi “the clever beasts” yang akhirnya memahami batas kecerdasan kita sendiri.
Prospek untuk 2045-2070 bukanlah masyarakat hijau yang bersih, tetapi kemungkinan besar masyarakat hibrida yang terluka namun lebih bijak, yang telah mengalami trauma ekologis yang mendalam dan menyimpan kesedihan planet dalam DNA budaya mereka. Mereka mungkin tidak bisa “menyelesaikan” krisis iklim, tetapi mereka akan mengembangkan “ars moriendi planetaris”—seni kematian planet yang baik—yang meliputi keindahan elegi, solidaritas antar spesies, dan komitmen untuk memperhatikan dunia sampai napas terakhirnya.
Bagi Indonesia, peluangnya terletak pada kemampuan untuk menyintesiskan kearifan ekologis tradisional yang penuh perasaan dengan kesadaran ilmiah kontemporer tentang keruntuhan.Negara ini bisa menjadi pionir bukan dalam teknologi geoengineering, tetapi dalam budaya ketahanan elegiak—cara-cara komunitas meratapi, merawat ingatan, dan menemukan makna baru di tengah perubahan yang tak terelakkan. Sad Planets mengajarkan bahwa di ujung segala logika, mungkin hanya dengan belajar menjadi penjaga upacara perpisahan untuk sebuah dunia, kita dapat menemukan kembali rasa hormat dan perhatian yang merupakan fondasi sejati dari keberlanjutan apa pun.
Dalam kelanjutan yang penuh intensitas, Sad Planets karya Pettman dan Thacker mencapai nadir dan puncak refleksinya. Sequence-sequence terakhir ini merajut sebuah elegik yang kompleks bagi planet, memadukan sains, mitos, dan efek dalam sebuah simfoni akhir tentang keberadaan dan keruntuhan.
Masa depan yang digambarkan Sad Planets adalah pilihan antara dua jalur:
- Jalur Alienasi Total: Kita semakin terputus dari Bumi, mengobati kesedihan planet dengan distraksi digital atau fantasi eksodus kosmik, menjadikan Bumi benar-benar sebuah “planet sedih” yang ditinggalkan dalam arti psikologis dan ekologis.
- Jalur Berkabung dan Pemulihan Afektif: Kita membiarkan diri merasakan kesedihan kosmik ini secara kolektif, mengakui keterikatan dan tanggung jawab kita. Dari kesadaran afektif ini bisa lahir bentuk politik dan etika baru yang lebih radikal, sebuah “dipengaruhi bersama oleh kesedihan planet yang sama.”
Pada 2070, dunia mungkin akan dihuni oleh generasi yang secara intrinsik memahami diri mereka sebagai makhluk planetari yang berkabung, yang identitasnya dibentuk oleh kesedihan atas dunia yang rusak yang mereka warisi. Tugas mereka bukan lagi “menyelamatkan” Bumi dalam narasi heroik lama, melainkan “merawat reruntuhan dengan penuh kasih” dan belajar membangun peradaban baru di atas puing-puing dengan kerendahan hati kosmis. Masa depan keberlanjutan, dalam pandangan Sad Planets, dimulai dengan kemampuan kita untuk men-dengar tangisan planet—dan tangisan kita sendiri di dalamnya—lalu menjadikannya dasar untuk sebuah solidaritas yang baru, melampaui manusia.
Bogor, 1 Januari 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Damono, S. D. (2017). Pada Suatu Hari Nanti. Dalam Hujan Bulan Juni. Gramedia Pustaka Utama.
Derrida, J., & Dufourmantelle, A. (2000). Of Hospitality. Stanford University Press.
Nasr, S. H. (1996). Religion and the Order of Nature. Oxford University Press.
Pettman, D., & Thacker, E. (2024). Sad Planets. Polity Press.
Sagan, C. (1994). Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. Random House.