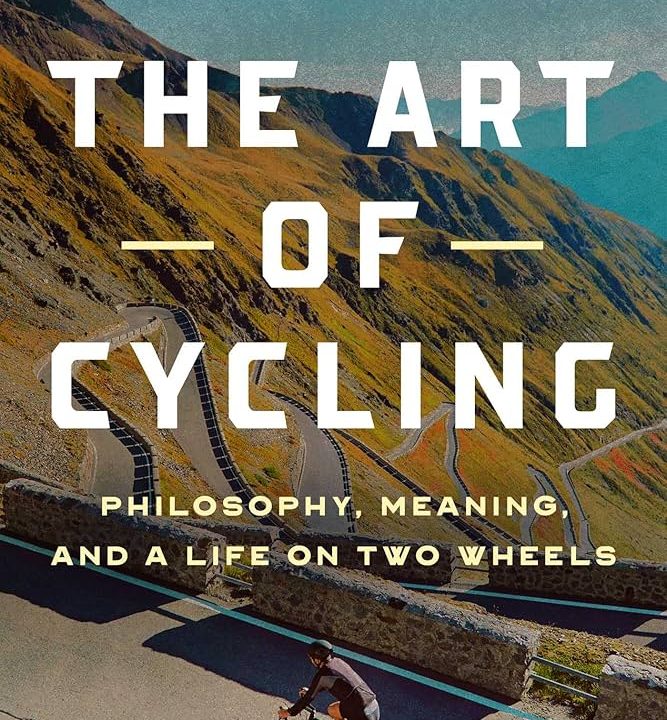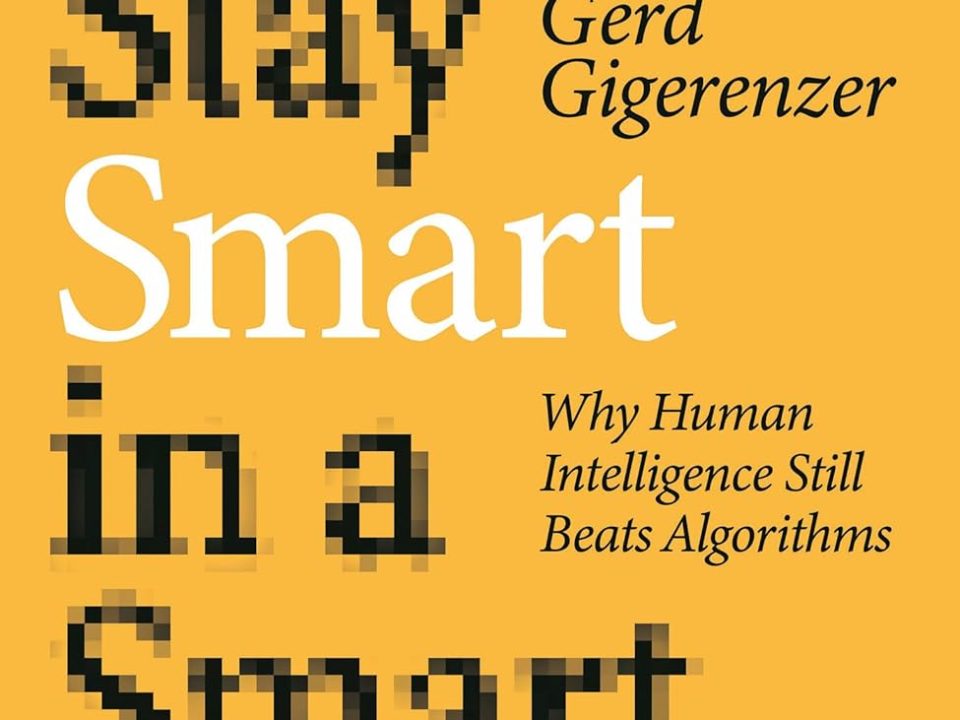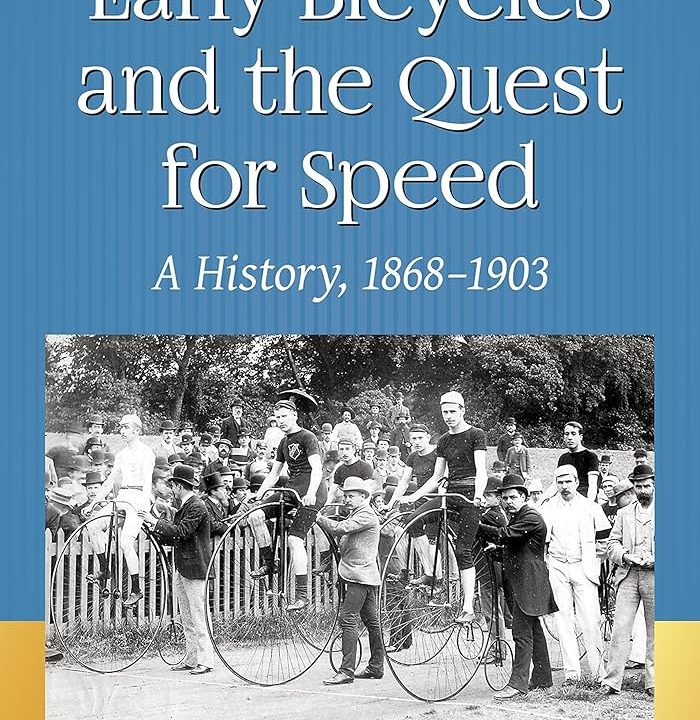Rubarubu #82
Ryokan:
Ketika Sebuah Penginapan Menjadi Cara Hidup
Di sebuah kota kecil pegunungan Jepang, seorang pemilik ryokan bangun sebelum subuh, bukan untuk memeriksa angka okupansi atau ulasan daring, melainkan untuk memastikan onsen sudah pada suhu yang tepat, bunga musiman terpasang di tokonoma, dan nasi dimasak dengan air yang sama seperti yang digunakan kakeknya puluhan tahun lalu. Dalam adegan semacam inilah Chris McMorran membuka refleksi etnografisnya: ryokan bukan sekadar bisnis penginapan, melainkan institusi sosial, moral, dan kultural yang mengikat manusia, lanskap, dan waktu.
Buku ini, Ryokan: Mobilizing Hospitality in Rural Japan karya Chris McMorran (University of Hawai‘i Press, 2022), berangkat dari pertanyaan sederhana namun radikal: bagaimana praktik hospitalitas tradisional dapat “digerakkan” (mobilized) untuk menjawab krisis pedesaan Jepang—depopulasi, penuaan, dan marginalisasi ekonomi—tanpa mengorbankan martabat lokal? Dari sini, McMorran menelusuri ryokan sebagai alat mobilisasi sosial, bukan mesin pertumbuhan.
Buku ini dibuka dengan nada yang tenang namun sarat urgensi. McMorran mengajak pembaca masuk ke pedesaan Jepang yang indah, teratur, dan tampak “selesai”—namun justru di situlah masalahnya. Di balik lanskap pegunungan, onsen yang beruap, dan bangunan kayu ryokan yang terawat, terdapat kerja yang belum selesai (work to do): kerja mempertahankan kehidupan sosial, ekonomi, dan moral di tengah penyusutan penduduk dan runtuhnya struktur desa.
McMorran memulai dengan pengamatan lapangan tentang pemilik ryokan yang bekerja hampir tanpa jeda. Kerja ini bukan hanya kerja ekonomi, tetapi kerja relasional—menjaga hubungan dengan tamu lama, memasak dengan bahan lokal yang makin sulit diperoleh karena petani menua, serta bernegosiasi dengan pemerintah daerah yang melihat ryokan sebagai “aset pariwisata” tanpa sepenuhnya memahami bebannya.
Di sinilah tema besar buku diperkenalkan: hospitalitas bukanlah keadaan alami, melainkan hasil kerja sosial yang intens, rapuh, dan sering tidak diakui. Ryokan tidak bertahan karena efisiensi pasar, tetapi karena dedikasi manusia yang menolak membiarkan tempat mereka mati perlahan. Prolog ini menegaskan bahwa buku ini bukan tentang nostalgia pedesaan, melainkan tentang tenaga moral yang dikerahkan untuk menunda—atau mengubah—kepunahan sosial desa Jepang.
Ryokan sebagai Infrastruktur Sosial Pedesaan
Dalam bab-bab awal, McMorran menjelaskan sejarah ryokan sebagai institusi yang tumbuh bersama jaringan perjalanan pra-modern Jepang—peziarah, pedagang, dan pejabat feodal. Ryokan berkembang bukan sebagai hotel anonim, tetapi sebagai perpanjangan rumah tangga, tempat tamu diperlakukan sebagai okyakusama—bukan pelanggan, melainkan subjek relasional.
Hospitalitas Jepang sering diringkas dalam istilah omotenashi, yang oleh McMorran dibaca bukan sebagai keramahan performatif, melainkan etika perhatian tanpa transaksi eksplisit. Ryokan menjadi simpul tempat nilai-nilai ini dirawat, diwariskan, dan diuji dalam konteks ekonomi modern. Namun buku ini tidak romantis. Ia menunjukkan bahwa di Jepang kontemporer, terutama di wilayah pedesaan, ryokan berada di bawah tekanan berat: penurunan wisata domestik, dominasi hotel korporat, dan logika pariwisata massal. Dalam situasi inilah, ryokan “dimobilisasi”—oleh negara, oleh kebijakan pariwisata, dan oleh komunitas—sebagai solusi pembangunan.
Bagian inti buku ini membahas bagaimana ryokan diposisikan sebagai alat revitalisasi desa. Pemerintah lokal dan nasional mempromosikan ryokan sebagai “warisan budaya hidup” (living cultural heritage), sekaligus mesin ekonomi berbasis pariwisata. McMorran menunjukkan ambivalensi strategi ini.
Di satu sisi, ryokan mampu:
- Menjaga pekerjaan lokal berbasis keluarga
- Mengikat generasi muda pada kampung halaman
- Mempertahankan lanskap dan praktik ekologis setempat
Namun di sisi lain, mobilisasi ini sering:
- Membebani pemilik ryokan dengan ekspektasi moral dan ekonomi berlebihan
- Mengubah hospitalitas menjadi komoditas estetika
- Menempatkan desa sebagai “objek pengalaman” bagi wisatawan kota
McMorran dengan jeli menunjukkan ketegangan antara hospitalitas sebagai praktik relasional dan pariwisata sebagai industri pertumbuhan.
Salah satu kontribusi penting buku ini adalah pembahasan tentang kerja tak terlihat, terutama kerja perempuan. Ryokan bergantung pada tenaga kerja emosional dan afektif—menyambut, melayani, merawat—yang sering kali diwariskan antar generasi perempuan dalam keluarga.
Di sini, McMorran berbicara tentang moral economy of hospitality, di mana kerja tidak semata diukur oleh upah, tetapi oleh kehormatan, kesinambungan keluarga, dan hubungan dengan tamu. Namun moral ekonomi ini rapuh ketika berhadapan dengan standar industri pariwisata global.
Refleksi ini mengingatkan pada kritik Karl Polanyi tentang ekonomi yang “terlepas” (disembedded) dari masyarakat, serta pada gagasan Ivan Illich tentang nilai guna yang hilang ketika praktik hidup dikomodifikasi.
Ryokan mengingatkan kita pada ide retreat—retret—yang menjadi fondasi imajiner pariwisata pedesaan Jepang. Ryokan dipasarkan sebagai tempat melarikan diri dari kota: dari kebisingan Tokyo, dari tekanan kerja, dari kehidupan modern yang serba cepat. McMorran menunjukkan bahwa narasi ini sangat kuat dan efektif, namun juga problematis. Ia mengisahkan bagaimana ryokan di daerah pegunungan atau onsen terpencil membingkai diri sebagai ruang keheningan dan pemulihan. Tamu datang untuk “menyepi”, menikmati makanan musiman, mandi air panas, dan merasakan Jepang “yang sesungguhnya”. Namun bagi tuan rumah, ketenangan ini justru diciptakan melalui kerja yang sangat intens: jadwal ketat, kesiapsiagaan penuh, dan perhatian tanpa henti terhadap detail.
McMorran menganalisis paradoks ini dengan tajam: ketenangan tamu dibangun di atas kerja tak terlihat tuan rumah. Retreat bukanlah kondisi alami pedesaan, melainkan sebuah pengalaman yang diproduksi. Di sini, ryokan menjadi semacam mesin pengalih stres perkotaan—sementara stres struktural pedesaan justru semakin dalam. Gagasan retreat ini lalu dikaitkan dengan sejarah modern Jepang, ketika desa diposisikan sebagai “ruang pemulihan nasional” setelah industrialisasi dan perang. Ryokan lalu menjadi perantara antara kota dan desa, modernitas dan tradisi, produktivitas dan istirahat. Namun McMorran bertanya: sampai kapan desa bisa terus menjadi tempat pelarian bagi orang lain, tanpa menjadi tempat hidup yang layak bagi warganya sendiri?
Ryokan menurut Chris McMorran
Dalam pembacaan Chris McMorran, ryokan bukan sekadar penginapan tradisional Jepang, melainkan sebuah institusi sosial, ekonomi, dan politik yang berfungsi sebagai mesin hospitalitas dalam konteks pedesaan Jepang yang mengalami krisis demografis dan ekonomi.
Secara ringkas namun mendalam, ryokan dapat didefinisikan sebagai:
Sebuah bentuk usaha penginapan berbasis rumah tangga di Jepang yang memobilisasi praktik hospitalitas tradisional (omotenashi) sebagai kerja ekonomi, alat revitalisasi pedesaan, dan mekanisme reproduksi identitas nasional, sambil sekaligus menyembunyikan relasi kerja, gender, dan kekuasaan yang menopangnya.
Definisi ini menekankan bahwa ryokan bukan hanya tempat, tetapi proses sosial yang terus diproduksi.
Elemen Kunci dalam Definisi Ryokan ala McMorran
1. Ryokan sebagai institusi hospitalitas yang dimobilisasi
McMorran menegaskan bahwa ryokan tidak bisa dipahami sebagai warisan budaya statis. Ia adalah bentuk “mobilized hospitality”—hospitalitas yang secara aktif digerakkan oleh:
- negara (melalui kebijakan pariwisata dan revitalisasi desa),
- pasar (melalui industri pariwisata domestik dan internasional),
- dan rumah tangga pedesaan (sebagai strategi bertahan hidup).
Dengan kata lain, ryokan adalah hospitalitas yang bekerja—bukan sekadar nilai moral.
2. Ryokan sebagai strategi bertahan pedesaan
Dalam konteks Jepang yang mengalami:
- depopulasi desa,
- penuaan penduduk,
- dan penurunan sektor pertanian, ryokan berfungsi sebagai alat ekonomi substitutif. Ia menggantikan peran pertanian dan industri yang melemah, menjadikan keramahan sebagai sumber pendapatan utama.
McMorran menunjukkan bahwa ryokan sering muncul di wilayah yang “ditinggalkan” oleh pembangunan modern, sehingga: ryokan menjadi cara agar desa tetap “bernilai” dalam imajinasi nasional dan ekonomi.
3. Ryokan sebagai kerja, bukan hanya budaya
Salah satu kontribusi terpenting McMorran adalah membongkar mitos omotenashi.
Dalam wacana populer, omotenashi dipuji sebagai keramahan tulus tanpa pamrih. McMorran justru menegaskan bahwa di ryokan:
- omotenashi adalah kerja intensif,
- sangat tergenderkan (didominasi perempuan, terutama lansia),
- sering kurang terlihat dan kurang dihargai secara ekonomi.
Dengan demikian, ryokan adalah tempat kerja emosional (emotional labor), bukan hanya panggung budaya.
4. Ryokan sebagai ruang yang dipolisikan
McMorran juga mendefinisikan ryokan sebagai ruang sosial yang dikontrol.
Ryokan:
- mengatur perilaku tamu,
- menyaring siapa yang “cocok” sebagai pelanggan,
- menjaga citra Jepang yang bersih, tertib, dan harmonis.
Dalam arti ini, ryokan berfungsi sebagai alat reproduksi identitas nasional Jepang, terutama dalam menghadapi wisatawan asing.
5. Ryokan sebagai bentuk kapitalisme khas
McMorran tidak menempatkan ryokan di luar kapitalisme, tetapi sebagai bentuk kapitalisme skala kecil berbasis rumah tangga.
Ryokan adalah:
- usaha keluarga,
- bergantung pada kerja intensif, bukan ekspansi,
- beroperasi dengan margin tipis,
- dan sangat rentan terhadap krisis (pandemi, bencana, perubahan selera).
Ia adalah contoh kapitalisme perawatan (care-based capitalism) yang sering dipromosikan sebagai “berkelanjutan”, tetapi justru menyerap risiko ke tingkat rumah tangga.
Demikian ringkasnya Ryokan adalah institusi penginapan berbasis rumah tangga di pedesaan Jepang yang memobilisasi hospitalitas tradisional sebagai bentuk kerja ekonomi, strategi bertahan hidup, dan alat reproduksi identitas nasional, sekaligus mereproduksi ketimpangan kerja, gender, dan tanggung jawab pembangunan dalam sistem kapitalisme pariwisata.
Definisi McMorran penting karena:
- membongkar romantisasi pariwisata budaya,
- menggeser fokus dari “pengalaman tamu” ke kerja dan kehidupan tuan rumah,
- dan memberi kerangka kritis untuk membaca homestay, desa wisata, dan pariwisata berbasis komunitas di Indonesia.
Dengan definisi ini, ryokan tidak lagi sekadar inspirasi estetika, melainkan cermin strukturalbagi banyak praktik pariwisata pedesaan di dunia.
Ryokan, Lanskap, dan Ekologi Kehidupan
Ryokan dalam buku ini tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu tertanam dalam lanskap: pegunungan, sungai panas, sawah, dan hutan. McMorran menunjukkan bagaimana hospitalitas tradisional Jepang secara implisit mengajarkan etik ekologi, melalui makanan musiman (shun), penggunaan air lokal, dan ritme kerja yang mengikuti alam.
Di sini, ryokan menjadi contoh ekonomi kecukupan, bukan ekonomi akumulasi. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran degrowth dan dengan etika Islam tentang qana’ah (cukup), atau kosmologi Nusantara tentang hidup selaras dengan alam. Seperti ditulis oleh filsuf Jepang Watsuji Tetsurō, manusia selalu hidup dalam aidagara—relasi antar-manusia dan dengan lingkungan. Ryokan adalah bentuk konkret dari aidagara yang terinstitusionalisasi.
McMorran tidak menawarkan ryokan sebagai model universal, melainkan sebagai cermin kritis. Ia mengajak pembaca melihat bagaimana praktik lokal dapat:
- Menantang paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan
- Menawarkan alternatif ekonomi berbasis relasi
- Mengungkap biaya tersembunyi dari “revitalisasi”
Dalam konteks global—termasuk Indonesia—ryokan mengingatkan kita pada:
- homestay desa adat,
- pondok pesantren sebagai ruang hospitalitas,
- atau rumah-rumah tumpangan tradisional Nusantara.
Seperti kata antropolog James Scott, bentuk-bentuk kehidupan kecil dan lokal sering kali menyimpan “arts of not being governed”—cara bertahan tanpa tunduk sepenuhnya pada logika negara dan pasar.
McMorran memaparkan pengalaman personal untuk membincangkan lanskap sebagai konstruksi sosial dan politik. Pedesaan Jepang, sebagaimana ditampilkan dalam brosur pariwisata dan promosi ryokan, bukanlah lanskap “alami”, melainkan lanskap yang dirancang, dipilih, dan dibingkai. Ia memberikan contoh konkret bagaimana ryokan dan pemerintah daerah bekerja sama “menata” desa: menyembunyikan bangunan modern, menonjolkan sawah terasering, memulihkan rumah tua sebagai estetika tradisional. Lanskap menjadi panggung tempat narasi Jepang pedesaan dipertontonkan. Namun McMorran menunjukkan bahwa proses ini sering kali menghapus realitas sosial: rumah kosong akibat depopulasi, lahan terbengkalai karena kekurangan tenaga kerja, dan ketergantungan ekonomi pada wisata musiman. Lanskap yang indah menyamarkan ketidakstabilan struktural.
Ia juga menyentuh isu ekologis. Ryokan sering dipromosikan sebagai “ramah lingkungan”, tetapi McMorran menolak klaim sederhana ini. Ia menunjukkan bahwa keberlanjutan di pedesaan Jepang bukan hasil inovasi hijau modern, melainkan praktik lama yang kini semakin sulit dipertahankan karena tekanan ekonomi dan demografi. Analisis ini memperlihatkan bagaimana lanskap bukan sekadar latar, melainkan medium kekuasaan, tempat nilai tertentu—keheningan, keaslian, tradisi—diprioritaskan, sementara konflik dan kerja keras disembunyikan.
Pariah in Paradise
Pada bagian lain McMorran memperkenalkan figur yang ia sebut sebagai “pariah in paradise”: para pekerja ryokan, pemilik kecil, dan penduduk desa yang menjadi tulang punggung industri hospitalitas, namun sering dipinggirkan dalam narasi sukses pariwisata. Ia mengisahkan bagaimana pemilik ryokan kecil kerap diperlakukan ambigu oleh negara dan pasar. Di satu sisi, mereka dipuji sebagai penjaga tradisi; di sisi lain, mereka ditekan untuk beradaptasi dengan standar industri—digitalisasi, bahasa asing, sertifikasi—yang sering kali tidak realistis bagi usaha keluarga kecil.
Ia menyentuh dimensi kelas dan stigma. Kerja hospitalitas di pedesaan sering dianggap “kurang modern” dan “tidak menjanjikan” oleh generasi muda. Akibatnya, regenerasi tersendat. Ryokan yang indah berdiri di tengah krisis pewarisan. McMorran menyoroti ironi pahit: mereka yang membuat “surga” bagi wisatawan justru hidup dalam ketidakpastian struktural. Dalam bahasa sosiologi kritis, ryokan menjadi situs eksploitasi afektif—di mana kehangatan, keramahan, dan dedikasi moral diekstraksi tanpa jaminan masa depan.
Namun Bagian ini tidak berakhir dalam keputusasaan. McMorran juga menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan halus: pemilik ryokan yang menolak ekspansi, yang memilih tamu tertentu, atau yang menegaskan batas kerja demi menjaga martabat hidup. Di sini, ryokan muncul sebagai ruang negosiasi etis—bukan sekadar bisnis.
Ryokan tampil bukan sebagai simbol romantik Jepang tradisional, melainkan sebagai arena konflik antara hospitalitas, kapitalisme pariwisata, dan keberlanjutan pedesaan. McMorran dengan konsisten menunjukkan bahwa apa yang tampak tenang, indah, dan “selesai” justru menyimpan pekerjaan besar yang belum rampung: pekerjaan menjaga kehidupan agar tetap bermakna tanpa menyerah pada logika pertumbuhan.
Buku ini juga membawa pembaca masuk lebih dalam—secara harfiah dan simbolik—ke “dalam” ryokan. McMorran menyingkap mekanisme internal kerja hospitalitas: rutinitas, hirarki, dan relasi kekuasaan yang membentuk kehidupan sehari-hari di balik pintu geser tatami. Ia menggambarkan ryokan sebagai organisme sosial yang kompleks. Tidak ada pemisahan tegas antara ruang kerja dan ruang hidup. Dapur, kamar tamu, ruang keluarga, dan kantor administrasi saling bertumpuk. Bekerja di ryokan berarti hidup di dalamnya—secara fisik dan emosional. Inilah yang dimaksud McMorran dengan inside job: hospitalitas bukan pekerjaan yang bisa ditanggalkan saat jam kerja selesai.
Melalui observasi etnografis, McMorran menunjukkan bagaimana pemilik dan pekerja ryokan menginternalisasi peran mereka. Senyum, kesopanan, dan kesiapsiagaan bukan sekadar standar layanan, tetapi bagian dari identitas diri. Namun internalisasi ini juga menciptakan kerentanan: kelelahan kronis, batas personal yang kabur, dan rasa bersalah ketika tidak mampu memenuhi ekspektasi tamu. Bab ini secara halus mengkritik romantisasi “kerja dengan hati”. McMorran tidak menyangkal nilai etis hospitalitas, tetapi ia menunjukkan bahwa ketika kerja moral sepenuhnya diinternalisasi, eksploitasi menjadi sulit dikenali—bahkan oleh pelakunya sendiri.
Ryokan bagaimanapun adalah sebuah usaha, sebuah bisnis. Judul How to Succeed in Business (Bab 5) ini terdengar ironis—dan memang demikian. McMorran tidak menawarkan resep sukses ala buku bisnis. Sebaliknya, ia membongkar ketegangan antara logika pasar modern dan realitas ryokan pedesaan. Ia menceritakan bagaimana pemilik ryokan dihadapkan pada tekanan untuk “berhasil”: meningkatkan okupansi, menarik wisatawan asing, memodernisasi fasilitas, dan memanfaatkan platform digital. Namun “kesuksesan” ini sering datang dengan harga mahal—utang, beban kerja berlebih, dan hilangnya kendali atas ritme hidup.
McMorran memberikan contoh konkret pemilik ryokan yang mencoba mengikuti saran konsultan bisnis atau kebijakan pariwisata pemerintah, hanya untuk menemukan bahwa skala kecil dan konteks lokal mereka tidak kompatibel dengan model pertumbuhan standar. Banyak yang akhirnya bertahan bukan karena strategi ekspansi, tetapi karena menolak untuk tumbuh—menjaga ukuran usaha agar tetap bisa dikelola secara manusiawi. Bab ini mem-perlihatkan bahwa dalam konteks ryokan, keberhasilan sering berarti cukup: cukup tamu, cukup pendapat-an, cukup tenaga untuk bertahan tanpa mengorbankan kesehatan dan relasi sosial. Di sini, McMorran secara implisit mengaitkan ryokan dengan etika pasca-pertumbuhan—sebuah ekonomi bertahan hidup yang bermartabat, bukan ekonomi akumulasi.
Dalam menulis buku ini McMorran mengikuti satu hari penuh dalam kehidupan ryokan—dari pagi buta hingga larut malam—untuk menunjukkan betapa padat dan berlapisnya kerja hospitalitas. Hari dimulai sebelum matahari terbit: membersihkan kamar, menyiapkan sarapan, memeriksa onsen. Tidak ada jeda jelas antara tugas satu dan lainnya. Waktu makan sering terselip di antara pekerjaan. Interaksi dengan tamu berlangsung terus-menerus, menuntut perhatian penuh, bahkan saat tubuh sudah lelah. McMorran menekankan bahwa pekerjaan ini bukan hanya fisik, tetapi juga afektif. Membaca suasana hati tamu, menyesuaikan tingkat keakraban, menjaga keheningan—semuanya adalah bentuk kerja emosional yang intens. Kesalahan kecil dapat terasa besar karena menyangkut kehormatan pribadi dan reputasi keluarga.
Dengan menggambarkan satu hari secara detail, buku ini menghapus ilusi bahwa ryokan adalah tempat kerja “tenang” atau “sederhana”. Justru sebaliknya, ketenangan yang dialami tamu dibayar dengan kepadatan waktu dan energi tuan rumah.
Bab ini membawa diskusi ke wilayah yang lebih luas: perawatan (care) sebagai persoalan profesional, sosial, dan politik. McMorran mengaitkan ryokan dengan krisis perawatan di Jepang—negara yang menua dengan cepat dan kekurangan sistem dukungan pedesaan.
Ia menunjukkan bahwa ryokan sering berfungsi sebagai ruang perawatan informal: merawat pekerja lanjut usia, mendukung anggota keluarga yang sakit, bahkan membantu tamu yang mengalami kesepian atau krisis emosional. Namun semua ini terjadi di luar kerangka “perawatan profesional” yang diakui negara.
Pertanyaan yang diajukan McMorran tajam: apakah hospitalitas bisa—atau seharusnya—menggantikan sistem perawatan sosial? Dan jika iya, siapa yang membayar biaya emosional dan materialnya? Ia memperlihatkan batas hospitalitas. Keramahan dan dedikasi moral tidak bisa terus menerus mengisi kekosongan kebijakan publik. Di titik ini, ryokan menjadi cermin krisis yang lebih luas: ketika negara dan pasar mundur, komunitas dipaksa menanggung beban perawatan—sering tanpa sumber daya memadai.
McMorran berpendapat ryokan adalah institusi etis yang bekerja melampaui fungsi ekonomi-nya, tetapi justru karena itu ia rentan terhadap eksploitasi struktural. Hospitalitas tampil sebagai kekuatan yang menjaga kehidupan pedesaan tetap berjalan, namun juga sebagai medan ketegangan antara kepedulian dan kelelahan, antara makna dan ketidakpastian.
McMorran mendiskusikan ryokan dalam konteks ruang—bukan ruang netral, melainkan ruang yang diatur, diawasi, dan dipolitisasi. Ryokan tidak hanya menjadi tempat menyambut, tetapi juga medan di mana norma sosial, nasionalisme kultural, dan ekspektasi pasar global bertemu dan bertabrakan. Ia menunjukkan bahwa ruang ryokan terus-menerus “dipolisikan”: oleh negara, oleh industri pariwisata, oleh norma budaya Jepang tentang kesopanan, dan bahkan oleh tamu itu sendiri. Aturan tentang siapa yang boleh masuk, bagaimana berpakaian, kapan berbicara, dan bagaimana menggunakan onsen bukan sekadar tradisi—melainkan mekanisme kontrol yang menjaga citra “Jepang otentik”.
McMorran memberi contoh konkret tentang bagaimana tamu asing, pekerja migran, atau kelompok minoritas sering kali menjadi subjek ketegangan. Ryokan harus menegosiasikan antara inklusivitas ekonomi (membutuhkan tamu dan tenaga kerja) dan eksklusivitas budaya (menjaga “atmosfer Jepang”). Dalam praktiknya, ini berarti penyaringan halus: bukan larangan terang-terangan, tetapi aturan implisit yang membuat sebagian orang merasa “tidak sepenuhnya pantas berada di sini”.
Ia menyingkap bagaimana negara dan lembaga pariwisata memobilisasi ryokan sebagai alat soft power—memamerkan Jepang sebagai bangsa beradab, ramah, dan tradisional. Namun citra ini bergantung pada kerja penghapusan: konflik disembunyikan, ketegangan diredam, dan per-bedaan dipoles agar tidak mengganggu pengalaman tamu.
Dengan demikian, policing ryokan space bukan sekadar soal tata tertib, melainkan soal siapa yang berhak atas ruang pedesaan, dan dengan syarat apa. Ryokan menjadi miniatur dari politik nasional: terbuka secara ekonomi, tetapi terjaga secara kultural.
Hospitalitas sebagai Kerja Peradaban
Ryokan Jepang sangat menarik jika dibincangkan dalam konteks homestay/desa wisata indonesia dalam cermin kritis. Bagaimana keramahan menjadi bagian dari infrastruktur.
Di Jepang, ryokan sering dipahami sebagai simbol keanggunan tradisi—tatami, futon, onsen, dan omotenashi yang halus. Di Indonesia, homestay dan desa wisata dipromosikan sebagai wajah keramahan Nusantara—senyum tuan rumah, makanan rumahan, dan “keaslian” desa. Keduanya tampak berbeda secara budaya, tetapi sesungguhnya berbagi satu nasib struktural yang sama: hospitalitas dijadikan infrastruktur ekonomi untuk menutup krisis pedesaan.
Baik ryokan maupun desa wisata muncul dan direproduksi bukan semata karena nilai budaya, melainkan karena ketimpangan pembangunan yang memusatkan sumber daya di kota. Hospitalitas lalu dimobilisasi sebagai jalan keluar: desa diminta “ramah”, “autentik”, dan “melayani” agar tetap hidup.
Ryokan berakar pada sistem penginapan periode Edo, melayani pelancong, pedagang, dan samurai. Namun dalam bentuk modernnya, seperti yang ditunjukkan Chris McMorran, ryokan adalah produk negosiasi antara negara, pasar pariwisata, dan krisis pedesaan pasca-industrial. Ia bukan sekadar warisan, melainkan institusi yang terus diadaptasi agar cocok dengan logika ekonomi modern. Homestay dan desa wisata Indonesia, sebaliknya, relatif baru sebagai kebijakan nasional. Mereka berkembang pesat pasca-2000-an, terutama melalui program Kementerian Pariwisata, Dana Desa, dan narasi “pariwisata berbasis masyarakat”. Tradisi desa—gotong royong, rumah panggung, upacara adat—dikemas sebagai produk pengalaman untuk wisatawan domestik dan global.
Dalam kedua kasus, tradisi tidak hilang, tetapi diarahkan: dipilih, disederhanakan, dan dipentaskan agar sesuai dengan selera pasar.
Ryokan dan desa wisata sama-sama hidup dari janji “keaslian”. Namun keaslian ini tidak netral.
Ryokan harus tetap “Jepang”: tenang, bersih, tertib, dan tidak mengganggu imaji nasional. Tamu asing diterima, tetapi sering harus menyesuaikan diri dengan norma implisit. Ruang ryokan dipolisikan agar citra Jepang tidak retak. Desa wisata Indonesia menghadapi tekanan serupa. Desa harus tampil “alami”, “sederhana”, dan “tradisional”, meski warganya hidup dalam realitas modern yang kompleks. Konflik agraria, kemiskinan, atau migrasi tenaga kerja sering disembunyikan agar tidak merusak pengalaman wisata.
Dalam kedua kasus, hospitalitas berfungsi sebagai mekanisme penyensoran sosial: yang tidak cocok dengan narasi pariwisata disingkirkan dari panggung. Negara Jepang memobilisasi ryokan sebagai alat revitalisasi pedesaan dan soft power budaya. Negara Indonesia memo-bilisasi desa wisata sebagai solusi ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan penarik devisa. Namun ada kesamaan yang mencolok: hospitalitas dijadikan substitusi kebijakan struktural. Ketika pertanian tidak menguntungkan, ketika industri tidak hadir, ketika layanan publik menipis, desa diminta bertahan dengan keramahan. Baik ryokan maupun homestay akhirnya memikul beban yang terlalu besar: menjaga budaya, menghidupi keluarga, melayani pasar, dan menutupi kegagalan sistem pembangunan yang lebih luas.
Meski serupa secara struktural, ada perbedaan penting. Ryokan cenderung lebih ter-institusionalisasi, terstandar, dan terikat pada regulasi ketat. Desa wisata Indonesia lebih beragam: dari yang dikelola komunitas secara kolektif hingga yang diserahkan pada investor luar. Di Indonesia, masih ada ruang resistensi: desa adat yang membatasi pariwisata, komunitas yang menolak over-tourism, atau inisiatif yang menempatkan pariwisata sebagai pelengkap, bukan pusat ekonomi. Ruang ini lebih sempit di Jepang, tetapi bukan tidak ada.
Dari perbandingan ini, satu pelajaran besar muncul: hospitalitas tidak bisa menjadi fondasi tunggal ekonomi pedesaan. Ryokan mengajarkan disiplin, kualitas, dan penghormatan pada relasi. Desa wisata Indonesia mengajarkan fleksibilitas, gotong royong, dan adaptasi lokal. Namun keduanya menunjukkan bahaya yang sama: ketika keramahan dieksploitasi tanpa keadilan struktural, ia berubah dari kebajikan menjadi beban. Masa depan yang lebih etis menuntut pergeseran: dari pariwisata sebagai tujuan, menuju kehidupan desa sebagai pusat, di mana hospitalitas adalah ekspresi relasi sosial, bukan tuntutan pasar.
Catatan Akhir: Mobilizing Hospitality
Epilogue buku ini tidak berfungsi sebagai penutup biasa, melainkan sebagai refleksi filosofis dan politis atas seluruh argumen yang telah dibangun. Di sini, McMorran mengajukan pertanyaan paling mendasar: apa yang sebenarnya sedang dimobilisasi ketika kita berbicara tentang hospitalitas?
Ia menegaskan bahwa hospitalitas bukan hanya praktik moral atau warisan budaya, melainkan sumber daya sosial yang terus diekstraksi. Negara, pasar, dan masyarakat urban memobilisasi hospitalitas pedesaan Jepang untuk berbagai tujuan: revitalisasi ekonomi, pelestarian identitas nasional, dan penyangga krisis sosial seperti penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja perawatan. Namun, McMorran menolak narasi heroik yang melihat ryokan sebagai solusi ajaib bagi masalah pedesaan. Ia menunjukkan bahwa hospitalitas memiliki batas. Ia bisa menghangatkan relasi, tetapi tidak bisa menggantikan kebijakan publik. Ia bisa menopang komunitas, tetapi tidak bisa sendirian melawan struktur ekonomi yang menguras desa.
Epilogue ini juga memperlihatkan paradoks besar: ryokan diminta untuk tetap “tradisional”, tetapi beroperasi dalam ekonomi modern yang tidak ramah terhadap tradisi. Mereka harus fleksibel, adaptif, inovatif—namun juga otentik, stabil, dan “tak berubah”. Beban kontradiksi ini jatuh terutama pada tubuh dan emosi para pekerja, khususnya perempuan. McMorran kemudian mengajak pembaca untuk melihat hospitalitas sebagai bentuk kerja relasional jangka panjang, bukan komoditas pengalaman sesaat. Ia menyiratkan bahwa masa depan pedesaan tidak bisa hanya bergantung pada pariwisata—apalagi pariwisata yang mengandalkan romantisasi masa lalu.
Yang paling penting, epilogue ini menawarkan sebuah pembalikan perspektif: alih-alih bertanya bagaimana ryokan bisa menyelamatkan desa, kita seharusnya bertanya bagaimana masyarakat dan negara bisa berhenti mengeksploitasi etika kepedulian pedesaan. Hospitalitas, dalam pembacaan McMorran, adalah cermin krisis global: ketika sistem ekonomi gagal menyediakan kesejahteraan, ia mengandalkan moralitas lokal untuk menutup celah. Ryokan menjadi contoh nyata bagaimana kerja berbasis kepedulian—yang sering dipuji sebagai “nilai budaya”—justru berisiko menjadi mekanisme penundaan keadilan struktural.
Epilogue ini berakhir dengan nada yang tidak pesimistis, tetapi realistis dan etis. McMorran tidak menyerukan penghapusan ryokan, melainkan rekontekstualisasi. Ia membayangkan masa depan di mana hospitalitas tidak lagi dimobilisasi secara sepihak, melainkan dinegosiasikan secara adil—dengan pengakuan atas batas manusiawi, kebutuhan perawatan, dan hak untuk hidup layak.
Ryokan Jepang dan homestay Indonesia memperlihatkan wajah global dari satu krisis yang sama: desa diminta menyelamatkan sistem yang tidak adil dengan nilai-nilai moralnya sendiri. Jika hospitalitas ingin berkelanjutan, ia harus dibebaskan dari logika pertumbuhan tanpa batas. Ia harus diiringi oleh:
- keadilan kerja,
- batas jumlah wisatawan,
- pengakuan atas kerja perawatan,
- dan kedaulatan desa atas ruang hidupnya.
Tanpa itu, baik ryokan maupun desa wisata hanya akan menjadi museum hidup bagi kenyamanan orang lain, bukan rumah yang layak bagi penghuninya sendiri.
Jika seluruh buku ini dibaca sebagai satu kesatuan, maka Epilogue mengikat semuanya menjadi satu tesis besar: hospitalitas adalah kerja moral yang telah dipolitisasi oleh krisis kapitalisme pedesaan. Ryokan tidak runtuh karena kegagalan nilai, melainkan karena terlalu banyak nilai dibebankan padanya tanpa dukungan struktural. Ia diminta menjadi ekonomi, budaya, perawatan, dan identitas—sekaligus. Dalam konteks global (dan sangat relevan dengan desa-desa Indonesia), Ryokan mengajukan peringatan penting: ketika kita memuja kearifan lokal tanpa mengubah sistem yang mengekstraksinya, kita sedang merayakan keberlanjutan semu.
Ryokan: Mobilizing Hospitality in Rural Japan adalah buku tentang masa depan yang belajar dari masa lalu tanpa nostalgia kosong. Ia menunjukkan bahwa hospitalitas bukan sekadar layanan, tetapi cara mengorganisasi kehidupan bersama. Ryokan sebagai pelajaran tentang masa depan pedesaan.
Dalam dunia yang dikejar oleh efisiensi, skala, dan pertumbuhan, ryokan mengajarkan nilai yang hampir terlupakan: perhatian, keberlanjutan, dan keterlekatan pada tempat. Buku ini menjadi kontribusi penting bagi wacana post-growth, degrowth, dan pembangunan berbasis komunitas, tidak hanya di Jepang, tetapi di mana pun desa-desa berjuang untuk tetap hidup dengan martabat.
Bogor, 30 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
McMorran, C. (2022). Ryokan: Mobilizing hospitality in rural Japan. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
https://uhpress.hawaii.edu/title/ryokan-mobilizing-hospitality-in-rural-japan/
Polanyi, K. (1944). The great transformation. Boston: Beacon Press.
Illich, I. (1973). Tools for conviviality. New York: Harper & Row.
Watsuji, T. (1996). Watsuji Tetsurō’s Rinrigaku: Ethics in Japan. SUNY Press.
Scott, J. C. (2009). The art of not being governed. Yale University Press.