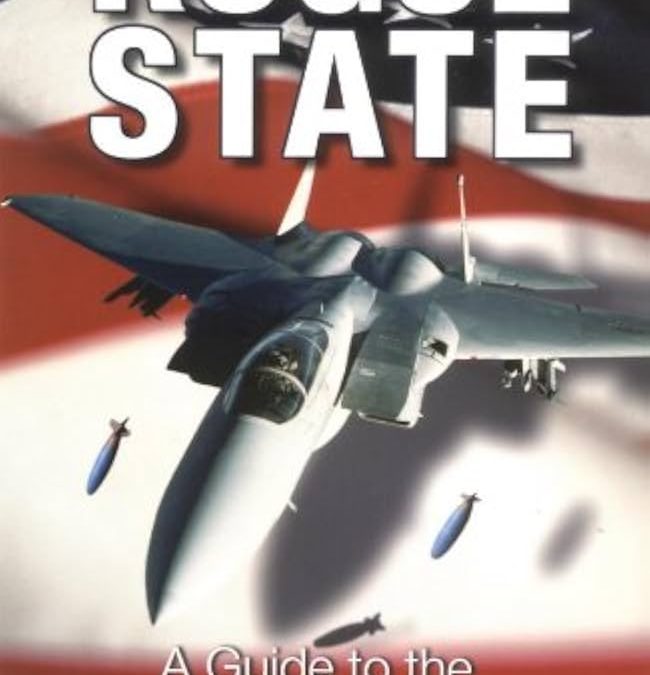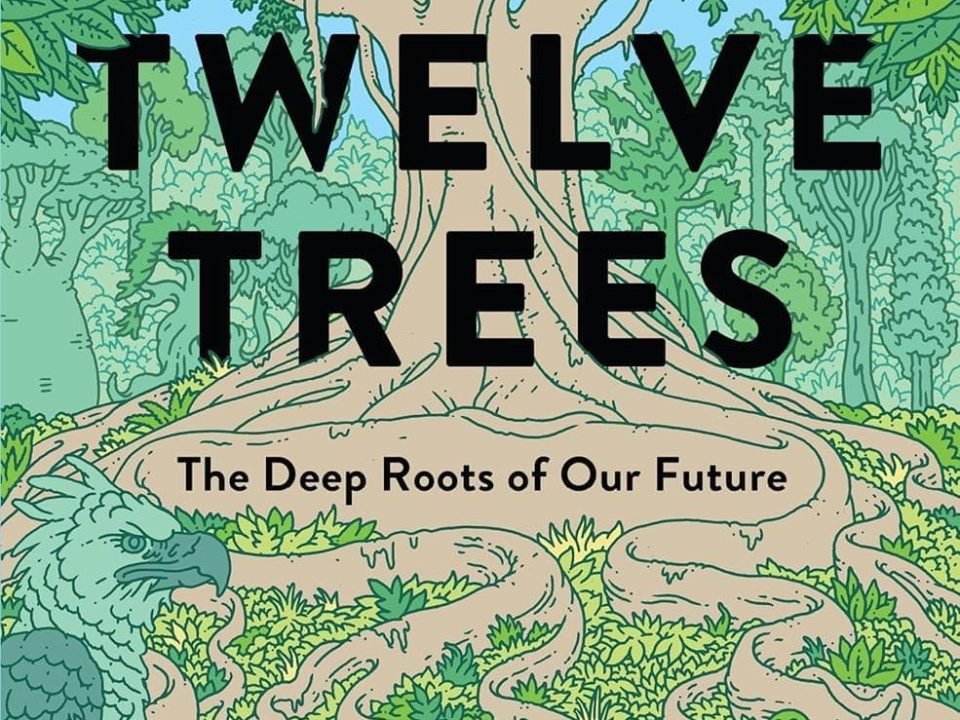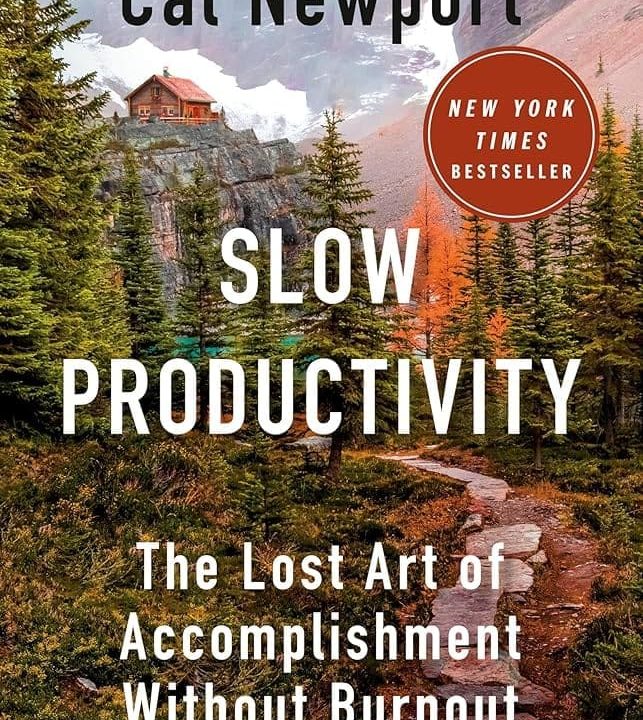Rubarubu #76
Rogue State: Kisah Dunia dari Sudut Pandang
Seorang Pengkritik Amerika
Inilah planet di bawah bayang-bayang kekuasaan. Pada pagi yang hening menjelang 11 September 2001, nyaris tak seorang pun di luar lingkaran intelijen menduga bahwa hari itu akan menjadi simbol rentetan tragedi global yang tak tertandingi. Ketika empat pesawat komersial Amerika digunakan sebagai senjata oleh teroris, menara kembar World Trade Center runtuh seperti metafora literal dari runtuhnya narasi keselamatan pasca–Perang Dingin. Namun, sebagai William Blum tulis dalam Author’s Foreword, tragedi itu tidak muncul dari ketiadaan — melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif, berulang, dan kadang brutal selama lebih dari setengah abad. williamblum.org
Blum, seorang mantan analis di Departemen Luar Negeri AS yang kemudian menjadi kritikus tajam kebijakan neokolonial Amerika, membuka buku ini dengan pengakuan bahwa meskipun serangan 11 September tidak bisa dibenarkan secara moral, ia memahami penyebabnya sebagai produk dari tindakan AS sendiri yang telah bertahun-tahun menyebabkan penderitaan di luar negeri — penderitaan yang berujung pada kebencian yang terkadang meledak sebagai kekerasan teror. williamblum.org Narasi ini bukan sekadar argumen politik; ia adalah pengantar yang memaksa pembaca untuk melihat ulang asumsi kita tentang sebab, akibat, moralitas, dan kekuasaan. Kegelisahan dan kejengkelannya pada rezim negaranya itu ditumpahkan dalam Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower oleh William Blum (Zed Books, 2002), dikemas dalam tiga bagian, dalam lebih dari 300 halaman.
Dalam Introduction, Blum mengajak kita mundur sejenak dari kejadian 11 September dan melihat gambaran yang lebih luas: selama tujuh puluh tahun lebih sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat telah meyakinkan dunia bahwa hanya dirinya yang bisa melindungi dunia dari “konspirasi internasional jahat” — dari komunisme hingga terorisme. Ia menulis dengan ironi tajam bahwa Washington menawarkan jaminan keselamatan ini sambil meminta negara lain membuka tanahnya bagi perusahaan AS, memberi veto atas pemilihan pemimpinnya, dan menerima intervensi militer demi “keamanan.” williamblum.org
Blum mencatat bahwa narasi heroik semacam itu telah mempengaruhi cara orang Amerika memandang dunia — bahwa negara mereka tidak hanya paling kuat, tetapi juga paling baik. Namun sejarah yang ia ulas dalam pendahuluan menggugah kita untuk mempertanyakan hal itu. Ia mengungkapkan rincian serangkaian eksperimen militer pada pasukan AS sendiri — seperti penggunaan gas mustard dan lewisite pada tentara tanpa izin mereka — yang kemudian disangkal bertahun-tahun lamanya oleh Pentagon, menyisakan trauma yang tidak tertangani. williamblum.org
Kemudian, dengan narasi yang kuat dan dokumentatif, Blum menelusuri keputusan politik yang membawa dampak global: keterlibatan AS dalam perang di Afghanistan, dukungan terhadap kelompok mujahidin selama Perang Dingin, serta pernyataan Brzezinski bahwa keterlibatan itu dimaksudkan untuk melemahkan Uni Soviet. Faktanya, konsekuensi perang itu — dari ribuan korban sipil hingga lahirnya kelompok ekstrem — masih menghantui geopolitik saat ini. williamblum.org
Blum tidak menutup mata pada paradoks moral yang mengikat kebijakan luar negeri AS: sementara Amerika mengklaim diri sebagai penjaga kebebasan dan hak asasi manusia, tindakan pemerintahnya sering kali tampak bertentangan dengan prinsip tersebut. Ia menunjukkan bagaimana retorika “kemanusiaan” telah digunakan untuk membenarkan serangan militer yang menghasilkan kehancuran besar, tepat ketika media dan pejabat terlibat dalam narasi yang lebih mirip propaganda daripada pelaporan kritis. williamblum.org
Buku ini kemudian terstruktur sebagai semacam arsip kolektif tindakan AS yang kontroversial, berkat kerja Blum yang teliti: ia menyatukan klaim, statistik, kutipan pejabat, dan dokumentasi sejarah yang berlapis. Tetapi bahkan dari pendahuluan saja, kita dapat merasakan nada yang Blum ingin tekankan: bahwa kekuasaan tanpa akuntabilitas kerap menghasilkan tragedi, dan bahwa seringkali “kebijakan luar negeri yang baik” adalah label yang disematkan untuk menutupi motif ekonomi dan geopolitik yang jauh lebih rumit. williamblum.org
Relevansi Rogue State pada abad ke-21 tidak hanya soal kritik terhadap kebijakan luar negeri AS, tetapi juga soal bagaimana dominasi kekuatan global memengaruhi isu keberlanjutan planet. Dalam era perubahan iklim, migrasi masif akibat konflik, dan ketidaksetaraan ekonomi yang melebar, arah kebijakan luar negeri negara superpower tetap berpengaruh besar terhadap:
- Sumber daya alam dan ekosistem: intervensi militer sering merusak lanskap, polusi lingkungan, infrastruktur pertanian, dan keseimbangan ekologi di negara yang menjadi medan perang;
- Pembangunan berkelanjutan: bantuan pembangunan seringkali bersyarat dan memaksakan model globalisasi yang tidak ramah lingkungan;
- Perubahan iklim dan keadilan iklim: negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menjadi pihak yang paling rentan terhadap keputusan yang diambil oleh kekuatan besar, meskipun kontribusi historis mereka terhadap emisi global jauh lebih kecil.
Kisah yang dibuka Blum — tentang bagaimana narasi moral digunakan untuk membenarkan tindakan agresif — mencerminkan tantangan global di mana narasi tentang “pertumbuhan ekonomi” dan “stabilitas” kadang menutupi dampak ekologis dan sosial yang merugikan rakyat di belahan dunia lain.
Pemikiran Blum dapat dikaitkan dengan analisis Noam Chomsky tentang imperialisme modern, terutama dalam Hegemony or Survival, yang menolak narasi bahwa hegemoni global sejati membawa kedamaian. Dan dalam tradisi Muslim intelektual seperti Ali Shariati, ada penekanan serupa bahwa kekuasaan yang tidak bertanggung jawab akan merusak martabat manusia dan keseimbangan sosial — baik secara internal maupun eksternal. William Blum bukan akademisi menara gading, bukan pula aktivis yang berteriak di jalanan. Ia adalah sesuatu yang lebih sunyi sekaligus lebih berbahaya bagi kekuasaan: seorang pengingat yang tekun.
Ours and Theirs: Kekerasan yang Disahkan, Kekerasan yang Dikutuk
William Blum membuka bagian ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana namun mengguncang: mengapa terorisme begitu sering “memilih” Amerika Serikat sebagai sasaran? (Why Do Terrorists Keep Picking on the United States?). Alih-alih menerima jawaban populer—bahwa Amerika dibenci karena kebebasan dan nilai-nilainya—Blum mengajak pembaca menelusuri arsip sejarah kebijakan luar negeri AS yang panjang dan berdarah. Dalam narasinya, terorisme tidak muncul sebagai kejahatan metafisis yang lahir dari kebencian irasional, melainkan sebagai reaksi historis terhadap intervensi politik, militer, dan ekonomi yang berulang.
Blum menulis dengan nada ironis bahwa Washington sering terkejut ketika kekerasan “kembali pulang”, padahal selama puluhan tahun kebijakan luar negeri Amerika telah menjadikan kekerasan sebagai instrumen yang sah. Dalam logika negara adidaya, pemboman disebut “intervensi kemanusiaan”, sementara pembalasan terhadapnya disebut “terorisme”. Inilah garis pemisah yang terus-menerus digeser: kekerasan mereka adalah kebrutalan; kekerasan kita adalah kebijakan.
Narasi ini mencapai titik krusial ketika Blum membahas Afghanistan dalam America’s Gift to the World—the Afghan Terrorist Alumni. Di sini, ia menunjukkan bagaimana Amerika Serikat—melalui CIA dan kerja sama dengan Pakistan serta Arab Saudi—secara sistematis melatih, mempersenjatai, dan mengideologisasi kelompok militan Islam selama perang melawan Uni Soviet. Para pejuang ini, yang kemudian dikenal sebagai “alumni Afghanistan”, tidak hanya dilatih secara militer tetapi juga dipoles sebagai simbol perlawanan heroik. Namun setelah Perang Dingin berakhir, mereka berubah status: dari “pejuang kebebasan” menjadi “teroris internasional”.
Penulis yang lahir di New York pada 1933 dan sempat bekerja di jantung sistem yang kelak ia bongkar—Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini menegaskan bahwa transformasi ini bukan perubahan moral, melainkan perubahan kepentingan geopolitik. Amerika, tulisnya, tidak pernah benar-benar bermasalah dengan terorisme; yang dipermasalahkan adalah siapa yang mengendalikannya dan ke arah mana senjatanya diarahkan. Pandangan ini menjadi benang merah yang menjalin seluruh bagian Ours and Theirs.
Dalam pembahasan tentang Assassinations, Blum menyingkap sejarah panjang pembunuhan politik yang didukung atau diorkestrasi oleh Amerika Serikat—dari Iran, Kongo, Vietnam, hingga Amerika Latin. Ia menunjukkan bahwa pembunuhan target politik telah lama dilembagakan sebagai alat kebijakan luar negeri, meskipun secara terbuka dikecam jika dilakukan oleh aktor non-negara. Blum menulis dengan getir bahwa apa yang disebut “teror” ketika dilakukan oleh individu, berubah menjadi “operasi rahasia” ketika dilakukan oleh negara.
Kekerasan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam Excerpts from US Army and CIA Training Manuals, Blum mengutip dokumen pelatihan resmi yang mengajarkan teknik intimidasi, pemerasan, infiltrasi, hingga eliminasi lawan politik. Manual-manual ini, yang digunakan untuk melatih militer dan paramiliter di negara-negara klien AS, menjadi bukti tertulis bahwa praktik-praktik yang secara publik dikecam—teror, penyiksaan, pembunuhan—justru diajarkan secara sistematis. Di sini, arsip menjadi saksi bisu kemunafikan kekuasaan.
Pembahasan tentang Torture memperdalam ironi tersebut. Blum menunjukkan bahwa meskipun Amerika secara retoris menolak penyiksaan, praktik ini terus berlangsung—baik secara langsung maupun melalui “outsourcing” ke rezim sekutu. Penyiksaan menjadi bagian dari rantai intelijen global, di mana penderitaan manusia diperlakukan sebagai variabel teknis. Blum tidak menulis dengan kemarahan berapi-api, melainkan dengan ketenangan dokumenter yang justru membuat narasinya lebih mengerikan: penyiksaan bukan penyimpangan, melainkan prosedur.
Narasi kemudian bergerak ke The Unsavories dan Training New Unsavories, istilah Blum untuk para diktator, jenderal brutal, dan pelanggar HAM yang didukung Amerika selama mereka “berguna”. Dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara, Washington secara konsisten bersekutu dengan rezim yang melakukan pembantaian massal, selama rezim tersebut anti-komunis atau pro-investasi Barat. Blum menekankan bahwa pelanggaran HAM bukanlah harga yang “terpaksa” dibayar, melainkan sering kali konsekuensi yang diterima dengan sadar.
Konsep ini mencapai puncaknya dalam War Criminals: Theirs and Ours. Blum menguliti standar ganda yang tajam: musuh diadili di pengadilan internasional, sementara sekutu—dan Amerika sendiri—kebal dari akuntabilitas. Ia menulis bahwa istilah “penjahat perang” adalah kategori politik, bukan hukum universal. Keadilan internasional, dalam praktiknya, tunduk pada kekuatan militer dan ekonomi.
Bab ini ditutup dengan salah satu contoh paling mengganggu dalam buku ini: Supporting Pol Pot. Blum mengungkap bahwa setelah rezim Khmer Merah bertanggung jawab atas kematian sekitar dua juta orang di Kamboja, Amerika Serikat tetap mendukung keberadaan Pol Pot di forum internasional—bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kalkulasi geopolitik melawan Vietnam dan Uni Soviet. Di sini, absurditas moral mencapai titik nadir: pelaku genosida didukung demi “keseimbangan kekuatan”.
Pengalaman singkat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu, terutama pada awal 1960-an, justru menjadi titik balik. Ketika ia menyaksikan bagaimana kebijakan luar negeri Amerika dijalankan bukan demi demokrasi, melainkan demi kepentingan geopolitik dan korporasi, ia memilih keluar dan berbalik arah.
Sejak saat itu, hidup Blum diabdikan untuk satu proyek besar: mendokumentasikan intervensi Amerika Serikat di seluruh dunia—kudeta, perang rahasia, sabotase politik, pembunuhan, dan manipulasi ekonomi—dengan ketekunan seorang arsiparis dan keteguhan seorang moralist sekuler. Ia menulis dengan gaya lugas, hampir tanpa retorika, seolah berkata: biarkan fakta-fakta itu sendiri yang menuduh.
Terorisme sebagai Cermin
Melalui bagian Ours and Theirs, William Blum tidak sekadar menyusun dakwaan terhadap Amerika Serikat. Ia membangun sebuah cermin sejarah, tempat pembaca—khususnya pembaca dari negara kuat—dipaksa melihat wajah kekerasan yang sering disangkal. Terorisme, dalam analisis Blum, bukanlah anomali, melainkan produk sampingan dari kebijakan global yang menormalkan kekerasan selama dilakukan atas nama stabilitas, keamanan, dan kepentingan nasional.
Bab ini menantang kita untuk bertanya: siapa yang berhak mendefinisikan teror? Dan lebih jauh lagi: apakah dunia dapat berharap pada perdamaian selama kekuasaan global terus mempraktikkan moralitas ganda?
Jika pada bagian Ours and Theirs William Blum membongkar standar ganda dalam soal terorisme dan pelanggaran HAM, maka dalam bagian United States Use of Weapons of Mass Destruction ia melangkah lebih jauh—ke wilayah yang lebih gelap, lebih sunyi, dan sering kali lebih dilupakan: kekerasan berskala masif yang dilembagakan, dinormalisasi, dan dibungkus sebagai keniscayaan sejarah. Blum memaparkan tentang senjata pemusnah massal ketika kekerasan menjadi sistem.
Blum membuka bagian ini dengan kenyataan yang jarang diucapkan secara jujur: Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah menggunakan senjata pemusnah massal secara langsung terhadap populasi sipil. Namun alih-alih menjadi catatan penyesalan yang membentuk etika global, fakta ini justru tenggelam dalam narasi kemenangan dan pembebasan.
Dalam pembahasan Bombings, Blum membawa pembaca kembali ke Perang Dunia II—ke Hiroshima dan Nagasaki—bukan sebagai peristiwa heroik yang “mengakhiri perang”, melainkan sebagai eksperimen kekuatan mutlak. Ia mengutip perdebatan internal di kalangan ilmuwan dan pejabat militer yang sejak awal telah mengetahui bahwa Jepang nyaris menyerah, dan bahwa pengeboman atom lebih dimaksudkan sebagai pesan geopolitik kepada Uni Soviet. Dengan gaya dingin dan berbasis arsip, Blum menunjukkan bahwa kehancuran dua kota dan ratusan ribu nyawa sipil diperlakukan sebagai variabel strategis.
Namun narasi Blum tidak berhenti pada bom atom. Ia mengingatkan bahwa pemboman konvensional Amerika—dari Dresden hingga Vietnam, Laos, Kamboja, Irak, dan Afghanistan—sering kali menimbulkan kehancuran yang secara fungsional tidak jauh berbeda dari senjata pemusnah massal. Dalam statistik yang nyaris tak terbaca oleh emosi manusia, Blum mencatat jutaan korban sipil, kota-kota yang diratakan, dan lanskap ekologis yang hancur selama generasi. Bom bukan hanya alat perang, tetapi alat pembentuk dunia pascaperang.
Kekerasan ini menjadi lebih sunyi namun lebih panjang dampaknya ketika Blum membahas Depleted Uranium. Senjata ini, yang digunakan secara luas dalam Perang Teluk dan konflik-konflik berikutnya, meninggalkan warisan yang tidak meledak, tidak terbakar, dan tidak selesai saat perang usai. Uranium terdeplesi menyusup ke tanah, air, dan tubuh manusia—meningkat-kan kanker, cacat lahir, dan kerusakan genetik. Blum mencatat bagaimana pemerintah Amerika secara konsisten menolak mengakui dampak ini, meskipun laporan medis dan lingkungan dari Irak dan Balkan terus menumpuk. Di sini, perang berubah menjadi kondisi biologis yang diwariskan lintas generasi.
Narasi serupa muncul dalam pembahasan Cluster Bombs. Blum menggambarkan bom-bom ini sebagai “perang yang tertunda”, karena sebagian besar korban bukan jatuh saat konflik berlangsung, melainkan bertahun-tahun kemudian—anak-anak yang mengira sisa bom sebagai mainan, petani yang menggarap ladang, atau keluarga yang kembali ke rumah yang tak lagi aman. Dalam arsip yang ia kutip, Blum menunjukkan bahwa Amerika mengetahui sepenuhnya risiko ini, namun tetap memproduksi dan menggunakannya secara luas. Kematian, dalam konteks ini, tidak lagi menjadi akibat sampingan, melainkan probabilitas yang diterima.
Bagian ini semakin mengerikan ketika Blum memasuki wilayah United States Use of Chemical and Biological Weapons Abroad. Ia menelusuri penggunaan Agent Orange di Vietnam—herbisida yang merusak hutan, tanah, dan tubuh manusia secara permanen. Blum tidak hanya mencatat jumlah korban, tetapi juga dampak ekologis yang mengubah hubungan manusia dengan tanahnya sendiri. Hutan yang mati, sungai yang tercemar, dan generasi yang lahir dengan cacat menjadi saksi bahwa perang modern bukan hanya membunuh musuh, tetapi juga masa depan.
Yang membuat narasi ini semakin menghantui adalah ketika Blum menunjukkan bahwa praktik serupa juga terjadi at Home. Dalam United States Use of Chemical and Biological Weapons at Home, ia mengungkap eksperimen rahasia terhadap warga Amerika sendiri—penyebaran zat kimia dan biologis di kota-kota, pengujian pada tentara dan warga sipil tanpa persetujuan mereka, serta penyangkalan sistematis setelahnya. Negara, dalam konteks ini, tidak hanya melukai “yang lain”, tetapi juga menguji batas etika terhadap rakyatnya sendiri.
Bagian ini mencapai dimensi geopolitik yang lebih luas dalam Encouragement of the Use of CBW by Other Nations. Blum menunjukkan bahwa Amerika tidak hanya menggunakan senjata kimia dan biologis, tetapi juga mendorong, melatih, atau menutup mata terhadap penggunaannya oleh negara lain selama selaras dengan kepentingannya. Dari Irak Saddam Hussein hingga sekutu-sekutu lain, senjata pemusnah massal berubah menjadi alat yang fleksibel—dikecam atau ditoleransi tergantung siapa yang memegangnya.
Kekerasan yang Tidak Pernah Netral
Melalui bagian United States Use of Weapons of Mass Destruction, William Blum membangun argumen yang konsisten dan menghantui: senjata pemusnah massal bukan penyimpangan dari tatanan internasional, melainkan produk logis dari sistem kekuasaan yang menempatkan dominasi di atas kehidupan. Kekerasan, dalam skala ini, tidak lagi bersifat emosional atau reaktif, tetapi administratif—diukur, disetujui, dan dilupakan.
Blum tidak menulis untuk membangkitkan rasa bersalah semata, melainkan untuk mengganggu amnesia kolektif. Ia menantang pembaca untuk melihat bahwa masa depan dunia—termasuk isu keberlanjutan, kesehatan global, dan keadilan ekologis—tidak dapat dilepaskan dari sejarah penggunaan kekerasan berskala massal ini. Lingkungan yang rusak, tubuh yang sakit, dan masyarakat yang trauma adalah arsip hidup dari kebijakan masa lalu. Karya puncaknya, Rogue State, adalah ringkasan padat dari puluhan tahun risetnya. Buku ini bukan pamflet ideologis, melainkan katalog panjang tentang bagaimana kekuasaan bekerja ketika ia merasa kebal hukum. Blum tidak tertarik pada spekulasi; ia mengumpulkan dokumen, laporan resmi, arsip media, dan kesaksian sejarah. Dalam tradisi ini, ia lebih dekat dengan sejarawan seperti Howard Zinn dan pemikir kritis seperti Noam Chomsky, meskipun gayanya jauh lebih kering dan tanpa kompromi.
Blum juga menulis Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, yang menjadi rujukan utama bagi banyak peneliti Global South. Ia hidup sederhana, jauh dari pusat kekuasaan dan sorotan media arus utama. Ketika meninggal dunia pada 2018, ia tidak meninggalkan institusi atau murid formal, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih sulit dihancurkan: arsip ingatan tentang kekerasan negara yang tidak bisa lagi dengan mudah disangkal.
Negara Nakal di Tengah Dunia: Kekuasaan Tanpa Cermin
Pada bagian A Rogue State versus the World, William Blum membawa pembaca keluar dari medan perang yang kasatmata—bom, senjata kimia, dan kehancuran fisik—menuju wilayah yang lebih halus namun tak kalah mematikan: arsitektur kekuasaan global yang bekerja melalui intervensi, manipulasi, pengawasan, dan impunitas. Jika bagian-bagian sebelumnya memperlihatkan bagaimana kekerasan dijalankan, maka di sini Blum menunjukkan bagaimana kekerasan itu dinormalisasi, disangkal, dan dilembagakan sebagai kebijakan luar negeri.
Dalam A Concise History of United States Global Interventions, 1945 to the Present, Blum menyajikan sebuah katalog sejarah yang nyaris tak terbayangkan panjangnya. Dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara, dari Timur Tengah hingga Afrika, intervensi Amerika Serikat muncul bukan sebagai pengecualian, melainkan sebagai pola. Kudeta, operasi rahasia, invasi terbuka, embargo ekonomi, dan perang proksi berulang dengan motif yang hampir selalu sama: menjaga kepentingan strategis, mengamankan sumber daya, dan mencegah alternatif sistem—terutama yang menantang kapitalisme Amerika—bertumbuh. Blum menulis sejarah ini bukan dengan retorika kemarahan, melainkan dengan ketenangan arsip, seolah ingin menunjukkan bahwa yang paling mengerikan dari kekerasan ini adalah betapa rutinnya ia terjadi.
Rutinitas itu berlanjut dalam Perverting Elections, ketika Blum memperlihatkan bagaimana demokrasi—nilai yang paling sering diklaim Amerika sebagai misinya—justru menjadi alat manipulasi. Ia mengisahkan pemilihan umum yang “dibantu”, “diarahkan”, atau “dikoreksi” melalui pendanaan, propaganda, tekanan ekonomi, hingga operasi rahasia. Demokrasi, dalam praktik ini, bukan soal kedaulatan rakyat, melainkan hasil yang dapat diterima Washington. Blum menunjukkan bahwa intervensi elektoral tidak selalu membutuhkan tank; sering kali cukup dengan uang, konsultan, dan narasi.
Di sinilah Trojan Horse: The National Endowment for Democracy mengambil peran sentral. Blum membedah bagaimana lembaga yang secara resmi mempromosikan demokrasi justru berfungsi sebagai kelanjutan dari operasi rahasia CIA dalam bentuk yang lebih dapat diterima publik. Dengan bahasa yang tajam namun terukur, ia memperlihatkan bagaimana pendanaan “masyarakat sipil” dan “pelatihan demokrasi” sering kali menjadi cara untuk membentuk lanskap politik negara lain sesuai kepentingan Amerika. Kuda Troya ini datang bukan dengan senjata, melainkan dengan proposal dan seminar.
Ketegangan antara citra moral dan praktik kekuasaan mencapai panggung global dalam The US versus the World at the United Nations. Blum menunjukkan bagaimana Amerika Serikat, yang sering berbicara tentang tatanan internasional berbasis aturan, justru menjadi salah satu pelanggar paling konsisten terhadap resolusi PBB—terutama ketika menyangkut Israel, perang, dan sanksi. Hak veto menjadi alat untuk membekukan akuntabilitas, dan PBB berubah dari forum kolektif menjadi arena tarik-menarik kepentingan sepihak.
Sementara itu, dalam Eavesdropping on the Planet, Blum membawa pembaca ke dunia pengawasan global. Ia menelusuri bagaimana Amerika memata-matai sekutu dan lawan, warga negara sendiri dan dunia internasional, menciptakan lanskap di mana privasi menjadi ilusi. Pengawasan ini bukan sekadar soal keamanan, tetapi tentang kendali informasi sebagai bentuk kekuasaan modern. Dunia, dalam narasi ini, berubah menjadi ruang dengar raksasa, dan kedaulatan negara-negara lain menjadi relatif.
Kekuasaan ini mengambil bentuk yang lebih kasar dalam Kidnapping and Looting, ketika Blum mengungkap praktik penculikan lintas negara, extraordinary rendition, dan perampasan aset. Hukum internasional diperlakukan sebagai rintangan, bukan batas. Orang-orang “menghilang”, negara-negara dilewati, dan keadilan ditunda tanpa batas waktu. Di sini, negara adidaya bertindak seolah hukum adalah sesuatu yang berlaku bagi orang lain.
Salah satu bagian paling simbolik muncul dalam How the CIA Sent Nelson Mandela to Prison for 28 Years. Blum menelusuri bagaimana ikon perjuangan anti-apartheid dunia pernah dicap sebagai teroris, dan bagaimana intelijen Amerika berperan dalam penangkapannya. Kisah ini bukan sekadar tentang Mandela, melainkan tentang bagaimana sejarah moral sering ditulis ulang setelah kemenangan diraih. Musuh hari ini dapat menjadi pahlawan esok hari—tanpa pernah ada permintaan maaf.
Kemunafikan struktural ini semakin nyata dalam The CIA and Drugs: Just Say “Why Not?”. Blum menyusun bukti bagaimana perdagangan narkoba sering kali ditoleransi, bahkan difasilitasi, selama ia mendanai operasi rahasia atau mendukung sekutu strategis. Perang melawan narkoba, dalam perspektif ini, menjadi perang selektif—keras terhadap yang lemah, lunak terhadap yang berguna.
Semua ini bermuara dalam Being the World’s Only Superpower Means Never Having to Say You’re Sorry. Blum merangkum kondisi psikologis sebuah kekaisaran yang tidak terbiasa bertanggung jawab. Tidak ada pengadilan internasional yang sungguh-sungguh menjerat, tidak ada reparasi yang memadai, tidak ada penyesalan institusional. Impunitas menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah menjadi identitas.
Pertanyaan mendasar muncul dalam The United States Invades, Bombs and Kills for It… but Do Americans Really Believe in Free Enterprise?. Blum mempertanyakan kontradiksi antara retorika pasar bebas dan praktik intervensi militer untuk melindungi kepentingan korporasi. “Kebebas-an” yang diperjuangkan sering kali bukan kebebasan rakyat, melainkan kebebasan modal untuk bergerak tanpa hambatan.
Akhirnya, dalam A Day in the Life of a Free Country, Blum menutup bagian ini dengan ironi yang pahit. Kehidupan sehari-hari di negara “bebas” digambarkan berdampingan dengan penjara massal, pengawasan, propaganda, dan ketidaktahuan yang terstruktur. Kebebasan, dalam konteks ini, menjadi kata yang sering diucapkan tetapi jarang diperiksa.
Kekuasaan Tanpa Penyesalan: Superpower yang Tak Pernah Belajar Menunduk
Pada Bab 25, Being the World’s Only Superpower Means Never Having to Say You’re Sorry, William Blum sampai pada inti psikologi kekuasaan Amerika Serikat. Di sini, kritiknya tidak lagi semata-mata historis atau faktual, melainkan eksistensial. Ia menggambarkan sebuah negara yang, karena posisinya sebagai satu-satunya adidaya pasca–Perang Dingin, hidup dalam kondisi yang nyaris tidak pernah menuntut refleksi diri. Kesalahan tidak perlu diakui, karena tidak ada otoritas yang cukup kuat untuk menuntut pengakuan itu. Dalam dunia seperti ini, impunitas bukan penyimpangan, melainkan struktur.
Blum menunjukkan bahwa tidak adanya permintaan maaf resmi—atas kudeta, perang, pembantaian sipil, atau penghancuran negara lain—bukanlah soal lupa atau kebetulan diplomatik. Ia adalah konsekuensi logis dari sebuah tatanan global di mana kekuasaan tertinggi tidak memiliki cermin. Permintaan maaf mengandaikan kesetaraan moral; sementara status superpower justru dibangun di atas asumsi bahwa Amerika berada di atas hukum yang ia tuntut untuk ditaati orang lain. Maka, tragedi-tragedi internasional berulang tanpa rekonsiliasi, dan sejarah bergerak maju dengan luka yang tidak pernah ditutup.
Dalam bab ini, Blum juga menyentuh dimensi domestik: bagaimana masyarakat Amerika sendiri jarang diajak untuk benar-benar menghadapi konsekuensi kebijakan luar negeri negaranya. Ketidaktahuan bukan sekadar akibat kurang informasi, melainkan hasil dari ekosistem media dan pendidikan yang meminimalkan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam logika ini, penyesalan dianggap kelemahan, dan kritik internal mudah dicap sebagai tidak patriotik. Kekuasaan, dengan demikian, menjadi kebiasaan yang kebal terhadap rasa bersalah.
Bab 26—The United States Invades, Bombs and Kills for It… but Do Americans Really Believe in Free Enterprise?—membongkar paradoks yang menjadi jantung ideologi Amerika modern. Di satu sisi, Amerika mengklaim diri sebagai pembela pasar bebas dan persaingan terbuka. Di sisi lain, Blum menunjukkan bagaimana kekuatan militer, sanksi, dan intervensi politik digunakan secara sistematis untuk menjamin bahwa “pasar bebas” hanya bebas bagi pihak-pihak yang sejalan dengan kepentingan Amerika.
Blum mengajak pembaca melihat bahwa perang dan invasi sering kali tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi: perlindungan korporasi besar, akses terhadap sumber daya, atau pencegahan munculnya model ekonomi alternatif. Dalam konteks ini, “free enterprise” kehilangan makna normatifnya dan berubah menjadi retorika legitimasi. Negara-negara yang memilih jalan berbeda—nasionalisasi, sosialisme, atau kemandirian ekonomi—sering kali menjadi target tekanan atau kekerasan, bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka berhasil tanpa izin.
Pertanyaan Blum sangat mendasar dan mengganggu: jika pasar benar-benar bebas, mengapa ia harus dipertahankan dengan bom? Jika demokrasi benar-benar unggul, mengapa ia membutuh-kan kudeta? Bab ini memperlihatkan bahwa kekerasan negara bukanlah anomali dalam kapital-isme global versi Amerika, melainkan instrumen pendukungnya. Dengan kata lain, pasar bebas yang dibayangkan tidak pernah sepenuhnya dilepaskan dari laras senjata. Kemudian, dalam Bab 27, A Day in the Life of a Free Country, Blum menutup bukunya dengan ironi yang tenang namun menghantam. Ia mengajak pembaca menyusuri kehidupan sehari-hari di negara yang menyebut dirinya paling bebas di dunia. Tidak ada ledakan besar, tidak ada deklarasi perang—hanya rutinitas. Namun justru di sanalah kebebasan diuji.
Blum menggambarkan sebuah masyarakat yang hidup di bawah pengawasan, propaganda, dan ketimpangan struktural, tetapi tetap diyakinkan bahwa mereka bebas. Kebebasan dipersempit menjadi pilihan konsumsi, bukan partisipasi politik yang bermakna. Media berlimpah, tetapi narasi sempit. Hak formal ada, tetapi substansi sering hilang. Dalam “hari biasa” itu, perang terjadi jauh di luar pandangan, atas nama keamanan, tanpa keterlibatan sadar dari warga yang konon berdaulat.
Bab penutup ini bukan sekadar kritik terhadap Amerika, melainkan peringatan universal. Blum seakan mengatakan bahwa kebebasan yang tidak disertai kesadaran, tanggung jawab, dan empati global mudah berubah menjadi mitos yang nyaman. Sebuah negara dapat menyebut dirinya bebas, sambil secara simultan menyangkal kebebasan orang lain—dan bahkan tidak merasa perlu menjelaskan kontradiksi itu.
Kekuasaan, Kebisuan, dan Tanggung Jawab Sejarah
Dalam tiga bab terakhir ini, Rogue State mencapai kedalaman moralnya. William Blum tidak lagi sekadar mendokumentasikan apa yang dilakukan Amerika Serikat di dunia, tetapi memper-tanyakan jenis dunia apa yang dihasilkan oleh kekuasaan tanpa akuntabilitas. Superpower yang tidak pernah meminta maaf adalah superpower yang tidak pernah belajar. Dan dunia yang membiarkan hal itu terjadi adalah dunia yang ikut memikul akibatnya. Blum menutup bukunya bukan dengan seruan heroik, melainkan dengan kesunyian yang mengusik: bagaimana jika ketidakadilan global hari ini bukan kegagalan sistem, melainkan keberhasilannya? Dan jika demikian, keberanian terbesar bukanlah memenangkan perang, melainkan mengakui kesalahan.
Rogue State bukan sekadar buku tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Rogue State sebagai kritik atas sistem global modern. Ia adalah diagnosis sistemik tentang bagaimana tatanan global modern bekerja ketika kekuasaan militer, ekonomi, dan narasi ideologis menyatu tanpa penyeimbang yang efektif. William Blum tidak menulis sejarah sebagai arsip netral; ia menulisnya sebagai catatan moral dunia yang kehilangan mekanisme koreksi diri.
Dalam buku ini, Amerika Serikat tampil bukan sebagai penyimpangan dari sistem internasional, melainkan sebagai produk paling matang dari sistem itu sendiri—sebuah sistem yang meng-gabungkan kapitalisme global, militerisme, dan legitimasi moral berbasis “demokrasi” serta “keamanan”. Dengan menelusuri kudeta, perang rahasia, intervensi ekonomi, manipulasi pemilu, dan dukungan terhadap rezim represif, Blum memperlihatkan bahwa apa yang sering disebut “tatanan internasional berbasis aturan” sejatinya adalah tatanan berbasis kekuasaan yang selektif.
Dalam dunia Blum, hukum internasional tidak gagal—ia bekerja sebagaimana dirancang: melindungi yang kuat dan mendisiplinkan yang lemah. Yang disebut “negara nakal” bukanlah mereka yang paling banyak melanggar hukum, melainkan mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanggarnya tanpa konsekuensi.
Kita bisa sejenak membandingkan Blum dan Hannah Arendt: dari banalitas kejahatan ke banalitas kekuasaan. Hannah Arendt, dalam laporannya tentang Adolf Eichmann, memper-kenalkan konsep banality of evil—bahwa kejahatan besar sering dilakukan bukan oleh monster, melainkan oleh orang biasa yang taat prosedur dan berhenti berpikir. Blum memperluas intuisi ini ke tingkat geopolitik. Dalam Rogue State, kejahatan internasional bukan hasil niat jahat individual, melainkan produk rutin birokrasi kekuasaan.
Pemboman, sanksi yang melaparkan rakyat, dukungan terhadap penyiksaan, dan perang proksi tidak dilakukan oleh tokoh tunggal yang jahat, melainkan oleh rantai institusional yang bekerja “normal”: pejabat yang menandatangani dokumen, analis yang menulis memo, jurnalis yang mengulang siaran pers, dan warga yang menerima semuanya sebagai harga keamanan. Inilah banalitas versi global: kejahatan yang terjadi karena semua orang melakukan “pekerjaannya” dengan baik.
Seperti Arendt, Blum tidak hanya menuduh pelaku langsung, tetapi juga lingkungan yang memungkinkan ketidakberpikiran moral. Ketika kekuasaan tidak lagi dipertanyakan, dan ketika kepatuhan menggantikan penilaian etis, maka sistem itu sendiri menjadi mesin kejahatan—tanpa perlu aktor jahat yang sadar.
Blum dan Noam Chomsky mungkin akan bersepakat dalam meja diskusi yang panas dingin jika berbicara tentang Rogue State yang disodorkannya. Ini adalah soal kekuasaan, propaganda, dan persetujuan yang direkayasa. Jika Arendt membantu kita memahami dimensi moral, maka Noam Chomsky memberi kita alat untuk membaca dimensi ideologis dari kritik Blum. Rogue State sangat sejalan dengan tesis Chomsky tentang manufacturing consent: bahwa kekerasan global Amerika tidak bisa berlangsung tanpa rekayasa persetujuan domestik.
Blum menunjukkan bagaimana media arus utama, lembaga pendidikan, dan bahasa politik membentuk dunia simbolik tempat intervensi selalu “terpaksa”, korban selalu “tidak disengaja”, dan musuh selalu “mengancam”. Dalam narasi ini, Amerika tidak pernah menyerang—ia selalu “merespons”. Tidak pernah menjajah—ia “menstabilkan”. Tidak pernah melanggar hukum—ia “menjaga tatanan”.
Di sinilah Rogue State menjadi arsip tandingan: sebuah upaya merusak konsensus palsu dengan menghadirkan fakta-fakta yang sengaja dikeluarkan dari ingatan publik. Seperti Chomsky, Blum percaya bahwa kontrol atas narasi sama pentingnya dengan kontrol atas senjata. Tanpa dominasi wacana, dominasi material tidak akan bertahan lama.
Blum dan Ibn Khaldun: dinamika kekuasaan dan awal kemunduran. Jika Arendt dan Chomsky membantu kita membaca modernitas, Ibn Khaldun memberi perspektif jangka panjang tentang siklus peradaban. Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan mencapai puncaknya ketika solidaritas (‘asabiyyah) kuat, tetapi mulai runtuh ketika kekuasaan berubah menjadi kemewahan, impunitas, dan kehilangan batas moral.
Dari sudut pandang Khaldunian, Amerika Serikat dalam Rogue State tampak berada pada fase kekuasaan yang terlalu besar untuk dikoreksi, namun terlalu rapuh untuk direfleksikan. Ketika kekerasan menjadi rutin, ketika hukum hanya berlaku ke luar, dan ketika elite hidup terpisah dari konsekuensi tindakannya, maka kemunduran bukan soal “jika”, melainkan “kapan”.
Blum tidak menubuatkan kejatuhan, tetapi ia menyediakan gejala-gejalanya: perang tanpa akhir, musuh yang terus diciptakan, dan legitimasi yang semakin bergantung pada paksaan, bukan persetujuan. Dalam bahasa Ibn Khaldun, ini adalah tanda bahwa ‘asabiyyah telah digantikan oleh koersi.
Lantas apa makna bagi Global South: pelajaran bagi Indonesia? Bagi negara-negara Global South—termasuk Indonesia—Rogue State adalah buku peringatan. Ia mengingatkan bahwa dalam sistem global saat ini, kedaulatan bukanlah kondisi permanen, melainkan negosiasi terus-menerus dengan kekuatan besar. Demokrasi, HAM, dan pembangunan sering kali menjadi bahasa moral yang fleksibel—dipuji ketika sejalan, ditekan ketika menyimpang.
Bagi Indonesia, pelajarannya bukan sinisme, tetapi kewaspadaan strategis. Blum mengajarkan bahwa:
- Netralitas harus disertai kapasitas intelektual dan institusional.
- Kemandirian ekonomi adalah syarat utama kemandirian politik.
- Ingatan sejarah—tentang intervensi, utang, dan tekanan geopolitik—harus dijaga agar tidak diulang dalam bentuk baru.
Indonesia, seperti banyak negara Global South, berada di persimpangan antara menjadi subjek sejarah atau sekadar medan perebutan kepentingan. Dalam dunia yang digambarkan Blum, negara yang lupa sejarahnya akan mudah diyakinkan bahwa ketergantungan adalah kerja sama, dan dominasi adalah bantuan.
Catatan Akhir: Impunitas dan Ingatan Sejarah
Pada akhirnya, Rogue State adalah buku tentang impunitas—bukan hanya impunitas hukum, tetapi impunitas moral dan historis. Kekuasaan terbesar bukanlah yang paling banyak menghancurkan, melainkan yang paling berhasil menghapus jejak kehancurannya dari ingatan kolektif.
Ingatan sejarah adalah bentuk perlawanan paling sunyi namun paling tahan lama. Tanpa ingatan, tidak ada pembelajaran; tanpa pembelajaran, tidak ada pertobatan; dan tanpa pertobatan, kekerasan akan terus tampil sebagai kebijakan rasional. Blum menulis untuk melawan lupa. Ia menulis agar dunia tidak menerima kekuasaan tanpa pertanggungjawaban sebagai sesuatu yang normal.
Dalam dunia yang dikuasai oleh negara-negara yang “tidak pernah perlu meminta maaf”, tugas etis kita—sebagai warga global, sebagai bangsa-bangsa di pinggiran kekuasaan—adalah mengingat, mencatat, dan menolak normalisasi kejahatan. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah medan pertempuran makna tentang masa depan.
Dan mungkin, sebagaimana disiratkan Blum, keadilan global tidak akan lahir dari kekuatan terbesar, melainkan dari ingatan yang tidak mau tunduk.
Melalui A Rogue State versus the World, William Blum menyusun potret sebuah kekuasaan yang tidak sekadar dominan, tetapi mendefinisikan ulang norma global sambil menempatkan dirinya di luar norma itu sendiri. Negara nakal, dalam pengertian Blum, bukanlah negara yang melanggar hukum internasional sekali-dua kali, melainkan negara yang membentuk sistem di mana pelanggaran menjadi kebijakan.
Bagian ini memperluas kritik Blum dari soal kekerasan fisik menjadi kekerasan struktural—kekerasan terhadap kedaulatan, demokrasi, kebenaran, dan ingatan kolektif. Ia mengajak pembaca untuk melihat bahwa dunia yang kita huni hari ini—penuh ketidakstabilan, ketimpangan, dan krisis keberlanjutan—tidak lahir dari kekacauan semata, melainkan dari sejarah panjang intervensi yang jarang dipertanggungjawabkan.
William Blum dan Matt Kennard berasal dari generasi, gaya, dan konteks yang berbeda, tetapi karya mereka saling melengkapi. Dua Suara, Satu Ingatan Kolektif. Blum adalah penjaga memori jangka panjang, sementara Kennard adalah penyusup ke masa kini yang sedang berlangsung. Keduanya berbagi satu keyakinan mendasar: bahwa dunia tidak akan menjadi lebih adil jika kekerasan struktural terus disamarkan sebagai kebijakan normal.
Jika Blum mengajarkan kita pentingnya mengingat, Kennard mengajarkan kita keberanian untuk melihat dari dekat. Bersama-sama, mereka menyumbang pada satu proyek besar yang belum selesai: membangun kesadaran global bahwa kekuasaan, betapapun besarnya, harus tetap diingat, dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan.
Jakarta-Cirebon, 6 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Blum, W. (2002). Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower. Zed Books. williamblum.org
Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower. (n.d.). In Wikipedia. Wikipedia