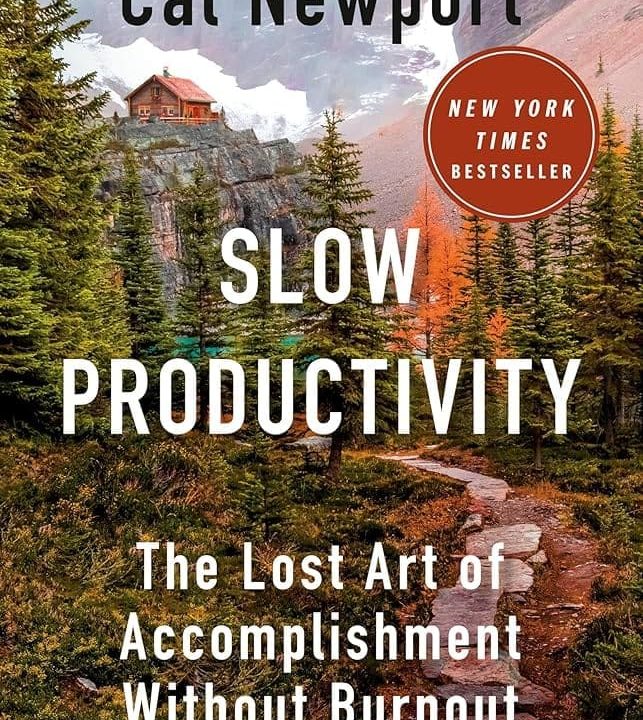Rubarubu #55
On Bicycles:
200 Tahun Mengayuhi New York
Mengayuh Kota: Sepeda dan Kehidupan Urban New York (1800–2000-an)
Pada awal abad ke-19, jauh sebelum mobil mendominasi jalanan, New York sudah mengenal kegilaan baru: sepeda. Evan Friss membuka kisahnya dengan adegan-adegan kota yang nyaris terlupakan—orang-orang berkerumun menyaksikan velocipede beroda kayu melintas di jalan berbatu Manhattan, anak-anak muda kelas menengah mempraktikkan teknologi baru yang menjanjikan kebebasan, kecepatan, dan otonomi personal. Dalam salah satu arsip yang dikutip Friss, seorang pengamat abad ke-19 mencatat bahwa sepeda adalah “alat yang membuat manusia percaya bahwa kota dapat dijinakkan oleh tubuhnya sendiri” (Friss, 2019).
Buku ini menelusuri dua abad sejarah sepeda di New York City, bukan sebagai garis lurus kemajuan, tetapi sebagai siklus naik-turun yang selalu terkait dengan perubahan kekuasaan, kelas sosial, gender, ras, dan imajinasi tentang kota modern. Sepeda, dalam narasi Friss, adalah cermin dari bagaimana sebuah kota memahami siapa yang berhak atas ruang jalan.
Pada akhir 1800-an, sepeda berkembang pesat seiring revolusi industri. Sepeda sebagai teknologi emansipasi (abad ke-19). Friss menunjukkan bahwa sepeda bukan sekadar alat rekreasi, melainkan teknologi sosial. Ia membuka mobilitas baru bagi perempuan—mendorong perubahan busana, kebiasaan sosial, dan bahkan diskursus feminisme awal. Susan B. Anthony, misalnya, pernah menyatakan bahwa sepeda “telah melakukan lebih banyak hal untuk emansipasi perempuan dibandingkan apa pun di dunia” (dikutip dalam Friss, 2019). Itulah bagian dari buku On Bicycles: A 200-Year History of Cycling in New York City karya Evan Friss (Columbia University Press, 2019).
Evan Friss, seorang sejarawan urban dan akademik Amerika yang mengkhususkan diri pada sejarah transportasi, kota, dan lingkungan, dengan fokus khusus pada peran sepeda dalam membentuk kehidupan perkotaan, membuka On Bicycles dengan sebuah pembalikan perspektif yang penting: ia menolak melihat sepeda hanya sebagai objek teknologi atau moda transportasi alternatif. Bagi Friss, sepeda adalah arsip bergerak—jejak sejarah yang terukir di jalan, trotoar, kebijakan publik, dan konflik sehari-hari kota New York. Sejak awal, ia menegaskan bahwa buku ini bukanlah kisah linear tentang “kemajuan” sepeda, melainkan cerita tentang perebutan ruang, makna, dan kekuasaan.
Dalam pengantar ini, Friss mengajak pembaca membayangkan New York bukan sebagai kota mobil yang “secara alami” kita kenal hari ini, melainkan sebagai ruang yang selalu diperebutkan. Jalan-jalan kota, sejak awal abad ke-19, adalah arena negosiasi antara berbagai tubuh: pejalan kaki, kusir kereta, pedagang kaki lima, anak-anak, dan kelak pesepeda. Dengan demikian, pertanyaan sentral buku ini bukan “kapan sepeda datang?”, melainkan “mengapa sepeda begitu sering dipinggirkan, lalu kembali, lalu dipinggirkan lagi?” Sepeda sebagai sejarah kota, bukan sekadar alat.
Friss menekankan bahwa sejarah sepeda adalah sejarah politik kota. Siapa yang dianggap pengguna jalan yang sah, siapa yang dianggap pengganggu, dan teknologi apa yang diberi prioritas selalu mencerminkan nilai dominan suatu era. Ia menunjukkan bahwa konflik sepeda hari ini—tentang bike lane, keselamatan, atau gentrifikasi—memiliki akar yang jauh lebih dalam daripada yang sering disadari.
Dalam pengantar ini pula, Friss memperkenalkan metodologinya: riset arsip yang luas, surat kabar lama, catatan hukum, foto, dan kisah warga biasa. Pendekatan ini membuat sepeda tampil bukan sebagai simbol abstrak, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari warga New York lintas kelas, ras, dan gender. Sepeda, dalam narasi Friss, adalah teknologi yang selalu “terlalu sederhana” untuk kekuatan besar, namun terlalu penting untuk diabaikan sepenuhnya.
Secara implisit, Introduction ini juga mengajukan pertanyaan etis: kota seperti apa yang ingin kita bangun? Kota yang dirancang untuk kecepatan dan akumulasi, atau kota yang memberi ruang bagi tubuh manusia, ritme lambat, dan perjumpaan sosial? Dengan cara ini, Friss menempatkan sejarah sepeda sebagai cermin krisis perkotaan modern.
Di New York, klub-klub sepeda bermunculan, jalur khusus mulai diperdebatkan, dan sepeda menjadi simbol warga kota modern yang aktif dan mandiri. Namun sejak awal pula, konflik muncul: antara pejalan kaki, kusir kereta, dan pesepeda; antara kelas pekerja dan elit; antara kebebasan individual dan ketertiban kota.
Salah satu kontribusi paling penting buku ini adalah menunjukkan bagaimana dominasi mobil bukanlah sesuatu yang “alami”, melainkan hasil keputusan politik, hukum, dan ekonomi pada abad ke-20. Jalanan, karena proses politik dan kekuasaan kemudian berangsur berubah: dari jalan milik publik ke jalan milik mobil. Friss menelusuri bagaimana pada awal 1900-an, sepeda secara perlahan disingkirkan dari pusat kota melalui regulasi lalu lintas, kampanye keselamatan yang bias, dan perubahan desain jalan.
Pada masa Robert Moses, perencana kota legendaris (dan kontroversial), New York dibangun ulang untuk mobil: jalan tol, parkiran, dan suburbanisasi. Sepeda direduksi menjadi mainan anak-anak atau alat rekreasi di taman, bukan sarana transportasi serius. Friss dengan tajam menunjukkan bahwa ini bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi pergeseran moral: dari kota sebagai ruang bersama menjadi kota sebagai mesin kecepatan.
Di sini buku Friss beresonansi dengan pemikir urban seperti Jane Jacobs, yang mengkritik kota modern karena mematikan kehidupan jalanan, dan Lewis Mumford, yang melihat teknologi transportasi sebagai pembentuk nilai peradaban, bukan alat netral. “Streets and their sidewalks are the main public places of a city.” —Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (1961)
Selain On Bicycles, Friss yang juga menulis “The Cycling City: Bicycles and Urban America in the 1890s” (University of Chicago Press, 2015), yang meneliti demam sepeda pertama di Amerika dan dampaknya terhadap kota-kota seperti Chicago, New York, dan Philadelphia, juga menyo-roti dimensi yang sering diabaikan: ras dan kelas. Dan sepeda dikayuh diantara keduanya. Pada paruh kedua abad ke-20, sepeda tetap hidup di komunitas pekerja, imigran, dan minoritas—kurir, pekerja informal, dan warga yang tidak terjangkau sistem transportasi mahal. Namun praktik ini kerap distigmatisasi: sepeda dipandang sebagai simbol kemiskinan, bukan pilihan sadar.
Narasi ini penting karena membongkar mitos bahwa “kebangkitan sepeda” di akhir abad ke-20 adalah fenomena baru. Yang berubah bukan keberadaan sepeda, melainkan siapa yang diizin-kan mengklaimnya secara simbolik. “The history of cycling is not just about bicycles; it is about power, access, and who gets to claim the streets.” —Evan Friss, On Bicycles (2019)
Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, sepeda kembali ke pusat perdebatan kota New York. Ini menandai kebangkitan kembali aktivisme, perhatian terhadap krisis lingkungan, dan kota berkelanjutan. Krisis lingkungan, kemacetan, dan ketimpangan transportasi melahir-kan gelombang baru aktivisme. Friss mengulas peran komunitas akar rumput, advokasi kebijak-an, hingga perubahan di era Walikota Michael Bloomberg—pembangunan bike lane, sistem bike-sharing, dan pengakuan sepeda sebagai bagian sah dari mobilitas kota.
Namun Friss tidak romantis. Ia menunjukkan bahwa kebijakan sepeda pun bisa menjadi bagian dari gentrifikasi hijau: jalur sepeda yang indah sering hadir bersamaan dengan naiknya harga sewa dan pengusiran warga lama. Sepeda, sekali lagi, menjadi arena konflik: antara keberlanjut-an dan keadilan sosial.
Tetapi sepeda bisa sebagai sebuah cara baru mendorong etika kota. Secara implisit, On Bicycles mengajukan tesis filosofis: cara sebuah kota memperlakukan sepeda mencerminkan nilai moralnya. Apakah kota dibangun untuk tubuh manusia atau untuk mesin? Untuk keber-samaan atau kecepatan? Untuk kehidupan sehari-hari atau akumulasi ekonomi?
Dalam semangat ini, buku Friss sejalan dengan pemikir seperti Ivan Illich, yang melihat sepeda sebagai teknologi yang menjaga skala manusiawi, serta Henri Lefebvre, dengan gagasan right to the city—hak warga untuk membentuk ruang hidupnya sendiri. Dalam tradisi Islam, resonansi etis ini dapat dibaca melalui konsep maslahah (kemaslahatan publik) dan mizan (keseimbang-an). Kota yang memberi ruang bagi sepeda adalah kota yang mengakui keseimbangan antara tubuh, lingkungan, dan kehidupan sosial—bukan semata efisiensi ekonomi.
Pada Awalnya Adalah Ejekan
Bab pertama, “Rough Start”, membawa pembaca ke awal abad ke-19, ketika sepeda—dalam bentuk awalnya yang masih kasar dan eksperimental—pertama kali muncul di New York. Tidak ada sambutan heroik atau visi utopis. Yang ada justru kekacauan, ejekan, dan kecelakaan.
Friss menggambarkan bagaimana velocipede dan draisine, nenek moyang sepeda modern, memasuki kota yang jalannya masih dipenuhi lumpur, batu besar, kotoran kuda, dan lalu lintas yang tidak teratur. Sepeda awal ini berat, sulit dikendalikan, tanpa rem yang memadai, dan sering kali berbahaya. Surat kabar mencatat jatuhnya pengendara, bentrokan dengan pejalan kaki, dan kemarahan warga yang merasa ruangnya direbut oleh alat aneh yang melaju tanpa aturan jelas.
Di sini Friss menunjukkan bahwa sejak kelahirannya, sepeda langsung dicap sebagai masalah ketertiban umum. Bukan karena sifat alaminya, melainkan karena kota belum memiliki kerangka sosial dan hukum untuk menampung teknologi baru ini. Banyak pemerintah kota merespons dengan larangan, pembatasan, dan regulasi yang tidak konsisten. Sepeda dipandang sebagai hiburan eksentrik kaum muda atau kelas tertentu, bukan sebagai moda transportasi yang sah.
Namun yang menarik, Friss menolak membaca fase ini sebagai kegagalan. Justru dalam “awal yang kasar” ini terlihat pola yang akan berulang selama dua abad berikutnya: setiap kali sepeda muncul sebagai alternatif serius, ia akan diperlakukan sebagai penyimpangan. Konflik dengan pejalan kaki, tuduhan membahayakan keselamatan publik, dan stigmatisasi moral sudah hadir sejak awal. Bab ini juga memperlihatkan bagaimana sepeda sejak dini terkait dengan kelas sosial. Pada fase awal, hanya mereka yang memiliki waktu luang dan modal yang bisa mencoba teknologi baru ini. Hal ini memicu kecemburuan dan resistensi, tetapi sekaligus membuka ruang imajinasi baru tentang mobilitas personal—bahwa seseorang dapat bergerak cepat tanpa bergantung pada kuda atau angkutan umum.
Dengan pendekatan sejarah yang mendalam, Evan Friss memberikan konteks penting untuk memahami peran sepeda—bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi sebagai kekuatan yang terus-menerus membentuk dan merefleksikan kehidupan kota. Misalnya buku On Bycycles ini Friss dengan cermat menunjukkan bahwa resistensi terhadap sepeda bukan semata reaksi spontan, melainkan bagian dari proses sosial yang lebih luas: kota selalu lambat mene-rima teknologi yang mengganggu tatanan lama. Jalanan New York saat itu bukan ruang netral, melainkan struktur sosial yang melayani kepentingan tertentu. Sepeda, dengan tubuh manusia sebagai mesinnya, mengganggu hierarki tersebut.
Di akhir bab, Friss menanamkan benih gagasan penting: bahwa kegagalan awal sepeda bukan karena ia tidak cocok dengan kota, tetapi karena kota belum siap membayangkan dirinya secara berbeda. Rough Start bukan hanya kisah tentang teknologi yang belum matang, tetapi tentang imajinasi urban yang masih sempit.
Dengan bagian awal ini Friss secara halus membangun argumen besar buku: bahwa sejarah sepeda adalah sejarah ketegangan antara kemungkinan dan kekuasaan. Sepeda sejak awal menawarkan bentuk mobilitas yang lebih setara, lebih manusiawi, dan lebih murah. Justru karena itu, ia sering dianggap ancaman. Dalam konteks hari ini—ketika sepeda kembali dipromosikan sebagai solusi krisis iklim—Friss mengingatkan bahwa tanpa perubahan struktur sosial dan politik kota, sepeda akan terus mengalami siklus marginalisasi yang sama. Awal yang kasar itu, pada dasarnya, belum pernah benar-benar berakhir.
Friss kemudian pada Bab Up and Down membawa pembaca memasuki akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, periode ketika sepeda mengalami lonjakan popularitas yang dramatis di New York—sebuah “boom” yang disertai dengan kecemasan sosial yang tak kalah besar. Sepeda tidak lagi sekadar mainan eksentrik, tetapi menjadi fenomena massal yang mengubah ritme kota, gaya berpakaian, hingga relasi gender.
Friss menggambarkan era ini sebagai momen ketika sepeda menjadi simbol kebebasan individual. Teknologi sepeda yang semakin ringan dan stabil memungkinkan lebih banyak orang—termasuk perempuan dan kelas pekerja—untuk bergerak lebih jauh dan lebih mandiri. Sepeda memberi tubuh kebebasan baru dari jadwal transportasi umum dan ketergantungan pada kuda atau kereta. Di jalan-jalan New York, sepeda menghadirkan kemungkinan mobilitas yang lebih demokratis.
Namun, Friss menunjukkan bahwa setiap kebebasan baru selalu memicu reaksi balik. Populari-tas sepeda segera disertai dengan kepanikan moral. Surat kabar dan otoritas kota mulai meng-gambarkan pesepeda sebagai sembrono, tidak bermoral, bahkan berbahaya bagi tatanan sosial. Kritik terhadap pesepeda perempuan menjadi sangat tajam, karena sepeda dianggap merusak norma kesopanan dan peran gender tradisional. Dalam narasi Friss, sepeda tidak hanya meng-ganggu lalu lintas, tetapi juga mengganggu imajinasi sosial tentang siapa yang berhak bergerak bebas.
Bab ini juga memperlihatkan bagaimana sepeda naik dan turun seiring perubahan teknologi dan kebijakan. Ketika mobil mulai diperkenalkan dan jalan-jalan diaspal untuk kecepatan yang lebih tinggi, sepeda perlahan tersingkir. Friss menekankan bahwa penurunan ini bukan akibat “kemajuan alamiah”, melainkan hasil keputusan politik dan ekonomi yang secara sistematis memprioritaskan kendaraan bermotor.
“Up and Down” dengan demikian menjadi kisah tentang siklus berulang: sepeda muncul sebagai solusi, diterima secara luas, lalu disingkirkan ketika dianggap mengganggu kepentingan yang lebih besar. Friss memperlihatkan bahwa ketidakstabilan posisi sepeda dalam kota modern adalah tanda dari ketegangan mendasar antara mobilitas berbasis manusia dan logika pertumbuhan berbasis mesin.
Bab “Moses” adalah salah satu bagian paling politis dalam buku ini. “Kota untuk mobil, bukan untuk tubuh,” tulisnya. Di sini Friss memusatkan perhatian pada Robert Moses, arsitek utama infrastruktur New York abad ke-20, yang visinya tentang kota hampir sepenuhnya menyingkir-kan sepeda dan pejalan kaki. Friss tidak menggambarkan Moses sebagai tokoh satu dimensi, melainkan sebagai perwujudan zaman. Moses percaya pada skala besar, kecepatan, dan kontrol teknokratis. Jalan raya, jembatan, dan taman yang ia bangun didesain untuk mobil dan untuk aliran cepat, bukan untuk perjumpaan manusia. Dalam visi ini, sepeda tampak seperti sisa masa lalu yang tidak efisien, tidak modern, dan tidak produktif.
Bab ini menunjukkan bagaimana keputusan Moses secara sistematis menghapus sepeda dari lanskap kota. Jalur hijau berubah menjadi jalan raya. Ruang publik diatur ulang agar mengalir-kan mobil secepat mungkin. Sepeda, jika muncul, dianggap sebagai penghalang atau anomali. Friss menekankan bahwa ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan ontologis tentang apa itu kota: dari ruang hidup menjadi mesin pergerakan.
Yang penting, Friss mengaitkan visi Moses dengan ketimpangan sosial. Infrastruktur yang dibangun Moses sering kali mengorbankan komunitas miskin dan minoritas, memecah lingkungan, dan memperparah segregasi. Dalam konteks ini, sepeda—yang berpotensi menjadi alat mobilitas murah dan inklusif—tidak hanya diabaikan, tetapi secara implisit dianggap tidak sesuai dengan kota yang berorientasi pada kelas menengah pemilik mobil.
Bab “Moses” memperlihatkan bagaimana hilangnya sepeda bukan karena ia tidak berguna, tetapi karena ia tidak cocok dengan ideologi modernitas tertentu. Sepeda menjadi korban dari keyakinan bahwa kemajuan harus berarti lebih besar, lebih cepat, dan lebih bermesin.
Friss membawa argumennya ke titik ekstrem ketika Ia mengulas tentang kebijakan sepeda menjadi ilegal: momen ketika sepeda secara resmi dilarang atau sangat dibatasi di ruang-ruang tertentu di New York. Larangan ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan sebagai klimaks dari dekade-dekade stigmatisasi dan marginalisasi. Friss menelusuri bagaimana kebijakan pelarang-an sepeda sering dibenarkan atas nama keselamatan publik, ketertiban, dan efisiensi lalu lintas. Namun, ia menunjukkan bahwa argumen-argumen ini jarang diterapkan secara simetris. Mobil—yang secara statistik jauh lebih berbahaya—justru diberi ruang lebih besar. Sepeda menjadi kambing hitam karena tubuh pesepeda terlihat, rentan, dan mudah disalahkan.
Bab ini juga mengungkap dimensi kelas dari larangan sepeda. Ketika sepeda diasosiasikan dengan kemiskinan atau ketidakmampuan membeli mobil, pembatasan terhadap sepeda secara efektif menjadi pembatasan terhadap mobilitas kelompok tertentu. Friss menekankan bahwa larangan sepeda bukan hanya soal transportasi, tetapi tentang siapa yang dianggap layak berada di ruang publik. Namun, Friss tidak menutup bab ini dengan nada pesimistis total. Ia mencatat bahwa setiap larangan selalu memicu perlawanan. Komunitas pesepeda, aktivis, dan warga kota terus menuntut hak atas jalan. Dalam resistensi-resistensi kecil ini, Friss melihat benih dari kebangkitan sepeda di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.
Sepeda dan Politik Penyingkiran
Bab 2, 3, dan 4 secara kolektif memperlihatkan bagaimana sepeda di New York bukan sekadar kalah bersaing dengan mobil, tetapi disingkirkan secara aktif melalui norma sosial, visi peren-canaan kota, dan kebijakan hukum. Friss mengajak pembaca memahami bahwa konflik sepeda hari ini—tentang jalur sepeda, larangan, dan keselamatan—adalah gema dari sejarah panjang perebutan ruang kota.
Dalam kerangka yang lebih luas, bagian ini menjadikan sepeda sebagai simbol dari pertanyaan yang lebih besar: apakah kota dibangun untuk mesin atau untuk manusia? Dan siapa yang berhak menentukan jawabannya?
Bab “Bloomberg” menandai titik balik penting dalam sejarah sepeda di New York: Kembalinya sepeda dan politik kota kontemporer. Setelah lebih dari setengah abad berada di pinggiran—terdesak oleh mobil, dilarang secara hukum, dan distigmatisasi secara sosial—sepeda kembali memasuki pusat perdebatan publik pada awal abad ke-21, khususnya di bawah kepemimpinan Michael Bloomberg sebagai wali kota. Friss menggambarkan era Bloomberg bukan sebagai kebangkitan sepeda yang romantis, melainkan sebagai proses yang penuh konflik, resistensi, dan ambiguitas. Pemerintahan Bloomberg secara aktif mempromosikan jalur sepeda, program bike-sharing, dan desain ulang jalan kota untuk mengakomodasi pesepeda. Untuk pertama kalinya sejak era pra-mobil, sepeda kembali diakui sebagai bagian sah dari sistem transportasi kota.
Namun, Friss dengan cermat menunjukkan bahwa kebangkitan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia berlangsung di tengah proyek besar “penataan ulang kota” yang sering dikaitkan dengan gentrifikasi, privatisasi ruang publik, dan logika kota global yang kompetitif. Jalur sepeda, bagi sebagian warga, dipersepsikan bukan sebagai simbol keadilan mobilitas, melain-kan sebagai tanda perubahan demografis dan ekonomi yang mengancam komunitas lama.
Di sinilah Friss menolak narasi sederhana tentang sepeda sebagai “kebaikan universal”. Ia memperlihatkan bagaimana sepeda dapat menjadi alat emansipasi sekaligus simbol eksklusi, tergantung konteks sosial dan politiknya. Di bawah Bloomberg, sepeda sering dipromosikan dengan bahasa efisiensi, kesehatan, dan daya saing global—bukan terutama dengan bahasa keadilan sosial atau hak atas kota.
Friss juga menyoroti konflik sengit antara pesepeda, pengendara mobil, dan pejalan kaki. Penentangan terhadap jalur sepeda sering kali emosional, mencerminkan ketakutan kehilangan ruang, status, dan kontrol. Seperti dalam sejarah sebelumnya, sepeda kembali menjadi proyeksi kecemasan sosial yang lebih besar: tentang siapa kota ini untuk siapa.
Bab ini menegaskan satu tesis penting: sepeda tidak pernah netral. Bahkan ketika ia dipromosi-kan sebagai solusi ramah lingkungan dan sehat, sepeda tetap terikat pada struktur kekuasaan yang lebih luas. Era Bloomberg menunjukkan bahwa memasukkan sepeda ke dalam kota modern tanpa mengubah logika dasar pembangunan dapat menghasilkan paradoks—kemajuan ekologis yang berjalan berdampingan dengan ketimpangan sosial.
Sepeda sebagai Teknologi yang Subversif
Sepeda adalah teknologi yang tampak sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya ia bersifat subversif. Ia menolak logika dominan modernitas perkotaan yang mengidentikkan kemajuan dengan kompleksitas teknis, kecepatan, dan akumulasi kapital. Sepeda tidak membutuhkan bahan bakar fosil, tidak memerlukan infrastruktur mahal, tidak memproduksi data bernilai ekonomi tinggi, dan tidak menciptakan ketergantungan struktural pada industri besar. Dalam istilah filsuf teknologi Ivan Illich, sepeda adalah convivial tool: alat yang memperluas kemampuan manusia tanpa menggantikannya atau menaklukkannya.
Subversivitas sepeda terletak pada relasi kuasa yang ia ganggu. Kapitalisme perkotaan bekerja melalui hierarki kecepatan dan ukuran: kendaraan besar menguasai ruang lebih besar, bergerak lebih cepat, dan diberi prioritas hukum serta simbolik. Sepeda membalik hierarki ini. Ia meng-klaim ruang jalan dengan tubuh manusia sebagai pusatnya. Ia menolak gagasan bahwa mobilitas harus dimediasi oleh mesin mahal dan energi eksternal. Dalam praktik sehari-hari, seorang pesepeda secara diam-diam mempertanyakan mengapa kota harus dirancang untuk mesin, bukan untuk manusia.
Dalam pengertian Michel Foucault, sepeda adalah teknologi yang mengganggu governmentality modern. Ia sulit diatur sepenuhnya, sulit dimonetisasi secara total, dan tidak cocok dengan sistem pengawasan berbasis kepemilikan kendaraan bermotor. Karena itu, sepanjang sejarah—seperti ditunjukkan Evan Friss—sepeda sering dicurigai, diatur berlebihan, atau dilarang. Bukan karena ia berbahaya, tetapi karena ia terlalu bebas.
Kapitalisme perkotaan membutuhkan pertumbuhan berkelanjutan: lebih banyak kendaraan, lebih banyak konsumsi energi, lebih banyak infrastruktur, lebih banyak kredit, lebih banyak asuransi. Sepeda adalah benda yang secara teknologi yang tidak cocok dengan kapitalisme perkotaan. Sepeda justru bekerja dalam logika cukup. Ia tahan lama, murah, dapat diperbaiki, dan tidak cepat usang. Dari perspektif ekonomi politik, sepeda adalah teknologi dengan low turnover—ia tidak menghasilkan siklus konsumsi yang agresif.
Lebih jauh, sepeda tidak menginternalisasi logika eksternalitas kapitalisme. Mobil memindah-kan biaya sosialnya—polusi, kemacetan, kecelakaan, krisis iklim—kepada publik. Sepeda justru menghasilkan manfaat publik: udara lebih bersih, ruang lebih aman, kota lebih hidup. Dalam bahasa Jason Hickel, sepeda adalah teknologi post-growth: ia meningkatkan kualitas hidup tanpa meningkatkan ekstraksi atau emisi.
Karena itu sepeda selalu “tidak cocok”. Ia tidak cocok dengan real estate spekulatif yang mem-butuhkan jalan besar. Tidak cocok dengan industri otomotif. Tidak cocok dengan kota yang dirancang untuk produktivitas maksimum dan waktu tempuh minimum. Sepeda memper-lambat, mendekatkan, dan memperlihatkan wajah kota yang rapuh—sesuatu yang ingin disembunyikan oleh kapitalisme urban.
Sepeda dan Etika Tubuh
Secara filosofis, sepeda juga mengusulkan etika tubuh yang berbeda. Tubuh bukan beban yang harus dipindahkan secepat mungkin, melainkan subjek yang mengalami ruang. Bersepeda mengembalikan pengalaman sensorik kota: panas, hujan, bau, suara, dan pertemuan tak terduga. Dalam hal ini, sepeda dekat dengan kritik Hannah Arendt terhadap dunia modern yang kehilangan vita activa—kehidupan yang benar-benar dialami, bukan sekadar dikelola. Sepeda menolak pemisahan radikal antara manusia dan lingkungan. Tubuh pesepeda langsung me-rasakan kualitas udara, kemiringan jalan, dan tekstur kota. Dengan demikian, sepeda adalah teknologi ekologis bukan karena “hijau” secara simbolik, tetapi karena ia memulihkan hubungan etis antara tubuh dan dunia.
Jakarta: Kota yang Menganggap Sepeda sebagai Anomali
Di Jakarta, sepeda masih diperlakukan sebagai anomali. Jalan-jalan dirancang untuk mobil dan motor, sementara sepeda dianggap “tidak realistis”, “tidak cocok dengan cuaca”, atau “menghambat lalu lintas”. Argumen ini mencerminkan logika yang sama seperti New York abad ke-20: ketidakcocokan sepeda bukanlah soal iklim atau budaya, melainkan soal prioritas politik.
Jalur sepeda di Jakarta sering bersifat simbolik, terputus, dan mudah dihapus ketika dianggap mengganggu arus kendaraan bermotor. Sepeda diterima sejauh ia menjadi gaya hidup kelas menengah, bukan sebagai alat mobilitas rakyat. Ini menunjukkan paradoks kapitalisme hijau: sepeda diterima sebagai citra, tetapi ditolak sebagai struktur.
Dalam konteks Jakarta, sepeda menjadi subversif justru ketika ia dipraktikkan oleh kelas pekerja—kurir, buruh, pedagang kecil—yang menggunakannya bukan sebagai pilihan gaya hidup, tetapi sebagai kebutuhan. Di sinilah sepeda berhadapan langsung dengan ketimpangan kota.
Bandung: Antara Imajinasi Kreatif dan Realitas Infrastruktur
Bandung sering membayangkan dirinya sebagai kota kreatif dan ramah sepeda. Namun secara struktural, sepeda tetap terpinggirkan. Ruang publik sempit, jalan menanjak dianggap alasan, dan kebijakan sering berhenti pada festival atau hari bebas kendaraan. Sepeda menjadi bagian dari estetika kota, bukan dari sistem transportasi. Secara filosofis, ini menunjukkan bagaimana kapitalisme perkotaan dapat menyerap simbol sepeda tanpa mengubah relasi kuasa. Sepeda dirayakan sebagai citra kreatif, tetapi tidak sebagai teknologi yang mengubah distribusi ruang. Subversi sepeda diredam dengan festivalisasi.
Kota-kota Indonesia: Sepeda sebagai Etika Perlawanan Halus
Di banyak kota kecil dan menengah di Indonesia, sepeda sebenarnya masih hidup—bukan sebagai ideologi, tetapi sebagai praktik keseharian. Di desa dan kota pinggiran, sepeda adalah alat ekonomi lokal, solidaritas sosial, dan mobilitas rendah emisi. Namun justru kota-kota inilah yang paling terancam oleh ekspansi kapitalisme infrastruktur: jalan besar, kendaraan besar, dan proyek-proyek mobilitas yang menghapus praktik lokal. Dalam konteks ini, sepeda dapat dibaca sebagai etika perlawanan halus terhadap kolonialisme mobilitas. Ia mengingatkan bahwa modernitas tidak harus berarti kecepatan dan ekstraksi, tetapi dapat berarti kecukupan dan kedekatan.
Catatan Akhir: Dua Abad yang Belum Selesai
Evan Friss menutup bukunya dengan refleksi bahwa sejarah sepeda di New York bukanlah kisah nostalgia, melainkan pelajaran politik. Setiap jalur sepeda adalah hasil perjuangan; setiap peng-gusuran sepeda adalah keputusan ideologis. Sepeda bertahan bukan karena kelemahan-nya, tetapi karena ketahanannya—sebuah teknologi sederhana yang terus kembali setiap kali kota mencari jalan keluar dari krisisnya sendiri.
Dalam epilog, Friss menarik benang panjang dari dua abad sejarah sepeda di New York untuk menyampaikan refleksi yang lebih luas tentang masa depan kota. Ia menolak gagasan bahwa sejarah sepeda bergerak menuju akhir yang pasti. Tidak ada “kemenangan final” bagi sepeda, sebagaimana tidak ada kekalahan permanen. Yang ada hanyalah perjuangan yang terus berulang.
Friss menekankan bahwa konflik tentang sepeda hari ini—tentang keselamatan, ruang jalan, dan kebijakan transportasi—adalah gema langsung dari perdebatan yang telah berlangsung sejak abad ke-19. Dengan demikian, memahami sejarah bukanlah nostalgia, melainkan alat kritis untuk membaca masa kini. Kota modern, dalam pandangan Friss, masih bergulat dengan pertanyaan yang sama: apakah ruang publik akan dikelola untuk efisiensi mesin atau untuk kehidupan manusia?
Epilog ini juga mengangkat dimensi etis sepeda secara lebih eksplisit. Sepeda, sebagai teknologi yang sederhana dan berbasis tenaga manusia, menawarkan visi kota yang lebih lambat, lebih dekat, dan lebih egaliter. Namun Friss mengingatkan bahwa visi ini hanya dapat terwujud jika disertai perubahan struktural—dalam kebijakan, budaya, dan distribusi kekuasaan. Friss menutup buku dengan nada yang waspada namun tidak sinis. Ia mengakui bahwa sepeda kini menghadapi tantangan baru: komersialisasi, platformisasi, dan instrumentalitas dalam ekonomi hijau. Tetapi ia juga melihat potensi yang sama seperti dua ratus tahun lalu—bahwa sepeda tetap mampu membuka ruang imajinasi tentang kota yang berbeda.
Epilogue ini menegaskan pesan moral buku secara keseluruhan: masa depan sepeda bukan soal teknologi, melainkan soal pilihan politik dan nilai-nilai kolektif. Sepeda akan selalu menjadi cermin. Cara kita memperlakukannya akan menunjukkan bagaimana kita memahami keadilan, kebebasan, dan keberlanjutan dalam kehidupan urban.
Dalam perjalanan sejarahnya, On Bicycles mencapai sintesis historisnya: sepeda bukanlah artefak pinggiran, melainkan indikator sensitif dari arah peradaban kota. Dari awal yang kasar, pelarangan, penyingkiran oleh mobil, hingga kebangkitan kontemporer, sepeda terus menguji klaim kota modern tentang kemajuan.
Sepeda adalah teknologi yang tampak terlalu kecil untuk mengubah dunia. Namun justru di situlah kekuatannya. Ia paling efisien. “The bicycle is the most efficient machine ever created.” —Ivan Illich, Energy and Equity (1974). Ia memaksa kita bertanya: mengapa kota kita dibangun seperti ini? Untuk siapa kecepatan, ruang, dan energi itu dialokasikan? Dalam krisis iklim global, sepeda bukan solusi teknis, tetapi kritik hidup terhadap cara hidup. Ia subversif karena ia sederhana. Ia tidak cocok karena ia jujur. Dan di kota-kota Indonesia hari ini, sepeda masih menunggu satu hal yang sama seperti dua ratus tahun lalu: keberanian politik untuk mem-bayangkan kota bagi manusia, bukan bagi mesin. Sepeda sebagai cermin peradaban.
Dalam era krisis iklim global, On Bicycles mengingatkan kita bahwa masa depan kota mungkin justru terletak pada teknologi lama yang pernah kita abaikan—bukan sebagai solusi tunggal, tetapi sebagai cara hidup yang lebih adil, lambat, dan manusiawi.
Bogor, 21 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Daftar Pustaka
Friss, E. (2019). On bicycles: A 200-year history of cycling in New York City. Columbia University Press.
Illich, I. (1974). Energy and equity. Harper & Row.
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. Random House.
Mumford, L. (1964). The highway and the city. Harcourt, Brace & World.
Lefebvre, H. (1996). Writings on cities (E. Kofman & E. Lebas, Trans.). Blackwell.
Anthony, S. B. (1896/1998). The feminist papers. University of Illinois Press.