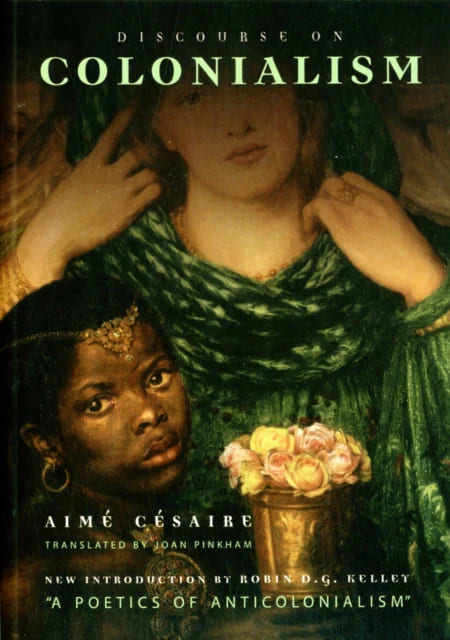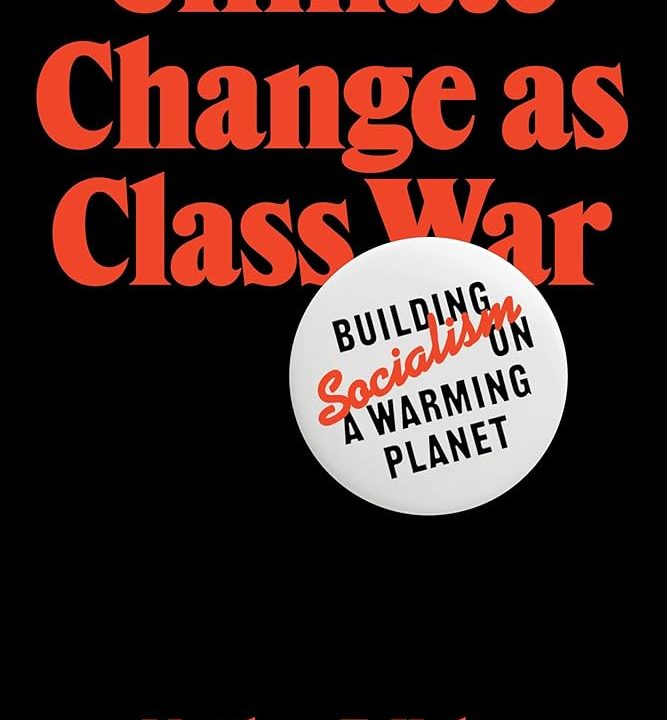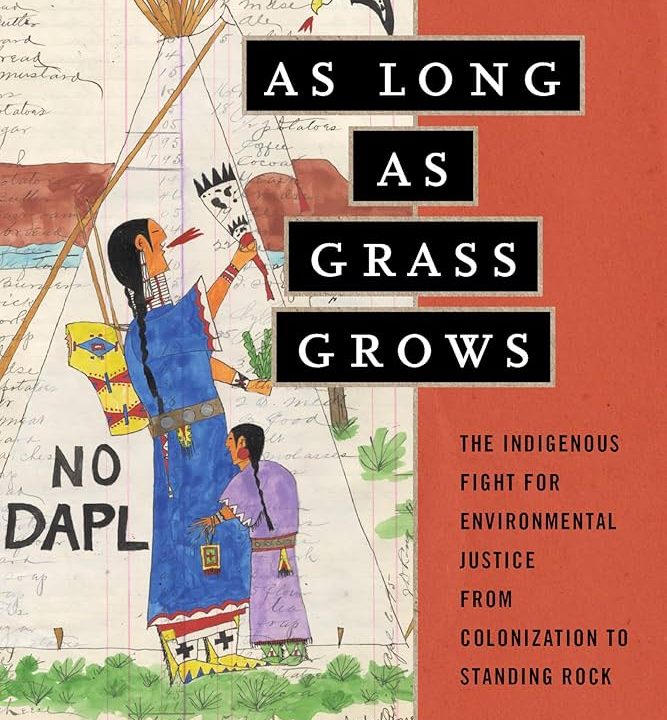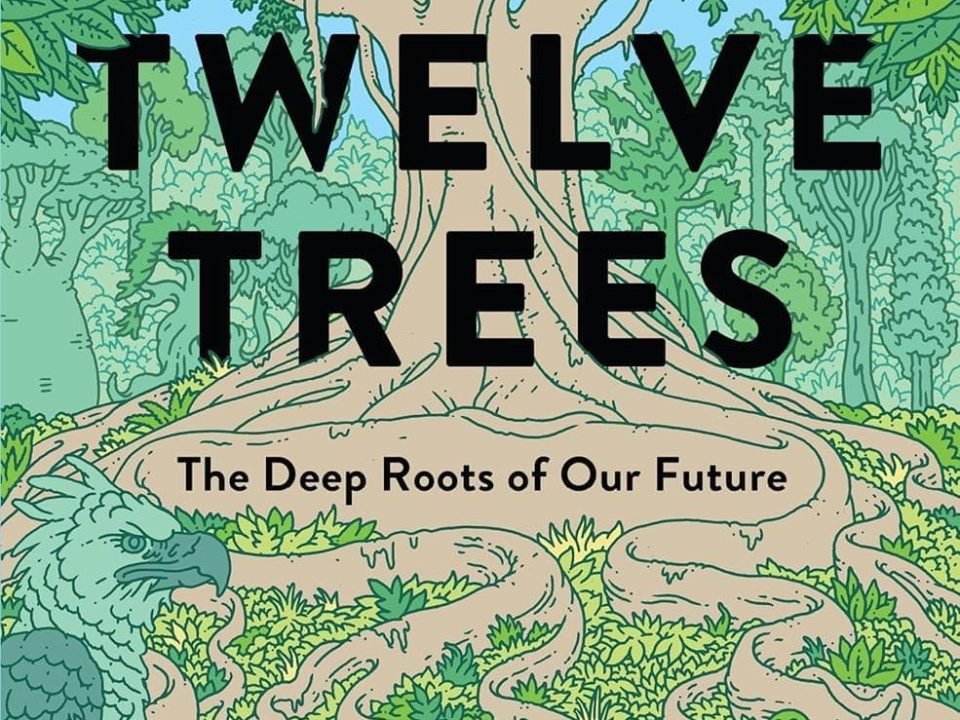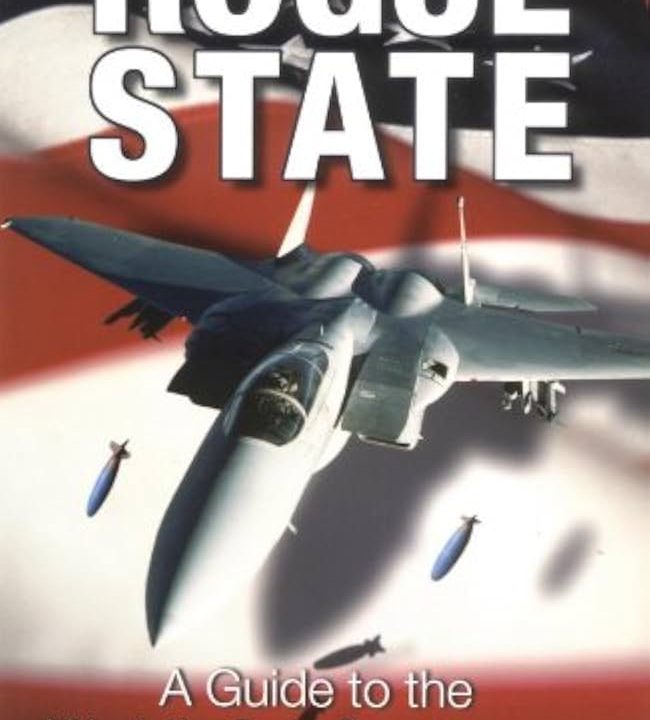Rubarubu #15
Menjadi Manusia Setelah Kolonialisme:
Membaca Ulang Wawancara Aimé Césaire (1967)
Di sebuah desa pesisir yang sunyi, seorang anak menatap kapal asing yang menambat di pelabuhan—kapal yang membawa insinyur, misionaris, pedagang, dan bendera besar. Orang-orang tua desa mengingat cerita nenek moyang tentang “tamu” yang datang bukan sekadar untuk berdagang: tanah mereka lambat-lambat diukur, ditandai, dibagi; sungai yang dulu milik banyak keluarga tiba-tiba punya pemilik baru. Kisah kecil ini bergema dalam Discourse on Colonialism, Aimé Césaire: esai yang pada akhirnya mengatakan bahwa kolonialisme bukan “kesalahan administrasi” melainkan sebuah proyek kekerasan yang merusak jiwa penindas dan terjajah. Césaire mengakhiri dengan panggilan moral: jangan lagi menyamakan peradaban Eropa dengan kemanusiaan; renungkan bagaimana suatu peradaban bisa mengklaim kemajuan sambil melakukan barbarisme.
Lalu ia menulis:
Wacana tentang Kolonialisme
Sebuah peradaban yang tak sanggup menyelesaikan
persoalan-persoalan yang diciptakannya sendiri
adalah peradaban yang tengah menuju keruntuhan.
Sebuah peradaban yang memilih memejamkan mata
terhadap masalah-masalahnya yang paling genting
adalah peradaban yang terserang penyakit.
Sebuah peradaban yang memperalat
prinsip-prinsipnya untuk kelicikan dan penipuan
adalah peradaban yang sedang sekarat.
Faktanya, apa yang disebut peradaban Eropa—
peradaban “Barat”—
yang dibentuk oleh dua abad kuasa borjuis,
telah terbukti tak mampu menyelesaikan dua persoalan raksasa
yang justru lahir dari keberadaannya sendiri:
masalah kaum proletar
dan masalah kolonial.
Eropa tak mampu membela dirinya,
tak di hadapan “akal budi”,
tak pula di hadapan “hati nurani”;
dan semakin hari
ia berlindung dalam kemunafikan—
sebuah kemunafikan yang kian menjijikkan
karena kian kehilangan daya menipunya.
Eropa tak dapat dipertahankan.
Begitulah, bisik-bisik para strateg Amerika.
Itu sendiri tidaklah penting.
Yang penting adalah bahwa “Eropa” kini
tak dapat dipertahankan—secara moral, secara spiritual.
Dan hari ini, dakwaan itu dilayangkan bukan hanya oleh massa Eropa,
tetapi oleh dunia seluruhnya,
oleh puluhan juta manusia
yang dari kedalaman perbudakan
menegakkan diri sebagai para hakim.
Para kolonialis boleh membunuh di Indochina,
menyiksa di Madagaskar,
memenjara di Afrika Hitam,
meneror di Hindia Barat.
Namun kini, kaum terjajah tahu
bahwa mereka memiliki keunggulan.
Mereka tahu bahwa “tuan-tuan” mereka yang sementara itu
sedang berdusta—
dan karena itu,
bahwa para tuan itu rapuh.
Dan karena aku diminta berbicara tentang kolonisasi dan peradaban,
marilah kita langsung menuju
pada kebohongan pokok
yang menjadi sumber segala kebohongan lainnya:
Kolonisasi dan peradaban?
***
Bait demi bait yang ditulis Aimé Césaire itu, bukan saja sebagai jejak perlawanan tetapi juga sebuah pernyataan perang terhadap kolonialisme. Teks itu diutliskan sebagai pembuka halaman pada buku Discourse on Colonialism. Buku ini aslinya diterbitkan dalam bahasa Perancis, bahasa kaum penjajah yang menggunakan bahasa untuk menguasai pikiran dan gagasan. Judulnya: Discours sur le colonialisme by Editions Presence Africaine, 1955. Versi bahasa Inggris saya gunakan yang diterjemahkan oleh Joan Pinkham, Monthly Review Press: New York and London, 1972. Buku ini pada dasarnya himpunan wawancara dari beberapa pihak. Pikirannya seperti tumpah dalam seluruh wawancara yang ada dalam buku ini.
Discourse on Colonialism dinilai sebagai kritik paling tajam terhadap barat. Pada tahun 1950, Césaire menerbitkan Discours sur le colonialisme, esai politis yang menyatakan bahwa kolonialisme bukanlah proyek pembawa “peradaban”, melainkan sistem brutal yang merusak baik penjajah maupun yang dijajah. Ia menuduh Eropa—khususnya borjuasi Barat—mengizinkan barbarisme tumbuh, hingga akhirnya melahirkan Nazisme; sebuah cermin dari kekejaman kolonial yang sebelumnya mereka toleransi ketika diarahkan kepada bangsa-bangsa non-Eropa. Esai ini menjadi teks fundamental dalam studi pascakolonial dan kajian ras kritis.
Aimé Césaire (1913–2008), Aimé Fernand David Césaire, — penyair, pemikir, dan pejuang antikolonial adalah dramawan, intelektual, dan politisi Martinique yang menjadi salah satu suara paling berpengaruh dalam kritik kolonialisme abad ke-20. Lahir di Basse-Pointe, Martinique—sebuah koloni Prancis di Karibia—Césaire tumbuh dalam lingkungan yang menaruh nilai tinggi pada pendidikan. Kecemerlangannya membawanya ke École Normale Supérieure di Paris, tempat ia berjumpa dengan Léopold Sédar Senghor dan para intelektual Afrika lain yang kelak melahirkan gagasan besar Négritude.
Percakapan Intelektual
Pada tahun 1967, di Havana yang sedang bergelora oleh semangat revolusi, Aimé Césaire duduk berhadapan dengan penyair Haiti, René Depestre. Di balik suasana kongres budaya yang penuh optimisme, percakapan mereka justru bergerak pada sesuatu yang lebih dalam—sebuah upaya menamai luka panjang kolonialisme, sekaligus merumuskan kemungkinan dunia baru setelah reruntuhan tersebut. Ketika Césaire berbicara, suaranya mengandung ketenangan seorang yang telah menyaksikan kengerian kolonial dari dekat, tetapi juga kekokohan seorang penyair yang yakin bahwa masa depan dapat dituliskan ulang.
Dalam percakapan ini, Césaire kembali mengingatkan bahwa kolonialisme tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga menghancurkan struktur batin manusia. Itulah sebabnya ia tidak mau dipaksa memilih antara “politik” dan “ras”; baginya, rasialisme adalah mekanisme ideologis yang menopang kolonialisme. Pemisahan keduanya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kekuasaan. Ketika ia mengatakan bahwa kolonialisme “selalu membutuhkan rasialisme untuk beroperasi,” ia sedang mengajak dunia melihat bahwa rasisme bukanlah sikap pribadi, melainkan sebuah infrastruktur kekuasaan yang membentuk seluruh arsitektur penjajahan. Barangkali inilah sebabnya hingga hari ini, rasisme tetap hidup bahkan ketika imperium-imperium kolonial telah runtuh.
Césaire lalu berbicara tentang Négritude, konsep yang sering disalahpahami sebagai romantisasi identitas kulit hitam. Dalam wawancara itu, ia mengoreksi: Négritude bukanlah esensialisme; bukan pula kultus warna kulit. Ia menyebutnya sebagai “gerak balik dari manusia yang dipaksa melupakan dirinya.” Négritude adalah upaya mengembalikan manusia yang telah direduksi menjadi objek oleh kolonialisme. Ini bukan tentang menegaskan “kehitaman,” tetapi tentang memulihkan kemanusiaan yang telah dipreteli. Dalam dunia yang makin ditandai oleh krisis identitas dan politik perbedaan, definisi Césaire terasa sangat relevan: ia menawarkan subyektivitas sebagai ruang pembebasan, bukan sebagai pagar pembatas.
Césaire memang salah satu pencetus istilah Négritude. Bersama Senghor dan Léon-Gontran Damas, Césaire merumuskan Négritude: sebuah gerakan sastra, budaya, dan politik yang menegaskan kembali martabat, identitas, dan nilai kebudayaan kulit hitam di tengah dunia kolonial. Karya puisinya yang ikonik, Cahier d’un retour au pays natal (1939), menjadi salah satu manifestasi paling kuat dari gerakan ini—sebuah campuran antara liris, politik, dan pemberontakan intelektual.
Inti tuduhan: kolonialisme sebagai moral dan estetika pembusukan
Césaire memulai dengan amarah intelektual: ia menolak klaim bahwa “peradaban Barat” adalah kemajuan moral universal. Alih-alih, ia menggambarkan kolonialisme sebagai penyakit yang menenggelamkan hati nurani: “No one colonizes innocently” (baris ini menjadi motto esainya). Menurut Césaire, penjajahan memaksa pembenaran moral (rasisme, dehumanisasi) sehingga penindas dapat melakukan kekerasan tanpa merasa bersalah; pada akhirnya penjajahan merusak kebudayaan dan peradaban Eropa sendiri — memperlihatkan bahwa “peradaban” yang membunuh dan memperbudak sesama manusia sesungguhnya hanyalah kemunduran moral berlapis rasionalitas. Esai ini adalah seruan untuk mengakui hipokrisi tersebut dan menggugatnya secara etis.
“Tetapi kemudian aku mengajukan pertanyaan berikut: apakah kolonisasi benar-benar telah mempertemukan peradaban? Atau, jika kau lebih suka, dari semua cara untuk menjalin pertemuan, apakah kolonisasi adalah cara yang terbaik? Jawabku: tidak.”
“Dan kemudian, pada suatu hari yang cerah, kelas borjuis terbangun oleh sebuah kejutan dahsyat: gestapo bekerja, penjara-penjara penuh, para penyiksa di ruang penyiksaan
mencipta, menyempurnakan, memperdebatkan teknik mereka.
Orang-orang terkejut, mereka gusar. Mereka berkata: ‘Aneh sekali! Tapi sudahlah—itu hanya Nazisme, nanti juga berlalu!’
Dan mereka menunggu, dan mereka berharap; dan mereka menutupi kebenaran dari diri mereka sendiri—bahwa inilah barbarisme, barbarisme yang tertinggi, barbarisme puncak
yang merangkum semua barbarisme sehari-hari; bahwa ini memang Nazisme, ya, tetapi sebelum mereka menjadi korbannya, mereka adalah para kaki tangannya; bahwa mereka telah mentoleransi Nazisme sebelum itu menimpa mereka, bahwa mereka mengampuninya,
memejamkan mata terhadapnya, melegitimasi keberadaannya, karena sampai saat itu Nazisme hanya diterapkan pada bangsa-bangsa non-Eropa; bahwa mereka turut membesarkan Nazisme itu, bahwa mereka bertanggung jawab atasnya, dan bahwa sebelum ia menenggelamkan seluruh peradaban Barat-Kristen dalam air merah darahnya, Nazisme itu telah merembes,
meresap, menetes dari setiap celah.”
“Ya, akan sangat berharga untuk mempelajari secara klinis, secara rinci, langkah-langkah yang ditempuh Hitler dan Hitlerisme, dan mengungkap kepada para borjuis yang sangat terhormat, sangat humanis, sangat Kristen di abad ke-20, bahwa tanpa disadarinya, ia menyimpan seorang Hitler dalam dirinya, bahwa Hitler bersemayam di dalam dirinya, bahwa Hitler adalah demon-nya; bahwa bila ia menghujat Hitler, ia sedang bersikap tak konsisten; dan bahwa, pada dasarnya,apa yang tidak bisa ia maafkan dari Hitler bukanlah kejahatan itu sendiri, bukan kejahatan terhadap manusia, bukan penghinaan terhadap martabat manusia, tetapi kejahatan terhadap orang kulit putih, penghinaan terhadap manusia putih, dan kenyataan bahwa Hitler menerapkan pada Eropa prosedur kolonialis yang sebelumnya hanya dikhususkan bagi orang-orang Arab di Aljazair, kuli-kuli India, dan orang-orang kulit hitam Afrika.
Dan inilah hal terbesar yang kutuduhkan pada pseudo-humanisme: bahwa terlalu lama ia telah mereduksi hak-hak manusia; bahwa konsepnya tentang hak-hak itu telah—dan masih—
sempit, terpecah-pecah, tidak lengkap, berat sebelah, dan, jika dipikirkan dalam keseluruhannya, amatlah rasis secara menyedihkan.”
“Kolonisasi: sebuah jembatan depan—dalam kampanye untuk ‘mencivilisasi barbarisme,’
yang dari dalamnya dapat muncul kapan saja peniadaan peradaban, secara murni dan sederhana. Di tempat lain aku telah mengutip panjang lebar beberapa insiden yang dipetik dari sejarah ekspedisi kolonial. Sayangnya, hal itu tidak disukai semua orang. Tampaknya aku dituduh mengeluarkan kerangka-kerangka tua dari lemari.”
Keputusan Césaire keluar dari Partai Komunis Prancis menjadi salah satu momen paling penting dalam wawancara tersebut. Ia keluar bukan karena menolak gagasan sosialisme, tetapi karena merasa Marxisme Eropa gagal menangkap realitas kolonial. Itu bukan sekadar kritik politis; itu kritik epistimologis. Bagi Césaire, revolusi harus dimulai dari kesiapan untuk mendengarkan suara yang selama ini diredam: suara kaum terjajah, kaum kulit hitam, kaum yang dianggap tidak memiliki sejarah. Ia ingin sosialisme yang berangkat dari Karibia dan Afrika—bukan doktrin yang diimpor dari Paris. Di sini, ia telah lebih dulu menempuh jalan yang kelak disebut para sarjana sebagai “dekolonisasi pengetahuan.”
Namun bagian paling indah dari wawancara itu adalah ketika Césaire berbicara tentang puisi. Baginya, puisi bukan eskapisme, melainkan alat revolusi. Ia percaya bahwa kolonialisme bekerja dengan menaklukkan bahasa, imajinasi, dan simbol; maka pembebasan pun harus terjadi pada level itu. Dengan bahasa puitis, manusia yang hancur oleh kolonialisme dapat membayangkan dirinya kembali. Dunia dapat ditulis ulang. “Puisi adalah cara untuk membangun kembali manusia,” kira-kira begitu ia mengisyaratkan. Pernyataan itu terasa benar ketika kita menyadari bahwa imperium-imperium besar runtuh bukan hanya karena perang, tetapi karena imajinasi moral dunia telah berubah.
Puisi sebagai alat politik dan pemulihan imajinasi. Depestre menanyakan apakah puisi dapat menjadi senjata revolusioner. Césaire menjawab bahwa bahasa puitis mampu membongkar hegemoni mental kolonial. Baginya, kolonialisme bukan hanya sistem ekonomi-politik, tetapi juga sistem yang membunuh imajinasi. Puisi membuka ruang bagi pembacaan ulang realitas, menjadi wahana bagi subjek terjajah untuk menyusun kembali dunia. Dengan demikian, seni tidak bersifat dekoratif, tetapi merupakan bagian integral dari perjuangan dekolonial.
Puisi juga sebagai alat dekolonisasi imajinasi. Césaire menjelaskan bahwa bagi dirinya puisi adalah senjata politik. Bahasa puitis mampu menghancurkan struktur mental kolonial yang mengatur cara subjek terjajah melihat dunia. Dalam wawancara ini ia menyatakan bahwa kolonialisme bukan hanya kekerasan fisik dan ekonomi, melainkan penjajahan imajinasi, dan puisi berfungsi membuka ruang-ruang dunia baru di luar logika kolonial (lihat bagian wawancara dalam Discourse on Colonialism).
Perhatiannya pada seni, kebudayaan, dan estetika resistensi sangat tinggi. Karya sastra tak ubahnya sebagai senjata dalam perjuangan. Césaire bukan hanya polemik politik; ia juga membela potensi artistik dan budaya terjajah untuk menolak narasi penjajah. Esainya mempromosikan gagasan bahwa kesusastraan, puisi, dan budaya rakyat adalah alat pembebasan: bahasa dan imajinasi mampu memulihkan martabat dan menumbuhkan kebangkitan kolektif. Ia sendiri, penyair sekaligus politikus, menaruh harapan besar pada sastra sebagai medium perlawanan—suatu tema yang menghubungkan estetika dengan politik: lawan kolonialisme bukan hanya di rumput lapangan perjuangan, tetapi juga dalam bacaan, lagu, dan pikiran yang menolak dehumanisasi.
Césaire juga berbicara mengenai kekerasan revolusioner. Ia tidak menolaknya, tetapi tidak juga memujinya. Ia melihat kekerasan anti-kolonial bukan sebagai ekspresi kehendak destruktif, melainkan sebagai efek logis dari sistem yang sudah terlanjur brutal. Namun ia tetap berhati-hati agar perjuangan tidak terjebak dalam kultus kekerasan. Baginya, tujuan akhir politik adalah kehidupan—bukan kematian. Humanisme universal baru, yang ia bayangkan lahir dari perjuangan Dunia Ketiga, harus dibangun di atas asas kesetaraan dan martabat, bukan dendam atau supremasi baru.
Argumen historis: kekerasan, ekonomi, dan mental kolonial
Césaire menggabungkan analisis historis dan moral. Ia menelusuri bagaimana kolonialisme secara sistematis menggunakan kekerasan (militer, hukum, budaya) untuk memaksa kerja, mengekspor kekayaan alam, dan memformat subjek terjajah sebagai “lain” yang lebih rendah. Di sini kolonialisme dipahami bukan hanya sebagai penguasaan wilayah, tetapi sebagai organisasi ekonomi — eksploitasi yang menghasilkan keuntungan besar bagi pusat. Lebih jauh, ia menekankan efek psikologis: mentalitas penjajah menjadi brutal dan kejam; penjajahan mematahkan empati dan menormalisasi kebiadaban sebagai instrumen politik.
Pada bagian akhir wawancara, Césaire mengekspresikan kekagumannya pada Revolusi Kuba dan gerakan anti-kolonial Afrika. Ia melihat mereka sebagai bukti bahwa dunia yang selama ini dianggap pinggiran justru merupakan pusat energi sejarah. Dari sinilah Césaire merumuskan utopia-nya: bahwa dunia yang lebih adil akan lahir dari selatan, dari mereka yang pernah ditindas, dari mereka yang tahu bagaimana rasanya kehilangan tanah, sejarah, dan bahasa.
Membaca ulang wawancara ini hari ini—dalam dunia yang kembali penuh perang, genosida, ketimpangan, dan kolonialisme baru—kita seakan mendengar gema suara Césaire mengingatkan: “Selama ada manusia yang direduksi menjadi barang, kolonialisme belum selesai.” Wawancara ini bukan sekadar percakapan sejarah, tetapi jendela menuju proyek yang belum tuntas: memanusiakan kembali dunia.
Dan mungkin, seperti Césaire, kita semua sedang belajar bahwa kemanusiaan bukan warisan, melainkan tugas. Meskipun kolonialisme adalah luka yang menganga, tetapi lewat itulah cahaya akan memasukimu. Seperti kata Rumi (terjemahan, mis. Coleman Barks): “The wound is the place where the light enters you.”
Césaire mengusung Politisi Radikal memperjuangkan hak-hak pekerja, pendidikan, dan otonomi budaya. Pada 1956, ia memutuskan hubungan dengan Partai Komunis Prancis dan menerbitkan Lettre à Maurice Thorez, di mana ia menegaskan perlunya politik yang berakar pada pengalaman kolonial kulit hitam, bukan dogma Eropa. Kembali ke Martinique, Césaire menjadi wali kota Fort-de-France selama lebih dari 50 tahun (1945–2001) sekaligus anggota Majelis Nasional Prancis.
Warisan
Aimé Césaire wafat pada 17 April 2008 di Fort-de-France. Warisannya tetap hidup: sebagai penyair revolusioner, bapak pendiri Négritude, dan salah satu pemikir terbesar yang membongkar mitos “peradaban Barat”. Kata-katanya terus menggema dalam studi sastra, aktivisme dekolonial, dan wacana politik global—menandai dirinya sebagai salah satu intelektual paling tajam dalam menantang kekuasaan kolonial dan rasial.
Beberapa kutipan penting Césaire yang sering dikutip: “No one colonizes innocently.” Dan gagasannya bahwa kolonialisme “dehumanizes even the colonizer himself.” Untuk memperkaya pembacaan, kita dapat menautkannya pada pemikir lain: Frantz Fanon menulis bahwa dekolonisasi adalah proses pembentukan manusia baru—“decolonization is the creation of new men” (Fanon, The Wretched of the Earth). Edward Said (Orientalism) menunjukkan bagaimana wacana Barat memproduksi representasi yang membenarkan dominasi. Dari tradisi Muslim/Asia, Fazlur Rahman dan Ali Shariati menekankan perlunya ijtihad dan pembaruan moral ketika agama dihadapkan pada struktur sosial yang tidak adil—pemikiran yang resonan dengan seruan Césaire untuk pembaruan etika dan politik. Puisi dan metafora Rumi—mis. “the wound is the place where the light enters you”—dapat menjadi resonansi spiritual terhadap gagasan bahwa penderitaan sejarah juga menyimpan kemungkinan kebangkitan etis.
Ia mengritik tajam universalitas Barat dan “civilizing mission.” Salah satu bagian paling sengit adalah pembongkaran narasi “mission civilisatrice” — alasan moral yang sering dipakai Eropa untuk menjustifikasi penaklukan: “kami akan membawa kemajuan, pendidikan, peradaban.” Césaire membalik klaim itu: yang dibawa penjajah sering hanya kehancuran—pemiskinan, penyakit, perampasan budaya, dan trauma kolektif. Ia menyatakan bahwa “peradaban” yang memproduksi kamp konsentrasi, perbudakan sistemik, dan pembantaian tak layak disebut suci. Kritiknya menantang gagasan bahwa modernitas Barat otomatis bermoral; modernitas tanpa keadilan adalah kerapuhan etis.
Meskipun ditulis pada 1950-an, Césaire terasa mengejutkan relevan sekarang. Relevansi kontemporer: imperialisme baru dan kapitalisme ekstraktif. Ia memberi kerangka untuk memahami bagaimana “neo-kolonialisme” — bentuk baru intervensi ekonomi, politik, dan budaya oleh kekuatan pusat — terus berlangsung lewat utang, korporasi multinasional, dan tekanan geopolitik. Dalam era perubahan iklim, ekstraksi sumber daya, pasar global, dan militerisasi, dakwaan Césaire terhadap kolonialisme menjadi lensa penting: negara dan korporasi yang menempatkan keuntungan di atas kehidupan manusia dan alam meneruskan logika yang sama yang dulu membenarkan penjajahan.
Dan itu tentu saja menemukan relevansi untuk Indonesia: sejarah lokal, kontinuitas, dan pelajaran. Sebab untuk Indonesia, buku Césaire berbicara langsung. Penjajahan Belanda membentuk struktur ekonomi ladang komoditas (rempah, kopi, karet, sawit) yang terus mewariskan pola ekstraktif—pemisahan tanah adat, kerja paksa, dan subordinasi budaya. Di masa kini, pola tersebut muncul kembali dalam megaprojek infrastruktur, industri ekstraktif (tambang, sawit, nikel), dan tekanan pasar global. Césaire mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan hak rakyat dan kelestarian ekologi hanyalah reproduksi kolonialisme: modernitas tanpa keadilan. Pesan praktisnya: rekonstruksi bangsa memerlukan pengakuan sejarah, redistribusi, dan pemulihan martabat komunitas terpinggirkan.
Discourse on Colonialism dipuji luas sebagai teks penting dekonstruksi kolonialisme: ia berpengaruh pada pemikir dekolonial, aktivis, dan generasi pergerakan kemerdekaan. Pemikiran Césaire adalah warisan intelektual yang sangat berharga. Pengamat memuji keberaniannya — retorika yang tajam, kemarahan moral, dan visi pembebasan. Kritik terhadap Césaire menuduhnya kadang-kadang memakai generalisasi ekstrem—menyamaratakan Eropa secara moral dan mengabaikan kompleksitas internal di negara-negara Eropa atau variasi pengalaman kolonial. Beberapa akademisi menilai gaya polemiknya lebih emotif daripada analitis; namun banyak pula mengatakan bahwa kekuatan esai ada pada kemampuannya membangkitkan kesadaran etis, bukan hanya menyajikan data. Warisannya jelas: ia menyumbang bahasa moral yang tak lekang untuk memahami dan menentang bentuk-bentuk kekuasaan yang menistakan kemanusiaan.
Solidaritas internasional dan peran dunia ketiga
Di bagian akhir wawancara, Césaire menegaskan pentingnya solidaritas transnasional. Ia memuji Revolusi Kuba dan gerakan kemerdekaan Afrika sebagai contoh keberhasilan bangsa-bangsa yang menolak takdir kolonial.^12 Baginya, Asia–Afrika–Amerika Latin adalah “laboratorium humanisme baru”. Pernyataan ini meneguhkan imajinasi geopolitik Césaire: dunia masa depan harus dibangun dari pengalaman mereka yang paling tertindas, bukan dari pusat-pusat metropolitan yang selama berabad-abad mendominasi sejarah dunia.^13
Césaire mengungkapkan kekagumannya pada Revolusi Kuba dan gerakan-gerakan pembebasan di Afrika. Ia melihat Afrika–Asia–Amerika Latin sebagai pusat munculnya humanisme universal baru, sebuah dunia yang dibangun bukan oleh kekuatan imperium tetapi oleh rakyat yang pernah diperbudak dan dijajah. Ini memperlihatkan imajinasi geopolitik Césaire yang berbasis solidaritas Selatan–Selatan.
Bogor, 20 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Césaire, A. (1972). Discourse on Colonialism (J. Pinkham, Trans.). New York & London: Monthly Review Press. (Originally published 1955).
Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. Grove Press.
Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
Memmi, A. (1965). The Colonizer and the Colonized. Beacon Press.
Rumi, J. (1999). The Essential Rumi (C. Barks, Trans.). HarperCollins.