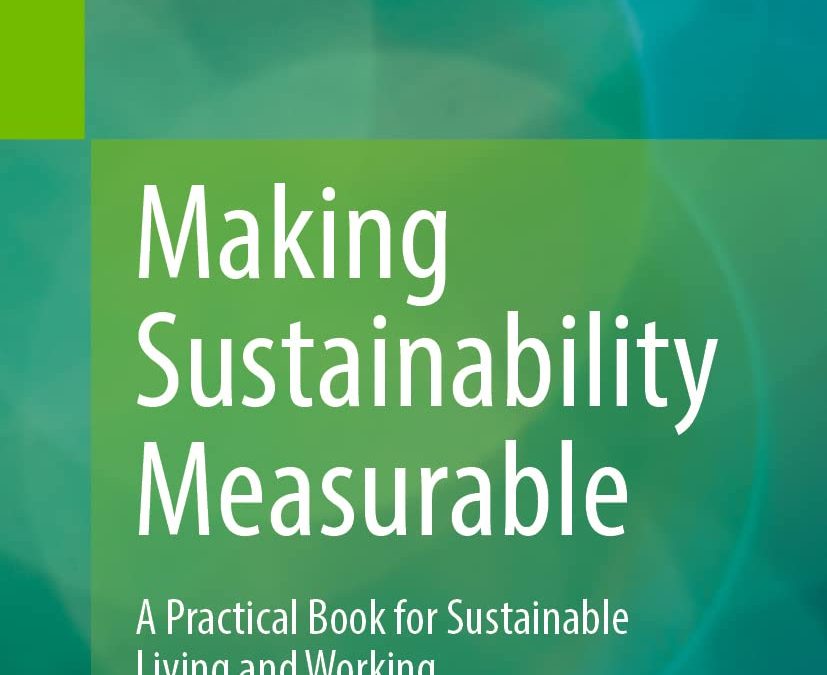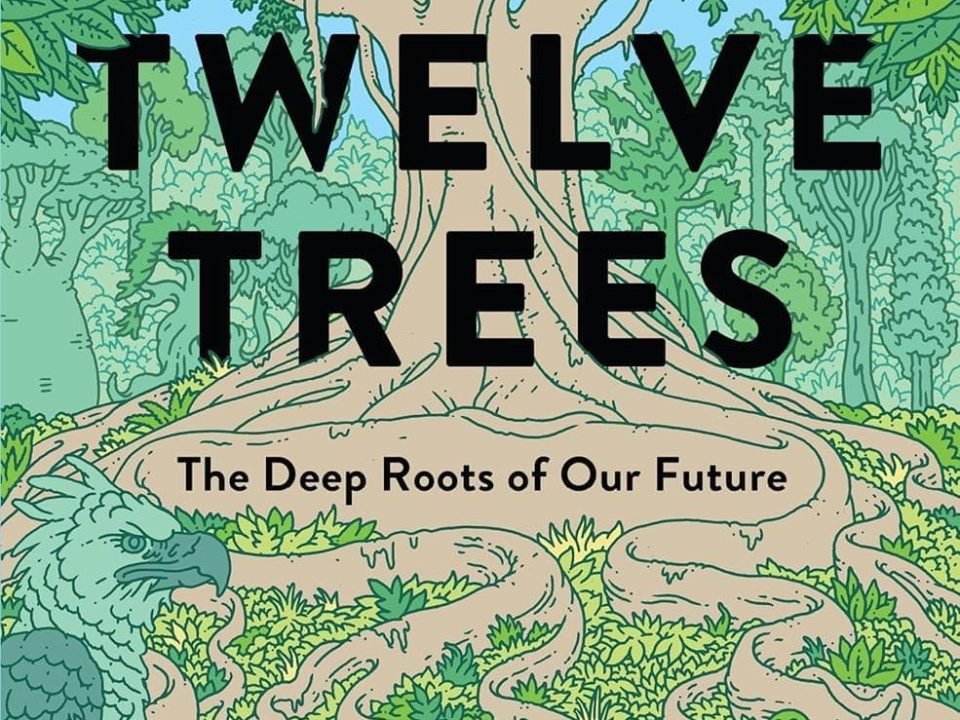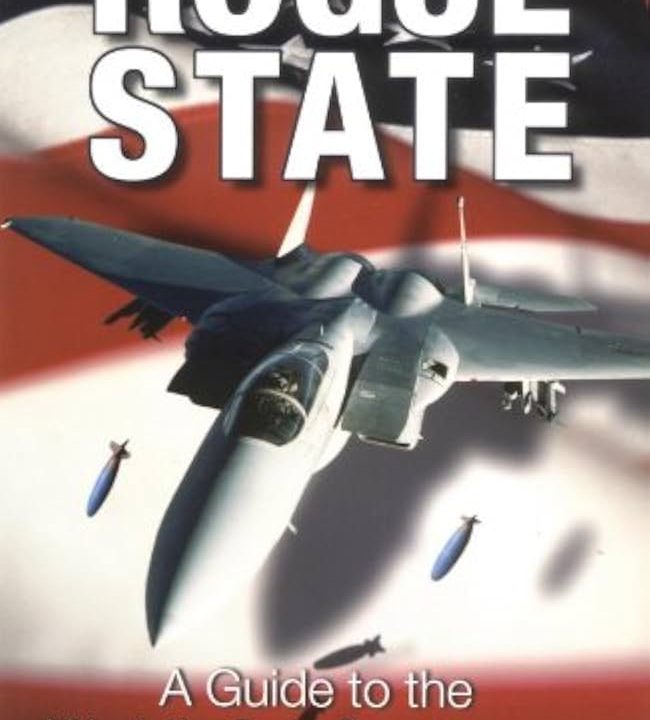Rubarubu #47
Mengukur Keberlanjutan, Mengukur Dampak
Di sebuah sore yang gerah di Jakarta, seorang manajer operasional bernama Anton menyisirkan jarinya yang gemetar pada laporan keberlanjutan perusahaannya. Di hadapannya terbentang lautan data yang kontradiktif: angka penghematan energi kantor mereka terlihat mengesankan di grafik, namun di luar jendela, truk-truk pengangkut produknya masih mengeluarkan asap hitam; klaim pengurangan limbah plastik mereka tertulis rapi, sementara di pabrik, tumpukan kemasan sekali pakai masih menggunung. Selama ini, kata “berkelanjutan” bagi Anton hanyalah sekumpulan klaim kosong dalam presentasi PowerPoint dan laporan tahunan yang tak pernah benar-benar mencerminkan realitas.
Keputusasaan itu memuncak ketika putri semata wayangnya yang berusia tujuh tahun bertanya dengan polos, “Ayah, kata guru, perusahaan Ayah sudah go green. Itu artinya Ayah sudah menyelamatkan bumi untuk masa depan aku, kan?” Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau—tajam dan tak terelakkan. Malam itu, dengan beban pertanyaan sang putri yang tak bisa ia jawab, Anton menemukan buku “Making Sustainability Measurable” di kedalaman internet. Saat ia membuka halaman pertamanya, seperti ada pencerahan: yang selama ini ia rasakan bukanlah kegagalan menerapkan keberlanjutan, melainkan kegagalan mengukurnya dengan cara yang berarti. Buku itu bukan sekadar menawarkan teori, melainkan sebuah kompas di tengah kabut greenwashing—alat untuk menerjemahkan niat baik menjadi angka yang jujur, aksi yang terverifikasi, dan dampak yang nyata; sebuah peta untuk mengubah kebanggaan semu menjadi perubahan yang sesungguhnya.
Paradigma Baru dalam Mengukur Keberlanjutan
Buku Michael Wühle, “Making Sustainability Measurable: A Practical Book for Sustainable Living and Working” (2023) ini merevolusi konsep keberlanjutan dengan mentransformasikan-nya dari sekadar wacana normatif menjadi kerangka kerja terukur yang aplikatif. Melalui pendekatan sistemik, Wühle membangun jembatan antara teori keberlanjutan kompleks dan implementasi praktis dalam kehidupan sehari-hari baik di tingkat individu, komunitas, maupun korporasi. Seperti kata Rachel Carson: “In nature nothing exists alone.” → mengingatkan keterkaitan ekologis.
“Keberlanjutan tanpa pengukuran hanyalah ilusi; pengukuran tanpa aksi adalah hipokrisi,” tegas Wühle dalam bab pembuka. Filosof Jerman Hans Jonas dalam “The Imperative of Responsibility” menyatakan, “Bertindaklah sehingga efek dari tindakanmu compatible dengan kelangsungan kehidupan manusia yang autentik,” prinsip yang menemukan ekspresi operasional dalam pendekatan Wühle. Buku ini dengan tegas menolak keberlanjutan sebagai konsep abstrak dan sebaliknya memposisikannya sebagai disiplin praktis yang memerlukan metrik, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan.
Buku ini membangun fondasi teoretis dengan mengintegrasikan konsep Triple Bottom Line (People, Planet, Profit) dengan System Thinking dan analisis siklus hidup. Wühle memperkenal-kan “Sustainability Measurement Matrix” yang memetakan dampak aktivitas manusia terhadap berbagai dimensi keberlanjutan secara kuantitatif dan kualitatif. “Kita tidak dapat mengelola apa yang tidak kita ukur, dan kita tidak boleh mengukur apa yang tidak penting untuk dike-lola,” tulisnya. Ekonom terkenal E.F. Schumacher dalam “Small is Beautiful” menginga-tkan, “Budaya yang mengagungkan angka-angka tanpa memahami makna di baliknya sedang menuju kehancuran,” peringatan yang dijawab Wühle dengan menekankan pentingnya konteks dalam interpretasi data keberlanjutan.
Buku ini menyajikan toolkit praktis untuk mengukur jejak ekologis dan sosial individu. Wühle mengembangkan “Personal Sustainability Index” yang mencakup parameter konsumsi energi, air, generasi sampah, pola mobilitas, dan kontribusi sosial. “Setiap keputusan konsumsi adalah suara untuk masa depan yang kita inginkan,” paparnya. Untuk konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan mengingat tingginya pertumbuhan kelas menengah perkotaan yang mulai sadar lingkungan namun masih memerlukan panduan praktis untuk mengubah kesadaran menjadi aksi terukur.
Perusahaan-perusahaan bisa menggunaan buku ini untuk melakukan transformasi bisnis menuju operasi berkelanjutan melalui integrasi Environmental, Social, and Governance (ESG) metrics dalam proses pengambilan keputusan. Wühle menyajikan studi kasus bagaimana perusahaan dapat mengukur return on investment dari praktik keberlanjutan. “Keberlanjutan bukan biaya, melainkan investasi dalam ketahanan bisnis,” klaimnya yang didukung data empiris. Di Indonesia, pendekatan ini dapat membantu UMKM dan korporasi besar dalam memenuhi tuntutan regulasi dan ekspektasi konsumen yang semakin peduli lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Wühle mengeksplorasi peran teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), blockchain, dan artificial intelligence dalam memungkinkan pengukuran keberlanjutan real-time dan transpar-an. Wühle menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengatasi tantangan greenwashing melalui verifikasi data yang independen. “Teknologi adalah amplifier niat baik; ia membuat keberlanjutan tidak hanya terukur tetapi juga terverifikasi,” jelasnya. Inovator Indonesia seperti startup di bidang renewable energy dan waste management dapat menerapkan prinsip-prinsip ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan skalabilitas solusi mereka.
Aspek kebijakan publik dan tata kelola keberlanjutan dinilai penting karena bisa mendorong ekosistem yang kondusif untuk transformasi keberlanjutan. Buku ini membahas bagaimana pemerintah dan otoritas publik dapat mengadopsi kerangka pengukuran keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan. Wühle mengusulkan “Sustainability Budgeting” yang mengalokasikan anggaran berdasarkan dampak keberlanjutan. “Kebijakan publik harus diukur bukan hanya oleh pertumbuhan ekonomi tetapi oleh peningkatan modal alam dan sosial,” serunya. Untuk Indonesia, pendekatan ini selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN namun memerlukan penguatan kapasitas institusional dan sistem data yang terintegrasi.
Amartya Sen (parafrase ide keadilan): “Capability approach” relevan untuk menilai apakah adaptasi meningkatkan kapabilitas manusia.
Bagian 3 — “Adaptation to Climate Change and Its Consequences Require Sustainability,” Michael Wühle memulai bagian ini dengan tesis yang sederhana tapi mendasar: respons terhadap perubahan iklim yang hanya bersifat reaktif atau teknis tidak akan cukup. Adaptasi—yaitu usaha untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan memanfaatkan peluang yang timbul—harus ditautkan pada tujuan keberlanjutan (sustainability) agar efektif, adil, dan tahan lama. Ia menekankan dua poin: (a) adaptasi harus menghindari “maladaptation” — tindakan yang menyelesaikan satu masalah sementara memperbesar risiko/ketidakadilan di sistem lain; dan (b) adaptasi perlu diukur dan dievaluasi dengan indikator yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Argumen sentralnya: tanpa kerangka keberlanjutan, upaya adaptasi sering menjadi proyek jangka pendek atau alat pemasaran politik/korporat, bukan transformasi struktural.
Wühle (inti): “Adaptation tanpa keberlanjutan mudah jadi maladaptation.”
Wühle mengusulkan kerangka tiga-lapis: Mitigasi | Adaptasi | Sustainability. Dalam kerangka ini adaptasi bukanlah lawan mitigasi; keduanya saling melengkapi—tetapi keduanya harus diukur dengan tolok ukur keberlanjutan. Ia menjelaskan bahwa banyak kebijakan adaptasi bersifat “tepian” (sea wall, kanal, pompa) yang memberi solusi cepat tetapi berbiaya tinggi, berdampak buruk terhadap ekosistem, dan tidak menjawab kerentanan sosial. Sebagai gantinya Wühle mempromosikan solusi berbasis alam (nature-based solutions), desain infrastruktur yang adaptif, dan kebijakan sosial seperti jaminan pendapatan atau relokasi partisipatif, semua dirancang agar memenuhi kriteria lingkungan, ekonomi, dan keadilan sosial. Intinya: adaptasi harus dipandang sebagai transformasi sistemik yang mengejar kesinambungan (long-term viability).
Prinsip-prinsip praktis Adaptasi
Wühle merumuskan beberapa prinsip operasional dan praktis yang menjadi panduan untuk adaptasi berkelanjutan:
- Do no harm (hindari maladaptation) — setiap intervensi harus diuji risiko eksternalitasnya.
- Multi-scalar design — intervensi harus bekerja di level rumah tangga, komunitas, kota, dan wilayah.
- Ecosystem integration — gunakan dan pulihkan layanan ekosistem (mangrove, rawa, perkebunan) sebagai garis pertahanan.
- Equity & participation — libatkan kelompok rentan sejak perancangan (bukan setelah kebijakan ditetapkan).
- Measurability — rancang indikator yang jelas, terukur, dan transparan.
Wühle menekankan bahwa prinsip-prinsip ini harus disematkan ke dalam proses perencanaan, pembiayaan, dan pemantauan adaptasi.
Pengukuran: metrik, indikator, dan sistem monitoring
Salah satu kontribusi teknis utama Wühle adalah pembahasan tentang bagaimana membuat adaptasi “terukur” — bukan hanya klaim naratif. Ia mengusulkan indikator multidemensional: indikator fisik (mis. frekuensi banjir, area mangrove), indikator sosio-ekonomi (mis. pendapatan rumah tangga pasca-bencana, akses layanan dasar), indikator institusional (mis. partisipasi publik, transparansi dana), dan indikator ekosistem (mis. keanekaragaman, fungsi layanan ekosistem). Ia juga menekankan perlunya baseline data, sistem pemantauan jangka panjang, dan penggunaan teknologi (satelit, sensor, sistem informasi geografis) yang digabung dengan pengetahuan lokal. Kunci yang ditegaskan: pengukuran bukan hanya untuk evaluasi donor, melainkan alat untuk pembelajaran adaptif (adaptive management).
Bagiamanapun upaya adaptasi perubahan iklim memerlukan biaya. Wühle membahas mekanisme pembiayaan: kombinasi dana publik, swasta, hibah internasional, dan instrumen inovatif (green bonds untuk adaptasi, asuransi mikro, mekanisme pembiayaan berbasis hasil). Namun ia memberi peringatan: pembiayaan yang berbasis pinjaman tanpa proteksi sosial bisa melipatgandakan beban bagi negara dan komunitas rentan. Ia mendukung model pembiayaan berbasis komunitas dan blended finance yang memprioritaskan akses bagi masyarakat paling terdampak, sambil mensyaratkan hasil keberlanjutan yang terukur. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi syarat utama agar dana tidak melahirkan proyek simbolik (greenwashing) tetapi benar-benar membangun ketahanan.
Making Sustainability Measurable
Making Sustainability Measurable menjadi inti metodologis dari seluruh buku Wühle. Ia berangkat dari pertanyaan sederhana tapi radikal: “Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar hidup dan bekerja secara berkelanjutan?” Wühle menolak gagasan bahwa keberlanjutan dapat didefinisikan hanya dengan niat baik atau slogan; ia menegaskan bahwa keberlanjutan harus diukur agar bisa dikelola, dievaluasi, dan ditingkatkan. Ia menulis, “What cannot be measured will not be managed.”Dari sini ia menguraikan prinsip-prinsip pengukuran keber-lanjutan yang mencakup tiga dimensi: lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tambahan dimensi keempat — personal meaning atau makna pribadi — yang ia anggap penting agar transformasi menjadi internal dan otentik.
Kemudian Wühle memperkenalkan kerangka SMART-Sustainability Indicators: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Namun ia memperluas konsep ini dengan menekankan pentingnya context-sensitivity: indikator keberlanjutan tidak universal, melainkan harus menyesuaikan ekosistem lokal dan budaya kerja. Dalam praktiknya, ia mendorong pembentukan Sustainability Scorecard yang berisi metrik konkret, seperti: konsumsi energi per unit produksi, emisi CO₂ per pekerja, jumlah jam pelatihan lingkungan, atau indeks kesejahteraan karyawan. Semua ini ia tekankan bukan sekadar alat audit, tetapi sarana pembelajaran organisasi.
Kekuatan bagian ini adalah upaya Wühle menghubungkan antara sains pengukuran dan etika tindakan. Ia menulis: “Numbers are not the end; they are mirrors that tell us who we are becoming.” Kalimat ini menandai pendekatan humanistik dalam sains keberlanjutan — bahwa pengukuran bukanlah reduksi, melainkan cara reflektif untuk memahami dampak diri. Relevansinya bagi Indonesia besar sekali: banyak korporasi, lembaga, dan pemerintah daerah yang mengklaim “hijau” tanpa kerangka metrik yang konsisten. Prinsip Wühle menuntut transparansi data dan akuntabilitas publik. Pengukuran keberlanjutan bisa mengubah praktik CSR menjadi proses pembelajaran sosial. Vaclav Smil pernah menulis, “Without quantification, sustainability is faith, not practice.”
Serupa yang diungkapkan Abdul Basith Muhammad (intelektual Muslim) yang menekankan, “Amal saleh menuntut hisab — perhitungan atas setiap tindakan.” Keduanya menggema dalam semangat Wühle: keberlanjutan yang nyata membutuhkan pengukuran dan tanggung jawab.
Wühle bergerak dari sistem menuju manusia. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan keberlanjutan adalah mindset dan kepemimpinan pribadi. Fazlun Khalid: “You cannot heal the planet unless you heal the self.” Keberlanjutan tidak mungkin diwujudkan hanya dengan alat ukur dan kebijakan; ia tumbuh dari kesadaran individu yang memahami keterhubungan dirinya dengan sistem kehidupan. Ia menulis, “Sustainability is not a project, it is a habit of being.”
Wühle membedakan antara technical success (pencapaian indikator) dan transformational success (perubahan nilai). Dalam pandangannya, organisasi yang benar-benar sukses adalah yang menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari identitas kolektif, bukan sebagai proyek tambahan. Untuk itu ia mengajukan empat “kunci sukses”:
- Clarity of purpose — memahami mengapa kita melakukan perubahan;
- Consistency — memastikan praktik harian selaras dengan nilai;
- Commitment — bertahan dalam ketidaknyamanan proses transisi;
- Community — bekerja dalam jaringan dukungan sosial.
Menariknya, Wühle menautkan konsep sukses ini dengan psikologi motivasi dan etika spiritual. Ia menulis, “Sustainability leadership begins with self-leadership.” Keberlanjutan, baginya, tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga kebijaksanaan.
Dalam konteks global saat ini — di mana banyak kebijakan hijau runtuh karena kepemimpinan yang terfragmentasi — pesan ini krusial. Untuk Indonesia, bagian ini relevan dalam konteks perubahan perilaku birokrasi dan korporasi: kepemimpinan yang berani mengubah pola konsumsi dan budaya kerja dari orientasi laba jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang. Albert Schweitzer: “Example is not the main thing in influencing others; it is the only thing.”
Rumi (dalam versi terjemahan): “Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.” Wühle sejalan dengan pandangan-pandangan ini — keberlanjutan sejati dimulai dari dalam diri dan diperluas ke tindakan kolektif.
Sustainability: The Future Is Waiting for You
Ini bagian penutup yang reflektif sekaligus inspirasional. Wühle menutup bukunya dengan nada optimistis dan mendalam: masa depan keberlanjutan bukan utopia yang jauh, melainkan ruang kemungkinan yang menunggu keberanian kita untuk bertindak. Ia menulis, “The future is not written — it is waiting for those who dare to measure, to change, and to care.”
Wühle mengajak pembaca meninggalkan sikap pasif dan rasa tidak berdaya di tengah krisis global. Ia menekankan konsep agency — kemampuan individu dan kolektif untuk mencipta arah sejarah baru. Menurutnya, setiap langkah kecil yang terukur — mengurangi limbah, mengubah pola makan, memperbaiki rantai pasok, atau memperkuat komunitas — adalah bagian dari mosaik perubahan besar. Dalam konteks krisis iklim, keputusasaan sering dianggap realistis, tetapi Wühle menegaskan bahwa “hope is not naïve — it is the engine of responsibility.”
Bagian ini sangat selaras dengan etika Islam tentang amanah dan tawakkul — bertindak dengan kesadaran tanggung jawab dan harapan. Dalam konteks Indonesia, pesan ini berarti mem-bangun narasi positif: bahwa perubahan kecil masyarakat lokal, komunitas nelayan, petani, atau pekerja kreatif, bila diukur dan dipelihara, dapat menciptakan gelombang besar trans-formasi keberlanjutan. Vaclav Havel: “Hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.”
Pemenang Nobel Lingkungan, Wangari Maathai suatu mengungkapkan bahwa: “It’s the little things citizens do. That’s what will make the difference.” Kalau kita membuka-buka lembaran kebijaksanaan dari Dunia Islam, maka akan menemukan Ali bin Abi Thalib ra. yang berkata: “He who has hope has everything.”
Ketiganya menegaskan dimensi moral dan spiritual dari keberlanjutan yang Wühle ajak pembaca untuk hidupi.
Relevansi Global dan Indonesia
Tiga bagian ini membentuk satu kesatuan pesan: Ukur keberlanjutan dengan jujur dan kontekstual (Bagian 7); Jadikan perubahan berkelanjutan sebagai etos dan gaya hidup (Bagian 11); Bangun harapan aktif dan tindakan terukur menuju masa depan yang adil (Bagian 13).
Bagi dunia yang kini menghadapi krisis ekologi, sosial, dan moral, pendekatan Wühle adalah jembatan antara data dan nilai.
Secara global, argumen Wühle relevan: kita menyaksikan gelombang kebijakan adaptasi yang reaktif—polder, seawall, dan relokasi terpusat—yang seringkali menghasilkan dampak sosial dan ekologis jangka panjang. Buku ini mengingatkan pembuat kebijakan agar berfokus pada solusi integratif. Di tingkat global, pesan Wühle menentang green capitalism yang hanya mengganti warna ekonomi tanpa mengubah nilainya. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan harus terukur tapi juga manusiawi.
Untuk Indonesia pesan-pesan ini sangat konkret: negara kepulauan dan tropis menghadapi ancaman dari kenaikan permukaan laut, penurunan muka tanah (subsidence), kebakaran lahan gambut, dan perubahan pola curah hujan yang memengaruhi pertanian. Implementasi prinsip Wühle merekomendasikan: restorasi mangrove dan rawa gambut sebagai perlindungan pesisir; diversifikasi mata pencaharian nelayan; perencanaan kota yang memprioritaskan resapan air dan ruang hijau; serta skema relokasi yang partisipatif. Pembiayaan adaptasi Indonesia harus menghindari pinjaman jangka panjang yang mengikat daerah, dan sebaliknya memprioritaskan bantuan berbasis hasil dan hibah pembangunan kapasitas lokal.
Bagi Indonesia — negeri yang kaya biodiversitas namun rapuh oleh deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya — pendekatan ini adalah panggilan etis. Mengukur berarti menatap realitas; dan menatap realitas berarti siap berubah. Indonesia memerlukan paradigma spiritual materialism reversal: bukan kekayaan yang menentukan nilai hidup, tetapi keseimbangan yang menumbuhkan kelimpahan sejati. Wühle mengingatkan bahwa “sustainability is a mirror”— cermin bagi bangsa untuk melihat siapa kita di tengah pusaran global.
Untuk Indonesia, ia relevan dalam:
- reformasi kebijakan lingkungan dan iklim agar berbasis indikator;
- pendidikan dan pelatihan kepemimpinan hijau di lembaga publik dan korporasi;
- penguatan ekonomi sirkular dan inovasi sosial di tingkat komunitas.
Dengan kata lain, Wühle menawarkan model keberlanjutan yang bisa diukur dan dihayati — bukan sekadar slogan, tetapi jalan hidup. Amartya Sen (parafrase ide keadilan): “Capability approach” relevan untuk menilai apakah adaptasi meningkatkan kapabilitas manusia.
Kritik dan Apresiasi
Beberapa kritikus menganggap pendekatan Wühle terlalu idealis dan sulit diterapkan pada korporasi besar yang beroperasi di pasar global. Namun keunggulan bukunya justru terletak pada humanisasi keberlanjutan — bahwa di balik sistem dan angka, ada kesadaran. Dalam ulasan Sustainability Times (2024), disebut: “Wühle’s book translates climate ethics into everyday discipline.” Ia memulihkan dimensi moral dalam pengukuran, hal yang sering hilang dalam birokrasi lingkungan. Apresiasi juga datang dari akademisi etika lingkungan Jerman, Anja Keller, yang menulis bahwa Wühle “mengajarkan keberlanjutan sebagai bentuk refleksi spiritual yang terukur, bukan sekadar checklist.”
Pada akhirnya, filosofi Wühle menuntun kita pada pemahaman baru: bahwa keberlanjutan adalah bentuk cinta yang dapat diukur. Mengukur bukan berarti meniadakan makna; justru dengan mengukur, kita menjaga makna agar tidak hilang. Dalam konteks spiritual, ini adalah bentuk muhasabah ekologis — perhitungan diri agar dunia tetap seimbang. Sebagaimana Jalaluddin Rumi berkata, “You are not a drop in the ocean; you are the entire ocean in a drop.” Maka setiap tindakan kecil yang kita ukur dan ubah adalah gema dari kesadaran kosmik yang lebih besar. Masa depan, seperti kata Wühle, “is waiting for those who dare to measure, to change, and to care.”
Pengamat kebijakan adaptasi cenderung memuji pendekatan Wühle yang menekankan pengukuran dan pencegahan maladaptation — itu memberikan alat konkret bagi perencana. Pujian sering menyorot kualitas praktik-oriented dan penekanan pada indikator. Kritik yang muncul (dari pengamat praktis) biasanya dua macam: (a) teknis-politik — argumen soal pengukuran dan data bisa menjadi beban bagi negara berkembang yang memiliki kapasitas institusional rendah; (b) normatif — ada kebutuhan untuk menegaskan lebih kuat aspek transformasi struktural (reformasi agraria, redistribusi modal) yang sering diluar lingkup proyek adaptasi biasa. Beberapa aktivis komunitas menilai bahwa buku ini kuat di level perencanaan, namun perlu lebih banyak contoh lapangan di negara-negara Global South yang merefleksikan keterbatasan kapasitas lokal. Secara keseluruhan, buku dipandang sebagai jembatan antara teori dan praktik adaptasi yang bertanggung jawab.
Rekomendasi operasional singkat
Berikut ringkasan langkah praktis berdasarkan bagian Wühle:
- Inventarisasi risiko & baseline data — tingkat desa hingga kabupaten.
- Skema partisipatif — forum lokal untuk merancang opsi adaptasi; hak veto komunitas terdampak.
- Prioritaskan Nature-based Solutions — mangrove, rawa gambut, urban green infrastructure.
- Rancang indikator adaptasi berkelanjutan: fisik, ekonomi, sosial, institusional.
- Blended finance & hibah — akses langsung untuk komunitas miskin pesisir/pertanian.
- Pemantauan jangka panjang & pembelajaran adaptif — review periodik, dashboard publik.
- Perlindungan sosial & jalur ekonomi alternatif — pekerja tambang/kelapa sawit membutuhkan program transisi.
Indikator contoh untuk “adaptasi yang berkelanjutan”
- Ekologi: luas mangrove/restorasi (ha), kualitas air (nutrien), keanekaragaman indikator (spesies penanda).
- Sosial: % rumah tangga dengan akses ke air bersih pasca-bencana, % rumah tangga dengan pendapatan diversifikasi.
- Ekonomi: biaya ekonomi bencana per kapita, % investasi publik untuk NbS.
- Institusional: % proyek adaptasi dengan konsultasi komunitas, transparansi pembiayaan (lacak dana).
Bagian 3 karya Wühle adalah seruan praktis: jika kita ingin bertahan dalam iklim yang berubah, maka adaptasi harus menjadi bagian dari strategi keberlanjutan menyeluruh—menghubungkan ekologi, ekonomi, dan keadilan sosial. Untuk Indonesia pesan ini bersifat mendesak dan aplikatif: dari restorasi gambut sampai perencanaan kota, dari jaminan sosial hingga akses pembiayaan lokal. Tantangan terbesarnya adalah kapasitas institusional dan politik: adaptasi berkelanjutan memerlukan tata kelola yang transparan, anggaran yang jelas, dan penguatan kapasitas komunitas. Namun jika diimplementasikan dengan prinsip yang Wühle uraikan—hindari maladaptation, ukur hasilnya, dan pusatkan keadilan—adaptasi bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih aman dan adil.
Bagian penutup buku ini memproyeksikan evolusi pengukuran keberlanjutan menuju standar global yang terintegrasi dan sistem sertifikasi yang lebih robust. Wühle mengakui tantangan implementasi, termasuk kompleksitas metodologis dan resistensi terhadap perubahan. “Perjalanan menuju keberlanjutan adalah maraton, bukan sprint; konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan,”simpulnya. Environmental economist Prof. Robert Costello memberi-kan apresiasi kritis: “Wühle telah memberikan kontribusi penting dalam operasionali-sasi keberlanjutan, meski perlu kewaspadaan terhadap reduksionisme berlebih-an.”Aktivis muda Indonesia, Melati Wijsen, menyatakan, “Generasi kami membutuhkan alat konkret, bukan sekadar wacana,” mengonfirmasi relevansi pendekatan Wühle bagi generasi mendatang.
Catatan Akhir: Mengukur agar Tidak Lupa
Membaca buku Making Sustainability Measurable seperti mengukur harapan di tengah krisis.
Michael Wühle memulai dari keyakinan sederhana: apa yang tidak diukur, akan dilupakan. Dalam dunia yang penuh retorika hijau, pengukuran menjadi bentuk dzikr — pengingat. Filsuf Prancis Michel Serres menyebut bahwa manusia modern kehilangan kontrak alami dengan bumi karena ia berhenti mendengar dan berhenti menghitung secara bermakna. Wühle, dalam semangat itu, mengembalikan pengukuran bukan sebagai kalkulasi teknokratik, melainkan sebagai kesadaran reflektif atas keberadaan.
Ketika kita mengukur emisi, limbah, atau energi, sesungguhnya kita sedang mengukur jejak diri di bumi. Setiap angka menjadi jejak moral. Numbers,” tulis Wühle, “are mirrors that tell us who we are becoming.” Ia mengajarkan bahwa keberlanjutan tidak bisa berhenti pada narasi moral — ia harus menjadi praktik yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi.
Filsafat Aristoteles mengajarkan aretê — kebajikan yang tumbuh dari keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks Wühle, keberlanjutan adalah bentuk aretê ekologis: hidup di antara ambisi dan kesederhanaan. Pengukuran keberlanjutan bukanlah cara mengendalikan alam, melainkan cara mengendalikan diri. Dengan menghitung konsumsi dan dampak, kita belajar tentang batas — dan batas, dalam filsafat, adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan.
Fazlun Khalid (esp. etika ekologis): “The earth is a trust (amanah)” — mengena pada prinsip keadilan antargeneras. Dalam Islam, konsep serupa muncul sebagai mizan (timbangan keseimbangan), sebagaimana disebut dalam QS Ar-Rahman: “Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan timbangan (mizan), supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu.” Dengan demikian, mengukur keberlanjutan adalah tindakan spiritual: menghidupkan kembali kesadaran terhadap mizan kosmik.
Sementara itu pada Bagian The Key to Your Success, buku ini menegaskan bahwa keberlanjutan dimulai bukan dari kebijakan, melainkan dari kesadaran. Di sini ia bersua dengan pemikiran Søren Kierkegaard dan Rumi — keduanya menekankan bahwa perubahan sejati bermula dari dalam diri. Wühle menyebut, “Sustainability leadership begins with self-leadership.” Dalam konteks ini, kepemimpinan keberlanjutan adalah tindakan eksistensial: menjadi pribadi yang sanggup bertanggung jawab di hadapan masa depan yang belum lahir. Martin Heidegger menyebutnya Fürsorge — kepedulian yang melampaui waktu kini. Pemimpin keberlanjutan bukan hanya manajer sumber daya, tetapi penjaga makna (custodian of meaning).
Wühle membawa keberlanjutan keluar dari ranah ekonomi menuju ranah spiritual. Ia berbicara tentang habit of being, kebiasaan keberadaan yang sadar dan peduli. Spiritualitas dalam arti ini bukan dogma, melainkan energi moral yang membuat manusia mampu menolak ketamakan sistemik. Ia sejalan dengan gagasan Thomas Berry yang menulis, “The universe is not a collection of objects, but a communion of subjects.”
Dalam cara berpikir ini, keberlanjutan bukan strategi, melainkan doa — bentuk kesetiaan terhadap kehidupan. Rumi pernah menulis, “Let the beauty we love be what we do.” Maka mengelola bumi adalah ibadah estetis: menciptakan harmoni antara tindakan dan cinta.
“Sustainability—The Future Is Waiting for You,” tulis Wühle, mengubah harapan menjadi etika tindakan. Wühle menolak sikap apatis di tengah krisis iklim; ia memaknai harapan bukan sebagai optimisme kosong, melainkan sebagai pilihan moral. Ia sejalan dengan Vaclav Havel: “Hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense.” Harapan, dalam filsafat Wühle, adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan yang belum terbentuk. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan kecil — menghemat air, menanam pohon, memperbaiki sistem — adalah kontribusi eksistensial terhadap keberlanjutan planet. Dalam konteks ini, manusia adalah co-creator, bukan korban perubahan iklim.
Bogor, 8 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Wühle, M. (2023). Making Sustainability Measurable: A Practical Book for Sustainable Living and Working.Hohenlinden, Germany.
- Berry, T. (1999). The Great Work: Our Way into the Future. Bell Tower.
- Havel, V. (1990). Disturbing the Peace. Vintage.
- Kierkegaard, S. (1843). Either/Or. Copenhagen.
- Rumi, J. (2004). The Essential Rumi. HarperOne.
- Serres, M. (1995). The Natural Contract. University of Michigan Press.
- Khalid, F. (2019). Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis. Islamic Foundation.
- Khalid, F. (parafrase ide). Environmental ethics and Islamic perspectives. (Sumber ide etis: tulisan-tulisan Fazlun Khalid tentang amanah/khalifah).
- Carson, R. (1962). Silent Spring. Houghton Mifflin.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Maathai, W. (2006). Unbowed: A Memoir. Knopf.
- Schweitzer, A. (1965). Out of My Life and Thought. Johns Hopkins University Press.
- Smil, V. (2019). Growth: From Microorganisms to Megacities. MIT Press.