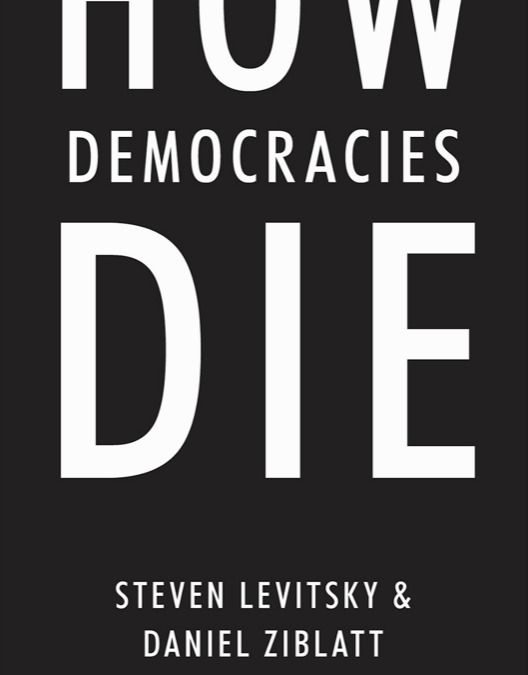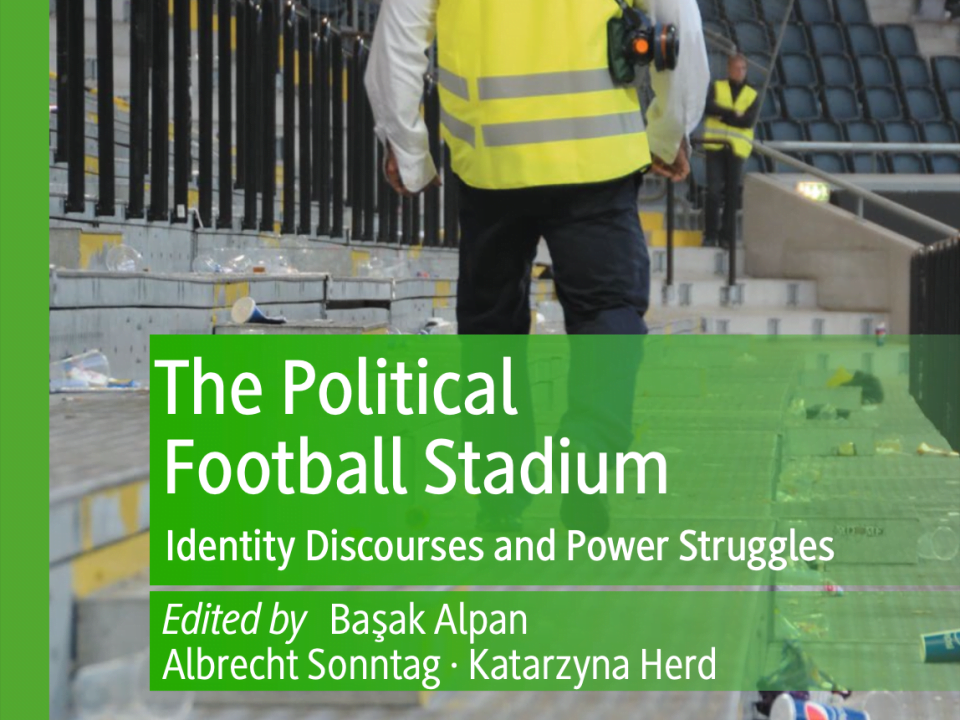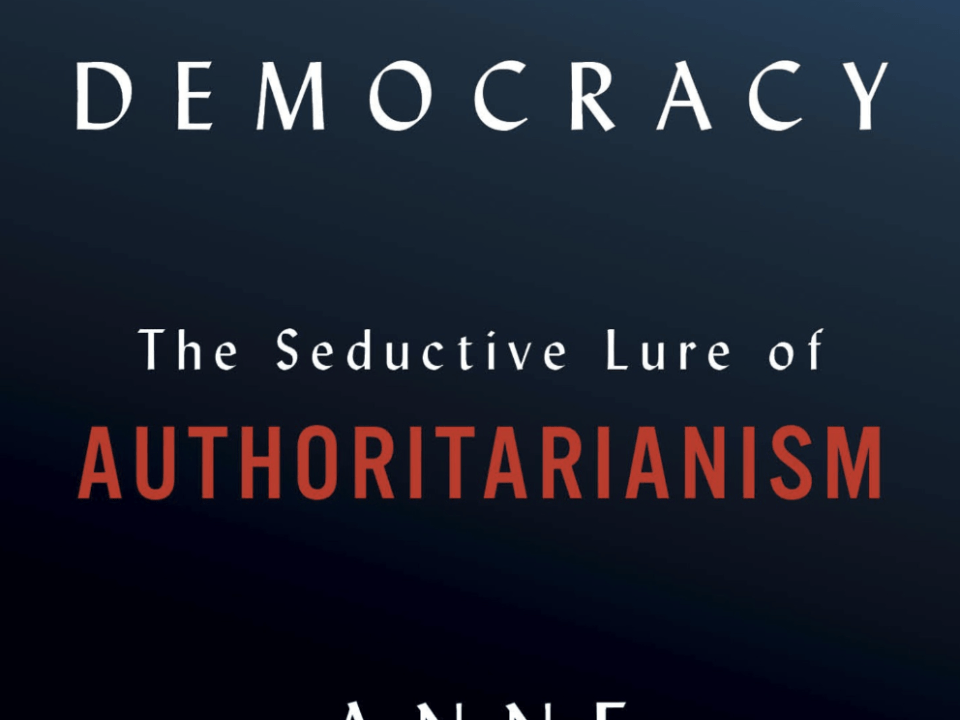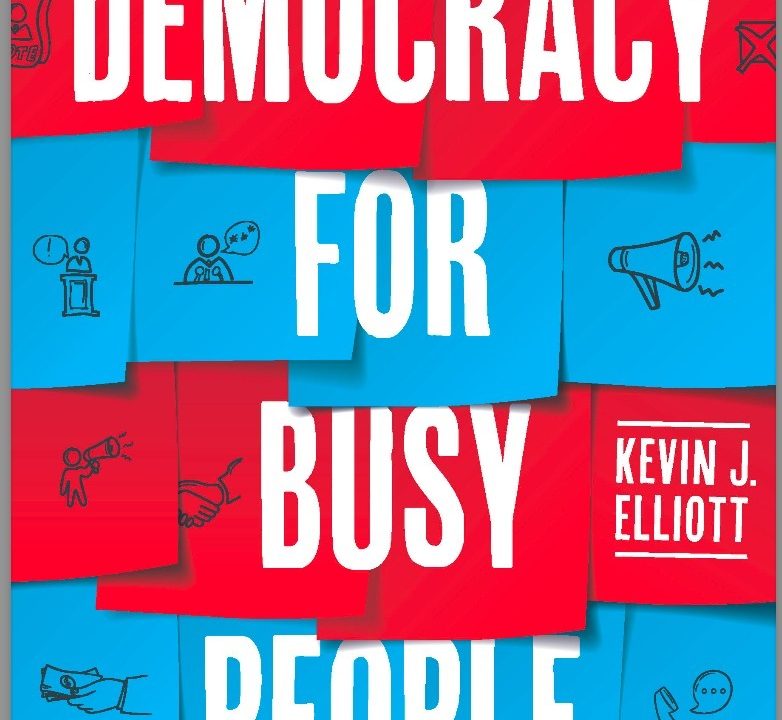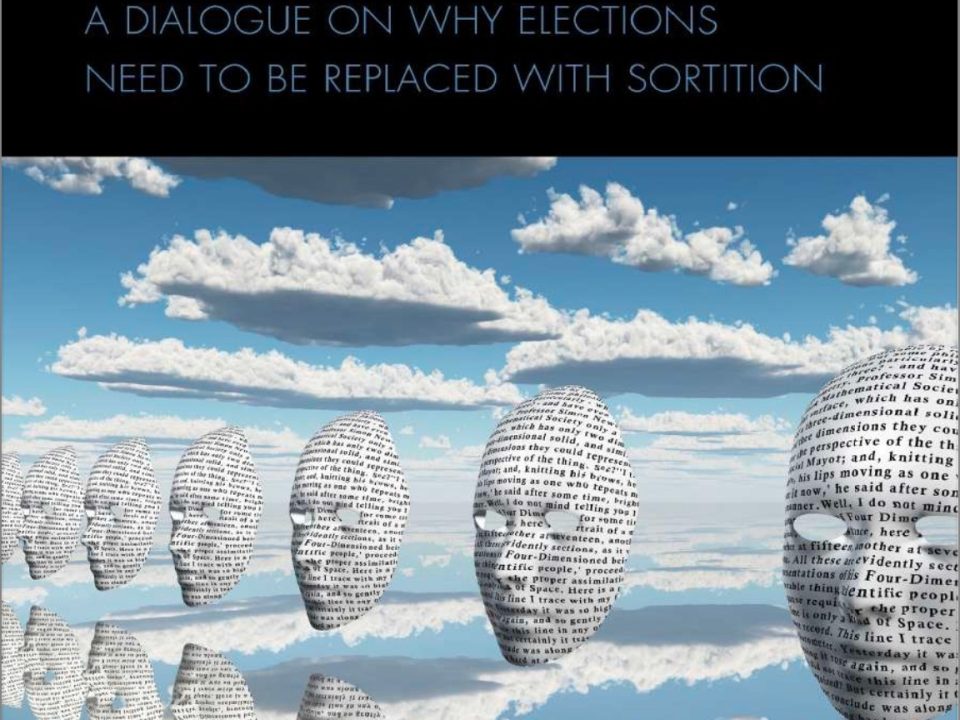“Is our democracy in danger?” begitulah pertanyaan yang menggelisahkan orang-orang yang mencermati perkembangan demokrasi baik di Amerika maupun di beberapa bagian lain di dunia. Pertanyaan itu pulalah yang dituliskan Levitsky dan Ziblatt sebagai pembuka bukunya, “How Democracies Die” (2018).
Kita ambil contoh Venezuela. Hugo Chavez adalah political outsider yang mencerca apa yang digambarkan sebagai elit pemerintahan yang korup, dan berjanji untuk membangun demokrasi yang lebih otentik dengan menggunakan kekayaan minyak yang luar biasa di negara itu untuk memperbaiki kehidupan orang miskin. Dengan terampil Chavez memanfaatkan kemarahan rakyat jelata Venezuela. Rakyat kebanyakan yang diantaranya merasa diabaikan atau diperlakukan buruk oleh partai-partai politik yang mapan. Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1998. “Demokrasi telah terinfeksi. Dan Chavez adalah satu-satunya antibiotik yang kita miliki,” demikian kata seorang wanita yang berasal dari negara bagian asal Chavez di Barinas.
Ketika Chavez meluncurkan revolusi yang dijanjikannya, dia melakukannya secara demokratis. Pada tahun 1999, diadakan pemilu bebas untuk majelis konstituante baru, dimana sekutunya memenangkan mayoritas yang signifikan. Ini memungkinkan para chavistas—sebutan untuk pera pendukung Chavez— untuk menulis konstitusi baru tanpa diganggu partai lain minoritas. Itu adalah move yang konstitusional dan demokratis, dan untuk memperkuat legitimasi, diadakan pemilihan presiden dan legislatif baru pada tahun 2000. Chavez dan sekutu-sekutunya memenangkannya.
Populisme Chavez memicu oposisi yang kuat, dan pada bulan April 2002, ia sempat ada upaya penggulingan oleh militer. Kudeta gagal. Chávez meendapatkan legitimasi demokratis yang makin kuat. Baru pada tahun 2003 Chávez mengambil langkah pertama yang jelas menuju otoritarianisme. Dengan dukungan publik yang memudar, ia menghentikan referendum yang dipimpin oposisi yang akan menuntutnya mundur — sampai setahun kemudian, ketika harga minyak yang meningkat telah membantunya untuk menang. Pada 2004, pemerintah memasukkan daftar hitam orang-orang yang telah menandatangani petisi tuntuntan mundur, tetapi pemilihan umum tahun 2006 kembali Chávez mampu mempertahankan posisi dengan kemenangan tipis. Rezim Chavista semakin represif setelah 2006, menutup sebuah stasiun televisi besar, menangkap atau mengusir politisi oposisi, hakim, dan tokoh media atas tuduhan yang meragukan, dan menghilangkan batasan masa jabatan presiden sehingga Chavez dapat tetap berkuasa tanpa batas.” Contoh kekuasaan lain juga dipaparkan dalam buku ini.
Kini membunuh demokrasi tidak selalu dengan senjata.
Jalan pemilihan umum yang bisa menimbulkan kerusakan itu juga bisa sangat berbahaya, meskipun melalui jalan yang berbeda, demikian tulis Levitsky dan Ziblatt. Dengan kudeta klasik, seperti di Chili, Pinochet, kematian demokrasi itu segera dan jelas bagi semua orang. Istana kepresidenan terbakar. Presiden dibunuh, dipenjarakan, atau dikirim ke pengasingan. Konstitusi ditangguhkan atau dibatalkan. Di jalan pemilihan umum, tidak satu pun dari hal-hal ini terjadi. Tidak ada tank di jalanan. Konstitusi dan lembaga demokrasi lainnya tetap berjalan. Orang-orang masih memilih. Para otokrat yang terpilih masih mempertahankan sebuah sisa demokrasi sambil memanipulasi isi substansinya. “The tragic paradox of the electoral route to authoritarianism is that democracy’s assassins use the very institutions of democracy—gradually, subtly, and even legally—to kill it.” (p.22).
Dengan merefleksikan situasi demokrasi di Amerika Serikat dengan terpilihnya Trump pada tampuk kekuasaan, penulis buku ini, sedihnya, menjawab “ya” atas pertanyaan “Is our democracy in danger?” Di belahan dunia yang lain fenomena yang terjadi di negeri Paman Sam itu juga terjadi. “American politicians now treat their rivals as enemies, intimidate the free press, and threaten to reject the results of elections. They try to weaken the institutional buffers of our democracy, including the courts, intelligence services, and ethics offices.” (p.10). Pernyataan ini serta merta, bagi saya, tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Tanah Air beta. Oposisi diperlakukan seperti musuh yang siap dihancurkan. Partai-partai diobok-obok agar mereka semua merapat ke rezim yang berkuasa. Media yang dikuasai para saudagar politik, dengan begitu, juga berada di bawah ketiak kekuasaan. Kebebasan pers tamat. Perbedaan pendapat diperlakuan dengan buruk. Kebebasan menyuarakan pendapat di depan publik dibatasi.
Levitsky dan Ziblatt lantas mengembangkan empat sinyal peringatan dini. Sinyal ini bisa digunakan untuk membantu kita mengidentifikasi dan mengetahui adanya gelagat otoriterian bagi orang-orang atau partai politik yang akan naik panggung kekuasaan. Ketika kita paham salah satu diantara empat sinyal peringatan dini itu maka kita harus waspada untuk mencegahnya. Pada dasarnya kekuasaan itu dikontestasi diantara para politisi dan partai politik maka mau tidak mau menjadi penting untuk mengetahui tabiat politisi dan partai politik tersebut. Hindari memilih politisi/calon legislatif atau partai politik yang mempunya gelagat dan juga jejak sejarah yang buruk bagi kehidupan demokratis. Sebab bagaimanapun partai politik dan orang-orang yang menggerakkannya adalah penjaga (atau pembunuh) demokrasi.
Kita periksa dalam empat sinyal itu dan kita sepatutnya khawatir jika ada politisi dan calon penguasa: 1) menolak rules of the game demokrasi, dalam perkataan dan tindakan, 2) menolak legitimasi oposisi, 3) memberi toleransi atau mendorong kekerasan, atau 4) mengindikasi keinginan untuk membatasi kebebasan sipil dari oposisi termasuk media.”
Bagi penulis buku ini dan kita saksikan bersama sebagian besar negara di dunia ini menyelenggarakan pemilu secara reguler. Tetapi tetap saja demokrasi bisa akan mati. Tetapi dengan cara yang berbeda. Sejak berakhirnya Perang Dingin, sebagian besar kekacauan demokratis tidak disebabkan oleh para jenderal dan tentara tetapi oleh pemerintah dan para legislatif yang terpilih melalui kotak suara. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah menumbangkan lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hongaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. “Kemunduran demokratik hari ini dimulai di kotak suara.”
Dalam beberapa waktu ini saya membaca buku yang menarik “How Democracies Die” (2018). Buku ini ditulis oleh Steven Levitsky dan rekannya Daniel Ziblatt. Saya browsing buku-buku soal itu karena penasaran dengan situasi urusan politik dan kekuasaan—yang seperti biasa—gaduh. Tetapi begitulah hidup kita yang kadang juga penuh kegaduhan. Biarlah. Saya ingin tahu saja pasti ada orang-orang yang menulis buku soal itu. Dan betul saja diantara beberapa buku tentang demokrasi terkini, buku inilah yang cukup menarik perhatian saya. Membaca bagaimana demokrasi mampus.
Apakah Indonesia ada gelagat yang demikian?
—Dwi R. Muhtaman—
Pontianak, 08102018
#BincangBuku #01