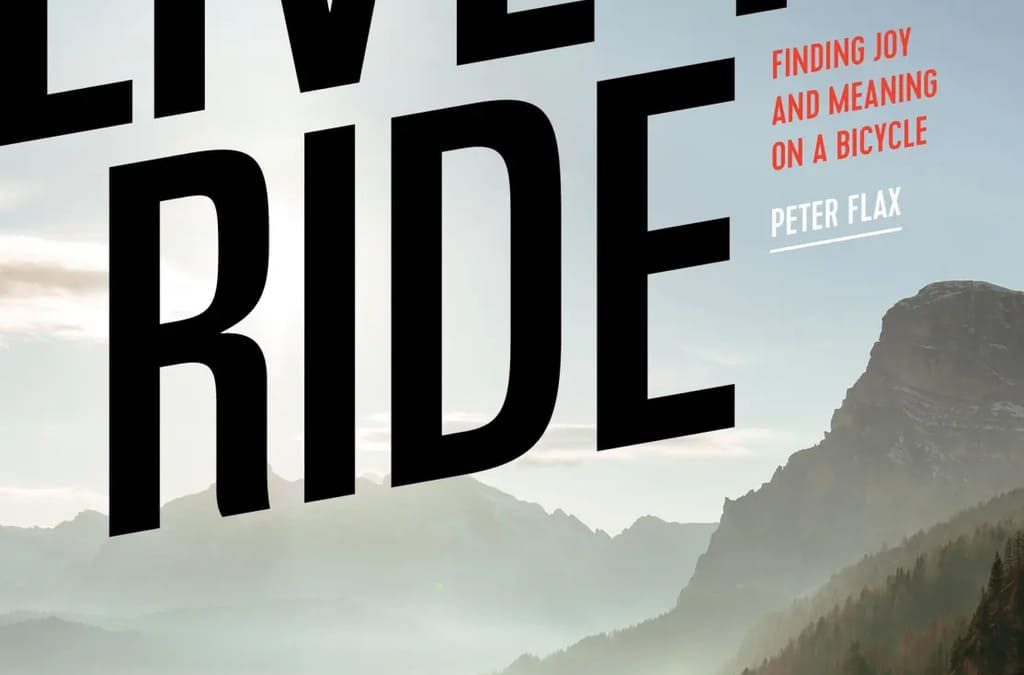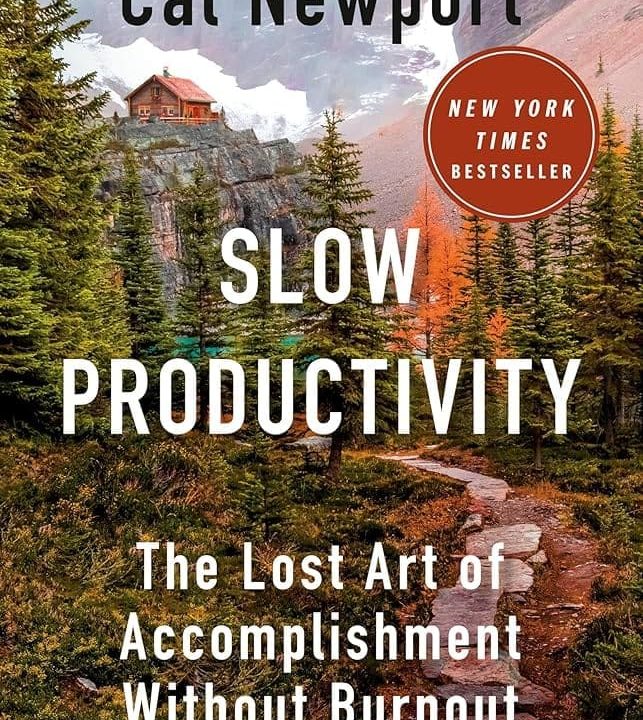Rubarubu #51
Live to Ride:
Mengayuh Sebagai Guru Kehidupan
Sepeda sebagai Jalan Pulang ke Diri Sendiri
Peter Flax membuka Live to Ride bukan dengan statistik atau manifesto, melainkan dengan pengalaman tubuh: momen ketika roda mulai berputar, napas menemukan ritmenya, dan dunia terasa sedikit lebih masuk akal. Dalam salah satu refleksi awalnya, Flax menulis bahwa bersepeda sering kali menjadi satu-satunya waktu ketika pikirannya “tidak ditarik ke masa lalu atau didorong ke masa depan, tetapi hadir sepenuhnya di sini.” Buku ini lahir dari pengalaman semacam itu—sepeda sebagai jalan masuk menuju kegembiraan sederhana dan makna yang tidak spektakuler, tetapi mendalam.
Live to Ride: Finding Joy and Meaning on a Bicycle karya Peter Flax (Artisan Books, New York, 2024), bukan buku teknis tentang sepeda, juga bukan sejarah seperti karya Evan Friss atau Jody Rosen. Ia adalah memoar reflektif, esai filosofis ringan, dan meditasi eksistensial yang memposisikan sepeda sebagai praktik hidup. Flax—seorang penulis, editor, dan pesepeda seumur hidup—menggunakan kisah perjalanan, percakapan, dan pengamatan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa bersepeda bukan sekadar aktivitas, melainkan cara berada di dunia.
Buku Live to Ride ini bergerak dalam potongan-potongan esai yang saling terhubung, masing-masing berangkat dari pengalaman konkret: bersepeda sendirian di pagi hari, perjalanan panjang lintas kota, kegagalan fisik, kecelakaan kecil, atau sekadar momen berhenti di pinggir jalan. Dari situ, Flax menarik benang refleksi tentang kebahagiaan, penderitaan, waktu, persahabatan, tubuh, dan ketidaksempurnaan hidup. Alih-alih menyusun argumen linear, Flax membiarkan narasi mengalir seperti perjalanan sepeda itu sendiri: ada tanjakan berat, turunan yang membebaskan, jalan buntu, dan kejutan yang tak direncanakan. Gaya ini memperkuat pesan inti buku: makna hidup tidak selalu ditemukan lewat tujuan besar, tetapi melalui proses bergerak dan bertahan.
Hidup itu seperti menyatukan antara sepeda, tubuh, dan kegembiraan yang tidak spektakuler. Salah satu tema sentral Live to Ride adalah joy—kegembiraan yang tidak meledak-ledak, tidak heroik, tetapi konsisten dan membumi. Flax menolak gagasan bahwa kebahagiaan harus selalu intens atau produktif. Bersepeda, baginya, justru mengajarkan kebahagiaan yang lahir dari pengulangan, kesederhanaan, dan penerimaan batas tubuh. Ia menulis tentang rasa sakit di kaki, paru-paru yang terbakar, dan kelelahan yang perlahan berubah menjadi ketenangan. Di sini, sepeda berfungsi sebagai guru stoik: mengajarkan bahwa penderitaan kecil adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang bermakna. Pandangan ini sejalan dengan refleksi filosofis klasik, misalnya Epictetus yang menekankan latihan diri (askesis) sebagai jalan menuju kebebasan batin. “Happiness is not the absence of difficulty,” tulis Flax, “but the willingness to keep pedaling through it.”
Makna, Waktu, dan Kehadiran
Flax juga menggunakan sepeda untuk merefleksikan hubungan manusia dengan waktu. Dalam dunia yang terobsesi kecepatan dan efisiensi, bersepeda menghadirkan tempo alternatif. Ia cukup cepat untuk membawa kita jauh, tetapi cukup lambat untuk memungkinkan perhatian.
Di atas sepeda, Flax merasakan waktu tidak sebagai sesuatu yang harus “dihemat” atau “dimaksimalkan”, melainkan dialami. Hal ini mengingatkan pada pemikiran Henri Bergson tentang durée—waktu sebagai pengalaman hidup, bukan sekadar satuan kronologis. Sepeda, dalam hal ini, menjadi teknologi yang membebaskan manusia dari tirani jam dan target.
Walaupun banyak kisah Flax bersifat personal dan soliter, Live to Ride juga menekankan dimensi sosial bersepeda. Ada dorongan untuk membangun dan merawat komunitas, ada saatnya untuk menikmati kesendirian. Sepeda membangun intensitas relasi manusia. Ia menulis tentang persahabatan yang tumbuh di jalan, percakapan singkat dengan orang asing, dan rasa saling memahami di antara pesepeda yang bahkan tidak saling mengenal. Namun Flax juga jujur tentang kesendirian. Bersepeda sendirian sering kali menjadi ruang kontemplasi, bahkan kesedihan. Buku ini tidak meromantisasi sepeda sebagai solusi atas semua masalah, tetapi mengakuinya sebagai ruang aman untuk menghadapi diri sendiri. Dalam hal ini, sepeda berfungsi seperti praktik spiritual—mirip khalwa dalam tradisi Islam atau meditasi dalam Zen—sebuah latihan hadir bersama diri dan dunia.
Bersepeda mengajarkan kita tentang etika kesederhanaan dan kehidupan yang cukup. Meskipun tidak secara eksplisit berbicara tentang krisis iklim atau degrowth, Live to Ride mengandung etika yang sangat relevan dengan isu-isu tersebut. Flax secara implisit mengkritik budaya konsumsi berlebihan, kompetisi ekstrem, dan obsesi performa. Ia lebih tertarik pada sepeda yang “cukup baik” daripada yang paling canggih, pada perjalanan yang bermakna daripada yang tercepat. Sikap ini selaras dengan gagasan enoughness yang dikemukakan oleh pemikir seperti E.F. Schumacher (Small Is Beautiful) dan, dalam konteks Asia, konsep qana’ah dalam etika Islam—merasa cukup sebagai dasar kebahagiaan dan keadilan.
Secara tematis, Live to Ride beresonansi dengan banyak pemikir dan tradisi. Albert Camus pernah menyinggung tentang penerimaan absurditas hidup dan kegigihan untuk terus bergerak. Islam juga mengajarkan untuk senantiasa melakukan pergerakan, khususnya dalam gagasan perjalanan (safar) sebagai sarana mengenal diri dan ciptaan Tuhan (QS Al-Ankabut: 20). Sebab pengalaman yang mendalam lahir dari kedekatan tubuh dengan lanskap (Arne Naess).
Mengayuh sebagai Cara Hidup
Dalam Introduction Live to Ride, Peter Flax mengajak pembaca masuk bukan ke dunia sepeda sebagai objek, melainkan ke pengalaman mengayuh sebagai cara berada di dunia. Ia tidak memulai dengan klaim besar tentang keberlanjutan, kesehatan, atau perubahan iklim. Ia memulai dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan, justru karena itu, lebih radikal: rasa senang yang tidak perlu dibenarkan. Kegembiraan yang tidak harus produktif. Perasaan hidup yang muncul ketika tubuh, jalan, dan waktu akhirnya berdamai satu sama lain.
Flax menulis tentang bagaimana sepeda hadir dalam hidupnya bukan sebagai alat prestasi, tetapi sebagai teman yang setia dalam berbagai fase kehidupan—masa muda yang gelisah, usia dewasa yang penuh tuntutan, dan momen-momen ketika dunia terasa terlalu bising. Mengayuh sepeda, baginya, adalah bentuk kembali ke ritme yang lebih manusiawi. Di atas sepeda, dunia tidak dihapus, tetapi diperlambat. Jarak tidak dieliminasi, tetapi dirasakan. Tubuh tidak dieksploitasi, tetapi diajak bekerja sama.
Nada pengantar ini sangat penting, karena sejak awal Flax menolak menjadikan sepeda sebagai simbol moral yang menggurui. Ia tidak berkata, “Anda harus bersepeda agar menjadi orang baik.” Sebaliknya, ia berkata, “Inilah yang terjadi ketika saya bersepeda: hidup terasa sedikit lebih jujur.” Pendekatan ini membuat Live to Ride terasa intim, nyaris seperti percakapan pelan di sela-sela istirahat di pinggir jalan.
Di sini, sepeda tampil sebagai teknologi yang tidak memisahkan manusia dari dirinya sendiri. Flax menyadari bahwa banyak teknologi modern bekerja dengan logika eksternal: lebih cepat, lebih jauh, lebih efisien. Sepeda, sebaliknya, bekerja dengan logika internal. Ia tidak bisa dipisahkan dari kondisi tubuh, cuaca, tanjakan, rasa malas, dan rasa senang. Mengayuh berarti menerima batas. Tetapi justru di dalam batas itulah muncul kebebasan.
Sebagai seorang pesepeda seumur hidup, Flax telah menulis tentang budaya bersepeda—dengan fokus pada advokasi, balapan, dan keindahan gaya hidupnya—selama beberapa dekade. Berdasarkan pengalaman panjang itu buku yang ditulisnya ini juga menekankan bahwa bersepeda mengajarkan jenis kebahagiaan yang jarang dibicarakan hari ini: kebahagiaan yang tidak spektakuler. Tidak ada “hasil” besar dari satu kali bersepeda. Tidak ada pencapaian permanen. Yang ada hanyalah pengalaman sementara—keringat, napas terengah, angin di wajah—yang segera berlalu. Namun, justru karena tidak bisa disimpan atau dikapitalisasi, pengalaman itu terasa murni.
Di titik ini, bagian Introduction Flax bertemu dengan pengalaman banyak pesepeda di Indonesia, meskipun konteks sosialnya sangat berbeda. Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau kota-kota kecil, bersepeda sering kali bukan pilihan gaya hidup ideal, melainkan negosiasi harian dengan kemacetan, lubang jalan, cuaca ekstrem, dan ketidakhadiran infrastruktur. Namun justru karena itu, pengalaman mengayuh menjadi sangat nyata. Tidak ada ilusi romantis. Setiap kilometer terasa mencerahkan.
Bagi banyak orang di Indonesia, bersepeda bukan soal “escape” dari dunia modern, tetapi bertahan hidup di dalamnya dengan martabat. Tukang ojek sepeda, pekerja informal, atau pesepeda pagi yang menyelinap di antara motor dan mobil mengalami apa yang Flax gambarkan secara filosofis: kehadiran penuh tubuh di ruang publik yang sering kali tidak ramah. Sepeda di sini bukan simbol kesederhanaan yang nyaman, melainkan praktik kesabaran dan keberanian sehari-hari.
Flax, yang merupakan mantan pemimpin redaksi Bicycling, majalah sepeda terbesar di dunia, dan saat ini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi AS untuk The Red Bulletin, majalah gaya hidup aktif yang diterbitkan oleh Red Bull, dalam pengantarnya, juga menyentuh dimensi waktu. Ia menulis bahwa bersepeda mengubah cara kita mengalami hari. Waktu tidak lagi terasa sebagai sumber daya yang harus diperas, tetapi sebagai aliran yang bisa diikuti. Ini sangat kontras dengan kehidupan urban kontemporer—baik di New York maupun Jakarta—di mana waktu selalu terasa kurang. Mengayuh sepeda, bahkan hanya sebentar, menciptakan celah kecil dalam rezim keterdesakan itu.
Dalam konteks Indonesia, celah ini sering muncul di pagi hari. Pesepeda subuh, jalanan yang belum sepenuhnya dikuasai kendaraan bermotor, udara yang masih bisa dihirup. Di saat itulah sepeda menjadi semacam ritual—bukan ritual religius formal, tetapi latihan kesadaran. Mirip dengan riyadhah dalam tradisi Islam: latihan tubuh yang sekaligus latihan batin. Tidak untuk pamer, tidak untuk hasil instan, tetapi untuk menjaga keseimbangan diri.
Introduction ini juga secara halus menyiapkan pembaca untuk satu tesis besar buku: bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dengan menambah, tetapi sering kali dengan mengurangi. Mengurangi kecepatan. Mengurangi ekspektasi. Mengurangi jarak antara tubuh dan dunia. Sepeda menjadi sarana pengurangan itu—less, tetapi terasa more.
Flax tidak mengidealkan bersepeda sebagai solusi universal. Ia mengakui ketidaknyamanan, rasa bosan, bahkan ketakutan. Tetapi justru kejujuran inilah yang membuat pengantarnya kuat. Hidup, seperti bersepeda, tidak selalu menyenangkan. Tetapi ada nilai dalam terus mengayuh, dalam menerima bahwa kegembiraan sering muncul bukan ketika semua berjalan sempurna, melainkan ketika kita tetap bergerak meski tidak pasti.
Sebagai pengantar, Introduction Live to Ride bekerja seperti tanjakan awal: tidak terlalu curam, tetapi cukup untuk mengubah napas dan cara pandang. Pembaca diajak memahami bahwa buku ini bukan tentang sepeda semata, melainkan tentang bagaimana menjalani hidup yang cukup, hadir, dan bersahabat dengan keterbatasan. Di dunia yang menuntut kita selalu lebih cepat dan lebih banyak, Flax mengusulkan sesuatu yang terdengar sederhana—bahkan naif—tetapi sebenarnya subversif: hidup dengan ritme kayuhan.
Dan di situlah sepeda, baik di jalan-jalan New York maupun gang-gang kota Indonesia, menjadi bahasa universal: bahasa tubuh yang berkata bahwa hidup tidak harus dikejar. Ia bisa dikayuh.
Peter Flax yang tulisannya telah muncul di puluhan media, termasuk Outside, Men’s Health, majalah New York dan Los Angeles, Peloton, Runner’s World, Bicycling, dan Men’s Journal ini merancang kerangka tulisan berdasarkan enam tema: ADVENTURE, SPEED, UTILITY, NATURE, COMPETITION, dan SELF-EXPRESSION. Masing-masing dijelaskan dengan lugas dan penuh makna filosofis.
Adventure: Mengayuh ke Ketidakpastian yang Bersahabat
Bagi Peter Flax, petualangan tidak selalu berarti menaklukkan gunung atau menjelajah benua. Dalam bagian Adventure, ia justru menggeser makna petualangan ke sesuatu yang lebih halus dan sehari-hari: kesediaan untuk keluar dari rutinitas yang kaku dan menyerahkan diri pada ketidakpastian kecil. Sepeda memungkinkan bentuk petualangan semacam ini—bukan petualangan heroik, melainkan petualangan manusiawi.
Mengayuh sepeda membuka kemungkinan untuk tersesat tanpa benar-benar hilang. Jalan kecil yang tidak ada di peta, gang sempit yang berakhir di warung kopi, tanjakan yang awalnya tampak sepele tetapi menguras napas. Flax menulis bahwa sepeda menciptakan hubungan baru dengan ruang: kita tidak sekadar melewati lanskap, tetapi masuk ke dalamnya. Tidak ada kaca yang memisahkan tubuh dari udara, suara, dan bau. Petualangan muncul bukan dari tujuan, melainkan dari perjalanan itu sendiri.
Di Indonesia, makna petualangan ini terasa sangat nyata. Bersepeda di desa, misalnya, berarti mengikuti kontur alam dan ritme sosial sekaligus. Jalan tanah yang berubah menjadi lumpur setelah hujan, anak-anak yang melambaikan tangan, suara adzan yang melintas dari satu kampung ke kampung lain. Petualangan tidak dikurasi oleh industri pariwisata; ia muncul spontan dari interaksi dengan tempat dan manusia. Flax menekankan bahwa sepeda mengajarkan kita untuk tidak mengontrol segalanya. Ada hari ketika angin melawan, rantai berbunyi aneh, atau tubuh terasa berat tanpa sebab. Petualangan bukan tentang mengalahkan rintangan, melainkan tentang belajar berdamai dengannya. Dalam hal ini, sepeda menjadi guru kerendahan hati—ia mengingatkan bahwa hidup tidak harus selalu efisien untuk menjadi bermakna.
Speed: Kecepatan yang Dipilih, Bukan Dipaksakan
Dalam bagian Speed, Flax menawarkan refleksi yang nyaris filosofis tentang kecepatan. Ia tidak menolak kecepatan sepenuhnya. Ia juga tidak memuja kelambatan sebagai nilai moral absolut. Yang ia kritik adalah kecepatan yang tidak kita pilih, kecepatan yang dipaksakan oleh sistem—oleh jadwal, algoritma, dan tuntutan produktivitas.
Sepeda, bagi Flax, menawarkan kecepatan yang bersifat relasional. Ia cukup cepat untuk membuat jarak terasa mungkin, tetapi cukup lambat untuk membuat dunia tetap terbaca. Di atas sepeda, kita tidak melesat melewati kota; kita bernegosiasi dengannya. Setiap tanjakan memperlambat, setiap turunan mempercepat. Kecepatan bukan sesuatu yang konstan, melainkan hasil dialog antara tubuh dan lingkungan. Pengalaman ini sangat kontras dengan logika kendaraan bermotor modern, di mana kecepatan sering menjadi tujuan itu sendiri. Flax mengamati bahwa semakin cepat kita bergerak, semakin sedikit kita benar-benar hadir. Sepeda, sebaliknya, memulihkan hubungan antara waktu dan pengalaman. Lima kilometer tidak lagi sekadar angka, tetapi serangkaian sensasi: denyut jantung, perubahan cahaya, suara roda di aspal.
Di kota-kota Indonesia, di mana kemacetan telah menjadi kondisi permanen, sepeda sering kali menawarkan paradoks menarik: ia terasa lebih cepat justru karena ia lebih lambat. Pesepeda tidak terjebak dalam logika berhenti–jalan–berhenti yang melelahkan mental. Mereka bergerak dengan ritme yang stabil, meski sederhana. Dalam kemacetan Jakarta, misalnya, sepeda menciptakan flow kecil di tengah kekacauan.
Flax melihat di sini pelajaran eksistensial: hidup yang terlalu cepat sering kali kehilangan arah, sementara hidup yang terlalu lambat bisa kehilangan daya. Sepeda berada di tengah—cukup cepat untuk bergerak maju, cukup lambat untuk merasakan makna. Kecepatan yang dipilih ini menjadi bentuk kebebasan yang jarang kita sadari pentingnya.
Utility: Kegunaan yang Tidak Kehilangan Jiwa
Bagian Utility membawa refleksi Flax ke wilayah yang sering diremehkan: kegunaan. Dalam budaya modern, sesuatu dianggap bernilai jika ia efisien, serbaguna, dan menghemat waktu. Flax tidak menyangkal bahwa sepeda adalah alat yang sangat berguna—untuk bekerja, berbelanja, mengantar anak, atau sekadar berpindah tempat. Namun ia menolak gagasan bahwa kegunaan harus mengorbankan kesenangan atau makna.
Sepeda, tulis Flax, adalah contoh langka dari teknologi yang berguna tanpa mengalienasi. Ia tidak membuat penggunanya pasif. Ia tidak memisahkan fungsi dari pengalaman. Saat kita menggunakan sepeda, kita tetap sepenuhnya hadir sebagai subjek, bukan sekadar operator mesin. Tubuh bekerja, pikiran mengamati, dan tujuan tercapai tanpa kehilangan rasa.
Dalam konteks Indonesia, aspek kegunaan ini sangat menonjol. Di banyak kota kecil dan desa, sepeda masih menjadi tulang punggung ekonomi mikro: pedagang sayur, tukang servis, pengantar barang. Sepeda bukan simbol gaya hidup hijau kelas menengah, melainkan alat bertahan hidup. Namun justru di situlah nilai filosofisnya muncul: kegunaan yang tidak terpisah dari kehidupan sosial.
Flax menulis bahwa sepeda mengaburkan batas antara bekerja dan hidup. Perjalanan menuju tempat kerja tidak sepenuhnya terpisah dari pengalaman hidup itu sendiri. Tidak ada transisi brutal dari “waktu pribadi” ke “waktu produktif.” Mengayuh menjadi jembatan yang halus antara keduanya. Lebih jauh, Utility dalam perspektif Flax juga menyentuh etika konsumsi. Sepeda tidak menuntut pembaruan terus-menerus. Ia bisa diperbaiki, diwariskan, dan digunakan lintas generasi. Dalam dunia yang dibangun di atas keusangan terencana, sepeda berdiri sebagai teknologi yang membangkang secara diam-diam.
Di Indonesia, di mana budaya memperbaiki masih hidup—tambal ban, bengkel kecil di pinggir jalan—sepeda menemukan ekosistem alaminya. Ia tidak bergantung pada sistem besar. Ia hidup dari relasi lokal, keterampilan tangan, dan kepercayaan.
Nature: Tubuh Manusia sebagai Bagian dari Lanskap
Dalam bagian Nature, Peter Flax menempatkan sepeda bukan sekadar alat untuk bergerak di alam, tetapi sebagai sarana untuk berada di dalamnya. Bersepeda, bagi Flax, adalah pengalam-an ekologis yang intim—bukan dalam pengertian romantik yang abstrak, melainkan dalam perjumpaan fisik antara tubuh dan dunia. Udara yang dihirup, panas yang menempel di kulit, angin yang melawan atau mendorong, semuanya membentuk dialog langsung antara manusia dan lanskap.
Flax menulis bahwa sepeda menghapus ilusi dominasi atas alam. Kita tidak “menguasai” tanjakan; kita bernegosiasi dengannya. Kita tidak menaklukkan cuaca; kita menyesuaikan diri. Dalam pengalaman ini, alam tidak tampil sebagai latar belakang pasif, tetapi sebagai mitra aktif yang menentukan ritme dan batas.
Di Indonesia, relasi ini terasa sangat kuat. Bersepeda di pesisir berarti menghadapi angin laut yang asin dan tak terduga; di pegunungan, kabut bisa turun tanpa peringatan; di sawah, jalan sempit mengajarkan kehati-hatian dan rasa hormat. Sepeda memaksa pesepeda untuk membaca tanda-tanda alam yang sering diabaikan oleh pengguna kendaraan bermotor: perubahan cahaya, aroma hujan, suara serangga. Flax melihat di sini suatu pemulihan kesadaran ekologis yang sederhana namun mendalam. Tanpa perlu jargon atau ideologi, sepeda mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang bergantung pada kondisi alam. Dalam krisis iklim global, pengalaman ini menjadi penting bukan karena ia menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi karena ia membentuk kepekaan etis—rasa ikut terlibat, bukan terpisah.
Competition: Melawan Orang Lain atau Mendengarkan Diri Sendiri
Bagian Competition dalam Live to Ride ditulis dengan ambivalensi yang jujur. Flax tidak menolak kompetisi sepenuhnya; ia mengakui daya tariknya, energi yang ia bangkitkan, dan peran historisnya dalam budaya sepeda. Namun ia juga mengingatkan bahwa kompetisi, jika tidak disadari, bisa menggeser makna bersepeda dari pengalaman menjadi performa. Bagi Flax, kompetisi yang paling bermakna bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan batas-batas internal: rasa malas, ketakutan, dan keraguan diri. Sepeda menyediakan arena di mana ukuran kemenangan tidak selalu berupa podium, melainkan kemampuan untuk tetap mengayuh ketika tubuh ingin berhenti.
Di Indonesia, kompetisi bersepeda sering hadir dalam dua wajah. Di satu sisi, ada event balap yang semakin profesional dan tersponsori, mengikuti logika olahraga modern. Di sisi lain, ada “kompetisi sunyi” yang jauh lebih umum: siapa yang paling sabar di jalan rusak, siapa yang paling konsisten mengayuh meski hujan, siapa yang paling mampu berbagi ruang dengan pengguna jalan lain.
Flax menegaskan bahwa sepeda mengajarkan bentuk kompetisi yang tidak harus merusak solidaritas. Kita bisa berusaha menjadi lebih cepat tanpa merendahkan yang lain. Kita bisa mendorong diri sendiri tanpa harus menjadikan orang lain sebagai musuh. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan terpolarisasi, pelajaran ini terasa relevan jauh melampaui konteks olahraga.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua perjalanan perlu diukur. Tidak setiap kayuhan harus dicatat, diunggah, dan dibandingkan. Ada nilai dalam bersepeda yang tidak bisa dikonversi menjadi data—dan justru di situlah maknanya bertahan.
Self-Expression: Identitas yang Bergerak
Dalam Self-Expression, Flax menyentuh dimensi paling personal dari bersepeda. Sepeda, tulisnya, adalah perpanjangan dari kepribadian. Pilihan jenis sepeda, cara berpakaian, rute yang diambil, bahkan cara mengayuh, semuanya menjadi bentuk ekspresi diri yang bergerak di ruang publik.
Namun Flax berhati-hati agar ekspresi diri tidak jatuh menjadi konsumsi identitas. Ia mengkritik kecenderungan budaya sepeda modern yang terlalu fokus pada citra—sepeda sebagai simbol status, gaya hidup, atau afiliasi kelas. Baginya, ekspresi diri sejati muncul ketika sepeda membantu seseorang menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri, bukan lebih mirip dengan citra ideal yang dipasarkan.
Di Indonesia, ekspresi diri melalui sepeda tampak dalam keragaman yang kaya. Ada sepeda tua yang dirawat dengan penuh kasih, sepeda lipat yang praktis, sepeda gunung yang penuh lumpur, hingga sepeda rakitan yang mencerminkan kreativitas lokal. Setiap sepeda menceritakan kisah sosial dan personal: tentang akses, selera, dan kondisi hidup.
Flax melihat bahwa bersepeda memungkinkan ekspresi diri yang tidak agresif. Kita hadir di ruang publik tanpa mendominasi. Kita terlihat, tetapi tidak bising. Dalam kota-kota yang penuh klakson dan iklan, sepeda menawarkan bentuk kehadiran yang lebih lembut—namun tidak pasif. Lebih dalam lagi, Self-Expression juga berarti menemukan suara batin. Banyak pesepeda, tulis Flax, menemukan bahwa ide-ide terbaik mereka muncul saat mengayuh. Pikiran bergerak mengikuti ritme tubuh. Dalam keheningan relatif ini, sepeda menjadi ruang kontemplasi bergerak.
Live to Ride: Finding Joy and Meaning on a Bicycle karya Peter Flax kaya hikmah, filsafat hidup, dan pelajaran etis yang dapat kita bawa melampaui dunia sepeda. Sejak pindah ke Los Angeles sepuluh tahun yang lalu, ia hanya menggunakan sepeda untuk berkomuter, mengayuh hampir 100.000 mil hanya untuk pergi dan pulang dari tempat kerjanya. 100.000 mil setara dengan 160.934,4 kilometer. Jarak ini setara dengan:
- Mengelilingi Bumi kira-kira 4 kali (keliling Bumi di khatulistiwa adalah sekitar 40.075 km).
- Hampir separuh jarak dari Bumi ke Bulan (jarak rata-rata Bumi-Bulan adalah sekitar 384.400 km).
Itu adalah jarak yang sangat luar biasa untuk ditempuh hanya dengan bersepeda untuk keperluan komuter!
Bersepeda dan Hikmah Dasar
Hikmah paling mendasar dari Live to Ride adalah bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi dalam gerak yang konsisten, sadar, dan berirama. Gerak sebagai cara hidup yang bermakna. Bersepeda menjadi metafora kehidupan: kita bergerak bukan karena tujuan akhir semata, melainkan karena proses bergerak itu sendiri memberi makna. Flax menunjukkan bahwa kebahagiaan yang lahir dari bersepeda bersifat embodied happiness—kebahagiaan yang dirasakan oleh tubuh, bukan hanya dipikirkan oleh pikiran. Dalam dunia modern yang terlalu kognitif dan abstrak, sepeda mengembalikan manusia pada kebijaksanaan tubuh: kelelahan, napas, denyut jantung, dan rasa cukup. Hikmahnya sederhana namun radikal: hidup tidak harus dipercepat untuk menjadi bernilai.
Bersepeda juga mengandung filsafat kehidupan: kesederhanaan yang aktif, bukan pasif. Buku ini mengajarkan suatu filsafat kesederhanaan yang aktif. Sepeda bukanlah simbol asketisme yang menolak dunia, melainkan cara berada di dunia dengan intensitas yang tepat. Ia menolak dua ekstrem: konsumsi berlebihan dan penarikan diri total. Flax tidak mengajarkan “kurangi segalanya”, melainkan “temukan ukuran yang pas”. Dalam hal ini, Live to Ride sejalan dengan filsafat just enough dan etika pasca-pertumbuhan (post-growth ethics): hidup baik bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mengalami lebih dalam.
Filsafat ini mengajarkan bahwa:
- Kecepatan tidak identik dengan kemajuan
- Teknologi tidak selalu harus semakin kompleks
- Kenyamanan berlebihan justru menjauhkan kita dari rasa hidup
Sepeda hadir sebagai teknologi yang cukup: cukup cepat, cukup sederhana, cukup menantang, cukup manusiawi.
Sepede menumbuhkan kesadaran etika relasional: tubuh, alam, dan orang lain. Salah satu pelajaran etis terpenting dari buku ini adalah bahwa bersepeda melatih kepekaan relasional. Kita belajar membaca alam, menghormati ruang publik, dan berbagi jalan dengan orang lain.
Flax menekankan bahwa pesepeda tidak bisa bersikap egois tanpa segera menuai konsekuensinya. Jalan sempit, cuaca, tanjakan, dan kehadiran orang lain memaksa kita untuk:
- Bersabar
- Mengalah
- Mendengarkan ritme sekitar
Dalam konteks krisis iklim, etika ini menjadi sangat relevan. Sepeda mengajarkan bahwa solusi ekologis tidak selalu datang dari inovasi besar, tetapi dari perubahan cara kita berelasi dengan dunia. Ini adalah etika rendah hati: manusia bukan pusat segalanya, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang lebih luas.
Pada sisi lain sepeda juga menjadi pelajaran tentang kompetisi dan diri. Live to Ride mengajar-kan pembacaan ulang terhadap makna kompetisi. Flax tidak menolak kompetisi, tetapi menggeser arahnya. Kompetisi yang sehat adalah kompetisi dengan diri sendiri—bukan untuk menjadi lebih unggul dari orang lain, melainkan untuk menjadi lebih jujur terhadap kemampuan dan batas diri. Pelajarannya jelas: hidup bukan perlombaan linier, melainkan perjalanan dengan ritme yang berbeda-beda. Dalam masyarakat yang obsesif pada peringkat, kecepatan, dan produktivitas, sepeda mengajarkan cara bersaing tanpa menghancurkan diri.
Kemenangan sejati bukan tiba lebih dulu, tetapi tiba dengan utuh.
Sepeda memberi makna kebebasan: otonomi yang sederhana. Bagi Flax, kebebasan bukanlah ketiadaan batas, melainkan kemampuan mengatur ritme sendiri. Sepeda memberi otonomi yang nyata: kita memilih kapan berhenti, kapan melaju, kapan berbelok. Tidak ada mesin yang sepenuhnya mengambil alih keputusan. Ini adalah pelajaran politik yang halus namun penting. Di dunia yang semakin dikendalikan oleh sistem besar—energi fosil, infrastruktur raksasa, logika pasar—sepeda menjadi simbol kebebasan yang berskala manusia. Kebebasan yang tidak spektakuler, tetapi berkelanjutan.
Pelajaran eksistensial: kegembiraan sebagai tindakan etis. Salah satu kontribusi paling khas Live to Ride adalah penegasan bahwa kegembiraan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan etis. Flax menolak narasi bahwa hidup berkelanjutan harus selalu berat, suram, dan penuh pengorbanan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kegembiraan yang sederhana—meluncur di pagi hari, menaklukkan tanjakan kecil, merasakan angin—adalah sumber energi moral. Tanpa kegembiraan, perubahan gaya hidup tidak akan bertahan.
Dengan kata lain: merawat dunia dimulai dari merawat rasa senang hidup di dalamnya.
Catatan Akhir: Hidup untuk Mengayuh
Sepeda pada akhirnya bisa menjadi guru kehidupan. Jika Live to Ride dibaca sebagai satu kesatuan, sepeda tampil bukan sekadar sebagai alat, melainkan sebagai guru kehidupan. Ia mengajarkan:
- Cukup, bukan berlebih
- Gerak, bukan stagnasi
- Kesadaran, bukan pelarian
- Relasi, bukan dominasi
Dalam dunia yang semakin cepat, bising, dan eksploitatif, hikmah terbesar dari buku ini adalah keberanian untuk memilih jalan yang lebih pelan namun lebih manusiawi. Sepeda, dalam pandangan Peter Flax, bukan jawaban untuk semua masalah. Tetapi ia adalah pertanyaan yang terus mengingatkan: Bagaimana kita ingin bergerak di dunia ini—dan dengan harga apa?
Dan mungkin, di sanalah makna hidup modern mulai menemukan kembali keseimbangannya.
Penutup Sementara: Tiga Dimensi, Satu Etika Hidup. Melalui Adventure, Speed, dan Utility, Peter Flax sebenarnya sedang merumuskan sebuah etika hidup yang sederhana namun radikal. Petualangan tanpa dominasi. Kecepatan tanpa keterasingan. Kegunaan tanpa kehilangan jiwa. Sepeda menjadi medium konkret untuk etika ini—bukan sebagai metafora abstrak, tetapi sebagai praktik harian.
Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk lebih jauh, lebih cepat, dan lebih efisien, sepeda mengajukan pertanyaan yang pelan namun mengganggu: cukup seberapa cepat, seberapa jauh, dan seberapa berguna agar hidup tetap terasa hidup? Di jalanan Indonesia yang padat, berdebu, dan penuh kontradiksi, pertanyaan itu bergema dengan sangat nyata—di setiap kayuhan yang memilih untuk tetap bergerak, meski dunia terasa terlalu cepat.
Melalui Nature, Competition, dan Self-Expression, Peter Flax memperluas makna bersepeda dari aktivitas fisik menjadi praktik eksistensial. Sepeda menghubungkan manusia dengan alam tanpa romantisasi berlebihan, menawarkan tantangan tanpa kekerasan simbolik, dan membuka ruang ekspresi diri tanpa harus tunduk pada logika konsumsi. Dalam konteks Indonesia—dengan alam yang rentan, kota yang padat, dan masyarakat yang beragam—etika bersepeda semacam ini bukan sekadar gaya hidup alternatif, melainkan kemungkinan masa depan. Masa depan di mana bergerak tidak selalu berarti merusak, bersaing tidak harus menyingkirkan, dan mengekspresikan diri tidak harus menguasai ruang.
Jika sepeda adalah bahasa, maka bagian-bagian ini menunjukkan bahwa ia berbicara dengan aksen yang lembut namun tegas: hidup bisa bergerak maju tanpa harus melupakan dunia tempat ia berpijak.
Pada akhirnya, Live to Ride bukan buku tentang bagaimana menjadi pesepeda yang lebih cepat atau lebih kuat. Ia adalah buku tentang bagaimana hidup dengan sedikit lebih jujur, lebih sabar, dan lebih hadir. Sepeda menjadi metafora sekaligus praktik nyata: hidup tidak harus spektakuler untuk bermakna; ia hanya perlu terus dijalani.
Buku ini melengkapi narasi besar tentang sepeda yang telah dibangun oleh Two Wheels Good, On Bicycles, The Brompton, dan Just Enough. Jika buku-buku tersebut berbicara tentang sejarah, politik, industri, dan etika kecukupan, Live to Ride berbicara tentang jiwa manusia yang mengayuh di tengah dunia yang lelah.
Bogor, 24 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Al-Qur’an al-Karim.
- Arendt, H. (1958). The Human Condition. University of Chicago Press.
- Camus, A. (1955). The Myth of Sisyphus. Vintage.
- Flax, P. (2024). Live to Ride: Finding Joy and Meaning on a Bicycle. New York, NY: Artisan Books.
- Naess, A. (1989). Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge University Press.
- Schumacher, E. F. (1973). Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered. Harper & Row.