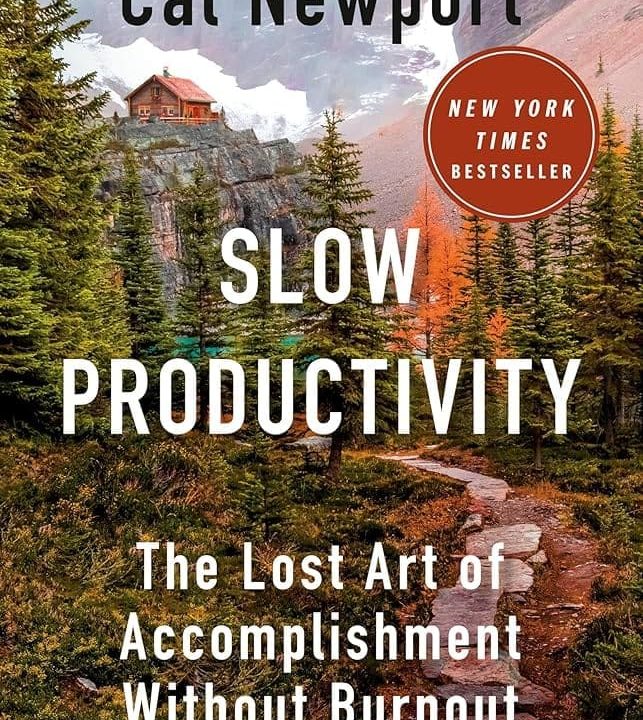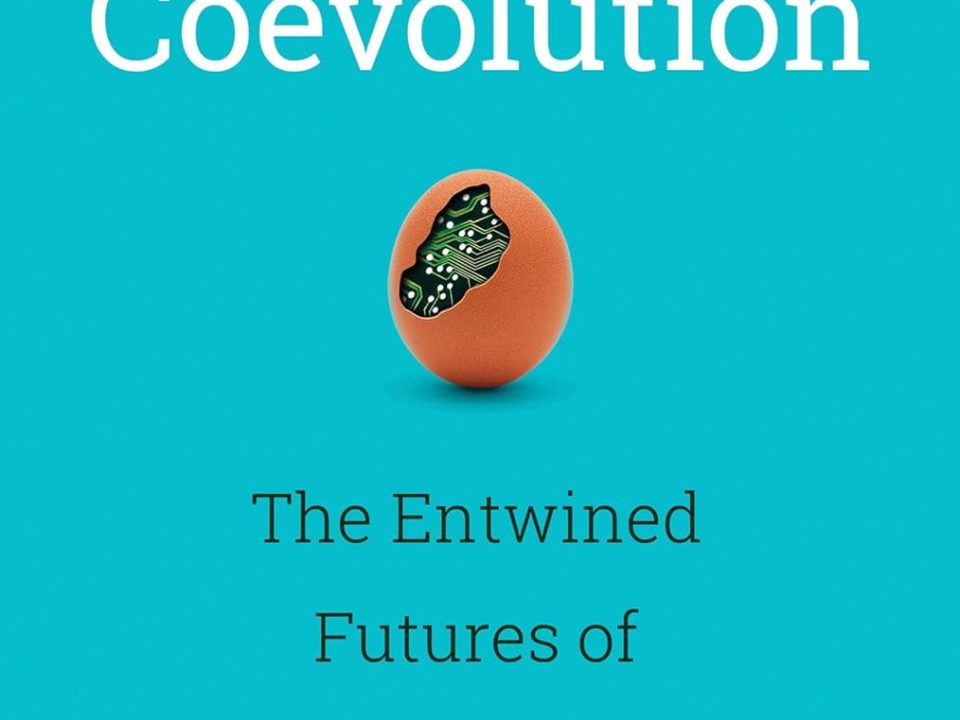Rubarubu #74
How Propaganda Works:
Ketika Bahasa Kekuasaan Menjadi Sejarah
Ketika Kata-Kata Menjadi Senjata
Pada suatu pagi di abad ke-20, seorang warga negara yang taat hukum membaca surat kabar, mendengarkan pidato pemimpin negaranya, dan merasa yakin bahwa semua yang dilakukan negara adalah demi keamanan dan moralitas. Ia tidak merasa dipaksa, tidak pula dibohongi secara kasar. Ia hanya “dibimbing” untuk memahami dunia dengan cara tertentu. Dari pengalaman sehari-hari semacam inilah Jason Stanley memulai kegelisahannya: propaganda modern tidak bekerja terutama lewat kebohongan telanjang, melainkan lewat manipulasi nilai, emosi, dan identitas yang tampak sah.
Membaca How Propaganda Works di zaman kekuasaan narasi akan memberi pemahaman yang lebih baik atas tsunami informasi. Buku ini makin relevan kini. Dalam Preface dan Introduction: The Problem of Propaganda, masalah Propaganda Stanley menegaskan bahwa propaganda sering disalahpahami sebagai sesuatu yang hanya dilakukan oleh rezim otoriter. Ia justru menunjukkan paradoks yang mengganggu: propaganda paling efektif tumbuh subur dalam masyarakat demokratis, karena ia beroperasi di dalam bahasa kebebasan, rasionalitas, dan moralitas publik itu sendiri. Stanley membedakan propaganda dari sekadar persuasi. Propaganda adalah praktik diskursif yang merusak nilai-nilai rasional yang secara eksplisit diklaimnya. Ia menggunakan bahasa kebebasan untuk membenarkan penindasan, bahasa keamanan untuk melegitimasi kekerasan, dan bahasa tradisi untuk melanggengkan ketimpangan. Dengan kata lain, propaganda adalah pengkhianatan internal terhadap ideal demokrasi.
Di sini Stanley banyak dipengaruhi oleh filsafat bahasa dan epistemologi sosial: bagaimana makna kata dibentuk oleh konteks kekuasaan, dan bagaimana publik diarahkan untuk menerima ketimpangan sebagai “akal sehat”.
Secara keseluruhan, How Propaganda Works membangun argumen bertahap namun saling terkait: Stanley pertama-tama menguraikan konsep propaganda yang menipu secara moral (undermining propaganda)—yaitu bentuk propaganda yang tidak selalu menyampaikan informasi palsu, tetapi mengaktifkan prasangka laten (ras, agama, kelas, gender) sehingga publik gagal menilai argumen secara rasional. Ia mencontohkan bagaimana retorika “law and order” di Amerika Serikat tampak netral, tetapi secara historis dan kultural memanggil ketakutan rasial terhadap warga kulit hitam.
Propaganda, menurut Stanley, bekerja dengan mereduksi kelompok tertentu menjadi ancaman moral atau eksistensial, sehingga kebijakan diskriminatif terasa perlu dan sah. Dalam kerangka ini, propaganda bukan sekadar komunikasi politik, melainkan arsitektur emosi publik. Bagian selanjutnya membahas bagaimana propaganda beroperasi melalui ideologi—bukan sebagai sistem keyakinan eksplisit, melainkan sebagai latar belakang asumsi yang tak dipertanyakan. Stanley yang merupakan filsuf, penulis, dan profesor Amerika terkemuka yang dikenal luas atas karyanya dalam bidang filsafat bahasa, epistemologi, dan analisis kritis terhadap politik kontemporer, terutama propaganda dan fasisme ini, meminjam gagasan dari Marx, Althusser, dan teori ideologi kontemporer untuk menunjukkan bahwa propaganda berhasil ketika ia tak lagi dikenali sebagai propaganda.
Ia juga menyoroti peran media, pendidikan, dan institusi pengetahuan dalam mereproduksi propaganda secara tidak sadar. Jurnalisme yang mengklaim netralitas sering kali justru menjadi kendaraan propaganda ketika gagal mempertanyakan kerangka naratif dominan.
Propaganda, Identitas, dan Ketimpangan
Salah satu kekuatan utama buku ini adalah analisis Stanley tentang hubungan propaganda dan identitas sosial. Propaganda memanfaatkan kecemasan kolektif—tentang perubahan demografi, krisis ekonomi, atau ancaman eksternal—lalu mengarahkannya kepada kelompok tertentu sebagai kambing hitam. Dalam konteks ini, Stanley beresonansi kuat dengan Hannah Arendt, yang dalam The Origins of Totalitarianismmenunjukkan bagaimana kebohongan politik modern tidak bertujuan menyembunyikan kebenaran, melainkan menghancurkan kapasitas publik untuk membedakan benar dan salah. Propaganda bukan sekadar soal informasi, tetapi soal pembentukan dunia bersama.
Stanley juga sejalan dengan Noam Chomsky, khususnya dalam Manufacturing Consent, tentang bagaimana media arus utama di negara demokratis berfungsi sebagai sistem propaganda yang halus namun efektif, melalui seleksi isu, bahasa, dan kerangka interpretasi.
Dalam lanskap geopolitik kontemporer, analisis Stanley terasa semakin relevan. Retorika “perang melawan teror”, “intervensi kemanusiaan”, atau “stabilitas global” sering kali berfungsi sebagai bahasa moral yang menutupi kepentingan ekonomi dan strategis. Ini mengingatkan pada kritik Edward Said tentang bagaimana bahasa peradaban dan keamanan digunakan untuk membenarkan dominasi global.
Propaganda juga menjadi instrumen neokolonialisme: negara-negara Global South sering direpresentasikan sebagai “gagal”, “korup”, atau “tidak siap berdemokrasi”, sehingga intervensi ekonomi dan politik dari luar tampak wajar. Di sini, Stanley bertemu dengan pemikir Global South seperti Frantz Fanon, yang melihat bahasa kolonial sebagai alat psikologis penaklukan.
Konteks Indonesia: Propaganda, Demokrasi, dan Media Sosial
Dalam konteks Indonesia, How Propaganda Works membantu membaca fenomena kontemporer: politik identitas, polarisasi agama dan etnis, serta penggunaan istilah moral (“radikal”, “anti-Pancasila”, “asing”) untuk membungkam kritik. Propaganda tidak selalu datang dari negara; ia juga beredar melalui media sosial, influencer politik, dan buzzer digital.
Bahasa pembangunan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan untuk menyingkirkan isu keadilan ekologis, hak masyarakat adat, atau ketimpangan struktural. Di sinilah propaganda bekerja secara halus: ketika ketidakadilan dipresentasikan sebagai keniscayaan teknokratis.
Pemikiran Stanley dapat diperkaya dengan tradisi Islam kritis, misalnya Ibn Khaldun, yang telah lama mengingatkan bahwa kekuasaan bertahan bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan narasi legitimasi yang diterima sebagai kebenaran sosial.
Prospek Masa Depan: Melawan Propaganda.
Stanley yang menyelesaikan gelar sarjana dalam bidang filsafat dan matematika di Universitas Negeri New York di Binghamton dan meraih gelar Ph.D. dalam filsafat dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1995, dengan disertasi yang membahas teori referensi dan semantik ini memang tidak menawarkan solusi sederhana. Namun, ia menekankan pentingnya pendidikan kritis, literasi media, dan kesadaran akan prasangka struktural. Di sini ia sejalan dengan Paulo Freire, yang melihat pembebasan sebagai proses dialogis: belajar mem-baca dunia sebelum membaca kata. Di masa depan, ketika kecerdasan buatan, algoritma, dan ekonomi atensi semakin menguasai ruang publik, propaganda akan semakin personal, cepat, dan sulit dideteksi. Buku ini menjadi peringatan dini: demokrasi tidak runtuh hanya oleh kekerasan, tetapi oleh bahasa yang kehilangan kejujurannya.
Jason Stanley memulai pembacaan tentang propaganda bukan dari abad ke-20, melainkan jauh lebih dalam—ke jantung sejarah pemikiran politik itu sendiri. Dalam Chapter 1: Propaganda in the History of Political Thought, ia mengajak pembaca menyadari bahwa propaganda bukanlah penyimpangan modern dari politik, melainkan bagian inheren dari cara kekuasaan selalu membentuk realitas sosial melalui bahasa.
Dalam polis Yunani kuno, Plato sudah mencurigai daya bahasa. Dalam Republic, ia menaruh perhatian besar pada mitos pendiri (noble lies)—kebohongan yang disengaja demi stabilitas negara. Stanley membaca Plato bukan sebagai pembela propaganda, melainkan sebagai pemikir yang sadar bahwa narasi politik selalu beroperasi di wilayah emosi dan imajinasi, bukan sekadar rasio. Negara, bagi Plato, membutuhkan cerita agar warganya menerima struktur sosial yang tidak sepenuhnya setara. Di sini, propaganda belum disebut demikian, tetapi fungsinya sudah hadir: membuat ketimpangan terasa wajar.
Aristoteles, melalui Rhetoric, menggeser fokus dari kebenaran menuju persuasi yang efektif. Stanley menunjukkan bahwa sejak saat itu, politik tak lagi dapat dipisahkan dari retorika. Logos, ethos, dan pathos menjadi perangkat sah untuk membentuk opini publik. Namun, celah moral terbuka: ketika pathos—emosi—mengalahkan penilaian rasional, retorika berubah menjadi alat manipulasi.
Tradisi ini berlanjut dalam pemikiran modern. Hobbes memahami bahwa ketertiban politik memerlukan pengendalian opini, sementara Rousseau menyadari bahwa kehendak umum tidak muncul secara spontan, tetapi harus dibentuk. Stanley menegaskan bahwa bahkan dalam pemikiran Pencerahan—yang mengagungkan rasionalitas—selalu ada pengakuan implisit bahwa massa perlu diarahkan, bukan sekadar diyakinkan melalui argumen murni.
Masuk ke abad ke-20, refleksi menjadi lebih gelap. Totalitarianisme—yang dianalisis oleh Hannah Arendt—menunjukkan propaganda dalam bentuk ekstrem: bukan untuk meyakinkan, tetapi untuk menghancurkan kapasitas berpikir. Stanley menempatkan pemikir seperti Arendt dan Orwell sebagai saksi bahwa propaganda modern bukan lagi soal kebohongan sesaat, melainkan pembangunan dunia alternatif yang konsisten dan tertutup. Namun, Stanley menolak anggapan bahwa propaganda adalah “penyakit rezim otoriter”. Di sinilah ia bergerak ke Chapter 2: Propaganda Defined.
Apa Itu Propaganda? Ketika bahasa mengkhianati nilainya sendiri maka kita akan menyaksikan banyak sekali kebohongan yang disulap sebagai kebenaran. Dalam bab kedua, Stanley melaku-kan pekerjaan konseptual yang sangat presisi. Ia tidak puas dengan definisi propaganda sebagai “informasi palsu” atau “persuasi politik”. Baginya, propaganda adalah praktik komunikasi yang merusak nilai-nilai normatif yang secara eksplisit diklaimnya sendiri. Pro-paganda bisa saja berisi fakta. Ia bisa terdengar rasional. Ia bahkan bisa mengutip nilai luhur seperti kebebasan, keamanan, atau keadilan. Tetapi propaganda bekerja ketika bahasa itu mengaktifkan prasangka laten—rasial, gender, kelas, agama—yang membuat audiens gagal menilai argumen secara adil.
Stanley membedakan antara supportive propaganda dan undermining propaganda. Yang pertama mendukung nilai yang memang ingin ditegakkan (misalnya propaganda kesehatan publik), sementara yang kedua—yang menjadi fokus utama buku ini—secara diam-diam menggerogoti fondasi rasional demokrasi.
Ia memberi contoh bagaimana slogan seperti “law and order” atau “national security” di Amerika Serikat tampak netral, tetapi secara historis dan kultural memanggil ketakutan rasial tertentu. Di sini, propaganda tidak berbohong; ia menggeser konteks interpretasi. Fakta yang sama, dalam bingkai berbeda, menghasilkan kesimpulan moral yang berbeda pula. Stanley menekankan bahwa propaganda bekerja melalui ideologi—bukan sebagai sistem keyakinan eksplisit, melainkan sebagai latar belakang asumsi yang tidak disadari. Ideologi inilah yang menentukan siapa yang dianggap rasional, siapa yang dianggap ancaman, dan siapa yang layak didengar. Dalam kerangka ini, propaganda adalah arsitektur makna, bukan sekadar pesan.
Definisi ini mempersiapkan pembaca untuk argumen paling provokatif dalam buku: bahwa demokrasi liberal modern adalah lahan paling subur bagi propaganda semacam ini.
Bagi Stanley inilah paradoks demokrasi. Propaganda justru marak di tengah kebebasan atau demokrasi. Dalam Chapter 3: Propaganda in Liberal Democracy, Stanley membongkar mitos kenyamanan bahwa kebebasan pers dan pluralisme otomatis melindungi masyarakat dari propaganda. Justru sebaliknya: propaganda paling efektif ketika ia bersembunyi di balik kebebasan. Demokrasi liberal mengandaikan warga yang rasional dan setara. Namun, Stanley menunjukkan bahwa ketimpangan sosial—ras, ekonomi, pendidikan—membuat asumsi ini rapuh. Propaganda mengeksploitasi ketimpangan tersebut dengan menyelaraskan pesan politik pada emosi dan identitas kelompok, bukan pada penalaran universal.
Media memainkan peran sentral. Bukan karena media selalu berbohong, tetapi karena kerangka pemberitaan sering kali mengulang asumsi dominan. Ketika media mengklaim netralitas tanpa refleksi kritis, ia dapat menjadi kendaraan propaganda—seperti yang lama dikritik Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent. Dalam demokrasi liberal, propaganda tidak memerintah melalui larangan, melainkan melalui normalisasi. Ia membuat ketidakadilan terasa masuk akal, kekerasan terasa perlu, dan eksklusi terasa alami. Yang paling berbahaya, propaganda semacam ini membuat warga merasa mereka berpikir bebas, padahal horizon pikirannya sudah diarahkan.
Stanley menekankan bahwa propaganda demokratis jarang bersifat total. Ia parsial, fragmentaris, dan kontekstual. Namun justru karena itu, ia sulit dilawan. Tidak ada satu kebohongan besar untuk dibongkar, melainkan ribuan pembingkaian kecil yang membentuk realitas bersama.
Jika ketiga bab ini dibaca sebagai satu kesatuan, maka argumen Stanley menjadi jelas: propaganda bukan penyimpangan dari politik rasional, tetapi bayangannya yang selalu mengintai. Ia merajut benang merah: bahasa, kekuasaan, dan tanggung jawab moral.
Sejak Plato hingga demokrasi liberal, bahasa politik selalu berada di antara pencerahan dan manipulasi. Yang membedakan masyarakat adil dan tidak adil bukan absennya propaganda, melainkan kemampuan kolektif untuk mengenalinya, mengkritiknya, dan membatasi daya rusaknya. Dalam dunia yang dibanjiri informasi, propaganda tidak mengandalkan kebohongan, tetapi kelelahan moral dan kebingungan epistemik.
Di sinilah buku Stanley menjadi peringatan serius bagi masyarakat kontemporer—termasuk Indonesia—bahwa demokrasi tidak hanya memerlukan pemilu dan kebebasan berbicara, tetapi juga etika berbahasa, keadilan sosial, dan pendidikan kritis. Tanpa itu, kebebasan bisa berubah menjadi tirai yang menutupi dominasi.
Ketika Bahasa Tidak Lagi Netral: Kontrol, Ideologi, dan Penjinakan Pikiran
Pada titik ini dalam How Propaganda Works, Jason Stanley membawa pembaca memasuki wilayah yang paling sunyi sekaligus paling berbahaya dalam politik modern: bahasa itu sendiri. Jika pada bab-bab sebelumnya propaganda dipahami sebagai praktik komunikasi yang merusak nilai demokrasi, maka dalam Chapter 4: Language as a Mechanism of Control Stanley memper-lihatkan bagaimana bahasa bukan sekadar kendaraan propaganda, melainkan infrastrukturnya. Bahasa adalah medan tempat kekuasaan bekerja paling halus, paling efektif, dan paling sulit dilacak.
Stanley menolak anggapan bahwa bahasa politik hanyalah alat netral yang bisa dipakai baik atau buruk tergantung niat penggunanya. Ia menunjukkan bahwa bahasa selalu hadir dengan jejak sosial, sejarah, dan hierarki. Kata-kata membawa muatan moral dan politis yang tidak pernah sepenuhnya transparan bagi para penuturnya. Dalam kerangka ini, propaganda tidak selalu berbentuk slogan bombastis atau kebohongan terang-terangan, melain-kan pemilihan kata yang tampak wajar namun mengarahkan cara berpikir.
Dalam bab ini, Stanley banyak mengulas apa yang ia sebut sebagai code words atau dog whistles— ungkapan yang secara literal terdengar netral, tetapi secara sosial memanggil asosiasi tertentu pada kelompok tertentu. Istilah seperti “law and order”, “welfare dependency”, atau “illegal alien” di konteks Amerika Serikat tidak sekadar deskriptif; ia mengaktifkan sejarah panjang rasisme, ketakutan, dan stigma. Bahasa semacam ini bekerja sebagai mekanisme kontrol justru karena ia tidak mengumumkan dirinya sebagai alat kontrol.
Yang penting, Stanley menegaskan bahwa efek bahasa ini tidak bergantung pada kesadaran pendengar. Bahkan warga yang merasa diri rasional dan antirasis dapat terdorong pada kesimpulan tertentu karena kerangka bahasa yang mereka gunakan sudah dimuat dengan asumsi ideologis. Bahasa, dengan demikian, tidak hanya menyampaikan pikiran; ia membentuk horizon kemungkinan berpikir.
Di sinilah Stanley memperluas analisisnya dengan memanfaatkan filsafat bahasa dan epistemologi sosial. Ia menunjukkan bahwa propaganda bekerja dengan menciptakan ketim-pangan epistemik—sebagian kelompok diposisikan sebagai kredibel, rasional, dan layak dipercaya, sementara kelompok lain dianggap emosional, irasional, atau berbahaya. Bahasa adalah alat utama dalam proses ini. Ketika media atau politisi menggambarkan satu kelompok sebagai “rioters” dan kelompok lain sebagai “concerned citizens”, perbedaan moral sudah ditanamkan sebelum argumen apa pun disampaikan.
Namun, bahasa saja tidak cukup untuk menjelaskan daya tahan propaganda. Di sinilah Chapter 5: Ideology masuk sebagai fondasi teoritis yang lebih dalam. Stanley mendefinisikan ideologi bukan sebagai seperangkat doktrin eksplisit yang dianut secara sadar, melainkan sebagai struktur keyakinan implisit yang mengatur bagaimana kita memahami dunia sosial. Ideologi bekerja paling efektif justru ketika ia tidak terlihat sebagai ideologi. Ia menjadi “akal sehat”, “kenyataan apa adanya”, atau “cara dunia memang bekerja”. Dalam bab ini, Stanley secara eksplisit berdialog dengan tradisi Marxis, teori kritis, dan pemikir seperti Louis Althusser, tetapi ia mengembangkan pendekatan khasnya sendiri. Ideologi, menurut Stanley, adalah filter epistemik: ia menentukan bukti mana yang dianggap relevan, suara mana yang dianggap sah, dan penderitaan siapa yang dianggap nyata.
Propaganda, dalam pengertian ini, tidak menciptakan ideologi dari nol. Ia mengaktifkan dan memelihara ideologi yang sudah ada, sering kali ideologi yang menopang hierarki sosial—rasisme, seksisme, nasionalisme eksklusif, atau kapitalisme yang tidak dipertanyakan. Bahasa propaganda bekerja karena ia beresonansi dengan struktur ideologis yang sudah tertanam dalam pengalaman sehari-hari masyarakat.
Stanley menekankan bahwa ideologi bukan sekadar kesalahan berpikir individual. Ia ber-sifat kolektif dan institusional. Sekolah, media, sistem hukum, dan praktik ekonomi semuanya berkontribusi membentuk apa yang dianggap “normal”. Propaganda kemudian masuk bukan sebagai kekuatan eksternal, melainkan sebagai peneguhan terhadap apa yang sudah terasa masuk akal.
Di titik ini, kritik Stanley menjadi sangat tajam terhadap demokrasi liberal. Demokrasi sering membanggakan diri sebagai sistem yang menghormati rasionalitas dan perdebatan terbuka. Namun, Stanley menunjukkan bahwa jika ideologi menentukan siapa yang dianggap rasional sejak awal, maka perdebatan itu sendiri sudah tidak setara. Propaganda dalam demokrasi liberal bekerja bukan dengan membungkam oposisi, tetapi dengan mendefinisikan oposisi sebagai tidak masuk akal, tidak patriotik, atau tidak bermoral.
Bahasa dan ideologi, ketika bersatu, menghasilkan bentuk kontrol yang nyaris sempurna: kontrol tanpa paksaan fisik, tanpa sensor resmi, tanpa polisi pikiran. Warga berbicara bebas, tetapi dalam batas-batas makna yang sudah ditentukan. Mereka memilih, tetapi dari pilihan-pilihan yang telah dibingkai. Mereka merasa otonom, tetapi otonomi itu berjalan di atas rel ideologis yang tidak mereka bangun sendiri. Stanley pernah mengajar di beberapa universitas ternama, termasuk Universitas Michigan, Universitas Cornell, dan Universitas Rutgers. Sejak 2013, ia menjabat sebagai Profesor Filsafat Jacob Urowsky di Universitas Yale. Di Yale, ia juga terafiliasi dengan Departemen Linguistik dan menjadi bagian dari Yale’s Institute for Social and Policy Studies. Karya akademis awalnya berfokus pada bidang filsafat bahasa, semantik formal, dan epistemologi. Beberapa tulisannya membahas konsep seperti pengetahuan implisit, konteks dalam bahasa, dan struktur semantik.
Stanley tidak menawarkan solusi sederhana. Ia justru menutup analisis ini dengan implikasi moral yang berat: melawan propaganda berarti melawan kenyamanan ideologis kita sendiri. Ia menuntut kewaspadaan terhadap bahasa yang kita gunakan, kesediaan untuk memper-tanyakan “akal sehat”, dan keberanian untuk mendengar suara yang oleh ideologi dominan dianggap tidak kredibel.
Dalam konteks ini, How Propaganda Works bukan hanya buku tentang politik, melainkan tentang etika berbahasa dan tanggung jawab epistemik warga. Bahasa bisa menjadi alat pembebasan, tetapi juga bisa menjadi kandang emas. Ideologi bisa memberi makna, tetapi juga bisa membutakan. Dan propaganda—sebagaimana ditunjukkan Stanley—berhasil bukan karena kebodohan publik, melainkan karena kerapuhan manusia dalam menghadapi dunia sosial yang kompleks dan timpang.
Ketika Ideologi Menjadi Tak Terlihat: Politik, Elit, dan Normalisasi Ketidakadilan
Pada bagian akhir How Propaganda Works, Jason Stanley membawa pembaca pada titik yang paling mengganggu sekaligus paling jujur dari analisisnya: propaganda bukanlah penyimpangan dari politik modern, melainkan mekanisme normal yang menopang ideologi politik dominan. Jika bab-bab sebelumnya membedah bahasa dan ideologi sebagai struktur umum, maka Chapter 6: Political Ideologies memperlihatkan bagaimana ideologi politik konkret—liberalisme, konservatisme, nasionalisme—menjadi lahan subur bagi propaganda untuk bekerja secara sistematis.
Stanley memulai dengan menegaskan bahwa ideologi politik tidak sekadar kumpulan pandang-an normatif yang diperdebatkan secara rasional di ruang publik. Ia adalah kerangka interpretatif yang membentuk persepsi warga tentang keadilan, tanggung jawab, dan kelayakan moral. Dalam konteks ini, propaganda bekerja bukan dengan menciptakan ideologi baru, melainkan dengan mengaktifkan versi ideologi yang menguntungkan struktur kekuasaan yang ada.
Dalam Political Ideologies, Stanley menunjukkan bagaimana propaganda sangat efektif dalam ideologi yang mengklaim netralitas moral—terutama liberalisme politik. Ketika liberalisme mendefinisikan dirinya sebagai sistem yang menjunjung kebebasan individu dan rasionalitas, propaganda masuk dengan cara membingkai ketimpangan struktural sebagai kegagalan personal, kemiskinan sebagai akibat pilihan individu, dan kekerasan negara sebagai kebutuhan keamanan. Dengan kata lain, ideologi liberal menyediakan bahasa moral yang membuat ketidakadilan tampak sah.
Stanley tidak menolak ideologi tertentu secara simplistik. Ia justru menunjukkan paradoksnya: ideologi politik paling rentan terhadap propaganda justru ketika ia menganggap dirinya paling rasional dan paling bebas dari bias. Di titik ini, propaganda tidak lagi tampak sebagai mani-pulasi, melainkan sebagai “penjelasan masuk akal tentang realitas”.
Dari sini, Stanley bergerak ke analisis yang lebih konkret dan tajam dalam Chapter 7: The Ideology of Elites: A Case Study. Jika bab sebelumnya bersifat teoretis, bagian ini adalah pembuktian empiris bahwa propaganda bukan sekadar fenomena massa, melainkan diproduksi dan disirkulasikan oleh elite politik, ekonomi, dan intelektual. Dalam studi kasus ini, Stanley menelusuri bagaimana elite membangun ideologi yang mempresentasikan kepentingan mereka sebagai kepentingan universal. Ia menunjukkan bahwa elite tidak selalu berbohong secara sadar. Sebaliknya, mereka sering kali sungguh-sungguh percaya pada narasi yang mereka produksi, karena ideologi mereka diperkuat oleh posisi sosial, pendidikan, dan lingkungan epistemik yang homogen.
Salah satu poin paling penting dari bab ini adalah analisis Stanley tentang ketimpangan epistemik. Elite memiliki akses pada platform, legitimasi, dan otoritas simbolik yang membuat pandangan mereka dianggap “objektif” atau “ahli”, sementara pengalaman kelompok terpinggirkan dianggap anekdotal, emosional, atau bias. Dalam kondisi ini, propaganda bekerja bukan dengan membungkam suara lain, tetapi dengan mendefinisikan suara mana yang layak didengar sejak awal.
Stanley memperlihatkan bahwa ideologi elite sering kali mengemas kebijakan yang merugikan banyak orang—pemotongan layanan publik, deregulasi, perang, atau kriminalisasi kemiskinan—sebagai keputusan teknokratis yang “tidak punya alternatif”. Bahasa efisiensi, rasionalitas ekonomi, dan keamanan nasional menjadi alat ideologis yang menyingkirkan pertanyaan moral.
Yang mengerikan, menurut Stanley, adalah bahwa propaganda elite ini tidak memerlukan konspirasi besar. Ia bekerja melalui rutinitas profesional: laporan kebijakan, opini media, kurikulum pendidikan, dan diskursus akademik. Dengan demikian, propaganda menjadi bagian dari apa yang disebut Hannah Arendt sebagai banality of evil: kejahatan yang tidak lahir dari niat jahat, tetapi dari kepatuhan pada kerangka berpikir yang tidak pernah dipertanyakan.
Semua ini mengantar pada Conclusion, di mana Stanley tidak menawarkan penutup yang menenangkan, melainkan refleksi etis yang menuntut tanggung jawab pembaca. Ia menegaskan kembali tesis utamanya: propaganda merusak demokrasi bukan dengan menghancurkan institusi formal, tetapi dengan merusak kondisi epistemik yang memungkinkan warga menilai keadilan secara setara.
Dalam kesimpulannya, Stanley menolak ilusi bahwa pendidikan formal atau kecerdasan individu cukup untuk melawan propaganda. Yang dibutuhkan adalah keadilan epistemik—yang berarti pengakuan serius terhadap pengalaman kelompok yang selama ini dimarjinalkan, serta kesediaan untuk menantang bahasa dan ideologi yang terasa “alami”.
Stanley menekankan bahwa melawan propaganda adalah tugas moral kolektif. Ia menuntut kewaspadaan terhadap cara kita berbicara, mendengarkan, dan mempercayai otoritas. Demokrasi, dalam pandangan ini, bukan sekadar prosedur pemilu, tetapi praktik etis yang rapuh, yang hanya bisa bertahan jika warganya bersedia menghadapi ketidaknyamanan intelektual dan moral.
Buku ini ditutup dengan kesadaran pahit namun penting: propaganda tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Ia adalah bayangan dari kehidupan politik itu sendiri. Tetapi yang bisa—dan harus—diperjuangkan adalah kemampuan untuk mengenalinya, menamainya, dan menolak normalisasinya.
Dengan demikian, How Propaganda Works bukan hanya analisis tentang manipulasi politik, melainkan peringatan filosofis tentang betapa mudahnya kebebasan berpikir tergelincir menjadi kepatuhan ideologis, bahkan—atau terutama—di masyarakat yang menyebut dirinya bebas.
Propaganda sebagai Normalitas: Sintesis How Propaganda Works
Jason Stanley menulis How Propaganda Works bukan untuk menjelaskan propaganda sebagai teknik manipulasi semata, melainkan untuk membongkar kondisi moral dan epistemik yang membuat propaganda bekerja secara sah dan efektif dalam masyarakat modern. Tesis utama-nya sederhana namun radikal: propaganda paling berbahaya bukan ketika ia berbohong, melainkan ketika ia mengatakan kebenaran yang disusun untuk melayani ketidakadilan.
Buku ini secara keseluruhan bergerak dari sejarah pemikiran politik, definisi propaganda, analisis bahasa dan ideologi, hingga studi kasus elite dan kesimpulan normatif. Namun benang merahnya konsisten: propaganda bekerja dengan merusak keadilan epistemik, yaitu kondisi di mana semua warga dapat berpartisipasi setara dalam memahami dan menilai realitas sosial.
Stanley menunjukkan bahwa propaganda tidak membutuhkan sensor atau diktator. Ia justru tumbuh subur dalam demokrasi liberal, karena demokrasi mengandalkan bahasa—dan bahasa adalah medan kekuasaan. Ketika bahasa politik memisahkan fakta dari pengalaman moral kelompok tertentu, propaganda telah bekerja.
Di sinilah Stanley berdiri dalam satu garis intelektual dengan Arendt, Chomsky, Bourdieu, dan Foucault—namun dengan fokus khasnya sendiri.
Stanley dan Hannah Arendt: Banalitas Kejahatan dan Normalisasi Bahasa
Hannah Arendt, dalam Eichmann in Jerusalem, memperkenalkan konsep banalitas kejahatan: kejahatan besar sering dilakukan bukan oleh monster, melainkan oleh individu biasa yang berhenti berpikir secara moral. Stanley memperluas wawasan ini ke ranah bahasa politik.
Bagi Stanley, propaganda adalah banalitas kejahatan dalam bentuk linguistik. Ia tidak selalu memerintahkan kekerasan, tetapi menormalkan kerangka berpikir yang membuat kekerasan tampak masuk akal, perlu, atau tak terelakkan. Seperti Eichmann yang berbicara dalam klise administratif, propaganda berbicara dalam klise moral: stabilitas, keamanan, pembangunan, pertumbuhan, efisiensi.
Keduanya sepakat bahwa bahaya terbesar bukan kebohongan terang-terangan, melain-kan ketiadaan refleksi. Dalam bahasa Arendt, propaganda menghancurkan thinking without a banister—kemampuan berpikir tanpa pegangan ideologis.
Stanley dan Noam Chomsky: Dari Manipulasi Media ke Ketidakadilan Epistemik
Noam Chomsky, melalui Manufacturing Consent, menekankan propaganda sebagai hasil struktural dari kepemilikan media, kepentingan ekonomi, dan kekuasaan negara. Stanley tidak menolak analisis ini, tetapi melangkah lebih jauh. Jika Chomsky fokus pada bagaimana informasi disaring, Stanley fokus pada bagaimana makna dibentuk. Stanley menunjukkan bahwa propaganda tidak selalu datang dari media besar, tetapi dari bahasa moral sehari-hari yang memisahkan “warga baik” dari “ancaman”, “produktif” dari “beban”, “moderat” dari “radikal”.
Chomsky berbicara tentang manipulasi opini; Stanley berbicara tentang penciptaan ketimpang-an dalam siapa yang dianggap rasional, kredibel, dan layak didengar. Dengan kata lain, Stanley menggeser kritik propaganda dari ekonomi politik informasi ke etika pengakuan sosial.
Stanley dan Pierre Bourdieu: Kekuasaan Simbolik dan Bahasa yang Sah
Pierre Bourdieu memberi kita konsep kekuasaan simbolik: kemampuan untuk menentukan makna tanpa terlihat memaksakan. Di sinilah Stanley dan Bourdieu bertemu sangat erat.
Stanley menunjukkan bahwa propaganda bekerja ketika bahasa elite menjadi bahasa yang sah, sementara bahasa kelompok terpinggirkan dianggap emosional, subjektif, atau tidak ilmiah. Ini persis dengan analisis Bourdieu tentang linguistic capital: siapa yang berbicara dengan aksen yang benar, istilah yang benar, dan dalam forum yang benar.
Dalam propaganda, ketidakadilan tidak perlu dipaksakan; ia diterima sebagai wajar, karena telah dibingkai dalam bahasa netral. Ketika kebijakan keras disebut “penyesuaian struktural”, ketika penggusuran disebut “penataan”, propaganda telah menang secara simbolik.
Stanley dan Michel Foucault: Diskursus, Kekuasaan, dan Normalisasi
Michel Foucault melihat kekuasaan bukan sebagai milik, tetapi sebagai relasi yang tersebar dalam diskursus. Stanley sepakat, tetapi memberi dimensi normatif yang lebih tajam. Bagi Stanley, propaganda adalah diskursus yang merusak kondisi demokrasi, karena ia menciptakan hierarki epistemik: ada yang dianggap tahu, ada yang dianggap tidak. Jika Foucault menganalisis bagaimana kebenaran diproduksi, Stanley bertanya: kebenaran untuk siapa, dan dengan biaya moral apa?
Dengan demikian, Stanley mengembalikan pertanyaan etika ke dalam analisis diskursus—sesuatu yang sering absen dalam pembacaan Foucauldian yang terlalu deskriptif.
Propaganda dalam Politik Indonesia: Bahasa Pembangunan dan Stabilitas
Dalam konteks Indonesia, analisis Stanley terasa sangat dekat. Bahasa “pembangunan” sering digunakan untuk membenarkan penggusuran, eksploitasi sumber daya, atau perampasan tanah adat. Fakta ekonomi disajikan, tetapi pengalaman moral warga terdampak dihapus. Ini adalah propaganda dalam arti Stanley: kebenaran faktual yang dipisahkan dari keadilan. Bahasa “stabilitas” dan “keamanan nasional” sering dipakai untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan sipil, atau menjustifikasi kekerasan negara. Seperti yang Stanley jelaskan, propa-ganda bekerja dengan menciptakan ancaman imajiner yang hanya bisa diatasi dengan kepatuhan.
Istilah “radikalisme” berfungsi sebagai label ideologis yang mengaburkan perbedaan antara kritik struktural dan kekerasan nyata. Ia menciptakan garis moral palsu antara “kita” dan “mereka”, yang membuat dialog epistemik mustahil. Bahkan nasionalisme, ketika direduksi menjadi simbol dan slogan, dapat menjadi propaganda yang menyingkirkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan sejarah kekerasan negara.
Catatan Akhir: Propaganda, Ingatan Sejarah, dan Perlawanan Warga
Stanley dikenal karena kemampuannya menghubungkan teori filosofis yang kompleks dengan isu-isu politik praktis. Karyanya sering bersifat interdisipliner, menggabungkan wawasan dari filsafat, ilmu politik, sosiologi, dan linguistik. Dia secara aktif terlibat dalam debat publik, menulis opini untuk media seperti The New York Times, The Guardian, dan The Washington Post, serta sering muncul sebagai pembicara dalam wawancara dan diskusi tentang demokrasi, ketidaksetaraan, dan ancaman terhadap institusi liberal.
Ia yang adalah putra dari seorang korban selamat Holocaust, sebuah latar belakang yang me-mengaruhi minatnya pada bahaya fasisme dan propaganda, terus menjadi suara yang ber-pengaruh dalam diskusi tentang kebenaran, demokrasi, dan etika publik. Melalui tulisannya, ia mengajak pembaca untuk kritis terhadap bahasa dan narasi politik, serta waspada terhadap cara-cara di mana ideologi dapat merusak fondasi masyarakat terbuka.
Propaganda pada akhirnya adalah perang melawan ingatan. Ia bekerja dengan memutus hubungan antara masa lalu dan masa kini, antara pengalaman dan bahasa. Ketika sejarah disederhanakan, ketika penderitaan dinormalisasi, propaganda telah menghapus kemungkinan tanggung jawab moral. Melawan propaganda bukan sekadar soal “melawan hoaks”. Ia adalah praktik etis mengingat: mengingat suara yang disenyapkan, pengalaman yang diremeh-kan, dan luka yang disembunyikan oleh bahasa resmi.
Perlawanan warga, dalam kerangka Stanley, bukan terutama revolusi besar, tetapi tindakan kecil mempertahankan keadilan epistemik: mendengarkan yang tidak didengar, menolak bahasa yang merendahkan, dan mempertanyakan kata-kata yang terlalu rapi. Dalam dunia yang dipenuhi statistik, slogan, dan algoritma, perlawanan mungkin justru dimulai dari sesuatu yang sangat manusiawi: keberanian untuk berkata bahwa ada sesuatu yang tidak adil, meskipun bahasa resmi mengatakan sebaliknya. Di situlah demokrasi hidup—bukan sebagai sistem, tetapi sebagai praktik ingatan dan keberanian moral.
How Propaganda Works adalah buku filsafat politik yang membumi dan mendesak. Ia mengajarkan bahwa melawan propaganda bukan sekadar soal membongkar kebohongan, tetapi memulihkan kondisi moral dan epistemik agar warga dapat berpikir bersama secara adil.
Seperti ditulis oleh George Orwell—seorang penulis yang semangatnya terasa dekat dengan Stanley—“If thought corrupts language, language can also corrupt thought.” Di dunia yang dibanjiri kata-kata, tugas kita bukan menambah suara, tetapi menjernihkan makna.
Cirebon, 8 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi (APA)
Stanley, J. (2015). How propaganda works. Princeton University Press.
Arendt, H. (1951). The origins of totalitarianism. Harcourt Brace.
Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). Manufacturing consent. Pantheon.
Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.
Fanon, F. (1963). The wretched of the earth. Grove Press.
Ibn Khaldun. (1967). The Muqaddimah (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.