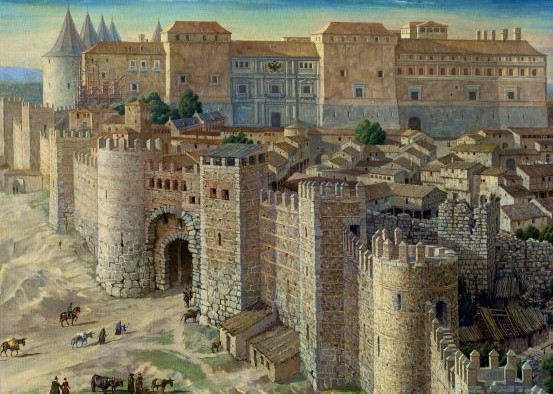halaman drm #23
Pesan Ozon IV: Teknologi
Dwi R. Muhtaman
“We shape our tools and thereafter our tools shape us.”
— Marshall McLuhan (Media Theorist) —
“It has become appallingly obvious that
our technology has exceeded our humanity.”
–Albert Einstein (Physicist)–
“Technology is nothing.
What’s important is that you have faith in people,
that they’re good and smart, and if you give them tools,
they’ll do wonderful things with them.”
–Steve Jobs (Co-founder of Apple Inc.)–
Aku kadang berpikir keras. Menelusuri jawaban sebuah tanya ini: apakah sebetulnya yang dihadapi umat manusia pada abad modern ini. Zaman di mana lompatan-lompatan teknologi hampir terjadi di mana pun di celah-celah rekahan bumi ini. Terjadi pada satu era yang konon tak pernah terbayangkan pada jauh kurun waktu sebelumnya. Zaman ini tak pernah ada dalam catatan sejarah peradaban manusia lampau. Mungkin hanya ada dalam catatan atau coretan-coretan manusia-manusia kreatif yang sempat mengantisipasi kemajuan yang bakal di capai oleh anak cucunya. Ramalan-ramalan para futuristik kuno semacam Nostradamus (1503–1566), seorang astrolog dan penyair asal Prancis yang terkenal karena bukunya Les Prophéties, kumpulan quatrain (puisi empat baris) yang konon berisi ramalan tentang masa depan. Ia memprediksi perang besar, seperti Perang Dunia II dan ramalan tentang teknologi modern seperti pesawat terbang dan listrik. Beberapa interpretasi menyatakan Nostradamus meramalkan perubahan besar di abad ke-21, termasuk ancaman global seperti perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Dari Amerika Tengah ada Ramalan Mayan (Suku Maya). Peradaban Maya dikenal karena kalendernya yang canggih dan prediksi astronomis. Kalender Suku Maya menandai akhir siklus panjang pada 21 Desember 2012, yang diinterpretasikan oleh sebagian orang sebagai “akhir dunia” atau transformasi global. Tidak ada bencana besar yang terjadi pada 2012, tetapi periode ini sering dipandang sebagai titik balik dalam kesadaran manusia terhadap isu global, seperti ekologi dan keberlanjutan.
Di Indoneisa ada Ramalan Jayabaya (Raja Kediri, abad ke-12). Raja Kerajaan Kediri di Jawa Timur yang dikenal melalui Ramalan Jayabaya menyatakan akan datang masa ketika “kereta berjalan tanpa kuda” (diinterpretasikan sebagai mobil). Kehancuran nusantara oleh kekuatan asing yang sering diasosiasikan dengan penjajahan Belanda. Dan datangnya era keemasan setelah masa sulit, di mana “ratu adil” akan memimpin dengan bijaksana. Banyak yang menghubungkan prediksi ini dengan periode reformasi dan potensi munculnya pemimpin baru yang membawa keadilan sosial, meski pada kenyataannya tidak sedikit kesusahan pasca reformasi hingga kini.
Yang tak kalah menarik adalah Ramalan Veda (India Kuno). Tulisan suci Hindu seperti Mahabharata dan Bhagavata Purana memuat prediksi tentang masa depan, terutama di era Kali Yuga (zaman kegelapan). Ramalan itu menyebutkan dunia akan dikuasai oleh keserakahan, kemunafikan, dan degradasi moral. Kemajuan teknologi besar, tetapi membawa kehancuran ekologis. Beberapa ramalan ini sesuai dengan tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis moral.
Ramalan Ronggowarsito (1802–1873) tak kalah menarik untuk direnungkan. Ia adalah seorang pujangga Keraton Surakarta yang terkenal dengan ramalannya tentang Zaman Edan. Era di mana banyak orang kehilangan akal sehat karena keserakahan dan kemunafikan. Akan muncul periode pembaruan setelah kekacauan. Banyak yang menganggap “Zaman Edan” menggambarkan era modern dengan tantangan korupsi, konflik sosial, dan transformasi politik.
Ramalan Leonardo da Vinci (1452–1519), seorang polymath Italia yang meninggalkan banyak sketsa dan catatan yang sering dianggap visioner. Sketsanya antara lain tentang mesin terbang dan robot. Memprediksi tentang revolusi dalam ilmu kedokteran dan teknologi. Banyak idenya, seperti helikopter dan lensa optik, telah menjadi kenyataan dalam bentuk teknologi modern.
Ramalan I Ching (China Kuno). I Ching, atau Kitab Perubahan, adalah teks filsafat dan ramalan dari Tiongkok kuno. Di dalamnya menggambarkan perubahan siklus dalam kehidupan manusia dan peradaban. Mengisyaratkan bahwa harmoni dapat dicapai jika manusia hidup selaras dengan alam. Seruan untuk harmoni ini relevan dengan isu-isu seperti keberlanjutan dan perubahan iklim.
Itulah contoh sebagian para futuris kuno dari berbagai peradaban memiliki pola yang serupa: memprediksi kemajuan teknologi yang luar biasa, krisis moral atau lingkungan, dan kebutuhan akan harmoni manusia dengan alam. Dalam konteks Indonesia, ramalan Jayabaya dan Ronggowarsito sering dipandang sebagai refleksi atas kondisi sosial-politik saat ini. Ramalan ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dan kini bukan lagi impian. Kenyataan yang menakjubkan. Bahkan kadangkala, ia menggetarkan, menggoyang-goyang dan mengombang-ambingkan kebudayaan dan manusia sendiri.
Penggal masa kemajuan yang mempermainkan dan mempertaruhkan “rasa” kemanusiaan manusia. Betapa tidak. Teknologi yang hadir hadir di sekitar kita telah merayap dan menyusup jauh. Amat jauh. Ia pada mulanya kita cari. Kita selidiki dimana-mana. Diapun kita temukan. Kita bangga dengan segala jenis temuan itu. Kita jadi berdiri paling tegak di horizon planet bumi ini. Lebih jauh lagi, kita terlena. Seolah-olah paling berkuasa di hidup ini. Tapi itu tak berlangsung lama. Karena ’loncatan-loncatan alam pikir dan waktu’ telah ”ditangkap manusia-bersama dengan itu loncatannya malah melebihi yang bisa ditangkap, lalu ia pun lepas. Melejit. Jauh meninggalkan kita. Melesat. Dan selalu melesat. Di antara itu, kita tak henti-hentinya melesat. Dan keterpurukan pun tidak bisa kita palingkan. Lalu …
Lalu teknologi itu mulai mengatur kita. Mempengaruhi pilihan kata. Bahkan menentukan sesuatunya untuk kita. Mengajar dan mendikte kita. Membimbing dan mengarahkan kita. Mempengaruhi pikiran … dan bahkan menentukan masa depan kita.
Beragam cara orang menginterpretasikan teknologi. Apapun bisa kita anggap sebuah teknologi. Teknologi, tulis Pfaffenberger, didefinisikan secara antropologis, bukanlah sekadar budaya material, melainkan sebuah fenomena sosial total dalam pengertian yang digunakan oleh Mauss—sebuah fenomena yang menyatukan unsur material, sosial, dan simbolik dalam jaringan asosiasi yang kompleks. Bagi Lemonnier lain lagi. Menurtunya, teknologi mencakup semua aspek dari proses tindakan terhadap materi, baik itu menggaruk hidung, menanam ubi jalar, atau membuat pesawat jumbo… Teknologi, seperti mitos, larangan pernikahan, atau sistem pertukaran, merupakan produksi sosial itu sendiri.
Ingold mempunyai pandangan yang menarik. Baginya pergeseran dari konsep klasik tekhnê ke konsep modern teknologi telah membawa perubahan mendalam dalam cara kita memahami hubungan antara manusia dan aktivitasnya. Gambaran tentang seorang pengrajin yang sepenuhnya tenggelam dalam keterlibatan inderawi dengan material telah digantikan oleh gambaran seorang pekerja yang tugasnya adalah menggerakkan suatu sistem kekuatan produktif eksternal, sesuai dengan prinsip-prinsip mekanis yang sepenuhnya tidak memperhitungkan kemampuan dan kepekaan manusia secara individu.
Kemanusiaan berada di persimpangan jalan. Ledakan teknologi dan kemajuan eksponensialnya sedang mengubah makna menjadi manusia. Seiring teknologi terus berkembang, pengaruhnya yang luar biasa terhadap kehidupan kita semakin mendalam. Gaya hidup algoritmik kita kini sepenuhnya mengambil alih kehidupan. Teknologi saat ini membuat keputusan tentang apa yang kita beli, berita yang kita baca, siapa yang kita pilih, pekerjaan yang kita dapatkan, orang yang kita temui, hingga iklan yang kita lihat.
Di balik manfaat dan kemenangan yang dibawa oleh teknologi baru, ada banyak konsekuensi yang sangat merugikan masyarakat dan planet kita.
Jika kita melihat lebih dekat pada teknologi apa pun, akan tampak bahwa teknologi adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan benar, teknologi dapat, dan telah, membuat hidup kita lebih mudah, efisien, dan lebih baik. Namun, teknologi yang sama, jika berada di tangan yang salah atau digunakan secara tidak benar, dapat membawa kerusakan serius bagi kemanusiaan.
Kemajuan selalu memiliki harga. Kertas, misalnya, secara fundamental mengubah cara informasi disimpan dan didistribusikan, tetapi hingga kini produksinya menyumbang besar pada deforestasi. Teknologi, seperti obat-obatan, tidak bebas dari efek samping. Sebagai contoh:
– Teknologi yang menjanjikan dunia bebas kanker dapat menyebabkan kanker.
– Teknologi yang menjanjikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berbicara dan otonomi juga dapat mengancam demokrasi.
– Dalam dunia konektivitas digital yang tak terbatas, jutaan orang tetap merasa kesepian. Isolasi dan depresi adalah krisis kesehatan masyarakat.
– Teknologi digital membantu budaya kita menolak akal sehat tetapi justru memberi penghargaan besar pada kemarahan, kebohongan, dan mitos.
– Teknologi telah mempercepat kecenderungan manusia untuk menghabiskan sumber daya hingga ke dasar, baik secara metaforis maupun harfiah, alih-alih bercita-cita menuju regenerasi dan keberlanjutan.
Hal ini tidak mengherankan, karena pandangan ke belakang selalu lebih jelas. Jarang sekali para pencipta teknologi pada saat penemuan dapat menilai dengan baik bagaimana sistem mereka akan digunakan, atau benar-benar mengetahui manfaat maupun kerugian yang akan ditimbulkannya. Meskipun dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang kita bisa mengantisipasi segala potensi dampak yang akan terjadi. Membuat simulasi model yang bisa memperkirakan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan risiko.
Industrialisasi meningkatkan standar hidup kita, tetapi juga menyebabkan banyak polusi. Dengan cara yang sama, teknologi telah memperburuk dampak perubahan iklim. Planet ini berada dalam mode darurat penuh. Emisi terus meningkat. Bumi berubah menjadi gurun. Lautan memanas. Spesies mengalami kepunahan. Hutan Amazon terbakar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ekosistem runtuh. Es mencair. Terumbu karang sekarat.
Kita perlu melakukan sesuatu. Dan kita harus melakukannya sekarang!! Kita jelas merupakan generasi terakhir yang dapat mengubah arah perubahan iklim, tetapi kita juga generasi pertama yang mengalami banyak konsekuensi tak terduga darinya.
Chris Ategeka dalam bukunya: The Unintended Consequences of Technology
Solutions, Breakthroughs and the Restart We Need (2022) menguraikan bahwa secara umum, teknologi sering dipahami sebagai artefak. Pandangan ini menonjolkan keberadaan materialnya, asal-usul, penciptaan, dan penggunaannya. Dengan mengutip beberapa sumber Ategeka menulis “Dalam etnografi klasik tentang pengenalan dan adopsi teknologi baru atau “asing” dalam konteks baru …., artefak seperti kapak batu dan baja diidentifikasi dan dijelaskan, kadang-kadang dengan cara deterministik dan evolusioner. Hingga saat ini, dalam catatan populer, teknologi sering dipisahkan dari sosial dan tubuh manusia, sehingga tampak “menonjol” secara material.
Bagi Ategeka, keterpisahan itu karena masih terlalu sedikit narasi yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan teknologi dan hubungan sosial menjadi satu kesatuan yang terpadu, yang membutuhkan kita meninggalkan pemisahan antara teknologi dan masyarakat yang khas modernitas. Atau, mungkinkah ada sesuatu yang melekat dalam teknologi yang memberikannya kekuatan ajaib atau membuatnya lenyap, seperti palu Heidegger yang hanya muncul ketika rusak, tongkat buta Merleau-Ponty, atau infrastruktur yang tidak terlihat?
Sementara sosiolog atau sejarawan teknologi biasanya mempelajari perkembangan produk atau inovasi dalam sains atau teknik modern, dan sebagian besar ilmu teknik tidak menganggap hal lain sebagai teknologi, antropolog bekerja dengan konsep yang lebih luas. Luasnya konsep ini tercermin dalam Handbook yang ditulis Ategeka, dengan bab-bab yang mencakup teknik anyaman keranjang, teknologi reproduksi, teknologi kecantikan, dan teknologi pemerintahan.
Antropolog dan arkeolog, tulis Ategeka, selalu berbagi minat pada hal-hal yang paling sederhana dan sering dianggap remeh dalam kehidupan sehari-hari, dan mempelajari hal-hal ini sebagai teknologi atau budaya material: biasanya keranjang, pot, cangkul, panah, atau alat lainnya, termasuk pipet, ponsel pintar, dan mobil. Pada saat yang sama, antropolog mencatat berbagai praktik teknologi manusia kontemporer yang melibatkan semua jenis aktivitas sementara dan bahan yang mudah rusak yang tidak meninggalkan jejak untuk penggalian arkeologis.
Apa yang dianggap sebagai teknologi dalam konteks tertentu dan untuk siapa adalah beberapa pertanyaan terbuka yang dibawa ke berbagai bidang studi dan situs penelitian lapangan.
Menurut Ategeka, antropolog telah memberikan beberapa definisi berguna tentang teknologi yang menekankan bahwa untuk memahami teknologi, kita harus melampaui artefak dan mencakup tubuh manusia, keterampilan, tradisi, praktik, proses, dan sistem sosio-teknis dalam konseptualisasinya. Kami memilih empat kutipan kontras untuk membuka volume ini, berdasarkan perspektif yang berbeda tentang teknologi yang mereka tawarkan, yang didasarkan pada tiga tradisi antropologis yang berbeda di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Perbedaan ini sebagian dapat dipahami melalui cara istilah “teknik” dan “teknologi” digunakan dalam bahasa Prancis dan Inggris.
Dalam entri ensiklopedianya tahun 1994 tentang teknologi, François Sigaut membahas istilah-istilah tersebut secara sistematis dan mendefinisikan techniques (istilah yang lebih disukai dalam antropologi Prancis) dengan merujuk pada proposisi Marcel Mauss: “Kami menyebut teknik sebagai serangkaian gerakan atau tindakan, umumnya dan sebagian besar manual, yang terorganisir dan tradisional, serta bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diketahui bersifat fisik, kimia, atau organik” (Mauss 2006 [1941/1948], hlm. 149).
Aspek teknologi yang berkaitan dengan gerakan tubuh dan tindakan material yang terlibat dalam teknik sering luput dari perhatian sarjana Anglo-Amerika karena konotasi modernis dari “teknologi” dalam bahasa Inggris. Di sini, konsep teknologi biasanya mengacu pada pencapaian teknik modern, “singkatnya, teknik-teknik yang diinformasikan oleh konten dan metode yang relatif ilmiah.”
Pemahaman ini, seperti yang ditunjukkan Nathan Schlanger (2006), mengarah pada perbedaan hierarkis antara “teknik” dan “teknologi”. Dalam hierarki ini, “teknik” dan keterampilan teknis berlaku untuk fenomena yang bersifat tradisional, skala kecil, atau implisit, sementara “teknologi” mengacu pada fenomena yang dianggap modern, kompleks, dan canggih. Dalam pengertian ini, “teknologi” tidak ada dalam masyarakat pra-modern, hanya ada “alat” dan keterampilan teknis. Pikirkan, misalnya, perbedaan antara teknik kerajinan keranjang dan teknologi balistik.
Dan kita tak akan pernah jera meleburkan diri dalam cahaya dan kegelapan teknologi itu. Meski kita gelisah dalam tidur ini … Sungai terus mengalir. Embun pagi bergulir lewat ujung dedaunan. Matahari tersaput awan. Balon menyarat tajam. Memandu kerlap kerlip bintang. Kerlap kerlipnya kehidupan. Sudah tentu hidup–suka atau duka–tak akan pernah kita sia-sia kan. Ia air yang mengalir ke lautan. Lautan yang dulu pernah melahirkan sungai, mengalirkan kita. Meski sepanjang alur alir itu kita berhadapan dengan hembusan dahsyat nafas kita sendiri. Nafas ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski ia menyeruak ke sel-sel tubuh, ke arah nadi, otot-otot, darah, detak jantung, derap langkah sampai menyusup dalam pikiran kita. Ia mengiris kita berkeping-keping. Lalu serta merta menyusun kita lagi. Dan begitu terus menerus … sampai kita tak mampu lagi menghentikan diri kita. Meninggalkan diri sendiri dengan satu pesan: jangan sampai terkejut, ketika di suatu pagi yang marak, sejuk dan cerah kita mendapati diri kita telah tiada.
Begitulah. Sebuah derap yang anggun telah mengajak manusia pergi mendahului peradabannya. Sementara banyak yang lainnya, malah merayap, tertinggal kereta zaman. Mereka yang terlambat datang di dermaga itu, hingga tertinggal-manis saja tak jemu bergelut dengan luka-luka lama peradaban manusia. Kemiskinan, penindasan, korban nafas, peniadaan hak-hak azasi … dan seterusnya. Itu niscaya adalah duri di tenggorokan peradaban ummat manusia. Tapi ada yang tidak peduli dengan duri itu. Tidak merasa sakit. Sebab yang di telannya adalah sekaligus meniadakan dari rasa sakitnya. Atau yang di telan adalah buah kuldi yang menipiskan dan menumpulkan ketajaman rasa solidaritas atas penderitaan orang lain.
Apakah arti semua itu? Apakah yang menjadi tanggungjawab kita? Dimanakah peran kita sebagai manusia sosial dan berbudi luhur? Kadang aku cuma menggeremeng, menggerutu saja. Aapakah relevan di atas luka yang robek menganga itu, lalu kita ikut cuma memikirkan kepentingan kelompok ras dan jenisnya. Lebih-lebih hanya buat vested interest (kecuali kalau terjadi penindasan atas kelompok tersebut).
Sebab kita sekarang berhadapan dengan permasalahan-permasalahan global universal. Yang membutuhkan penyelesaian politik dan global pula. Ada soal politik dan global juga. Ada soal kemiskinan di gigir kita tegak. Ada kelaparan di sisi-sisi kita mencari kehidupan. Ada masalah kegegapgempitaan iptek dan budaya. Juga tak kancrit pula adalah nasib planet bumi bersama ini: tempat dan ladang kita menabur benih, menyiang, bercocok tanam, mengembala, memanen. Lalu menjual hasil panenan kita.
Dan sekarang ladang ruang tumbuh itu kini di hinggapi berbagai masalah yang perlu di dekati secara bersama-sama, global dan holistis. Bersatu padu menyingsingkan lengan baju. Berholopiskuntul baris. Bergandengan tangan memecahkan masalah bersama untuk kemaslahatan bersama itu.
Aku bertanya: Apakah masih relevan berdebat untuk kepentingan golongan belaka, untuk kepentingan sektoral thok. Aku bertanya. Dan pertanyaanku membentur tembok. Tinta-tinta berceceran di kertas. Aku bercermin cerminnya aku pukul. Dan kulihat darah mengalir lewat jari-jari tanganku. Menetes ke bumi. Tumbuh pertanyaan baru. Pada kurun sekarang, pada bumi yang berputar kita dituntut untuk bekerja sama. Bukankah keterbukaan tengah terjadi dimana-mana, telah menemukan pintu untuk keluar masuk. Keterbukaan berarti mendorong manusia untuk lebih saling mengenal sebagai sesama saudara. Keterbukaan itu telahj adi simbol bagi manusia untuk berpikir egaliter, empati, global dan holistis. Dan saling tenggang rasa. Namun mesti kita sadari sifat syaitani manusia yang terus mencecar sifat mulianya. Ia lalu menciptakan konglomerat untuk merebut saingannya, membuat fanatisme kelompok untuk mengklaim ”kebenaran” kelompoknya. Menyingkirkan pesaing-pesaing yang menggatalkan status quonya dan seterusnya dan sterusnya.
Air terjun mengalir menyeret semua ragam warna dan bentuknya. Di langit, luka itu makin menganga. Kebersamaan kita dilecehkan. Kita di tantang. Solidaritas kita di gugat. Keholistikan, globalisme pemikiran dan sifat universalisme kita di cegat, di pertanyakan sebelum kita mampu bergandeng tangan.
Ini memang cuma fenomena alam belaka. Noktah raksasa yang menyiratkan perjalanan peradaban manusia. Serakah kita memikirkan diri sendiri. Tegakah kita mewarisi anak cucu kita sebuah taman main yang menyengsarakan?
Ozon bukanlah apa-apa. Hanya mainan Tuhan. Kelakar Tuhan pada khalifahnya. Tuhan suatu waktu memang bisa serius tapi jenaka pun bisa. Dan ozon adalah setetes rasa humor Tuhan yang bagaimanapun cukup mencekam manusia. Padahal itu belum apa-apa. Bukan main.
Jakarta, 11 Oktober ’89
diperbarui Februari 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
1 Pfaffenberger, B. (1988). Fetishised objects and humanised nature: Towards an anthropology of technology. In M. H. Bruun, A. Wahlberg, R. Douglas-Jones, C. Hasse, K. Hoeyer, D. B. Kristensen, & B. R. Winthereik (Eds.), The Palgrave Handbook of the Anthropology of Technology (p. 249). Palgrave Macmillan.
2 Lemonnier, P. (1992). Elements for an anthropology of technology. In M. H. Bruun, A. Wahlberg, R. Douglas-Jones, C. Hasse, K. Hoeyer, D. B. Kristensen, & B. R. Winthereik (Eds.), The Palgrave Handbook of the Anthropology of Technology (pp. 1–2, 11). Palgrave Macmillan.
3 Ingold, T. (1997). Eight themes in the anthropology of technology. In M. H. Bruun, A. Wahlberg, R. Douglas-Jones, C. Hasse, K. Hoeyer, D. B. Kristensen, & B. R. Winthereik (Eds.), The Palgrave Handbook of the Anthropology of Technology (pp. 130–131). Palgrave Macmillan.
4 Ategeka, C. (2022). The unintended consequences of technology: Solutions, breakthroughs and the restart we need.Berrett-Koehler Publishers.