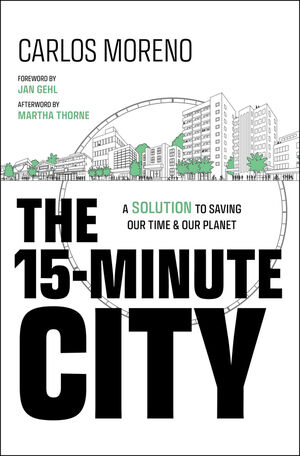Sustainability 17A #50
Gaza, Genosida dan Lingkungan
Dwi R. Muhtaman,
sustainability partner
“It is said that no one truly knows a nation
until one has been inside its jails.
A nation should not be judged by
how it treats its highest citizens,
but its lowest ones.
War diminishes humanity by its
violent suppression of the moral laws
that sustain human society.”
— Nelson Mandela
“Di tengah krisis iklim yang semakin parah, warga Palestina di Gaza berjuang untuk menyelamatkan tanah dan mata pencaharian mereka. Namun pemboman yang berulang-ulang dan blokade yang tiada henti merupakan upaya yang menghancurkan dalam membangun ketahanan iklim.” Pernyataan ini bukan terjadi selama invasi Israel dalam hampir sembilan bulan ini, memasuki Hari ke 248, saat artikel ini ditulis. Ini adalah bagian dari artikel yang berjudul: Gaza’s race against climate breakdown. Ditulis oleh Khalil Abu Yahia, Natasha Westheimer dan Mor Gilboa di media independen +972 Magazine pada 13 January 2022.
Kekurangan air dan listrik yang semakin parah. Banjir dahsyat di wilayah perkotaan yang padat. Kerawanan pangan diperburuk oleh peningkatan suhu secara drastis, penurunan curah hujan secara keseluruhan, dan dampak jangka panjang dari bahan kimia beracun. Ini adalah masa depan suram yang menanti Jalur Gaza, sebuah hotspot perubahan iklim yang tidak memiliki kebutuhan dasar kemanusiaan, serta kapasitas dan sumber daya untuk bersiap menghadapi dan meminimalkan dampak kerusakan iklim. Namun untuk mengatasi kedua masalah ini diperlukan langkah-langkah yang diambil setelah hampir dua dekade blokade darat, udara, dan laut yang dilakukan oleh Mesir dan Israel. Dan pemboman yang berulang kali dilakukan oleh Israel juga memperburuk kerusakan lingkungan di Jalur Gaza. Sehingga semakin melemahkan kemampuan Gaza untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis iklim yang sedang berlangsung.
Oleh karena itu, dua juta penduduk Gaza sebenarnya tinggal di penjara terbuka – penjara yang rentan terhadap agresi dan penghancuran yang tiada henti, serta pembatasan tanpa kompromi Israel terhadap pergerakan orang dan material. Dalam realitas yang rapuh ini, infrastruktur pendukung kehidupan yang paling dasar, seperti akses terhadap air bersih dan pasokan listrik terus menerus berada dalam ancaman. Dan sumber daya dan persediaan inilah yang paling rentan terhadap kerusakan iklim – membuat Gaza dan penduduknya berpacu dengan waktu untuk menjadikan wilayah tersebut layak huni, tidak hanya saat ini, namun juga di masa depan yang penuh ketidakpastian dan semakin tidak menentu.
Pada intinya, ketahanan iklim adalah tentang memperkuat kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah perubahan iklim. Namun memperkuat pasokan air dan listrik pada dasarnya tidak mungkin dilakukan mengingat kondisi yang diberlakukan Israel dan Mesir terhadap Gaza. Ketidakmampuan Gaza untuk membangun ketahanan iklim adalah “..bagian dari mekanisme penindasan sistematis yang bertujuan untuk memperdalam dominasi Israel atas Gaza,” Alexia Guilaume, peneliti hukum di Al-Haq, salah satu dari enam kelompok hak asasi manusia Palestina yang dilarang Israel pada bulan Oktober, mengatakan kepada +972.
Sektor pertanian juga terkena dampaknya. Israel menjatuhkan bom fosfor di tanah milik Ali dan keluarganya, dan menembaki sumur air mereka. “Kami pertama kali merasakan roket dan tercekik oleh baunya,” kenang Ali. “Kemudian kami melihat bom berjatuhan di tanah kami. Setelah kekerasan mereda, saya membawa teman saya, seorang insinyur pertanian, untuk memeriksa lahan kami, dan dia mengatakan lahan tersebut penuh dengan racun. Kami kemudian mengetahui dari Kementerian Kesehatan di Gaza bahwa Israel menggunakan bom fosfor.”
Itulah perlakuan zionis Israel pada rakyat dan Bangsa Palestina pada awal 2022.
Bahkan pada dua dekade sebelumnya Israel dituduh menggunakan bom-bom berbahaya tidak saja mada manusia tetapi juga lingkungan dan dengan cara yang melanggar hukum: serangan tahun 2008/9. Penembakan tanpa pandang bulu di wilayah sipil yang padat penduduknya. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan tubuh manusia, bom kimia ini juga dapat mencemari tanah dan menjadi racun bagi tanaman, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
“Kami tidak bisa menanam sayuran apa pun di tempat yang hancur akibat bom fosfor,” kata Ali. “Sejak bom ini digunakan di lahan kami, semua pepohonan di sekitarnya menghasilkan tanaman dengan warna dan rasa yang berbeda dibandingkan yang bisa kami tanam sebelumnya. Israel menggunakan senjata-senjata ini untuk menargetkan kami dan mensterilkan tanah kami. Mereka meracuni buah dan sayuran kita, bahkan setelah dicuci, sehingga menciptakan kerawanan pangan karena penurunan produksi.”
Bahan kimia yang digunakan dalam senjata Israel seperti fosfor semakin membahayakan kesehatan masyarakat di Gaza. Tamer Yousef, seorang ahli saraf yang tinggal di salah satu rumah sakit besar di Gaza, menjelaskan bahwa karena “pohon dan tanaman dapat menyerap bahan kimia beracun ini, produksi pertanian mereka menjadi tidak sehat.”
Pada 25 March 2009 sebuah laporan diterbitkan oleh Human Rights Watch. Judulnya, Rain of Fire: Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza. Laporan ini mendokumentasikan penggunaan amunisi fosfor putih secara ekstensif oleh Israel selama 22 hari operasi militernya di Gaza, dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, yang diberi nama Operasi Cast Lead. Berdasarkan investigasi mendalam di Gaza, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berulang kali meledakkan amunisi fosfor putih di udara di wilayah berpenduduk, membunuh dan melukai warga sipil, dan merusak bangunan sipil, termasuk sekolah, pasar, dan bangunan-bangunan sipil, gudang bantuan kemanusiaan dan rumah sakit.
Amunisi fosfor putih tidak membunuh, secara langsung, sebagian besar warga sipil di Gaza – lebih banyak lagi yang tewas akibat rudal, bom, artileri berat, peluru tank, dan tembakan senjata ringan – namun penggunaannya di lingkungan padat penduduk, termasuk pusat kota Gaza City, melanggar hukum kemanusiaan internasional (the hukum perang), yang mengharuskan dilakukannya semua tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian sipil dan melarang serangan tanpa pandang bulu.
Ketika invasi Israel Oktober 2023 berlangsung dan memasuki hari ke 60, total emisi karbon yang ditimbulkan dari invasi Israel ini telah mencapai 281,315 tonnes of CO2 equivalent. Ini hanya dalam waktu dua bulan telah melampaui emisi tahunan Central African Republic. Emisi dihasilkan dari masing-masing Israeli aircraft missions (121,000 tonnes of CO2 equivalent), US supply flights (133,650), Israeli artillery (13,600), Israeli bombs, Tanks and armoured (6,689). Sedangkan pihak perlawanan HAMAS sejumlah 713 dari roket yang diluncurkan.
Lebih lanjut studi yang dilakukan Benjamin Neimark, Patrick Bigger, Frederick Otu-Larbi, Reuben Larbi menyatakan bahwa proyeksi emisi dari 60 hari pertama perang Israel-Gaza lebih besar dari emisi tahunan dari 20 negara dan wilayah.
❖ Jika kita memasukkan infrastruktur perang yang dibangun oleh Israel dan Hamas, termasuk infrastruktur milik Hamas jaringan terowongan dan pagar pelindung Israel atau ‘Dinding Besi’, total emisinya meningkat menjadi lebih dari 33 negara dan wilayah.
❖ Biaya karbon dalam rekonstruksi Gaza sangat besar. Membangun kembali Gaza memerlukan upaya total angka emisi tahunannya lebih tinggi dibandingkan 130 negara lain, sehingga setara dengan angka emisi tahunan Selandia Baru.
❖ Sifat perhitungan ini yang bersifat ad-hoc menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kewajiban pelaporan emisi dari semua aktifitas militer untuk masa perang dan masa damai melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Sebagian besar (lebih dari 99%) dari 281.000 metrik ton karbon dioksida (setara CO2) diperkirakan dihasilkan dalam 60 hari pertama setelah serangan Hamas tanggal 7 Oktober dapat dikaitkan dengan pemboman udara dan invasi darat Israel ke Gaza, menurut analisis pertama yang dilakukan oleh para peneliti di Inggris dan AS.
Menurut penelitian tersebut, yang hanya didasarkan pada segelintir aktivitas padat karbon dan oleh karena itu mungkin merupakan perkiraan yang terlalu rendah, kerugian iklim dalam 60 hari pertama respons militer Israel setara dengan pembakaran setidaknya 150.000 ton batu bara.
Analisis tersebut, yang belum ditinjau oleh rekan sejawat, mencakup CO2 dari misi pesawat terbang, tank, dan bahan bakar dari kendaraan lain, serta emisi yang dihasilkan dari pembuatan dan peledakan bom, artileri, dan roket. Ini tidak termasuk gas-gas lain yang menyebabkan pemanasan global seperti metana. Hampir setengah dari total emisi CO2 berasal dari pesawat kargo Amerika yang menerbangkan pasokan militer ke Israel.
Roket Hamas yang ditembakkan ke Israel pada periode yang sama menghasilkan sekitar 713 ton CO2, yang setara dengan sekitar 300 ton batu bara – yang menggarisbawahi asimetri mesin perang masing-masing pihak. Hingga Juni 2024, penjajah Israel telah menjatuhkan 70.000 ton bom di gaza dan hal itu telah menghasilkan antara 420.265 dan 652.552 ton karbon dioksida dan 37 juta ton puing-puing.
“Studi ini hanyalah gambaran singkat dari dampak perang yang lebih besar… gambaran sebagian dari emisi karbon yang sangat besar dan polutan beracun yang lebih luas yang akan tetap ada lama setelah pertempuran berakhir,” kata Benjamin Neimark, dosen senior di Queen Mary. University of London (QMUL), dan rekan penulis penelitian yang dipublikasikan pada hari Selasa di Social Science Research Network.
Akibat invasi brutal dan biadab tersebut Gaza diperkirakan mengalami penurunan curah hujan yang tidak menentu dan berkurang 20% pada 2050. Suhu diperkirakan akan terus meningkat, 2,5 derajat pada tahun 2055, seiring dengan meningkatnya musim kemarau, gelombang panas, dan kekeringan.
Kenaikan permukaan air laut menimbulkan risiko erosi pantai dan intrusi air asin ke akuifer Gaza yang sudah terkuras, terkontaminasi, dan diekstraksi berlebihan. Polusi air tanah dan tanah serta pembuangan limbah memperburuk degradasi lingkungan; 90-95% air tanah sudah tidak dapat diminum. Saat ini, akses terhadap air sangat dibatasi oleh Israel sehingga kurang dari 15 liter dari tingkat kelangsungan hidup layak. Pada COP28 November lalu, para pejabat Badan Energi Sumber Daya Air dan Otoritas Kualitas Lingkungan Palestina menyatakan bahwa perjanjian pembelian air yang tidak layak dan mahal dengan Israel sejak 1995 tidak menyediakan cukup air untuk memenuhi seluruh kebutuhan Palestina.
Gaza merupakan masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Namun, blokade Israel telah membatasi ekspor produk pertanian dan impor bahan-bahan penting, seperti pupuk, peralatan pertanian dan irigasi. Hal ini berkontribusi terhadap kerawanan pangan karena lahan subur menyusut akibat zona penyangga, perambahan militer Israel, dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan.
Penghancuran 100 m2 bangunan perkantoran menghasilkan sekitar 1000 metrik ton sampah dan ≤ 110,000 kg emisi CO2. Karena itulah Greta Thunberg yang memampangkan fotonya dengan poster “stand with Gaza” dan para aktivis lingkungan dunia ikut bersuara dan berdiri bersama Palestina? Tentu saja itu membuat berang Israel dan juga Jerman. Sejumlah media yang bias juga memojokkan para aktifis lingkungan karena dukungannya pada Palestina dan Gaza.
Gaza diblokade selama 17 tahun. Israel menahan pasokan dan akses bahan bakar dan listrik di wilayah tersebut. Akibatnya, masyarakat Gaza beralih ke energi surya (solar panel) untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah mereka. “Warga Gaza sudah adaptif terhadap iklim, dan sekitar 60% energi mereka berasal dari tenaga surya,” kata Majdalani, Direktur Eco-Peace Middle East untuk Palestina (dikutip dari Aljazeera). Pemboman Israel telah merusak dan menghancurkan ribuan bangunan yang banyak diantaranya beratap panel surya.
“Penghancuran panel surya tidak hanya menargetkan kesejahteraan masyarakat, tetapi
juga mengurangi upaya warga Gaza dalam melakukan adaptasi iklim dan langkah-langkah untuk mengamankan energi bersih,” katanya.
Lalu, berapa kontribusi emisi karbon dari sektor militer? Nilainya 5,5% dari total emisi global per tahun. Jumlah ini lebih banyak dari gabungan industri penerbangan dan pengiriman. Artinya, tanpa ada perang/konflik/genosida saja industri militer sudah menjadi kontributor signifikan emisi karbon. Namun, nilainya hampir tidak pernah diperhitungkan. Jika industri militer adalah sebuah negara, maka nilai emisi karbonnya menduduki peringkat 4 terbesar setelah Amerika Serikat, China, dan India, bahkan lebih besar daripada Rusia.
(Global Carbon Budget, 2021 & Scientists for Global Responsibility). Data emisi perang dan militerisme agak sulit didapatkan karena kerahasiaan. Karena itulah, menurut Benjamin Neimark, selalu ada celah dalam pelaporan ke UNFCCC yang ditetapkan pada masa pemerintahan George HW Bush dan kemudian ditegaskan kembali di Paris pada tahun 2015, seehingga penghitungan karbon oleh militer tetap bersifat sukarela, dan banyak yang tidak melaporkan emisinya sama sekali. Faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Military Emission Gap menunjukkan bahwa saat ini hanya 4 negara yang menyediakan beberapa laporan emisi, meskipun tidak lengkap ke UNFCCC.
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh genosida yang dilakukan Israel di Gaza sangatlah luas. “Perang mempunyai dampak langsung terhadap perubahan iklim dengan meningkatkan emisi karbon dan menghancurkan infrastruktur. Jalur Gaza adalah contoh nyata dalam menghadapi krisis yang kompleks dari sudut pandang kemanusiaan, lingkungan hidup, kesehatan dan iklim akibat perang berulang yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir,” kata Omar Shoshan, Presiden Persatuan Lingkungan Hidup Yordania. But wait. It’s not a war.
It’s genocide. Itulah kenapa pada akhirnya dunia berpihak pada Palestina (IG @gregetkallabuana).
Dua bulan pertama genosida yang dilakukan Israel di Gaza ternyata ikut memperparah krisis iklim dengan menyumbang: 281,315 ton emisi karbon. Sejak serangan darat militer tanggal 27 Oktober, 22% lahan pertanian di Gaza Utara dihancurkan oleh Israel. Israel menghancurkan 70% armada penangkapan ikan di Gaza. Ternak kelaparan, tidak mampu menyediakan makanan atau menjadi sumber makanan.
“Saya memiliki 120 pohon zaitun, yang biasanya menghasilkan 12 ton buah zaitun. Namun tahun ini, hanya menghasilkan satu ton! Suhu ekstrim dan distribusi curah hujan yang tidak merata berdampak serius pada fase pembungaan dan jumlah pohon. Kami tidak pernah menyaksikan penurunan jumlah pohon selama sepuluh tahun terakhir,” Labu Ibrahim, seorang petani di Gaza, mengatakan kepada Komite Internasional Palang Merah pada tahun
2021 (climate-refugees.org).
Di Gaza, pola penghancuran yang konsisten disertai dengan pelepasan bahan kimia berbahaya secara terus-menerus ke lahan pertanian serta penguasaan bank benih di Palestina, yang mengatur kesehatan, pangan, dan pergerakan rakyat Palestina. Selain itu, sumber-sumber air di Gaza terus-menerus terkontaminasi dan terhambat, menjadikan air menjadi langka dan berbahaya, sehingga melanggengkan ketergantungan dan merampas sumber daya penting masyarakat. Pendudukan tersebut mengalihkan air laut ke pipa-pipa air yang terhubung ke wilayah perkotaan, mengeringkan masyarakat dari air tawar, mewajibkan mereka menggunakan air asin, sekaligus mengganggu ekosistem laut dan habitat pesisir untuk mendapatkan kendali jangka pendek. Oleh karena itu, lebih dari 90 persen air di Jalur Gaza tidak cukup untuk keperluan minum atau pertanian, sehingga menempatkan warga pada risiko tinggi terkena penyakit.
Gaza adalah tempat di mana dampak perubahan iklim memperburuk kebutuhan kemanusiaan yang serius akibat genosida.
Pada awal tahun 2022, para jurnalis mulai bertanya berdampak pada krisis iklim dari invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Meskipun ada jawaban untuk kebakaran hutan, kilang minyak yang terbakar, tetapi kendaraan militer yang menggunakan bahan bakar diesel, data emisi yang dicari tidak tersedia. Analisis dan perdebatan internasional selama dua dekade mengenai hubungan antara perubahan iklim dan keamanan berfokus pada bagaimana destabilisasi iklim yang cepat dapat merusak keamanan suatu negara. Namun negara-negara tersebut mengabaikan bagaimana pilihan keamanan nasional, seperti belanja militer atau perang, dapat berdampak pada iklim, sehingga melemahkan keamanan kolektif kita.
Dengan semakin cepat terjadinya kerusakan iklim, kita harus mampu memahami dan meminimalkan emisi dari semua aktivitas masyarakat, baik di masa damai maupun perang. Namun jika menyangkut emisi militer atau konflik, hal ini masih belum bisa dicapai.
Perang selalu memberi dampak yang luar biasa. Dampak bagi kemanusiaan sudah bisa dipastikan. Invasi yang dilakukan oleh Occupied State of Palestine/OSP atau Negara Penjajah Palestina di wilayah Negara Palestina telah membunuh lebih dari 30.000 warga sipil. Sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Tetapi dampak lingkungan juga tidak kalah dahsyatnya seperti diuraikan sebelumnya. Dampak konflik bersenjata terhadap lingkungan alam sering kali diakui, namun skalanya masih diremehkan. Dari tahun 1946 hingga 2010, konflik merupakan satu-satunya faktor penentu penurunan populasi satwa liar tertentu. Hukum humaniter internasional melindungi lingkungan alam dan bertujuan untuk membatasi kerusakan yang diakibatkannya, bukan hanya karena lingkungan menopang kehidupan manusia, namun karena nilai intrinsiknya. Menggunakan lingkungan alam sebagai senjata, atau mengarahkan serangan terhadapnya, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan akibat konflik bersifat insidentil. Misalnya, serangan terhadap sasaran militer sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan; dan aktivitas yang menunjang konflik seperti perburuan liar juga menimbulkan dampak buruk.
Selama perang saudara selama 15 tahun di Mozambik, Taman Nasional Gorongosa kehilangan lebih dari 90% hewannya. Kerbau Afrika berkurang dari 14.000 menjadi 100 individu, dan populasi kuda nil dari 3.500 menjadi 100. Populasi gajah menurun dari 2.000 menjadi 200, karena daging gajah digunakan untuk memberi makan tentara dan gadingnya dijual untuk membiayai pembelian senjata, amunisi. dan perbekalan.
Krisis iklim dan lingkungan hidup saat ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan fisik dan mental, hingga makanan, air, dan mata pencaharian kita. Meskipun krisis ini berdampak pada semua orang, mereka yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat termiskin dan terpinggirkan. Orang-orang yang hidup dalam konflik sering kali bercerita kepada kita tentang perubahan lingkungan besar-besaran yang mereka saksikan. Kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya menjadi lebih sulit karena kekerasan yang mereka alami, namun juga karena perubahan iklim dan lingkungan. Mereka sering kali tidak siap menghadapi bahaya iklim yang berulang.
Tetapi secara hukum internasional tidak ada perlindungan yang kuat atas lingkungan pada situasi konflik. Michael Bothe mengupas soal itu. Menurutnya perdebatan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan konflik bersenjata dimulai sekitar tahun 1970 karena bertemunya dua gerakan politik: di satu sisi, kesadaran akan masalah lingkungan termasuk kepedulian terhadap generasi mendatang dan, di sisi lain, kebutuhan untuk membangun hukum konflik bersenjata, mengisi beberapa celah yang ditinggalkan oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 dan mencerminkan pengalaman konflik yang telah terjadi sejak saat itu. Terdapat (dan sedang ada) ketegangan antara kepentingan militer untuk memenangkan perang dan kepentingan lingkungan dalam melestarikan planet ini untuk generasi mendatang. Protokol I tambahan pada Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977 merupakan kemenangan bagi kepentingan militer dengan menetapkan ambang batas kerusakan lingkungan yang tidak diperbolehkan dengan cara yang jauh dari memenuhi kebutuhan pelestarian lingkungan. Namun wacana yang ramai telah dimulai dan membawa kemajuan, namun masih jauh dari hasil akhir yang memuaskan. Unsur-unsur utamanya adalah penerapan kaidah-kaidah mengenai perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil terhadap perlindungan lingkungan hidup, asas kehati-hatian terhadap lingkungan hidup, diakuinya kebutuhan untuk menetapkan kawasan-kawasan yang dilindungi demi pelestarian lingkungan hidup, kegiatan-kegiatan yang intensif dalam bidang lingkungan hidup, dan kegiatan-kegiatan yang intensif. pencarian fakta lingkungan hidup, tantangan untuk mempertahankan tata kelola lingkungan hidup yang diperlukan dalam kondisi konflik bersenjata dan restorasi lingkungan sebagai bagian dari pembangunan perdamaian setelah konflik.
Brian E. Fogarty dalam bukunya: War, Peace, and the Social Order menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu diliputi oleh tindakan-tindakan perlawanan atau bekerjasama. Perang dan damai. Diskusi mengenai perang dan perdamaian, menurutnya, jika dilakukan secara mendalam, cenderung memecah masyarakat menjadi dua aliran pemikiran. Pendekatan pertama didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang kejam dan bahwa lapisan masyarakat yang beradab adalah satu-satunya yang menyelamatkan kita dari kekacauan dan penghancuran diri. Kita memerlukan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah yang kuat, ajaran yang otoriter, dan lembaga-lembaga lain untuk melindungi kita dari satu sama lain, karena dorongan alamiah manusia (yang banyak ditunjukkan dengan melihat surat kabar mana pun) adalah untuk bersaing, mengeksploitasi orang lain, dan umumnya bertindak mutlak atas kemauan-minat sendiri.
Sebaliknya, pendekatan kedua bertumpu pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang damai, yang secara alamiah atau sunnatullah diberkahi dengan keinginan bawaan untuk bekerja sama dan memelihara. Mereka yang menganut pandangan ini menganggap tatanan sosial dan paksaan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan yang menyertainya adalah penyebab jatuhnya umat manusia dari kasih karunia. Kekerasan dan perang adalah perilaku yang tidak wajar bagi manusia, dan dapat dikurangi atau bahkan dicegah jika kejahatan yang disebabkan oleh peradaban dapat diatasi.
Singkatnya, masyarakat adalah sumber permasalahan umat manusia, bukan solusinya. Kedua posisi ini, secara kebetulan, mencerminkan pokok perdebatan di antara para filsuf “kontrak sosial” pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, khususnya Hobbes dan Rousseau.
Setiap pandangan memunculkan fiksi yang berbahaya. Yang pertama menyiratkan bahwa perdamaian hanya bisa dibeli dengan mengorbankan kebebasan dan martabat manusia; kecenderungan alami untuk berperang melawan satu sama lain harus dikendalikan oleh struktur sosial dan politik yang semakin menindas. Memang benar, ada yang berpendapat bahwa seiring dengan pertambahan populasi manusia, pengendalian ini harus diperketat untuk mengakomodasi kelangkaan dan persaingan yang semakin besar. Oleh karena itu, peperangan dapat diharapkan dan bahkan mungkin diterima sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kendali, atau setidaknya sebagai produk sampingan yang tidak dapat dihindari dari proses tersebut.
Pandangan kedua ini mengkondisikan pemahaman manusia dengan mengingkari bahwa perang dan kekerasan adalah fenomena alam yang bisa dipahami. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk memperlakukan realitas perang seolah-olah hal tersebut merupakan pengecualian terhadap keadaan alamiah; sebuah kesalahan kosmik yang mungkin bisa diperbaiki hanya dengan menyadari bahwa perang dan kekerasan itu buruk. Aliran pemikiran ini biasanya memandang perang sebagai akibat dari tindakan elit yang mementingkan diri sendiri, komunisme sedunia, atau kapitalisme sedunia—singkatnya, niat buruk orang-orang jahat yang telah memperoleh cukup kekuasaan untuk melakukan korupsi dan memimpin orang lain berperang. Pandangan seperti ini menggagalkan tujuan mengakhiri perang dengan menjadikannya sebagai hal yang tidak dapat diduga.
Tidak ada asumsi yang dapat diterima. Upaya mencapai perdamaian harus dimulai dengan keyakinan bahwa perdamaian sejati dapat dicapai tanpa meningkatnya perbudakan dan pemiskinan. Bagaimanapun juga, manusia pada umumnya baik satu sama lain jika diberi kesempatan. Mereka dengan sukarela menjalin persahabatan, menikah, dan membesarkan keluarga. Orang tua mungkin mengorbankan kenyamanan dan kesempatan mereka sendiri seumur hidup, hanya demi memberikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Manusia tidak selalu terlibat dalam perang seperti yang didefinisikan sekarang. Pernyataan ini seharusnya tidak mengherankan, karena manusia tidak selalu terlibat dalam aktivitas apa pun yang dianggap melekat pada kodratnya. Semua institusi budaya yang tampak alamiah menjadi bagian dari keberadaan manusia pasti diciptakan oleh nenek moyang manusia; ada suatu masa dalam sejarah manusia sebelum gagasan tentang pemerintahan ditemukan, sebelum adanya bangsa, sekolah, tulisan dan hukum. Ada suatu masa sebelum manusia sampai pada ide menanam tanaman atau memelihara hewan.
Para antropolog menyebut masa ini dalam sejarah manusia sebagai era Paleolitik; Zaman Batu Tua. Disebut demikian karena teknologi terpenting pada masa itu adalah pembuatan perkakas dari batu, hanya menggunakan kayu, tulang, dan batu lainnya. Kemampuan untuk membuat peralatan dan senjata berburu membuat komunitas tetap hidup, karena perburuan hewan dan pengolahannyalah (memotong daging, mengikis kulit, dan sejenisnya) yang membuat masyarakat tetap hidup.
Budaya-budaya ini disebut budaya mencari makan, atau alternatifnya, budaya pemburu-pengumpul. Mencari makan adalah satu-satunya cara mencari nafkah yang diketahui manusia sepanjang sejarah manusia. Sejak zaman hominid paling awal, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu, setiap kebudayaan menganggap bahwa cara hidup adalah dengan berburu daging dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan liar. Bukan berarti kebudayaan-kebudayaan ini sama dalam segala hal, karena masih banyak keadaan lain yang menentukan bagaimana manusia dapat hidup. Misalnya, masyarakat hutan mengembangkan teknik rumit untuk menjebak dan memburu mamalia kecil dan hewan pengerat serta membangun tempat berlindung dari hasil hutan. Sebaliknya, orang Indian dataran rendah berburu kerbau dan mengolah hewan tersebut untuk digunakan hampir semua bagiannya dengan cara tertentu. Masyarakat Kepulauan Pasifik mencari ikan dan bernavigasi, dan masyarakat Arktik sebagian besar hidup dari anjing laut dan ikan paus.
Ada sebuah perumpamaan di mana seorang anak kecil terlihat berjalan di sepanjang pantai yang sepi, sesekali membungkuk untuk mengambil sesuatu dan membuangnya ke laut. Seorang pejalan kaki berhenti dan menanyakan apa yang dia lakukan, dan dia menjawab: “Air pasang sudah surut, dan bintang laut ini akan mengering dan mati jika saya tidak membuangnya kembali.” Pejalan kaki melihat ke atas dan ke bawah untaian panjang tersebut dan berkata, “Tetapi lautnya sangat luas—Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan semua bintang laut di pantai yang satu ini. Anda tidak akan pernah membuat perbedaan besar dalam skema yang lebih besar.” Anak laki-laki itu mengambil bintang laut lainnya, melemparkannya ke dalam air, dan berkata: “Benar, tapi saya baru saja menyelamatkan yang itu.”
Cerita kecil ini menarik garis yang jelas antara dua perspektif mengenai peran individu dalam perilaku masyarakat. Orang yang lewat memandang aktivitas anak laki-laki itu sebagai hal yang tidak penting; meski tidak berbahaya namun kekanak-kanakan dan sentimental, membuang waktu dan energi. Anak laki-laki tersebut tahu bahwa dia tidak akan pernah berpengaruh penting, namun dia tetap merasa terdorong untuk mengubah “pendatang kecil di dunia ini” karena rasa tanggung jawab pribadinya.
Setiap karakter mewakili posisi kutub mengenai peran individu dalam mempengaruhi perubahan sosial. Keterlibatan “prinsip” anak laki-laki tersebut berasal dari kesadaran bahwa masyarakat pada akhirnya terdiri dari individu-individu dan tindakan sosial pada akhirnya merupakan gabungan dari banyak tindakan individu. Jika setiap orang membuang kembali semua bintang laut yang mereka lihat, hal ini akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masalah kematian bintang laut. Demikian pula, jika setiap orang bertindak lebih adil dan damai, atau jika setiap orang mendaur ulang, atau jika setiap orang menyumbangkan bagiannya secara adil untuk amal, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Anak laki-laki tersebut tahu bahwa menunggu orang lain atau lembaga tertentu untuk mengatasi masalahnya adalah pendekatan yang pasif dan mengalah: Dunia yang lebih baik dimulai dari saya.
Epigraf dari Nelson Mandela yang saya kutip di atas “Dikatakan bahwa seseorang tidak benar-benar mengetahui suatu bangsa sampai dia berada di dalam penjaranya. Suatu bangsa seharusnya tidak dinilai dari bagaimana mereka memperlakukan warganya yang paling tinggi, tetapi yang paling rendah. Perang merendahkan kemanusiaan dengan penindasan kekerasan terhadap hukum moral yang menopang masyarakat manusia.” Nelson Mandela mengucapkan ini karena pengalaman pribadinya yang mendalam selama 27 tahun dipenjara di masa apartheid. Melalui pengalaman tersebut, Mandela menyaksikan secara langsung ketidakadilan dan kondisi keras yang dialami oleh para tahanan, yang sebagian besar adalah tahanan politik. Ucapannya menyoroti keyakinannya bahwa ukuran sejati suatu masyarakat adalah bagaimana ia memperlakukan anggota-anggotanya yang paling rentan dan terpinggirkan, menekankan perlunya perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap semua individu, termasuk mereka yang dipenjara. Bagian terakhir dari kutipan ini juga berbicara tentang dampak perang terhadap standar moral dan etika, menyoroti bagaimana kekerasan merusak prinsip-prinsip fundamental yang menopang peradaban manusia. Mandela mengalami perlakukan itu dari pemerintah negaranya, Afrika Selatan yang aparteid. Inilah yang terjadi lebih dari 76 tahun di Palestina di bawah penjajahan Israel, dan jauh lebih buruk dari yang terjadi di Afrika Selatan (1948-1994).
Gaza dan Palestina adalah kompas moral dan etika dunia. Mereka telah membongkar wajah-wajah kemunafikan dunia Barat. Mereka yang nampak sangat penduli pada hak-hak azasi manusia pada dasarnya pembohong dan penyangkal. Mereka yang nampak sangat penduli pada lingkungan hidup pada dasarnya penghancur dan tidak peduli pada lingkungan hidup.
Situgede, Bogor,
13 Juni 2024