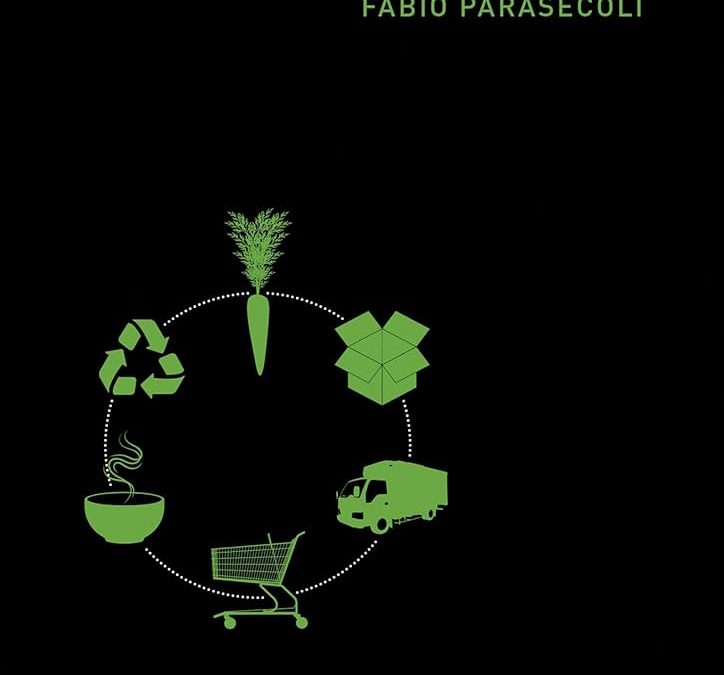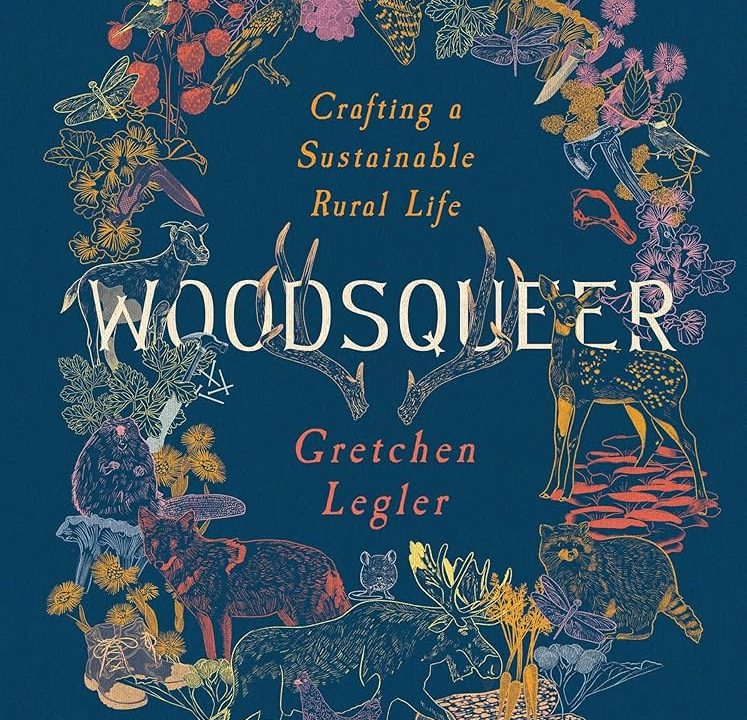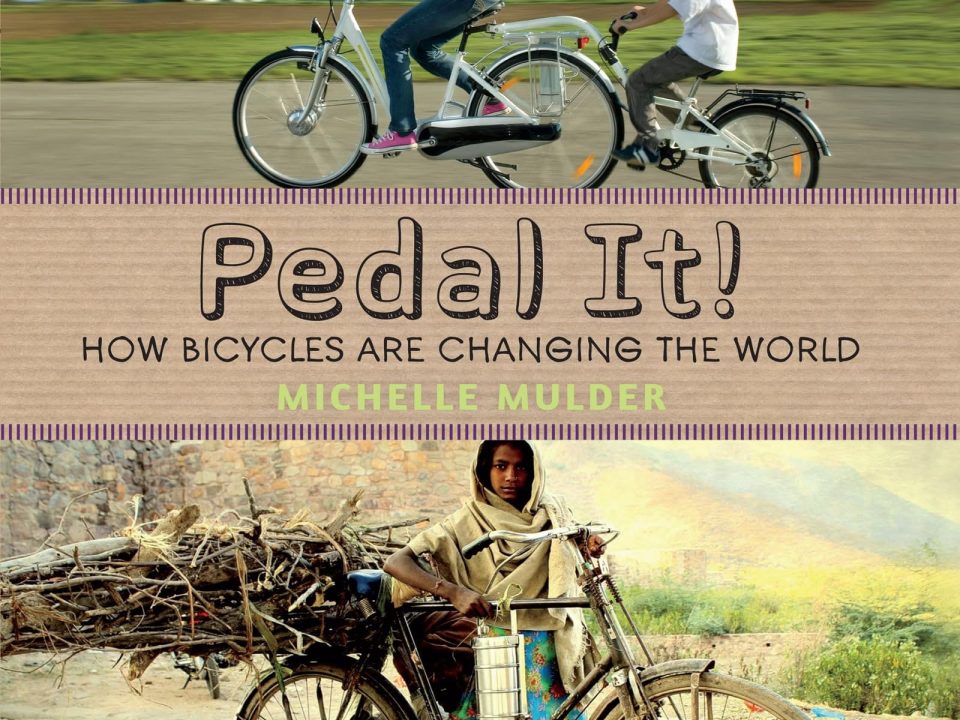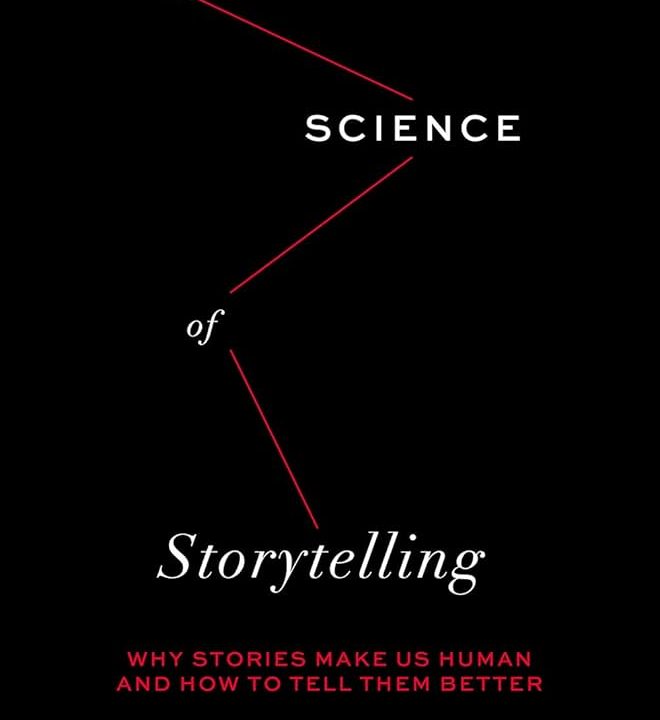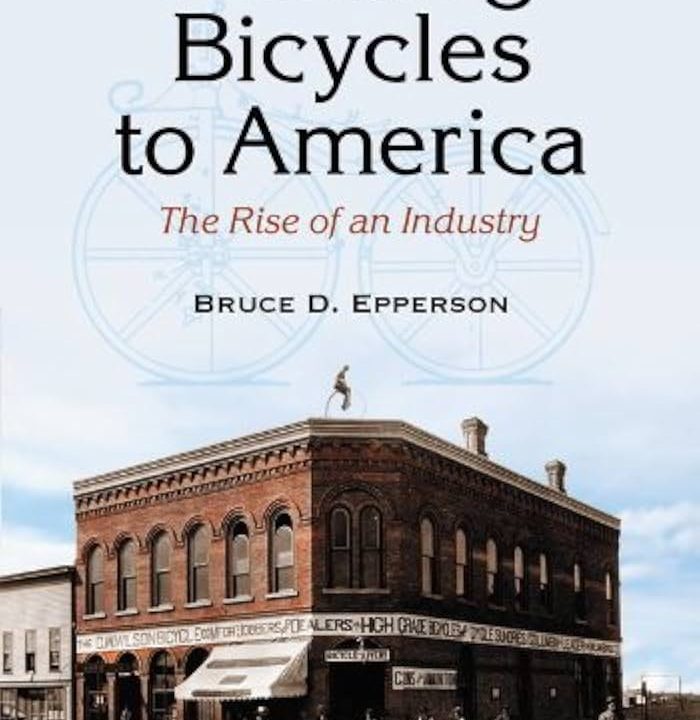Rubarubu #102
Food :
Makanan sebagai Arena Politik Global
Kisah Sepiring Nasi
Di sebuah warung makan padang di jantung Jakarta, seorang ibu muda bernama Sari terpaku melihat anaknya yang berusia lima tahun dengan lancar memesan burger melalui aplikasi ponsel. Sementara di meja sebelah, kakek-neneknya sedang menyantap gulai nangka dan daun singkong rebus—warisan kuliner yang telah turun-temurun. Dalam satu ruangan yang sama, terhampar tiga generasi dengan hubungan yang berbeda terhadap makanan: dari yang sakral-tradisional, praktis-lokal, hingga global-digital. Momen inilah yang kemudian mengantar Sari pada pencarian makna di balik setiap suapan makanan, sebuah pencarian yang membawanya pada buku Fabio Parasecoli “Food”—sebuah karya yang membongkar bagaimana pangan telah menjelma menjadi medan pertarungan politik, identitas, dan kekuasaan dalam arus globalisasi.
Di dunia yang semakin menyadari bahwa makanan bukan sekadar bahan bakar, tetapi simpul kompleks dari politik, ekonomi, identitas, dan teknologi, muncul seorang penjelajah intelek-tual yang khusus memetakan persimpangan-persimpangan rumit ini: Fabio Parasecoli.
Parasecoli adalah sosok akademikus lintas disiplin dan kosmopolitan. Latar belakangnya mencerminkan pendekatannya yang holistik terhadap studi makanan. Ia merupakan Professor of Food Studies di The New York University (NYU) dan sebelumnya mengajar di University of Gastronomic Sciences di Pollenzo, Italia—sebuah pusat studi gastronomi terkenal di dunia. Dan ia membuka bukunya dengan tesis provokatif bahwa makanan bukan sekadar kebutuh-an biologis, melainkan “arena pertarungan makna dan kekuasaan” dalam sistem pangan global. Melalui pendekatan cultural studies, ia menelusuri bagaimana makanan menjadi alat diplomasi internasional, soft power, dan instrumen hegemoni budaya. “Setiap gigitan makanan menyimp-an narasi tentang hubungan kekuasaan, perdagangan global, dan negosiasi identitas,” tulis Parasecoli. Filosof Prancis Pierre Bourdieu dalam teori kapital simboliknya menyatakan, “Selera makanan adalah selera yang diinternalisasi,” yang menggambarkan bagaimana preferensi kuliner mereproduksi struktur sosial yang ada.
Buku ini menelusuri jejak kolonialisme dalam sistem pangan kontemporer. Karena ternyata kolonialisme juga berkait dengan globalisasi rantai pasok. Parasecoli menunjukkan bagaimana komoditas seperti kopi, gula, dan rempah-rempah tidak hanya mengubah pola konsumsi Eropa tetapi juga menciptakan hierarki global yang masih bertahan hingga kini. “Rantai pasok makan-an modern adalah pewaris langsung dari rute perdagangan kolonial,”paparnya. Dalam konteks Indonesia, analisis ini menjelaskan mengapa komoditas seperti kelapa sawit dan kopi tetap menjadi sumber konflik agraria dan ketimpangan, sekaligus menjadi alat diplomasi ekonomi di forum internasional.
Gastrodiplomasi dan Identitas Nasional
Parasecoli memperkenalkan konsep “gastrodiplomasi”—penggunaan makanan sebagai alat diplomasi budaya. Ia menganalisis bagaimana negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Meksiko membangun citra nasional melalui promosi kuliner. “Makanan menjadi paspor kultural yang membuka pintu diplomasi,” jelasnya. Indonesia dengan program “Indonesia Spice Up the World” dapat belajar dari analisis ini, bahwa gastrodiplomasi bukan sekadar promosi kuliner, melainkan strategi membangun pengaruh kultural global. Karier akademisnya tidak berlabuh di satu tempat; ia telah menjadi profesor tamu dan peneliti di berbagai institusi bergengsi di Eropa, Asia, dan Amerika, menunjukkan jangkauan dan pengaruh globalnya. Gelar PhD-nya dalam Ilmu Politik mengungkap fondasi analitisnya: ia melihat makanan sebagai arena kekuasaan, sebuah lensa yang kuat untuk mengamati dinamika sosial.
Parasecoli tak lupa menguraikan hubungan antara kapitalisme digital dan ekonomi pangan. Parasecoli membahas bagaimana platform seperti Uber Eats, GoFood, dan aplikasi delivery lainnya mengubah hubungan kita dengan makanan. Parasecoli menunjukkan bagaimana algoritma mempengaruhi preferensi konsumen dan menciptakan bentuk ketergantungan baru. “Data tentang selera makanan menjadi komoditas yang lebih berharga daripada makanan itu sendiri,” kritiknya. Di Indonesia, dominasi GoFood dan GrabFood tidak hanya mengubah pola konsumsi tetapi juga menciptakan relasi kuasa baru dalam ekosistem kuliner.
Parasecoli dengan tajam mengkritik sistem pangan industrial yang tidak berkelanjutan dan tidak adil. Ia memperdebatkan perlunya “demokratisasi sistem pangan” yang memberi ruang bagi produsen kecil dan konsumen. “Krisis pangan adalah krisis demokrasi,” tegasnya. Aktivis makanan Indonesia seperti Arief Aziz menyoroti bahwa “kedaulatan pangan Indonesia terancam ketika kita lebih bangga dengan makanan impor daripada kekayaan pangan lokal.”
Buku ini mengeksplorasi bagaimana makanan menjadi penanda identitas kultural dalam masyarakat migran. Parasecoli menunjukkan proses “hibriditas kuliner” dimana makanan tradisional beradaptasi dengan konteks baru, menciptakan bentuk-bentuk kuliner hybrid. “Makanan migran adalah narasi perjalanan yang dapat disantap,” ujarnya. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam perkembangan masakan Peranakan yang memadukan unsur Tionghoa dan lokal.
Bab penutup (Paragraf 7: Etika Konsumsi dan Masa Depan Pangan) membahas tanggung jawab etis konsumen dalam sistem pangan global. Parasecoli mendorong pembaca untuk menjadi “konsumen yang reflektif” yang menyadari dampak politik dan lingkungan dari pilihan makanan mereka. “Setiap kali kita makan, kita memilih dunia seperti apa yang kita inginkan,” tulisnya. Cendekiawan Muslim Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mizan menekankan, “Makanan yang halal bukan hanya yang secara formal halal, tetapi yang diperoleh dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan sosial.”
Buku ini mendapat apresiasi dari Food Studies Scholar Prof. Krishnendu Ray sebagai “peta intelektual yang indispensable untuk memahami geopolitis pangan abad ke-21.” Namun, kritikus seperti Dr. Marion Nestle menilai Parasecoli terlalu fokus pada wacana dan kurang memberikan solusi praktis. Untuk Indonesia, buku ini menawarkan kerangka untuk menganalisis kebijakan pangan nasional, dari ketahanan pangan hingga promosi kuliner, dengan kesadaran bahwa setiap keputusan tentang makanan adalah keputusan politik.
Environment and Sustainability
Parasecoli membahas hubungan kompleks antara sistem pangan global dengan lingkungan, mengeksplorasi bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi makanan berdampak pada keberlanjutan ekologis. Ia menegaskan bahwa “krisis pangan modern adalah cerminan dari krisis ekologis yang lebih luas” (hlm. 89), menekankan bahwa masalah kelaparan, obesitas, dan kerusakan lingkungan saling terkait dalam sistem yang sama.
Parasecoli memulai analisisnya dengan menelusuri jejak ekologis sistem pangan industrial. Ia menunjukkan bagaimana agricultural intensification sejak Revolusi Hijau justru menciptakan paradoks: meningkatkan produksi pangan sambil merusak fondasi ekologis yang mendukung-nya. Data yang disajikan mengungkapkan bahwa pertanian modern menyumbang 30% emisi gas rumah kaca global dan menjadi penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati (hlm. 92-93). Dalam konteks Indonesia, temuan ini menjelaskan mengapa konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan lahan pertanian tidak hanya mengancam biodiversitas tetapi juga memperparah perubahan iklim.
Bagian kedua bab ini mengkritik “mitos efisiensi” dalam sistem pangan global. Parasecoli mem-bongkar bagaimana rantai pasok pangan yang panjang dan kompleks justru menciptakan in-efisiensi ekologis melalui food miles yang berlebihan dan packaging yang tidak berkelanjutan. Ia mencatat bahwa “makanan rata-rata menempuh 1.500 mil sebelum sampai di piring konsumen” (hlm. 98), sebuah paradoks di era yang mengklaim peduli keberlanjutan. Untuk Indonesia, ini relevan dengan ketergantungan pada impor pangan yang tidak hanya me-ngancam ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan jejak karbon.
Bab ini kemudian membahas konsep “keadilan lingkungan” (environmental justice) dalam sistem pangan. Parasecoli menunjukkan bagaimana dampak negatif lingkungan paling berat ditanggung oleh komunitas miskin dan marginal, sementara manfaat ekonomi dinikmati oleh korporasi agribisnis global. “Polusi dari pupuk kimia dan pestisida paling banyak mencemari air minum komunitas pedesaan miskin” (hlm. 105). Di Indonesia, ini terlihat dalam kasus pencemaran sungai oleh limbah perkebunan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat lokal.
Parasecoli juga menganalisis gerakan “food sustainability” yang muncul sebagai respons terhadap krisis ekologis. Ia membedakan antara pendekatan “eco-modernization” yang berusaha membuat sistem existing lebih hijau, dengan “food sovereignty” yang menuntut transformasi radikal sistem pangan. “Sustainability bukan tentang membuat kapitalisme hijau, tetapi tentang membangun sistem pangan yang benar-benar adil dan regeneratif” (hlm. 112). Gerakan petani Indonesia seperti Serikat Petani Indonesia (SPI) mengadvokasi pendekatan kedua melalui konsep kedaulatan pangan.
Bagian penting bab ini membahas “etika konsumsi” dan tanggung jawab konsumen. Parasecoli memperingatkan terhadap “ethical consumerism” yang bisa terjebak dalam greenwashing, sambil mengakui bahwa pilihan konsumen memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan. “Setiap kali kita makan, kita memilih jenis pertanian seperti apa yang kita dukung” (hlm. 118). Filsuf Indonesia, Rocky Gerung, pernah menyatakan bahwa “konsumsi adalah tindakan politik,” yang sejalan dengan argumen Parasecoli.
Bab ditutup dengan analisis tentang “masa depan pangan berkelanjutan” yang mengeksplorasi inovasi seperti pertanian perkotaan, protein alternatif, dan agroekologi. Parasecoli bersikap kritis terhadap solusi teknokratis yang mengabaikan dimensi keadilan sosial. “Teknologi bisa menjadi alat untuk keberlanjutan, tetapi hanya jika diarahkan oleh nilai-nilai keadilan dan kesetaraan”(hlm. 125). Cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. Din Syamsuddin, menekankan bahwa “kelestarian lingkungan adalah bagian dari maqasid syariah,” yang sejalan dengan pesan inti bab ini.
Bab 4 ini meninggalkan pembaca dengan pemahaman bahwa transformasi sistem pangan menuju keberlanjutan bukan hanya soal teknologi, tetapi terutama tentang politik, keadilan, dan etika—sebuah pesan yang sangat relevan untuk Indonesia yang sedang bergulat dengan tantangan ketahanan pangan dan kerusakan lingkungan.
Pada Bab 6: “Hunger and Food Security,” Fabio Parasecoli membuka dengan narasi yang menggugah tentang seorang petani kecil di Sub-Sahara Afrika yang justru mengalami kelaparan di tengah ladangnya sendiri—sebuah paradoks yang mengilustrasikan kompleksitas masalah ketahanan pangan global. Parasecoli menyatakan bahwa “kelaparan di abad ke-21 bukanlah masalah kelangkaan pangan, melainkan masalah akses dan distribusi yang timpang” (hlm. 147). Bab ini secara sistematis membongkar mitos bahwa solusi kelaparan terletak semata pada peningkatan produksi pangan.
Bagian pertama bab ini menganalisis dimensi kelaparan yang sering terabaikan: “kelaparan tersembunyi” (hidden hunger) akibat defisiensi mikronutrien. Parasecoli menunjukkan bahwa sekitar dua miliar orang menderita kekurangan vitamin dan mineral esensial, bahkan di negara-negara dengan ketersediaan kalori yang memadai (hlm. 150-152). Di Indonesia, masalah ini tercermin dalam tingginya prevalensi stunting yang mencapai 24,4% menurut Riskesdas 2018, yang tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan kalori tetapi juga kualitas gizi yang buruk.
Parasecoli kemudian mengkritik konsep “ketahanan pangan” (food security) yang dominan, yang terlalu menekankan ketersediaan pangan di tingkat nasional tanpa mempertimbangkan akses individu dan rumah tangga. “Sebuah negara dapat mencapai ketahanan pangan secara agregat sementara warganya masih mengalami kelaparan” (hlm. 155). Analisis ini sangat relevan untuk Indonesia, di mana swasembada beras di tingkat nasional tidak serta-merta menjamin akses pangan yang memadai bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan.
Bab ini secara khusus membahas “feminisasi kelaparan”—fakta bahwa perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional terkena dampak kerawanan pangan. Parasecoli menunjukkan bagaimana norma sosial dan struktur patriarki membatasi akses perempuan terhadap sumber daya produktif, pendidikan, dan pengambilan keputusan. “Perempuan menghasilkan 60-80% makanan di negara berkembang, namun memiliki akses terbatas terhadap tanah dan kredit” (hlm. 161). Di Indonesia, hal ini terlihat dalam ketimpangan kepemilikan lahan antara laki-laki dan perempuan, serta beban ganda yang harus ditanggung perempuan dalam memastikan kecukupan pangan keluarga.
Parasecoli bukanlah akademikus yang hanya berdiam di menara gading. Ia aktif terlibat dalam diskusi publik dan media. Ia sering kali menjadi narasumber untuk media internasional seperti The New York Times, The Guardian, BBC, dan NPR, di mana ia menjelaskan fenomena makanan kontemporer—dari tren makanan jalanan hingga dampak geopolitik pada rantai pasok—dengan otoritas dan kejelasan. Ia juga penulis artikel yang produktif untuk berbagai publikasi, menghubungkan penelitian mutakhir dengan isu-isu yang sedang hangat diper-bincangkan. Keterlibatannya dalam konferensi internasional dan proyek-proyek kebijak-an menunjukkan komitmennya untuk menggunakan pengetahuan tentang makanan sebagai alat perubahan sosial.
Parasecoli menganalisis peran “financialization of food” dalam memperburuk kerawanan pangan. Parasecoli menjelaskan bagaimana spekulasi di pasar komoditas berjangka dapat memicu volatilitas harga pangan yang berdampak buruk bagi konsumen miskin. “Makanan telah menjadi alat spekulasi finansial, terlepas dari fungsinya sebagai kebutuhan dasar manusia” (hlm. 168). Krisis pangan 2008 disebut sebagai contoh bagaimana spekulasi di pasar keuangan global dapat memicu kerusuhan pangan di berbagai negara. Parasecoli juga mem-bedah hubungan antara konflik dan kelaparan, menunjukkan bagaimana kelaparan sering digunakan sebagai senjata perang. “Di dunia modern, lebih banyak orang yang mati karena kelaparan yang disebabkan oleh konflik daripada karena baku tembak” (hlm. 174). Situasi di Papua menjadi contoh bagaimana konflik dan keterbatasan akses dapat menciptakan kerawanan pangan yang akut.
Bab ini menawarkan kritik terhadap rezim bantuan pangan internasional yang sering kali justru memperburuk ketergantungan dan menghancurkan pasar lokal. Parasecoli mencatat bahwa “bantuan pangan darurat diperlukan dalam krisis, tetapi dapat menjadi kontraproduktif jika mengganggu sistem pangan lokal” (hlm. 179). Pengalaman Indonesia dengan impor beras yang sering kali tidak tepat waktu dan mengganggu harga di tingkat petani menjadi ilustrasi dari masalah ini.
Sebagai alternatif, Parasecoli mengadvokasi pendekatan “kedaulatan pangan” (food sovereignty) yang menekankan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri. “Kedaulatan pangan bukan hanya tentang memiliki cukup makanan, tetapi tentang memiliki kendali atas bagaimana makanan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi” (hlm. 185). Gerakan petani Indonesia melalui Aliansi Petani Indonesia telah lama memperjuangkan konsep ini melalui advokasi reforma agraria dan perlindungan terhadap benih lokal.
Aktivis pangan Indonesia, Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, menyata-kan bahwa “kelaparan di Indonesia adalah buah dari kebijakan pangan yang meming-girkan petani kecil dan nelayan tradisional,” yang sejalan dengan analisis Parasecoli. Sementara itu, cendekiawan Muslim Prof. M. Amin Abdullah menekankan bahwa “jaminan atas pangan yang cukup dan bergizi adalah bagian dari maqasid syariah dalam melindungi jiwa (hifzh an-nafs).”
Bab ini ditutup dengan penekanan bahwa solusi kelaparan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi produksi, distribusi, akses, dan keberlanjutan ekologis. “Meng-akhiri kelaparan memerlukan lebih dari sekadar tekno-fiksasi; memerlukan transformasi sistemik menuju keadilan pangan” (hlm. 192)—sebuah pesan yang sangat relevan bagi Indonesia dalam merancang strategi penanganan kerawanan pangan pasca-pandemi.
“Bagaimana kita akan memberi makan 10 miliar manusia pada tahun 2050 tanpa menghancur-kan planet ini?” (hlm. 195), pertanyaan provokatif Parasecoli. Parasecoli menolak narasi simplistik yang mengandalkan solusi teknokratis, dan sebaliknya menawarkan peta jalan multidimensi yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan transformasi sosial-politik.
Ia melemparkan kritik tajam “solusionisme teknologi” (tech-solutionism) yang mendominasi wacana masa depan pangan. Parasecoli mengakui potensi inovasi seperti daging kultur, pertanian presisi, dan pertanian vertikal, namun memperingatkan bahwa “teknologi tanpa keadilan hanya akan memperdalam ketimpangan yang ada” (hlm. 198). Dalam konteks Indonesia, ini relevan dengan euforia terhadap smart farming yang perlu diimbangi dengan perhatian pada akses petani kecil terhadap teknologi tersebut.
Parasecoli kemudian membahas bangkitnya “ekonomi pangan alternatif” yang mencakup gerakan slow food, CSA (Community Supported Agriculture), dan pasar petani. Ia menunjukkan bagaimana model-model ini tidak hanya menawarkan alternatif ekonomi, tetapi juga “membangun kembali hubungan sosial antara produsen dan konsumen” (hlm. 204). Di Indonesia, gerakan seperti Garda Pangan di Surabaya dan berbagai komunitas petani organik menunjukkan potensi model ini, meski masih terbatas skalanya.
Bab ini secara khusus menyoroti pentingnya “pengetahuan pangan tradisional” dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Parasecoli menekankan bahwa “kearifan pangan lokal bukanlah relik masa lalu, melainkan sumber ketahanan untuk masa depan” (hlm. 209). Keanekaragaman pangan lokal Indonesia seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian tradisional menjadi contoh bagaimana biodiversitas dapat menjadi asuransi terhadap krisis pangan global.
Bagian penting bab ini membahas “politik pangan transformatif” yang diperlukan untuk perubahan sistemik. Parasecoli menyerukan “reformasi tata kelola pangan global” yang lebih inklusif dan demokratis, serta penguatan sistem pangan lokal. “Masa depan pangan yang berkelanjutan memerlukan demokratisasi sistem pangan dari tingkat lokal hingga global” (hlm. 215). Untuk Indonesia, ini berarti perluasan ruang partisipasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan pangan nasional.
Catatan Akhir: Pilihan Kolektif atas Pangan
Sebagai penulis, Parasecoli dikenal karena kemampuannya menjembatani wawasan akademis yang mendalam dengan keterbacaan bagi khalayak luas. Bukunya yang sangat terkenal, “Food” (2019), diterbitkan oleh MIT Press dalam seri The MIT Press Essential Knowledge Series. Buku ini bukan buku masak atau sejarah makanan biasa; ia adalah “panduan kritis” yang padat dan brilian. Dalam kurang dari 200 halaman, Parasecoli membawa pembaca berkelana melalui “politics of food“, menelusuri bagaimana apa yang kita makan dibentuk oleh—dan sekaligus membentuk—kebijakan pertanian, pasar global, budaya pop, isu gender, dan inovasi teknologi seperti makanan berkelanjutan (sustainable food) dan daging hasil kultur (cultured meat). Gaya tulisnya jelas, analitis, dan sering kali provokatif, mendorong pembaca untuk mempertanyakan asumsi mereka tentang setiap suapan.
Selain “Food“, Parasecoli telah menulis dan menyunting banyak buku penting lainnya, seperti “Al Dente: A History of Food in Italy” (yang menawarkan narasi sejarah yang kaya dan kritis, jauh dari romantisme kuliner semata), “Knowing Where It Comes From: Labeling Traditional Foods to Compete in a Global Market“, dan “Feasting Our Eyes: Food Films and Cultural Identity in the United States“. Karyanya menjadi rujukan wajib dalam bidang Food Studies yang sedang berkembang pesat.
Parasecoli mendedikasikan bagian khusus untuk membahas “pendidikan pangan” sebagai kunci transformasi. Ia mengusulkan integrasi literasi pangan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal, mencakup aspek gizi, keberlanjutan, dan politik pangan. “Setiap orang harus menjadi food citizen, bukan sekadar food consumer” (hlm. 221). Inisiatif seperti program Edukasi Pangan di sekolah-sekolah Indonesia dapat diperluas untuk mencakup dimensi politik dan ekologi pangan.
Bab ini juga mengeksplorasi masa depan “keadilan pangan global” dalam konteks perubahan iklim. Parasecoli menekankan bahwa “negara-negara kaya yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan iklim harus memimpin dalam mendanai adaptasi sistem pangan di negara berkembang” (hlm. 227). Bagi Indonesia, ini berarti memperkuat posisi dalam negosiasi iklim internasional untuk memastikan keadilan iklim dalam sistem pangan global.
Akhirnya, Parasecoli menawarkan visi yang menggabungkan realisme dan optimisme: “Masa depan pangan tidak ditakdirkan; ia akan dibentuk oleh pilihan kolektif kita hari ini” (hlm. 233). Ia menutup dengan seruan untuk “gerakan pangan yang inklusif dan visioner” yang melampaui sektoralisme dan mampu menghubungkan isu pangan dengan keadilan sosial, keberlanjutan
ekologis, dan demokrasi.
Pemikir Indonesia, Rocky Gerung, pernah menyatakan bahwa “masa depan Indonesia ditentukan oleh kemampuannya mengelola pangan sebagai hak, bukan komoditas,” yang sejalan dengan pesan akhir Parasecoli. Sementara cendekiawan Muslim Prof. Komaruddin Hidayat menekankan bahwa “jaminan pangan adalah amanah ketuhanan yang harus diwujudkan dalam tata kelola yang berkeadilan.”
Pada intinya, Fabio Parasecoli adalah seorang dekonstruktor dan kontekstualisator. Ia dengan terampil mengurai (deconstruct) sepiring makanan untuk mengungkap lapisan-lapisan makna yang tersembunyi: dari ketidaksetaraan yang tersirat dalam sistem pangan global hingga pertarungan identitas dalam iklan makanan. Sekaligus, ia menempatkan (contextualize) makanan ke dalam alur sejarah dan jaringan sosialnya yang lebih luas, menunjukkan bagaimana ia terkait erat dengan migrasi, kolonialisme, kapitalisme, dan perubahan iklim.
Dengan demikian, Parasecoli telah membantu mendefinisikan “Food Studies” sebagai bidang studi yang serius, kritis, dan relevan. Ia mengajak kita untuk melihat bahwa makanan adalah teks budaya yang paling mendasar—satu yang ditulis oleh kekuatan global, tetapi juga dibaca, dialami, dan diubah oleh setiap individu di meja makan mereka. Melalui tulisan dan pengajaran-nya, ia memberikan peta intelektual yang sangat dibutuhkan untuk menavigasi lanskap pangan kita yang kompleks dan seringkali kontradiktif di abad ke-21.
Bab penutup ini meninggalkan pembaca dengan pemahaman bahwa masa depan pangan bukanlah takdir, melainkan pilihan politik dan etis yang harus kita buat bersama—sebuah pesan yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang berada di persimpangan jalan antara melanjutkan model industrial atau beralih ke sistem pangan yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.
Bogor, 9 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi:
Parasecoli, F. (2019). Food. The MIT Press.
Kutipan Tambahan Relevan:
- “Kuliner adalah bahasa yang paling universal dan paling personal sekaligus” – Chef Indonesia William Wongso
- “Makanan terbaik adalah yang tidak hanya memuaskan lidah, tetapi juga memuliakan kehidupan” – Prinsip gastronomi Indonesia
- “Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan” (QS. Al-A’raf: 31)
- “Tell me what you eat, and I will tell you who you are” – Jean Anthelme Brillat-Savarin
- “Food is not just fuel, it’s information” – Dr. Mark Hyman