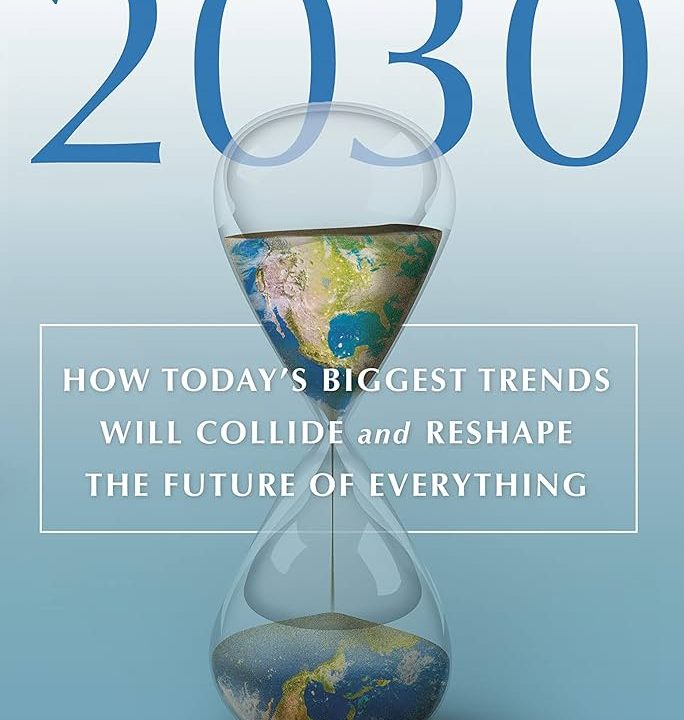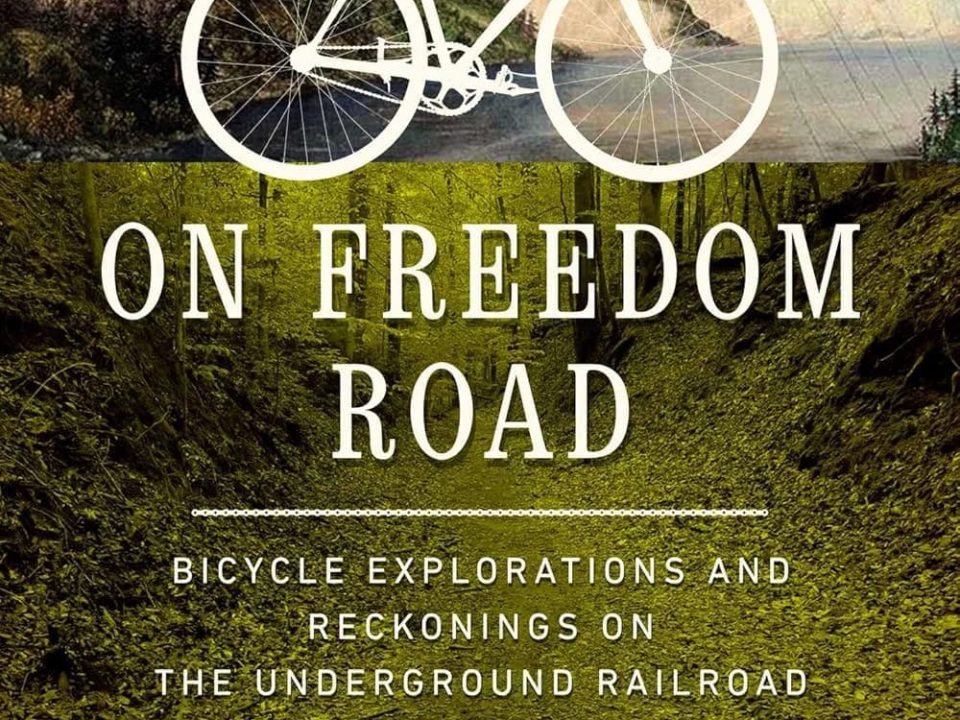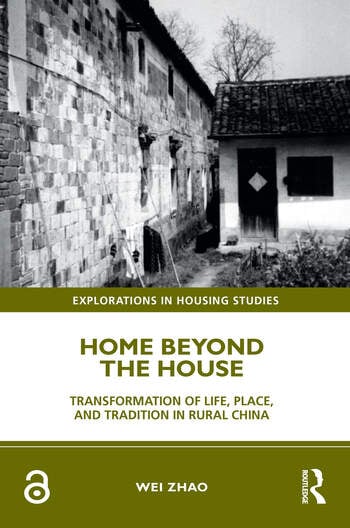Rubarubu #88
Tomorrows vs Yesterdays:
Sebuah Percakapan yang Menentukan
Pada suatu panel di Konferensi DLD 2020, seorang venture capitalist dengan antusias memproklamirkan, “Masa depan bukan lagi milik negara-bangsa, tetapi milik perusahaan teknologi yang paling inovatif!” Di sebelahnya, seorang sejarawan teknologi dengan tenang membalas, “Tapi jika masa depan hanya didefinisikan oleh efisiensi algoritma dan ekstraksi data, lalu di mana ruang untuk kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi kita yang rapuh?” Ketegangan produktif inilah yang menjadi denyut nadi buku “Tomorrows vs Yesterdays: Conversations in Defense of the Future,”yang diedit oleh Andrew Keen.
Buku ini bukan sebuah manifesto tunggal, melainkan sebuah simposium—sebuah pertukaran gagasan yang hidup dan sering kali bertolak belakang antara para pemikir terkemuka dunia tentang satu pertanyaan mendesak: Bagaimana kita membela masa depan yang manusiawi, inklusif, dan demokratis di era ketika teknologi digital sering kali mengancam untuk melanggengkan ketimpangan masa lalu? Seperti yang ditulis Keen dalam pengantarnya, esensi dari pertahanan ini terletak pada percakapan itu sendiri: “The future is not a algorithmically predetermined destination but a conversation—a noisy, contentious, and profoundly human argument about what we want to become” (Keen, 2020, p. xv).
Perdebatan yang Membentuk Hari Esok
Diedit dari seri percakapan “Keen On” di konferensi DLD, buku ini menghadirkan benturan perspektif antara para optimis teknologi, skeptis budaya, peretas etis, dan pemikir politik. Strukturnya yang dialogis memungkinkan pembaca untuk menyelami kompleksitas isu tanpa tuntutan jawaban yang mudah.
Buku Tomorrows vs Yesterdays: Conversations in Defense of the Future. DLD Atlantic Books (2020) ini mengelilingi beberapa medan pertempuran intelektual utama. Topik-topik yang menjadi perbincangan adalah tentang:
Masa Depan Demokrasi vs. Teknokratik Oligarki: Percakapan yang paling berapi-api sering kali membahas ancaman terhadap demokrasi liberal. Yuval Noah Harari memperingatkan tentang bahaya “dataisme”—di mana otoritas berpindah dari manusia yang berperasaan ke sistem pemrosesan data yang tak berperasaan. Dia berargumen bahwa jika kita tidak hati-hati, kita berisiko menciptakan “digital dictatorships” yang jauh lebih efektif daripada rezim totaliter abad ke-20 (Harari, dalam Keen, 2020). Sementara itu, figur seperti Eric Schmidt (mantan CEO Google) mungkin membela peran teknologi dalam memberdayakan warga dan meningkatkan transparansi. Buku ini mempertanyakan: apakah platform seperti media sosial adalah ruang publik baru atau mesin untuk perpecahan dan manipulasi? Sejarahwan Niall Ferguson memberikan konteks dengan membandingkan disintegrasi digital saat ini dengan zaman reformasi, di mana penemuan mesin cetak memicu perpecahan agama dan perang—sebuah peringatan bahwa teknologi disruptif selalu menjadi kekuatan politis yang tidak stabil (Ferguson, dalam Keen, 2020).
Kebangkitan (dan Pertahanan) Humanisme: Di tengah narasi tentang AI yang maha kuasa dan pascamanusia, banyak kontributor yang membela humanisme yang diperbarui. Michele G. Sanders, dalam wawancara tentang masa depan kerja, mungkin menekankan bahwa otomasi tidak boleh dilihat sebagai takdir, tetapi sebagai pilihan politik. Tantangannya adalah me-rancang kebijakan—seperti pajak robot atau jaminan pendapatan dasar—yang memastikan kemakmuran dibagikan secara luas. Penyair dan filsuf Muslim Prof. Dr. Nurdeng Deuraseh dari Malaysia, dalam karya-karyanya tentang etika teknologi Islam, menawarkan perspektif paralel yang relevan. Ia menekankan konsep “maslahah” (kemanfaatan umum) dan “mizan” (kese-imbangan), menegaskan bahwa inovasi apa pun harus diuji bukan pada kecanggihannya, tetapi pada kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara holistik dan adil, menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual (Deuraseh, 2017). Ini adalah seruan untuk memasukkan etika ke dalam desain teknologi, bukan sebagai renungan akhir.
Nostalgia vs. Imajinasi Radikal: Judul buku ini, “Tomorrows vs Yesterdays,” menangkap ketegangan sentral. Beberapa pembicara memperingatkan terhadap nostalgia yang beracun—keinginan untuk kembali ke masa lalu yang sering kali diromantisasi dan tidak inklusif. Yang lain, seperti penulis seperti Douglas Coupland, mungkin mengingatkan kita bahwa masa depan yang dibayangkan pada abad ke-20 (perjalanan antariksa, kemakmuran universal) telah menyusut menjadi peningkatan yang kecil dan personal pada gawai kita. Tantangannya, kemudian, adalah “merebut kembali imajinasi kita tentang masa depan.” Seniman seperti Olafur Eliasson, yang karyanya membahas iklim dan persepsi, mungkin berargumen bahwa seni memiliki peran penting dalam membuat alternatif masa depan yang dapat dirasakan dan diharapkan, bukan hanya dihitung dan diprediksi.
Contoh Konkret dalam Buku: Percakapan mungkin menyentuh kasus nyata seperti:
- Krisis Privasi & Facebook: Diskusi tentang Cambridge Analytica akan menjadi studi kasus tentang bagaimana arsitektur perhatian yang dieksploitasi dapat menggerogoti fondasi demokrasi.
- Mobilitas Otonom: Debat tentang mobil self-driving akan mengungkap pertarungan antara visi efisiensi bebas kemacetan dan ancaman terhadap jutaan pekerjaan pengemudi, serta pertanyaan etis yang dalam tentang pengambilan keputusan algoritmik dalam kehidupan dan kematian.
- Kesenjangan Digital: Pandemi COVID-19, yang terjadi sekitar waktu publikasi, akan disebut sebagai amplifier ketidaksetaraan yang dramatis, memperlihatkan bagaimana akses ke teknologi digital menjadi penentu peluang, pendidikan, dan bahkan kesehatan.
Panggung untuk Percakapan yang Penting
Buku “Tomorrows vs Yesterdays” dibuka bukan dengan pernyataan kebenaran tunggal, melainkan dengan sebuah undangan—undangan untuk memasuki sebuah ruang percakapan di mana masa depan itu sendiri sedang diperdebatkan, dipertahankan, dan dibayangkan ulang. Bagian pembuka ini berfungsi sebagai panggung yang mempersiapkan pembaca untuk simposium gagasan yang akan menyusul. Dalam Kata Pengantar buku ini, Steffi Czerny, pendiri konferensi DLD (Digital-Life-Design), mengajak kita untuk memahami konteks kelahiran buku ini. Czerny mungkin menggambarkan DLD bukan sekadar pertemuan elite teknologi, tetapi sebagai “laboratorium hidup” atau “mikrokosmos” dari percakapan global tentang dampak digital terhadap kehidupan manusia. Sebagai tuan rumah yang telah menyaksikan evolusi wacana digital dari euforia awal tahun 2000-an hingga kecemasan mendalam tahun 2010-an, ia memberikan kredibilitas pada kumpulan dialog ini.
DLD merupakan sebuah konferensi media dan jaringan global elit yang berfokus pada inovasi digital, teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, dan dampaknya terhadap masyarakat. DLD sering digambarkan sebagai “Davos-nya dunia digital” atau “konferensi untuk para pembangun masa depan”, karena menyatukan para pemimpin dari berbagai bidang—teknologi, bisnis, seni, politik, akademisi, dan media—untuk berdiskusi tentang tren yang akan membentuk dunia esok.
Didirikan pada tahun 2005 di München, Jerman, oleh Steffi Czerny dan Yossi Vardi (entrepreneur internet Israel). DLD dimiliki dan diselenggarakan oleh Hubert Burda Media, sebuah konglomerat media dan penerbitan Jerman yang kuat. Ini memberi DLD perspektif Eropa yang kental dan jaringan yang dalam di persimpangan media lama dan baru. Steffi Czerny tetap menjadi direktur dan kekuatan kreatif di balik DLD, membentuk kurasi dan narasinya.
Format dan Atmosfer DLD berbeda dengan konferensi teknologi biasa. DLD terkenal karena kurasi yang sangat selektif, desain yang estetis, dan atmosfer yang intim meski dihadiri oleh orang-orang sangat berpengaruh. Lebih menekankan pada percakapan, wawasan strategis, dan jaringan kualitas tinggidaripada pengumuman produk atau sesi teknis “how-to”. Sesi-sesinya sering kali berbentuk diskusi panel, wawancara mendalam (seperti yang kemudian dibukukan dalam Tomorrows vs Yesterdays), dan presentasi singkat yang provokatif. Jaringan peserta (The “DLD Circle”) sangat global tetapi dengan simpul kuat di Eropa, AS, dan Israel.
Tema utamanya adalah “Digital-Life-Design”—menjelajahi bagaimana teknologi digital meresap ke setiap aspek kehidupan manusia: cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, berkreasi, dan memerintah. Cakupannya luas dan antardisiplin, meliputi: AI & Masa Depan Pekerjaan, Kesehatan Digital, Keberlanjutan & Teknologi Hijau, Masa Depan Kota, Keamanan Siber, Seni & Kreativitas, Etika Teknologi, dan Tata Kelola Digital.
DLD secara signifikan berpengaruh sebagai pembentuk wacana. DLD adalah tempat di mana ide-ide besar tentang masa depan pertama kali diujikan di depan audiens yang berpengaruh. Ini adalah barometer untuk tren pemikiran di kalangan elite global. Jaringan kekuasaan konferensi ini dengan memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi yang sering melahirkan investasi, kemitraan, dan kebijakan. Ini adalah ruang di mana modal, ide, dan pengaruh bertemu. Perspektif Eropa: Sebagai tandingan terhadap narasi yang didominasi Silicon Valley, DLD sering kali membawa suara kritis Eropa yang lebih peduli dengan regulasi, privasi (seperti GDPR), tanggung jawab sosial, dan humanisme digital. Platform untuk Buku dan Gagasan: Seperti yang terlihat dalam Tomorrows vs Yesterdays, DLD berfungsi sebagai inkubator dan platform peluncuran untuk buku-buku dan gagasan penting yang membingkai debat publik.
Czerny menekankan bahwa di era “kebisingan digital” dan algoritma yang mengurung kita dalam ruang gema (echo chambers), nilai dari sebuah ruang fisik untuk dialog yang terbuka, kontradiktif, dan penuh rasa hormat menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Kata Pengantar ini menetapkan nada bahwa buku ini adalah upaya untuk menangkap kilatan-kilatan kebijaksanaan dari ruang percakapan tersebut dan membekukannya dalam bentuk cetak, sehingga percakap-an itu dapat bergaum lebih luas, melampaui ruang konferensi di Munich atau New York. Ia menegaskan bahwa pertanyaan “bagaimana kita ingin hidup?” di abad digital adalah pertanya-an kolektif, dan DLD—serta oleh perpanjangan, buku ini—berusaha menjadi katalisator untuk menjawabnya.
Pendahuluan yang ditulis oleh editor, Andrew Keen, adalah esai yang memetakan medan intelektual dengan jelas. Keen, yang dikenal dengan kritik tajamnya terhadap “cult of the amateur” dan dampak sosial internet, segera membingkai dilema sentral. Dia melukiskan dua gaya tarik yang kuat dan berbahaya yang mengancam akan merobek masa depan kita:
- “Yesterday’s Pull” (Tarik-Menarik Masa Lalu): Ini adalah kekuatan nostalgia reaksioner yang dimanifestasikan dalam kebangkitan populisme nasionalis, keinginan untuk membangun kembali “tembok” (baik fisik maupun digital), dan romantisasi atas suatu masa lalu yang homogen dan sering kali fiktif. Ini adalah pelarian dari kompleksitas modernitas.
- “Tomorrow’s Default” (Kelokan Masa Depan yang Tanpa Pikir): Ini adalah kekuatan determinisme teknologi yang tak terkritik—keyakinan bahwa jalur kita sudah ditetapkan oleh logika pasar dan inovasi teknologi Silicon Valley. Ini adalah masa depan yang pasif, di mana kita hanyut menuju dunia yang ditentukan oleh efisiensi algoritma dan nilai pemegang saham, sering kali dengan mengorbankan humanisme, privasi, dan demokrasi.
Di antara dua jurang inilah, Keen berargumen, kita harus membangun jalan ketiga: sebuah “pertahanan masa depan” yang aktif dan sadar. Pertahanan ini tidak otomatis. Ia harus di-perjuangkan melalui “konversasi”—konflik dan kolaborasi gagasan yang mendalam. Keen mungkin mengutip percakapan tertentu dari buku sebagai contoh, menunjukkan bagaimana seorang kapitalis ventura dan seorang filsuf mungkin bentrok, namun dari bentrokan itulah pemahaman yang lebih bernuansa muncul.
Pendahuluan ini juga menjelaskan metodologi buku: ini bukan risalah akademis, melainkan catatan dari garis depan pemikiran, dengan semua spontanitas, ketidaklengkapan, dan percikan wawasan yang datang dari dialog langsung. Keen menempatkan dirinya sebagai moderator yang terlibat, yang percaya bahwa dalam pertukaran inilah imajinasi kita tentang hari esok bisa diperbaiki dan diperkaya.
Sebuah Panggilan untuk Kewarganegaraan Digital yang Kritis
Secara bersama-sama, Kata Pengantar dan Pendahuluan menyiapkan panggung untuk drama intelektual yang akan terjadi. Czerny memberikan konteks ruang (dimana percakapan ini terjadi), sementara Keen memberikan konteks ideologis (mengapa percakapan ini penting).
Mereka menyampaikan pesan bersama: Masa depan bukanlah destinasi yang diberikan kepada kita oleh para jenius di Silicon Valley atau oleh para demagog yang merindukan zaman keemas-an. Masa depan adalah sebuah konstruksi, sebuah pilihan kolektif. Dan pilihan itu hanya bisa dibuat secara bermakna jika kita terlibat dalam pertukaran gagasan yang menantang, men-dengarkan pihak yang tidak kita setujui, dan dengan berani mempertanyakan narasi-narasi yang dominan—baik yang menjual nostalgia maupun yang menjual kemajuan tanpa jiwa.
Dengan demikian, pembuka buku ini adalah sebuah manifesto untuk dialog. Ia mengajak kita, para pembaca, untuk tidak menjadi penonton pasif, tetapi untuk bergabung dalam percakapan, untuk mengambil sikap, dan akhirnya, untuk ikut serta dalam aksi kolektif “membela masa depan” yang layak untuk dihuni semua manusia. Seperti yang mungkin dirujuk Keen dari pe-mikiran Socrates, dialog yang jujur adalah fondasi dari masyarakat yang sehat—dan di dunia yang terhubung digital, kesehatan masyarakat itu kini berskala global.
Bagian pertama buku ini, berjudul “The Crisis”, tidak bertele-tele. Ia langsung membawa kita ke garis depan pertempuran yang menentukan zaman kita. Ini bukan krisis finansial atau pandemi biasa, melainkan krisis tata kelola, kebenaran, dan kemanusiaan itu sendiri yang dipercepat dan diperparah oleh teknologi digital. Melalui empat percakapan dengan pemikir dan pelaku kunci, Andrew Keen memetakan sebuah medan perang multidimensi di mana demokrasi, jurnalisme, dan otonomi individu berada dalam keadaan terkepung.
Shoshana Zuboff: Kuasa Instrumentarian dan Pencurian Masa Depan
Percakapan dengan Shoshana Zuboff, sang arsitek konsep “Surveillance Capitalism”, mem-berikan kerangka teoritis yang mengerikan untuk memahami krisis ini. Zuboff meng-gambarkan bagaimana kapitalisme pengawasan telah menciptakan sebuah bentuk kekuasaan baru: “instrumentarian power”. Ini bukanlah pengawasan Orwellian demi kontrol politik langsung, melainkan logika ekonomi yang lebih halus dan total. Perusahaan seperti Google dan Facebook, menurutnya, telah melakukan “pencurian pengalaman manusia” dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data kita diekstraksi, dianalisis, dan digunakan untuk memprediksi dan akhirnya memengaruhi perilaku kita, mengubahnya menjadi produk yang bisa diperdagangkan di “pasar perilaku masa depan”.
Bagi Zuboff, ini adalah krisis eksistensial karena melibatkan “pengambilalihan kedaulatan manusia”. Ketika keputusan tentang apa yang kita lihat, pikirkan, dan lakukan semakin diserahkan kepada mesin prediktif yang dioptimalkan untuk keterlibatan dan konversi (misalnya, klik atau pembelian), kita kehilangan hakikat untuk menjadi subjek otonom yang menentukan nasib sendiri. Masa depan, dalam visinya, bukan lagi waktu yang terbuka untuk kita ciptakan, tetapi sebuah probabilitas yang telah diprediksi dan dimanipulasi untuk keuntungan pihak lain. Krisis ini adalah kematian privasi bukan sebagai kesopanan, tetapi sebagai fondasi kebebasan.
John Borthwick: Pragmatisme di Tengah Badai
Berbeda dengan analisis struktural Zuboff, percakapan dengan John Borthwick, seorang venture capitalist dan pendiri Betaworks, mewakili suara dari dalam mesin itu sendiri—suara yang menyadari masalah tetapi mencari jalan keluar yang pragmatis. Borthwick tidak menyangkal kekuatan disruptif yang dijelaskan Zuboff, tetapi dia mungkin melihatnya sebagai “efek samping yang berbahaya dari sebuah paradigma yang pada dasarnya memberdayakan”.
Dia mungkin berargumen bahwa krisis saat ini juga merupakan momen peluang besar. Sebagai seorang investor, dia melihat potensi dalam teknologi “ethical by design” dan platform yang memprioritaskan kedaulatan data pengguna. Percakapannya dengan Keen kemungkinan berpusat pada pertanyaan: Bisakah kapitalisme ventura, yang mendanai banyak raksasa pengawasan ini, juga mendanai penyelamatannya? Borthwick mewakili pandangan bahwa solusi terhadap ekses teknologi akan datang dari inovasi teknologi lebih lanjut—dari Web3, protokol terdesentralisasi, dan model bisnis baru yang mengembalikan kontrol kepada pengguna. Bagi dia, krisis adalah panggilan untuk berinovasi, bukan untuk mundur.
Maria Ressa: Pertempuran Nyata untuk Fakta dan Hidup
Jika Zuboff memberikan teorinya dan Borthwick membahas kemungkinan teknis, maka Maria Ressa, jurnalis pemenang Nobel Perdamaian dari Filipina, membawa kita ke dalam krisis dengan darah dan air mata. Percakapannya adalah kesaksian langsung tentang bagaimana alat-alat yang dibahas oleh Zuboff—platform media sosial dan mesin disinformasi—ditujukan untuk melumpuhkan demokrasi dan membungkam kebenaran.
Ressa menggambarkan dengan gamblang bagaimana pemerintah otoriter seperti di bawah Rodrigo Duterte menggunakan Facebook sebagai “senjata pemusnah massal” untuk menyebarkan propaganda, mengobarkan kebencian, dan menyerang jurnalis seperti dirinya. Bagi Ressa, krisis ini sangat konkret: ini adalah krisis “kematian fakta” yang mengarah pada kekerasan nyata dan pembunuhan. Dia menekankan bahwa algoritma yang dioptimalkan untuk kemarahan dan kebohongan telah “meracuni ruang publik” secara global. Perlawanannya bukan hanya filosofis, tetapi merupakan pertaruhan nyata untuk bertahan hidup.
Percakapannya menjadi seruan mendesak untuk pertanggungjawaban platform dan perlindungan bagi mereka yang berada di garis depan mempertahankan demokrasi di dunia digital.
Rana Foroohar: Kemandirian dan Kedaulatan Ekonomi Nasional
Percakapan dengan Rana Foroohar, kolumnis ekonomi Financial Times, melengkapi segitiga krisis ini dengan menambahkan dimensi geopolitik dan ekonomi-makro. Foroohar menganalisis bagaimana dominasi monopoli teknologi AS (seperti Google, Amazon, Facebook, Apple) telah menciptakan ketergantungan global sekaligus memicu reaksi balik. Dia berbicara tentang “financialization” dan bagaimana ekosistem teknologi besar telah memusatkan kekuasaan ekonomi dengan cara yang mencekik inovasi sejati dan memperburuk ketimpangan.
Dia mungkin mengidentifikasi krisis sebagai “krisis kedaulatan”. Negara-negara di Eropa dan Asia mulai menyadari bahwa ketergantungan pada infrastruktur digital dan cloud asing adalah risiko keamanan nasional. Ini memicu gerakan menuju “digital sovereignty” dan “techno-nationalism”, seperti peraturan GDPR di Eropa atau upaya Tiongkok menciptakan ekosistem teknologinya sendiri. Bagi Foroohar, pertahanan masa depan mungkin memerlukan rekalibrasi hubungan antara negara dan pasar, dengan intervensi pemerintah yang lebih kuat untuk memecah monopoli, melindungi data warga, dan memastikan bahwa keuntungan teknologi dibagikan secara lebih luas dalam masyarakat.
Keempat percakapan ini, ketika dirangkai, mengungkapkan krisis yang bukan tunggal, tetapi sebuah sindrom yang saling memperkuat. Zuboff memberikan diagnosa mendalam tentang penyakitnya: logika ekonomi yang mengubah pengalaman manusia menjadi komoditas. Ressa menunjukkan gejala paling akut dan mematikan dari penyakit itu: erosi demokrasi dan kebenaran. Foroohar menganalisis dampak sistemiknya pada kedaulatan negara dan struktur ekonomi global. Sementara itu, Borthwick mewakili salah satu aliran pemikiran tentang pengobatannya: inovasi yang dikoreksi dari dalam sistem kapitalis teknologi itu sendiri.
Mereka bersama-sama menggambarkan sebuah dunia di mana pertempuran untuk masa depan sedang berlangsung di tiga arena sekaligus: di tingkat individu (otonomi vs. modifikasi perilaku), di tingkat masyarakat (demokrasi vs. otoritarianisme digital), dan di tingkat global (kedaulatan vs. dominasi platform global). Bagian “The Crisis” ini dengan efektif membangunkan pembaca: pertahanan masa depan bukanlah latihan akademis; itu adalah kebutuhan yang mendesak dan multidimensional, yang membutuhkan pemahaman dari sudut ekonomi, teknologi, jurnalisme, dan geopolitik sekaligus.
Kedaulatan, Perhatian, dan Pemberontakan
Setelah memetakan lanskap krisis yang suram di Bagian 1, buku ini bergerak ke tahap refleksi dan reaksi. Bagian 2, “Waking Up From Utopia”, mengeksplorasi momen kesadaran kolektif—saat ilusi tentang internet sebagai ruang yang secara inheren bebas, egaliter, dan emansipatoris akhirnya pudar. Melalui percakapan dengan lima pemikir yang masing-masing memiliki hubungan intim (dan sering kali sakit hati) dengan revolusi digital, Andrew Keen menyelidiki kebangkitan dari mimpi itu dan upaya-upaya awal untuk menemukan jalan yang lebih bijaksana.
David Kirkpatrick: Sang Sejarawan yang Menyaksikan Revolusi Menyimpang
Percakapan dengan David Kirkpatrick, penulis The Facebook Effect, berfungsi sebagai kesaksian sejarah dari dalam. Sebagai seorang jurnalis yang mendokumentasikan kebangkitan Facebook sejak dini, Kirkpatrick memiliki perspektif unik tentang bagaimana utopia sosial yang dijanjikan oleh Mark Zuckerberg—”membuat dunia lebih terbuka dan terhubung”—berubah menjadi ladang yang kompleks dan sering kali beracun. Dia mungkin menggambarkan momen-momen kunci di mana insentif bisnis (iklan yang ditargetkan, pertumbuhan pengguna dengan segala cara) mulai mendikte logika platform, mengorbankan koneksi sosial yang bermakna. Percakapannya adalah tentang kekecewaan seorang saksi: bagaimana alat yang dirancang untuk mempersatukan justru menjadi mesin polarisasi yang sempurna, dan bagaimana optimisme awal para pionir bertabrakan dengan realitas yang keras tentang sifat manusia dan dinamika kekuasaan.
Douglas Rushkoff: Sang Humanis yang Menyerukan “Kelompok Tayangan”
Suara Douglas Rushkoff, penulis buku seperti Program or Be Programmed, adalah seruan untuk kewarganegaraan digital yang aktif dan sadar. Sebagai seorang yang awalnya bersemangat tentang potensi liberasi budaya siber, Rushkoff kini menjadi kritik vokal terhadap ekonomi perhatian yang eksploitatif. Percakapannya dengan Keen kemungkinan berpusat pada konsep “mindfulness”di tingkat sistem. Dia menyerukan agar kita “keluar dari layar”—bukan secara harfiah meninggalkan teknologi, tetapi memulihkan jarak kritis dan otonomi kognitif kita. Dia mungkin menganjurkan untuk memikirkan ulang teknologi bukan sebagai sesuatu yang “kita gunakan”, tetapi sebagai lingkungan yang “kita huni”, dan oleh karena itu kita harus mendesainnya dengan nilai-nilai manusia di pusatnya. Bagi Rushkoff, “bangun” berarti menolak peran pasif sebagai useratau data point, dan kembali menjadi human being yang berdaulat di ruang digital.
Eli Pariser: Memetakan Ruang Gema dan Mencari Yang Terlupakan
Eli Pariser, dengan bukunya yang seminal The Filter Bubble, membawa kita ke mekanisme yang membuat kita tertidur dalam mimpi buruk yang dipersonalisasi. Percakapannya melanjutkan proyeknya untuk mengungkap bagaimana algoritma, dengan membius kita dalam “ruang gema” (echo chambers) dan “gelembung filter” (filter bubbles), sebenarnya menghancurkan pengalam-an publik yang bersama. Pariser mengingatkan kita bahwa utopia koneksi telah berubah menjadi distopia fragmentasi, di mana realitas bersama menguap. Namun, sebagai seorang aktivis, dia mungkin juga membahas jalan keluar: upaya untuk mendesain algoritma “pengem-bang wawasan” (serendipity engine) yang justru memperkenalkan kita pada ide-ide yang menantang dan perspektif yang terlupakan, atau membangun platform yang memprioritaskan deliberasi kewargaan di atas keterlibatan emosional. “Bangun,” baginya, adalah tentang menyadari bahwa apa yang tidak kita lihat di linimasa kita sama pentingnya dengan apa yang kita lihat.
Kenneth Cukier: Kebangkitan Data dan Tanggung Jawab Baru
Suara Kenneth Cukier, editor data senior The Economist dan penulis Big Data, memberikan nuansa yang berbeda. Dia mungkin tidak melihat kebangkitan dari utopia, melainkan kebangkitan kepadarealitas baru yang digerakkan oleh data. Percakapannya mengakui kekuatan transformatif dari data besar dan AI, tetapi menekankan bahwa kita kini bangun untuk menyadari beban tanggung jawab yang luar biasa yang menyertainya. Ini adalah tanggung jawab untuk membangun etika, tata kelola, dan sistem akuntabilitas di sekitar teknologi yang pada dasarnya tidak netral. Cukier mungkin berbicara tentang perlunya “literasi data” yang baru, di mana para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan warga biasa memahami logika probabilistik dan bias yang melekat dalam sistem algoritmik. “Bangun” di sini berarti meninggalkan anggapan naif bahwa data adalah “benih minyak” yang obyektif, dan mulai mengelolanya sebagai sumber daya publik yang kritis yang membutuhkan pengawasan demokratis.
Peter Sunde: Sang Anarkis Digital yang Masih Membara
Percakapan dengan Peter Sunde, salah satu pendiri situs berbagi file The Pirate Bay, menutup bagian ini dengan nada pemberontakan yang belum padam. Sunde adalah simbol dari cita-cita internet awal yang paling radikal: kebebasan informasi absolut, perlawanan terhadap monopoli hak cipta, dan skeptisisme mendalam terhadap otoritas korporat dan negara. Percakapannya dengan Keen pasti penuh dengan sinisme terhadap “kebangkitan” yang terlalu nyaman dari para pemikir arus utama. Baginya, mungkin banyak solusi yang ditawarkan hari ini hanyalah perbaikan kosmetik pada sistem yang rusak dari dalam.
Sunde mewakili suara yang mempertanyakan apakah kita benar-benar “bangun”, atau hanya beralih dari satu mimpi (utopia teknologi) ke mimpi lain (reformisme yang diatur oleh perusahaan yang sama). Dia mungkin mengadvokasikan untuk desentralisasi radikal, enkripsi, dan model peer-to-peer sebagai satu-satunya pertahanan sejati terhadap pengawasan dan kontrol. Bagi Sunde, semangat pemberontakan dari masa lalu internet harus tetap hidup, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai kompas etis untuk menolak masa depan yang terkonsolidasi dan terkontrol oleh segelintir raksasa korporat.
Dari Pasif menjadi Aktif, dari Pengguna menjadi Warga
Secara kolektif, kelima percakapan dalam bagian ini menandai peralihan dari fase kejut dan diagnosis (Bagian 1) ke fase refleksi dan pencarian agensi. Mereka menggambarkan kebangkitan bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses berlapis: kebangkitan sejarah(Kirkpatrick), kebangkitan kesadaran individu (Rushkoff), kebangkitan terhadap arsitektur perhatian (Pariser), kebangkitan terhadap tanggung jawab teknis (Cukier), dan kebangkitan semangat perlawanan (Sunde).
Mereka sepakat bahwa utopia telah berakhir, tetapi mereka berbeda dalam responnya. Apakah kita perlu menjadi lebih “melek” (mindful) secara individu, mendesain ulang algoritma, membangun literasi baru, atau memberontak terhadap struktur itu sendiri? Bagian ini meninggalkan kita dengan keyakinan bahwa “bangun” berarti menolak untuk ditakdirkan oleh teknologi. Itu berarti memulai pekerjaan sulit untuk mengambil kembali kendali—atas perhatian kita, data kita, ruang publik kita, dan imajinasi kita tentang apa yang mungkin—dari logika yang tampaknya tak terelakkan dari platform yang kita ciptakan dalam keadaan mabuk euphoria digital.
Perang Informasi, Politik Identitas, dan Lunturnya Konsensus
Setelah membangunkan kita dari mimpi utopis dan mengkonfirmasi krisis multidimensi, buku ini bergerak ke jantung institusi yang paling terancam: demokrasi liberal. Bagian 3, “Democracy and Its Digital Discontent,” menyelidiki bagaimana ekosistem digital yang baru saja kita “bangun” ini secara aktif menggerogoti fondasi politik masyarakat terbuka. Melalui percakapan dengan lima analis politik dan komunikasi yang tajam, Andrew Keen memetakan medan perang baru di mana kebenaran, kepercayaan, dan narasi bersama menjadi rebutan.
Peter Pomerantsev: Seni Peperangan Realitas yang Dibajak
Percakapan dengan Peter Pomerantsev, penulis This Is Not Propaganda, membawa kita ke dalam dunia “informasionalisme”—di mana informasi bukan lagi alat untuk menggambarkan realitas, tetapi senjata untuk menciptakan dan menghancurkannya. Sebagai ahli yang mempelajari disinformasi Rusia, Pomerantsev menggambarkan bagaimana otoritarianisme abad ke-21 tidak lagi membungkam kebenaran, tetapi membanjiri ruang publik dengan kebohongan, teori konspirasi, dan kebisingan hingga warga tidak lagi dapat membedakan fakta dari fiksi. Ini adalah strategi untuk “melarutkan” realitas yang dapat dipercaya.
Bagi Pomerantsev, kegerahan digital demokrasi terletak pada kerentanannya terhadap serangan ini. Platform media sosial, dengan logika viralnya, adalah amplifier yang sempurna untuk konten yang memecah belah dan memanipulasi emosi. Percakapannya mungkin menyoroti bagaimana hal ini menciptakan “chaos oleh desain”, melemahkan kohesi sosial dan kepercayaan pada institusi demokratis hingga ke titik lumpuh. Dia melihat demokrasi berjuang bukan melawan ideologi tandingan yang koheren, tetapi melawan semacam nihilisme informasi yang terorganisir.
Ece Temelkuran: Dari Demokrasi ke “Demokra-tur” dan Kehancuran Imajinasi Politik
Suara Ece Temelkuran, penulis How to Lose a Country: The Seven Steps from Democracy to Dictatorship, adalah seruan dari garis depan. Sebagai jurnalis Turki yang menyaksikan negaranya sendiri mengalami erosi demokratis, dia membawa analisis yang membara tentang politik emosi dan identitas. Temelkuran berargumen bahwa ketidakpuasan digital telah dieksploitasi oleh para populis untuk menggantikan politik berbasis program dengan politik berbasis identitas dan rasa malu. Mereka menawarkan bukan kebijakan, tetapi perasaan “kembali menjadi besar” dan musuh bersama untuk dibenci.
Bagi dia, kegelisahan terbesar adalah “kehilangan bahasa bersama” dan “kehancuran imajinasi politik”. Ketika wacana publik direduksi menjadi pertempuran suku digital, kemampuan untuk membayangkan masa depan kolektif yang inklusif pun hilang. Percakapannya adalah peringatan bahwa teknologi digital mempercepat proses yang sudah ada: memecah-belah tubuh politik menjadi fragmen-fragmen identitas yang mudah dimanipulasi, membuat demokrasi deliberatif—yang bergantung pada argumen dan kompromi—menjadi hampir mustahil.
Catherine Fieschi: Kebangkitan Populisme dan Anatomi Ketidakpuasan
Catherine Fieschi, ahli ilmu politik dan penulis Populocracy: The Tyranny of Authenticity and the Rise of Populism, menambahkan kedalaman analitis pada gejala yang diamati Temelkuran. Dia membedah bagaimana ketidakpuasan ekonomi dan kultural dimanfaatkan oleh gerakan populis, dan bagaimana platform digital adalah alat yang ideal bagi mereka. Populisme, dalam analisisnya, menawarkan ilusi “keterhubungan langsung” antara pemimpin dan “rakyat sejati,” melewati dan mendiskreditikan institusi perantara (media, partai politik, peradilan) yang justru merupakan tulang punggung demokrasi liberal.
Percakapannya dengan Keen mungkin membahas bagaimana algoritma menguatkan kecurigaan ini dengan memprioritaskan konten yang “otentik” (sering kali berarti emosional dan anti-establishment) di atas yang kompleks atau berbasis fakta. Kegerahan digital demokrasi, dalam pandangannya, adalah krisis perantara. Ketika kepercayaan pada “sistem” runtuh, dan digantikan oleh perasaan langsung namun dangkal melalui media sosial, ruang untuk tata kelola yang rasional dan akuntabel menyusut.
Ian Bremmer: G-Zero dan Vacuum of Digital Governance
Suara geopolitik Ian Bremmer, presiden Eurasia Group, mengangkat skala analisis ke tingkat global. Dia melihat kegelisahan demokrasi dalam konteks “dunia G-Zero”—era di mana kekuatan hegemon seperti AS mundur dari peran kepemimpinan global, menciptakan kekosongan tata kelola. Ke dalam kekosongan inilah perusahaan teknologi raksasa melangkah, menjadi “negara-negara de facto” baru dengan kekuasaan dan pengaruh yang menyaingi bangsa-bangsa, namun tanpa akuntabilitas demokratis sama sekali.
Bagi Bremmer, kegelisahan demokrasi bukan hanya fenomena dalam negeri; ini adalah krisis tata kelola global. Siapa yang membuat aturan untuk ruang siber, data lintas batas, atau AI? Jika bukan negara-negara demokratis yang bersatu, maka akan ditentukan oleh otokrasi seperti Tiongkok atau oleh kepentingan komersial perusahaan teknologi. Percakapannya menekankan bahwa pertahanan masa depan demokrasi memerlukan koalisi negara-negara demokratis untuk bersama-sama membangun kerangka tata kelola digital yang berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dan transparansi—sebuah tantangan yang sangat besar di era fragmentasi.
Martin Wolf: Ekonomi Politik dari Keruntuhan Kepercayaan
Percakapan ditutup oleh Martin Wolf, komentator ekonomi utama Financial Times, yang menghubungkan semua benang ke ekonomi politik. Wolf menganalisis bagaimana ketimpangan ekonomi yang meningkat, stagnasi upah, dan rasa ketidakamanan telah menciptakan reservoir ketidakpuasan yang besar. Ekosistem digital kemudian memompa dan mengarahkan ketidakpuasan ini, memusatkannya pada institusi demokrasi yang dianggap gagal memberikan jawaban.
Bagi Wolf, kegelisahan digital dan ekonomi tidak terpisahkan. Platform yang menguntungkan dari perhatian dan data tidak hanya memecah belah politik, tetapi juga sering kali memperkuat model ekonomi yang mengonsentrasikan kekayaan dan kekuasaan, sehingga memperdalam ketidakpuasan yang mendasarinya. Dia mungkin berargumen bahwa untuk mempertahankan demokrasi, kita tidak hanya perlu memperbaiki ruang informasi, tetapi juga mereformasi ekonomi kapitalis digital itu sendiri untuk memastikan bahwa ia bekerja bagi banyak orang, bukan hanya segelintir orang. Tanpa keadilan ekonomi, kepercayaan—fondasi demokrasi—akan terus terkikis.
Kelima percakapan ini bersama-sama melukiskan gambar lingkaran setan yang mematikan:
- Ketidakpuasan ekonomi dan kultural yang sudah ada dimanfaatkan oleh aktor populis dan otoriter.
- Mereka menggunakan alat-alat platform digital (disinformasi, politik identitas) untuk mengubah ketidakpuasan itu menjadi kemarahan yang terfragmentasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokratis.
- Kelemahan dan kurangnya tata kelola global di ruang digital memungkinkan hal ini terjadi dengan sedikit hambatan, sementara perusahaan teknologi mengumpulkan kekuatan tanpa akuntabilitas.
- Hasilnya adalah pelemahan lebih lanjut dari kemampuan demokrasi untuk memberikan solusi kolektif, yang pada gilirannya memperdalam ketidakpuasan awal.
Bagian ini menegaskan bahwa “kegerahan digital” demokrasi bukanlah gejala sampingan, tetapi penyakit sistemik. Pertahanan masa depan, sebagaimana disarankan oleh para pemikir ini, harus bersifat multidimensi: melawan perang informasi, membangun kembali narasi bersama yang koheren, memperkuat institusi perantara, membentuk aliansi tata kelola global, dan yang terpenting, mengatasi ketidakadilan ekonomi yang memberi bahan bakar pada seluruh api ini. Demokrasi harus belajar berjuang di medan perang baru ini, atau risiko menjadi relik dari “yesterday” yang tidak dapat dipertahankan.
Memperbaiki Masa Depan: Diplomasi, Pekerjaan, Kedaulatan, dan Sentakan Realitas
Setelah mendiagnosis krisis (Bagian 1), membangunkan kita dari mimpi (Bagian 2), dan mengupas ancaman terhadap demokrasi (Bagian 3), buku ini akhirnya beralih ke kemungkinan solusi. Bagian 4, “Fixing the Future,” menghadirkan empat percakapan dengan praktisi yang tidak hanya memetakan masalah tetapi juga mengajukan rencana aksi yang konkret—meski sering kali berbeda. Mereka mewakili bidang diplomasi, ekonomi tenaga kerja, tata kelola digital, dan kritik pasar bebas, masing-masing menawarkan seperangkat alat untuk membangun kembali.
Richard Stengel: Diplomasi Informasi di Zaman Kebohongan Viral
Percakapan dengan Richard Stengel, mantan Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Publik AS dan mantan editor TIME, membawa kita ke arena peperangan narasi global. Bagi Stengel, “memperbaiki masa depan” berarti membuat demokrasi kembali kompetitif dalam pertempuran untuk memenangkan hati dan pikiran. Setelah era di mana AS dianggap “memenangkan” Perang Dingin dengan narasi kebebasan, kini ia menyaksikan negara-negara otoriter seperti Rusia dan Tiongkok dengan lihai memanfaatkan alat-alat digital untuk mempromosikan model tata kelola alternatif—dari “demokrasi terpimpin” hingga “kapitalisme pengawasan negara.”
Stengel berargumen bahwa demokrasi liberal tidak bisa lagi bersikap defensif. Ia harus aktif “berinvestasi dalam diplomasi publik dan informasi abad ke-21,” yang berarti mendukung jurnalisme independen, membangun platform untuk bertukar ide, dan secara proaktif mempromosikan nilai-nilai keterbukaan dan hak asasi manusia dengan cara yang menarik dan dapat diakses—bukannya menggurui. Baginya, perbaikan dimulai dengan mengakui bahwa pertarungan untuk masa depan adalah pertarungan cerita, dan demokrasi harus kembali pandai bercerita. Namun, dia juga pasti mengakui paradoksnya: bagaimana mempromosikan “kebenaran” dan “keterbukaan” di lingkungan yang justru dirancang untuk memutarbalikkan dan menutupi?
Carl Benedikt Frey: Menata Ulang Masyarakat untuk Gelombang Otomatisasi Kedua
Suara Carl Benedikt Frey, ekonom Oxford yang terkenal dengan penelitiannya tentang masa depan pekerjaan, menempatkan pekerjaan dan keamanan ekonomi sebagai fondasi utama untuk masa depan yang stabil. Percakapannya mengingatkan kita bahwa “memperbaiki” berarti mempersiapkan gelombang disrupsi yang akan datang dari AI dan robotika—yang bisa jauh lebih besar daripada era komputerisasi sebelumnya.
Frey tidak terjebak dalam prediksi apokaliptik, tetapi menekankan pilihan kebijakan. Dia mungkin membahas perlunya investasi besar-besaran dalam pendidikan seumur hidup dan pelatihan ulang (reskilling), reformasi sistem pajak yang saat ini sering kali menguntungkan modal di atas tenaga kerja, dan eksperimen dengan kebijakan seperti jaminan pekerjaan sektor publik atau pajak robot. Intinya, pasar tenaga kerja tidak akan “memperbaiki dirinya sendiri”. Tanpa intervensi yang cerdas dan berani, otomatisasi akan memperdalam ketimpangan dan memicu ketidakpuasan sosial yang lebih besar, meracuni politik dan menghancurkan kohesi sosial yang sudah rapuh. Masa depan yang “terperbaiki” adalah masa depan di mana manfaat teknologi dibagikan secara luas.
Toomas Ilves: Sang Arkitek Kedaulatan Digital Estonia
Percakapan dengan Toomas Ilves, mantan Presiden Estonia, menawarkan bukti nyata bahwa perbaikan itu mungkin. Di bawah kepemimpinannya, Estonia berubah dari negara pasca-Soviet menjadi “masyarakat digital paling maju di dunia.” Bagi Ilves, “memperbaiki masa depan” adalah soal membangun kepercayaan melalui teknologi, bukan melawannya. Dia akan menceritakan bagaimana Estonia membangun identitas digital warga negara yang aman, memungkinkan pemungutan suara online, akses rekam medis, dan hampir semua layanan pemerintah dilakukan secara digital dengan efisiensi dan transparansi yang tinggi.
Kuncinya, menurutnya, adalah desain yang berpusat pada warga, dengan prinsip “once-only” (data hanya diminta sekali ke pemerintah), dan komitmen pada kedaulatan data (data warga Estonia disimpan di server dalam negeri). Ilves memberikan visi alternatif dari dominasi perusahaan teknologi AS: sebuah model “digital republic” di mana negara demokratis menggunakan teknologi untuk memberdayakan warganya, memperkuat kepercayaan pada institusi, dan melindungi diri dari campur tangan asing. Perbaikan, dalam pandangannya, bersifat teknis, politis, dan konstitusional sekaligus.
Scott Galloway: Sentakan Realitas Kapitalisme dan Pembubaran Raksasa Teknologi
Percakapan ditutup dengan gaya yang membedah dan provokatif dari Scott Galloway, profesor pemasaran dan komentator bisnis. Bagi Galloway, kebanyakan wacana tentang “memperbaiki masa depan” terlalu abstrak. Solusinya sederhana namun radikal: membubarkan raksasa teknologi (Big Tech).
Dia menganalisis bagaimana monopoli seperti Facebook, Google, Amazon, dan Apple telah “mencaplok kapitalisme”—mereka memonopoli perhatian, data, dan inovasi, mencekik kompetisi, dan mengikis kedaulatan demokratis. Percakapannya penuh dengan tuntutan konkret: penegakan hukum antitrust yang kuat, perpajakan yang adil atas keuntungan digital, dan regulasi yang memaksa platform bertanggung jawab atas konten berbahaya seperti halnya penerbit tradisional. Galloway tidak percaya pada perbaikan dari dalam atau solusi teknis.
Baginya, akar penyakitnya adalah konsentrasi kekuasaan yang luar biasa, dan satu-satunya obatnya adalah desentralisasi paksa melalui kekuatan negara. “Memperbaiki masa depan” berarti mengembalikan dinamisme ekonomi, kompetisi ide, dan kekuasaan kepada masyarakat dan pasar yang sebenarnya, bukan mengizinkan oligopoli swasta untuk menentukan takdir kita.
Emporium Alat untuk Perbaikan
Keempat pembicara ini menawarkan seperangkat alat yang saling melengkapi, meski terkadang tegang, untuk kotak perbaikan masa depan:
- Alat Narasi (Stengel): Memenangkan pertempuran ide dan memulihkan daya tarik demokrasi.
- Alat Sosial-Ekonomi (Frey): Memastikan transisi teknologi tidak meninggalkan mayoritas masyarakat, melalui pendidikan dan jaring pengaman.
- Alat Tata Kelola Teknis (Ilves): Membangun infrastruktur digital negara yang transparan, efisien, dan terpercaya yang melayani warga.
- Alat Kekuatan Pasar dan Negara (Galloway): Memangkas kekuasaan perusahaan yang menghalangi, dengan menggunakan penegakan hukum dan regulasi yang tegas.
Secara bersama-sama, mereka menggeser fokus dari apa yang salah ke apa yang bisa dilakukan. Mereka menunjukkan bahwa “memperbaiki” bukanlah tentang menemukan satu solusi ajaib, tetapi tentang melakukan banyak hal sekaligus dengan tekun: bercerita lebih baik, mendidik ulang tenaga kerja, membangun institusi digital yang tangguh, dan memiliki keberanian politik untuk menjinakkan kekuatan pasar yang telah menjadi terlalu besar. Masa depan yang bisa dipertahankan, menurut bagian ini, harus direbut melalui kombinasi diplomasi, kebijakan sosial, inovasi tata kelola, dan—yang tidak kalah pentingnya—dengan kemauan untuk menggunakan kekuatan regulasi negara terhadap kekuatan korporat yang paling perkasa.
Peta Intelektual untuk Membela Masa Depan yang Manusiawi
Dalam simfoni percakapan yang disusun oleh Andrew Keen dalam Tomorrows vs Yesterdays, suara-suara yang tampaknya bertolak belakang—dari Shoshana Zuboff yang mengutuk kapitalisme pengawasan hingga Scott Galloway yang menyerukan pembubaran Big Tech, dari Maria Ressa yang berjuang untuk fakta hingga Toomas Ilves yang membangun republik digital—sebenarnya sedang menyulam sebuah peta intelektual yang koheren. Peta ini tidak menunjuk ke satu jalan keluar yang sederhana, melainkan merangkai sebuah diagnosis kolektif dan sebuah kerangka aksi multidimensi untuk membela masa depan demokrasi dan humanisme di abad digital. Benang merah yang menjalin mereka semua adalah pengakuan akan satu pertarungan eksistensial: pertarungan untuk kedaulatan.
Kedaulatan yang Dicuri: Dari Individu hingga Negara
Pertarungan ini terjadi di tiga level yang saling terkait, dan setiap intelektual dalam buku ini mengisi satu sudut dari segitiga krisis ini. Di level paling intim, kedaulatan individu menjadi sasaran. Shoshana Zuboff, dengan konsep surveillance capitalism, menjelaskan mekanisme pencurian ini: pengalaman manusia yang paling pribadi diekstraksi dan diubah menjadi bahan baku untuk memprediksi dan memodifikasi perilaku. Douglas Rushkoff dan Eli Pariser melengkapi gambaran ini dengan menunjukkan konsekuensi kognitifnya: kita kehilangan otonomi perhatian, terperangkap dalam gelembung filter yang menghancurkan kapasitas kita untuk berpikir kritis dan berempati terhadap yang lain. Di sini, kedaulatan diri dirampok bukan dengan paksaan, tetapi dengan desain yang memanipulasi pilihan dari dalam.
Keroposnya kedaulatan individu secara massal langsung meruntuhkan level kedua: kedaulatan politik demokratis. Peter Pomerantsev dan Ece Temelkuran menunjukkan dengan lugas bagaimana alat-alat yang sama yang mengekstraksi data individu digunakan untuk mengekstraksi legitimasi politik. Disinformasi dan politik identitas berbasis kemarahan memecah belah tubuh politik, melarutkan realitas bersama, dan menghancurkan kepercayaan pada institusi. Catherine Fieschi menganalisisnya sebagai krisis perantara, sementara Ian Bremmer melihatnya sebagai krisis tata kelola global di mana negara-bangsa kehilangan kendali atas ruang yang kini dikuasai oleh aktor korporasi tanpa akunabilitas. Maria Ressa adalah saksi hidup dari bagaimana proses ini tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi membunuhnya perlahan-lahan.
Hal ini mengarah pada level ketiga, kedaulatan kolektif suatu masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri. Di sinilah analisis ekonomi Martin Wolf dan Carl Benedikt Frey menjadi krusial. Mereka menunjukkan bahwa krisis politik ini berakar pada kerapuhan ekonomi: ketimpangan dan ketidakamanan kerja yang diciptakan dan diperparah oleh model bisnis digital. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk maju bersama, mereka menjadi rentan terhadap narasi populisme dan perpecahan. Masa depan sebagai proyek kolektif pun bubar.
Namun, buku ini bukan sekadar katalog kehancuran. Setiap diagnosis dilengkapi dengan preskripsi, yang bersama-sama membentuk strategi pertahanan berlapis.
- Pembatasan Kekuasaan (The Check): Lapisan pertama adalah membatasi kekuatan yang telah menjadi terlalu besar. Scott Galloway menyuarakannya paling keras: gunakan kekuatan antitrust untuk mendesentralisasi monopoli teknologi. Tanpa ini, upaya lain akan seperti memperbaiki rumah yang fondasinya dikikis oleh raksasa korporat. Ini adalah prasyarat politik.
- Pembangunan Kedaulatan Alternatif (The Build): Lapisan kedua adalah membangun infrastruktur kedaulatan baru. Di sinilah Toomas Ilves memberikan cetak biru yang konkret: kedaulatan digital melalui negara. Dengan membangun identitas digital publik yang aman dan sistem tata kelola data yang transparan, negara dapat merebut kembali peran sebagai pelayan publik, memulihkan kepercayaan, dan melindungi warga dari eksploitasi korporasi. Ini adalah jawaban tekno-politik terhadap kekosongan tata kelola.
- Pemberdayaan Kapasitas (The Empower): Lapisan ketiga adalah mempersenjatai warga dan masyarakat dengan kapasitas baru. Carl Benedikt Frey berbicara tentang reskilling dan jaring pengaman ekonomi. Richard Stengel berbicara tentang diplomasi publik dan literasi media untuk memenangkan pertempuran narasi. Kenneth Cukier menekankan literasi data. Ini adalah investasi pada modal manusia dan sosial.
- Revolusi Kesadaran (The Awaken): Lapisan terdalam adalah perubahan kesadaran, yang digaungkan oleh Douglas Rushkoff dan Eli Pariser. Kita harus “keluar dari layar” secara kritis, merebut kembali perhatian kita, dan menuntut teknologi yang dirancang untuk pengayaan manusia, bukan eksploitasinya. Ini adalah landasan budaya dari segala perubahan.
Catatan Akhir: Humanisme sebagai Kompas Tertinggi
Benang merah terakhir yang menyatukan semua suara ini, dari Zuboff hingga Ressa, dari Rushkoff hingga Ilves, adalah komitmen pada humanisme yang diperbarui. Mereka tidak menolak teknologi, tetapi menolak tekno-determinisme—gagasan bahwa kita harus pasrah pada logika efisiensi, pertumbuhan, dan pengawasan. Mereka membela masa depan di mana teknologi adalah alat yang melayani nilai-nilai kemanusiaan: otonomi, martabat, keadilan, kebenaran, dan demokrasi deliberatif.
Percakapan-percakapan dalam Tomorrows vs Yesterdays pada akhirnya adalah latihan dalam imajinasi politik ulang. Mereka menolak nostalgia akan masa lalu (yesterdays) yang tertutup dan sering kali tidak adil, tetapi juga menolak tomorrow yang dipaksakan oleh Silicon Valley yang hanya menjanjikan kemudahan dengan harga kebebasan. Sebagai gantinya, mereka membayangkan—dan mulai merancang—sebuah day after tomorrow yang lain: sebuah masa depan yang direbut kembali melalui kombinasi kekuatan negara yang direformasi, masyarakat sipil yang waspada, warga negara yang berdaya, dan desain teknologi yang beretika. Di peta intelektual ini, membela masa depan bukanlah tugas untuk seorang jenius atau satu kebijakan ajaib. Ia adalah proyek kolektif yang sulit dan mendesak untuk menjahit kembali kedaulatan yang telah tercabik-cabik di setiap level—dan menjadikan manusia, sekali lagi, sebagai ukuran dari segala sesuatu.
Intisari dari “Tomorrows vs Yesterdays” adalah keyakinan bahwa masa depan bukanlah produk teknis yang pasif, tetapi hasil dari keputusan kolektif kita hari ini. Buku ini berargumen melawan determinisme teknologi—gagasan bahwa kita hanya dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan yang tak terelakkan. Sebaliknya, ia menyerukan “keterlibatan kritis” yang gigih. Pertahanan melawan tirani teknologi dengan melalui dialog kritis.
Relevansinya pada tahun 2024 dan seterusnya semakin jelas. Ketika AI generatif menjadi arus utama, pertanyaan tentang kreativitas, kepenulisan, dan keaslian yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat mendesak. Ketika geopolitik teknologi memecah dunia menjadi blok-blok yang bersaing, diskusi tentang tata kelola dan nilai-nilai global menjadi penting. Buku ini berfungsi sebagai “alat pelatihan mental” untuk kewarganegaraan di abad digital, membekali pembaca dengan kemampuan untuk mempertanyakan klaim besar dari para evangelis teknologi dan menghadapi nostalgia reaksioner dengan visi alternatif yang terinformasi.
Pada akhirnya, buku ini membela masa depan dengan cara yang paling manusiawi: dengan percakapan. Ia mengakui, dalam kata-kata filsuf Hannah Arendt, bahwa “esensi dari tindakan manusia adalah natality—kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru.” Percakapan-percakapan dalam “Tomorrows vs Yesterdays” adalah upaya untuk melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru tersebut. Mereka mengingatkan kita bahwa pertahanan terbaik terhadap masa depan yang dystopian atau mundur ke masa lalu yang ilusi adalah keberanian untuk memperdebatkan, mendengarkan, dan bersama-sama membayangkan banyak ‘hari esok’ yang mungkin—dan kemudian berjuang untuk yang paling manusiawi di antaranya.
Bogor, 2 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Deuraseh, N. (2017). Etika Teknologi Dalam Islam: Konsep Maslahah dan Mizan. Penerbit Universiti Malaya.
Harari, Y. N. (dalam wawancara). (2020). Dalam A. Keen (Ed.), Tomorrows vs Yesterdays: Conversations in Defense of the Future. DLD Atlantic Books.
Keen, A. (Ed.). (2020). Tomorrows vs Yesterdays: Conversations in Defense of the Future. DLD Atlantic Books.