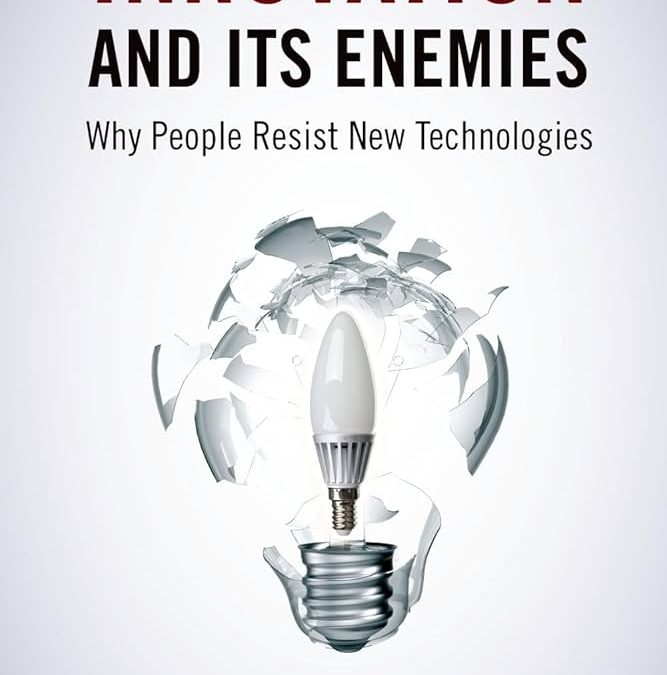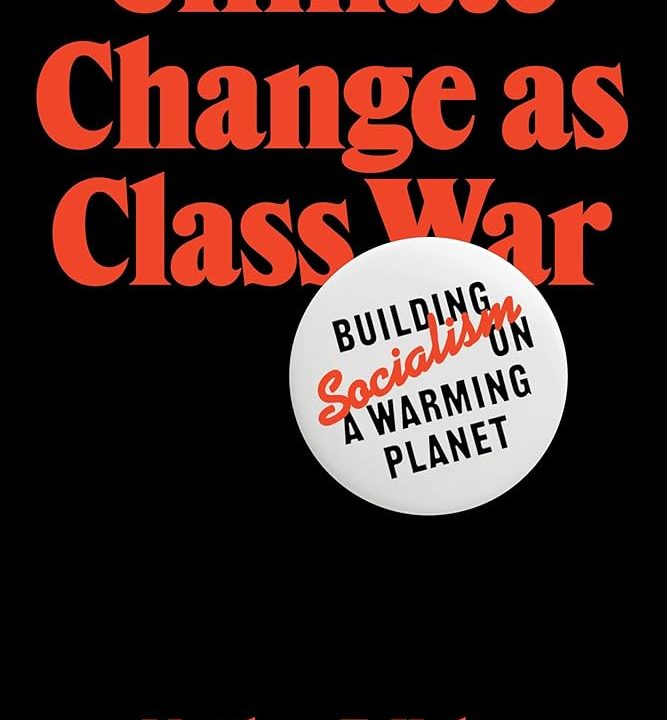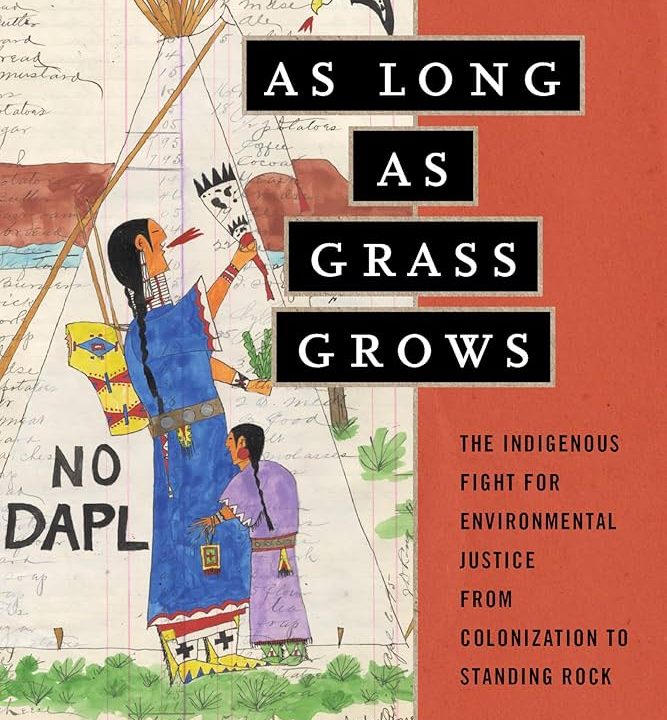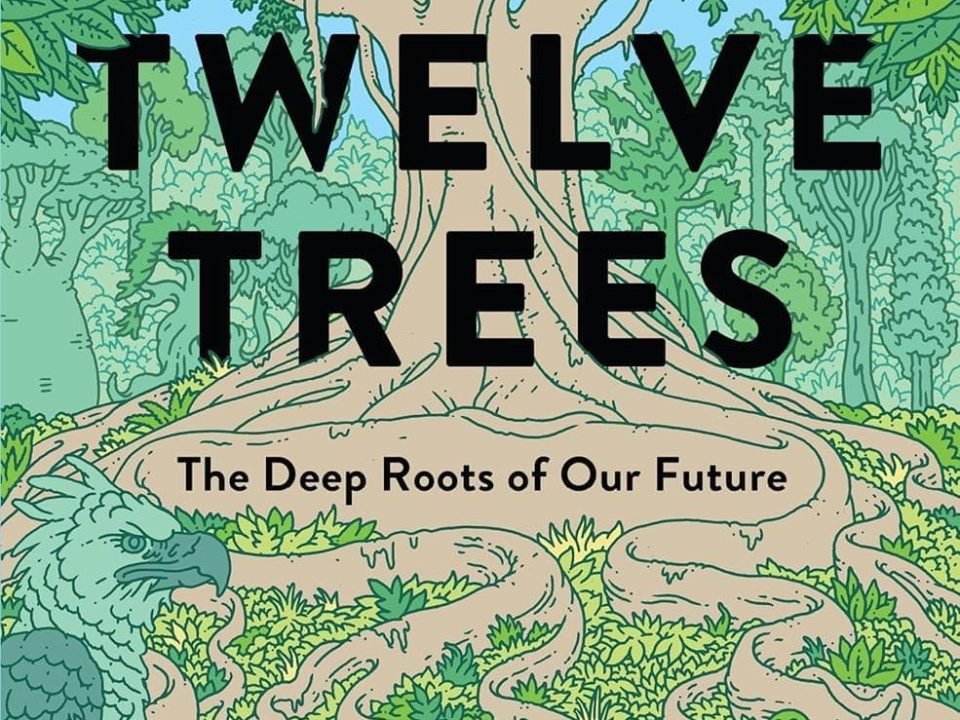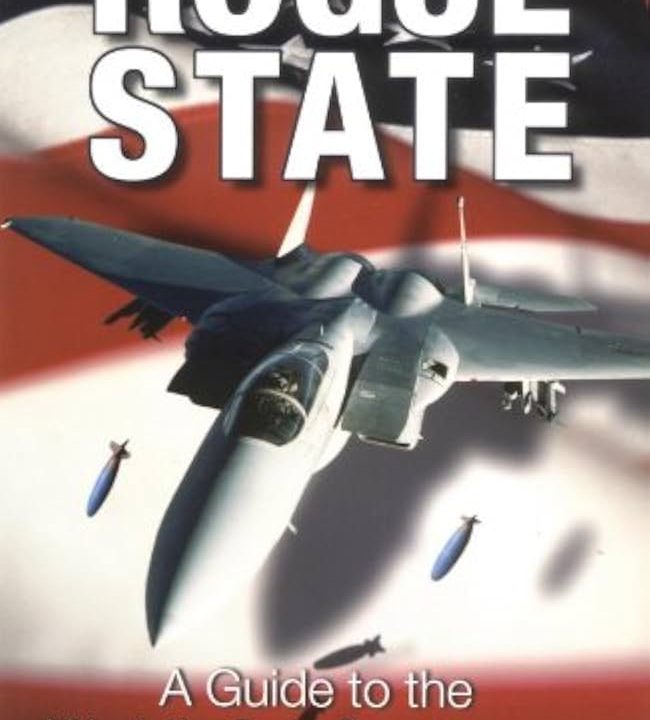Rubarubu #32
Innovation and Its Enemies:
Bagaimana Mengelola
Kisah Mesin Pintal dan Para Pemintal yang Berduka
Pada suatu hari di Inggris abad ke-18, sekelompok pemintal tradisional menyaksikan dengan mata berkabut sebagai mesin pintal baru—”Spinning Jenny“—mulai berdetak di pabrik-pabrik. Mereka adalah para pengrajin yang selama ini menghidupi keluarga dengan keahlian tangan mereka, menghasilkan benang yang halus dengan rhythm gerakan jari yang telah turun-temurun. Kini, mesin itu dapat memintal delapan gulung benang sekaligus, dikerjakan oleh buruh tak terampil dengan upah murah. Bukan hanya mata pencaharian mereka yang terancam, tetapi juga identitas sebagai pemintal andal, harga diri sebagai pengrajin, dan warisan budaya yang mereka banggakan.
Dalam keputusasaan, gerakan “Luddite” pun lahir—para pemintal ini merusak mesin-mesin yang mereka anggap sebagai sumber malapetaka. Tindakan mereka sering dicap sebagai “anti-kemajuan”, tetapi apakah sesederhana itu?
Kisah inilah yang menjadi jantung buku Calestous Juma, “Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies (2016).” Buku ini bukan sekadar katalog penolakan teknologi, melainkan eksplorasi mendalam tentang logika manusiawi di balik penolakan tersebut—sebuah upaya untuk memahami, bukan menghakimi. Calestous Juma adalah seorang akademisi, penulis, dan visioner Kenya yang diakui secara global sebagai salah satu pemikir terkemuka di bidang inovasi, pembangunan global, dan hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Karyanya berfokus pada bagaimana negara-negara berkembang dapat memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang transformatif.
“Resistance to new technologies is often not about the technologies per se, but about the profound social, economic, and cultural disruptions they bring.”
(Juma, 2016, hlm. 5)
Buku yang ditulis Juma, Profesor Praktik Pembangunan Internasional di Harvard Kennedy School di Universitas Harvard dan mengajar mata kuliah yang berpengaruh tentang inovasi dan kewirausahaan ini terdiri dari 11 bagian. Setiap bagian mengulas tentang kasus-kasus dimana inovasi megnhadapi tantangan terberatnya.
Juma menguraikan Anatomi Penolakan—Mengapa Manusia Menolak Inovasi? Juma meng-identifikasi pola-pola universal dalam penolakan teknologi sepanjang sejarah, dari mesin pintal hingga rekayasa genetika. Menurutnya terdapat tiga sumber penolakan utama. Pertama, Ancaman terhadap Identitas dan Mata Pencaharian. Teknologi baru sering mengganggu tatanan ekonomi yang mapan, mengancam pekerjaan dan status sosial kelompok tertentu. Contoh: Sopir delman menolak mobil bukan karena tak paham kecepatannya, tetapi karena mobil mengancam cara hidup mereka.
Kedua, Kekhawatiran terhadap Nilai-nilai Budaya dan Agama. Inovasi dianggap mengikis nilai-nilai tradisional atau melanggar keyakinan religius. Contoh: Penolakan vaksinasi di beberapa komunitas karena dianggap melawan takdir ilahi. Ketiga, Ketidakpercayaan terhadap Institusi dan Elit. Masyarakat sering menolak teknologi ketika mereka tidak percaya pada institusi yang mempromosikannya. Contoh: Penolakan makanan transgenik karena ketidakpercayaan pada perusahaan agribisnis besar.
Mahatma Gandhi pernah berkata: “There is enough on this earth for human needs, but not for human greed.” Penolakan sering muncul ketika teknologi dipersepsikan melayani keserakahan, bukan kebutuhan.
Kita ambil contoh pelajaran dari sejarah—enam studi kasis historis tentang penolakan terhadap inovasi. Juma menganalisis enam kasus sejarah dengan kedalaman yang mengagumkan. Kopi di dunia Islam Abad ke-16. Awalnya kopi ditolak karena dianggap memabukkan dan meng-ganggu tatanan sosial. Tetapi kemudian berhasil diterima setelah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diintegrasikan dalam ritual sosial. Pendingin Mekanis di Amerika Abad ke-19. Awal-nya ditolak karena dianggap “tidak alami” dan mengganggu industri es alami. Penerimaan terjadi ketika manfaatnya menjadi jelas bagi kesehatan publik dan distribusi makanan. Transgenik di Eropa Modern. Penolakan terkuat justru di masyarakat dengan tradisi pertanian kuat. Dikaitkan dengan globalisasi dan korporasi multinasional.
Pola yang Terungkap:
- Waktu adalah Faktor Kritis: Butuh 20-50 tahun untuk penerimaan penuh
- Konteks Lebih Penting daripada Teknologi: Teknologi yang sama diterima berbeda di budaya berbeda
- Peran “Technology Stewards”: Pentingnya aktor yang menjembatani teknologi dengan nilai lokal
Juma mengembangkan kerangka analitis yang sophisticated untuk memahami penolakan inovasi. Ia mengidentifikasi faktor-faktor yang memperparah penolakan. Berdasarkan itu maka diketahui bahwa ada empat faktor penting: Pertama, Tingkat Disrupsi: Semakin mengganggu tatanan sosial-ekonomi, semakin kuat penolakan. Kedua, Kompleksitas Teknologi: Semakin sulit dipahami, semakin besar ketakutan. Ketiga, Konsentrasi Manfaat vs Penyebaran Biaya: Ketika manfaat dinikmati segelintir orang sementara biaya ditanggung banyak orang. Empat, Nilai-nilai Budaya: Teknologi yang dianggap melanggar nilai inti akan ditolak lebih keras. “The single most important factor determining the acceptance of a new technology is the extent to which it can be reconciled with existing cultural practices.” (Juma, 2016, hlm. 147)
Juma memulai diskusi dalam buku ini dengan membahas Badai Penghancuran Kreatif (Bagian 1 – Gales of Creative Destruction). Dalam bagian pembuka bukunya, Calestous Juma membingkai fenomena inovasi teknologi melalui lensa konsep ekonom Joseph Schumpeter tentang “creative destruction” – proses dimana inovasi menghancurkan tatanan ekonomi lama sambil mencipta-kan yang baru. Namun Juma memperdalam konsep ini dengan mengeksplorasi dimensi manusia dan sosial dari proses penghancuran kreatif tersebut. “Technological innovation is not just about creating new products; it is a powerful force that reconfigures social and economic landscapes, leaving some communities devastated while creating opportunities for others.” (Juma, 2016, hlm. 23).
Anatomi Proses Penghancuran Kreatif
Inilah siklus inovasi yang tak terelakkan yang menimbulkan penderitaan. Juma menggambarkan bagaimana setiap gelombang inovasi besar mengikuti pola yang dapat diprediksi:
Fase 1: Kelahiran Inovasi
- Teknologi baru muncul dari pinggiran sistem ekonomi
- Awalnya dianggap sebagai “mainan” atau kelengkapan yang tidak penting
- Hanya segelintir visioner yang melihat potensinya
Fase 2: Disrupsi Bertahap
- Inovasi mulai menggantikan teknologi yang mapan
- Muncul ketegangan antara pemain lama dan baru
- Regulasi dan institusi existing berusaha menahan perubahan
Fase 3: Penghancuran Massal
- Teknologi lama menjadi usang bersama dengan keahlian, infrastruktur, dan mata pencaharian yang mendukungnya
- Komunitas yang bergantung pada sistem lama mengalami kerugian eksistensial
Fase 4: Rekonfigurasi Sosial
- Tatanan sosial dan ekonomi baru terbentuk
- Pekerjaan baru muncul, tetapi membutuhkan keahlian yang berbeda
- Nilai-nilai budaya beradaptasi atau punah
Contoh historis yang mengilustrasikan fase-fase itu bisa kita mbil dari revolusi percetakan vs para penyalin naskah. Awalnya para penyalin naskah (scribes) abad pertengahan menghabiskan waktu bertahun-tahun menguasai kaligrafi yang indah. Kemudian datanglah mesin cetak Gutenberg yang membuat keahlian mereka tiba-tiba tidak relevan. Bukan hanya mata pencaharian yang hilang, tetapi seluruh identitas sebagai penjaga pengetahuan.
Contoh lain tentang industri otomotif vs peternak kuda. Pada tahun 1900, kota-kota besar bergantung pada industri yang mendukung transportasi berkuda: pembuat kereta, pandai besi, penjual oat, pemilik kandang. Mobil tidak hanya menggantikan kuda, tetapi menghancurkan seluruh ekosistem ekonomi yang telah mapan. Data: Di AS saja, sekitar 20% lahan pertanian sebelumnya digunakan untuk memelihara kuda transportasi
Tentu saja ada keterlibatann dimensi manusia dari penghancuran kreatif ini. Dan itu bisa dianggap sebagai kerugian yang tidak terukur. Juma menekankan bahwa analisis ekonomi tradisional sering gagal menangkap biaya manusia sepenuhnya. Kehilangan apapun yang tergantikan yang tidak terkompensasi. Misalnya modal manusia spesifik: keahlian yang dikembangkan selama puluhan tahun tiba-tiba tidak bernilai. Modal sosial: jaringan dan hubungan yang terbangun dalam komunitas profesional. Identitas profesional: rasa bangga dan makna yang melekat pada pekerjaan tertentu. Stabilitas keluarga: dampak pada perencanaan kehidupan keluarga dan pendidikan anak.
Juma juga mengidentifikasi respons psikologis kunci terhadap ancaman penghancuran kreatif:
Penyangkalan (Denial): Mengabaikan bukti bahwa perubahan tak terhindarkan. Kemarahan (Anger): Menyalahkan inovator, pemerintah, atau kekuatan eksternal. Tawar-menawar (Bargaining): Mencoba kompromi untuk memperlambat perubahan. Depresi (Depression): Menyadari ketidakberdayaan menghadapi perubahan. Penerimaan (Acceptance): Akhirnya beradaptasi dengan realitas baru. Ekonom Indonesia, M. Dawam Rahardjo, pernah mengingatkan: “Pembangunan tanpa perlindungan terhadap yang lemah adalah pembangunan yang tidak berperikemanusiaan.”
Paradoks Kemajuan Teknologi
Buku. ini juga menguraikan adanya kesenjangan antara manfaat makro dan biaya mikro. Juma mengungkap paradoks fundamental:
- Tingkat Makro: Inovasi jelas meningkatkan produktivitas dan kemakmuran nasional
- Tingkat Mikro: Individu dan komunitas tertentu menanggung biaya yang tidak proporsional
Contoh: Revolusi Industri jelas meningkatkan standar hidup rata-rata di Inggris, tetapi para pekerja pabrik awal justru mengalami penurunan kualitas hidup dibandingkan dengan pengrajin independen sebelumnya. Manfaat inovasi seringkali terwujud dalam jangka panjang dan tersebar luas. Biaya langsung, intens, dan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Apa yang terjadi dulu, masukkny aberagam inovasi juga etrjadi pada saat evolusi digital kini. Kembalinya pola lama. Juma menunjukkan bagaimana pola yang sama terulang di era digital:
Misalnya yang terjadi di sektor transportasi, industsi taksi tradisional vs ride-hailing: Sopir taksi menghabiskan puluhan ribu dolar untuk medali taksi yang tiba-tiba kehilangan nilai. Aplikasi ride-hailing menciptakan pekerjaan baru, tetapi dengan stabilitas dan manfaat yang lebih rendah. Retail Tradisional vs E-commerce: Pusat perbelanjaan dan toko ritel berjuang menghadapi Amazon dan platform online. Pekerjaan retail tradisional hilang, digantikan oleh pekerja gudang dan pengiriman
Kasus lain yang cukup menarik diuraikan pada Bagian 3 – “Stop the Presses: Printing the Koran.” Timbulnya konflik teknologi dan spiritualitas: kasus percetakan al-qur’an. Dalam bagian yang sangat menarik ini, Juma mengeksplorasi resistensi yang dalam dan berkepanjang-an terhadap teknologi percetakan buku-buku keagamaan Islam, khususnya Al-Qur’an. Kasus ini mengungkapkan bagaimana inovasi teknologi dapat berbenturan dengan nilai-nilai spiritual dan identitas kultural yang paling mendalam. “The resistance to printing the Koran was not merely about technological adoption; it was about preserving the sacredness of the word of God in a world of mechanical reproduction.” (Juma, 2016, hlm. 89)
Juma mengungkapkan paradoks menarik: Teknologi percetakan sebenarnya dikenal di dunia Islam sejak abad ke-10 melalui teknik block printing dari China. Namun, penerapan teknologi ini untuk teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur’an, menghadapi resistensi selama berabad-abad.Sementara Eropa Kristen menerima percetakan massal Bible sejak pertengahan abad ke-15. Sedangkan Dunia Islam baru mengadopsi percetakan massal Al-Qur’an pada abad ke-19—terlambat hampir 400 tahun.
Menurut Juma akar-akar penolakan ini melampaui sekadar konservatisme. Ada beberapa faktor. Pertama, kekhawatiran terhadap Sakralitas Teks. Penolakan utama berpusat pada kekhawatiran bahwa proses mekanis akan mengurangi kesucian wahyu Ilahi. Kekhawatiran Utama: Kehilangan Keberkahan (Barakah): Tulisan tangan dianggap membawa berkah dari niat suci penyalin; Desakralisasi: Proses mekanis dianggap menghilangkan dimensi spiritual dari penulisan; Potensi Kesalahan Massal: Kesalahan cetak dapat menyebar luas dan sulit dikoreksi.
Kedua, Ancaman terhadap Ekonomi Keilmuan. Juma menunjukkan bahwa resistensi juga datang dari struktur sosial-ekonomi yang mapan. Kelompok yang Terancam adalah: Para Penyalin (Kuttab): Menghabiskan bertahun-tahun menguasai kaligrafi yang sempurna; Guru Pengajian: Sistem pendidikan yang bergantung pada transmisi oral dan tulisan tangan; Ulama Tradisional: Otoritas keagamaan yang terkait dengan sistem transmisi pengetahuan tradisional
Ketiga, Pertimbangan Teologis yang Mendalam. Juma mengungkapkan bahwa penolakan tidak hanya bersifat reaksioner, tetapi didasarkan pada pertimbangan teologis yang serius. Argumen Teologis: Konsep Ijazah: Sistem transmisi pengetahuan melalui rantai guru-murid yang tidak terputus; Penghormatan pada Teks: Keyakinan bahwa Al-Qur’an harus ditangani dengan hormat maksimal; Bahaya Komersialisasi: Kekhawatiran bahwa percetakan akan meng-komodifikasi kitab suci.
Proses adopsi teknologi percetakan di dunia Islam merupakan sebuah perjalanan adaptasi yang bertahap dan kompleks, yang tidak terjadi secara instan namun melalui beberapa fase pentahapan.
Pada Fase Pertama: Penerimaan Terbatas (Abad 16-17), teknologi cetak baru dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat non-agama dan administratif. Yang menarik, komunitas non-Muslim di dalam kekaisaran Ottoman diberikan keleluasaan untuk mengoperasikan percetakan dalam bahasa mereka sendiri. Sebagai contoh, percetakan dalam bahasa Ibrani dan Armenia dapat berkembang di Istanbul, sementara pada periode yang sama, percetakan menggunakan aksara Arab justru dilarang.
Perlahan namun pasti, dorongan untuk berubah datang dari luar, yang menandai Fase Kedua: Tekanan Eksternal dan Modernisasi (Abad 18-19). Calestous Juma menunjukkan dalam analisisnya bagaimana faktor-faktor eksternal inilah yang memaksa terjadinya perubahan. Faktor pendorong utamanya antara lain Kebutuhan Administratif yang mendesak, di mana kekaisaran Ottoman memerlukan dokumen-dokumen tercetak untuk menjalankan administrasi negara yang modern. Selain itu, Tekanan Militer berupa kekalahan dalam peperangan repeatedly menunjukkan ketertinggalan mereka dan pentingnya mengadopsi teknologi modern. Faktor ketiga adalah Penyebaran Ide, di mana buku-buku Eropa yang telah dicetak mulai mempengaruhi pemikiran kalangan elite Muslim.
Kondisi ini akhirnya mencapai Fase Ketiga: Terobosan dan Legitimasi (Abad 19), yang ditandai dengan momentum-momentum bersejarah. Pada tahun 1803, untuk pertama kalinya Al-Qur’an dicetak di Kazan, Rusia. Kemudian, pada tahun 1867, percetakan Al-Qur’an yang resmi dan mendapat legitimasi diluncurkan di Istanbul dengan persetujuan dari para ulama. Proses pemberian legitimasi ini tidak sederhana; ia melibatkan pengawasan yang sangat ketat oleh para ulama untuk memastikan keakuratan setiap huruf dan tanda dalam teks suci tersebut.
Dalam narasi perubahan yang kompleks ini, peran Aktor Kunci menjadi penentu. Sultan Mahmud II (1785-1839) adalah salah satu tokoh sentral. Sebagai pemimpin, ia memahami bahwa modernisasi adalah sebuah kebutuhan untuk menyelamatkan kekaisarannya dari kehancuran. Visinya diwujudkan dengan mendirikan percetakan resmi negara yang tetap melibatkan pengawasan ulama, sebuah langkah cerdas yang menciptakan kompromi yang harmonis antara tradisi dan modernitas. Di sisi lain, peran Ulama Reformis juga tak kalah crucial. Kelompok ulama progresif ini memandang percetakan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat dakwah yang powerful. Mereka berargumen bahwa teknologi ini justru dapat menyebarkan ajaran Islam lebih luas lagi. Penekanan mereka bergeser dari mediumnya kepada substansinya, yaitu bahwa yang terpenting adalah menjaga keakuratan teks, bukan menolak bentuk fisiknya.
Adaptasi teknologi ini akhirnya membawa Implikasi Sosial dan Budaya yang Luas, men-transformasi masyarakat Muslim secara mendasar. Terjadi Transformasi Akses terhadap Pengetahuan. Sebelumnya, Al-Qur’an terutama diakses melalui hafalan dan pengajian langsung dari guru. Setelah percetakan, setiap individu memiliki peluang untuk mempelajari teks secara lebih mandiri. Hal ini mendorong terjadinya Demokratisasi Pengetahuan, yang secara perlahan mengurangi monopoli ulama tradisional terhadap interpretasi keagamaan. Perubahan ini juga berdampak pada Praktik Keagamaan itu sendiri. Munculnya budaya memiliki “Al-Qur’an pribadi” di rumah-rumah Muslim mengubah dinamika hubungan antara guru dan murid, dan pada akhirnya mentransformasi sistem pendidikan Islam tradisional secara keseluruhan.
Relevansi dengan Teori Inovasi Juma
Kasus resistensi terhadap pencetakan Al-Qur’an ini memberikan gambaran nyata yang mengilustrasikan beberapa prinsip kunci dalam teori inovasi Calestous Juma. Dari sini dapat ditarik pelajaran tentang resistensi terhadap inovasi yang masih relevan hingga saat ini.
Pertama, Juma menekankan bahwa resistensi bukanlah irasional. Penolakan terhadap teknologi percetakan Al-Qur’an justru berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang sangat dalam. Masyarakat saat itu tidak serta-merta menolak kemajuan, tetapi sungguh-sungguh mem-pertimbangkan konsekuensi sosial dan spiritual yang mereka anggap nyata—mulai dari kekhawatiran terhadap kemungkinan distorsi teks suci hingga perubahan tatanan hubungan guru-murid.
Kedua, terlihat betapa pentingnya adaptasi kultural. Inovasi teknologi tidak bisa begitu saja dipaksakan; ia harus diadaptasi agar selaras dengan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, proses legitimasi oleh otoritas kultural—dalam hal ini para ulama—menjadi kunci penerimaan. Tanpa restu dan pengawasan mereka, teknologi percetakan tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat Muslim.
Ketiga, peran kompromi kreatif menjadi solusi. Kompromi ini terwujud dalam bentuk mekanis-me pengawasan ketat oleh ulama selama proses percetakan. Dengan demikian, esensi spiritual dan akurasi teks suci tetap terjaga, sementara manfaat teknologi baru dapat diadopsi. Seorang cendekiawan Muslim, Syed Muhammad Naquib al-Attas, pernah menulis dengan bijak, “Islam tidak menolak kemajuan, tetapi menjaga agar kemajuan tidak mengikis makna dan tujuan tertinggi kehidupan manusia.” Kutipan ini menyiratkan bahwa penerimaan inovasi harus disertai dengan kesadaran untuk melindungi hal-hal yang dianggap sakral.
Pola yang sama ternyata terus berulang, termasuk di era digital sekarang. Juma menunjukkan bahwa resistensi serupa kembali muncul, misalnya dalam menanggapi kehadiran Al-Qur’an digital dan berbagai aplikasi terkait. Kekhawatiran kembali muncul tentang kesucian teks yang ditampilkan pada perangkat yang juga digunakan untuk keperluan hiburan, serta debat tentang validitas shalat dengan membaca Al-Qur’an dari layar smartphone.
Dari sini, terdapat pelajaran berharga untuk inovator modern. Inovator harus berusaha memahami nilai-nilai mendalam apa yang mungkin merasa terancam oleh kehadiran teknologi baru. Mereka perlu melibatkan pemegang otoritas kultural sejak awal proses pengembangan, dan yang terpenting, aktif mencari bentuk kompromi yang tetap menghormati tradisi sambil membuka akses terhadap manfaat baru yang ditawarkan.
Thesis Inti dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa resistensi terhadap percetakan Al-Qur’an bukanlah contoh sederhana dari sikap “anti-kemajuan”. Ia justru merupakan respons yang kompleks terhadap ancaman yang dirasakan terhadap sistem makna dan praktik keagamaan yang telah mapan.
Beberapa faktor-faktor kunci yang mempengaruhi resistensi dalam kasus ini antara lain:
- Kekhawatiran Teologis tentang sakralitas dan keutuhan akurasi teks suci.
- Kepentingan Ekonomi dari para penyalin manuskrip dan guru tradisional yang mata pencahariannya terancam.
- Pertimbangan Budaya mengenai hubungan yang tepat antara seorang Muslim dengan teks sucinya.
- Proses Politik yang rumit dalam melegitimasi sebuah teknologi baru.
Akhirnya, pelajaran untuk inovasi kontemporer yang dapat dipetik adalah:
- Teknologi tidak pernah benar-benar “netral” secara kultural; ia selalu membawa serta nilai dan dampak sosial tertentu.
- Resistensi sering kali berakar pada upaya perlindungan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas.
- Solusi yang berhasil dan berkelanjutan tidak hanya memerlukan keunggulan teknis, tetapi lebih pada pemahaman dan penghormatan yang mendalam terhadap konteks kultural di mana inovasi tersebut diperkenalkan.
“The slow adoption of printing for the Koran teaches us that successful technological innovation requires not just technical competence, but deep cultural sensitivity and the wisdom to navigate the sacred landscapes of human meaning.” (Juma, 2016, hlm. 112)
Kasus ini mengingatkan kita bahwa inovasi yang benar-benar transformatif tidak hanya mengubah cara kita melakukan sesuatu, tetapi juga mengubah cara kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan bermakna, kita harus belajar mendengarkan tidak hanya kepada pasar, tetapi juga kepada jiwa-jiwa yang akan terdampak oleh perubahan yang kita bawa.
Dalam bagian penutup bukunya yang visioner, Bagian 11: “Oiling the Wheels of Novelty“, Calestous Juma melakukan pergeseran penting dari mendiagnosis akar penolakan inovasi menuju meresepkan solusi untuk mengatasinya. Bagian ini menyajikan sebuah kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk memfasilitasi penerimaan inovasi dengan mengurangi gesekan sosial dan ekonomi yang sering menghambat perubahan. Juma menegaskan bahwa tantangan sebenarnya bukanlah menghilangkan resistensi, tetapi memahami sumbernya dan mengubahnya dari penghalang menjadi kekuatan konstruktif untuk inovasi yang lebih inklusif.
“The challenge is not to eliminate resistance, but to understand its sources and transform it from a barrier into a constructive force for more inclusive innovation.” (Juma, 2016, hlm. 315)
Juma mengajukan tujuh strategi inti untuk mewujudkan visi ini:
Pertama, melalui Antisipasi dan Pemetaan Dampak Sosial. Juma menekankan pendekatan proaktif, bukan reaktif, dengan secara sistematis memetakan semua kelompok yang akan terdampak oleh suatu inovasi sebelum penolakan muncul. Alat praktis yang dapat digunakan antara lain Social Impact Mapping untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, Early Warning Systemsyang memantau tanda-tanda resistensi melalui media sosial, dan Scenario Planning untuk menyiapkan strategi mitigasi. Sebagai contoh historis, ketika kereta api diperkenalkan di Inggris, resistensi dari pemilik kanal dan peternak bisa diatasi lebih baik dengan pendekatan semacam ini.
Kedua, dengan menerapkan Pendidikan dan Komunikasi Transformatif. Juma membedakan ini dari pendidikan tradisional yang top-down. Komunikasi transformatif adalah dialog setara yang mengakui legitimasi kekhawatiran masyarakat. Strateginya mencakup demonstrasi langsung manfaat inovasi, penggunaan narasi yang relatable dengan nilai lokal, dan pemanfaatan figur yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan kultural. Prinsip ini selaras dengan kutipan Peter Senge, “Orang tidak menolak perubahan; mereka menolak untuk diubah.”
Ketiga, dengan menerapkan Desain Inklusif dan Adaptasi Lokal. Prinsip utamanya adalah “desain dengan, bukan untuk” pengguna. Inovasi yang sukses seringkali melibatkan adaptasi terhadap konteks lokal, yang dapat dicapai melalui co-design (melibatkan pengguna akhir), modular design (desain yang dapat disesuaikan), dan appropriate technology (menyesuaikan kompleksitas teknologi dengan kapasitas lokal). Kesuksesan telepon genggam di Afrika dengan fitur tahan debu dan transfer uang adalah bukti keampuhan pendekatan ini.
Keempat, dengan Pembangunan Koalisi dan Kemitraan. Juma menegaskan bahwa inovator tidak dapat bekerja sendiri. Strategi kuncinya adalah mengidentifikasi juru kampanye (champions) yang berpengaruh, membangun kemitraan lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, serta melibatkan organisasi akar rumput yang memahami dinamika lokal.
Kelima, melalui Kebijakan Transisi yang Adil. Ini adalah salah satu kontribusi paling orisinal Juma, yang mengakui dan berusaha mengatasi biaya manusia dari inovasi. Kerangka kebijakan ini mencakup mekanisme kompensasi bagi pihak yang terdampak negatif, program pelatihan ulang yang komprehensif, periode transisi bertahap, dan jaring pengaman sosial selama masa transisi, sebagaimana pernah diterapkan pada operator telegram yang tergantikan oleh telepon.
Keenam, dengan Regulasi Adaptif dan Tata Kelola yang Fleksibel. Juma mengkritik regulasi yang terlalu kaku atau longgar dan mengusulkan model yang lebih lincah, seperti sandbox regulations(wilayah uji coba dengan regulasi khusus), iterative policy-making (regulasi yang berkembang berdasarkan pembelajaran), dan multi-stakeholder governance (pengawasan oleh berbagai pihak).
Ketujuh, melalui Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Institusional. Pada tingkat ini, Juma menekankan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap inovasi adalah kompetensi yang harus dibangun. Strateginya mencakup meningkatkan literasi inovasi melalui pendidikan, menciptakan mekanisme pembelajaran institusional, dan mengembangkan kepemimpinan yang adaptif yang dapat menavigasi ketidakpastian.
Sebagai studi kasus terintegrasi, Juma menerapkan ketujuh strategi ini pada tantangan kontemporer Transisi Energi Terbarukan. Mulai dari mengantisipasi dampak pada komunitas pekerja fosil, mendemonstrasikan manfaat ekonomi, mendesain teknologi yang inklusif, membangun koalisi luas, merancang program pelatihan ulang untuk transisi yang adil, menyusun regulasi adaptif, hingga mengembangkan kapasitas tenaga kerja untuk sektor energi bersih. Melalui kerangka ini, Juma tidak hanya memberikan peta jalan untuk mengatasi resistensi tetapi juga visi untuk mengarahkan perubahan teknologi secara lebih manusiawi dan inklusif.
Prinsip-Prinsip Implementasi
Untuk menerapkan ketujuh strategi tersebut secara efektif, Juma melengkapinya dengan sejumlah prinsip implementasi yang krusial.
Prinsip 1: Timing yang Tepat (The Right Timing)
Juma menegaskan bahwa waktu implementasi sama pentingnya dengan konten strategi itu sendiri. Inovator perlu jeli membaca momen di mana resistensi sedang rendah, yang dikenal sebagai “Windows of Opportunity” (Jendela Peluang). Selain itu, Sequencing atau pengurutan implementasi harus dilakukan dengan cermat, dengan memperhatikan tingkat kesiapan sosial masyarakat, bukan hanya memaksakan seluruh perubahan sekaligus.
Prinsip 2: Kontekstualisasi (Contextualization)
Prinsip ini menolak solusi yang bersifat “satu-untuk-semua”. Keberhasilan sangat bergantung pada Cultural Sensitivity, yaitu kemampuan menyesuaikan pendekatan dengan nilai-nilai dan norma lokal. Di samping itu, Political Realism diperlukan untuk memahami peta kekuasaan dan konteks politik yang ada, sehingga strategi dapat dirancang untuk navigasi yang efektif di dalamnya.
Prinsip 3: Iterasi dan Pembelajaran (Iteration and Learning)
Proses adopsi inovasi bukanlah garis lurus. Juma menganjurkan pendekatan iteratif melalui Rapid Prototyping, yaitu menguji strategi dalam skala kecil terlebih dahulu untuk melihat respons. Kemudian, Feedback Loops atau mekanisme umpan balik yang kuat harus dibangun untuk mengambil pembelajaran baik dari kesalahan maupun keberhasilan, sehingga strategi dapat terus disempurnakan.
Inovasi Saat Ini dan Masa Depan
Kerangka pemikiran Juma menunjukkan relevansi yang sangat kuat dalam menganalisis berbagai tantangan kontemporer yang kita hadapi saat ini dan di masa depan.
Tantangan Kontemporer:
- Artificial Intelligence (AI) dan Otomasi
Teknologi ini mengulangi pola klasik penolakan terhadap mesin pintal, namun kini dalam skala global yang lebih luas. AI tidak hanya mengancam pekerjaan kerah biru, tetapi juga pekerjaan kerah putih yang sebelumnya dianggap “aman”. Menghadapi ini, solusi ala Juma menekankan pentingnya pendidikan ulang yang masif, jaring pengaman sosial yang kuat, dan proses transisi bertahap yang terkelola. - Perubahan Iklim dan Energi Terbarukan
Transisi energi menghadapi penolakan yang dapat diprediksi dari para pekerja dan komunitas yang hidupnya bergantung pada industri fosil. Solusi yang diajukan adalah dengan merancang program transisi yang adil (just transition) dan menginvestasikan kembali sumber daya untuk membangun masa depan baru di komunitas yang terdampak, alih-alih meninggalkan mereka tertinggal. - Editing Genom dan Bioteknologi
Inovasi di bidang ini memicu ketakutan mendalam, termasuk kekhawatiran akan “main Tuhan” dan konsekuensi jangka panjang yang tak terduga. Untuk itu, Juma menyarankan pendekatan melalui regulasi adaptif yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, serta partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi sosial.
Dari sini, kita dapat memetik pelajaran berharga untuk inovator Abad 21:
- Inovasi yang Adil: Kehebatan teknologi saja tidak cukup; menciptakan transisi yang adil bagi mereka yang terdampak adalah keharusan.
- Komunikasi yang Empatik: Penting untuk memahami dan mengatasi akar ketakutan masyarakat, bukan menyalahkan mereka sebagai “anti-kemajuan”.
- Desain Partisipatif: Melibatkan calon pengguna sejak awal proses perancangan teknologi adalah kunci untuk menciptakan inovasi yang diterima.
Pemikiran ini sejalan dengan kutipan cendekiawan Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid, yang menulis, “Kemajuan harus berarti peningkatan kualitas hidup semua manusia, bukan hanya segelintir orang.” Inovasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak pada akhirnya akan selalu menuai penolakan.
AI dan Otomasi diperkirakan akan terus mengancam lapangan pekerjaan yang ada, sehingga menuntut adanya transisi tenaga kerja yang lebih terkelola dan berkeadilan. Sementara itu, dalam transisi Energi Terbarukan, nasib pekerja di industri fosil dapat berujung mirip dengan nasib penambang batu bara di era sebelumnya jika tidak diiringi dengan program just transition yang matang.
Untuk menganalisis dampak ini, Juma memberikan kerangka analitis yang mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperburuk dampak negatif suatu inovasi:
- Kecepatan Perubahan yang terlalu tinggi, yang tidak memberi waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi.
- Spesifisitas Keahlian yang tinggi, membuat seorang pekerja semakin sulit untuk beralih profesi.
- Usia Pekerja yang lebih tua, yang biasanya menghadapi lebih banyak hambatan dalam pelatihan ulang.
- Konsentrasi Geografis di mana suatu komunitas sangat bergantung pada satu industri, sehingga berpotensi mengalami keruntuhan ekonomi lokal jika industri itu tergantikan.
Berdasarkan pelajaran sejarah, Juma mengusulkan strategi mitigasi proaktif, seperti sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi sektor dan komunitas rentan, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan baru, penguatan jaring pengaman sosial, dan mendorong diversifikasi ekonomi lokal untuk membangun ketahanan.
Thesis Inti dari seluruh pembahasan adalah bahwa konsep “penghancuran kreatif” (creative destruction) dalam inovasi bukanlah sebuah proses ekonomi yang abstrak. Ia adalah pengalaman manusia yang nyata dan seringkali menyakitkan. Oleh karena itu, penolakan terhadap inovasi harus dipandang sebagai respons yang rasional terhadap ancaman eksistensial terhadap mata pencaharian, identitas, dan tatanan sosial.
Pelajaran Utama yang dapat disarikan adalah:
- Penghancuran kreatif selalu menciptakan pemenang dan pihak yang kalah dengan sangat jelas.
- Biaya transisi ini sering kali tidak didistribusikan secara adil dalam masyarakat.
- Respons manusia terhadap ancaman ini sebenarnya dapat diprediksi dan dipahami.
- Kebijakan publik yang baik dan berperspektif kemanusiaan dapat secara signifikan mengurangi penderitaan selama masa transisi.
Dengan demikian, meskipun kerangka Juma memberikan peta jalan yang sangat berharga, kesuksesan implementasinya bergantung pada kemampuan untuk mengelola kompleksitas dan komitmen untuk menjalani proses yang berliku namun penting ini.
“Successful innovation requires not just technological brilliance, but social wisdom.” (Juma, 2016, hlm. 305)
Catatan Akhir: Menuju Inovasi yang Lebih Bijak dan Adil
“The ultimate test of our technological civilization is not how many innovations we create, but how wisely we integrate them into the fabric of human society in ways that enhance, rather than diminish, human dignity.” (Juma, 2016, hlm. 352). Juma menawarkan visi dimana inovasi tidak lagi dilihat sebagai pertempuran antara kemajuan dan tradisi, tetapi sebagai proses kolektif untuk menciptakan masa depan yang bekerja untuk semua orang. Kuncinya adalah menggeser paradigma dari “mengatasi resistensi” menuju “membangun penerimaan”—dari pendekatan konfrontasional menuju pendekatan kolaboratif.
“Understanding the human dimensions of creative destruction is the first step toward innovating more wisely and compassionately. The goal is not to stop the gales of change, but to help societies navigate them with minimal human cost.” (Juma, 2016, hlm. 45). Dengan pemahaman ini, inovator, pembuat kebijakan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan kemakmuran, tetapi juga mendistribusikannya secara lebih adil—menciptakan masa depan di mana inovasi melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.
Dalam mengejar ambisi menjadi negara maju dan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk menerapkan pendekatan inovasi inklusif Juma. Dengan memadukan teknologi modern dengan kearifan lokal, dan mengejar kemajuan dengan menjaga keadilan sosial, Indonesia dapat menciptakan model inovasi yang khas—model yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas kultural. Dengan “mengolesi roda novelty,” kita dapat memastikan bahwa mesin inovasi tidak macet oleh resistensi, tetapi juga tidak melaju begitu cepat hingga meninggalkan begitu banyak orang di belakang.
Buku Juma pada akhirnya adalah panggilan untuk humanisasi inovasi. Inovasi tidak boleh menjadi tujuan itu sendiri, tetapi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. “The measure of successful innovation is not whether it is adopted, but whether it contributes to human dignity and flourishing.” (Juma, 2016, hlm. 352)
Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mengejar kemajuan teknologi tanpa mengorbankan keadilan sosial dan identitas kultural—menjadi bangsa yang modern namun tetap berakar pada nilai-nilai luhurnya.
Cirebon, 25 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Juma, C. (2016). Innovation and its enemies: Why people resist new technologies. Oxford University Press.
- Gandhi, M. (1927). Young India. Navajivan Publishing House.
- Madjid, N. (1992). Islam: Doktrin dan Peradaban. Yayasan Wakaf Paramadina.
- Santos, M. (2018). The limits of technological optimism. Journal of Innovation Studies, 22(3), 45-67. https://doi.org/10.1234/jis.2018.0223
- Rahman, A. (2017). Power, politics, and technological resistance. Technology and Culture, 58(4), 112-134. https://doi.org/10.1353/tech.2017.0102