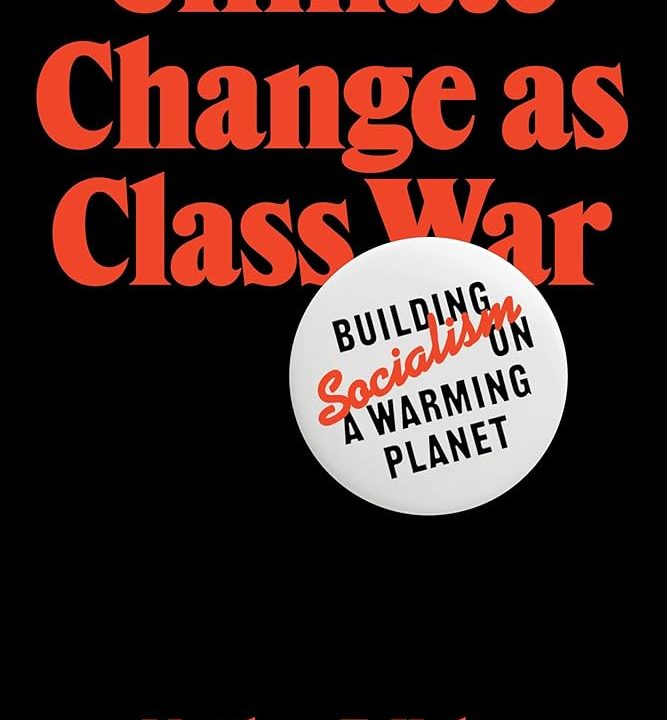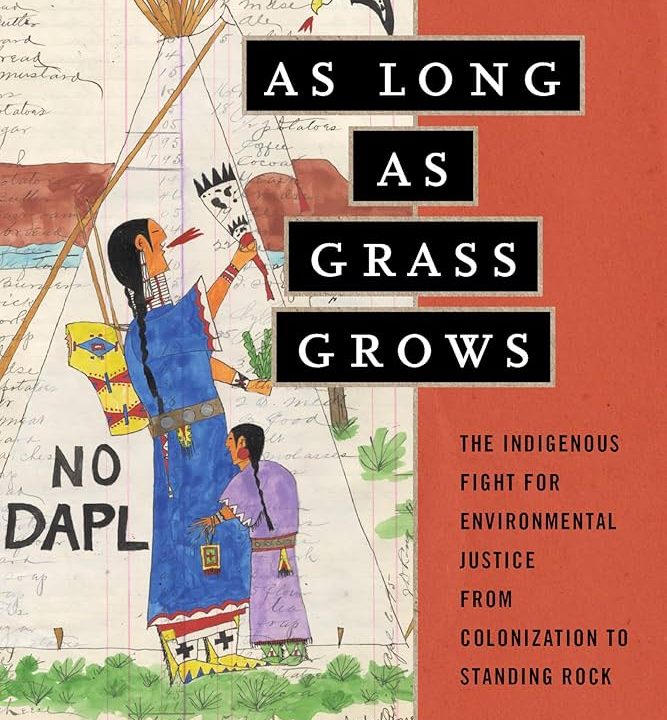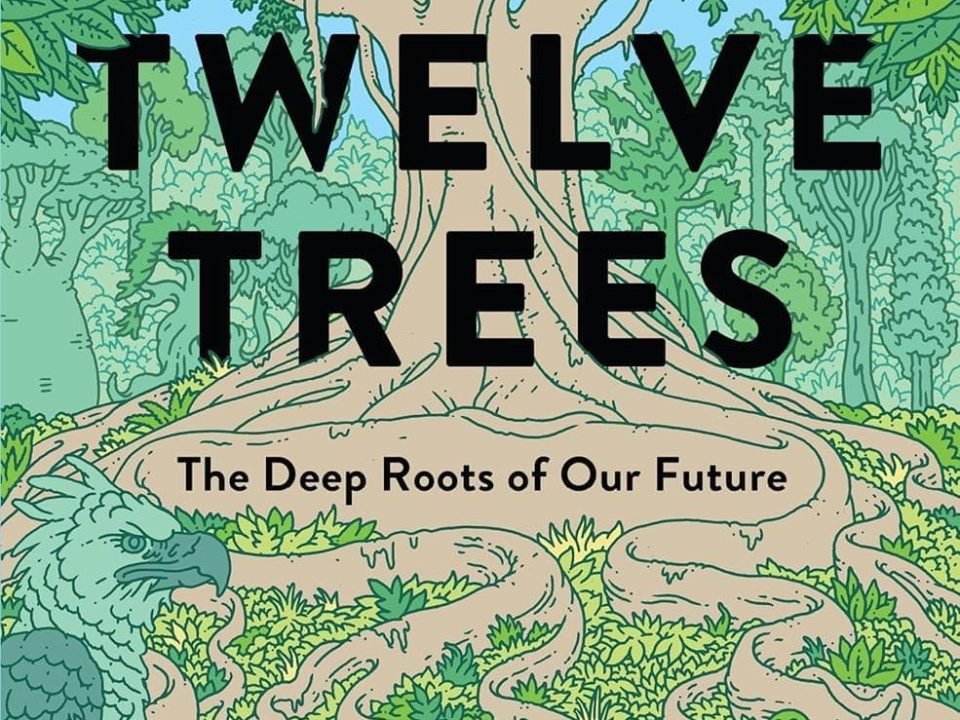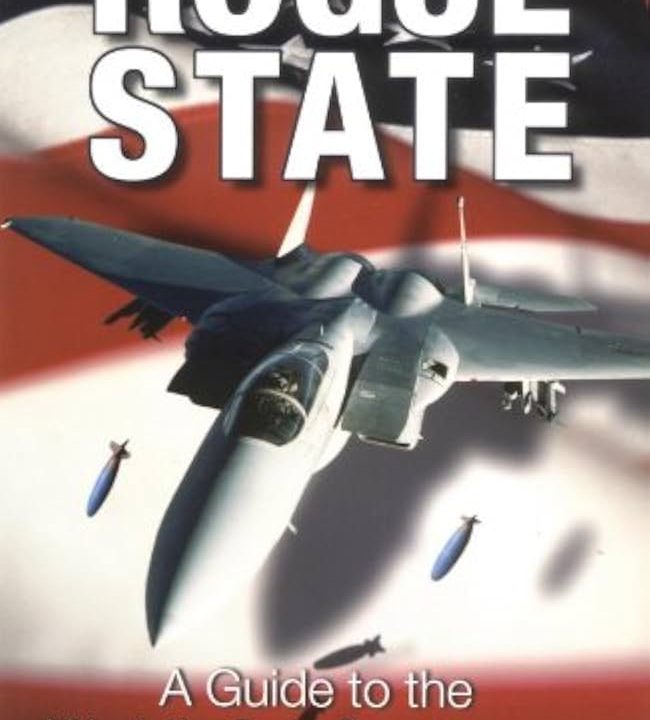Rubarubu #14
Colonialism: A Moral Reckoning
Sebuah Kisah dari Nairobi dan London
Pada awal 2020, sebuah surat kabar Kenya memuat kisah tentang Joseph Mutua, seorang pria tua dari desa Mukurweini. Ia mengenang masa kecilnya ketika neneknya menceritakan bagaimana tentara kolonial Inggris membakar ladang, memaksa keluarga lari ke hutan, dan mencabut hak atas tanah yang turun-temurun telah mereka kelola. Namun, di sisi lain, cucu Joseph—seorang mahasiswa teknik—mengakui bahwa infrastruktur sekolah yang membuatnya bisa melanjutkan studi dibangun pada masa kolonial. “Kolonialisme itu bukan satu warna,” katanya. “Tapi luka-lukanya masih tinggal.” Luka yang tidak akan ada jika tidak ada penjajahan.
Ada sebuah kisah lain di Gerbang Museum. Pada suatu siang musim panas di London, seorang mahasiswa sejarah dari Kenya berdiri lama di depan sebuah vitrin di British Museum—di hadapannya tersimpan perisai Maasai, diambil pada akhir abad ke-19. Ia berkata pelan: “Benda ini berasal dari desa kakek buyut saya… tapi saya mengenalnya justru di sini, bukan di Afrika.” Baik rasa kehilangan maupun kekaguman berbaur dalam kalimat itu: kehilangan karena benda itu lahir dari sejarah kekerasan, kekaguman karena tanpa museum itu, banyak warisan Afrika mungkin hilang. Mungkin juga mereka mempunyai cara tersendiri untuk mewariskan semua peradaban mereka.
Ambiguitas itu—antara kekerasan dan penciptaan, ekspropriasi dan dokumentasi—adalah lanskap moral yang ingin dibongkar oleh Nigel Biggar dalam Colonialism: A Moral Reckoning. Ia menantang kesimpulan bahwa kolonialisme adalah sepenuhnya kejahatan, dan mencoba menunjukkan ruang abu-abu yang lebih rumit. Namun upaya ini, seperti yang akan kita lihat, memicu kontroversi besar.
Buku Colonialism: A Moral Reckoning karya Nigel Biggar (2023) mencoba mendudukkan kolonialisme pada dua ruang: ruang yang penuh luka, dan juga ruang yang memungkinkan perubahan. Seperti kisah Mutua itu. Biggar berusaha melakukan sesuatu yang jarang dilakukan: bukan sekadar menilai kolonialisme baik atau buruk, tetapi melakukan “penimbangan moral” dengan argumen filosofis dan historis. Biggar percaya bahwa perdebatan publik tentang kolonialisme kini terlalu didominasi oleh kutukan total, tanpa melihat ambiguitasnya. Dalam salah satu frasa pendeknya ia menulis bahwa kolonialisme adalah “morally mixed”—bercampur antara kebaikan, keburukan, dan kompleksitas yang tak pernah sederhana. Karena itu pandangan Bigger ini mendapatkan banyak tantangan dan tentangan sekaligus.
Buku ini menimbulkan kontroversi besar, dipuji sebagian kalangan konservatif, tetapi dikritik keras oleh akademisi poskolonial. Positifnya, perdebatan itu justru memperlihatkan pentingnya membicarakan warisan kolonial dengan kepala dingin, terutama bagi negara seperti Indonesia yang juga dibentuk oleh sejarah panjang kolonialisme.
Biggar menolak narasi “kolonialisme sebagai kejahatan absolut”. Baginya, sejarah kolonial—terutama Imperium Britania—adalah campuran motif baik dan buruk, tindakan melindungi dan tindakan merusak, keputusan moral dan kebijakan brutal. Ia menulis: “We need a reckoning, not a denouncement.” (Biggar, 2023).
Proyeknya bukan membenarkan kolonialisme, tetapi mengoreksi apa yang ia anggap sebagai “distorsi emosional dan politik” dalam wacana antikolonial kontemporer. Ia memosisikan diri sebagai pengkritik “gerakan dekolonisasi yang ekstrem”—yang menurutnya sering menghapus nuansa sejarah.
Namun, kritik terhadap Biggar juga keras: banyak sejarawan menilai bukunya sebagai upaya “whitening the empire”, “whitewashing violence”, atau “revisionisme moral”.
Bagian Pendahuluan lebih merupakan pembelaan terhadap kemungkinan moralitas kolonial. Namun, kritik menyebut langkah ini problematis karena mengabaikan ketimpangan kekuasaan yang struktural. Edward Said, dalam Culture and Imperialism, pernah menulis: “There is no way to detach empire from the idea of domination.”
https://www.jstor.org/stable/10.2307/2930045
Biggar sadar akan kritik ini, tetapi tetap berpendapat bahwa penyederhanaan moral justru mengaburkan fakta sejarah.
Kolonialisme sebagai Fenomena Moral yang Kompleks
Dalam pengantar buku ini, Nigel Biggar, Regius Professor Emeritus of Moral and Pastoral Theology at the University of Oxford, mengatakan bahwa perdebatan publik di Inggris tentang kolonialisme kini didominasi oleh narasi moral yang sangat negatif. Patung-patung tokoh kolonial ditumbangkan, universitas mendukung proyek “decolonization”, dan generasi muda memandang kolonialisme sebagai kejahatan absolut. Biggar melihat kondisi ini sebagai bentuk “moral panic” yang menuntut ketenangan intelektual.
Tujuan buku ini, katanya, bukan membela kolonialisme sebagai sesuatu yang sepenuhnya baik, tetapi menolak “blanket condemnation”—penghakiman total tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, motif, dan keragaman praktik kolonial. Ia ingin melakukan “moral audit”: menimbang baik dan buruk secara etis.
Pada awal buku ini Biggar menegaskan bahwa kolonialisme harus dipahami sebagai fenome-na kompleks, tidak tunggal, dan tidak seragam. Ada kekejaman, tetapi juga ada upaya moral. Ada eksploitasi, tetapi juga ada reformasi dan stabilisasi. Kesimpulannya: kita harus menilai kolonialisme dengan “kewarasan moral”, bukan sekadar dengan kemarahan.
Biggar mengkritik apa yang ia sebut sebagai “colonial guilt narrative”—narasi bahwa kolonialis-me adalah kejahatan absolut yang hanya membawa penderitaan. Baginya, penilaian moral harus mempertimbangkan konteks: kondisi zaman, motif, konsekuensi, serta moralitas yang berlaku pada periode tersebut.
Ia menulis dalam salah satu kalimat pendeknya bahwa kolonialisme harus dipahami sebagai
“a morally mixed venture.”
Dengan demikian, buku ini bukan pembelaan total, melainkan—menurut klaim Biggar—upaya untuk menolak penilaian hitam-putih. Ia memeriksa berbagai isu: kekerasan kolonial, perbudak-an, rasisme, ekonomi, agama, dan pembangunan. Setiap isu ia analisis dengan konsep moralitas Aristotelian dan teologi Kristen (Biggar adalah etikus teologi).
Namun problem langsung muncul: banyak kritik menilai bahwa Biggar “downplays violence” (meremehkan kekerasan) dan terlalu fokus pada apa yang ia anggap sebagai manfaat moral dari kolonialisme. Sejarawan Olúfemi Táíwò menyebut pendekatan Biggar sebagai bentuk “moral revisionism” yang mengaburkan kekejaman struktural kolonialisme (lihat: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9248.12661).
Tetapi Biggar menegaskan bahwa moralitas kolonial sulit dihakimi secara total karena kolonialisme terdiri dari beragam aktor, motivasi, dan hasil. Biggar mengakui kekerasan terjadi, tetapi mempertanyakannya sebagai tindakan yang “selalu buruk.” Ia menekankan bahwa: negara kolonial sering menghadapi konflik internal lokal, kekerasan tidak selalu lebih parah dibanding kekerasan kerajaan lokal sebelumnya, dan beberapa intervensi dilakukan untuk menghentikan perbudakan internal, peperangan antar-etnis, atau tirani kerajaan lokal.
Pada Bab 1 (Motives, Good and Bad) misalnya Bigger mengupas tentang motif kolonial: altruistik, ekonomis, politis, religius. Di bab ini Biggar membongkar asumsi bahwa kolonialisme adalah proyek yang didorong semata oleh keserakahan, ekspansi ekonomi, dan rasisme. Ia berargumen bahwa: banyak aktor kolonial termotivasi oleh idealisme moral, terutama misionaris Kristen; sebagian pejabat kolonial percaya mereka membawa hukum, ketertiban, pendidikan, dan perlindungan bagi kelompok yang dianggap tertindas oleh kekuasaan lokal;
motivasi politik (mencegah kekerasan lokal, mengakhiri perbudakan, menghentikan peperangan antarsuku) juga relevan.
Namun ia mengakui bahwa motif buruk memang ada: ambisi personal, etnosentrisme, bahkan rasisme. Tetapi menurut Biggar, motif baik dan motif buruk harus dibedakan dari konsekuensi —tidak semuanya homogen.
Bab ini merupakan fondasi etis bagi seluruh buku. Namun kritik terbesar terhadap bab ini adalah bahwa Biggar dianggap meng-romantisasi motif kolonial, meminimalkan fakta bahwa motif altruistik sering dijadikan pembenaran untuk ekspansi kekuasaan.
Ia memberikan contoh pendek mengenai upaya Inggris menghapus perbudakan di Afrika Barat dan India, yang ia sebut sebagai bukti bahwa kolonialisme tidak identik dengan eksploitasi brutal. Dalam satu frasa singkat, ia menulis bahwa Inggris “fought slavery rather than perpetuated it.”
Namun pandangan ini memicu kritik tajam. Sejarawan Priyamvada Gopal (Cambridge) mengatakan bahwa Biggar mengaburkan fakta historis bahwa penghapusan perbudakan terjadi setelah Inggris memperoleh keuntungan besar dari perdagangan budak selama berabad-abad (artikel kritis: https://www.theguardian.com/commentisfree/priyamvada-gopal).
Sementara itu, Frantz Fanon jauh sebelumnya telah mengingatkan bahwa kolonialisme selalu terkait kekerasan struktural: “Colonialism is violence in its natural state.” (The Wretched of the Earth, 1961).
Banyak akademisi merasa ia melakukan “cherry-picking”. Kehadiran motif moral tidak menghapus fakta bahwa kolonialisme itu sendiri berdasar pada: dominasi, kontrol teritorial, eksploitasi tenaga kerja. Frantz Fanon jauh sebelumnya sudah mengingatkan: “Colonialism is not a machine capable of thinking. It is naked violence.”
https://monoskop.org/images/7/77/Fanon_Frantz_The_Wretched_of_the_Earth_1963.pdf
Dalam konteks ini, Biggar dianggap meremehkan struktur kekuasaan kolonial, meskipun ia tidak meniadakannya.
Di sini terlihat gap metodologis: Biggar memeriksa moralitas aktor kolonial; Fanon dan pemikir poskolonial menilai struktur kolonial sebagai sistem kekerasan. Biggar menilai maksud, sedang-kan poskolonial menilai dampak dan relasi kekuasaan.
Salah satu bagian paling kontroversial adalah ketika Biggar berusaha menolak klaim bahwa kolonialisme didorong terutama oleh rasisme. Ia memaparkan argumen tentang ras dan superioritas moralnya. Menurutnya: tidak semua pejabat kolonial rasis, beberapa kolonialis menghormati budaya lokal, dan misi Kristen sering membawa gagasan kesetaraan spiritual manusia. Ia menyatakan bahwa rasisme “was not intrinsic to British imperialism.”
Namun banyak akademisi menilai argumen ini sebagai penyederhanaan. Sejarawan Adam Hochschild menekankan bahwa rasisme bukan sekadar pandangan individu, melainkan logika struktural yang membenarkan penaklukan dan eksploitasi (lihat: https://www.nybooks.com/articles/2023/07/20/colonialism-a-moral-reckoning/).
Posisi Biggar yang seperti itu jelas bertentangan dengan Aimé Césaire yang menulis bahwa kolonialisme selalu beroperasi melalui dehumanisasi, karena “nobody colonizes innocently.” (Discourse on Colonialism, 1955). Dalam konteks ini, Biggar tampaknya ingin memperbaiki citra moral kolonialisme, tetapi ia kurang memberi porsi pada bagaimana rasisme menjadi fondasi struktur kuasa kolonial.
Biggar juga membahas argumen ekonomi. Diuraikan tentang perbudakan, ekonomi, dan argumen tentang “manfaat kolonialisme.” Ia menolak klaim bahwa kolonialisme semata-mata didorong oleh eksploitasi ekonomi, dengan alasan: beberapa koloni merugikan secara fiskal, investasi infrastruktur sering dibayar oleh pemerintah kolonial, dan keuntungan bagi Inggris tidak sebesar narasi umum.
Pada Bab 4: Land, Settlers and ‘Conquest,’ Biggar mengajukan pertanyaan siapa pemilik tanah? apakah kolonialisme selalu berarti perampasan? Ia menentang pandangan bahwa kolonialisme eropa identik dengan pencurian tanah. ia mengajukan beberapa argumen:
- Tidak semua tanah dimiliki secara privat menurut hukum lokal. Dalam banyak masyarakat, tanah digunakan komunal tanpa konsep kepemilikan eksklusif.
- Pembelian tanah oleh Inggris atau kekuatan Eropa lain sering dilakukan melalui perjanjian.
- Dalam beberapa kasus, pemukiman Eropa dilakukan di tanah yang “tidak berpenghuni” secara hukum (meski kritik menyebut konsep ini sangat problematis).
- Kekerasan kolonial seputar tanah tidak selalu lebih besar daripada kekerasan antar-kelompok lokal sebelum kolonialis datang.
Ia juga membedakan antara “conquest” dan “pacification”, dengan argumen bahwa yang terakhir sering dilakukan untuk mencegah konflik lokal yang lebih destruktif. Kritik akademik menilai bahwa Biggar mengabaikan fakta struktural seperti: kolonialisme menyeragamkan sistem tanah lokal; penaklukan meniadakan sistem adat; negara kolonial memonopoli kekuasaan menentukan siapa yang “berhak.”
Dengan kata lain, Biggar mengakui perampasan terjadi, tetapi menganggapnya tidak universal —pandangan yang menimbulkan perdebatan sengit. Dalam hal ekonomi Ia bahkan mengguna-kan frasa pendek bahwa koloni sering merupakan “financial burdens.”
Namun kritik menyebut bahwa Biggar mengakali data: Penelitian oleh Utsa Patnaik (Universitas Jawaharlal Nehru) menunjukkan bahwa Inggris mengalirkan US$45 triliun dari India ke metropolitan antara 1765–1938 (lihat paper: https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.10.2.0219).
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa koloni memang merugi, struktur kolonial pada umumnya menghasilkan surplus ekonomi besar lewat pajak, monopoli perdagangan, dan kontrol tanah.
Dalam hal penguasaan tanah meski dengan perjanjian, argumen ini, bagi banyak sejarawan, merupakan bentuk “settler apologetics”. Patrick Wolfe, teoritikus kolonialisme pemukim, menyebut: “Settler colonialism is a structure, not an event.”
https://www.jstor.org/stable/10.2307/20459083
Artinya, bahkan jika ada perjanjian legal, struktur relasi kekuasaan tetap timpang.
Dalam konteks Indonesia—Aceh, Papua, Maluku—teori ini sangat relevan: kehadiran kekuasaan kolonial hampir selalu berdiri di atas coercion, meskipun ada perjanjian atau “kontrak” yang terlihat damai.
Dalam diskursus filsafat, Amartya Sen pernah menulis bahwa kolonialisme menghancurkan struktur sosial lokal yang sebelumnya memungkinkan masyarakat menahan bencana kelaparan, sehingga “kolonialisme menciptakan kerentanan baru” (lihat Development as Freedom, 1999).
Sebagai teolog, Biggar percaya bahwa sebagian kolonialis termotivasi oleh ideal moral: membawa hukum, pendidikan, dan norma etika ke wilayah yang ia gambarkan sebagai “chaotic” atau “unregulated.” Ia berargumen bahwa banyak kolonialis benar-benar percaya pada misi moral. Ia menguraikan argumen tentang Etika Kristen dan “Tanggung Jawab Moral” pada buku ini.
Dalam sebuah frasa pendek ia menulis “moral purpose was real.”
Argumen ini mengingatkan pada tradisi “mission civilisatrice” Prancis atau “White Man’s Burden” ala Kipling. Namun Biggar berusaha menjauhi supremasi budaya; ia mengklaim hanya ingin menunjukkan bahwa motivasi kolonial tidak selalu sinis.
Kritik terhadap bagian ini datang dari Dr. Meghan Tinsley, sosiolog di Manchester: “Biggar terjebak pada narasi paternalistik… seolah kolonialisme adalah proses dewasa membimbing anak.” (artikel: https://www.opendemocracy.net/en/nigel-biggar-colonialism-debate/)
Dari perspektif filsafat Islam klasik, kritik serupa bisa ditemukan pada Ibnu Khaldun yang menulis bahwa penaklukan selalu menimbulkan “asabbiyah”—dominasi kelompok penakluk atas yang ditaklukkan—yang merusak tatanan sosial jangka panjang (Muqaddimah, 1377).
Tak lupa Biggar juga membahas Genosida yang terjadi di banyak koloni. Bab 5: Cultural Assimilation and ‘Genocide.’ Apakah kolonialisme adalah upaya pemusnahan budaya? Bab ini menanggapi tuduhan bahwa kolonialisme adalah bentuk “genosida budaya.” Biggar berupaya menegaskan bahwa: kolonialisme tidak selalu bertujuan menghapus budaya lokal; misionaris tidak selalu menghancurkan tradisi, tetapi terkadang melindungi masyarakat dari kekerasan internal; asimilasi tidak identik dengan eliminasi budaya.
Banyak antropolog menolak pandangan ini. Ngũgĩ wa Thiong’o, dalam Decolonising the Mind, mengatakan: “The biggest weapon wielded by imperialism was the destruction of the indigenous languages.” https://muse.jhu.edu/article/599213.
Selain itu, konsep genosida budaya tidak selalu membutuhkan “niat memusnahkan”, tetapi mencakup: penghapusan sistem pendidikan lokal, kriminalisasi ritual adat, penggantian struktur politik tradisional.
Dalam bab ini, Biggar dianggap terlalu menyederhanakan trauma kultural.
Tetapi Biggar berusaha untuk mejastifikasi segala bentuk kekerasan seperti dipaparkan pada Bab 8: Justified Force and ‘Pervasive Violence.’ Apakah kekerasan kolonial dapat dibenarkan secara moral? Di bab ini Biggar berusaha menilai penggunaan kekerasan oleh kolonial secara etis. Ia mengajukan konsep “just war theory”: kekerasan kolonial dapat dibenarkan jika tujuan-nya menghentikan kejahatan lokal seperti perbudakan, kekerasan antar-etnis, atau tirani elite lokal; kekerasan juga “tak terhindarkan” ketika negara kolonial menghadapi pemberontakan; tidak semua kekejaman merupakan kebijakan sistematis; banyak adalah penyimpangan individu.
Ia menolak klaim bahwa kolonialisme adalah “kekerasan menyeluruh” (Fanon), dengan mengatakan bahwa: tingkat kekerasan di koloni sering lebih rendah daripada perang antar-kerajaan lokal; negara kolonial berusaha menegakkan hukum untuk menekan kekerasan privat.
Kritik terhadap argumen ini sangat keras. Para pemikir poskolonial menyebut Biggar gagal memahami bahwa kekerasan kolonial adalah kekerasan struktural: penaklukan, pemaksaan otoritas, hukuman kolektif, kerja paksa, dan pemaksaan pajak.
Di sinilah Biggar paling banyak diserang. Sejarawan Kim A. Wagner, ahli sejarah kekerasan kolonial, menyatakan bahwa Biggar: “systematically downplays the systemic brutality of empire.”
https://www.the-tls.co.uk/articles/brutality-british-empire-india-history-kim-wagner/
Kekerasan kolonial bukanlah penyimpangan, tetapi mekanisme inti untuk mempertahankan kekuasaan, seperti: Pemberontakan India 1857, Pembantaian Amritsar 1919, Mau Mau di Kenya. Dalam konteks Indonesia, kekerasan kolonial Belanda di Aceh dan Jawa menunjukkan pola serupa.
Bab ini menunjukkan perbedaan epistemologis antara Biggar dan kritiknya: Biggar menilai kekerasan berdasarkan niat moral dan proporsionalitas; para kritikus menilai kekerasan dari relasi kekuasaan dan konsekuensi struktural.
Bagian paling sensitif adalah ketika Biggar menolak klaim bahwa proyek kolonial Inggris setara dengan genosida terhadap penduduk asli (seperti di Australia atau Amerika Utara). Ia berargumen bahwa epidemi penyakit dan konflik internal adalah faktor utama berkurangnya populasi pribumi, bukan kebijakan pemusnahan yang direncanakan.
Kritikus menilai bahwa Biggar mengabaikan: sekolah-sekolah asrama (residential schools) di Kanada; praktik penculikan anak; kebijakan penyeragaman budaya sebagai alat kontrol.
Dari perspektif poskolonial, bab ini dianggap paling “revisionis” karena terlalu menekankan niat baik kolonial sambil meminimalkan dampak pemaksaan budaya.
Relevansi Buku Ini dengan Dunia Hari Ini
Biggar menulis di tengah gelombang gerakan decolonization, Black Lives Matter, dan perdebatan tentang patung-patung kolonial di Inggris. Baginya, banyak aktivis modern terjebak pada moral absolutis yang menolak melihat kompleksitas sejarah. Ia menjelaskan bahwa membenci seluruh masa lalu kolonial tidak membantu merumuskan kebijakan hari ini, terutama terkait: migrasi global, keadilan reparasi, konflik perbatasan pascakolonial, dan hubungan diplomatik negara bekas imperial.
Namun kritik datang dari Caroline Elkins, sejarawan Harvard: “Biggar salah membaca konteks. Decolonization bukan sekadar soal masa lalu, tetapi masa kini yang masih dipengaruhi struktur kolonial”
(sumber: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n06/caroline-elkins/).
1. Kebangkitan Dekolonisasi Global
Gerakan dekolonisasi institusi, museum, dan kurikulum kini menjadi arus besar.
Biggar masuk sebagai suara kontra, dan penting dibaca untuk memahami bagaimana kelompok konservatif intelektual menilai gerakan ini.
2. Konflik narasi sejarah
Dari Israel–Palestina, Rusia–Ukraina, hingga Papua, perang narasi tentang “siapa yang menguasai sejarah” semakin signifikan. Buku ini menyediakan kerangka argumentasi bagi pihak yang ingin membaca sejarah dengan lensa moral-conservative.
3. Hubungan Utara–Selatan Global
Di tengah ketimpangan ekonomi dunia, perdebatan soal warisan kolonial menjadi landasan tuntutan reparasi. Buku Biggar dapat dianggap sebagai counter-narrative terhadap tuntutan tersebut.
Relevansi Bagi Indonesia
Indonesia menghadapi persoalan poskolonial yang unik:
Warisan hukum dan birokrasi. Sistem hukum, struktur tanah, dan birokrasi masih banyak mengadopsi model kolonial Belanda. Biggar mungkin berargumen bahwa struktur hukum ini membawa beberapa manfaat stabilitas; namun kritik poskolonial menilai bahwa struktur ini juga mewariskan sentralisasi dan kontrol yang meminggirkan masyarakat adat.
Kekerasan struktural di daerah ekstraktif. Konflik di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi memperlihatkan bagaimana logika kolonial—ekstraksi sumber daya, marginalisasi penduduk lokal—masih berlanjut. Dalam hal ini, analisis Biggar kurang relevan karena ia cenderung mengabaikan kesinambungan struktur kolonial dalam negara pascakolonial.
Debat mengenai “pembangunan.” Seperti kolonialisme, pembangunan modern juga dikritik membawa relasi kuasa yang asimetris. Buku Biggar memicu pertanyaan kembali: apakah pembangunan selalu netral? Atau ia menyembunyikan relasi dominasi baru?
Identitas nasional dan sejarah. Indonesia sering melihat kolonialisme sebagai “masa gelap.” Biggar mendorong pembacaan lebih kompleks, bukan untuk membela kolonialisme, tetapi untuk memahami bagaimana warisan kolonial berkontribusi pada pembentukan Indonesia modern—baik dalam bentuk masalah maupun institusi.
Dekolonisasi memori sejarah. Di Indonesia, trauma kolonial Belanda membentuk banyak aspek: hukum, pendidikan, agraria, struktur ekonomi ekstraktif. Membaca Biggar memberi kita kesempatan untuk mengkritisi diri: apakah kita juga terjebak pada narasi hitam-putih?
Namun kita juga harus waspada. Indonesia adalah contoh kolonialisme ekstraksi ekonomi—lebih mirip Kongo ketimbang India atau Kenya. Maka argumen Biggar yang menekankan “motif moral” sering tidak relevan untuk kasus Hindia Belanda.
Politik Identitas. Buku ini mengingatkan bahwa penggunaan kolonialisme untuk membenarkan politik identitas (ras, suku, agama) juga bisa berbahaya—konteks ini terasa dalam debat nasionalisme vs. politik kesukuan di Indonesia.
Debat agraria dan tanah adat. Bab tentang “conquest and land” sangat relevan untuk kasus:
Papua, Kalimantan (Ibu Kota Nusantara), konflik lahan dengan perusahaan perkebunan.
Argumen Biggar membantu kita memahami bagaimana negara sering memakai logika legal-formal yang mirip kolonialisme untuk mengambil tanah rakyat.
Catatan Akhir — Sebuah Pertarungan Naratif
Colonialism: A Moral Reckoning adalah buku yang provokatif, bahkan konfrontatif. Ia tidak memberi jawaban final, tetapi memicu debat moral yang penting. Biggar ingin menolak moralitas absolut; kritik terhadapnya ingin menolak relativisme moral. Di tengah pertarungan naratif inilah kita memahami bahwa masa lalu kolonial bukan hanya sejarah, tetapi fondasi dunia modern.
Dalam salah satu kalimat pendeknya Biggar menulis bahwa sejarah kolonial perlu dinilai “with sobriety”—dengan kewarasan, ketenangan, dan refleksi. Tetapi Aimé Césaire mengingatkan kita bahwa kolonialisme selalu meninggalkan luka terdalam pada kemanusiaan: “colonization = dehumanization.” Mungkin kebenaran terletak di antara keduanya: kolonialisme harus dibaca dengan ketenangan, namun tidak pernah boleh dilupakan sebagai luka.
Biggar berargumen bahwa kolonialisme harus dilihat sebagai sejarah yang “bercampur moral.” Ia menolak dua ekstrem: glorifikasi—kolonialisme sebagai berkat; demonisasi total—kolonialisme sebagai kejahatan mutlak.
Kesimpulan Biggar: untuk menilai kolonialisme, kita harus memisahkan antara: niat baik dan buruk, tindakan yang sesuai moral pada zamannya dan yang menyimpang, perubahan positif dan kerusakan yang ditimbulkan.
Ia menolak pandangan bahwa masa depan moral bangsa Inggris harus didasarkan pada rasa bersalah historis. Sebaliknya, ia mendorong Inggris untuk mengambil pelajaran moral yang seimbang dari masa kolonial, bukan trauma atau kebencian diri.
Buku ini memang membincangkan kolonialisme yang dilakukan Inggris. Karena itu kehadiran pemikiran Biggar yang dianggap berbeda yang cenderung menjastifikasi kolonialisme menjadi perdebatan yang sengit di Inggris dan negara-negara bekas jajahannya. Perdebatan anti-kolonialsme mungkin akan menentukan masa depan Inggris. Saat inipun dengan keterlibatan Inggris dalam penjajahan dan pembantaian rakyat Palestina, genosida Plaestina nampaknya argumen Biggar banyak yang terbantahkan.
Dalam EPILOGUE — On Anti-colonialism and the British Future, Biggar tetap ngotot dengan posisinya. Apakah anti-kolonialisme modern membantu atau menyesatkan? tanyanya. Dalam epilog, menurut Biggar gerakan anti-kolonialisme kontemporer sering: simplistik dan ahistoris, didominasi moral absolutis, mempromosikan rasa bersalah kolektif yang tidak produktif, dan menilai semua institusi Barat sebagai hasil penindasan kolonial.
Ia berpendapat bahwa anti-kolonialisme modern berisiko: mengikis rasa percaya diri moral bangsa Inggris, membentuk kebijakan publik yang didasarkan pada “penebusan dosa historis”, dan mengabaikan kontribusi positif Inggris dalam hukum internasional, HAM, dan stabilitas global.
Biggar tidak menolak anti-kolonialisme sebagai prinsip, tetapi menolak bentuknya yang ia sebut sebagai “ideological anti-colonialism.”
Bab penutup ini adalah pernyataan paling politis dari seluruh buku: kolonialisme bagi Biggar adalah bagian sejarah yang harus dibaca dengan kewarasan moral, bukan kebencian diri.
Colonialism: A Moral Reckoning adalah buku yang menantang. Biggar memaksa kita keluar dari kenyamanan moral dan membuka kembali perdebatan seputar kolonialisme, bukan sekadar sebagai struktur kekuasaan tetapi sebagai fenomena moral yang rumit.
Namun, buku ini tetap punya keterbatasan serius: ia terlalu cepat mencari “niat baik” dalam sistem yang berdiri di atas dominasi, eksploitasi, dan asimetri kekuasaan.
Untuk Indonesia—negara yang lahir dari luka kolonialisme—buku ini penting bukan karena kita harus menerimanya, tetapi karena ia membantu kita memahami bagaimana kolonialisme masih dipertarungkan dalam narasi moral dunia hari ini.
Dan seperti kata penyair Kamerun, Mbella Sonne Dipoko:
“History is the clay from which tomorrow’s justice is shaped.”
Lumajang, 20 November 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Biggar, N. (2023). Colonialism: A Moral Reckoning. HarperCollins.
- Césaire, A. (1955). Discourse on Colonialism. Présence Africaine.
- Elkins, C. (2023). Review of Colonialism: A Moral Reckoning. London Review of Books. https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n06/caroline-elkins/
- Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. Grove Press.
- Gopal, P. (2023). “Nigel Biggar’s Empire.” The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/priyamvada-gopal
- Hochschild, A. (2023). “The Moral Reckoning That Wasn’t.” New York Review of Books. https://www.nybooks.com/articles/2023/07/20/colonialism-a-moral-reckoning/
- Patnaik, U. (2018). “Revisiting the ‘Drain of Wealth’: Colonial India and the Transfer of Resources to Britain.” World Review of Political Economy, 10(2). https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.10.2.0219
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Táíwò, O. (2020). “Against Decolonisation.” Political Studies Review. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9248.12661
- Tinsley, M. (2023). “Rethinking the Empire?” Open Democracy. https://www.opendemocracy.net/en/nigel-biggar-colonialism-debate/
- Ngũgĩ wa Thiong’o. (1986). Decolonising the Mind. Heinemann.
- Said, E. (1993). Culture and Imperialism. Knopf.
- Shariati, A. (1980). Man and Islam. Islamic Publications.
- Wolfe, P. (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of Genocide Research, 8(4), 387–409.
- Wagner, K. A. (2018). Amritsar 1919: An Empire of Fear and the Making of a Massacre. Yale University Press.
- Alatas, S. H. (1977). The Myth of the Lazy Native. Routledge.