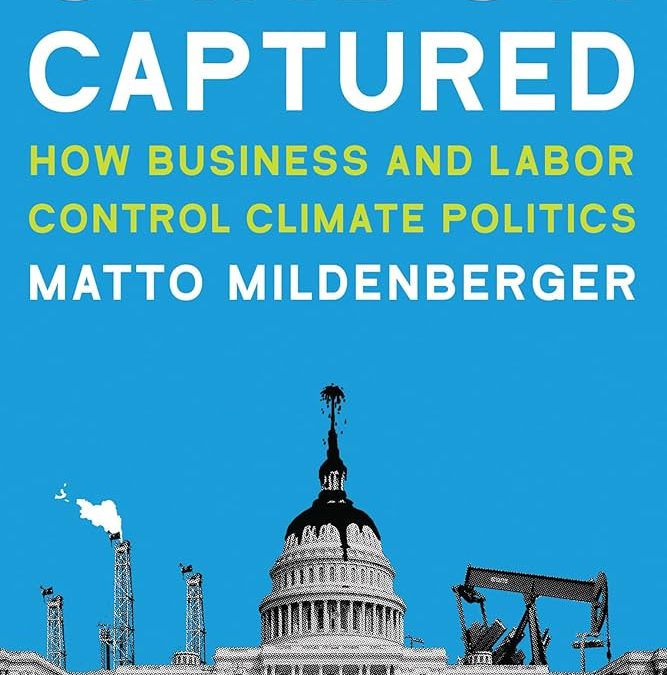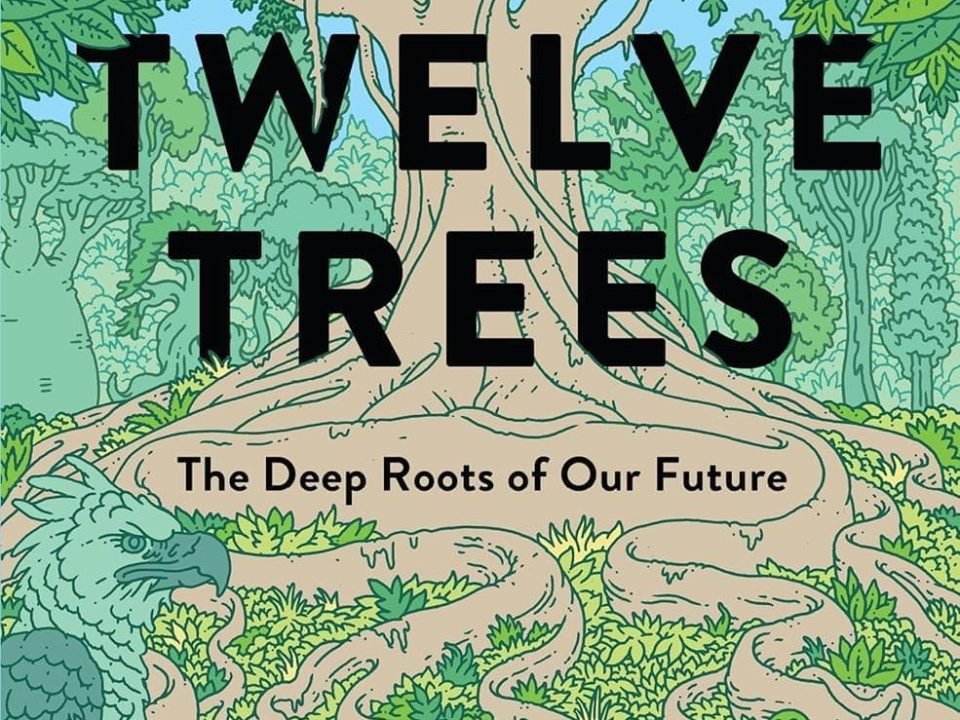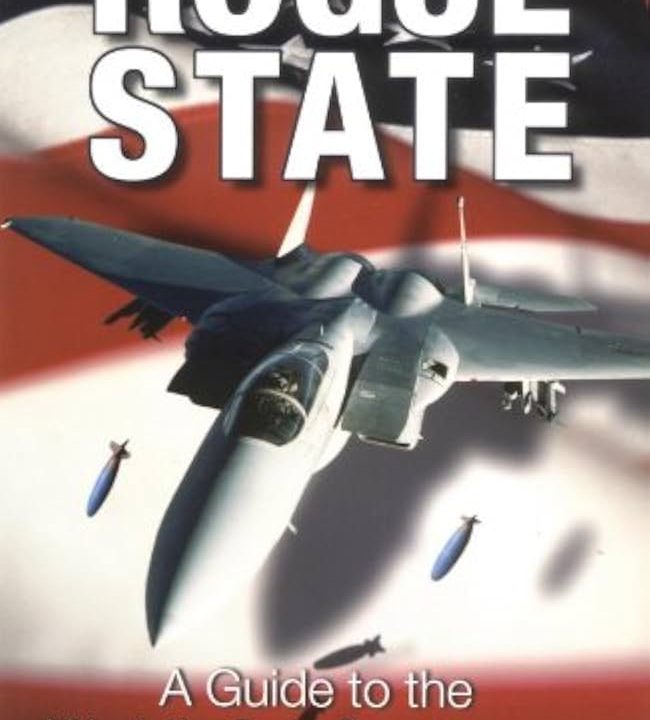Rubarubu #68
Carbon Captured:
Politik Mengendalikan Perubahan Iklim
Pada suatu hari musim dingin di sebuah kota tambang batu bara di AS, seorang operator shift tua menghitung jam kerjanya sambil mendengarkan berita tentang perjanjian iklim internasional yang dibahas jauh di Washington. Ia tahu: jika regulasi benar-benar diterapkan, pekerja seperti dia bisa dipindahkan, tambang bisa ditutup, keluarganya bisa kehilangan mata pencaharian. Namun di sisi lain, ilmuwan memperingatkan bahwa batu bara-dan fosil lainnya adalah penyumbang besar pemanasan global. Kisah ini menggambarkan dilema struktural yang diangkat dalam buku: bukan hanya soal teknis emisi, tetapi soal bagaimana bisnis dan serikat pekerja (labor) membentuk politik iklim — siapa yang diwakili, siapa yang diabaikan, siapa untung dan siapa rugi. Mildenberger menulis bahwa perubahan iklim bukan semata-masalah kolektif antar negara, tetapi masalah politik domestik: “global warming legislation has failed because of political fractures within countries.” Chicago Policy Review+2Taylor & Francis Online+2
Pada awal buku Carbon Captured: How Business and Labor Control Climate Politics (MIT Press, 2020), Mildenberger mengajak pembaca masuk ke dalam sebuah paradoks politik yang tampak sederhana namun membingungkan: mengapa kebijakan iklim yang tegas begitu sulit diwujudkan, padahal ancaman perubahan iklim sudah lama diketahui, didukung oleh sains yang kuat, dan secara luas diakui publik sebagai masalah serius? Ini bukan sekadar soal kurangnya pengetahuan, atau ketidakpedulian warga. Justru sebaliknya—kesadaran publik meningkat, retorika politik semakin hijau, dan pertemuan internasional terus berlangsung. Namun kebijakan yang benar-benar mengurangi emisi secara signifikan tetap tertahan, melemah, atau tertunda.
Mildenberger menyebut kondisi ini sebagai sebuah puzzle: kegagalan aksi iklim bukanlah akibat dari ketiadaan dukungan umum, melainkan dari cara kekuasaan terorganisasi dalam sistem politik modern. Ia menunjukkan bahwa dalam demokrasi kontemporer, kebijakan tidak hanya dibentuk oleh preferensi mayoritas pemilih, tetapi oleh struktur representasi yang jauh lebih kompleks dan timpang. Di sinilah ia mulai menggeser fokus dari “apa yang diinginkan publik” ke “siapa yang benar-benar didengar secara konsisten oleh pembuat kebijakan”. Narasi kemudian bergerak ke dunia aktor-aktor yang sering luput dari perhatian publik luas, namun sangat dekat dengan pusat pengambilan keputusan: kelompok bisnis dan serikat pekerja. Kedua kelompok ini, meskipun sering dipersepsikan sebagai pihak yang saling berseberangan, justru menempati posisi yang sangat strategis dalam politik iklim. Mereka memiliki kapasitas organisasi, sumber daya, keahlian teknis, dan—yang terpenting—hubungan rutin dengan negara. Berbeda dengan warga biasa yang “hadir” terutama saat pemilu, kelompok-kelompok ini hadir setiap hari dalam proses legislasi, regulasi, dan perumusan kebijakan.
Mildenberger menguraikan kerangka teori utama: yaitu konsep double representation — bahwa aktor industri yang intensif karbon memiliki representasi kuat di kedua sisi politik: di kiri lewat serikat pekerja industri (yang khawatir kehilangan pekerjaan) dan di kanan lewat asosiasi bisnis besar (yang khawatir biaya regulasi). Chicago Policy Review+1 Dia kemudian menempat-kan variabel-institusional seperti “corporatist vs pluralist” politik nasional, dan bagaimana ke-terkaitan serikat pekerja dengan partai politik kiri memengaruhi kapasitas legislasi iklim. Di bagian ini, Mildenberger juga mulai membedah perjalanan kebijakan iklim di AS, Norwegia, dan Australia sebagai studi kasus utama, dan menjelaskan bahwa perbedaan lintas negara dapat dijelaskan dengan interaksi institusi politik dan kepentingan karbon. MIT Press+1
Di sinilah Mildenberger memperkenalkan gagasan kunci yang menjadi fondasi teoritis buku ini: logika “double representation”. Dalam demokrasi modern, politisi tidak hanya mewakili warga sebagai pemilih, tetapi juga secara simultan mewakili—dan bergantung pada—aktor-aktor terorganisasi dalam ekonomi politik. Perusahaan besar dan serikat pekerja tidak hanya menjadi objek kebijakan; mereka adalah co-governors de facto. Negara membutuhkan mereka untuk investasi, lapangan kerja, stabilitas ekonomi, dan legitimasi sosial. Akibatnya, kepenting-an mereka terwakili secara struktural, bahkan ketika tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang publik atau planet.
Logika representasi ganda ini menciptakan ketegangan laten dalam politik iklim. Di satu sisi, publik menginginkan lingkungan yang aman dan masa depan yang berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan iklim yang ambisius sering kali mengancam model bisnis yang ada atau pekerjaan di sektor-sektor intensif karbon. Politisi, yang terjebak di antara dua tuntutan ini, cenderung memilih jalan tengah yang aman secara politik: kebijakan simbolik, target jangka panjang tanpa mekanisme keras, atau pengecualian-pengecualian yang melemahkan efektivitas kebijakan.
Mildenberger menolak penjelasan simplistis yang menyalahkan “keserakahan korporasi” semata. Ia menunjukkan bahwa bahkan serikat pekerja—yang secara historis memperjuangkan keadilan sosial—sering kali bersikap ambivalen atau bahkan menentang kebijakan iklim yang ketat jika dianggap mengancam pekerjaan anggotanya. Dengan demikian, kebuntuan iklim bukan hanya hasil dari dominasi modal, tetapi dari koalisi implisit antara stabilitas ekonomi jangka pendek dan struktur representasi politik yang bias terhadap status quo.
Alur narasi dua bab ini akhirnya membawa pembaca pada kesimpulan yang tidak nyaman: kegagalan aksi iklim bukanlah kecelakaan, melainkan hasil rasional dari sistem politik yang bekerja sebagaimana dirancangnya. Demokrasi liberal, dalam bentuknya saat ini, sangat responsif terhadap aktor yang terorganisasi dan memiliki kepentingan material langsung, namun jauh lebih lemah dalam merespons ancaman jangka panjang yang bersifat difus, seperti perubahan iklim.
Dengan membuka buku melalui dua bab ini, Mildenberger tidak hanya menjelaskan mengapa kebijakan iklim tersendat, tetapi juga mempersiapkan panggung analitis untuk pertanyaan yang lebih besar: bagaimana politik iklim bisa diubah jika masalah utamanya bukan kurangnya niat, melainkan struktur representasi itu sendiri? Di titik inilah Carbon Captured mulai menunjukkan dirinya bukan sekadar kritik, melainkan undangan untuk memikirkan ulang hubungan antara demokrasi, ekonomi, dan masa depan ekologis umat manusia.
Setelah menguraikan logika dasar double representation, Mildenberger membawa pembaca keluar dari ranah teori menuju medan empiris: politik iklim sebagaimana ia benar-benar berlangsung di negara-negara demokratis. Di sinilah buku ini berubah menjadi semacam perjalanan perbandingan lintas negara, memperlihatkan bagaimana struktur representasi yang sama dapat menghasilkan hasil kebijakan yang sangat berbeda—mulai dari kerja sama relatif harmonis hingga konflik terbuka yang melumpuhkan kebijakan iklim selama puluhan tahun.
Narasi pertama berhenti di Norwegia, sebuah negara yang sering dipuji sebagai teladan kebijakan iklim progresif. Namun Mildenberger tidak tertarik pada mitos keberhasilan semata.
Ia justru membedah bagaimana kerja sama kebijakan iklim di Norwegia dimungkinkan karena penataan ulang hubungan antara negara, bisnis, dan buruh. Di sana, sektor energi—termasuk industri minyak dan gas—tidak sepenuhnya berada di luar negara, melainkan terintegrasi ke dalam kerangka perencanaan nasional. Serikat pekerja memiliki kursi dalam proses transisi, bukan sebagai pihak yang harus dikorbankan, melainkan sebagai mitra yang dijamin masa depannya. Dengan kata lain, double representation tidak dihapus, tetapi dikelola dan dinego-siasikan secara terbuka, sehingga konflik laten dapat diredam sebelum berubah menjadi veto politik.
Dari Norwegia, kisah berpindah ke Amerika Serikat—contoh paling tajam tentang bagaimana logika representasi ganda dapat melumpuhkan aksi iklim. Dalam periode panjang sejak akhir 1980-an hingga pertengahan 2000-an, Mildenberger menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan iklim AS bukan disebabkan oleh penyangkalan sains semata. Justru pada periode awal, elite politik AS relatif sadar akan ancaman perubahan iklim. Namun kesadaran ini bertabrakan dengan struktur ekonomi-politik yang sangat terfragmentasi. Industri energi fosil yang kuat, serikat pekerja yang terikat pada sektor-sektor intensif karbon, serta sistem politik dengan banyak titik veto menciptakan kondisi di mana setiap upaya kebijakan iklim signifikan dapat dihentikan sebelum mencapai tahap implementasi.
Buku memaparkan perjalanan historis nasional: Mildenberger membahas bagai-mana kebijakan iklim muncul di AS sejak akhir 1980-an, bagaimana awalnya tampak momen-tum (misalnya kesaksian ilmuwan di Senat), tetapi kemudian tersendat. Ia menunjukkan bahwa bukan hanya industri saja yang menolak, tetapi juga serikat pekerja yang bergantung pada industri fosil ikut menekan agar regulasi dilunakkan. Chicago Policy Review Di Norwegia, ia menunjukkan bagaimana skandinavian model yang korporatis melindungi industri minyak & gas domestik meskipun menerapkan pajak karbon—yakni dengan pengecualian khusus dan subsidi terselubung, yang menunjukkan bahwa kepentingan pekerja dan bisnis tetap dipertahankan. Australia menjadi contoh bagaimana skema trading emisi bisa diadopsi dan kemudian dibatalkan ketika perubahan politik terjadi. Melalui bagian ini pembaca melihat bahwa pola kelembagaan dan representasi politik sangat menentukan hasil kebijakan, bukan semata niat bagus.
Mildenberger juga mendalami variabel institusional lain: misalnya kehadiran partai kiri yang kuat dan hubungan mereka dengan serikat pekerja, serta bagaimana hal itu memengaruhi apakah politik iklim akan maju atau tertahan. Ia meneliti bagaimana dalam sistem politik “pluralist” yang terbuka ada konflik terbuka antara bisnis karbon dan masyarakat sipil, sementara dalam sistem “korporatis” dominasi institusi pekerja + bisnis membuat kompromi lebih mungkin — namun sering menghasilkan kebijakan lemah. Review mengamati bahwa “the idea of a country’s level of corporatism vs pluralism … strongly influence what kind of policy trajectory the country takes.” Amateur Earthling Ia juga menggarisbawahi bahwa kapasitas regulasi bukan hanya soal teknologi atau ekonomi, tetapi soal kekuatan politik: siapa yang dapat veto, siapa yang dimarginalisasi, dan siapa yang membayar biayanya.
Pada bagian 4, buku mengkaji secara sistematis instrumen kebijakan iklim: pajak karbon, perdagangan emisi, mandat energi bersih, subsidi terbarukan, dan regulasi efisiensi. Mildenberger menegaskan bahwa banyak debat memperlakukan pajak karbon sebagai “solusi teknis” utama, tetapi ia menilai bahwa secara politik pajak sulit diterapkan jika pekerja dan bisnis besar dominan menolak. Sebaliknya, ia mendukung instrumen yang lebih mudah diterima politik seperti mandat energi bersih atau investasi publik dalam teknologi baru yang dapat membuat aliansi bisnis–pekerja. Observasi itu menunjukkan bahwa kebijakan yang “minimal biayanya bagi bisnis karbon” lebih layak secara politik, meskipun mungkin kurang optimal dari perspektif teknis. Kritik terhadap buku juga menyebut bahwa meskipun instrumen yang diperkenalkan realistik secara politik, mereka mungkin kurang cukup untuk perubahan cepat yang diperlukan. Chicago Policy Review+1
Mildenberger menampilkan studi kasus mendalam dan perbandingan lintas negara: AS, Norwegia, Australia, serta diskusi singkat tentang Jerman, Inggris, Jepang, dan Kanada. Di bagian ini dia menyajikan data historis, wawancara dengan lebih dari 100 pembuat kebijakan, pelobi, pekerja, serikat, dan menunjukkan bagaimana di tiap negara pola double representation muncul dan menghambat atau memutarbalikkan kebijakan. JSTOR Dia juga menggunakan grafik dan ilustrasi untuk menunjukkan bahwa negara-dengan institusi tertentu (mis. Norwegia) punya hasil kebijakan yang lebih lambat namun lebih stabil dibandingkan negara yang institusinya lebih terbuka (mis. AS) yang punya fluktuasi tinggi. Dari perspektif pembaca Indonesia, aspek komparatif ini penting sebagai pelajaran: institusi dan kekuatan politik lokal menentukan apakah regulasi iklim akan berhasil atau gagal.
Yang menarik, Mildenberger menolak narasi bahwa Amerika Serikat “tidak pernah bertindak”. Ia menunjukkan pergeseran penting pada periode 2007–2015, ketika kebijakan iklim mulai bergerak—meski tetap rapuh dan tidak konsisten. Perubahan ini bukan karena tiba-tiba struktur double representation lenyap, melainkan karena sebagian aktor ekonomi mulai melihat peluang dalam transisi energi. Munculnya industri energi terbarukan, perubahan kepentingan di tingkat negara bagian, serta restrukturisasi koalisi politik membuka celah bagi kebijakan iklim. Namun celah ini tetap terbatas, bergantung pada kompromi, dan mudah dibalik—sebuah pelajaran pahit tentang betapa rentannya kemajuan iklim jika tidak disertai perubahan struktural yang lebih dalam.
Dari Amerika, cerita kemudian berbelok ke Australia—sebuah studi tentang konflik iklim yang nyaris kronis. Di sini, double representation tidak dikelola atau dinegosiasikan, melainkan dipolitisasi secara ekstrem. Industri batu bara dan aktor politik konservatif berhasil membingkai kebijakan iklim sebagai ancaman langsung terhadap pekerjaan, identitas nasional, dan kedaulatan ekonomi. Serikat pekerja terbelah, negara kehilangan kapasitas mediasi, dan kebijakan iklim menjadi simbol perang budaya. Dalam konteks ini, Mildenberger menunjukkan bagaimana logika representasi ganda dapat berubah dari ketegangan laten menjadi konflik terbuka yang menghancurkan stabilitas kebijakan jangka panjang.
Setelah mengurai tiga konteks nasional yang sangat berbeda, Mildenberger berhenti sejenak untuk menguji pertanyaan yang lebih luas: apakah teori ini berlaku secara umum? Ia tidak mengklaim universalitas sederhana. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa double representation adalah kecenderungan struktural dalam demokrasi kapitalis, tetapi hasil akhirnya bergantung pada institusi, sejarah, dan kapasitas negara untuk menengahi konflik. Di negara dengan negara kesejahteraan kuat dan dialog sosial mapan, logika ini dapat dikelola. Di negara dengan polarisasi tinggi dan ekonomi politik yang terfragmentasi, ia menjadi sumber kebuntuan permanen.
Pada bagian 6, buku beralih ke implikasi politik dan strategi untuk masa depan: Mildenberger mengajukan bahwa agar aksi iklim berhasil, perlu dibangun koalisi yang menggabungkan pekerja yang terdampak (yang bergantung pada industri karbon) dengan sektor terbarukan atau teknologi bersih — apa yang disebut “just transition” dalam praktik. Dia memperingatkan bahwa hanya menyasar industri karbon tanpa memberikan jalan untuk pekerja akan menciptakan resistensi politik yang besar. Bahwa contoh aliansi seperti “BlueGreen Alliance” di AS menunjukkan bahwa memasukkan hak pekerja dan penciptaan lapangan kerja baru bisa menjadi kunci. Chicago Policy Review Untuk Indonesia, ini relevan: tenaga kerja batubara dan minyak banyak, maka strategi transisi harus mencakup perlindungan sosial, pelatihan ulang, dan diversifikasi ekonomi agar tidak menciptakan “winners and losers” yang ekstrem.
Kemudian Mildenberger menyoroti bahwa banyak wacana iklim masih terjebak pada premis “kolektif global” (free-rider antara negara) dan menegaskan bahwa akar penyebab adalah politik domestik dan aliansi yang lemah. anthemenviroexperts.com+1 Ia juga membahas bahwa teknologi seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) atau perdagangan karbon sering dijual sebagai solusi yang murah secara ekonomi, namun bisa jadi alat tunda yang memper-tahankan status quo industri fosil. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa perubahan struktur kekuasaan—bukan hanya instrumen teknis—adalah inti dari politik iklim. Sebagai kutipan pendukung: “Solutions that ignore power are doomed to reinforce what they intend to dismantle.” (Parafrase dari argumentasi buku) — ini mengingatkan kita pada pemikiran filosof Michel Foucault tentang kekuasaan: “Where there is power, there is resistance.” (Foucault). Dan dari perspektif etika Islam, misalnya pemikir seperti Fazlun Khalid mengingatkan bahwa konsep khalifahdan amanah dalam Islam menuntut bahwa manusia bertanggung-jawab atas ciptaan—yang berarti bahwa kebijakan iklim harus adil dan inklusif, bukan hanya efisiensi ekonomi.
Puncak analisis ini terletak pada bab tentang bagaimana logika representasi ganda dapat diganggu atau diubah. Mildenberger tidak menawarkan solusi teknokratis sederhana. Ia justru menekankan pentingnya perubahan politik yang lebih mendasar: memperluas basis koalisi iklim, menciptakan jaminan transisi bagi pekerja, membangun institusi yang mampu menyerap konflik distribusional, dan—yang paling sulit—mengubah relasi kekuasaan antara negara dan aktor ekonomi dominan. Aksi iklim yang efektif, dalam pandangan ini, bukan soal persuasi moral semata, melainkan soal membangun ulang siapa yang diwakili, kapan, dan dengan konsekuensi apa.
Dengan demikian, bagian tengah Carbon Captured ini memperlihatkan bahwa politik iklim bukanlah cerita tentang kegagalan kemauan, melainkan drama struktural tentang representasi, konflik, dan kemungkinan perubahan. Ia mengajarkan bahwa masa depan kebijakan iklim tidak akan ditentukan oleh satu konferensi global atau satu teknologi terobosan, melainkan oleh kemampuan masyarakat untuk merombak logika politik yang selama ini membuat planet menjadi pihak yang paling tidak terwakili.
Krisis Iklim adalah Krisis Demokrasi
Perubahan iklim sering dibicarakan sebagai krisis sains atau krisis teknologi, tetapi Carbon Captured dengan tenang dan tajam menunjukkan bahwa ia pada dasarnya adalah krisis demokrasi. Bukan karena demokrasi gagal mendengar suara rakyat, melainkan karena suara yang paling sering didengar bukanlah suara rakyat biasa atau bahkan suara masa depan, melainkan suara aktor-aktor ekonomi yang terorganisasi dan dekat dengan negara. Di sinilah krisis iklim bertemu dengan krisis representasi.
Mildenberger menamai struktur ini sebagai logika “double representation”: dalam demokrasi modern, politisi tidak hanya mewakili warga sebagai pemilih, tetapi juga mewakili—dan bergantung pada—kepentingan bisnis dan buruh yang terorganisasi. Negara membutuhkan investasi, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi; sebagai imbalannya, negara memberi akses istimewa pada proses pembuatan kebijakan. Iklim, yang tidak memiliki serikat, tidak memiliki lobi, dan tidak memberikan suara dalam pemilu, menjadi pihak yang paling tidak terwakili.
Kerangka ini sangat relevan untuk membaca politik iklim Indonesia. Indonesia sering menyatakan komitmen terhadap penurunan emisi, transisi energi, dan pembangunan hijau. Namun pada saat yang sama, batubara tetap menjadi tulang punggung ekonomi energi dan ekspor, serta fondasi politik pembangunan daerah. Dalam konteks ini, batubara bukan sekadar komoditas; ia adalah aktor politik. Ia mempekerjakan ratusan ribu pekerja, menopang PAD daerah, menghidupi rantai bisnis lokal, dan terhubung erat dengan elite politik nasional maupun daerah. Di sinilah logika representasi ganda bekerja secara telanjang.
Seperti kasus Amerika Serikat dan Australia yang dianalisis Mildenberger, Indonesia menunjukkan pola serupa: kesadaran iklim meningkat, tetapi kebijakan struktural tertahan. Pemerintah berbicara tentang net-zero, sementara PLTU baru masih direncanakan atau dipertahankan melalui skema perpanjangan usia. Ini bukan semata soal inkonsistensi moral, melainkan tentang siapa yang diwakili secara nyata dalam pengambilan keputusan.
Peran buruh menjadi simpul penting dalam dilema ini. Serikat pekerja di sektor energi fosil sering diposisikan sebagai penghambat transisi, padahal sesungguhnya mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap transisi yang tidak adil. Carbon Captured menunjukkan bahwa kebijakan iklim cenderung gagal ketika buruh diperlakukan sebagai korban tak terelakkan, bukan sebagai subjek politik yang harus dijamin masa depannya.
Di Indonesia, narasi “jangan korbankan buruh demi iklim” sering digunakan untuk memper-tahankan status quo—tanpa pernah benar-benar menawarkan jalan keluar yang adil bagi buruh itu sendiri. BUMN energi, terutama PLN dan perusahaan tambang negara, memperumit lanskap ini. Sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen negara, BUMN menjadi perwujudan paling nyata dari representasi ganda. Mereka harus menjaga kesehatan finansial, menyediakan energi murah, mempertahankan pekerjaan, dan sekaligus menjalankan agenda iklim. Ketegang-an ini sering berakhir pada kompromi setengah hati: transisi dilakukan secara retoris, tetapi ditunda secara struktural. Dalam bahasa Mildenberger, logika representasi ganda tidak diredam, melainkan dibekukan dalam kebijakan ambigu.
Pelajaran penting dari kasus Norwegia dalam Carbon Captured adalah bahwa keberhasilan relatif kebijakan iklim bukan datang dari menyingkirkan aktor ekonomi lama, melainkan dari menata ulang relasi negara, bisnis, dan buruh dalam kerangka transisi yang dinegosiasikan secara terbuka. Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan iklim, maka transisi energi tidak bisa hanya menjadi proyek teknokratik atau investasi hijau, tetapi harus menjadi proyek politik distribusional: siapa menanggung biaya, siapa menerima manfaat, dan siapa dijamin masa depannya.
Krisis representasi iklim di Indonesia juga bersifat temporal. Demokrasi kita sangat responsif terhadap kebutuhan hari ini—harga listrik, lapangan kerja, pertumbuhan—tetapi lemah dalam mewakili masa depan. Anak-anak yang akan hidup dengan banjir pesisir, petani yang akan menghadapi gagal panen, dan komunitas adat yang akan kehilangan hutan tidak memiliki kursi tetap di meja kebijakan. Carbon Captured mengingatkan bahwa tanpa institusi yang secara eksplisit mewakili kepentingan jangka panjang, demokrasi akan terus memproduksi kebijakan yang rasional secara politik, tetapi irasional secara ekologis.
Pada akhirnya, buku ini tidak menawarkan optimisme naif. Ia juga tidak menyerah pada sinisme. Ia mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sulit: apakah demokrasi mampu belajar mewakili lebih dari sekadar mereka yang paling kuat dan paling dekat? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini menyentuh inti pembangunan itu sendiri. Apakah negara hanya menjadi penengah kepentingan ekonomi yang ada, atau mampu menjadi arsitek transisi menuju masa depan yang layak dihuni?
Esai besar Carbon Captured mengajak kita melihat bahwa krisis iklim bukanlah kegagalan niat baik, melainkan cermin dari siapa yang kita anggap penting dalam politik. Jika iklim terus kalah, bukan karena ia tidak penting, tetapi karena ia tidak terorganisasi. Tugas politik iklim Indonesia ke depan bukan sekadar menurunkan emisi, melainkan mengganggu logika representasi lama dan membangun koalisi baru—di mana buruh tidak ditinggalkan, BUMN tidak terjebak, dan masa depan tidak terus-menerus dikorbankan atas nama stabilitas hari ini. Jika demokrasi ingin bertahan di zaman krisis iklim, ia harus belajar satu hal yang selama ini ia hindari: mewakili yang belum bersuara, dan melindungi yang belum lahir.
Secara global, buku ini sangat relevan dalam konteks di mana banyak negara yang telah menetapkan target net-zero namun masih bergulat dengan resistensi politik domestik — buku ini mengingatkan bahwa hambatan seringkali bukan teknis, melainkan struktural: politik, institusi, dan aliansi kekuatan. Di Indonesia, relevansinya tampak jelas: Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar, banyak pekerja dan komunitas tergantung pada industri batubara dan minyak/pelumas. Kebijakan pengurangan emisi, pengalihan ke energi terbarukan, atau CCS akan memengaruhi banyak pihak. Jika transisi dilakukan tanpa strategi yang memperhitungkan pekerja, wilayah terdampak, dan bisnis lokal, potensi resistensi politik besar.
Buku ini menawarkan kerangka analitis untuk memahami kenapa kebijakan iklim bisa berjalan lambat atau bahkan gagal: karena kekuatan bisnis-labor karbon dominan dan koalisi pro-iklim yang lemah. Dengan demikian, bagi pemangku kepentingan di Indonesia — pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, masyarakat adat — penting untuk membangun aliansi yang melibatkan pekerja transisi, diversifikasi ekonomi, pelatihan ulang, serta skema kebijakan yang adil dan pragmatis. Misalnya, mandat energi bersih atau insentif transisi mungkin lebih layak diterima secara politik dibanding pajak karbon yang langsung dibebankan kepada industri batubara tanpa kompensasi. Buku ini juga mengajak agar kita tak hanya mengejar target teknis, tetapi mereformasi institusi politik dan ekonomi agar representasi tenaga kerja dan komunitas terdampak dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan.
Catatan Akhir: Cermin Ketimpangan Politik dan Ekonomi
Buku ini menegaskan bahwa masa depan kebijakan iklim bergantung pada bagaimana kita membangun koalisi politik yang inklusif, memperluas representasi ke pekerja, komunitas yang terdampak, dan mengubah instrumen kebijakan supaya tidak hanya membebani bisnis besar tetapi juga memberikan insentif bagi transisi bersih. Mildenberger menekankan bahwa instrumen yang secara politik layak mungkin bukan yang paling optimal teknis, tetapi mereka bisa membuka jalan menuju kebijakan yang lebih ambisius kemudian. Ia juga menyoroti bahwa negara-dan wilayah-dengan institusi yang sangat tertaut dengan industri karbon perlu reformasi institusional agar hambatan-struktur bisa disingkirkan. Dari ulasan kritikus: buku ini “an engaging, deeply researched history of both international and domestic climate politics” yang “undeniably … underscores the importance of expanding the political contours of the environmental movement with policies that can improve both the environment and individual’s economic livelihoods.” Chicago Policy Review+1 Namun beberapa kritikus juga mencatat bahwa fokusnya sangat pada lima negara kaya, kurang mengeksplorasi negara-Global South secara mendalam, sehingga aplikasinya untuk negara berkembang bisa membutuhkan adaptasi.
Mildenberger memperlihatkan bagaimana kegagalan kebijakan iklim bukan terutama karena ketidaktahuan ilmiah, melainkan karena benturan politik domestik. Ia menelusuri sejarah politik iklim di tiga negara utama — Amerika Serikat, Norwegia, dan Australia — dan menunjukkan bahwa di masing-masing negara, industri karbon memiliki dua bentuk representasi politik yang saling memperkuat: melalui asosiasi bisnis besar yang berusaha menahan regulasi yang mengancam keuntungan mereka, dan; melalui serikat pekerja industri berat (batu bara, baja, minyak) yang khawatir kehilangan lapangan kerja.
Mildenberger menyebutnya sebagai double representation of carbon-intensive interests.
Ia menelusuri bagaimana, di Amerika Serikat, momentum awal untuk aksi iklim pada akhir 1980-an (ketika James Hansen memberi kesaksian di Kongres) terhenti karena koalisi “pro-business and labor” berhasil menggeser isu iklim menjadi wacana ekonomi nasional: lapangan kerja, biaya energi, dan ketergantungan pada impor. Dalam suasana Reaganomics, kepentingan industri fosil berhasil meleburkan diri ke dalam wacana patriotisme energi. Bahkan partai Demokrat, yang secara tradisional lebih dekat dengan serikat pekerja, tidak mampu mem-bentuk koalisi iklim kuat karena sebagian besar serikat di sektor energi menolak pajak karbon. Di sinilah Mildenberger menulis, “When workers’ organizations identify their members’ welfare with the carbon economy, climate politics fractures within the left itself.”
(Carbon Captured, p. 72)
Di Norwegia, ironi yang muncul adalah bahwa negara paling progresif dalam wacana lingkungan justru mempertahankan produksi minyak dan gas yang besar. Melalui sistem “corporatist bargaining”, serikat pekerja dan asosiasi bisnis bernegosiasi langsung dengan pemerintah. Hasilnya adalah kompromi yang menghasilkan pajak karbon yang relatif tinggi, tetapi dengan pengecualian besar bagi sektor minyak dan industri berat—sebuah “carbon capture” politik yang elegan: kebijakan ada, tetapi dampaknya kecil bagi pelaku utama. Sedangkan di Australia, Mildenberger menyoroti perjuangan panjang pembentukan dan pembatalan carbon pricing antara tahun 2007–2014, di mana kekuatan serikat dan industri batu bara menciptakan “veto structure” yang menggagalkan stabilitas kebijakan.
Dari bagian ini kita belajar bahwa politik iklim sangat bergantung pada konfigurasi sosial-ekonomi domestik. Ia tidak bisa dipahami hanya dengan model rasional pasar bebas atau perjanjian global. Bagi Indonesia, ini sangat relevan: serikat pekerja di sektor energi, tambang, dan transportasi masih kuat dan seringkali sejalan dengan kepentingan bisnis besar. Tanpa transformasi struktur representasi politik seperti ini, kebijakan iklim akan terus tersandera oleh ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan modal.
Mildenberger melakukan refleksi teoretis dan empiris yang tajam: selama tiga dekade terakhir, banyak analisis menganggap kegagalan aksi iklim global disebabkan oleh masalah “free rider antarnegara”, misalnya negara enggan bertindak karena takut negara lain tidak akan ikut. Namun, Mildenberger membalikkan asumsi ini: “Climate inaction is not driven by international free-riding but by domestic capture — the grip of carbon-intensive interests within national politics.” (Carbon Captured, p. 247)
Ia menunjukkan bahwa perdebatan internasional seperti Kyoto Protocol atau Paris Agreement sering dijadikan kambing hitam untuk kegagalan domestik, padahal akar masalah ada pada struktur kekuasaan di dalam negeri. Ia menggunakan data komparatif yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korporatisme tinggi (seperti Norwegia atau Jerman) mampu menghasilkan kesepakatan internal lebih stabil, walau cenderung kompromistis, sementara negara pluralis seperti AS atau Australia lebih sering mengalami fluktuasi dan kegagalan kebijakan.
Lebih jauh, Mildenberger memperingatkan bahwa solusi teknis seperti perdagangan karbon atau carbon capture and storage (CCS) sering kali digunakan untuk mempertahankan legitimasi industri karbon. Ia menulis bahwa CCS “allows business elites to appear proactive while structurally maintaining fossil capital” (p. 258). Dengan kata lain, banyak “solusi” hanya mengubah bentuk, bukan isi, dari dominasi karbon.
Analisis ini sangat relevan di masa kini: perusahaan minyak raksasa seperti ExxonMobil atau Pertamina misalnya, kini menampilkan narasi “transisi energi” dengan proyek co-firing batu bara, biofuel, atau CCS, yang dalam praktiknya mempertahankan struktur lama. Dalam konteks Indonesia, wacana transisi hijau sering dibingkai sebagai proyek teknologi besar, bukan restrukturisasi kekuasaan dan ekonomi daerah tambang.
Sebagaimana dikatakan oleh penyair dan aktivis Nigeria Nnimmo Bassey, “You cannot heal the planet without healing the injustices that have been built into our systems.” Pandangan ini selaras dengan tesis Mildenberger: krisis iklim adalah cermin ketimpangan politik dan ekonomi, bukan sekadar kegagalan ilmiah. Dengan nada realistis namun konstruktif buku diakhiri. Mildenberger menyimpulkan bahwa jalan menuju keadilan iklim dan kebijakan yang efektif hanya mungkin jika kekuatan sosial baru dibangun untuk menandingi koalisi bisnis-pekerja karbon. Ia menekankan bahwa alih-alih hanya mengandalkan “insentif pasar” atau “solusi teknokratis”, pemerintah dan gerakan sosial perlu membangun koalisi transisi yang adil (just transition) — yakni pendekatan yang menjamin pekerja industri karbon tidak ditinggalkan. Ia mencontohkan inisiatif seperti BlueGreen Alliance di AS, yang menggabungkan serikat pekerja dengan organisasi lingkungan untuk menuntut kebijakan iklim berbasis penciptaan lapangan kerja hijau. “Political feasibility does not mean lowering ambition; it means building new power.” (Carbon Captured, p. 280).
Mildenberger juga menegaskan pentingnya “repoliticizing” kebijakan iklim — bukan mensterilkan isu ini dari perdebatan, tetapi mengembalikan politik sebagai arena pembentukan aliansi dan solidaritas baru. Dalam hal ini, dia sejalan dengan pandangan filsuf politik Chantal Mouffe yang mengatakan bahwa “democracy requires the mobilization of passions towards collective goals.” (2005).
Ia juga memaparkan agenda reformasi institusi: perlunya regulasi transparan terhadap pendanaan politik dari industri energi, sistem kompensasi ekonomi bagi daerah tambang yang terdampak, serta mekanisme partisipasi publik yang nyata. Bagi Indonesia, hal ini sangat relevan. Program “transisi energi berkeadilan” (Just Energy Transition Partnership/JETP) akan gagal jika hanya menjadi proyek investasi dan utang tanpa membangun koalisi sosial di tingkat bawah — pekerja tambang, komunitas lokal, dan sektor publik.
Kritikus seperti Michael Toman (Climate Policy Journal, 2021) memuji buku ini karena “bringing political realism into climate economics,” sementara yang lain, seperti Christian Downie, mengingatkan bahwa pendekatan ini masih terbatas pada konteks negara maju. Meski demikian, Carbon Captured telah menjadi rujukan penting dalam ilmu politik lingkungan, karena menawarkan kerangka yang kuat tentang mengapa kebijakan iklim gagal dan bagaimana membangunnya kembali dengan memahami kekuasaan, representasi, dan kompromi.
Dalam konteks spiritual dan etis, pemikir Muslim seperti Seyyed Hossein Nasr pernah me-ngingatkan, “The ecological crisis is a spiritual crisis of modern man.” (Man and Nature, 1968). Pandangan ini memberi kedalaman moral pada gagasan Mildenberger: bahwa krisis iklim bukan hanya soal sistem energi, tetapi tentang sistem nilai dan solidaritas. Dunia membutuhkan politik iklim yang tidak sekadar efisien, tetapi juga berkeadilan — politik yang mengakui bahwa bumi dan pekerja sama-sama harus dilindungi.
Bogor, 31 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Mildenberger, M. (2020). Carbon Captured: How Business and Labor Control Climate Politics. Cambridge, MA: MIT Press.
Snyder, M. (2021, July 24). Labor, Business, and the Political Barriers to Climate Action. Chicago Policy Review. Retrieved from https://chicagopolicyreview.org/2021/07/24/labor-business-and-the-political-barriers-to-climate-action/
Amateur Earthling. (2023, February 25). Carbon Captured by Matto Mildenberger. Retrieved from https://amateurearthling.org/2023/02/25/carbon-captured/
Anthem EnviroExperts. (2020). Carbon Captured: How Business and Labor Control Climate Politics – review. Retrieved from https://anthemenviroexperts.com/environment-and-sustainability/carbon-captured-how-business-and-labor-control-climate-politics
Toman, M. (2021). Review of Carbon Captured. Climate Policy Journal.
Mouffe, C. (2005). On the Political. London: Routledge.
Nasr, S. H. (1968). Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man. London: Allen & Unwin.
Bassey, N. (2010). To Cook a Continent: Destructive Extraction and the Climate Crisis in Africa. Nairobi: Pambazuka Press.