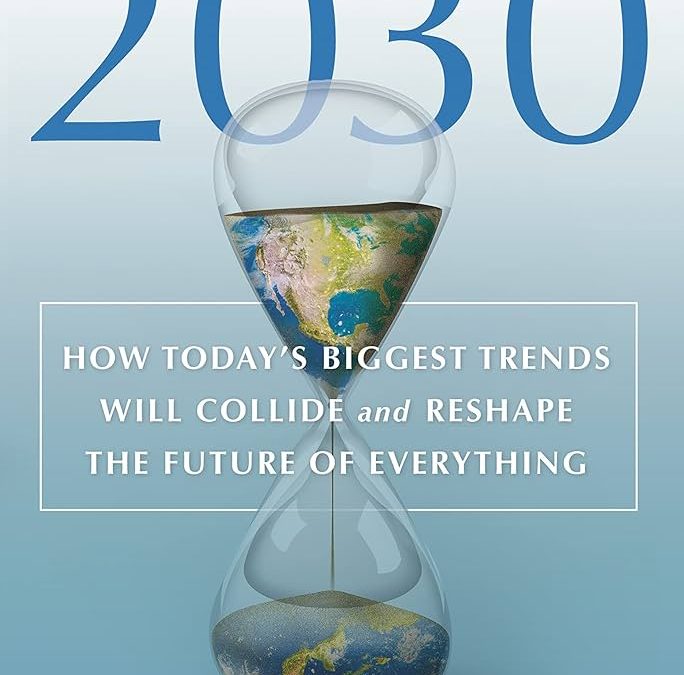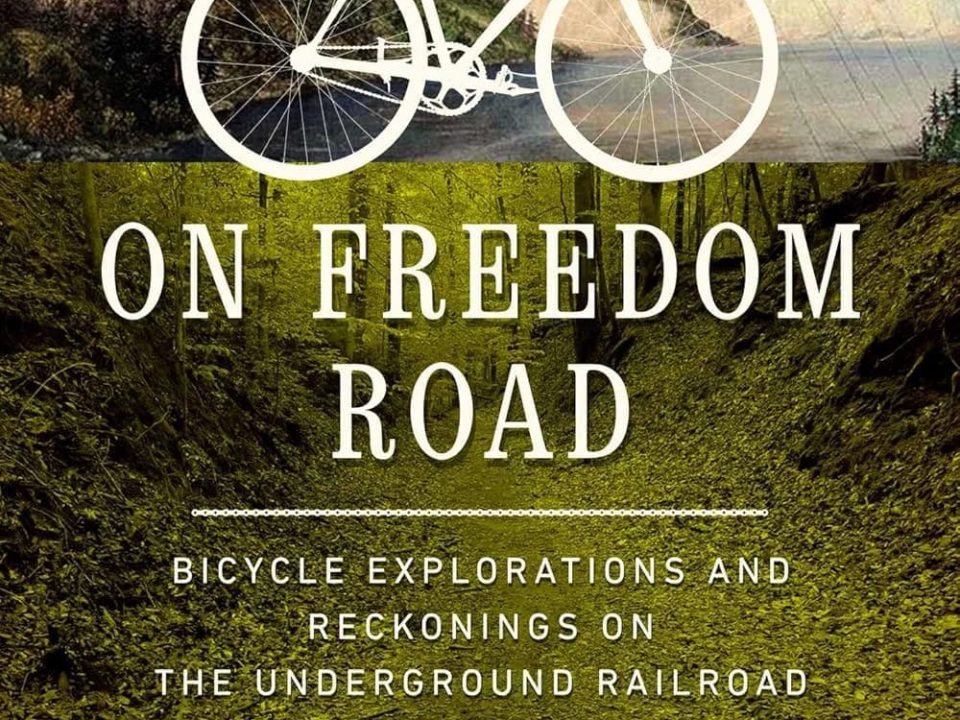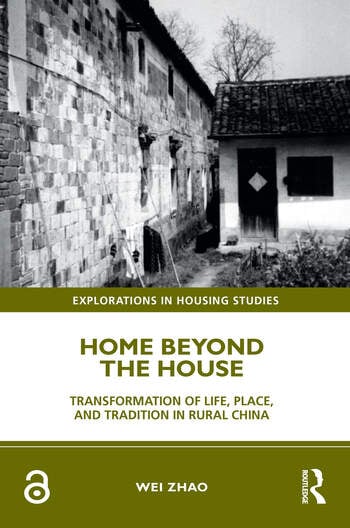Rubarubu #87
2030:
Membaca Masa Depan sebagai Tabrakan Tren Global
Pada suatu forum ekonomi global, Mauro F. Guillén—seorang sosiolog ekonomi dan profesor di Wharton—pernah mengajukan pertanyaan sederhana namun mengganggu: “Mengapa kita begitu sibuk memprediksi masa depan teknologi, tetapi begitu jarang memperhatikan bagaimana manusia akan hidup di dalamnya?” Pertanyaan ini menjadi napas utama buku 2030. Guillén tidak tertarik pada ramalan futuristik yang sensasional. Ia justru mengajak pembaca melihat masa depan sebagai hasil benturan tren sosial, demografis, ekonomi, teknologi, dan geopolitik yang sudah terjadi hari ini.
Inilah konteks pembuka buku 2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything (St. Martin Press, 2020), yang dirangkum secara kuat dalam Introduction: “The Clock Is Ticking”. Guillén menegaskan bahwa dekade 2020–2030 bukan sekadar fase transisi, melainkan titik kritis. Jam terus berdetak, dan keputusan—atau kelambanan—hari ini akan menentukan kualitas hidup miliaran manusia di masa depan. Ia menulis dengan nada mendesak namun rasional: bukan kepanikan, melainkan kesadaran struktural. “The future is not something that happens to us. It is something that we create—or fail to create—through our choices today.” (Guillén, 2020). Mauro F. Guillén adalah salah satu pemikir paling orisinal di Wharton School, di mana ia menjabat sebagai Zandman Professor dalam Manajemen Internasional dan mengajar di program andalannya, Advanced Management Program, serta banyak kursus lainnya untuk eksekutif, mahasiswa MBA, dan sarjana. Sebagai seorang ahli tren pasar global, ia adalah pembicara dan konsultan yang sangat dicari.
Menurut Guillén ada enam tabrakan besar yang membentuk dunia 2030. Alih-alih menyusun buku berdasarkan sektor atau wilayah, Guillén memilih pendekatan interseksional: bagaimana tren-tren besar saling bertabrakan dan menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga. Inilah kekuatan utama buku ini.
1. Demografi: Dunia yang Menua dan Dunia yang Muda Bertemu. Guillén menunjukkan bahwa pada 2030, dunia akan terbelah secara demografis. Negara-negara maju—Jepang, Eropa Barat, Korea Selatan—menua dengan cepat, sementara negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, dan sebagian besar Afrika justru mengalami bonus demografi. Namun bonus ini bukan otomatis berkah. Ia menekankan bahwa usia produktif tanpa pekerjaan bermakna adalah resep instabilitas sosial, sementara populasi lansia tanpa sistem perlindungan sosial adalah krisis fiskal. Di sinilah isu keberlanjutan muncul bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga keadilan antargenerasi. Dalam konteks Indonesia, argumen Guillén sangat relevan. Bonus demografi Indonesia menuju 2030 akan menjadi peluang besar atau beban berat, tergantung pada investasi hari ini dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan hijau (green jobs).
2. Urbanisasi dan Kota sebagai Titik Didih Keberlanjutan. Guillén menggambarkan kota bukan sekadar pusat ekonomi, tetapi medan konflik antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Pada 2030, dua pertiga manusia akan tinggal di kota. Pertanyaannya bukan lagi “apakah kota akan tumbuh?”, melainkan “untuk siapa kota itu dibangun?” “Cities will be where inequality, innovation, and sustainability collide most visibly.” (Guillén, 2020). Kota-kota pesisir seperti Jakarta menjadi contoh nyata. Perubahan iklim, naiknya permukaan laut, kemacetan, dan ketimpangan sosial bertemu dalam satu ruang. Guillén tidak menawarkan solusi teknokratik tunggal, melainkan menekankan governance adaptif, kolaborasi publik–swasta, dan partisipasi warga.
3. Teknologi: Bukan Penghancur Pekerjaan, tetapi Pengubah Makna Kerja. Berbeda dari narasi distopia tentang AI, Guillén mengambil posisi moderat namun kritis. Teknologi, menurutnya, tidak otomatis menghilangkan pekerjaan, tetapi mengubah keterampilan yang bernilai. Masalah terbesar bukan otomatisasi, melainkan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan reskilling. Pandangan ini selaras dengan Amartya Sen, yang menyatakan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kapabilitas manusia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi (Sen, 1999). Tanpa investasi sosial, teknologi justru memperlebar jurang ketimpangan—isu yang sangat terasa di negara berkembang, termasuk Indonesia.
4. Perempuan, Keluarga, dan Transformasi Struktur Sosial. Salah satu bagian paling progresif buku ini adalah analisis Guillén tentang peran perempuan. Ia menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan kerja adalah salah satu tren paling kuat menuju 2030, dengan implikasi besar terhadap fertilitas, ekonomi, dan politik. Namun Guillén juga mengingatkan: tanpa perubahan institusional—cuti melahirkan, childcare, fleksibilitas kerja—kemajuan ini akan rapuh. Dalam isu keberlanjutan, ini penting: ketahanan sosial adalah fondasi ketahanan ekologis. Pemikir Muslim kontemporer seperti Amina Wadud juga menekankan bahwa keadilan gender bukan isu sekunder, melainkan inti dari keadilan sosial (justice as balance), yang menjadi prasyarat keberlanjutan.
5. Migrasi, Identitas, dan Politik Ketakutan. Guillén melihat migrasi sebagai keniscayaan struktural, bukan anomali. Perubahan iklim, konflik, dan ketimpangan ekonomi akan mendorong mobilitas manusia. Tantangan terbesar bukan jumlah migran, melainkan narasi politik yang menyertainya. “The backlash against globalization is not about economics alone. It is about fear, identity, and perceived loss of control.” (Guillén, 2020). Di sinilah buku ini menjadi sangat relevan dengan krisis demokrasi global. Guillén sejalan dengan Hannah Arendt, yang mengingatkan bahwa politik ketakutan sering lahir dari ketidakmampuan institusi merespons perubahan struktural.
6. Kapitalisme, Ketimpangan, dan Masa Depan Kepercayaan. Guillén menutup dengan refleksi tajam tentang kapitalisme. Ia tidak mengadvokasi keruntuhannya, tetapi menegaskan bahwa kapitalisme tanpa legitimasi sosial tidak berkelanjutan. Ketimpangan ekstrem, krisis iklim, dan erosi kepercayaan publik akan memaksa transformasi model bisnis dan tata kelola.
Dalam konteks ini, agenda ESG, ekonomi hijau, dan keuangan berkelanjutan bukan tren moral semata, melainkan strategi bertahan hidup sistemik.
Meski tidak secara eksklusif membahas sustainability, 2030 justru memperlihatkan bahwa krisis lingkungan tidak bisa dipisahkan dari demografi, teknologi, dan politik. Guillén membantu kita memahami bahwa perubahan iklim bukan sekadar masalah emisi, tetapi masalah tata kelola, ketimpangan, dan solidaritas global. Bagi Indonesia, buku ini relevan sebagai cermin strategis: apakah transisi energi, pembangunan kota, dan reformasi pendidikan akan dijalankan sebagai proyek jangka pendek, atau sebagai investasi peradaban?
Mengikuti Bayi, Mengikuti Waktu
Mauro Guillén yang menggabungkan latar belakang pendidikannya sebagai seorang sosiolog dari Yale dan sebagai ekonom bisnis di tanah kelahirannya, Spanyol, untuk secara metodis mengidentifikasi dan mengukur peluang-peluang paling menjanjukan di persimpangan perkembangan demografis, ekonomi, dan teknologi, mengajak pembacanya untuk memulai pemahaman tentang masa depan bukan dari teknologi atau geopolitik, melainkan dari sesuatu yang paling mendasar dan sering diabaikan: kelahiran. Dalam gagasan yang dirangkum dalam Follow the Babies: Population Drought, the African Baby Boom, and the Next Industrial Revolution, ia menunjukkan bahwa masa depan ekonomi dan politik global sesungguhnya sedang ditulis di ruang bersalin hari ini.
Di sebagian besar dunia maju, bayi semakin jarang lahir. Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat, dan bahkan Tiongkok menghadapi apa yang Guillén sebut sebagai population drought—kekeringan demografis. Kota-kota tetap terang, teknologi semakin canggih, tetapi rahim-rahim sunyi. Konsekuensinya tidak langsung terasa, namun pelan dan pasti: kekurangan tenaga kerja, sistem pensiun yang rapuh, dan ekonomi yang kehilangan dinamika. Guillén menekankan bahwa ini bukan sekadar soal jumlah penduduk, melainkan hilangnya ritme regenerasi sosial.
Namun di sisi lain dunia, Afrika justru bergerak dengan irama yang berlawanan. Di sana, jutaan bayi lahir setiap tahun, membentuk apa yang ia sebut sebagai African baby boom. Guillén menolak pandangan lama yang melihat ledakan ini sebagai beban. Ia justru membaca potensi sejarah: Afrika bisa menjadi pusat tenaga kerja, konsumen, dan inovator dunia berikutnya—jika investasi pendidikan, kesehatan, dan institusi dilakukan secara serius. Dengan kata lain, revolusi industri berikutnya mungkin tidak lahir di Silicon Valley atau Shenzhen, melainkan di Lagos, Nairobi, atau Accra.
Dari bayi, Guillén kemudian membawa kita ke tahap kehidupan yang sering dipandang sebagai ujung jalan, padahal justru sedang berubah maknanya: usia tua. Dalam bagian Gray Is the New Black: Tech-Savvy Senior Citizens, Postponing Retirement, and Rethinking “Old” and “Young”, ia menantang stereotip tentang lansia sebagai kelompok pasif dan tertinggal teknologi. Justru sebaliknya, generasi yang kini memasuki usia 60 dan 70 tahun adalah generasi yang pernah bekerja dengan komputer, internet, dan globalisasi.
Guillén menggambarkan dunia di mana batas antara “muda” dan “tua” menjadi kabur. Banyak orang menunda pensiun bukan semata karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena makna kerja telah berubah. Kerja tidak lagi hanya soal bertahan hidup, melainkan identitas, koneksi sosial, dan kontribusi. Dalam masyarakat yang menua, lansia bukan beban, melainkan aset pengalaman dan stabilitas, terutama jika sistem kerja lebih fleksibel dan inklusif.
Ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan usia biologis, melainkan desain institusi yang masih berpikir dalam kategori abad ke-20: sekolah untuk muda, kerja untuk dewasa, pensiun untuk tua. Dunia 2030, menurut Guillén, menuntut siklus hidup yang jauh lebih cair—belajar seumur hidup, bekerja lintas usia, dan berkontribusi dalam berbagai bentuk.
Dari demografi dan usia, narasi Guillén bergerak ke perubahan yang tak kalah mendasar: kekuasaan ekonomi dan gender. Dalam Second Sex No More? The New Millionaires, Entrepreneurs, and Leaders of Tomorrow, ia menunjukkan bahwa salah satu pergeseran paling revolusioner abad ini adalah naiknya peran perempuan dalam pendidikan, bisnis, dan kepemimpinan. Guillén tidak merayakannya secara romantis, tetapi membacanya sebagai tren struktural yang akan membentuk ulang pasar, keluarga, dan politik. Ia mencatat bahwa perempuan kini menjadi mayoritas mahasiswa di banyak negara, semakin dominan dalam kewirausahaan, dan memainkan peran kunci dalam ekonomi konsumsi. Perempuan bukan lagi “pasar niche”, melainkan penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Namun Guillén juga jujur menunjukkan paradoksnya: kemajuan ini berjalan bersamaan dengan beban ganda, ketimpangan upah, dan institusi sosial yang belum sepenuhnya beradaptasi.
Yang menarik, Guillén mengaitkan kebangkitan perempuan dengan seluruh narasi sebelumnya. Tingkat pendidikan perempuan berhubungan langsung dengan angka kelahiran, kualitas kesehatan, dan stabilitas sosial. Dengan kata lain, masa depan demografi, produktivitas lansia, dan keberlanjutan ekonomi saling terkait melalui satu benang merah: perubahan peran manusia dalam struktur sosial lama. Dalam sintesis besar ini, Guillén seolah berkata bahwa masa depan tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal—bukan teknologi, bukan ekonomi, bukan politik—melainkan oleh interaksi antara siapa yang lahir, siapa yang menua, dan siapa yang memegang kendali sumber daya. Dunia 2030 akan dibentuk oleh bayi-bayi Afrika, lansia yang tetap produktif, dan perempuan yang semakin menentukan arah kekuasaan ekonomi.
Buku ini, melalui ketiga bagian tersebut, mengajarkan satu pelajaran penting: untuk memahami masa depan, kita harus belajar membaca manusia—dari awal kehidupan hingga usia senja—bukan sekadar grafik pertumbuhan atau inovasi teknologi. Karena pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan Guillén secara konsisten, masa depan adalah soal bagaimana kita mengatur hidup bersama dalam perubahan yang tak bisa dihindari.
Bagaimana kalau kita mempertemukan pandangan Mauro F. Guillén dengan Amartya Sen, Hannah Arendt, dan Ibn Khaldun dalam isu populasi dan siklus peradaban?
Mauro F. Guillén dalam 2030 melihat populasi bukan sekadar angka demografis, melainkan energi laten peradaban: potensi ekonomi, sumber inovasi, sekaligus sumber ketegangan. Ledakan bayi di Afrika, penuaan di Eropa dan Asia Timur, serta urbanisasi cepat dibaca Guillén sebagai ketidakseimbangan struktural yang akan membentuk ulang kekuasaan global. Bagi Guillén, masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling besar jumlahnya, tetapi oleh siapa yang paling adaptif dalam mengelola perubahan demografi.
Pandangan ini beririsan kuat dengan Amartya Sen, yang sejak lama menolak reduksi populasi menjadi masalah kuantitas semata. Sen menekankan bahwa kualitas hidup—pendidikan, kesehatan, kebebasan perempuan—lebih menentukan arah masyarakat dibanding laju pertumbuhan penduduk. Jika Guillén berbicara tentang demographic opportunity, Sen memberinya fondasi normatif: populasi menjadi berkah hanya bila manusia diperlakukan sebagai subjek berkemampuan (capable beings), bukan beban statistik. Dalam bahasa Sen, tantangan 2030 bukan soal “terlalu banyak atau terlalu sedikit orang”, melainkan terlalu sedikit kebebasan substantif untuk berkembang.
Sementara itu, Hannah Arendt membawa perspektif yang lebih eksistensial. Ia melihat krisis modern bukan terutama pada jumlah manusia, tetapi pada hilangnya ruang tindakan dan makna bersama. Dalam dunia yang dikelola oleh sistem, birokrasi, dan teknologi, manusia berisiko direduksi menjadi animal laborans—sekadar unit kerja dan konsumsi. Guillén relatif optimistis bahwa teknologi dan demografi baru membuka peluang partisipasi (digital citizens), tetapi Arendt mengingatkan: populasi besar dan terkoneksi tidak otomatis menghasilkan dunia bersama (common world). Tanpa ruang politik dan tanggung jawab moral, ledakan populasi justru bisa melahirkan keterasingan massal.
Perspektif Ibn Khaldun memberi kedalaman historis yang kontras namun relevan. Dalam Muqaddimah, ia melihat populasi sebagai bagian dari siklus peradaban: masyarakat tumbuh ketika solidaritas sosial (‘asabiyyah) kuat, lalu melemah ketika kemewahan, ketimpangan, dan ketergantungan berlebihan merusak kohesi. Guillén berbicara tentang siklus demografi global; Ibn Khaldun berbicara tentang ritme naik-turun peradaban. Keduanya bertemu pada satu intuisi: pertumbuhan tanpa kohesi sosial adalah awal kemunduran. Dengan demikian, Guillén dapat dibaca sebagai pemikir transisional: ia memetakan data dan tren global, sementara Sen menekankan keadilan dan kapasitas manusia, Arendt mengingatkan makna politik dan tindakan, dan Ibn Khaldun memperingatkan bahaya hilangnya solidaritas. Jika Guillén bertanya bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan populasi, maka ketiga pemikir itu bertanya lebih dalam: untuk peradaban seperti apa kita ingin bertahan? Di persimpangan inilah, isu populasi berubah dari soal teknis menjadi soal peradaban—bukan hanya tentang berapa banyak kita hidup, tetapi bagaimana dan untuk apa kita hidup bersama.
Guillén pada bagian lain bercerita tentang kerentanan kota, banalitas bertahan hidup, ledakan teknologi yang tak simetris, hingga runtuhnya imajinasi lama tentang kepemilikan dan uang. Kota yang tenggelam, teknologi yang meluap, dan uang yang kehilangan bentuk. Guillén membawa kita memasuki masa depan bukan lewat visi futuristik yang berkilau, melainkan melalui kenyataan yang pelan-pelan naik—air. Dalam gagasan yang dirangkum dalam Cities Drown First: Global Warming, Hipsters, and the Mundanity of Survival, kota-kota muncul sebagai paradoks modernitas: pusat inovasi sekaligus titik paling rapuhdari perubahan iklim. Kota tumbuh di pesisir, di delta, di dataran rendah—di tempat yang dahulu strategis bagi perdagangan dan kini paling rentan terhadap kenaikan muka laut, badai, dan banjir.
Yang menarik, Guillén tidak memulai dari bencana spektakuler, melainkan dari “banalitas bertahan hidup”. Ia menunjukkan bagaimana perubahan iklim jarang datang sebagai kiamat tunggal; ia hadir sebagai gangguan sehari-hari: asuransi yang mahal, transportasi yang macet oleh banjir, hunian yang tak lagi terjangkau. Bahkan gaya hidup urban—yang sering dipersoni-fikasikan lewat simbol-simbol kelas kreatif dan “hipster”—tak kebal. Kafe, co-working space, dan pusat budaya tetap ada, tetapi berdiri di atas fondasi yang semakin rapuh. Kota tidak runtuh karena satu peristiwa besar, melainkan karena akumulasi gangguan kecil yang menggerogoti daya hidupnya.
Dari kota yang tenggelam, Guillén menggeser fokus ke ironi besar abad ke-21: lebih banyak ponsel daripada toilet. Dalam More Cellphones than Toilets: Reinventing the Wheel, the New Cambrian Explosion, and the Future of Technology, ia membongkar asumsi bahwa kemajuan teknologi selalu berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup dasar. Dunia menyaksikan ledakan perangkat digital—ponsel murah, aplikasi, jaringan—bahkan di tempat-tempat yang kekurangan sanitasi, air bersih, dan infrastruktur kesehatan.
Guillén yang juga menulis buku antara lain The Architecture of Collapse, Global Turning Points, dan Emerging Markets Rule ini menyebut momen ini sebagai Cambrian explosion teknologi: ledakan cepat, beragam, dan sering tak terkendali. Inovasi tidak lagi bergerak dari pusat ke pinggiran; ia lahir secara lokal, pragmatis, dan sering kali “menemukan kembali roda” sesuai konteks setempat. Teknologi masa depan, menurut Guillén, tidak selalu canggih secara teknis, tetapi adaptif secara sosial. Ponsel menjadi dompet, klinik, sekolah, dan pasar—bukan karena desain ideal, melainkan karena kebutuhan mendesak.
Namun, dari sini muncul pertanyaan yang lebih dalam: jika teknologi merajalela, apa yang sebenarnya kita miliki?Guillén menjawabnya dengan menggugat konsep kepemilikan itu sendiri. Dalam Imagine No Possessions: Riding Waves, Network Effects, and the Power of 8.5 Billion Connections, ia menggambarkan dunia yang bergerak dari kepemilikan ke akses. Kita tidak lagi perlu memiliki mobil untuk bepergian, kantor untuk bekerja, atau bahkan barang fisik untuk merasa “memiliki” nilai.
Kekuatan sejati masa depan, menurut Guillén, terletak pada jaringan. Dengan miliaran koneksi manusia dan mesin, nilai tidak lagi terkunci pada benda, tetapi pada kemampuan untuk ter- hubung, berbagi, dan beradaptasi. Efek jaringan membuat pemenang semakin kuat, tetapi juga membuka ruang bagi bentuk-bentuk kolaborasi baru yang sebelumnya mustahil. Namun Guillén juga mengingatkan: dunia tanpa kepemilikan bukan dunia tanpa ketimpangan. Justru sebalik-nya, ketimpangan bisa berpindah dari “siapa yang punya barang” menjadi “siapa yang mengontrol platform dan data”.
Puncak dari rangkaian ini muncul ketika Guillén membahas uang—simbol paling konkret dari nilai modern. Dalam More Currencies than Countries: Printing Your Own Money, the Blockchain, and the End of Modern Banking, ia menunjukkan bahwa uang sedang kehilangan singularitas-nya. Jika dulu negara memonopoli mata uang, kini dunia menyaksikan proliferasi bentuk nilai: mata uang digital, kripto, token, poin, dan sistem pembayaran alternatif.
Guillén tidak merayakan ini sebagai kemenangan teknologi semata, melainkan membacanya sebagai krisis kepercayaan dan imajinasi institusional. Blockchain dan mata uang digital lahir bukan hanya karena teknologi memungkinkan, tetapi karena banyak orang merasa sistem perbankan dan negara tidak lagi cukup responsif. Uang menjadi lebih cair, lebih eksperimental, tetapi juga lebih rapuh terhadap spekulasi dan fragmentasi.
Dalam alur yang menyatu, Bab 5 hingga 8 membentuk satu pesan besar: masa depan tidak akan runtuh dalam satu ledakan, melainkan berubah bentuk secara perlahan. Kota-kota tidak lang-sung hilang, tetapi tenggelam setahap demi setahap. Teknologi tidak selalu memperbaiki hidup, tetapi mengisi celah yang ditinggalkan institusi. Kepemilikan tidak lenyap, tetapi ber-geser makna. Dan uang tidak menghilang, melainkan terpecah menjadi banyak bahasa nilai. Guillén seakan mengingatkan bahwa tantangan terbesar 2030 bukan kekurangan inovasi, melain-kan keterlambatan kita menyesuaikan makna hidup bersama. Bertahan hidup di masa depan bukan soal menjadi paling canggih, tetapi paling mampu membaca gelombang—iklim, teknologi, jaringan, dan kepercayaan—yang terus bergerak di bawah kaki kita.
Bertahan di Dunia yang Tidak Lagi Linear
Di bagian penutup 2030, Guillén tidak menawarkan ramalan besar atau janji keselamatan. Ia justru menurunkan nada, mengajak pembaca berhenti sejenak, dan melihat dunia masa depan dari sudut yang jarang diajarkan: berpikir lateral. Dalam Lateral Tips and Tricks to Survive 2030, masa depan digambarkan bukan sebagai jalan lurus yang bisa direncanakan dengan presisi, melainkan sebagai medan yang penuh tikungan, gangguan kecil, dan pergeseran mendadak. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling kuat atau paling pintar secara teknis, melainkan yang paling lentur secara mental dan sosial.
Guillén menekankan bahwa banyak institusi—pendidikan, bisnis, negara—dibangun di atas asumsi stabilitas: pertumbuhan bertahap, karier linear, teknologi yang berkembang rapi. Namun 2030, sebagaimana digambarkan sepanjang buku, adalah dunia benturan: antara populasi tua dan muda, kota dan iklim, teknologi dan ketimpangan, globalisasi dan fragmentasi. Dalam dunia seperti ini, solusi vertikal—lebih banyak regulasi, lebih banyak skala, lebih banyak kontrol—sering kali kalah cepat dibanding solusi lateral: kolaborasi lintas sektor, pembelajaran cepat, dan kemampuan membaca peluang di sela krisis.
Bertahan hidup, menurut Guillén, menjadi praktik sehari-hari yang bersifat praktis dan eksistensial sekaligus. Ia bukan soal “menang” dalam kompetisi global, melainkan tetap relevan—sebagai individu, organisasi, maupun masyarakat. Ini berarti berani menggabungkan identitas: menjadi profesional sekaligus pembelajar seumur hidup, warga lokal sekaligus aktor global, pengguna teknologi sekaligus pengkritiknya. Masa depan menuntut kemampuan berpindah peran tanpa kehilangan kompas etis.
Nada reflektif ini kemudian dipertajam dalam Postscript tentang COVID-19, yang ditulis Guillén sebagai respons terhadap peristiwa yang—ironisnya—membuktikan hampir seluruh argumen bukunya. Pandemi tidak digambarkan sebagai “angsa hitam” yang sepenuhnya tak terduga, melainkan sebagai akselerator brutal dari tren yang sudah ada: digitalisasi kerja, krisis kota besar, ketimpangan akses kesehatan, rapuhnya rantai pasok global, dan ketergantungan ekstrem pada konektivitas.
COVID-19, dalam pandangan Guillén, berfungsi seperti cermin besar. Ia memperlihatkan dengan jujur siapa yang adaptif dan siapa yang kaku. Organisasi yang mampu bertahan bukan yang paling mapan, tetapi yang mampu berubah cepat tanpa kehilangan kepercayaan internal. Negara yang relatif tangguh bukan semata yang kaya, tetapi yang memiliki modal sosial, komunikasi publik yang jelas, dan institusi yang mau belajar secara real time. Pandemi juga memperjelas paradoks utama era 2030: dunia semakin terhubung, tetapi risiko semakin terlokalisasi. Virus menyebar secara global, namun dampaknya sangat berbeda antar komunitas. Teknologi memungkinkan kerja jarak jauh, tetapi hanya bagi mereka yang sudah memiliki akses. Di sinilah Guillén kembali menegaskan pesan implisit seluruh buku: masa depan bukan hanya soal tren besar, tetapi soal bagaimana tren itu berinteraksi dengan struktur sosial yang sudah timpang.
Dalam alur penutup ini, Guillén seakan berkata bahwa 2030 bukanlah tujuan akhir, melainkan ambang kesadaran. Dunia tidak sedang menuju satu bentuk masa depan, tetapi banyak kemungkinan yang saling bertabrakan. COVID-19 hanyalah satu contoh bagaimana satu kejadian dapat mengubah prioritas, mempercepat adopsi teknologi, dan sekaligus memperdalam luka sosial.
Maka, bertahan di 2030 bukan tentang menguasai semua teknologi baru atau memprediksi krisis berikutnya, melainkan tentang membangun kapasitas adaptif yang manusiawi: kemampuan bekerja sama di tengah perbedaan, belajar dari kegagalan, dan menjaga makna hidup di dunia yang makin cair. Guillén menutup bukunya bukan dengan kepastian, tetapi dengan undangan—untuk menjadi aktor sadar di tengah ketidakpastian, bukan sekadar penumpang dari arus perubahan.
Berikut adalah esai reflektif–filosofis yang menyusun keseluruhan gagasan buku 2030 karya Mauro F. Guillénsebagai meditasi tentang “bertahan hidup” di abad ketidakpastian, sekaligus membandingkannya secara konseptualdengan karya-karya penting seperti Karl Polanyi, Shoshana Zuboff, dan beberapa pemikir lain yang relevan untuk membaca zaman kita.
Bertahan Hidup di Dunia yang Retak
Inilah dunia yang dibayangkan: Dari 2030 (Guillén) ke The Great Transformation (Polanyi) dan The Age of Surveillance Capitalism(Zuboff). Abad ke-21 tidak ditandai oleh satu krisis tunggal, melainkan oleh tumpukan krisis: demografi, iklim, teknologi, kesehatan, ekonomi, dan makna hidup itu sendiri. Dalam lanskap inilah 2030 karya Mauro F. Guillén hadir bukan sebagai buku ramalan futuristik, melainkan sebagai panduan eksistensial yang membumi—sebuah refleksi tentang bagaimana manusia, organisasi, dan masyarakat dapat bertahan hidup di dunia yang semakin tidak linear, tidak stabil, dan tidak bisa diprediksi.
Guillén tidak memulai dari ketakutan, tetapi dari kenyataan: bahwa tren-tren besar—penuaan penduduk, urbanisasi ekstrem, digitalisasi radikal, krisis iklim, dan fragmentasi geopolitik—sedang saling bertabrakan. Masa depan bukan hasil dari satu kekuatan dominan, melainkan dari interaksi tak terduga antar kekuatan. Karena itu, “bertahan hidup” dalam 2030 tidak berarti menjadi paling kuat, melainkan paling adaptif, paling lentur, dan paling mampu berpikir lateral.
Di titik ini, 2030 dapat dibaca sebagai kelanjutan tidak langsung dari kegelisahan klasik Karl Polanyi dalam The Great Transformation (1944). Polanyi menulis di tengah kehancuran Eropa akibat kapitalisme pasar bebas yang melepaskan ekonomi dari masyarakat. Ia menunjukkan bahwa ketika tanah, tenaga kerja, dan uang diperlakukan sebagai “komoditas fiktif”, masyarakat akan merespons dengan krisis sosial dan politik. Bagi Polanyi, bertahan hidup berarti mengembalikan ekonomi ke dalam relasi sosial dan moral—re-embedding, bukan deregulasi tanpa batas.
Guillén yang kelas online-nya di Coursera telah menarik lebih dari 100.000 peserta dari seluruh dunia ini, menulis dalam konteks berbeda, tetapi kegelisahannya serupa. Jika Polanyi menyaksikan kehancuran masyarakat industri awal, Guillén menyaksikan ketidakstabilan masyarakat global digital. Dalam 2030, pasar tidak lagi sekadar pasar; ia adalah jaringan algoritmik, platform, dan data. Namun pesan implisitnya sejalan dengan Polanyi: masalah utama bukan teknologi atau pasar itu sendiri, melainkan ketika keduanya bergerak lebih cepat daripada kemampuan sosial untuk beradaptasi.
Di sinilah The Age of Surveillance Capitalism (2019) karya Shoshana Zuboff memperdalam diagnosis Guillén. Jika 2030memetakan benturan tren, Zuboff membongkar logika kekuasaan baru di baliknya. Ia menunjukkan bagaimana kapitalisme mutakhir tidak lagi mengeksploitasi tenaga kerja secara langsung, melainkan perilaku manusia itu sendiri—melalui ekstraksi data, prediksi, dan manipulasi. Dalam dunia ini, bertahan hidup tidak cukup dengan adaptasi teknis; ia menuntut kesadaran politik dan etis. Guillén relatif optimistis terhadap teknologi sebagai peluang—pendidikan terbalik, kesehatan preventif, warga digital—sementara Zuboff jauh lebih waspada. Namun keduanya bertemu pada satu titik: masa depan tidak netral. Tanpa kesadaran kolektif, adaptasi dapat berubah menjadi kepasrahan. Bertahan hidup bisa tergelincir menjadi sekadar menyesuaikan diri dengan sistem yang merugikan.
Perbandingan ini menjadi lebih tajam bila kita memasukkan Zygmunt Bauman dengan konsep Liquid Modernity (2000). Bauman menggambarkan dunia modern sebagai cair: identitas, pekerjaan, relasi, dan institusi tidak lagi solid. Guillén, dalam 2030, sebenarnya menulis di dunia cair ini—di mana karier tidak linear, kota rapuh, dan kepemilikan bergeser menjadi akses. Bertahan hidup, dalam dunia cair Bauman dan dunia benturan Guillén, berarti hidup tanpa pegangan permanen, sambil terus merakit makna sementara.
Sementara itu, Ulrich Beck dalam Risk Society (1986) memberi bahasa sosiologis bagi kegelisahan Guillén: masyarakat modern tidak lagi terutama memproduksi kekayaan, melainkan memproduksi risiko. COVID-19, yang dibahas Guillén dalam postscript 2030, adalah contoh nyata: risiko global yang tak bisa ditangani oleh logika nasional atau pasar semata. Bertahan hidup di masyarakat risiko berarti membangun kapasitas reflektif kolektif, bukan sekadar respons teknokratik.
Dengan membaca 2030 berdampingan dengan Polanyi, Zuboff, Bauman, dan Beck, tampak jelas bahwa buku Guillén bukan sekadar analisis tren, melainkan bagian dari tradisi panjang pemikir-an tentang krisis modernitas. Perbedaannya, Guillén menulis dengan bahasa yang lebih prag-matis dan optimistis, seolah ingin mengatakan: kita mungkin tidak bisa menghentikan benturan, tetapi kita masih bisa belajar menari di antaranya.
Pada akhirnya, “bertahan hidup” di abad ketidakpastian bukanlah soal bertahan secara biologis atau ekonomis semata. Ia adalah soal bertahan sebagai manusia yang bermakna—yang mampu menjaga relasi, keadilan, dan martabat di tengah dunia yang semakin otomatis dan terfragmen-tasi. Jika Polanyi mengingatkan kita agar ekonomi tidak menghancurkan masyarakat, dan Zuboff memperingatkan agar teknologi tidak mengkolonisasi jiwa, maka Guillén mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh di tengah perubahan, bukan sekadar takut atau terlena olehnya.
Abad ketidakpastian bukan akhir dari sejarah, tetapi ujian terhadap kedewasaan peradaban. Bertahan hidup, dalam pengertian terdalamnya, adalah kemampuan untuk tetap belajar, tetap peduli, dan tetap manusia—bahkan ketika masa depan tidak lagi menjanjikan kepastian.
Beberapa Fakta Dan Angka
Tempat lahir revolusi industri berikutnya: Afrika Sub-Sahara
Alasannya: 500 juta acre lahan pertanian subur namun belum dikembangkan
Luas setara Meksiko: 500 juta acre, sekitar 202 juta hektare.
Persentase kekayaan dunia yang dimiliki perempuan pada tahun 2000: 15%
Persentase kekayaan dunia yang dimiliki perempuan pada tahun 2030: 55%
Jika Lehman Brothers adalah Lehman Sisters: krisis keuangan global dapat dihindari
Jumlah orang di dunia yang mengalami kelaparan pada tahun 2017: 821 juta
Jumlah orang di dunia yang akan mengalami kelaparan pada tahun 2030: 200 juta
Jumlah orang di dunia yang mengalami obesitas pada tahun 2017: 650 juta
Jumlah orang di dunia yang akan mengalami obesitas pada tahun 2030: 1,1 miliar
Persentase penduduk Amerika Serikat yang diproyeksikan mengalami obesitas pada tahun 2030: 50%
Persentase daratan dunia yang ditempati kota-kota pada tahun 2030: 1,1%
Persentase penduduk dunia yang tinggal di kota pada tahun 2030: 60%
Persentase emisi karbon global yang dihasilkan kota-kota pada tahun 2030: 87%
Persentase populasi perkotaan dunia yang terpapar kenaikan permukaan laut pada tahun 2030: 80%
Pasar konsumen kelas menengah terbesar saat ini: Amerika Serikat dan Eropa Barat
Pasar konsumen kelas menengah terbesar pada tahun 2030: Tiongkok
Pada tahun 2030, jumlah orang yang masuk ke kelas menengah di negara-negara berkembang: 1 miliar
Jumlah orang yang saat ini berada di kelas menengah di Amerika Serikat: 223 juta
Jumlah orang yang berada di kelas menengah di Amerika Serikat pada tahun 2030: 209 juta
Berikut fakta dan angka relevan khusus untuk Indonesia yang disusun mirip format “fact sheet” seperti pada contoh sebelumnya, berdasar data resmi dan sumber terpercaya:
Fakta dan Angka: Konteks Indonesia Menuju 2030
Populasi & Demografi: Total populasi Indonesia sekitar 283 juta jiwa pada 2024 menurut data PBB. UNdata
Pertanian & Lahan: Total luas lahan pertanian di Indonesia terus meningkat dan kini mencapai sekitar 56,4 juta hektare (sekitar 1,9% dari total lahan pertanian dunia berdasarkan OECD). OECD Sektor pertanian masih menyumbang sekitar 13%–14% terhadap PDB, dan menyerap sekitar 29% tenaga kerja nasional. UNdata+1
Ketahanan Pangan & Iklim: Perubahan iklim berisiko menurunkan produksi padi nasional hingga jutaan ton akibat fenomena seperti El Niño; misalnya produksi padi turun sekitar 1,12 juta ton pada 2023 dibandingkan 2022 karena variabilitas iklim. detiknews. Tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan rumah tangga di Indonesia masih signifikan, dengan prevalensi sekitar 8,5% pada 2023. Kompas
Malnutrisi & Obesitas: Indonesia menghadapi double burden: prevalensi obesitas meningkat tajam. Antara 2007 dan 2023, prevalensi obesitas hampir tiga kali lipat menurut kriteria WHO (BMI ≥30), dari sekitar 3,7% menjadi sekitar 10,4%. Nature. Sementara itu, underweight menurun, menandakan pergeseran pola gizi yang kompleks. Nature
Emisi & Lingkungan: Sektor pertanian di Indonesia, terutama dari sawah dan alih fungsi lahan, menjadi kontributor besar emisi gas rumah kaca (GRK), dengan emisi tinggi yang signifikan dari produksi padi—sekitar 78,3 juta ton CO₂ ekuivalen dari aktivitas padi saja. Kompas
Krisis iklim juga tercermin pada catatan suhu ekstrem: 2024 menjadi tahun terpanas di Indonesia sejak 1981, dengan anomali suhu lebih dari 1,6°C di atas masa pra-industri. Reddit
Urbanisasi & Risiko Risiko: Data populasi perkotaan terus meningkat; kota-kota besar seperti Medan telah mencapai sekitar 2,4 juta penduduk di dalam kota (melebihi 4,7 juta bila termasuk wilayah metropolitan) pada pertengahan 2024. Wikipedia. Urbanisasi menambah tekanan pada infrastruktur, layanan dasar, dan risiko lingkungan seperti banjir dan polusi.
Kemiskinan & Ketimpangan: Angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi sekitar 24 juta orang pada 2025, setelah beberapa dekade tren penurunan. Reddit Namun data distribusi menunjukkan bahwa kelas menengah relatif besar (puluhan juta), tetapi dalam tekanan ekonomi dan risiko turun kasta (misalnya 40% kelas menengah terancam menjadi miskin dalam laporan tertentu). Reddit
Berikut perbandingan ringkas antara proyeksi global 2030 dan kondisi Indonesia berdasarkan data yang tersedia, disajikan dalam gaya fakta & angka komparatif:
Perbandingan Proyeksi Global 2030 vs Indonesia
1. Populasi & Urbanisasi
Global: Diperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai sekitar 8,5 miliar jiwa pada 2030, dengan urbanisasi lanjut sehingga mayoritas manusia tinggal di kota-kota. beritadaerah.co.id
Indonesia: Kelas menengah tumbuh pesat dan urbanisasi meningkat; diperkirakan sekitar 71% penduduk akan tinggal di perkotaan pada 2030—suatu transformasi besar dari desa ke kota yang membuka peluang konsumsi, risiko lingkungan, dan tekanan infrastruktur. STAIDA SUMSEL – A Journey to Excellence.
Kedua proyeksi menunjukkan urbanisasi sebagai fenomena dominan—di mana kota menjadi sumbu pertumbuhan dan ketegangan sosial-ekologis.
2. Gizi & Kesehatan
Global: Organisasi kesehatan memperkirakan sekitar 1 miliar orang di dunia akan mengalami obesitas pada 2030, mencerminkan pergeseran nutrisi dan pola hidup yang cepat di banyak negara. worldobesity.org
Indonesia: Negara menghadapi double burden gizi: obesitas meningkat tajam (dari ~3,7% menjadi ~10,4%), sementara masalah malnutrisi historis belum sepenuhnya hilang. SpringerLink
Indonesia mengikuti tren global obesitas yang meningkat, tetapi juga dipaksa menghadapi malnutrisi dari arah lain—memperlihatkan ketimpangan gizi yang lebih kompleks.
3. Ketahanan Pangan & Kelaparan
Global: Walaupun sebagian tren malnutrisi menurun sejak 2019, sekitar ratusan juta orang masih mengalami kelaparan kronis, dan pada 2030 tujuan “Zero Hunger” sulit tercapai tanpa aksi multisektoral besar-besaran. MDPI
Indonesia: Meski produksi pangan meningkat, dampak iklim seperti El Niño telah mengurangi produksi padi nasional hingga lebih dari 1 juta ton dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan tekanan pada ketahanan pangan domestik. hijau.bisnis.com
Indonesia mencerminkan tren global: ketahanan pangan tetap rentan terhadap perubahan iklim, sekaligus tantangan nutrisi berkelanjutan.
4. Ekonomi & Kelas Menengah
Global: Proyeksi global menunjukkan pertumbuhan kelas menengah di banyak kawasan berkembang, yang memperluas pasar global dan konsumsi. Walaupun data spesifik global 2030 bervariasi, kelas menengah menjadi motor konsumsi terbesar di dunia. irp.fas.org
Indonesia: Diperkirakan pertumbuhan kelas menengah domestik mencapai puluhan juta, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional ≈ 5–6% per tahun hingga 2030. STAIDA SUMSEL – A Journey to Excellence.
Baik global maupun Indonesia menunjukkan bahwa kelas menengah tumbuh pesat, menciptakan dinamika konsumsi baru sekaligus risiko ketimpangan.
5. Risiko Iklim & Ekonomi
Global: Perubahan iklim diperkirakan dapat memotong PDB per kapita global hingga 20–24% di akhir abad ini jika mitigasi tidak efektif, menunjukkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi global. lestari.kompas.com
Indonesia: Efek iklim terhadap produksi pertanian dan ekonomi domestik telah terbukti nyata, dengan risiko menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya pangan, dan memperberat beban pemerintah untuk mitigasi dan adaptasi. hijau.bisnis.com
Keduanya memperlihatkan bahwa iklim adalah variabel ekonomi utama abad ini: bukan gangguan sementara, tetapi faktor struktural risiko.
Kesimpulan Perbandingan
Secara umum, proyeksi global 2030 dan kondisi serta proyeksi Indonesia menunjukkan pola yang sejalan dalam banyak hal, yakni:
- Urbanisasi semakin dominan sebagai fenomena global dan domestik.
- Masalah gizi ganda (obesitas & malnutrisi) menjadi tantangan struktural.
- Ketahanan pangan tetap rentan terhadap variabilitas iklim dan dinamika produksi.
- Kelas menengah berkembang sebagai kekuatan ekonomi baru.
- Perubahan iklim membawa risiko ekonomi jangka panjang yang nyata.
Namun, terdapat pula perbedaan kontekstual penting: Indonesia—sebagai negara berkembang besar—menghadapi bonus demografi (jumlah angkatan kerja produktif tinggi di 2030) yang belum dialami oleh banyak negara maju yang populasi menua. STAIDA SUMSEL – A Journey to Excellence.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa tantangan global bersifat simultan sekaligus berbeda menurut konteks negara, bahkan ketika pola umum tren besar sama. Hal ini menegaskan bahwa strategi adaptasi dan kebijakan keberlanjutan harus disesuaikan secara lokal sambil tetap terhubung dengan dinamika global — sebuah refleksi yang sangat sejalan dengan tema besar buku 2030 Mauro Guillén.
Berikut tabel komparatif ringkas antara Proyeksi Global 2030 dan Indonesia 2030, disusun dari tren yang dibahas dalam 2030 (Mauro F. Guillén) dan konteks Indonesia:
Tabel Komparatif: Proyeksi Global 2030 vs Indonesia 2030
| Dimensi | Global (2030) | Indonesia (±2030) | Makna Strategis |
| Jumlah Penduduk | ± 8,5 miliar jiwa | ± 300 juta jiwa | Dunia memasuki fase kepadatan dan kompleksitas; Indonesia menjadi salah satu negara besar penentu arah demografi global |
| Struktur Usia | Populasi menua di Eropa, Jepang, Tiongkok; baby boom di Afrika | Bonus demografi masih berlangsung, proporsi usia produktif tinggi | Indonesia berpotensi “menang waktu” jika lapangan kerja & pendidikan tersedia |
| Urbanisasi | ± 60% penduduk dunia tinggal di kota | ± 70% penduduk tinggal di wilayah perkotaan | Kota menjadi pusat risiko sekaligus solusi (ekonomi, iklim, kesehatan) |
| Kelas Menengah | Pertumbuhan terbesar di Asia & Afrika; Tiongkok jadi pasar utama | Kelas menengah tumbuh cepat namun rentan turun kelas | Konsumsi meningkat, tetapi ketimpangan dan ketahanan ekonomi jadi isu krusial |
| Kelaparan & Ketahanan Pangan | ± 200 juta orang masih berisiko kelaparan | Produksi pangan tertekan iklim; ketergantungan impor strategis | Ketahanan pangan menjadi isu keamanan nasional |
| Obesitas & Kesehatan | ± 1,1 miliar orang obesitas | Obesitas meningkat bersamaan dengan stunting | Beban ganda kesehatan: kelebihan dan kekurangan gizi sekaligus |
| Perubahan Iklim | Kota pesisir terancam; emisi didominasi kawasan urban | Wilayah pesisir, pulau kecil, & pertanian sangat rentan | Indonesia berada di “frontline” krisis iklim |
| Ekonomi Global | Pergeseran pusat ekonomi ke Asia | Target pertumbuhan ± 5–6% per tahun | Integrasi global membuka peluang sekaligus paparan guncangan eksternal |
| Teknologi & Digitalisasi | Lebih banyak ponsel daripada toilet; AI & platform dominan | Digitalisasi cepat tapi infrastruktur & literasi timpang | Risiko kesenjangan digital sekaligus peluang lompatan pembangunan |
| Risiko Sosial-Politik | Polarisasi, migrasi, krisis kepercayaan institusi | Ketimpangan, tekanan urban, disinformasi | Stabilitas sosial bergantung pada tata kelola dan keadilan |
Catatan Akhir
Secara komparatif, Indonesia mencerminkan miniatur dunia 2030:
- Urbanisasi cepat,
- Tekanan iklim nyata,
- Pertumbuhan kelas menengah yang rapuh,
- Dan pertarungan antara peluang teknologi dan risiko ketimpangan.
Perbedaannya, Indonesia belum terjebak sepenuhnya dalam jebakan penuaan seperti negara maju, tetapi justru menghadapi ujian institusional: apakah bonus demografi dan pertumbuhan kota akan dikelola sebagai collective capability (Amartya Sen), atau justru menjadi sumber krisis sosial ala disembedding yang diperingatkan Karl Polanyi.
Guillén tidak menutup bukunya dengan optimisme kosong. Ia menawarkan apa yang bisa disebut optimisme bersyarat—masa depan bisa lebih adil dan berkelanjutan, jika kita membaca tanda-tanda zaman dengan jujur dan bertindak lintas sektor.
Seperti kata penyair W.H. Auden: “We must love one another or die.” Dalam bahasa Guillén, kita bisa mengatakan: kita harus belajar beradaptasi bersama—atau menanggung konsekuensinya sendirian.
Cirebon, 10 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Guillén, M. F. (2020). 2030: How today’s biggest trends will collide and reshape the future of everything. New York, NY: St. Martin’s Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom. New York, NY: Knopf.
Arendt, H. (1958). The human condition. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Wadud, A. (2006). Inside the gender jihad: Women’s reform in Islam. Oxford: Oneworld Publications.
UN DESA. (2019). World population prospects. https://www.un.org/development/desa
IPCC. (2018). Global warming of 1.5°C. https://www.ipcc.ch
OECD. (2025). Indonesia: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. OECD. OECD
United Nations. (2024). UNdata – Indonesia demographic indicators. UN. UNdata
Kompas.id. (2024, Oct). Krisis Iklim Mengancam Ketahanan Pangan. Kompas
WRI Indonesia. (2025). The hidden cost of Indonesia’s food system. wri-indonesia.org
Nature Scientific Reports. (2025). Trends in double burden of malnutrition among Indonesian adults. Nature
Kompas.id. (2024). Simalakama Pertanian dalam Perubahan Iklim. Kompas