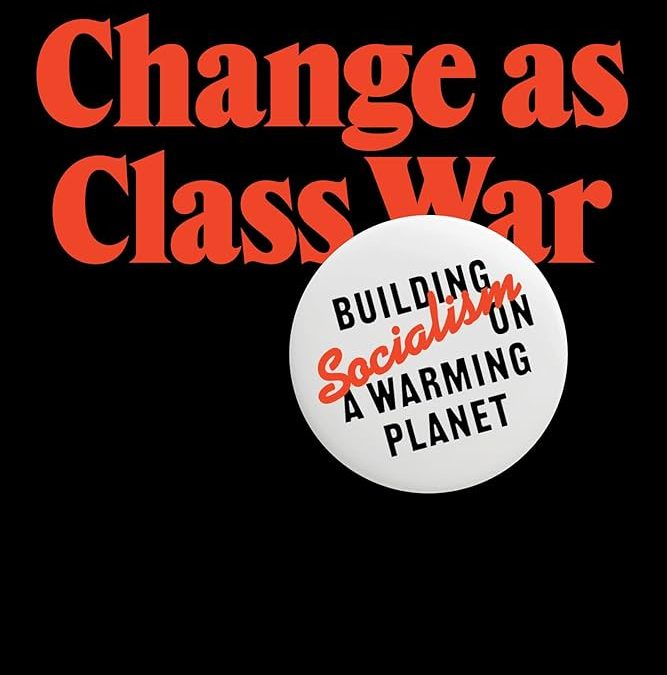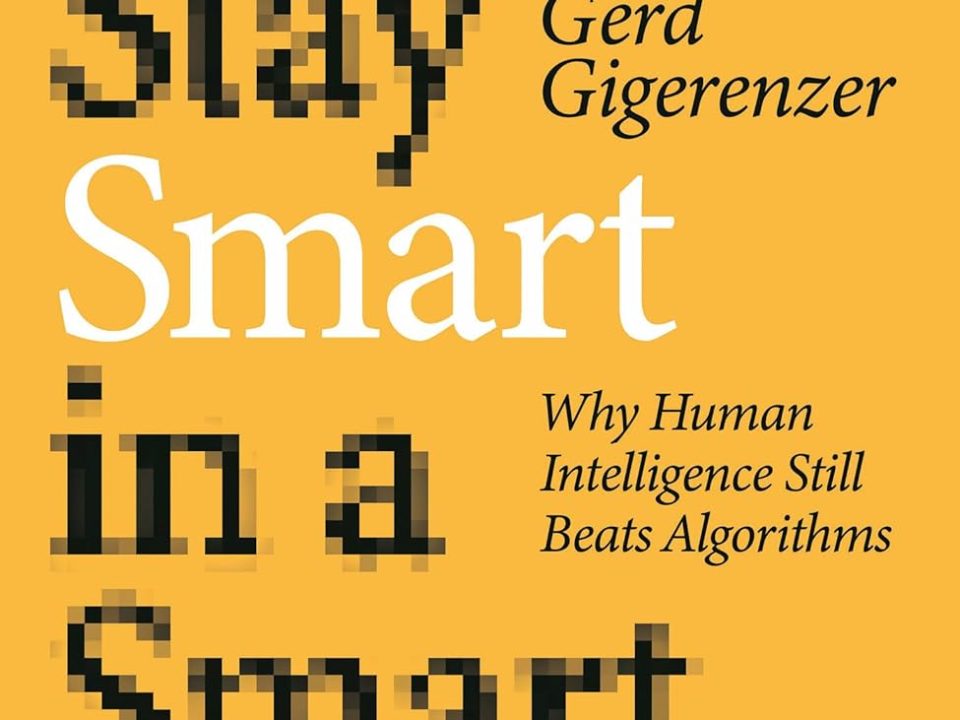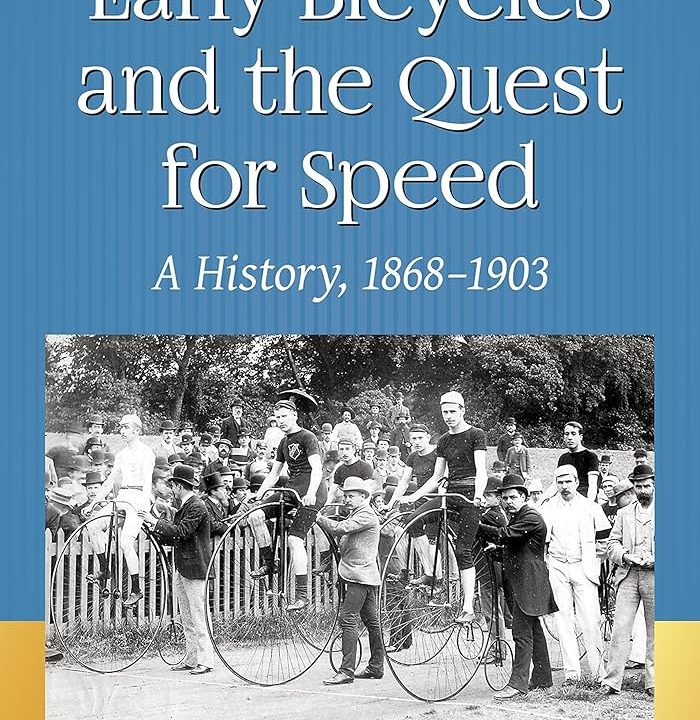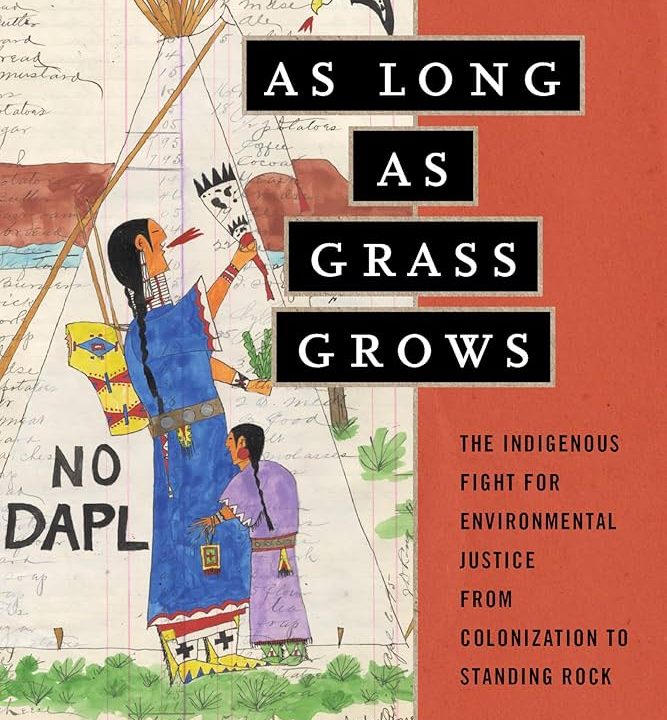Rubarubu #79
Climate Change as Class War:
Krisis Iklim sebagai Krisis Kekuasaan
Matthew T. Huber membuka Climate Change as Class War: Building Socialism on a Warming Planet (Verso, 2022) dengan sebuah klaim yang sengaja provokatif, sekaligus membongkar konsensus populer dalam diskursus iklim kontemporer: “Climate change is not the result of individual consumption choices, cultural values, or abstract ‘humanity.’ It is the outcome of class power.” (Huber, 2022). Dalam buku ini, Huber menolak narasi dominan yang menyalahkan “kita semua” sebagai penyebab krisis iklim. Ia menganggap bahasa seperti Anthropocene, overpopulation, atau consumer responsibility justru mengaburkan kenyataan politik yang jauh lebih tajam: emisi karbon adalah hasil dari sistem produksi kapitalis yang dikendalikan oleh kelas tertentu, bukan akibat pilihan moral individu semata.
Krisis iklim, bagi Huber, bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi konflik struktural antara kelas kapital dan kelas pekerja, sebuah class war yang berlangsung melalui energi, infrastruktur, dan negara.
Mengapa Narasi Iklim Saat Ini Gagal
Terdapat kritik terhadap “Climate Populism” dan moral ekologi. Huber secara tajam mengkritik apa yang ia sebut sebagai climate populism: pendekatan iklim yang menekankan perubahan gaya hidup, kesadaran moral, dan tekanan budaya—seperti mengurangi konsumsi daging, menghindari plastik, atau mengubah perilaku individu. Ia menunjukkan bahwa pendekatan ini:
gagal menurunkan emisi secara struktural, cenderung menyalahkan kelas pekerja, dan tidak menyentuh pusat kekuasaan ekonomi.
“Fossil fuels are burned not because consumers want them, but because capital accumulation depends on them.” (Huber, 2022). Contoh yang ia gunakan adalah sektor energi dan perumah-an di Amerika Serikat: rumah-rumah suburban boros energi bukan karena pilihan bebas konsumen, tetapi karena rezim pembangun-an, subsidi negara, dan logika keuntungan industri properti dan energi. Di sini, Huber sejalan dengan kritik Andreas Malm: “Capitalism is a system that turns fossil fuels into power.” (Malm, Fossil Capital, 2016).
Emisi, Energi, dan Kekuasaan Kelas. Energi, disadari atau tidak, sebagai infrastruktur kekuasaan. Bagian inti buku ini menjelaskan bahwa energi bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi material kekuasaan kelas kapital. Kapitalisme modern berkembang melalui energi murah, terkonsentrasi, dan dapat dikendalikan—terutama bahan bakar fosil. Huber menelusuri bagaimana: perusahaan energi, sektor transportasi, industri manufaktur, dan sistem logistik global, bergantung pada kontrol terpusat atas energi. “Decarbonization is not a technological challenge first and foremost; it is a political challenge.” (Huber, 2022).
Ia menolak ilusi bahwa transisi energi akan terjadi secara “alami” melalui pasar atau inovasi hijau tanpa konflik kelas.
Negara: Arena Kunci Perang Iklim. Berbeda dengan aktivisme iklim yang sering curiga pada negara, Huber menegaskan bahwa negara adalah aktor kunci dalam transisi energi. Ia me-nunjukkan bahwa: subsidi energi fosil, pembangunan jaringan listrik, transportasi publik,
dan perumahan hemat energi, selalu melibatkan intervensi negara dalam skala besar.
“There is no decarbonization without state planning.” (Huber, 2022). Dalam hal ini, Huber menghidupkan kembali tradisi sosialisme klasik—bukan sebagai nostalgia ideologis, tetapi sebagai strategi praktis menghadapi krisis iklim. Pandangan ini beresonansi dengan Karl Polanyi: “Laissez-faire was planned.” (The Great Transformation, 1944).
Jika kapitalisme diciptakan melalui kebijakan negara, maka transisi pasca-karbon pun harus direncanakan secara politik.
Sosialisme sebagai Proyek Iklim. Buku ini menguraikan aspek lain yang penting adanya gerakan dari environmentalism ke working-class climate politics. Huber mengusulkan pergeseran radikal: dari environmentalism menuju politik iklim berbasis kelas pekerja. Alih-alih menuntut pengorbanan individu, ia mengajukan program yang menjanjikan: pekerjaan hijau bergaji layak, energi murah dan publik, transportasi massal, perumahan terjangkau dan efisien. “The working class will not support climate politics that make life harder.” (Huber, 2022).
Di sini, ia mengkritik keras narasi “degrowth” yang sering gagal menjelaskan siapa yang harus mengorbankan apa. Tanpa keadilan kelas, politik iklim akan selalu rapuh.
Bagi Huber, sosialisme bukan sekadar ideologi ekonomi, melainkan prasyarat material untuk keberlanjutan planet. Sosialisme bagi energi dan masa depan peradaban. Ia menutup buku dengan argumen bahwa: krisis iklim tidak bisa diselesaikan oleh pasar, teknologi tanpa politik akan gagal, dan moralitas tanpa kekuasaan adalah ilusi. “Climate change is class war—whether we like it or not.” (Huber, 2022).
Pandangan ini selaras dengan pemikir Muslim kontemporer seperti Ali Shariati, yang menulis:
“Ketidakadilan struktural adalah bentuk kekufuran sosial.” Serta dengan kritik ekologis Seyyed Hossein Nasr, yang melihat krisis lingkungan sebagai akibat dari pemutusan etika kosmologis dan ekonomi (Man and Nature, 1968).
The Capitalist Class
Bagi Huber krisis iklim merupakan produk kekuasaan kapital. Bab pertama Climate Change as Class War berfungsi sebagai fondasi teoretis dan politis seluruh buku. Di sinilah Matthew T. Huber meletakkan tesis intinya secara sistematis: krisis iklim bukan disebabkan oleh umat manusia secara abstrak, melainkan oleh cara kapitalisme industri mengorganisasi produksi, energi, dan alam di bawah kendali kelas kapitalis. Alih-alih memulai dari konsumsi individu atau etika lingkungan, Huber kembali ke pertanyaan klasik Marxis: siapa yang menguasai alat produksi, dan untuk tujuan apa?
Judul subbab The Hidden Abode of the Climate Crisis ini mengacu langsung pada istilah Karl Marx, “the hidden abode of production”—ruang tersembunyi tempat eksploitasi sesungguhnya terjadi. Huber mengadaptasi konsep ini ke dalam konteks krisis iklim: akar emisi karbon tersembunyi bukan di dapur rumah tangga, tetapi di pabrik, jaringan energi, dan sistem produksi industri. Industrial capital yang seharusnya menjadi sosok climate responsibility.
Huber secara tegas melemparkan kritik terhadap narasi konsumen dan menolak narasi populer yang menyalahkan: gaya hidup individu, pilihan konsumsi, atau “kesadaran lingkungan” yang kurang. Menurutnya, narasi ini menyimpangkan tanggung jawab dari kelas kapitalis yang: mengontrol sistem energi, menentukan teknologi produksi, dan membentuk infrastruktur sosial. “The bulk of carbon emissions are locked into systems of production over which consumers have little control.” (Huber, 2022, Bab 1).
Sebagai contoh, seseorang tidak “memilih” untuk: tinggal di kota tanpa transportasi publik,bergantung pada listrik berbasis batu bara, atau bekerja di sektor yang intensif karbon.
Pilihan-pilihan ini dibentuk oleh struktur ekonomi dan kebijakan negara yang melayani kepentingan kapital. Huber menunjukkan adanya tanggung jawab historis kapital industri karena sejak Revolusi Industri, kapitalisme berkembang melalui: sentralisasi produksi, peningkatan skala industri, dan ketergantungan pada energi fosil murah. Emisi karbon meningkat bukan karena populasi semata, melainkan karena logika akumulasi kapital yang menuntut: efisiensi biaya,ekspansi terus-menerus, dan penguasaan alam sebagai input produksi. Contoh dunia nyata:
- 100 perusahaan fosil terbesar bertanggung jawab atas lebih dari 70% emisi global sejak 1988 (Carbon Majors Report).
- ExxonMobil, Shell, BP, dan Chevron telah mengetahui dampak iklim dari produk mereka sejak 1970-an, namun secara aktif mendanai disinformasi iklim.
Dalam kerangka Huber, ini bukan sekadar “kejahatan korporasi”, melainkan fungsi sistemik kapitalisme itu sendiri.
Carbon Exploitation
Subbab kedua, How the Nitrogen Cycle Became Fossil Capital, membawa pembaca ke wilayah yang lebih teknis namun krusial: hubungan antara kapitalisme, energi fosil, dan metabolisme alam, khususnya melalui siklus nitrogen. Dari metabolisme alam ke metabolisme kapital. Huber memanfaatkan konsep metabolic rift (keretakan metabolik) yang dikembangkan oleh Marx dan diperluas oleh John Bellamy Foster. Ia menunjukkan bagaimana kapitalisme: memisahkan produksi dari siklus ekologis alami, lalu menggantikannya dengan input energi fosil.
Salah satu contoh terpenting adalah industrialisasi pertanian melalui proses Haber–Bosch (awal abad ke-20), yang memungkinkan produksi pupuk nitrogen sintetis berbasis bahan bakar fosil. “The nitrogen cycle was effectively subordinated to fossil capital.” (Huber, 2022, Bab 1)
Sementara itu dalam sektor Pertanian, Energi, dan Emisi yang terjadi adalah: Dengan pupuk sintetis: produksi pangan melonjak, ketergantungan pada minyak dan gas meningkat, dan emisi gas rumah kaca (terutama N₂O) melonjak tajam. Pertanian modern tidak lagi berbasis ekologi lokal, tetapi: bergantung pada rantai pasok global, mesin berat berbahan bakar fosil, dan industri petrokimia. Contoh dunia nyata:
- Industri pupuk menyumbang sekitar 5% emisi global.
- Limpasan nitrogen menciptakan dead zones di laut (misalnya Teluk Meksiko).
- Negara-negara agraris di Global South menjadi bergantung pada input impor, memperdalam ketimpangan global.
Dalam pandangan Huber, ini adalah bentuk eksploitasi ganda: eksploitasi tenaga kerja, dan eksploitasi metabolisme alam.
Kelas Kapital sebagai Subjek Krisis Iklim
Bab ini menyimpulkan bahwa:
- krisis iklim adalah produk relasi produksi kapitalis,
- kelas kapital menguasai keputusan energi dan teknologi,
- sementara biaya ekologis dialihkan ke masyarakat luas dan generasi mendatang.
“Climate change is not humanity’s failure; it is capital’s success.” Di sinilah Huber menyiapkan langkah berikutnya dalam buku: jika krisis ini adalah perang kelas, maka solusinya juga harus bersifat kelas dan politik, bukan moralistik atau teknokratik semata.
Pandangan Huber dapat dibaca sejajar dengan:
- Andreas Malm – Fossil Capital
- John Bellamy Foster – The Ecological Rift
- Jason W. Moore – Capitalism in the Web of Life
Namun keunikan Huber terletak pada penekanan strategis: ia tidak berhenti pada diagnosis ekologis, tetapi mengarah pada agenda politik kelas pekerja sebagai subjek transisi iklim.
Menyingkap Ruang Tersembunyi Krisis Iklim
Matthew T. Huber membuka Climate Change as Class War dengan sebuah pembalikan sudut pandang yang tajam. Alih-alih memulai dari perilaku manusia secara umum—seperti konsumsi energi rumah tangga, gaya hidup boros, atau kurangnya kesadaran lingkungan—ia mengajak pembaca masuk ke apa yang oleh Karl Marx disebut sebagai the hidden abode of production. Di sanalah, menurut Huber, krisis iklim sesungguhnya berakar: bukan pada individu sebagai konsumen, melainkan pada sistem produksi kapitalis yang dikendalikan oleh kelas kapital industri.
Dalam subbab “The Hidden Abode of the Climate Crisis”, Huber membongkar ilusi bahwa perubahan iklim adalah akibat pilihan moral manusia sehari-hari. Narasi populer tentang jejak karbon pribadi, daur ulang, atau pilihan konsumsi hijau, menurutnya, justru berfungsi sebagai tirai ideologis yang menutupi sumber utama emisi. Mayoritas karbon dioksida tidak dihasilkan oleh keputusan individu, melainkan oleh infrastruktur energi dan produksi yang telah “dikunci” oleh kepentingan kapital selama lebih dari satu abad. Orang-orang tidak benar-benar memilih sistem transportasi berbasis mobil, listrik dari batu bara, atau kota tanpa ruang hijau; mereka hidup di dalam sistem yang dibangun untuk memaksimalkan akumulasi keuntungan.
Huber menegaskan bahwa sejak Revolusi Industri, kapitalisme berkembang melalui perluasan skala produksi yang sangat bergantung pada energi fosil murah. Batu bara, minyak, dan gas bukan sekadar sumber energi netral, melainkan fondasi material dari kekuasaan kelas kapital. Di sinilah tanggung jawab iklim menjadi persoalan kelas. Segelintir perusahaan energi dan industri berat—yang mengendalikan teknologi, investasi, dan kebijakan—memiliki peran yang sangat tidak sebanding dalam menciptakan krisis yang dampaknya ditanggung oleh masyarakat luas. Fakta bahwa sebagian besar emisi historis dapat ditelusuri ke segelintir korporasi bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang memprioritaskan keuntungan di atas keberlanjutan ekologis.
Dari sini, Huber membawa pembaca ke subbab kedua, “Carbon Exploitation: How the Nitrogen Cycle Became Fossil Capital”, yang memperdalam analisis dengan menyoroti hubungan antara kapitalisme, energi fosil, dan metabolisme alam. Ia mengembangkan gagasan metabolic rift—keretakan antara masyarakat manusia dan siklus ekologis—untuk menunjukkan bagaimana kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja, tetapi juga menginterupsi dan menun-dukkan proses-proses alamiah demi kebutuhan produksi.
Salah satu contoh paling penting adalah transformasi siklus nitrogen. Dengan ditemukannya proses Haber–Bosch pada awal abad ke-20, nitrogen atmosfer dapat diubah menjadi pupuk sintetis dalam skala industri, memungkinkan lonjakan produksi pangan yang luar biasa. Namun, keberhasilan ini datang dengan harga ekologis yang mahal. Pertanian modern menjadi se-penuhnya bergantung pada bahan bakar fosil, dari produksi pupuk hingga mesin-mesin berat dan transportasi global. Alam tidak lagi menjadi sistem yang berputar secara relatif seimbang, melainkan sekadar sumber daya yang dipaksa mengikuti ritme akumulasi kapital.
Huber menunjukkan bahwa ketergantungan ini menciptakan rantai kerusakan yang panjang: emisi gas rumah kaca meningkat, tanah dan air tercemar nitrogen, dan ekosistem laut mati akibat limpasan pupuk. Di saat yang sama, negara-negara agraris—terutama di Global South—menjadi semakin tergantung pada input industri yang mahal, memperdalam ketimpangan ekonomi dan ekologis global. Apa yang tampak sebagai kemajuan teknologi pertanian, dalam kerangka Huber, sebenarnya adalah contoh bagaimana kapitalisme mengubah metabolisme alam menjadi mesin eksploitasi berkelanjutan.
Bab ini secara keseluruhan membangun argumen bahwa krisis iklim bukan kegagalan moral umat manusia, melainkan keberhasilan sistem kapitalis dalam mengorganisasi produksi secara destruktif namun efisien. Kelas kapital bukan sekadar aktor pasif dalam perubahan iklim; merekalah subjek historis yang secara aktif membentuk sistem energi, pertanian, dan industri yang memanaskan planet. Dengan demikian, solusi krisis iklim tidak dapat direduksi menjadi perubahan perilaku individual atau inovasi teknologi semata. Ia menuntut konfrontasi politik dengan struktur kekuasaan kelas yang mengendalikan produksi dan energi.
Bab I ini menjadi landasan bagi seluruh buku: jika perubahan iklim adalah bentuk perang kelas yang terwujud dalam bentuk ekologis, maka jalan keluar yang realistis dan adil hanya mungkin melalui transformasi politik yang menantang dominasi kapital dan menempatkan kebutuhan sosial serta keberlanjutan ekologis di pusat pengambilan keputusan.
The Professional Class
Bagi Huber kini pengetahuan, moralitas, dan politik iklim telah terprivatisasi. Setelah me-nempatkan kelas kapital sebagai aktor struktural utama krisis iklim, Matthew T. Huber beralih pada kelas sosial yang tampaknya berada di sisi berlawanan dari kapital fosil, namun menurut-nya justru memainkan peran problematis dalam politik iklim kontemporer: kelas profesional. Bab ini membongkar paradoks yang tidak nyaman—bahwa sebagian besar wacana iklim progresif hari ini diproduksi dan dimediasi oleh kelompok yang secara material relatif ter-lindungi dari dampak terburuk krisis iklim, sekaligus diuntungkan oleh struktur ekonomi yang ada.
Dalam subbab “Credentialed Politics: Knowing the Climate Crisis”, Huber menyoroti bagai-mana krisis iklim telah menjadi medan produksi pengetahuan yang sangat terspesialisasi. Ilmuwan, akademisi, analis kebijakan, konsultan lingkungan, dan profesional NGO memegang otoritas epistemik yang besar dalam mendefinisikan apa itu krisis iklim, bagaimana ia dipahami, dan solusi apa yang dianggap sah. Pengetahuan tentang iklim menjadi sesuatu yang “dikredensialkan”—hanya mereka yang memiliki gelar, sertifikasi, atau posisi institusional tertentu yang diakui sebagai suara rasional dan sah.
Masalahnya, menurut Huber, politik yang dibangun di atas otoritas teknokratik ini cenderung menjauh dari konflik kelas dan relasi produksi. Krisis iklim direduksi menjadi persoalan manajemen risiko, optimasi kebijakan, dan perubahan perilaku yang “berbasis bukti”, sementara pertanyaan tentang kepemilikan energi, kontrol atas industri, dan kekuasaan ekonomi dikesampingkan sebagai terlalu ideologis atau tidak pragmatis. Pengetahuan yang seharusnya membuka ruang pembebasan justru berfungsi sebagai mekanisme depolitisasi.
Huber tidak menyangkal pentingnya sains iklim. Ia mengakui bahwa tanpa kerja ilmiah, krisis ini bahkan tidak akan terlihat. Namun ia menegaskan bahwa pengetahuan tidak netral secara politik. Ketika pengetahuan iklim dimonopoli oleh kelas profesional, ia cenderung diterjemah-kan ke dalam bahasa kebijakan yang kompatibel dengan kapitalisme—seperti pasar karbon, insentif hijau, dan inovasi teknologi—alih-alih bahasa perjuangan kelas atau keadilan struktural. Dalam praktiknya, ini menghasilkan politik iklim yang canggih secara teknis namun lemah secara sosial.
Subbab berikutnya, “Carbon Guilt: Privatized Ecologies, Degrowth, and the Politics of Less”, membawa kritik ini ke ranah moral dan budaya. Di sini Huber membedah fenomena yang sangat akrab dalam diskursus lingkungan kontemporer: rasa bersalah karbon. Individu—terutama dari kelas menengah terdidik—didorong untuk terus-menerus mengaudit jejak karbon pribadi mereka, mengurangi konsumsi, terbang lebih sedikit, makan lebih “berkelanjut-an”, dan hidup lebih sederhana. Sekilas, etos ini tampak radikal dan etis. Namun Huber melihatnya sebagai bentuk privatisasi tanggung jawab ekologis.
Dalam kerangka ini, krisis iklim berubah menjadi masalah etika personal, bukan konflik politik. Fokus pada “hidup lebih sedikit” sering kali mengabaikan fakta bahwa sebagian besar emisi berasal dari sistem produksi yang berada di luar kendali individu. Lebih jauh, politik pengurang-an konsumsi—yang sering dikemas dalam wacana degrowth versi moralistik—secara implisit menuntut pengorbanan dari mereka yang sebenarnya tidak menikmati kemewahan material sejak awal. Bagi kelas pekerja yang masih berjuang untuk akses terhadap perumahan layak, energi murah, dan mobilitas, seruan untuk “mengurangi” justru terasa sebagai pembatasan tambahan, bukan pembebasan.
Huber menekankan bahwa kelas profesional, dengan pendapatan relatif stabil dan fleksibilitas gaya hidup, lebih mampu menjadikan pengurangan konsumsi sebagai simbol kebajikan moral. Di sisi lain, kelas pekerja sering kali bergantung pada infrastruktur karbon-intensif bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan. Dengan demikian, politik karbon berbasis rasa bersalah berisiko memperdalam jurang kelas, sekaligus melemahkan potensi solidaritas politik yang luas.
Lebih problematis lagi, fokus pada moralitas individu memberi ruang bagi kelas kapital untuk menghindari tanggung jawab struktural. Selama krisis iklim dipahami sebagai akibat dari akumulasi pilihan pribadi yang buruk, sistem produksi industri dapat terus berjalan dengan sedikit gangguan. Dalam bahasa Huber, ini adalah bentuk politik iklim yang “aman”—cukup radikal untuk mengubah gaya hidup kelas menengah, tetapi tidak cukup radikal untuk menantang kepemilikan dan kontrol atas energi dan industri.
Bab II ini dengan demikian berfungsi sebagai kritik internal terhadap gerakan iklim progresif itu sendiri. Huber tidak menolak kepedulian moral atau pengetahuan ilmiah, tetapi ia mem-peringatkan bahwa tanpa orientasi kelas yang jelas, keduanya dapat berubah menjadi penghalang bagi perubahan yang lebih mendasar. Politik iklim yang terlalu bergantung pada kredensial, rasa bersalah, dan pengorbanan individu justru menjauhkan proyek transisi ekologis dari basis sosial yang paling menentukan: kelas pekerja.
Dengan menutup bab ini, Huber menyiapkan argumen lanjutannya: jika kelas kapital adalah sumber struktural krisis, dan kelas profesional sering kali memproduksi politik iklim yang terlepas dari konflik kelas, maka pertanyaan kunci berikutnya adalah bagaimana membangun politik iklim yang benar-benar berakar pada kepentingan dan kekuatan kelas pekerja. Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya.
The Working Class
Pada bagian The Working Class ini Huber menguraikan tentang Proletarian Ecology dan Politik Harapan Material. Setelah membongkar peran kelas kapital sebagai penggerak struktural krisis iklim dan mengkritik keterbatasan politik iklim kelas profesional, Matthew T. Huber mengakhiri kerangka kelasnya dengan beralih ke subjek yang menurutnya menentukan arah masa depan: kelas pekerja. Dalam bab “Proletarian Ecology: Working Class Interests and the Struggle for a Green New Deal”, Huber menolak anggapan bahwa kepentingan kelas pekerja secara inheren bertentangan dengan agenda ekologis. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa krisis iklim justru membuka peluang historis untuk menyatukan perjuangan ekologis dan perjuangan material kelas pekerja.
Huber memulai dengan menantang stereotip yang sering muncul dalam wacana lingkungan: bahwa kelas pekerja dianggap “tidak peduli lingkungan”, terlalu fokus pada pekerjaan, upah, dan keamanan ekonomi untuk memikirkan planet. Menurutnya, pandangan ini tidak hanya keliru, tetapi juga politis, karena mengabaikan fakta bahwa kelas pekerja adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim—mulai dari bencana alam, polusi industri, hingga ketidakstabilan ekonomi akibat transisi energi yang tidak adil.
Di sinilah Huber memperkenalkan konsep proletarian ecology, sebuah pendekatan yang memahami lingkungan bukan sebagai ruang moral abstrak, melainkan sebagai kondisi material kehidupan sehari-hari. Bagi kelas pekerja, udara bersih, air aman, perumahan layak, dan energi terjangkau bukanlah isu gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar. Ketika pabrik mencemari sungai, ketika panas ekstrem mengancam pekerja konstruksi, atau ketika badai menghancurkan rumah-rumah di wilayah miskin, krisis iklim menjadi pengalaman langsung, bukan sekadar grafik ilmiah.
Namun, Huber juga realistis dalam mengakui ketegangan yang nyata. Banyak pekerjaan kelas pekerja masih bergantung pada industri berbasis karbon, dari pertambangan batu bara hingga manufaktur berat. Karena itu, politik iklim yang hanya menawarkan pembatasan, pengurangan, atau pengorbanan tanpa jaminan material akan sulit mendapatkan dukungan luas. Huber menegaskan bahwa kelas pekerja tidak akan memimpin transisi iklim jika transisi tersebut berarti kehilangan pekerjaan, upah, dan keamanan hidup.
Di sinilah Green New Deal muncul sebagai poros strategis. Bagi Huber, Green New Deal bukan sekadar program lingkungan, melainkan proyek politik kelas yang menjanjikan pekerjaan bergaji layak, investasi publik besar-besaran, dan dekarbonisasi yang dipimpin negara. Ia menawarkan visi di mana transisi energi bukan ancaman, tetapi sumber kesejahteraan kolektif. Dengan menempatkan negara sebagai aktor utama—bukan pasar atau moralitas individu—Green New Deal membuka kemungkinan untuk merebut kembali sistem energi dari kontrol kapital swasta dan mengarahkannya demi kepentingan publik.
Huber menekankan bahwa hanya politik berbasis kelas pekerja yang mampu menandingi kekuatan kapital fosil. Konsumen hijau dan profesional berpendidikan tidak memiliki daya tawar struktural yang sama dengan pekerja yang mengoperasikan, memelihara, dan membangun infrastruktur material masyarakat. Dalam pengertian ini, kelas pekerja bukan sekadar korban krisis iklim, tetapi juga subjek potensial transformasi ekologis.
Dari Perang Kelas Menuju Solidaritas Spesies
Dalam bagian penutup, Huber meluaskan horizon argumennya dari konflik kelas menuju pertanyaan yang lebih eksistensial: bagaimana manusia sebagai spesies akan merespons krisis yang mengancam keberlangsungan kehidupan di Bumi. Namun, alih-alih meninggalkan analisis kelas, ia justru menegaskan bahwa solidaritas spesies hanya mungkin dibangun di atas keadilan sosial dan politik yang nyata.
Huber menolak gagasan abstrak tentang “kita semua bersama-sama” yang sering muncul dalam retorika iklim global. Baginya, seruan persatuan tanpa analisis kekuasaan hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan. Solidaritas spesies tidak berarti menghapus perbedaan kelas, melainkan mengakuinya dan mengatasinya secara politis. Selama segelintir aktor menguasai sumber daya, energi, dan keputusan produksi, “umat manusia” tidak pernah benar-benar menjadi subjek kolektif.
Pada titik inilah Huber menyatukan seluruh argumen bukunya. Krisis iklim adalah persimpangan sejarah: satu jalan mengarah pada otoritarianisme hijau, pengorbanan sepihak, dan konflik sosial yang semakin tajam; jalan lainnya membuka kemungkinan transformasi egaliter, di mana kebutuhan ekologis dan kesejahteraan material tidak dipertentangkan. Pilihan di antara kedua jalan ini tidak akan ditentukan oleh teknologi semata, melainkan oleh kekuatan politik dan aliansi kelas.
Huber mengakhiri bukunya dengan nada yang bersahaja namun tegas. Ia tidak menawarkan utopia tanpa konflik, tetapi juga menolak pesimisme ekologis yang melumpuhkan. Dengan membangun politik iklim yang berakar pada kepentingan kelas pekerja—politik yang menjanjikan pekerjaan, keamanan, dan kontrol demokratis atas energi—manusia dapat mulai membayangkan solidaritas yang melampaui kelas, bahkan melampaui spesies, tanpa mengorbankan keadilan.
Dalam pengertian ini, Climate Change as Class War bukan hanya analisis krisis, melainkan seruan untuk membangun kembali proyek emansipasi di era pemanasan global. Di tengah krisis iklim, Huber mengingatkan bahwa masa depan ekologis Bumi tidak terpisah dari pertanyaan lama yang terus kembali: siapa yang berkuasa, untuk siapa dunia ini diorganisasi, dan atas dasar solidaritas apa kita memilih untuk hidup bersama.
Climate Change as Class War dari Matthew T. Huber ini melengkapi pandangan yang dipaparkan Andreas Malm, John Bellamy Foster, dan Jason W. Moore, yang semuanya bisa disatukan dalam konsep “species solidarity”dari perspektif etika lingkungan.
Krisis iklim pada dasarnya adalah konflik kelas dan krisis peradaban. Huber, Malm, Foster, Moore, mendiskusikan pertanyaan tentang Solidaritas Spesies itu. Matthew T. Huber menutup Climate Change as Class War dengan gagasan species solidarity, sebuah seruan untuk melihat krisis iklim sebagai persoalan bersama umat manusia. Namun, tidak seperti retorika universalistik yang sering menyamarkan ketimpangan, solidaritas spesies versi Huber dibangun di atas fondasi konflik kelas. Baginya, manusia hanya dapat bertindak sebagai spesies kolektif jika relasi produksi kapitalis—yang memecah manusia ke dalam kelas-kelas antagonistik—ditransformasikan terlebih dahulu.
Pendekatan ini menempatkan Huber dalam satu keluarga pemikiran dengan Andreas Malm, John Bellamy Foster, dan Jason W. Moore. Namun, kesamaan genealogis ini tidak berarti keseragaman teoretis. Justru di antara mereka terdapat perbedaan penting tentang bagaimana krisis ekologis harus dipahami, siapa subjek sejarahnya, dan bagaimana solidaritas lintas manusia—bahkan lintas spesies—dapat dibayangkan.
Huber dan Malm secara spesifik bersentuha soal kapital fosil dan politik konfrontasi. Andreas Malm, dalam Fossil Capital dan How to Blow Up a Pipeline, menelusuri asal-usul pemanasan global ke keputusan historis kelas kapital Inggris abad ke-19 yang memilih mesin uap berbasis batu bara demi kontrol atas tenaga kerja. Di sini Malm dan Huber bertemu: krisis iklim bukan akibat “manusia”, melainkan keputusan kelas kapital dalam mengorganisasi produksi.
Namun perbedaannya terletak pada orientasi politik. Malm menekankan urgensi konfrontasi langsung terhadap infrastruktur fosil, bahkan membela tindakan sabotase sebagai respons terhadap kekerasan struktural kapitalisme karbon. Huber, sebaliknya, lebih berhati-hati terhadap politik minoritarian yang terpisah dari basis kelas pekerja. Ia mengkhawatirkan bahwa militansi tanpa proyek material yang inklusif justru mempersempit koalisi sosial. Dengan kata lain, Malm melihat sejarah iklim sebagai tragedi yang menuntut tindakan drastis, sementara Huber melihatnya sebagai konflik kelas yang menuntut hegemoni politik baru. Solidaritas spesies dalam versi Malm muncul dari kesadaran akan ancaman eksistensial, sedangkan bagi Huber, solidaritas tersebut hanya mungkin jika dibangun melalui kepentingan material kelas pekerja.
Sementara jika dibandingkan antara Huber dan pemikiran Foster yang berkaitan dengan metabolic rift dan ekologi politik marxis. John Bellamy Foster memberikan kerangka konseptual yang lebih filosofis melalui teori metabolic rift. Foster membaca Marx sebagai pemikir ekologis yang memahami kapitalisme sebagai sistem yang merusak metabolisme antara manusia dan alam. Dalam perspektif ini, krisis iklim adalah gejala dari keretakan ontologis antara masyarakat manusia dan siklus ekologis.
Huber mengadopsi banyak unsur dari Foster, terutama dalam analisis pertanian, energi, dan eksploitasi alam. Namun ia menggeser fokus dari kritik ontologis menuju strategi politik kelas. Jika Foster bertanya bagaimana kapitalisme merusak relasi manusia-alam, Huber bertanya siapa yang memiliki kekuatan untuk mengubahnya.
Di sinilah solidaritas spesies menjadi problematis secara filosofis. Foster cenderung melihatnya sebagai pemulihan relasi metabolik yang rusak—sebuah rekonsiliasi antara manusia dan alam. Huber lebih pragmatis: solidaritas tersebut harus dimediasi oleh institusi politik, negara, dan kelas sosial. Tanpa itu, “spesies” tetap menjadi abstraksi moral.
Kita bisa juga membandingkan pemikiran Huber dan Moore dalam aspek Kapitalisme dalam Jaring Kehidupan. Jason W. Moore menawarkan kritik paling radikal terhadap cara kita membingkai krisis ekologis. Dalam Capitalism in the Web of Life, ia menolak dikotomi manusia vs alam dan menggantinya dengan konsep oikeios, relasi historis antara manusia dan alam sebagai satu jaringan kehidupan. Moore juga menolak istilah Anthropocene, menggantinya dengan Capitalocene.
Dari perspektif Moore, konsep “species solidarity” berisiko tetap terjebak dalam humanisme modern yang memisahkan manusia dari alam. Solidaritas tidak cukup dipikirkan antar manusia; ia harus mencakup relasi manusia dengan dunia lebih-dari-manusia. Di titik ini, Moore lebih dekat dengan kritik ekologis radikal dan pemikiran pasca-humanis dibandingkan Huber.
Huber, meskipun kritis terhadap kapitalisme, tetap mempertahankan kerangka human-centered politics. Baginya, subjek perubahan adalah kelas pekerja manusia, bukan jaringan kehidupan secara keseluruhan. Di sinilah ketegangan filosofis muncul: apakah krisis iklim adalah konflik kelas manusia, atau krisis peradaban yang melibatkan seluruh biosfer?
Catatan Akhir: Menuju Solidaritas yang Lebih Dalam
Buku ini memberi kita pandangan tentang kritik etika lingkungan. Tetapi juga memahami keterbatasan solidaritas spesies. Dari sudut pandang etika lingkungan, konsep solidaritas spesies mengandung ambiguitas. Di satu sisi, ia melampaui egoisme nasional dan kelas. Namun di sisi lain, ia berisiko memperluas antropo-sentrisme: seolah-olah tujuan utama penyelamatan iklim adalah kelangsungan hidup manusia, bukan integritas ekosistem itu sendiri. Etika lingkungan—dari Aldo Leopold hingga Arne Naess—mengajukan etika tanah dan ekologi dalam yang menuntut pengakuan nilai intrinsik alam. Dalam kerangka ini, solidaritas sejati bukan hanya antar manusia, melainkan antar makhluk hidup. Solidaritas spesies versi Huber masih bersifat instrumental: alam dilindungi karena ia menopang kehidupan manusia.
Dalam pemikiran Islam, krisis ekologis dipahami bukan sebagai konflik spesies, melainkan krisis amanah. Manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh—wakil yang bertanggung jawab, bukan pemilik absolut. Al-Qur’an berulang kali menekankan mizan (keseimbangan) dan melarang fasad fil ardh (kerusakan di bumi).
Dari perspektif ini, solidaritas tidak berhenti pada spesies manusia. Ia meluas menjadi tanggung jawab kosmik terhadap seluruh ciptaan. Bahkan relasi kelas pun harus dibaca dalam kerangka etis yang lebih luas: eksploitasi alam dan eksploitasi manusia adalah dua ekspresi dari ke-sombongan yang sama, yaitu klaim kepemilikan mutlak atas apa yang sejatinya adalah titipan.
Pemikiran Islam dengan demikian menawarkan koreksi normatif terhadap Huber. Politik kelas memang penting, tetapi tanpa etika amanah dan keadilan kosmik, solidaritas spesies berisiko menjadi sekadar strategi bertahan hidup manusia, bukan transformasi moral peradaban.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa Huber memberikan kontribusi penting dengan me-ngembalikan politik iklim ke medan kelas dan kekuasaan material. Namun, ketika ia berbicara tentang solidaritas spesies, ia memasuki wilayah filosofis yang menuntut dialog lebih luas. Malm mengingatkan urgensi konfrontasi, Foster mengingatkan keretakan metabolik, Moore menantang humanisme modern, dan etika lingkungan serta pemikiran Islam meng-ingatkan bahwa krisis ini bukan hanya tentang bertahan hidup, melainkan tentang bagaimana kita hidup bersama—dengan sesama manusia dan dengan seluruh ciptaan.
Climate Change as Class War merupakan kontribusi penting dalam menyikapi krisi iklim. Pemikiran Huber ini merupakan koreksi tajam terhadap environmentalism liberal, pembelaan terhadap politik kelas dalam krisis iklim, dan manifesto sosialisme iklim yang serius secara material.
Buku ini tidak menawarkan kenyamanan moral, tetapi kejelasan konflik. Ia memaksa pembaca untuk memilih: antara kosmetika hijau kapitalisme, atau transformasi struktural yang berani.
Cirebon, 9 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
- Huber, M. T. (2022). Climate Change as Class War: Building Socialism on a Warming Planet. London: Verso.
https://www.versobooks.com/products/2806-climate-change-as-class-war - Malm, A. (2016). Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming. London: Verso.
https://www.versobooks.com/products/171-fossil-capital - Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. New York: Farrar & Rinehart.
- IPCC. (2021). AR6 Working Group I: The Physical Science Basis.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ - Nasr, S. H. (1968). Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man. London: George Allen & Unwin.
- Shariati, A. (1979). On the Sociology of Islam. Berkeley: Mizan Press.