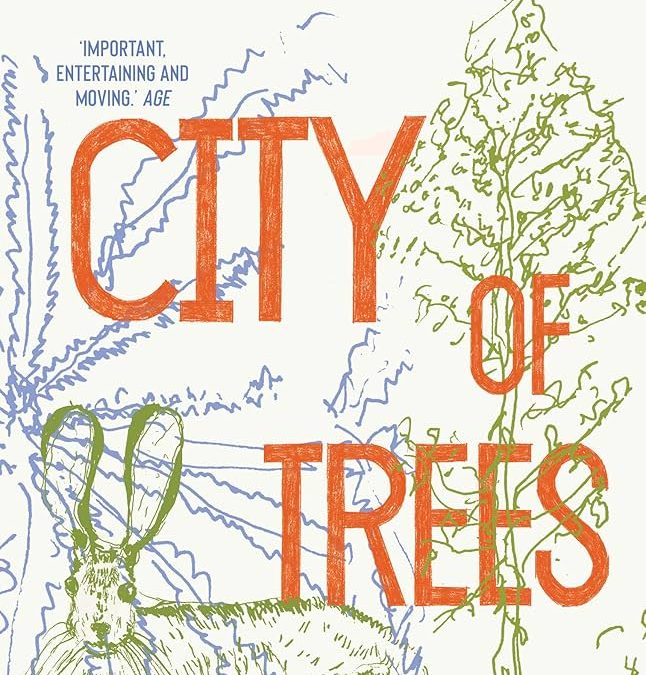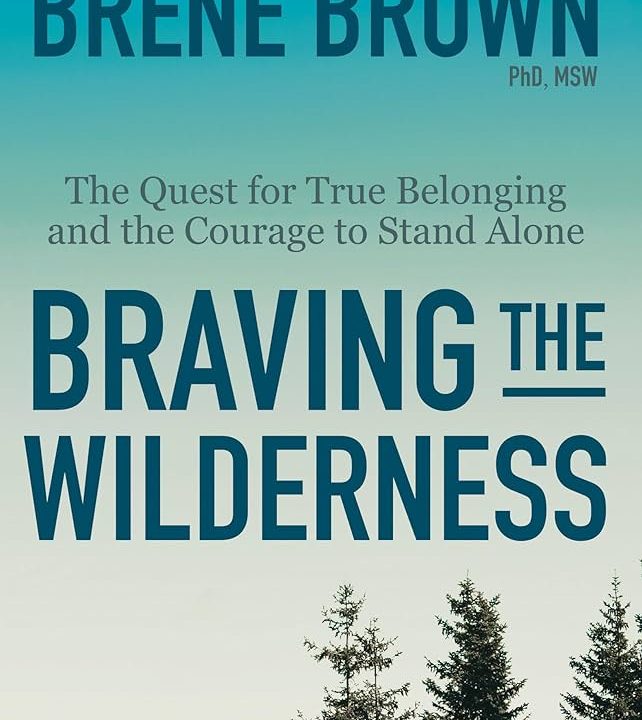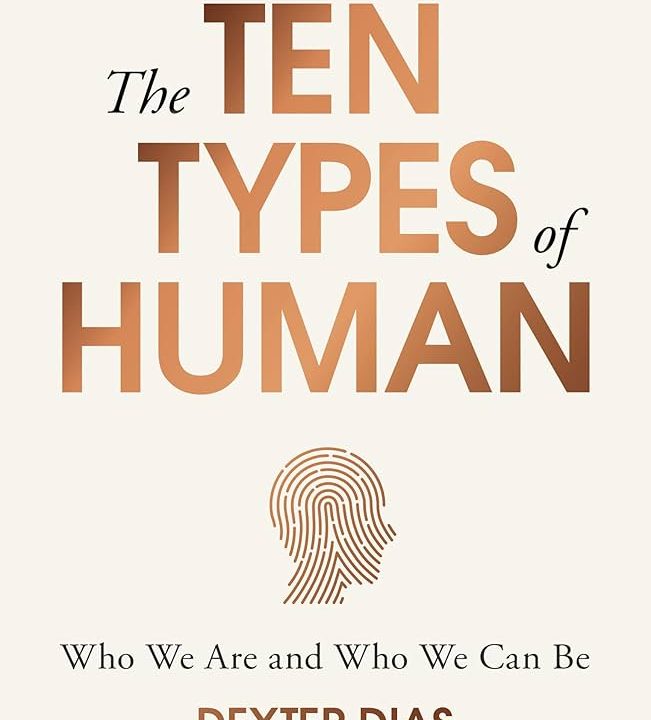Rubarubu #96
City of Trees:
Akar yang Menembus Beton
Di sebuah sudut kota Melbourne yang sibuk, sekelompok warga mempertahankan sebatang pohon Red River Gum (Eucalyptus camaldulensis) yang berusia ratusan tahun dari ancaman pembangunan. Bagi developer, ia adalah halangan. Bagi warga, ia adalah penanda waktu, saksi sejarah, dan makhluk hidup yang menjadi pusat komunitas. Perjuangan ini—antara pertumbuh-an linear kota dan keberlanjutan siklus hidup yang melingkar—adalah jantung dari buku Sophie Cunningham, City of Trees: Essays on Life, Death & the Need for a Forest (2019). Buku ini bukan manual ekologi, tetapi kumpulan esai meditatif yang merajut perjalanan personal sang penulis, sejarah kolonial Australia, ilmu iklim, dan biologi pohon menjadi suatu permadani reflektif tentang duka, ketahanan, dan kebutuhan mendesak kita akan hutan. Cunningham mengajak kita untuk tidak hanya “menyelamatkan pohon”, tetapi untuk belajar dari pohon—tentang cara hidup, cara mati, dan cara bertahan dalam dunia yang rusak. “Pohon adalah makhluk waktu. Mereka mengajarkan kita cara memperlambat, cara melihat, cara berada.” – Sophie Cunningham.
Pohon sebagai Guru dan Sahabat
Bagian pembuka buku ini menetapkan nada dengan membahas spesies-spesies pohon tertentu yang menjadi pintu masuk ke tema-tema universal:
Dimulai dengan Kisah Pohon Ek Pesisir, Coast Live Oak (Quercus agrifolia): Si Tabah Penjaga Memori. Cunningham menggunakan pohon ek pesisir California yang tangguh ini untuk membicarakan tentang ketahanan dan memori. Pohon ini hidup melalui kekeringan dan kebakaran, menyimpan sejarah dalam lingkaran tahunnya. Ia menjadi metafora untuk bagai-mana kita, sebagai individu dan masyarakat, dapat bertahan dari trauma—baik trauma personal seperti kehilangan, maupun trauma kolektif seperti krisis iklim. Pohon ini mengajarkan bahwa bertahan hidup bukan berarti tidak berubah, melainkan beradaptasi sambil tetap menjaga inti diri.
Sophie Cunningham mendekati Quercus agrifolia bukan sebagai spesimen botani semata, melainkan sebagai seorang tetua yang bijak, penuh luka, namun tak terpatahkan. Dalam deskripsinya yang puitis, ia menggambarkannya sebagai makhluk yang “tumbuh dengan per-lahan dan sengaja, seolah-olah waktu adalah sesuatu yang dapat dicicipi, bukan sesuatu yang harus dikejar.” Batangnya yang pendek dan gemuk sering kali bengkok, terkadang tampak seperti sekumpulan naga yang saling melilit, kulitnya yang pecah-pecah menyerupai kulit buaya yang telah melewati badai abadi. Daunnya yang kecil, keras, dan berujung duri adalah adaptasi cerdik terhadap iklim Mediterania California—mereka menghemat setiap tetes embun pagi dan melindungi diri dari kekeringan yang kejam.
Tetapi keajaiban sejati pohon ini, bagi Cunningham, terletak pada akarnya. Dalam esainya, ia bercerita tentang bagaimana sistem akar Live Oak yang luas dan dalam itu bukan hanya menambatkannya ke bumi, tetapi menjadi sebuah arkib hidup. Melalui lingkaran tahun pada kayunya dan pola pertumbuhannya, pohon ini merekam sejarah: tahun-tahun basah yang subur, musim kemarau yang panjang, bahkan jejak kebakaran yang menyapunya. Cunningham menulis, “Ia telah melihat kolonialisme Spanyol datang dan pergi, ia telah merasakan getar gempa bumi, dan ia tetap berdiri sementara kota-kota modern tumbuh dan runtuh di sekitar-nya.” Di bawah kanopinya yang rendah dan menyebar seperti payung raksasa, suku-suku asli California pernah berkumpul, para misionaris Spanyol beristirahat, dan kini para pejalan kaki kota mencari teduh. Ia adalah “living room” alam, ruang publik pertama yang selalu terbuka.
Aktivis dan pemikir India Vandana Shiva berjuang untuk “menjaga benih, menjaga tanah, menjaga masyarakat.” Ini adalah semangat yang sama dengan Cunningham: perawatan ekologis adalah perawatan sosial, dan pohon adalah pusat dari jaringan kehidupan itu.
Aspek sosialnya terungkap dalam narasi Cunningham tentang bagaimana komunitas di California Utara memandang pohon ini. Ia bukan hanya pemandangan; ia adalah tetangga dan penjaga. Cunningham menceritakan kisah warga yang memprotes rencana penebangan sebuah Live Oak tua untuk perluasan jalan. Bagi mereka, kehilangan pohon itu seperti kehilangan seorang kakek yang telah menjadi penanda arah, pemberi identitas, dan saksi kehidupan mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Estetika Live Oak, dalam pandangan Cunningham, bukanlah keindahan yang sempurna dan simetris, melainkan keindahan yang tangguh dan penuh karakter. Setiap lekuk, setiap cabang yang patah dan tumbuh kembali, menceritakan sebuah kisah ketahanan. “Keindahannya,” tulisnya, “terletak pada kemampuan-nya untuk tidak menjadi sempurna, tetapi untuk tetap ada, untuk bertahan melalui segala sesuatu yang telah dilemparkan dunia kepadanya. Ia mengajarkan kita bahwa ketahanan adalah suatu bentuk keanggunan.”
THE FALL: Bab ini adalah refleksi mendalam tentang kehancuran dan kematian. Cunningham yang juga penulis empat buku lainnya, Geography, Bird, Melbourne, dan Warning ini menulis tentang badai dahsyat yang merobohkan ribuan pohon di Melbourne, sebuah peristiwa yang ia saksikan dengan rasa pilu dan kagum. Kehancuran ini memaksanya untuk melihat kematian bukan sebagai akhir yang steril, tetapi sebagai bagian dari siklus ekologi yang subur. Pohon yang tumbang menjadi rumah bagi jamur, serangga, dan regenerasi. “Kita harus belajar bagaimana untuk jatuh, bagaimana untuk gagal, bagaimana untuk membusuk,” tulisnya. Ini adalah pelajaran untuk menerima kerapuhan planet dan diri kita sendiri, sebuah letting go yang diperlukan untuk pertumbuhan baru.
Kisah Sequoia Raksasa: Sang Kolom Waktu yang Bisu, Giant Sequoia (Sequoiadendron giganteum): Menghadap pada raksasa yang berusia ribuan tahun ini, Cunningham berbicara tentang waktu yang dalam dan transendensi. Sequoia adalah makhluk yang hidup dalam skala waktu geologis, membuat hiruk-pikuk urusan manusia tampak fana. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita, sebuah “kebutuhan akan hutan” yang bersifat spiritual—kebutuhan untuk merasa kecil dan terhubung dengan sejarah bumi yang panjang. Keberadaan mereka adalah teguran terhadap keserakahan jangka pendek kita.
Staying With The Trouble: Judul bab ini dipinjam dari frasa ahli biologi feminis Donna Haraway. Di sini, Cunningham menolak narasi keputusasaan atau optimisme kosong tentang krisis ekologi. Sebagai gantinya, ia menganjurkan untuk “tinggal di dalam kesulitan”—untuk sepenuh-nya menghadapi kenyataan pahit perubahan iklim, kepunahan massal, dan kehilangan, tanpa menjadi lumpuh. Ini adalah ajakan untuk tetap hadir, untuk memperhatikan, dan untuk ber-tindak dari tempat yang terinformasi oleh kasih sayang dan pemahaman yang mendalam. “Ini adalah tentang belajar bagaimana meninggalkan dunia yang sekarat dengan baik, dan me-nyambut yang baru, betapapun sulitnya itu,” ia merefleksikan.
Ketika Cunningham menulis tentang Sequoiadendron giganteum, nadanya berubah menjadi penuh kekaguman yang hampir religius. Ia mendeskripsikan pendakiannya ke hutan Sequoia Nasional bukan sebagai perjalanan wisata, melainkan sebagai sebuah ziarah. Pertemuan pertamanya dengan raksasa ini digambarkan sebagai pengalaman yang melampaui kata-kata: “Anda tidak hanya melihatnya; Anda merasakan kehadirannya di tulang-tulang Anda. Udara berubah, menjadi lebih dingin, lebih hening, dan bau tanah yang lembab serta kayu purba memenuhi paru-paru.”
Dari sisi biologis, Cunningham terpesona oleh skala yang tak terpahami. Ia bercerita tentang bagaimana kulit kayu Sequoia yang tebal, berserat, dan tahan api itu bagai baju zirah yang memungkinkannya bertahan dari kebakaran hutan—bukan dengan menghindar, tetapi dengan menyerap dan mengubahnya menjadi bagian dari ceritanya. Kebakaran justru diperlukan untuk membuka kerucutnya dan memberi ruang bagi regenerasi. Cunningham melihat ini sebagai paradoks yang mendalam: “Mereka adalah raksasa yang dibesarkan oleh api. Mereka membawa kehancuran di dalam kulit mereka, dan mengubahnya menjadi kelahiran kembali.” Ia juga menceritakan tentang sistem akar yang dangkal namun menyebar luas, saling terhubung dengan Sequoia lainnya di sekelilingnya, membentuk sebuah jaringan dukungan bawah tanah yang tak terlihat—metafora sempurna untuk komunitas dan saling ketergantungan.
Secara sosial dan historis, Sequoia bagi Cunningham adalah cermin yang memantulkan ke-sombongan dan kesementaraan manusia. Ia menceritakan periode “Sequoia mania” di abad ke-19, di mana para pemburu souvenir menebang pohon-pohon ini hanya untuk dipertonton-kan di pameran dunia, atau mengukir terowongan di batangnya agar kereta bisa melintas—tindakan yang kini ia lihat sebagai vandalisme yang memalukan. Pohon-pohon yang pernah menyaksikan peradaban manusia bermula ini dijadikan tontonan sirkus. Namun, di balik tragedi itu, Sequoia juga memicu gerakan konservasi awal. Keberadaan mereka yang begitu agung membuat beberapa orang tersadar akan kebutuhan untuk melindungi keajaiban alam dari keserakahan.
Estetika Sequoia, dalam tulisan Cunningham, adalah estetika keluasan, kekekalan, dan kerendahan hati. Warnanya bukan hijau muda yang riang, melainkan merah kayu yang dalam dan serius, seperti warna darah kering yang telah mengalir selama ribuan tahun. Keheningan di hutannya bukan ketiadaan suara, melainkan suatu jenis musik yang berbeda: “desahan angin di ketinggian kanopi yang tak terjangkau mata, tetesan air dari kabut yang mengembun di daun jarum, suara jantung Anda sendiri yang berdebar pelan karena sadar akan kecilnya diri.” Cunningham menyimpulkan refleksinya dengan sebuah kesadaran: “Berada di dekat Sequoia adalah pengingat bahwa kita hanyalah sebuah catatan kaki dalam buku sejarah bumi yang tebal ini. Dan itu bukanlah perasaan yang menyedihkan, melainkan sebuah kelegaan—kita dibebas-kan dari ilusi bahwa segalanya bergantung pada kita. Dunia telah ada jauh sebelum kita, dan akan tetap ada, dengan atau tanpa kita. Tugas kita adalah berjalan dengan lembut, dan meninggalkan ruang bagi kolom-kolom waktu yang bisu ini untuk terus tumbuh.”
Dalam kedua narasi ini, Cunningham tidak hanya memberikan deskripsi biologis; ia memberikan jiwa dan biografi kepada pohon-pohon tersebut. Mereka menjadi karakter dalam drama ekologi planet kita—yang satu adalah pejuang perkotaan yang tangguh, yang lain adalah raja hutan purba yang agung. Melalui mereka, kita belajar tentang waktu, ketahanan, komunitas, dan tempat kita yang sesungguhnya dalam jaringan kehidupan. Penyair Indonesia Sapardi Djoko Damono dalam “Hujan Bulan Juni” menangkap kesabaran dan pemberian diri alam: “tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni / dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu”. Puisi ini berbagi semangat yang sama dengan Cunningham: melihat alam sebagai subjek yang memiliki interioritas dan kebijakannya sendiri.
Buku ini adalah sebuah perjalanan melalui lanskap duka ekologis (ecological grief). Cunningham menelusuri kebakarannya sendiri atas kebakaran hutan Australia yang makin hebat, kepunahan spesies, dan derita yang ia rasakan melihat alam terkikis. Namun, duka ini bukanlah tujuan akhir. Melalui hubungannya dengan pohon—dari pohon pinggir jalan di kota hingga hutan purba—ia menemukan jalan menuju “ketenangan yang aktif”. Hutan, baginya, adalah ruang untuk meratap sekaligus sekutu untuk bertindak. Ia menunjukkan bagaimana sains (dari ahli ekologi seperti Suzanne Simard yang meneliti “Jaringan Kayu Bawah Tanah” tempat pohon berkomunikasi) dan spiritualitas dapat bertemu dalam pemahaman bahwa segala sesuatu saling terhubung.
Secara global, buku ini berbicara kepada setiap orang yang merasakan kecemasan ekologis (eco-anxiety). Ia menawarkan kerangka untuk mengubah kecemasan itu dari beban yang melumpuhkan menjadi sumber empati dan keterlibatan yang mendalam. Di Indonesia, di mana deforestasi, kebakaran gambut, dan konflik agraria masih menjadi masalah akut, pesan Cunningham terdengar sangat keras.
Buku ini mengajak kita untuk melihat hutan dan pohon bukan sebagai “sumber daya” atau “sumber emisi karbon” semata, tetapi sebagai subjek hidup, sebagai komunitas, dan sebagai guru. Pendekatan ini selaras dengan kearifan lokal banyak masyarakat adat Nusantara yang memandang hutan sebagai ibu dan ruang hidup yang sakral. Narasi Cunningham adalah senjata melawan logika ekstraktif yang melihat alam hanya sebagai komoditas. “Membutuhkan hutan adalah kebutuhan politis,” tulisnya. Di Indonesia, ini bisa diterjemahkan sebagai pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat, pendekatan konservasi yang berbasis komunitas, dan gerakan “menghidupkan kembali” hubungan emosional dan spiritual warga kota dengan pohon di lingkungan mereka.
“Hutan adalah sebuah komunitas. Tidak ada pohon yang berdiri sendiri.” – Cunningham merujuk pada sains Suzanne Simard. Dalam Islam, konsep “mizan” (keseimbangan) dan “khilafah” (perwalian) di bumi menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan dan komunitas ciptaan Allah. Alam bukan milik manusia, tetapi amanah.
Seperti Australia, Indonesia juga menghadapi bencana ekologis yang dipicu iklim. Sikap “staying with the trouble” berarti tidak melarikan diri dari realitas ini, tetapi menghadapinya dengan membangun ketahanan komunitas, memulihkan ekosistem, dan memperjuangkan keadilan iklim.
Masa depan yang diimajinasikan Cunningham bukanlah utopia hijau yang bebas masalah, tetapi dunia di mana manusia telah belajar “cara menjadi makhluk bumi yang baik”. Ini berarti meng-adopsi skala waktu yang lebih panjang (seperti sequoia), menerima siklus hidup dan mati (seperti pohon tumbang), dan membangun ketahanan bersama (seperti pohon ek). Prospeknya adalah peradaban yang dibimbing oleh etika perawatan (ethics of care), bukan dominasi, di mana kota-kota kita adalah “kota pepohonan” yang hidup dalam simbiosis dengan hutan-hutan di sekitarnya. “Kita tidak bisa mengatasi krisis dengan logika yang sama yang menciptakan-nya.” – Kutipan ini menggemakan pikiran Albert Einstein, dan Cunningham menerapkannya pada hubungan manusia-alam: kita perlu logika sirkular hutan, bukan logika linear eksploitasi.
Kisah Ginkgo: Fosil Hidup yang Menyembuhkan Kota
Sophie Cunningham yang mantan penerbit dan editor, salah satu pendiri The Stella Prize, dan kini menjabat sebagai Profesor Adjunct di Non/fiction Lab, RMIT University ini mendekati Ginkgo biloba dengan rasa hormat yang dalam, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan seorang bangsawan yang selamat dari kepunahan. Ia menggambar-kannya bukan sebagai pohon biasa, melainkan sebagai “sebuah arsip hidup, sebuah fragmen dari zaman ketika dinosaurus masih merumput di hutan-hutan purba. ” Daunnya yang ber-bentuk kipas dengan lekukan di tengahnya, baginya, menyerupai otak yang terbelah—suatu bentuk yang meramal-kan kekuatan kognitif yang akan dikandungnya. Cunningham dengan puitis menceritakan bagai-mana Ginkgo adalah satu-satunya anggota keluarganya yang selamat dari peristiwa kepunahan massal, sebuah “kesendirian evolusioner yang megah” yang membuatnya menjadi tautan langsung ke dunia yang sudah lama hilang.
Dari sisi biologis, ia terpesona oleh kekuatan Ginkgo yang luar biasa. Ia menceritakan kisah pohon Ginkgo di Hiroshima yang bertahan hanya beberapa ratus meter dari pusat ledakan bom atom, untuk kemudian bertunas kembali di antara puing-puing yang menyala-nyala. “Ia adalah simbol ketahanan yang tak terkatakan,” tulis Cunningham, “akar-akarnya menggenggam tanah yang terkontaminasi, daun barunya menantang langit yang masih beracun.” Kekuatannya tidak hanya terhadap radiasi, tetapi juga terhadap polusi kota modern. Cunningham menggambarkan bagaimana Ginkgo tumbuh dengan anggun di sepanjang trotoar kota-kota besar, daunnya yang seperti emas di musim gugur menciptakan karpet cahaya di atas beton—sebuah “kemewahan yang rendah hati” di tengah lingkungan perkotaan yang keras. Estetikanya adalah estetika kepastian dan ketenangan geometris. Pola cabangnya yang teratur dan daunnya yang simetris memberikan rasa keteraturan pada kekacauan kota. Namun, ada paradoks: buah betinanya mengeluarkan bau seperti mentega tengik yang menusuk, sebuah “pengingat bahwa keanggun-an sering kali datang dengan harga, bahwa kehidupan yang tangguh tidak selalu harum.”
Eucalyptus: Sang Pendatang yang Kontroversial
Dalam bab “Eucalyptus”, Cunningham mengungkap hubungan cinta-benci Australia dengan pohon ikoniknya sendiri. Ia menggambarkan Eucalyptus bukan sebagai pemandangan yang statis, melainkan sebagai “aktor dramatis di panggung lanskap Australia.” Dengan kulit kayunya yang terkelupas seperti lukisan abstrak, mengungkap warna-warna hijau limau, krem, dan karat di bawahnya, pohon ini bagai terus-menerus berganti kulit, “mencoba identitas baru di bawah matahari yang tak kenal ampun.” Aromanya—campuran kapur barus, obat, dan madu—bagi Cunningham adalah “parfum nostalgia bangsa,” wewangian yang langsung membangkitkan ingatan akan musim panas, kebakaran, dan tanah merah.
Namun, Cunningham tidak menyembunyikan kompleksitasnya. Dengan pengetahuan yang mendalam, ia bercerita tentang bagaimana Eucalyptus telah menjadi “korban dan penjahat” dalam narasi ekologi Australia. Sebagai spesies yang berevolusi dengan api, ia tidak hanya bertahan dari kebakaran tetapi memicunya—minyak daunnya yang mudah menguap adalah bahan bakar sempurna. Cunningham menggambarkan kebakaran hutan yang menghanguskan dengan metafora yang menghantui: “Mereka bukan terbakar; mereka meledak ke dalam nyala api, memenuhi langit dengan suara gemuruh yang seperti pesawat jet, melepaskan benih-benih mereka yang berkulit keras dalam sebuah tindakan regenerasi yang penuh kekerasan.” Secara sosial, pohon ini adalah simbol ambivalen: bagi masyarakat Aborigin, berbagai spesiesnya adalah apotek dan toko peralatan lengkap; bagi kolonis, ia adalah kayu dan penghalang; bagi para pendatang baru, ia adalah bahaya yang harus disingkirkan dari sekitar rumah. “Eucalyptus mengajarkan kita bahwa alam tidak peduli dengan kenyamanan kita,” tulis Cunningham, “ia mengikuti logikanya sendiri yang purba dan sering kali kejam.”
Moreton Bay Fig: Sang Penjajah yang Lembut
Pohon Moreton Bay Fig (Ficus macrophylla) digambarkan Cunningham sebagai makhluk yang “lapar akan ruang dan kehidupan.” Ia tidak hanya tumbuh; ia “mengklaim wilayah.” Deskripsinya tentang akar udara yang turun dari cabangnya seperti tirai hidup, yang akhirnya menjadi batang sekunder, adalah deskripsi tentang suatu kekuatan yang tak terbendung. “Ia adalah arsitek dan bangunannya sendiri,” tulisnya, “membangun katedral hidupnya sendiri, pilar demi pilar, sampai asalnya tidak dapat lagi dibedakan—sebuah organisme tunggal atau sebuah hutan kecil yang terhubung secara rahasia?” Kanopinya yang sangat luas menciptakan gua hijau yang gelap dan dingin di bawahnya, sebuah dunia yang terpisah dari matahari Australia yang menyilaukan.
Cunningham menceritakan kisah pohon-pohon Fig raksasa yang ditanam di taman-taman kota, seperti di Adelaide Botanic Garden, yang menjadi “monumen hidup untuk ambisi kolonial”—keinginan untuk menjinakkan dan mendominasi lanskap dengan menanam sesuatu yang begitu perkasa. Namun, pohon-pohon ini melampaui niat penanamnya. Mereka menjadi rumah bagi koloni kelelawar yang ribut, sarang bagi burung-burung, dan taman bermain imajinatif bagi anak-anak. Estetika Moreton Bay Fig adalah estetika kelimpahan yang hampir menakutkan. Ia terlalu besar, terlalu subur, terlalu banyak. “Ia adalah Midas dari dunia tumbuhan,” canda Cunningham, “segala yang disentuhnya menjadi lebat, menjadi hijau, menjadi lebih banyak.”
Namun, dalam esainya “I Don’t Blame the Trees“, Cunningham melakukan pembelaan yang menyentuh. Ketika pohon-pohon tua ini ditebang karena akarnya merusak pipa atau cabangnya dianggap berbahaya, ia tidak marah pada pohonnya. “Mereka hanya melakukan apa yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun: tumbuh, mencari air, memberikan naungan,” tulisnya. “Kitalah yang bodoh, menanam raksasa di tepi jalan sempit dan kemudian terkejut ketika mereka menjadi raksasa. Kesalahan ada pada imajinasi kita yang terbatas, bukan pada naluri mereka untuk hidup.”
Dalam bab-bab singkat namun padat seperti “Tourists Go Home” dan “Escape To Alcatraz“, Cunningham menggunakan pohon sebagai lensa untuk melihat ketegangan sosial. Wisatawan pulanglah dan pelarian ke Alcatraz dan Cunningham menggunakan pohon sebagai metafora sosial. Di “Tourists Go Home“, ia mungkin menceritakan tentang pohon-pohon di sebuah kota wisata yang menjadi saksi bisu atas gentrifikasi dan kehilangan roh sebuah tempat—pohon Magnolia tua yang mekar dengan sia-sia di depan airbnb yang kosong, atau deretan Palm yang ditanam hanya untuk instagram, kehilangan konteks ekologisnya. Pohon menjadi “korban pertama dari kecantikan yang disterilkan.”
Sementara “Escape To Alcatraz” pasti membawa kita ke pulau penjara yang terkenal itu, di mana Cunningham menemukan kisah ketahanan yang lain: taman-taman yang dahulu ditawan-an dan penjaga, yang kini dikuasai kembali oleh tanaman pribumi dan burung-burung laut. Di sini, pohon-pohon—mungkin Cypress yang meliuk-liuk diterpa angin laut—adalah simbol “kebebasan yang paradoks.” Mereka tumbuh di tanah yang paling tidak bebas, namun akar mereka menembus batu, cabang mereka mencapai ke arah San Francisco yang bebas di seberang sana. “Mereka adalah tahanan yang paling sukses,” tulis Cunningham, “melarikan diri dengan cara satu-satunya yang mungkin: dengan tetap tinggal, dengan berakar begitu dalam sehingga mereka menjadi pulau itu sendiri.”
Melalui semua deskripsi ini, Cunningham mencapai sesuatu yang mendalam: ia mengubah pohon dari pemandangan menjadi karakter, dari objek menjadi subjek, dari penghias menjadi pencerita. Setiap spesies menjadi cermin untuk memikirkan waktu, kolonialisme, ketahanan, dan kesalahan kita yang manusiawi. Ia menunjukkan bahwa untuk memahami sebuah tempat, kita harus mendengarkan kisah-kisah yang diceritakan oleh pohon-pohonnya.
Kisah Mexican Fan Palm: Tiang-Tiang Kemegahan yang Palsu
Sophie Cunningham memandang Mexican Fan Palm (Washingtonia robusta) dengan mata yang sinis sekaligus kasihan. Ia menggambarkannya bukan sebagai pohon, melainkan sebagai “kesombongan vertikal.” Di sepanjang jalan raya Los Angeles dan pinggiran kota Australia, mereka berdiri dalam barisan militer yang kaku, batangnya yang tinggi dan ramping seperti tiang telepon yang hidup, mahkotanya yang compang-camping terangkat ke langit seolah malu dengan tanah yang menahannya. “Mereka adalah imigran yang tidak pernah sepenuhnya diterima,” tulis Cunningham, “selalu terlihat seperti baru saja tiba, pakaiannya masih kusut dari perjalanan, belum belajar bahasa setempat.” Mereka tidak memberikan keteduhan yang berarti, daunnya yang kaku hanya menghasilkan bayangan belang-belang yang tak berguna di bawah terik matahari. Estetika mereka adalah estetika fasad dan ilusi—simbol tropis yang murah di lanskap yang bukan tropis, janji liburan yang tak pernah terpenuhi.
Cunningham menceritakan bagaimana mereka sering ditanam di depan kompleks perumahan baru, “sebuah tanda seru botani” yang menandakan modernitas dan kemewahan, tetapi justru mengungkapkan kemiskinan imajinasi dan kedangkalan ekologis. Mereka adalah pohon untuk dilihat dari jendela mobil yang melaju kencang, bukan untuk dirasakan atau dialami. Dalam esainya yang sinis “In The Long Run The House Always Wins“, Cunningham mungkin menggunakan Fan Palm ini sebagai metafora untuk pembangunan perkotaan yang berumur pendek—flamboyan namun rapuh, menang dalam gaya tetapi kalah dalam substansi, akhirnya tumbang oleh badai atau penyakit karena sistem akarnya yang dangkal dan terisolasi.
Kisah Yellowwood: Penari Sunyi yang Langka
Berlawanan dengan sang Palm yang norak, Yellowwood (Cladrastis kentukea) digambarkan Cunningham sebagai “penari balet di antara petinju.” Ia menemukannya di taman-taman yang tenang, bukan di jalan raya. Ia adalah pohon yang elegan, anggun, dengan pola percabangan yang lembut dan daun majemuknya yang seperti rendaan hijau yang berubah menjadi kuning keemasan yang menakjubkan di musim gugur. “Ia tidak meminta perhatian,” tulis Cunningham, “tetapi ketika ia mekar, dengan malai-malai bunganya yang seperti kepingan salju wisteria yang terjatuh, seluruh udara di sekitarnya berubah menjadi manis dan ringan.” Ia adalah spesialis, tumbuh lambat, membutuhkan tanah yang tepat dan keteduhan yang baik di masa mudanya.
Cunningham menceritakan kisah kelangkaannya—bagaimana ia hampir punah karena kayunya yang keras dan indah, dan bagaimana para ahli botani dan tukang kebun yang sabar berusaha melestarikannya. Dalam bab “FORT. DA!” (merujuk pada permainan “pergi-kembali” anak-anak Freud yang simbolis), Cunningham mungkin melihat Yellowwood sebagai simbol “kembali”-nya yang lambat dan penuh perjuangan, sebuah penegasan bahwa keindahan yang halus dan kompleks masih dapat menemukan celah untuk bertahan di dunia yang serba kasar. Ia adalah metafora untuk memori halus, untuk tradisi yang hampir hilang, untuk kesabaran itu sendiri.
Kisah Pohon Zaitun: Arsitek Waktu yang Keriput
Olive Tree (Olea europaea) adalah salah satu karakter paling bijak dalam galeri arboreal Cunningham. Ia menggambarkannya bukan melalui keagungan vertikal, tetapi melalui “kepadatan waktu yang tak terukur.” Batangnya yang bengkok, berlekuk-lekuk, dan sering berlubang, baginya, adalah “peta topografi dari penderitaan dan ketekunan.” Setiap lekukan menceritakan musim kemarau yang bertahan, setiap lubang adalah bekas cabang yang dikorbankan untuk bertahan hidup. “Mereka adalah ahli ekonomi yang genius,” tulis Cunningham, “mereka tahu persis berapa banyak yang harus diinvestasikan, kapan harus menarik diri, bagaimana hidup dengan sangat sedikit.” Daunnya yang berwarna perak di bagian bawah adalah reflektor cahaya matahari yang sempurna, sebuah teknologi bertahan hidup yang elegan. Cunningham menceritakan perjalanannya ke kebun zaitun tua, merasakan kesunyian yang sakral di antara barisan pohon-pohon keriput itu, mendengar bisikan angin yang berbeda di antara daun-daun kecilnya yang berderak.
Buahnya yang pahit harus direndam, dihancurkan, ditekan—”sebuah pengubahan penderitaan menjadi kemurnian.” Minyak zaitun, baginya, adalah “cairan waktu dan cahaya matahari,” sebuah konsentrat dari kesabaran sebuah lanskap. Pohon zaitun adalah simbol perdamaian hanya karena ia telah menyaksikan terlalu banyak perang; akarnya mencengkeram tanah di Mediterania yang penuh konflik seperti seorang ibu yang tak mau melepaskan anaknya.
Biyala Stories: Pohon dalam Narasi yang Terampas
Bab “Biyala Stories” kemungkinan adalah jantung politik dari buku ini, di mana Cunningham meninggalkan narasi pribadi dan estetika untuk masuk ke dalam kisah-kisah kolonial yang pahit. Biyala adalah nama pohon Moreton Bay Fig dalam bahasa suku Gadigal, penduduk asli wilayah Sydney. Di sini, Cunningham tidak lagi bercerita tentang pohon sebagai individu, tetapi sebagai “saksi dan korban.” Ia mungkin menceritakan bagaimana pohon Fig raksasa yang sama yang ia kagumi di taman kota, sebenarnya adalah penanda situs perkemahan atau pertemuan penting Gadigal yang telah dilupakan—atau sengaja dihapus—dari peta. Pohon itu adalah living archive, tetapi arsipnya ditulis dalam bahasa yang telah dibungkam.
Cunningham akan menggambarkan perasaan malu dan kesedihan yang mendalam saat menyadari bahwa “pohon yang saya puji sebagai simbol keindahan alam, bagi orang lain adalah nisan dari sebuah dunia yang dirampas.” Ia menceritakan upaya-upaya komunitas Aborigin untuk menghidupkan kembali pengetahuan tentang pohon-pohon ini—yang mana yang bisa dijadikan obat, yang mana yang menandai sumber air, yang mana yang menjadi lokasi upacara. Kisah-kisah Biyala ini adalah “akar yang putus”, sebuah narasi ekologi yang terfragmentasi. Cunningham menggunakan pohon untuk membongkar mitos terra nullius (tanah tak bertuan). “Bagaimana mungkin sebuah tanah dikatakan kosong,” tulisnya, “jika dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang namanya, kegunaannya, dan ceritanya telah dihafal dan diwariskan selama ribuan tahun?” Di sini, pohon menjadi alat untuk keadilan restoratif. Merawat pohon tua tidak lagi hanya soal konservasi ekologi, tetapi juga soal “mendengarkan kembali” dan menghormati cerita-cerita yang telah diukir dalam ingatan kolektifnya, meski dalam keheningan.
Melalui seluruh bagian ini, Cunningham mencapai kedalaman baru. Ia menunjukkan bahwa setiap pohon membawa tidak hanya sejarah ekologis, tetapi juga sejarah politik dan budaya. Fan Palm adalah sejarah imigrasi dan selera yang buruk; Yellowwood adalah sejarah konservasi dan kelangkaan; Olive Tree adalah sejarah peradaban Mediterania; dan Biyala adalah sejarah penaklukan dan ketahanan budaya. Dengan membaca pohon-pohon ini, kita membaca diri kita sendiri—nilai, kekerasan, dan kelupaan kita. Cunningham mengajak kita untuk tidak hanya melihat keindahan atau ketahanan mereka, tetapi juga untuk membaca luka dan beban sejarah yang mereka pikul, dan untuk bertanggung jawab atas cerita yang kita putuskan untuk dengar dan yang kita biarkan lenyap.
Kisah Coolibah: Penjaga Sunyi di Tanah yang Haus
Sophie Cunningham mendekati Coolibah (Eucalyptus microtheca/coolabah) dengan rasa hormat yang dalam, seperti seseorang yang sedang memasuki sebuah katedral alam. Ini bukan pohon perkotaan, melainkan penjaga kuno dari pedalaman Australia yang gersang. Ia menggambarkannya bukan melalui keagungan vertikal, tetapi melalui “ketekunan horizontalnya.” Dengan batang yang sering kali pendek dan bengkok, kulit kayu yang pecah-pecah seperti tanah kering, dan kanopi yang menyebar untuk memaksimalkan keteduhan yang langka, Coolibah adalah “ahli matematika kekurangan yang sempurna.” Cunningham menceritakan perjalanannya ke tepian billabong (kolam air sementara) di wilayah utara, di mana Coolibah adalah penanda kehidupan—ia selalu berada di dekat air, akar-akarnya menggali jauh ke dalam tanah untuk menemukan cadangan air yang tersembunyi. “Mereka adalah pustakawan air di gurun,” tulisnya, “menjaga rahasia lokasi mata air dalam lingkaran tahun mereka yang padat.”
Dalam esainya “History On Unthinking Feet“, Cunningham mungkin merefleksikan bagaimana pohon ini telah menjadi saksi bisu perjalanan masyarakat Aborigin dan para penjelajah Eropa yang tersesat, tanpa pernah memberikan rahasianya kecuali kepada mereka yang tahu membacanya. Estetikanya adalah estetika kesunyian dan daya tahan. Ia tidak menarik perhatian, tetapi kehadirannya memberikan rasa tenang yang mendalam. Ia adalah simbol dari sebuah Australia yang dalam dan abadi, jauh di balik hiruk-pikuk kota pesisir.
367 Collins Street (Falco peregrinus): Alam yang Membajak Kota
Dalam bab yang brilian ini, Cunningham mengalihkan fokus dari pohon ke penghuni udara kota: seekor alap-alap kawah (peregrine falcon) yang bersarang di puncak gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis Melbourne. Ini adalah kisah tentang “penjajahan balik.” Cunningham menggambarkan dengan penuh ketakjuman bagaimana burung pemangsa tercepat di dunia ini telah meninggalkan tebing-tebing alami dan memilih celah beton vertikal untuk membesarkan anak-anaknya. “Mereka tidak peduli dengan arsitektur postmodern,” tulisnya, “bagi mereka, ini hanyalah tebing baru dengan pemandangan yang bagus untuk berburu merpati kota.” Ia melukiskan adegan kontras yang absurd dan mengharukan: para broker yang terburu-buru di bawah, sementara di atas, sang falcon menjaga sarangnya dengan mata tajam yang sama yang digunakan nenek moyangnya untuk mengawasi lembah-lembah purba. Narasi ini menjadi pintu masuk Cunningham ke “The Age Of Loneliness“, di mana ia merenungkan isolasi ekologis manusia modern. Burung falcon yang beradaptasi itu justru menunjukkannya: “Kitalah yang mungkin lebih terisolasi, terkurung dalam gelembung kaca dan logam kita, sementara alam hanya berpindah alamat, terus berlanjut tanpa kita.” Kehadiran falcon itu adalah pengingat yang menusuk bahwa kita tidak pernah benar-benar mengusir alam; kita hanya mengubah panggungnya.
Mountain Ash: Raksasa yang Rentan dan Terbakar
Mountain Ash (Eucalyptus regnans) adalah raksasa lain dalam dunia Cunningham, tetapi dengan kisah yang berbeda dari Sequoia. Ia menggambarkannya sebagai “pencakar langit organik yang tumbuh paling cepat di dunia, tetapi dengan fondasi yang rapuh.” Dengan ketinggian yang bisa melebihi 100 meter, mereka adalah pohon tertinggi di Australia dan salah satu yang tertinggi di dunia. Cunningham mendeskripsikan sensasi berdiri di hutan Mountain Ash: “Anda merasa seperti di lantai dasar sebuah katedral Gothic yang cahayanya menyaring melalui jendela-jendela hijau di atap yang sangat tinggi. Suara Anda hilang, diserap oleh spons lumut dan pakis raksasa di bawah.” Namun, keagungan ini dibayangi oleh kerentanan ekstrem.
Seperti banyak eucalyptus, Mountain Ash berevolusi dengan api, tetapi kebakaran yang terlalu sering dan terlalu hebat—yang diperparah oleh perubahan iklim—membunuh mereka sebelum mereka sempat menghasilkan benih yang cukup. Cunningham menceritakan dengan pedih tentang hutan-hutan Mountain Ash tua yang habis dilalap api, meninggalkan “pemakaman pucat dari tiang-tiang arang yang menjulang ke langit yang tak peduli.” Mereka adalah simbol dari paradoks Australia: keperkasaan yang luar biasa sekaligus kehancuran yang mendadak. “Mereka adalah raksasa yang menari di atas api,” tulisnya, “dan kita telah mengobarkan api itu di bawah kaki mereka.” Cerita ini berhubungan dengan esai yang diekstrak dari “Peringatan: Kisah Topan Tracy”, di mana Cunningham kemungkinan menggambar paralel antara kehancur-an mendadak yang dibawa oleh topan kepada kota Darwin dengan kehancuran berulang yang dibawa api kepada hutan-hutan ini. Keduanya adalah peristiwa iklim ekstrem yang mengungkap ketidakstabilan sistem, baik sistem alam maupun sistem buatan manusia. Mountain Ash menjadi metafora yang tragis: ketinggian yang kita capai tidak menjamin ketahanan. Kita bisa menjadi raksasa, tetapi tetap musnah oleh angin (atau api) yang kita sendiri bantu ciptakan.
Sejarah, Isolasi, dan Kerapuhan
Melalui bagian-bagian ini, Cunningham membangun sebuah tesis yang semakin kompleks. Coolibah mewakili sejarah yang dalam dan tenang dari tanah itu sendiri, sejarah yang tertulis dalam pola ketahanan, bukan dalam dokumen. Burung falcon di 367 Collins Street mewakili adaptasi alam yang sinis dan menggugat isolasi manusia, menunjukkan bahwa “zaman kesepian” mungkin adalah kondisi manusia perkotaan, bukan kondisi planet. Dan Mountain Ash mewakili paradoks kerapuhan dalam keperkasaan, sebuah peringatan bahwa sistem yang paling megah pun bisa runtuh di bawah tekanan yang tepat—tekanan yang kini kita berikan.
Cunningham tidak lagi hanya merenungkan keindahan atau ketahanan pohon. Ia sekarang menggunakan mereka sebagai alat diagnostik untuk memeriksa demam planet dan penyakit sosial kita. Mereka adalah barometer sejarah kolonial, termometer isolasi perkotaan, dan seismograf untuk guncangan iklim yang akan datang. Dengan membaca mereka, kita tidak hanya belajar tentang ekologi, tetapi tentang patologi zaman kita—dan mungkin, jika kita mendengarkan dengan saksama, resep untuk kesembuhan yang tertanam dalam genetika mereka yang telah terbentuk melalui bencana selama jutaan tahun.
Catatan Akhir: Menenun Kembali Kain Kehidupan yang Terkoyak
Setelah berkelana melalui galeri arboreal Sophie Cunningham—dari pohon ek yang tabah hingga sequoia yang abadi, dari eukaliptus yang dramatis hingga fig yang menjajah, dari palm yang kesepian hingga ash yang rentan—kita sampai pada suatu kesadaran yang tak terbantahkan: narasi manusia dan narasi pohon bukanlah dua kisah yang terpisah. Mereka adalah benang yang saling menyilang dalam sebuah tenunan yang sama, sebuah kain kehidupan yang kini makin lama makin terkoyak. Cunningham, dengan gaya bertuturnya yang intim dan tajam, bukan sekadar menunjukkan keindahan pohon; ia melakukan pembedahan ontologis. Ia mengungkap bahwa setiap pohon adalah sebuah kitab filosofi hidup.
Pohon-pohon itu mengajarkan kita tentang waktu dalam skala yang membebaskan. Di hadapan sequoia berusia ribuan tahun atau pohon zaitun yang keriput, kegelisahan kita atas tenggat waktu, karier, dan tren media sosial mencair menjadi kesia-siaan. Kita diingatkan bahwa kita hanyalah sebuah catatan kaki dalam biografi Bumi yang panjang. Pelajaran ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk meringankan beban ke-akuan kita yang berlebihan, memberi kita ruang bernapas untuk melihat lebih luas.
Mereka juga adalah guru ketahanan yang bukan kekakuan, melainkan adaptasi. Lihatlah pohon ek pesisir dengan akarnya yang menggenggam erat dan daunnya yang berduri, atau coolibah di gurun dengan akar pencari airnya. Mereka tidak melawan kekeringan; mereka bernegosiasi dengannya. Mereka tidak menghindari api; beberapa justru menggunakannya untuk regenerasi. Ini adalah metafora yang kuat bagi manusia di tengah krisis iklim: ketahanan bukan tentang membangun tembok yang lebih tinggi, tetapi tentang belajar menari dengan perubahan, menjadi lenting, dan menemukan cara baru untuk tumbuh di tanah yang tandus.
Yang paling menyentuh adalah bagaimana Cunningham menunjukkan bahwa pohon adalah cermin sosial dan politik kita. Mexican fan palm yang kosong mencerminkan selera urban yang instan dan dangkal. Kisah biyala (fig teluk Moreton) yang namanya dirampas mengekspos luka kolonial dan penghapusan memori. Kehadiran alap-alap kawah di gedung pencakar langit adalah satire terhadap “zaman kesepian” manusia urban yang merasa terpisah dari alam, padahal alam hanya sedang beradaptasi di atas kepala kita. Pohon-pohon itu menyimpan sejarah yang tidak tertulis di buku—sejarah pertemuan, perampasan, dan ketahanan budaya.
Lalu, di mana letak saling membutuhkan yang vital itu?
Pohon membutuhkan manusia bukan sebagai tuan, tetapi sebagai penjaga dan penerjemah yang rendah hati. Mereka butuh kita untuk berhenti melihat mereka sebagai komoditas atau penghias, dan mulai mengenali mereka sebagai sesama subjek yang bernapas, berkomunikasi (melalui jaringan kayu bawah tanah), dan berbagi sejarah. Mereka butuh kita untuk melindungi tanah leluhur mereka dari spekulasi, untuk memulihkan sungai-sungai yang memberinya minum, dan untuk mengendalikan nafsu pembakaran bahan bakar fosil yang mengacaukan iklim tempat mereka berevolusi. Mereka butuh suara kita dalam dewan-dewan kota dan parlemen.
Sebaliknya, manusia sangat membutuhkan pohon, jauh melampaui oksigen dan keteduhan. Kita membutuhkan mereka sebagai penopang psikis dan spiritual di dunia yang semakin retak. Dalam bahasa Cunningham, mereka adalah “sahabat” dan “guru”. Di tengah gelombang eco-anxiety dan kesepian digital, hutan dan taman kota menjadi ruang penyembuhan, tempat kita mengatur ulang ritme saraf kita dengan ritme pertumbuhan yang lambat. Kita butuh mereka sebagai penanda identitas dan penjaga memori kolektif—pohon beringin di alun-alun, pohon keluarga di pekarangan. Lebih dari itu, kita butuh kebijaksanaan mereka untuk membangun peradaban yang tidak melawan, tetapi selaras dengan hukum alam. Desain kota, sistem pertanian, dan bahkan model ekonomi kita dapat belajar dari efisiensi ekosistem hutan, dari sirkularitas nutrisi, dan dari solidaritas komunitas pohon yang saling mendukung melalui jaringan akarnya.
Merawat hubungan ini adalah tugas paling mendesak abad ini. Ini bukan sekadar aktivisme konservasi, melainkan proyek regenerasi hubungan. Ini berarti:
- Membaca kembali lanskap dengan mata baru: Melihat pohon di jalan bukan sebagai objek, tetapi sebagai tetangga dengan sejarah.
- Berpolitik dengan akar: Memperjuangkan kebijakan yang mengakui hak-hak alam dan masyarakat adat yang menjaganya.
- Menghidupkan kembali cerita: Seperti Cunningham yang menghidupkan kisah Biyala, kita perlu menyelamatkan dan menghormati pengetahuan lokal tentang setiap pohon.
- Menanam dengan niat: Menanam pohon bukan sekadar aksi simbolis, tetapi sebuah komitmen untuk merawat sebuah kehidupan selama puluhan tahun ke depan, menjadi penjaga untuk generasi yang akan datang.
Pada akhirnya, Cunningham mengajak kita pada sebuah revolusi persepsi: Bumi bukanlah panggung tempat manusia berakting dan pohon menjadi latar belakang. Bumi adalah jaringan simbiosis yang hidup. Ketika kita melukai satu benang dalam jaringan itu—menebang hutan, mencemari sungai—kita mengoyak kain yang menopang kita sendiri. Merawat pohon, dengan demikian, adalah tindakan merawat diri dan masa depan kolektif kita yang paling dasar. Maka, berjalanlah ke luar. Sentuhlah kulit kayu yang kasar. Dengarkan desau daun. Di sanalah, dalam keheningan yang berbicara itu, terdapat undangan untuk kembali menjadi bagian dari suatu keutuhan, untuk merajut kembali hubungan yang telah lama terputus, dan bersama-sama—manusia dan pohon—membangun bumi yang tidak hanya lestari, tetapi juga penuh makna dan saling pengertian. Itulah inti dari “kebutuhan akan hutan”: kebutuhan untuk kembali pulang ke jaringan kehidupan yang saling terhubung.
City of Trees adalah buku yang diperlukan di tengah kebisingan krisis. Ia tidak menawarkan solusi teknologi cepat saji, tetapi proses penyembuhan dan penemuan makna. Cunningham mengajak kita untuk keluar, menyentuh kulit pohon, melihat ke atas kanopi, dan mengingat bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang luas, tua, dan tangguh. Dengan belajar dari ketahanan pohon, kita mungkin menemukan ketahanan untuk diri kita sendiri—untuk hidup, untuk mencintai, dan untuk berjuang merawat dunia yang fana dan berharga ini. Masa depan, tampaknya, tidak terletak pada melarikan diri ke alam, tetapi pada menjadi seperti alam: berakar, terhubung, dan tabah.
Cirebon 10 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi:
Cunningham, S. (2019). City of trees: Essays on life, death & the need for a forest. Text Publishing.
Haraway, D. J. (2016). Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene. Duke University Press.
Simard, S. (2021). Finding the mother tree: Discovering the wisdom of the forest. Alfred A. Knopf.
Shiva, V. (2005). Earth democracy: Justice, sustainability, and peace. South End Press.
(Damono, S. D. (1994). Hujan Bulan Juni. Grasindo).
(Konsep Mizan dan Khilafah dalam Islam dirujuk dari tafsir Al-Qur’an, misalnya QS. Ar-Rahman: 7-9 dan QS. Al-Baqarah: 30).