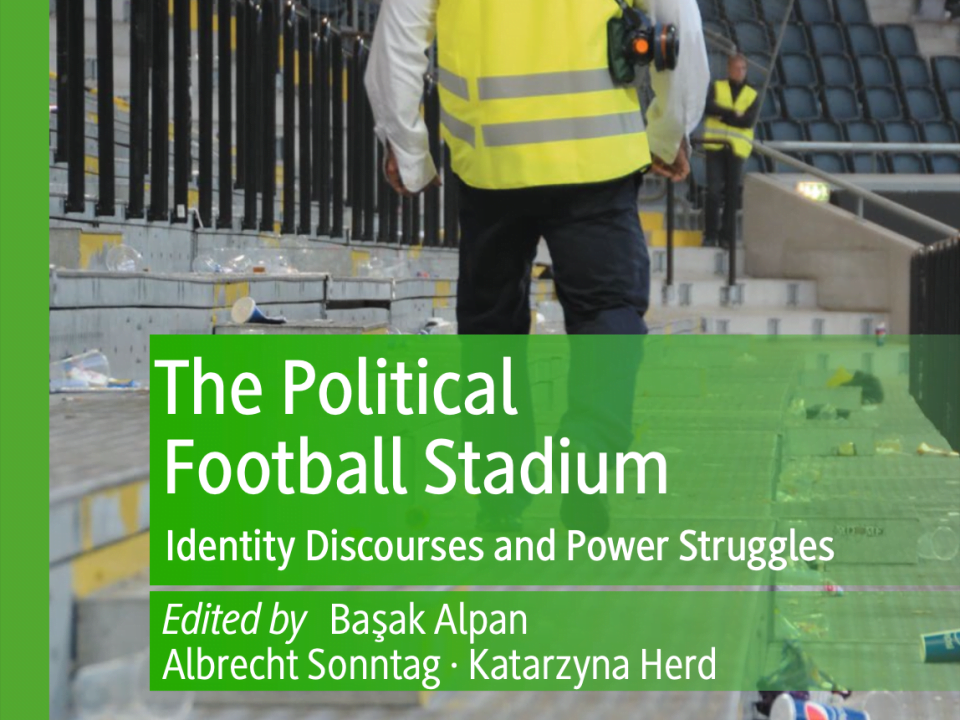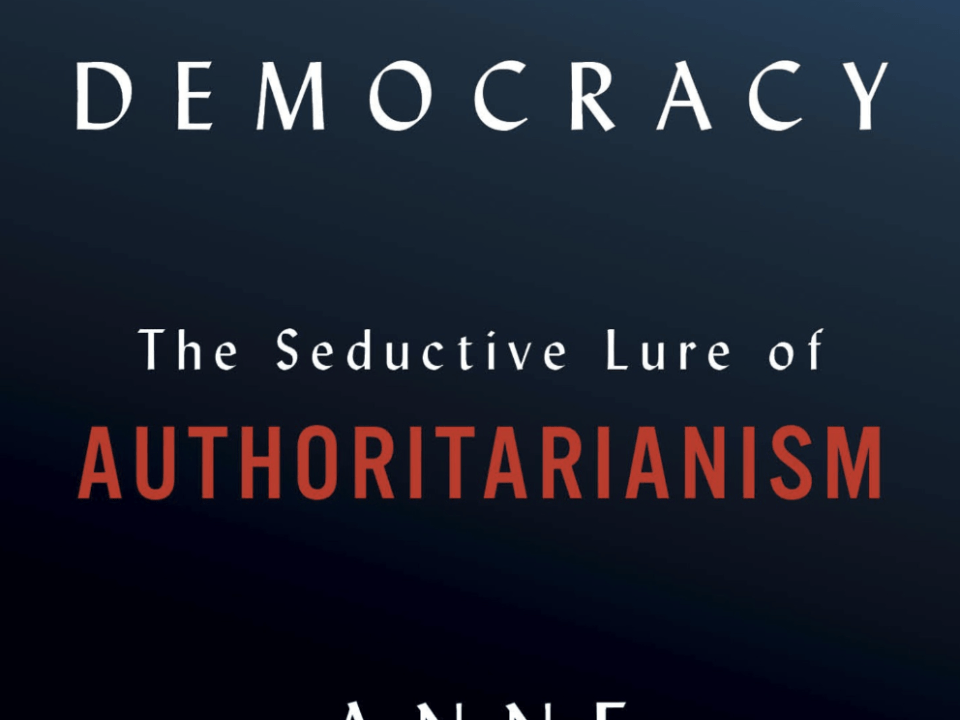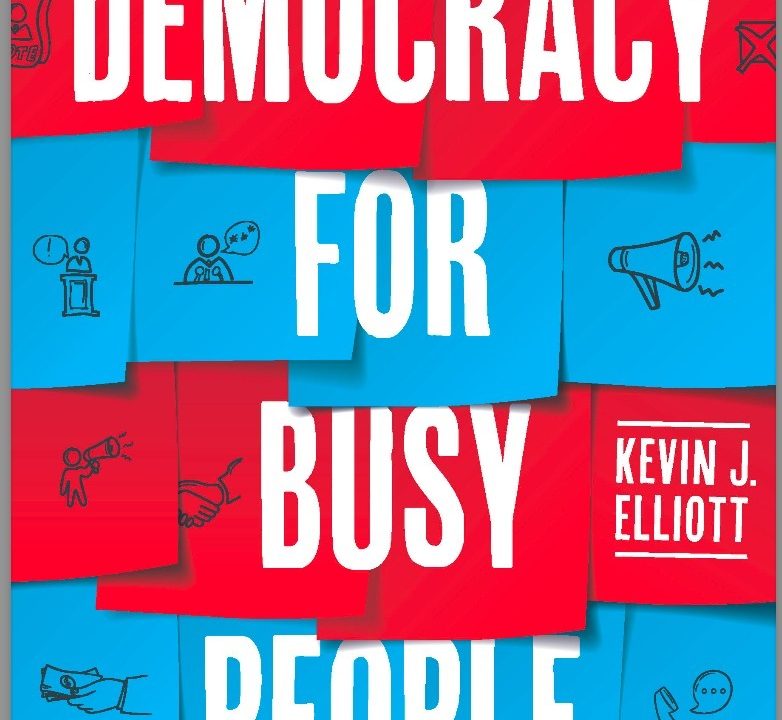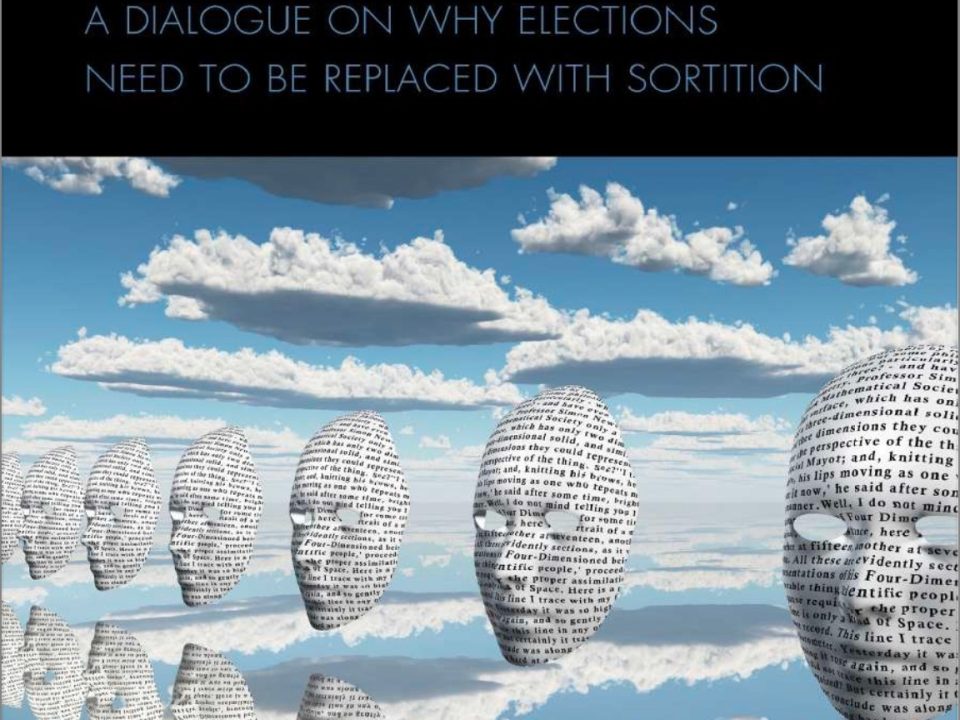“Cendekiawan padam karena dua hal: kekuasaan dan ketakutan.”
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor, 18112018
#BincangBuku #16
Ada dua buku lama berkaitan dengan intelektual yang masih bercokol di rak buku saya: Penghianatan Kaum Intelektual (Julien Benda, Gyramedia 1999), dan Cendekiawan dan Politik (Editor: Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, LP3ES 1983). Diantara buku-buku serupa tentang subyek itu, dua buku ini bisa memberikan refleksi perjalanan panjang kisah cendekiawan di Indonesia—termasuk mencari definisi yang tepat siapa dan apa cendekiawan yang pas untuk konteks Indonesia.
Studi klasik Julien Benda tahun 1920-an di Eropa bergema hingga hari ini. “Pengkhianatan kaum intelektual” adalah ungkapan yang membangkitkan banyak hal dalam dinamika intelektual di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sejak jaman pra-Socrates, kaum intelektual berkembang biak. Mereka adalah pencari pengetahuan non-materialistis yang percaya pada humanisme universal dan mewakili landasan masyarakat yang beradab. Menurut Benda, ini semua mulai berubah di awal abad kedua puluh. Di Eropa pada tahun 1920-an, para intelektual mulai meninggalkan keterikatan mereka pada cita-cita filosofis dan ilmiah tradisional, dan sebaliknya mengagung-agungkan partikularisme dan relativisme moral.
Sementara itu buku Cendekiawan dan Politik memuat tulisan Mohammad Hatta, Soedjamoko, Selo Soemardjan, Harsja W. Bachtiar, YB. Mangunwijaya, Afian, Arief Budiman, Wiratmo Soekito, Harry J. Benda, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Edward Shils. Deretan penulis dari orang-orang yang kita kenal sebagai cendekiawan. Saya yakin perbincangan terkini tentang cendekiawan masih marak, meski terasa makin tertutup kabut hiruk pikuk badai politik yang makin membuat posisi cendekiawan tenggelam. Atau ditenggelamkan.
Dimanapun peran sejati cendekiawan atau intelektual (dua istilah ini akan saya gunakan secara bergantian dengan maksud yang sama) selalu diimpikan. Masyarakat luas menaruh harapan pada cendekiawan sebagai pencerah jalan dalam menghadapi isu-isu pelik. Masyarakat berharap kaum cendekiawanlah yang mampu memberi petunjuk jalan yang jernih dan benar kemana melangkah. Sebab, “..suatu masyarakat yang menyingkirkan kaum intelektualnya, pada hakikatnya, sedang menyingkirkan dirinya sendiri. Karena kekuatan masyarakat itu untuk melanjutkan hidupnya akan bergantung juga kepada para anggotanya yang merasakan, menghayati, dan mencintai kebenaran (Soekito, 1983).”
Pertanyaannya siapakah intelektual itu? Apa peran dan tanggungjawabnya? “Who qualifies?” kata Noam Chomsky.
Dua buku yang saya sebutkan di atas memberi diskusi yang dalam tentang pertanyaan-pertanyaan itu—sebuah diskusi yang tetap relevan untuk kita angkat lagi kini meski terjadi seperempat abad yang lalu atau lebih.
Buku terbaru yang membincangkan intelektual datang dari seorang pemikir ahli linguistik Noam Chomsky. Bukunya berjudul: It is the Responsibility of Intelectuals to Speak the Truth and Expose the Lies (2017). Judul Buku ini sudah terang menunjukkan posisi Chomsky. Itulah tanggungjawab intelektual. Apapun implikasinya.
Chomsky adalah Institute Professor (emeritus) pada Department of Linguistics and Philosophy di the Massachusetts Institute of Technology and Laureate Professor of Linguistics and Agnese Nelms Haury Chair pada the Program in Environment and Social Justice di the University of Arizona. Chomsky adalah pengritik utama kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat manakala dianggap melenceng dari azas demokrasi dan melecehkan kemanusiaan.
Buku yang kita perbincangkan ini tidak secara detil membahas asal muasal dan definisi intelektual. Juga buku ini tidak membahas hal-hal yang bersifat spesifik lokal. Chomsky menggugat hal-hal besar yang telah terjadi dari kebijakan publik Amerika dan menganalisis peran-peran dan implikasi dari keberpihakan yang diambil oleh ‘intelektual.’ Amerika Serikat sebagai negara besar yang mempunyai pengaruh amat besar dalam percaturan politik ekonomi sosial budaya dunia tentu saja setiap kebijakan nasional yang diambil akan berpengaruh terhadap dinamika dunia. Karena itu membicarakan kejadian-kejadian kebijakan publik Amerika mau tidak mau menjadi teladan (pelajaran) yang baik bagi negara-negara lain.
Chomsky dalam It is the Responsibility of Intelectuals mengambil pendekatan sejarah untuk melihat bagaimana orang-orang yang diklaim sebagai intelektual bersikap atas isu-isu publik yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Isu itu mulai dari persoalan perang Vietnam, Intervensi Amerika di Equador, insiden “the Bay of Pigs” yang hampir membawa Amerika dan Kuba dalam kubangan perang yang berbahaya, konflik Jerman Barat-Timur sebelum unifikasi, hingga keterlibatan Obama dalam urusan Irak, termasuk kejadian tragis 9/11. Itu adalah isu-isu besar yang mempertaruhkan bukan saja Amerika, tetapi juga kemanusiaan. Bagaimana intelektual bersikap? Membela kepentingan nasional negaranya atau kemanusiaan yang lebih luas?
Pertama-tama Chomsky mengajukan pertanyaan soal siapa intelektual itu: “Who qualifies?
Pertanyaan ini pertama kali sebetulnya muncul dalam esai klasik Dwight MacDonald 1945 “Tanggungjawab Intelektual.” Esai ini adalah kritik pahit dan sinis dari para pemikir terkemuka yang memaparkan tentang “kesalahan kolektif” para pengungsi Jerman yang nyaris tidak bisa bertahan hidup di reruntuhan bencana perang. Terjadi situasi yang kontras antara kondisi para pengungsi yang penuh hina dina sebagai korban yang sengsara dengan reaksi tentara-tentara yang menang yang bersuka cita. Para pemikir itu adalah intelektual, yang melawan perang dan akibat-akibatnya. Yang tentara itu bukan intelektual (h. 10).
Menurut Chomsky, tulisan MacDonald menunjukkan rasa prihatin tentang perang. Dia mengajukan pertanyaan: Sejauh mana orang Jerman atau Jepang bertanggungjawab atas kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah mereka? Dan, dengan tepat, dia membalik pertanyaan itu kepada kita: Sejauh mana orang-orang Inggris atau Amerika yang bertanggungjawab atas serangan teror kejam terhadap penduduk sipil, disempurnakan sebagai teknik peperangan oleh negara-negara demokrasi Barat dan mencapai puncaknya di Hiroshima dan Nagasaki, yang merupakan kejahatan yang paling tak terkatakan dalam sejarah.
Sehubungan dengan tanggungjawab intelektual, masih ada pertanyaan lain yang sama-sama mengganggu. Intelektual berada dalam posisi untuk mengungkap kebohongan pemerintah, untuk menganalisis tindakan sesuai dengan penyebab dan motif mereka dan seringkali tersembul niat tersembunyi. Tanggungjawab para intelektual, kemudian, jauh lebih dalam dari apa yang disebut MacDonald sebagai tanggung jawab individual, mengingat keistimewaan unik yang dinikmati para intelektual (h.22).
“IT IS THE RESPONSIBILITY of intellectuals to speak the truth and to expose lies,” demikian Chomsky. Intelektual harus berani mengatakan kebenaran meski pun itu mungkin akan merugikan kepentingan nasional. Yang diperjuangkan adalah soal kemanusiaan. Dan negara atau pemerintahan pada dasarnya exist karena kepentingan kemanusiaan bagi warganya dan seluruh manusia. Kemampuan berbohong pemerintah tidak pernah diragukan. Media dalam dan luar negeri bisa dikuasai dan segenap perangkat-perangkat lain yang tersedia untuk melakukan kebohongan. Karena itu bagi intelektual yang mengetahui ada kebohongan maka menjadi tanggungjawabnya untuk mengungkapkan pada rakyat, publik.
“Intelektual di Barat, menurutnya, telah kehilangan minat untuk mengubah ide menjadi tuas sosial untuk transformasi radikal masyarakat. Sekarang kita telah mencapai masyarakat pluralistik Negara Kesejahteraan, mereka tidak melihat perlunya transformasi radikal masyarakat; kita dapat mengotak-atik cara hidup kita di sana-sini, tetapi akan salah jika mencoba memodifikasinya secara signifikan. Dengan konsensus intelektual ini, ideologi mati. ”(h. 56).
Konsep intelektual dalam pengertian modern menjadi terkenal dengan “Manifesto Intelektual” 1898 yang terjadi karena kasus Dreyfusards, yang terinspirasi oleh surat protes terbuka dari Émile Zola kepada presiden Prancis, mengutuk framing perwira artileri Perancis Alfred Dreyfus atas tuduhan pengkhianatan dan penyembunyikan dokumen rahasia militer—tuduhan yang di kemudian hari terbukti salah (h. 71). Sekelompok orang menandatangani Manifesto itu dan menamakan diri mereka sebagai Kaum Intelektual. Zola dijatuhi hukuman penjara karena pencemaran nama baik, dan melarikan diri dari negara—sesuatu yang tidak asing bagi kita di sini, saat ini, ketika ada suara kritik pada pemerintah.
Lalu siapakah yang disebut sebagai intelektual? Apakah kaum minoritas seperti Zola? Apakah yang dimaksud dengan tanggungjawab intelektual? Ini adalah pertanyaan yang selalu muncul sepanjang masa. Memang sebagai intelektual, publik mengharapkan mereka yang menjaga moral, tanggungjawab moral sebagai manusia yang punya martabat, integritas untuk memelihara kebebasan berpendapat, mendorong keadilan sosial dan perdamaian. Konsekwensi dari posisi ini sebagai intelektual maka di banyak negara, di banyak rezim mereka menjadi sasaran pembatasan. Dipenjarakan, dibunuh, disingkirkan. Juga terjadi di Amerika Serikat.
Karena tidak semua orang tunduk patuh pada kebijakan pemerintah yang dinilai salah atau bohong. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Bertrand Russell, Eugene Debs, Rosa Luxemburg, dan Karl Liebknecht, seperti Zola, dijatuhi hukuman penjara. Debs dihukum penjara sepuluh tahun karena mengajukan pertanyaan tentang “perang untuk demokrasi dan hak asasi manusia” pada saat Pemerintahan Presiden Wilson. Beberapa, seperti Thorstein Veblen dihukum; Veblen dipecat dari posisinya di the Food Administration setelah menyiapkan laporan yang menunjukkan bahwa kekurangan tenaga kerja pertanian dapat diatasi dengan mengakhiri kebijakan brutal Wilson pada tenaga kerja. Randolph Bourne dijatuhkan oleh jurnal progresif setelah mengkritik bangsa-bangsa imperialistik.
Pola pujian dan hukuman adalah cara klasik yang sudah dikenal sepanjang sejarah: mereka yang berbaris dalam ketiak negara biasanya dipuji, termasuk oleh ‘intelektual’ abal-abal dan mereka yang menolak untuk berbaris dalam ketiak negara dihukum, disingkirkan dan tidak menjadi pahlawan arus utama intelektual. Russell terus dihujat sampai setelah kematiannya.
Kalau kita tarik dalam konteks perkembangan sosial politik di Indonesia saat ini maka Buku Chomsky yang satu ini menegaskan kembali pentingnya intelektual tampil ke depan—siapapun itu yang masuk dalam kategori intelektual. Pada situasi sulit dalam 4 tahun belakangan ini sebagian rakyat merasa telah kehilangan intelektual. Orang-orang yang kita anggap mampu berperan sebagai—serupa atau yang tadinya–cendekiawan nyatanya lebih banyak bertingkah laku sebagai corong atau buzzer dari rezim belaka. Semua memposisikan sebagai pendukung rezim tak peduli apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Orang-orang yang kritis yang berseberangan menghadapi ‘serangan’ yang ‘mematikan.’ Kampus gamang. Kampus tak lagi bebas menjadi ruang bebas mimbar akademik yang mendebatkan beragam isu; kampus dan ‘intelektual’ di dalamnya telah banyak menjadi bagian stempel kebijakan publik.
Pengkhianatan yang ditulis Benda adalah pengkhianatan oleh para intelektual. Dia mengkritik para intelektual Eropa karena membiarkan komitmen politik. Mungkin pengkhianatan kaum intelektual akan terus memainkan drama yang tidak pernah selesai. Mungkin juga sudah dan sedang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Cendekiawan padam karena dua hal: kekuasaan dan ketakutan.
Ada yang beranggapan para pengritik (mungkin termasuk intelektual) lebih baik mengubah rezim dari dalam. Mampukah?
Sebuah laporan berjudul: Buasnya sistem politik Indonesia halangi upaya reformasi dari dalam oleh mantan aktivis, yang dimuat pada laman theconversation.com 6 April 2018 menyebutkan bahwa pada periode pemerintahan saat ini banyak aktifis LSM duduk dalam berbagai posisi di pemerintahan ini. Namun kehadiran para mantan aktivis itu tampaknya gagal dalam mewujudkan perubahan fundamental untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Ini berlaku terutama dalam isu-isu hak asasi manusia, layanan publik, dan korupsi. Dari “dalam sistem ”, para mantan aktivis belum mampu mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus lama hak asasi manusia dan kekerasan negara. Bagi yang bercokol di kantor-kantor BUMN malah sebagian dari BUMN tersebut mencatat kerugian.
Mungkin bukan buasnya sistem politik, tetapi justru lembeknya mantan aktifis itu bertarung pada ruang kekuasaan. Kursi kekuasaan terbukti lebih nikmat.
“As for the responsibility of intellectuals, there does not seem to me to be much to say beyond some simple truths. Intellectuals are typically privileged—merely an observation about usage of the term. Privilege yields opportunity, and opportunity confers responsibilities. An individual then has choices,” pungkas Chomsky (h. 101).
Sudah sepantasnya kaum intelektual bicara kebenaran dan mengungkap kebohongan.
Leadership Is Authenticity, Not Style