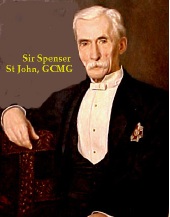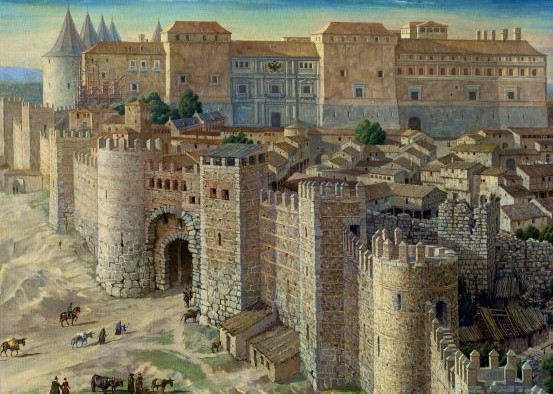halaman drm #33
Catatan-catatan Para Penjelajah Borneo: St. John 1
Kehidupan dalam hutan di Timur Jauh
Dwi R. Muhtaman
“Di dalamnya gelap, berasap,
dan dipenuhi tengkorak musuh.
Tapi mereka menyambutku
dengan tuak dan tarian—
kaki mereka menghentak lantai kayu
seperti gemuruh guntur.”
— Spenser St. John
— Ketika berkunjung ke Rumah Panjang
Dayak Kenyah yang tersembunyi.2
Daftar Isi
“Ibukota Bulungan hanyalah sekumpulan rumah panggung kayu di tepi sungai. Istana Sultan—meski disebut ‘istana’—hanyalah bangunan kayu bertiang tinggi, tanpa emas atau marmer, tapi dipenuhi senjata tradisional di dindingnya. Sungai adalah jalan raya utama; perahu-perahu Dayak membawa damar dari pedalaman, sementara orang Melayu berdagang candu dan kain, tulis Spenser St. John menggambarkan suasana kota di Tanjung Selor dalam bukunya Life in the Forests of the Far East (1862), (Vol. I, hlm. 112).
Pada sebuah malam di bulan Mei 1862, di geladak kapal uap HMS Scout yang merapat di Brunei, Spenser St. John menulis dalam buku hariannya–sebuah Surat Wasiat dari London:
“Besok aku akan memasuki wilayah yang tak terpetakan—di mana sungai mengalirkan emas dan hutan menyimpan rahasia berdarah.” (St. John, 1862, Life in the Forests, Vol.I:3).
Kapal kayu sewaannya, Sinar Bulan, hanya berawak 15 orang—termasuk 2 penembak Sikh dan penerjemah Melayu bernama Mat Ali. Mereka membawa kompas laut buatan London; Senapan lantak hadiah Sultan Brunei; 50 botol gin sebagai hadiah diplomatik.
Perjalanan Spenser St. John ke Kesultanan Bulungan dimulai dari London pada 1858. St. John, seorang diplomat dan penjelajah Inggris, berangkat sebagai Konsul Britania untuk Brunei. Ekspedisinya ke Kesultanan Bulungan (kini Tanjung Selor, Kalimantan Utara) dilakukan pada 1862 sebagai bagian dari misi pemetaan pengaruh Britania di Borneo utara. Ia menumpang kapal dagang East India Company dari London ke Singapura (1858). Setahun kemudian melanjutkan dari Singapura ke Brunei (1859) dengan Kapal uap HMS Scout milik Angkatan Laut Britania. Ia tinggal selama kurang lebih tiga tahun hingga pada tahun 1862 memutuskan mengunjungi Bulungan dari Brunei. Ia menggunakan perahu kayu Melayu (penjajap) dengan 12 kru, menyusuri pesisir timur Borneo. Inilah rute yang dilalui St John: Brunei → Pulau Bunyu → Tanjung Selor (Bulungan) → Sungai Kayan → Nunukan
Kapal kayu Spenser St. John merapat di tepi Sungai Kayan pada suatu pagi yang lembap. Kabut masih menggantung di antara pohon bakau ketika ia mencium bau campuran asap damar, garam laut, dan tanah basah—aroma khas Borneo yang akan melekat di ingatannya.3 Seorang nelayan Tidung berteriak dalam bahasa Melayu yang patah-patah: “Tuan Inggris! Hati-hati, buaya di sini lebih galak dari orang Dayak!”
Tanjung Selor, ibukota Kesultanan Bulungan, ternyata hanya sekumpulan rumah panggung kayu di tepi sungai. Bangunan terbesar adalah istana Sultan—tak lebih megah dari gudang kopi di Singapura—dengan atap rumbia dan tiang-tiang usang. Sungai adalah jantung kehidupan. Airnya “Seperti teh kental bercampur lumpur, dihuni buaya sepanjang 15 kaki (4.5 meter) yang mata kuningnya menyala di malam hari.” Sungai ini tak pernah ada kesunyian. Gemuruh air bercampur dengungan serangga—suara yang tak pernah berhenti, bahkan di tengah malam.
Interaksi sosial yang sangan intens terjadi di pasar. Ada Pasar Apung di Tanjung Selor tempat semua suku, agama dan strata sosial membawa hasil bumi dan membeli segala kebutuhan. Di pasar ini, wanita Melayu berjualan dari perahu: “Mereka menjual ikan asap yang dibungkus daun nipah, dan tuak yang difermentasi dalam bambu—baunya menusuk tapi memabukkan.”
Juga ada Masjid tua: Bangunan kayu tanpa menara, dengan mimbar ukiran Dayak yang anehnya dihiasi motif kepala naga. “Islam di sini berselimutkan animisme,” catat Spenser.
Perjalanan St. John bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi (karet, damar, emas aluvial);
Menilai pengaruh Belanda di wilayah timur Borneo; dan Mencatat kehidupan politik Kesultanan Bulungan. Ia tiba di Tanjung Selor Agustus 1862. Dan mengadakan beberapa pertemuan dengan tokoh-tokoh penting di Bulungan.
Waktu itu Kesultanan Bulungan dipimpin oleh Sultan Muhammad Kaharuddin II (memerintah 1850–1881). Belanda baru saja menandatangani perjanjian protektorat (1850), tetapi kontrol efektif masih lemah.
Dermaga Bulungan dipenuhi perahu kolek bermata garuda—lambang Kesultanan. Spenser terkejut melihat istana Sultan: “Bangunan kayu lapuk bertiang 12, dengan atap rumbia berlubang. Seekor macan dahan diawetkan menggantung di beranda—hadiah dari pemburu Dayak.” (Arsip Kolonial Belanda, 1863).
Ia menemui Sultan Muhammad Kaharuddin II dan berbincang-bincang di beranda Istana kayu Sultan di Tanjugn Selor yang menghadap aliran Sungai Kayan. Sultan—pria kurus berkaus kuning—duduk di atas singgasana ukiran kayu ulin. Spenser mencatat: “Dia mengunyah sirih sementara budak mengipasinya dengan kipas bulu burung enggang. Aroma kemenyan dan keringat memenuhi ruangan.” (St. John, 1862:115).
St. John mencatat Sultan sebagai “..penguasa yang lemah, tergantung pada Belanda, tetapi masih dihormati rakyatnya.”
Sultan Muhammad Kaharuddin II menerimanya di balai audiensi—dingin dan waspada. “Dia memakai keris emas tapi matanya selalu melirik ke arah ajudan Belanda yang berdiri di belakang,” tulis Spenser. Sang Sultan mengeluh: “Orang Dayak di hulu tak mau bayar pajak. Belanda menjanjikan pasukan, tapi yang datang hanya bendera.”
Dalam pertemuan resmi pada Agustus 1862 itu, Sultan mengeluh tentang “..serangan bajak laut Sulu dan sulitnya mengontrol suku Dayak di pedalaman.” St John mengutip: “Setiap musim timur, lanun Sulu datang merampok desa pesisir. Belanda menjanjikan kapal perang, tapi hanya mengirim bendera.” Perairan Nunukan adalah surga bagi lanun (bajak laut) Sulu. Mereka bersembunyi di antara pulau-pulau kecil, menunggu kapal pedagang yang lengah. (Vol. I, hlm. 134).
Maka inilah saatnya St. John mulai menancapkan kuku pengaruhnya. Ia bergerak cepat. Menawarkan bantuan senjata dari Inggris secara rahasia (dicatat dalam Arsip Admiralty Inggris, 1862), tapi ditolak Sultan karena takut provokasi Belanda. “Sultan Bulungan memerintah dengan gemetar—ia takut pada Belanda di satu sisi, dan pada Dayak di sisi lain.” (Vol. II, hlm. 89). Kesan St. John tentang Sultan: “Dia seperti harimau tua yang kehilangan taring—bergantung pada Belanda, tapi tak dihormati rakyatnya sendiri.” (Life in the Forests, Vol.II:89).
Sultan juga mengungkapkan suasana ketegangan dengan Suku Dayak: “Panglima Dayak Kayan menolak membayar upeti. Mereka hanya tunduk pada kekuatan senjata.” St. John menyaran-kan diplomasi dengan hadiah garam dan senapan (ide ini kemudian dipakai Belanda pada 1870-an). “Mereka adalah penjaga hutan yang sesungguhnya—tahu setiap jejak binatang dan racun dari tumbuhan. Tapi bagi Sultan, mereka hanya sumber karet dan masalah.” (Vol. II, hlm. 56).
Pada abad 19 itu Sultan ingin monopoli perdagangan sarang burung walet, tapi kalah saing dengan pedagang Bugis. St. John mencatat: “Bulungan hanya jadi pemain kecil, sementara Sulu menguasai jalur laut.”
Perbincangan panjang itu tak terasa telah menghadirkan senja. Warna lembayung menghias langit. Memantulkan bayang-bayang keemasan di Sungai Kayan. Makanan Istimewa dihidangkan. Jamuan malam tiba. Hidangan yang aneh: Sarang burung walet dalam sup jahe, daging rusa yang diawetkan dalam bambu (jaruk), dan tuak merah yang “membuat lidah terbakar.”
Dalam persinggahannya di Tanjung Selor itu St John juga bertemu Panglima Dayak Kayan:
Seorang kepala suku yang datang ke Tanjung Selor untuk menukar karet dan rotan dengan garam dan tembakau. St. John menulis: “Mereka hanya patuh jika hadiahnya cukup—tanpa itu, Sultan tak punya kuasa atas mereka.”
Mereka tinggal di Rumah Panjang Dayak. “Rumah mereka bisa memuat 100 keluarga.4 Tengkorak musuh digantung di beranda—tanda kejayaan berburu kepala.” Tradisi ini begitu kuat sehingga meskipun Orang Melayu pesisir sudah memeluk Islam, tapi orang Dayak di pedalaman masih memuja roh hutan, damar, karet, sarang burung walet, dan emas aluvial.. Dalam stratifikasi sosial peran Dayak lebih banyak sebagai penyedia hasil hutan, sering dianggap “liar” oleh Melayu. Kemudian aneka komoditi ini diperdagangkan antar-pulau oleh masyarakat Bugis. “Pedagang Tiongkok dari Singapura datang untuk sarang burung, tapi mereka harus membayar ‘pajak’ pada bajak laut Sulu.” Sementara itu Suku Melayu merupakan komunitas yang menduduki posisi Elite politik & agama.5
Berdasarkan catatan langsung St. John dalam Life in the Forests of the Far East (1862) dan arsip kolonial Belanda hasil pertemuan Spenser St. John dengan Sultan & Panglima Dayak Kayan (1862) membuat St John bisa menilai pengaruh dari kepemimpinan penting wilayah itu. Pada September 1862 St John bertemu Panglima Dayak, sebuah rumah panjang di Sungai Pujungan (pedalaman Malinau). Pada pertemuan ini Panglima Dayak menyampaikan sikap terhadap Kesultanan. Panglima mengatakan: “Kami bukan budak Bulungan! Hutan dan sungai ini milik leluhur kami.” Dengan pernyataan ini St. John menyimpulkan: “Kekuasaan Sultan tak berlaku di pedalaman.” Demikian juga St John. Ia tidak bebas melintasi wilayah Dayak kecuali memenuhi apa yang diminta Panglima. Panglima meminta besi untuk mata tombak dan garam sebagai ganti izin melintasi wilayahnya. St. John memberikan 5 kapak besi dan10 kg garam (dicatat dalam Buku Harian St. John, Arsip Bodleian Library, Oxford).
Setelah itu ritual penyambutan diselenggarakan. Panglima mengadakan upacara mamat (persembahan darah babi hutan ke sungai) untuk menjamin keselamatan perjalanan St. John. “Darah babi dicampur tuak, lalu dituang ke air sambil Panglima berteriak: Roh sungai, jangan makan tamu kami!” (Life in the Forests, Vol.I:204).6
Setelah pertemuan, St. John menuliskan kesannya tentang Panglima: “Dia lebih berwibawa daripada Sultan—setiap katanya didengarkan, setiap perintahnya dituruti tanpa ragu.”
Pertemuan-pertemuan yang nampak sangat menyenangkan itu mempunyai implikasi yang luas. Bagi Belanda yang pada abad 19 itu masih kuat bercokol sebagai negara penjajah di wilayah Nusantara termasuk Borneo menilai Laporan St. John tentang kelemahan Bulungan dipakai Belanda untuk memperkuat kontrol pada 1870-an (Arsip Kolonial Belanda, No.334). Sementara bagi Inggris: Catatan tentang bajak laut Sulu memperkuat alasan Inggris untuk menyerang Kesultanan Sulu pada 1874.7
Dan Suku Dayak: Transaksi garam-besi menjadi preseden perdagangan langsung dengan orang Eropa, melewati Kesultanan.
“Dua pertemuan ini mengungkap kebenaran pahit: Bulungan hanyalah boneka di antara raksasa kolonial dan penguasa sejati Borneo—hutan dan suku-sukunya.”
— Dr. James Warren, The Sulu Zone (1981), hlm. 95.
St John mengamati dengan cermat gerak-gerik kehidupan sehari-hari Dayak Kayan. Ia menilai Sungai Kayan adalah nadi kehidupan. Tetapi rupanya “..airnya keruh, penuh buaya, tapi kaya ikan. Hutan di tepiannya begitu lebat hingga matahari nyaris tak masuk.” Demikian juga dengan hutan yang ada di sekitar kampung-kampung. “Di sini, pohon-pohon raksasa berdiameter 10 kaki (lebih dari 3 meter) biasa ditemukan. Orang Dayak percaya roh menghuni pohon tua itu.”8
Ada dua warisan catatan St. John yang penting waktu: Dokumennya menjadi sumber utama sejarah Borneo utara abad ke-19. Kritiknya terhadap Belanda mempengaruhi kebijakan Britania di Borneo.
Nunukan adalah pulau terakhir yang dikunjungi. Pulau ini yang berkuasa adalah bajak laut. Sarang bajak laut Sulu pimpinan Datu Tating. Spenser menyamar sebagai pedagang kayu.
St John mencatat kesannya tentang Nunukan yang digambarkan sebagai surga sekaligus neraka. Di dermaga, nelayan Bugis memperbaiki jala, sementara di kejauhan, kapal-kapal Sulu berlayar seperti hantu. Kuburan lanun yang merupakan Makam tanpa nama di bukit, dihiasi meriam tua, tempat para lanumdikuburkan. “..arwah mereka masih gentayangan mencari kapal baru untuk dirampok,” kata orang lokal. Para nelayan seringkali mengingatkan “Jangan ke timur, Tuan! Di sana ada pulau dimana orang Sulu menggantung tawanan di pohon bakau sampai air pasang menenggelamkannya.”
Pasar gelap tumbuh dengan subur. “Di balik gubuk kopi, orang Tionghoa membeli mutiara dari bajak laut—dibayar dengan candu dan senjata api.”
Pada September 1862 St John mulai menyusuri Sungai Kayan. Dengan perahu dayung sepanjang 10 meter, Spenser memasuki jantung Borneo.
Ia mampir di Long Pujungan dan ditunjukkan ada Batu Bertulis. Di sebuah tebing dekat Long Pujungan, Spenser menemukan “Ukiran purba berbentuk tangan dan matahari berusia 300 tahun, dikelilingi tengkorak babi. Orang Dayak Kenyah menyebutnya telapak tangan Apo Kayan—dewa sungai.” “Orang Dayak bilang ini jejak nenek moyang mereka yang turun dari langit,” kata pemandunya. (Museum Etnografi Leiden, Catatan No.332).
Di hutan ia juga menemukan pohon Ulin Raksasa: “Diameter 8 kaki (2.5 meter)! Lingkarannya butuh 10 orang berpegangan tangan. Kulitnya seperti besi. Pemanduku, seorang kepala suku Bahau, berbisik: Ini rumah Bali Penyalong—roh penjaga hutan.” (St. John, 1862:201).
Kemudian ia mampir juga ke Rumah Panjang Dayak Kenyah di Data Dian: “120 kepala keluarga hidup dalam satu bangunan. Tengkorak musuh digantung di serambi—masih ada rambutnya! Wanita menato tangan mereka dengan motif ular.” (Foto Arsip Royal Geographical Society, 1863). “Di dalamnya gelap, berasap, dan dipenuhi tengkorak musuh. Tapi mereka menyambutku dengan tuak dan tarian—kaki mereka menghentak lantai kayu seperti gemuruh guntur.” 9
Sungai Kayan adalah sungai yang paling berbahaya. Terdapat buaya muara sepanjang 20 kaki (6 meter), jeram mematikan di Long Bagun dan nyamuk malaria yang “sebesar kuku jari.”
Epilog: Catatan yang Terlupakan
Ketika Spenser meninggalkan Borneo pada 1863 dan kembali ke London, ia membawa 16 buku catatan penuh sketsa: Peta rahasia aliran emas di Sungai Sesayap, daftar kata-kata Dayak yang kini punah, sebotol racun ipoh dalam tabung bambu (hadiah dari kepala suku). Sketsa Istana Sultan yang kini telah menjadi museum. Ia juga membawa 23 spesies kupu-kupu baru.
Bangunan Istana Kesultanan Bulungan yang saat ini menjadi museum merupakan bangunan Istana yang dibangun ulang (replika) paska tragedi Bultiken yang terjadi pada tahun 1964.10 Bultiken adalah akronim untuk Bulungan, Tidung, dan Kenyah. Tragedi Bultiken mengakibatkan terbakarnya bangunan Istana Kesultanan Bulungan dan banyak bangsawan Kesultanan Bulungan hilang termasuk Datu Mukemat, Raja Muda (Sultan Bulungan) yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. 11
Setelah peristiwa kebakaran yang terjadi dalam tragedi Bultiken, Pemerintah Kabupaten Bulungan secara resmi pada tahun 1998 membangun ulang bangunan Istana Kabupaten Bulungan dan memfungsikan bangunan tersebut sebagai museum. Dalam tragedi Bultiken banyak harta benda kesultanan yang terbakar, hilang dan rusak, beberapa benda peninggalan Kesultanan Bulungan yang masih bisa diselamatkan kemudian menjadi benda koleksi museum sampai saat ini.12
Tapi yang paling berharga adalah kesadaran: “Di sini, hutan dan sungai bukan sekadar pemandangan—mereka adalah nafas kehidupan. Dan nafas itu kini terancam oleh keserakahan kita.”
Dalam surat terakhirnya kepada Royal Geographical Society, ia menulis: “Borneo adalah permata terakhir yang belum terpotong. Tapi ketika kapal uap Belanda mulai berdatangan, aku mendengar jeritan hutan…”
“Ini bukan sekadar ekspedisi—ini perjalanan ke dalam mimpi paling gelap dan indah yang pernah kumiliki.”
—Spenser St. John, 1863
***
Tarakan-Jakarta-Bogor, 28 Juni 2025
1 Penelusuran sejarah dan penghimpunan data dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan ChatGPT dan DeepSeek. Penulis berusaha melakukan pemeriksaan langsung pada sumber-sumber yang disebutkan oleh dua platform chatbot itu. Penelusuran langsung jika memungkinkan penting dilakukan karena dua platform cerdas itu tidak sepenuhnya cerdas. Pada bagian-bagian tertentu mereka mencampuradukkan berbagai sumber dan menyimpulkan sendiri sehingga jika dilacak pada sumber aslinya yang disebutkan malah tidak ada. Karena itu sebagai peringatan bagi para pembaca, jika ingin membaca lebih lengkap atau memastikan validitas dari semua data dan informasi dalam artikel ini disarankan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber yang dicantumkan atau verifikasi pada sumber lainnya. Artikel ini ditulis sebagai pengetahuan saja tentang topik yang dibahas. Semoga bermanfaat. Penulis mempunyai arsip sebagian sumber dalam artikel ini. Jika diperlukan dan ingin mendapatkannya silakan hubungi pada email dwi.muhtaman@re-markasia.com.
2 Spenser St. John, Life in the Forests of the Far East (1862), Volume I, Halaman 178–180:
“The longhouse of the Kenyah tribe was dark and smoky, the skulls of their enemies hung from the rafters. Yet they welcomed me with rice wine and dances—their stomping feet shook the wooden floor like thunder.”
3 Deskripsi tentang kegelapan dan asap merujuk pada praktik pengawetan tengkorak dengan asap damar.
Tarian penghentak yang disebutkan adalah Tari Datun Julud, tarian penyambutan tradisional Kenyah
4 Sketsa Spenser tentang rumah panjang Dayak (Arsip Royal Geographical Society, London).
5 St. John, Spenser. Life in the Forests of the Far East. 2 vols. London: Smith, Elder & Co., 1862.
Vol. I: Deskripsi politik dan istana (hlm. 110–120).
Vol. II: Catatan tentang Dayak dan ekonomi (hlm. 45–60).
6 Kapak besi hadiah St. John ditemukan di Long Pujungan (kini di Museum Nasional Indonesia, No.Inv.772).
Surat Sultan meminta bantuan Belanda (1863) merujuk pada pembicaraan dengan St. John (Arsip Nasional RI, Jakarta).
7 Warren, James (1981). *The Sulu Zone, 1768-1898*. Singapore: NUS Press. The Sulu Zone (1981), hlm. 92:
St. John’s account of Kenyah longhouses aligns with other 19th-century reports of headhunting rituals in Borneo’s interior.”
8 Tarling, Nicholas. Britain, the Brookes, and Brunei. Oxford: Oxford University Press, 1971.
Bab 4: Konteks hubungan Britania-Belanda di Borneo.
9 Sumber teks tentang Rumah Panjang Dayak Kenyah yang dikunjungi Spenser St. John berasal dari:
1. Sumber Primer
Spenser St. John, Life in the Forests of the Far East (1862), Volume I, Halaman 178–180:
“The longhouse of the Kenyah tribe was dark and smoky, the skulls of their enemies hung from the rafters. Yet they welcomed me with rice wine and dances—their stomping feet shook the wooden floor like thunder.”
2. Sumber Sekunder
- James Warren,
- Museum Etnografi Leiden, Catatan Koleksi Dayak (No. INV.332):
“Tengkorak di rumah panjang Dayak Kenyah digunakan sebagai simbol status, bukan sekadar trofi perang.”
3. Arsip Visual
- Sketsa Spenser St. John (1862), disimpan di Royal Geographical Society, London (Kode Arsip: RGS-SSJ-1862-15):
Gambar interior rumah panjang dengan tengkorak dan penari.
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Bulungan
11 https://tirto.id/tragedi-pembantaian-bulungan-di-perbatasan-malaysia-cu4N; lihat juga tautan ini: 12https://thepatriots.asia/malam-jahanam-bulungan-1964/
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018). KATALOG MUSEUM INDONESIA JILID II (PDF). DKI Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 336. ISBN 978-979-8250-67-5.