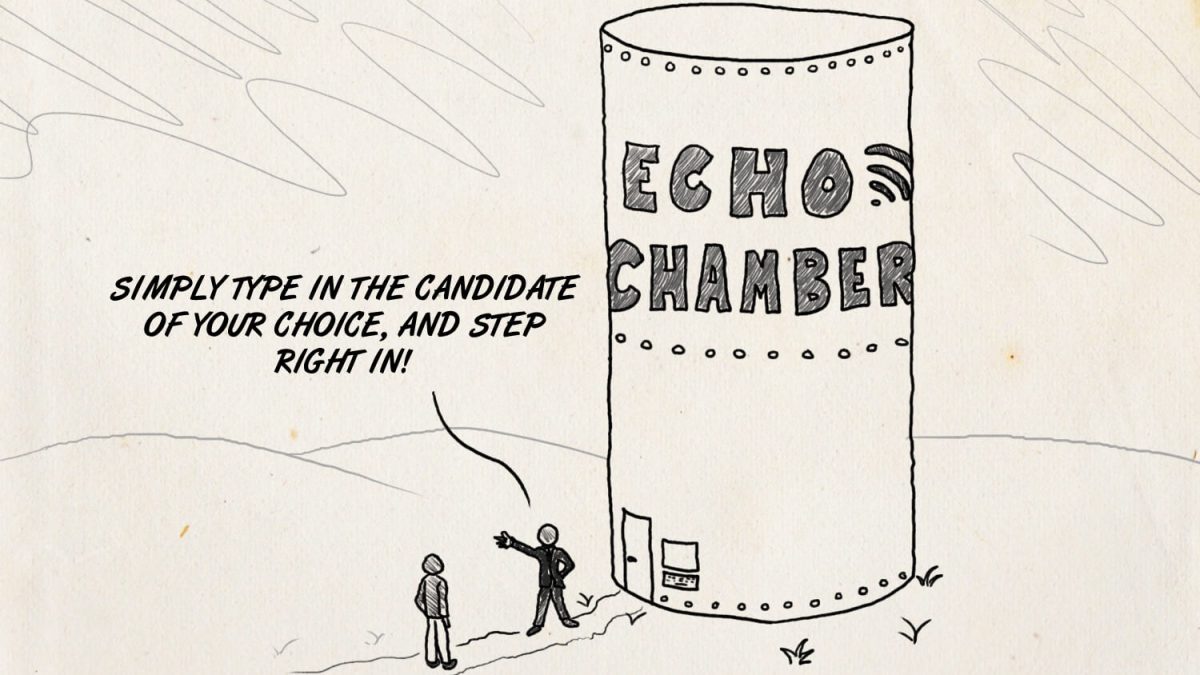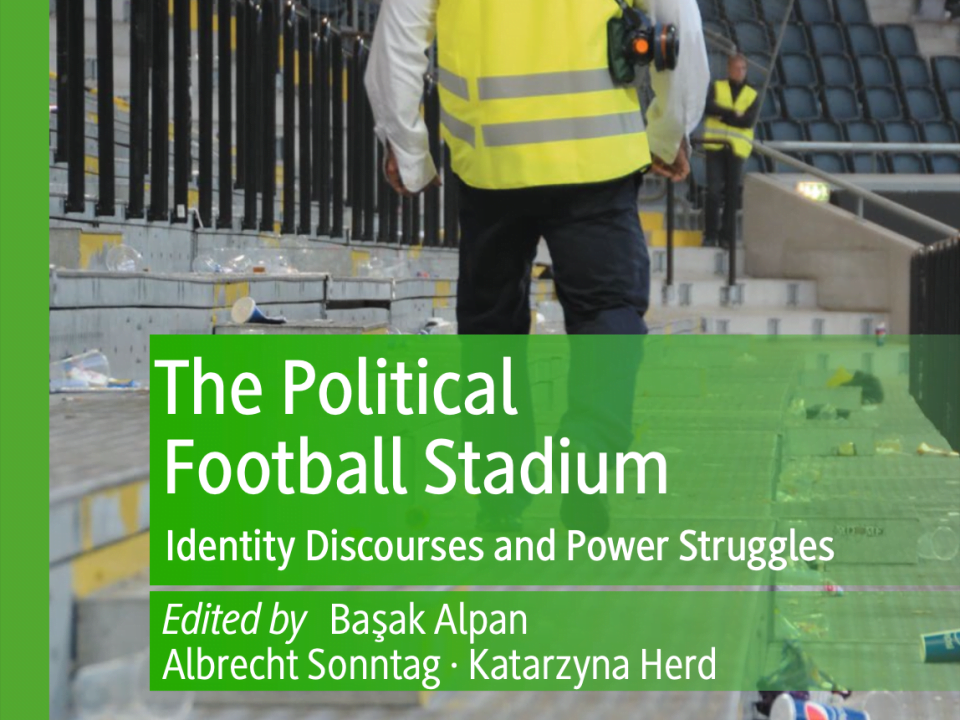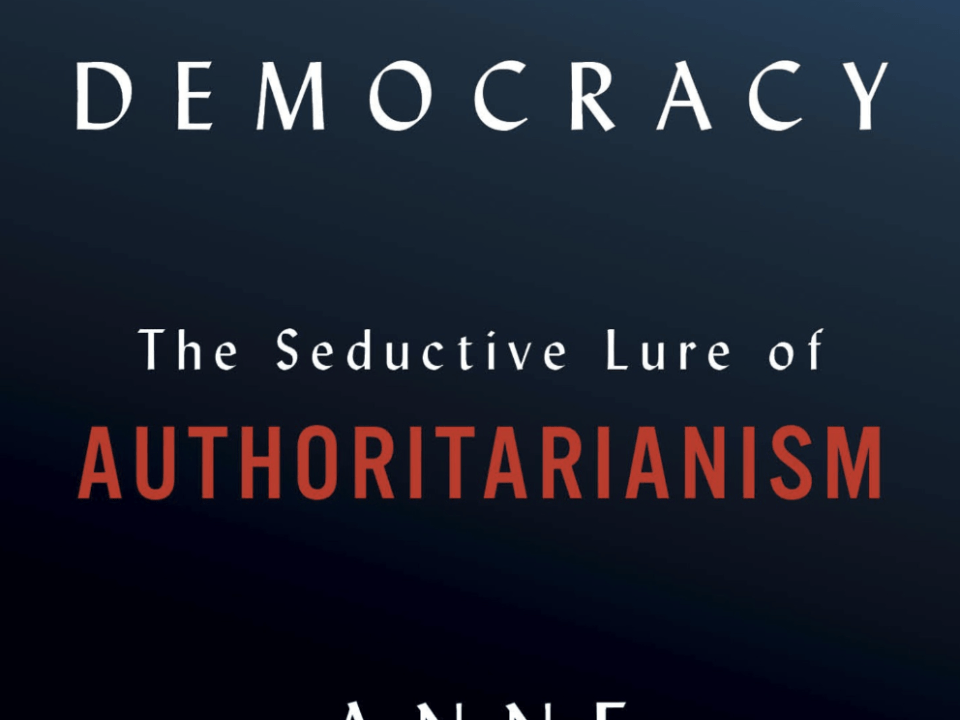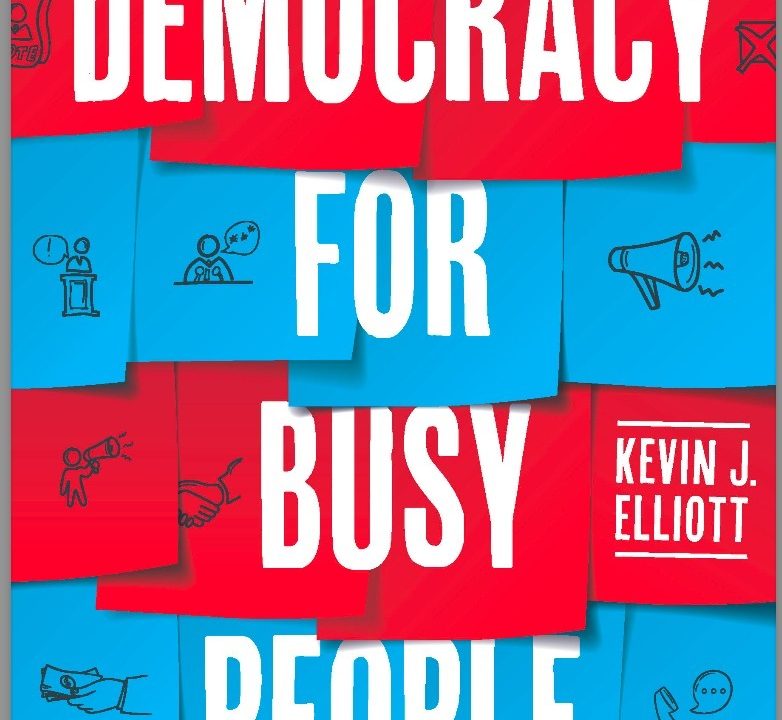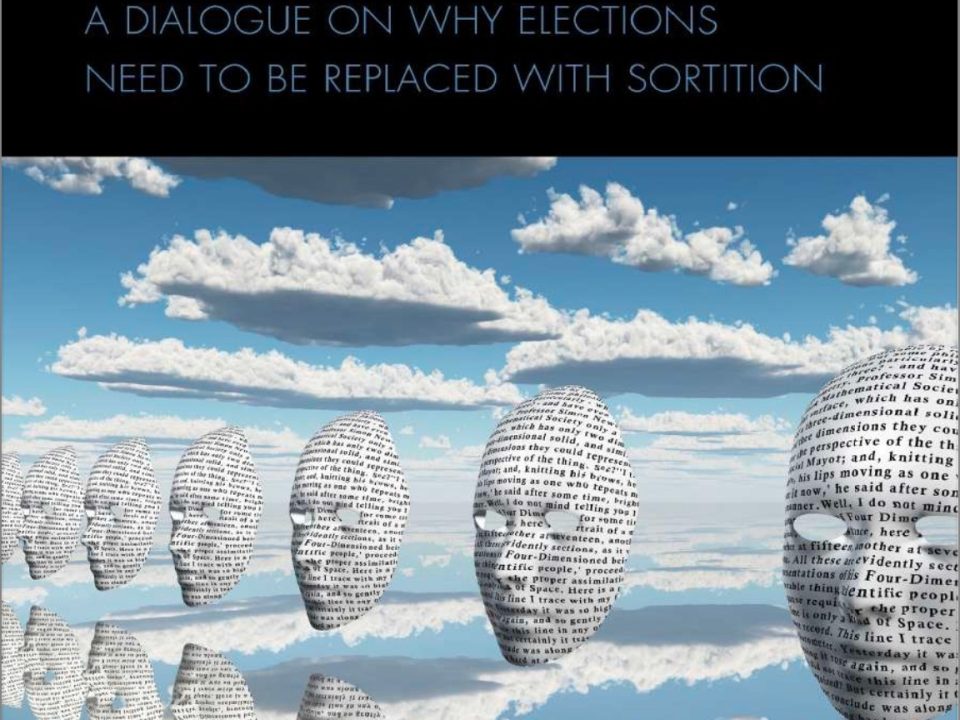Republik Echo Chamber: Demokrasi yang Terbelah
—Dwi R. Muhtaman—
Bogor, 12042019
#BincangBuku #23
“In a well-functioning democracy, people do not live in echo chambers or information cocoons. They see and hear a wide range of topics and ideas.”
Cass R. Sunstein. “#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media” (2017).
Kita saksikan dan alami akhir-akhir ini sulit sekali untuk bertukar pikiran, mengakui kebenaran logika berpikir atau menerima argumen dan fakta-fakta dari lawan bicara yang mempunyai pandangan politik berbeda. Mengapa? Jika kita amati dengan baik laman Facebook, Twitter dan sejumlah sosial media lainnya yang kita kelola seringkali berisi pandangan-pandangan yang sejalan dengan pandangan kita. Kita terhubung dengan orang-orang yang mempunyai haluan pikiran, hobby atau ketertarikan yang serupa dengan kita. Kita mengikuti hanya pandangan dan segala sesuatu yang seragam dengan pandangan, kepentingan kita. Sesuatu yang berbeda kita hindari. Termasuk, apalagi, dalam dunia politik. Kita mengikuti dan hanya bisa menerima argumentasi, informasi dan pandangan yang sejalan dengan atau mendukung pandangan politik kita.
Cass R. Sunstein dalam bukunya: “#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media” (2017), yang kita bincangkan ini mengupas dengan mendalam kecenderungan orang-orang untuk menyaring semua informasi hanya berdasarkan pandangan, pikiran, ketertarikan masing-masing. Semua hal yang ada di luar itu diabaikan. Kita makin cenderung bergerak ke arah homogenitas yang terbelah. Masing-masing mempunyai dan hidup dalam kepompongnya. Kecenderungan ini membuat demokrasi kita terbelah. Masyarakat tidak lagi berbincang dalam keragaman pikiran dan gagasan. Tidak lagi terjadi penyerbukan silang pandangan dan perspektif. Ini memperburuk mutu demokrasi. Gejala dan praktek-praktik ini seperti virus. Menjangkit pada semua negara dan lapisan masyarakat. Bukan hanya terjadi di Indonesia. Ia marak juga berjangkit di Amerika, Inggris, Perancis, Turki, Timur Tengah dan sejumlah negara-negara lain, dimanapun sosial media beraksi.
Bergemuruhnya sosmed sebagai perangkat hidup mutakhir saat ini telah membuat para ilmuwan demokrasi bertanya-tanya. Apa implikasi sosmed bagi kehidupan demokrasi? Cass Sunstein, penulis #republic adalah seorang sarjana hukum Amerika, khususnya di bidang hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum lingkungan, dan hukum dan ekonomi perilaku, Sunstein pernah menjadi Administrator untuk Urusan Informasi dan Regulasi Gedung Putih pada pemerintahan Obama selama 2009 – 2012. Buku lain yang juga membahas demokrasi dalam hubungannya dengan sosmed antara lain: POLITICAL TURBULENCE: HOW SOCIAL MEDIA SHAPE COLLECTIVE ACTION yang dikupas habis oleh HELEN MARGETTS, PETER JOHN, SCOTT HALE & TAHA YASSERI (2016). Kemudian NERVOUS STATES: Democracy and the Decline of Reason yang ditulis oleh WILLIAM DAVIES (2018). WHY DEMOCRACIES FLOUNDER AND FAIL: Remedying Mass Society Politics yang ditulis oleh Michael Haas (2019). Ini untuk menyebut beberapa saja.
Buku Sunstein terdiri dari 11 Bab. Ia mengupas topik-topik antara lain the daily me yang menggambarkan kecenderungan masyarakat yang hanya mendengar urusannya sendiri, membahas an analogy and an ideal yang memaparkan tentang pentingnya memelihara sebuah publik forum sebagai ruang bersama, lalu menganalisis soal polarisasi dalam masyarakat. Buku ini juga mengurai panjang lebar mengenai kewarganegaraan, freedom of speech dan terorisme; dan pada bagian akhir (Bab 11) ia mengingatkan lagi pada kita mengenai konsep #republic.
Masyarakat yang demokratis tidak akan berhasil jika mereka tidak mampu menghargai pandangan berbeda sesama warga negara, jika mereka percaya berita palsu, atau jika mereka melihat satu sama lain sebagai musuh atau lawan yang saling bermusuhan. Learned Hand, seorang hakim yang dikutip Sunstein mengatakan beberapa dekade yang lalu, “the spirit of liberty is that spirit which is not too sure that it is right” (h. 10). Ketidakpastian akan sesuatu yang benar barangkali membuat orang untuk belajar. Berburu melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan untuk menemukannya. Karena itulah kemajuan dicapai.
Apa yang disebut Sunstein sebagai democratic dystopia atau demokrasi yang buruk, kekalahan demokrasi adalah cermin dari dampak sosial media yang menciptakan keterbelahan dalam masyarakat. Ada kisah abadi tentang distopia demokrasi. George Orwell’s Nineteen Eighty-Four, dengan Big Brother yang ada di mana-mana, yang menyangkal pilihan, adalah visi paling umum tentang kekalahan demokrasi. Novel Orwell menggambarkan kemenangan otoriterianisme, yang dilambangkan dengan wajah terbuka, dan tercermin dalam Jerman Adolf Hitler, Uni Soviet Joseph Stalin, dan Mao Tse-tung China. Kisahnya adalah kisah kemenangan fasisme atau komunisme. Otoriter adalah soal sensor. Membungkam mereka yang tidak setuju dengan rezim. Bagi mereka, internet bisa menjadi ancaman besar, dan mereka gugup tentang media sosial, yang dengan susah payah menjadi target sensor (kecuali jika itu sesuai dengan tujuan mereka), (h. 11).
Pada tahun 1995, demikian tulis Sunstein, spesialis teknologi MIT Nicholas Negroponte menubuatkan munculnya “The Daily Me” (h. 16). Dengan Daily Me, Anda tidak akan bergantung pada surat kabar untuk mencermati apa yang Anda lihat, dan Anda dapat mengabaikan jaringan televisi. Sebagai gantinya, Anda dapat merancang paket komunikasi hanya untuk Anda, dengan masing-masing komponen sepenuhnya dipilih terlebih dahulu. Anda tinggal memilih apa yang Anda sukai. Apapun. Jika Anda ingin fokus hanya pada bola basket, Anda bisa melakukan itu. Jika seleramu pada William Shakespeare, Daily Me-mu bisa jadi Shakespeare, sepanjang waktu. Jika Anda suka membaca tentang roman — mungkin melibatkan selebriti favorit Anda — koran, televisi atau sosmed Anda bisa fokus pada urusan cinta terbaru soal itu.
Yang penting adalah bahwa dengan Daily Me, semua orang dapat menikmati arsitektur kontrol. Kita masing-masing akan sepenuhnya bertanggungjawab atas apa yang kita lihat dan dengar.
Dalam domain yang tak terhitung jumlahnya, manusia menunjukkan “homofili”: kecenderungan kuat untuk terhubung dan terikat dengan orang-orang yang seperti mereka. Kecenderungan homophily berkurang jika orang hidup dalam arsitektur sosial yang mengekspos mereka ke berbagai jenis orang — dalam hal perspektif, minat, dan keyakinan. Tetapi dengan arsitektur kontrol, “birds of a feather can easily flock together,” berkumpul hanya dengan orang-orang serupa. Pada 1990-an, gagasan Daily Me tampak agak tidak masuk akal. Tapi itu ide yang menarik. Negroponte mungkin meremehkan atau tidak menduga apa yang akan terjadi, apa yang sekarang telah tiba, dan apa yang ada di cakrawala. Kehadiran Daily Me ini bisa jadi sesuatu yang mengkhawatirkan.
Mungkin saja benar, tidak ada Daily Me, seutuhnya. Tapi kita sudah mulai merasakan kehadirannya. Misalnya saja, seperti dikutip Sunstein, dan juga saya kira sehari-hari kita alami di Indonesia, sebagian besar orang Amerika sekarang menerima banyak berita dari media sosial, dan di seluruh dunia, Facebook telah menjadi pusat pengalaman orang di dunia. Dulu dikatakan bahwa “Revolusi Tidak Akan Di Televisi”; mungkin ya atau mungkin tidak. Tetapi kita sangat yakin bahwa revolusi akan di-tweet (#Revolution). Pada 2016, misalnya, militer berupaya melakukan kudeta di Turki. Jaringan televisi utama negara berhasil dikuasai. Tetapi mereka gagal mengambil alih media sosial. Pemerintah dan pendukungnya berhasil menggunakan sosial media untuk memanggil dan menggerakkan publik ke jalan-jalan. Dan, dalam waktu singkat, mampu menstabilkan situasi. Upaya kudeta sering kali merupakan persoalan persepsi publik, apakah mereka berhasil atau gagal, dan media sosial memainkan peran utama dalam memerangi persepsi bahwa pemerintah sedang jatuh.
Konten Twitter Anda mungkin mencerminkan topik dan keyakinan pilihan Anda, dan itu mungkin memberikan banyak hal tentang politik — pajak, imigrasi, korupsi, ketidakadilan, hak sipil, perang dan perdamaian. Apa yang masuk dalam Twitter Anda adalah pilihan Anda, bukan orang lain. Anda mungkin memilih untuk memasukkan topik yang menarik minat Anda, dan sudut pandang yang Anda anggap cocok. Nampak merupakan sesuatu yang sangat alami. Untuk apa Anda mengikuti topik yang membuat Anda bosan dan perspektif yang Anda benci? Kita hanya mengikuti topik yang kita sukai dan sesuai dengan perspektif kita saja (h. 19).
Inilah yang membuat kita makin hidup dalam tempurung dan hanya bersuara dan mendengar dalam ruang yang bergaung, kamar gema, berbicara dan mendengarkan itu-itu saja yang ada dalam ruangan bergaung, echo chamber.
Dengan kemajuan teknologi sosial media dan internet, ternyata, kita tidak lagi perlu bersusah payah membuat Daily Me. Orang lain membuatnya untuk kita saat ini (dan Anda mungkin tidak tahu bahwa mereka melakukannya). Facebook sendiri melakukan beberapa kurasi, menyodorkan rekomendasi teman, topik, berita, buku, hiburan dan apapun yang sesuai dengan selera dan perspeksi Anda, dan begitu pula Google. Di Twitter kita bisa aktifkan pilihan “Trends for you.” Kita hidup di zaman algoritma, dan algoritma itu tahu banyak. Dengan meningkatnya kecerdasan buatan, algoritma merekat untuk meningkatkan kecerdasannya secara tak terbayangkan. Mereka (algoritma itu) akan belajar banyak tentang Anda, dan mereka akan tahu apa yang Anda inginkan atau sukai, sebelum Anda melakukannya, dan malah bisa lebih baik daripada Anda sendiri. Mereka bahkan akan mengetahui emosi Anda, lagi-lagi sebelum Anda sendiri tahu dan lebih baik daripada Anda. Mereka dapat meniru emosi mereka sendiri.
Bahkan sekarang, sebuah algoritma yang mempelajari sedikit tentang Anda dapat menemukan dan memberi tahu Anda apa yang cenderung disukai “orang seperti Anda.” Hal yang dapat membuat sesuatu yang makin dekat dengan Daily Me, hanya untuk Anda, dalam hitungan detik. Sebenarnya itu terjadi setiap hari. Jika algoritma tahu bahwa Anda menyukai jenis musik tertentu, ia mungkin tahu, dengan probabilitas tinggi, jenis film dan buku apa yang Anda sukai, dan kandidat politik apa yang akan menarik bagi Anda.
Dan jika ia tahu situs web apa yang Anda kunjungi, mungkin juga tahu produk apa yang mungkin Anda beli, dan apa pendapat Anda tentang perubahan iklim, korupsi, pandangan politik, kuliner, tempat wisata, pakaian dan imigrasi. Atau mari kita berselancar singkat dalam dunia hashtag. Dengan #Ireland, #SouthAfrica, #DemocratsAreCommunists, atau #ClimateChangeIsAHoax, #2019GantiPresiden, Anda dapat menemukan dalam sekejap sejumlah besar item yang menarik minat Anda, atau yang sesuai dengan atau bahkan memperkuat keyakinan Anda. Seluruh ide soal tagar adalah untuk memungkinkan orang menemukan tweet dan informasi yang menarik minat mereka. Ini adalah mekanisme penyortiran yang sederhana dan cepat. Anda dapat membuat tidak hanya Daily Me, melainkan #MeThisHour atau #MeNow. Banyak orang kini merupakan hashtag enterpreneur; mereka membuat atau menyebarkan tagar sebagai cara untuk mempromosikan gagasan, perspektif, produk, orang, fakta yang diduga, dan akhirnya tindakan (h. 21).
Demikian situasi kehidupan dunia baru kita dengan perangkat sosial media. Sunstein menganalisis secara mendalam tingkah laku baru dan menganalisisnya dalam konteks demokrasi. Keseragaman akan mengancam demokrasi. Sebab: “In a well-functioning democracy, people do not live in echo chambers or information cocoons. They see and hear a wide range of topics and ideas.”
Seperti yang akan kita lihat, banyak orang menyukai echo chamber, dan mereka sangat ingin tinggal di dalamnya. Namun banyak pula orang tidak suka echo chamber; mereka penasaran, bahkan sangat intens, dan mereka ingin belajar tentang segala macam topik dan banyak sudut pandang. Banyak orang hanya tertarik, secara default, ke situs yang paling terkenal atau populer, yang tidak memiliki orientasi ideologis yang jelas. Studi empiris menegaskan klaim-klaim ini, yang menunjukkan bahwa banyak anggota masyarakat sangat tertarik untuk melihat perspektif yang berbeda dari mereka sendiri, dan juga bahwa dengan penelusuran online, kebanyakan orang menghabiskan waktu mereka di situs-situs utama yang kurang memiliki keyakinan politik yang dapat diidentifikasi. Banyak orang terbuka (open minded), dan pandangan mereka bergeser berdasarkan apa yang mereka pelajari. Orang-orang semacam itu memiliki sifat standar moral publik yang jelas; mereka tidak terlalu yakin bahwa mereka benar, dan mereka ingin menemukan kebenaran.
Banyak orang lain lebih suka mendengar pendapat yang konsisten dengan pendapat mereka sendiri, tetapi mereka juga sangat ingin mendengar pendapat yang menantang mereka; mereka tidak menyukai gagasan echo chamber, dan mereka tidak menciptakannya untuk diri mereka sendiri.
Bagi saya yang membaca buku ini, jawaban Sunstein mengejutkan. Ia menganggap orang-orang yang cenderung hidup dalam echo chamber itu adalah violent extremism, ekstremisme keras. Jika orang yang berpikiran sama (like-minded) menggerakkan satu sama lain ke tingkat kemarahan yang lebih besar, konsekuensinya bisa benar-benar berbahaya. Ini barangkali yang bisa menjelaskan mengapa aneka demonstrasi untuk kepentingan apapun pada dasarnya digerakkan oleh echo chamber dalam tingkat tertentu. Sunstein menjelaskan satu sisi yang dianggap berbahaya.
Ruang gema dapat membuat orang percaya pada kepalsuan, dan mungkin sulit atau tidak mungkin untuk memperbaikinya (Baca misalnya buku: Trust Me I’m Lying yang ditulis oleh Ryan Holiday, 2012). Kepalsuan memakan korban. Salah satu ilustrasinya misalnya kepercayaan bahwa Presiden Barack Obama tidak dilahirkan di Amerika Serikat, dan banyak contoh di Indonesia. Seiring dengan kepalsuan itu, yang satu ini bukan yang paling merusak, tetapi keduanya mencerminkan dan berkontribusi pada politik kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kadang-kadang kebencian. Contoh yang lebih berbahaya adalah serangkaian kepalsuan yang membantu menghasilkan suara yang mendukung “Brexit” (eksodus Inggris dari Uni Eropa) pada 2016. Bahkan jika Brexit adalah ide yang baik (dan nampak tidak demikian), suara yang mendukungnya dimungkinkan, sebagian, dengan menggunakan media sosial yang sangat menyesatkan rakyat Inggris. Dalam kampanye presiden 2016 di Amerika Serikat, kepalsuan menyebar seperti api di Facebook. Di Indonesia kepalsuan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan lebih-lebih dalam masa pemilu.
Berita palsu ada di mana-mana. Sampai saat ini, media sosial belum membantu menghasilkan perang saudara di Amerika Serikat, Eropa atau Indonesia, tetapi hari itu mungkin akan datang jika kita tak mampu mengelolanya dengan bijak, adil dan berhati-hati. Di negara-negara dengan konflik laten sosial media telah mengubah konflik laten menjadi konflik nyata.
Mereka telah membantu mencegah kudeta (di Turki pada 2016).
Bagaimana mencegah keburukan echo chamber dan segenap aspek yang mengikuti? Sunstein percaya bahwa ruang publik internet adalah jaringan. Namun pengelompokan atau polarisasi masyarakat yang umum, maupun untuk politik, mempunyai risiko yang signifikan. Bahkan jika hanya sejumlah kecil orang memilih untuk mendengarkan dan berbicara dengan mereka yang berpikiran sama. Masyarakat yang bebas tentu akan mendapat manfaat dari domain publik yang menawarkan beragam topik dan posisi. Kemampuan masyarakat untuk mendengar dan mengapresiasi pandangan, pikiran dan gagasan yang berbeda akan menjadikan demokrasi yang bermutu dan menjadi prasyarat untuk memelihara sebuah republik. “..a republic, or at least a heterogeneous one, requires arenas in which citizens with varying experiences and prospects, and different views about what is good and right, are able to meet with one another and consult,” tulisan Sunstein (h. 454).
Apa yang dipaparkan Sunstein dalam 524 halaman ini adalah poin-poin tentang tata kelola, tetapi, seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian, ada masalah tentang kebebasan individu yang menjadi perhatian. Ketika orang memiliki banyak pilihan dan kebebasan untuk memilih di antara mereka, mereka memiliki kebebasan memilih, dan itu sangat penting. Seperti yang ditekankan Milton Friedman, orang harus “bebas memilih.” Tetapi kebebasan membutuhkan jauh lebih dari itu. Ini membutuhkan kondisi latar belakang tertentu, memungkinkan orang untuk memperluas cakrawala mereka sendiri dan mempelajari apa yang benar.
“For a healthy democracy, shared public spaces, online or not, are a lot better than echo chambers.”