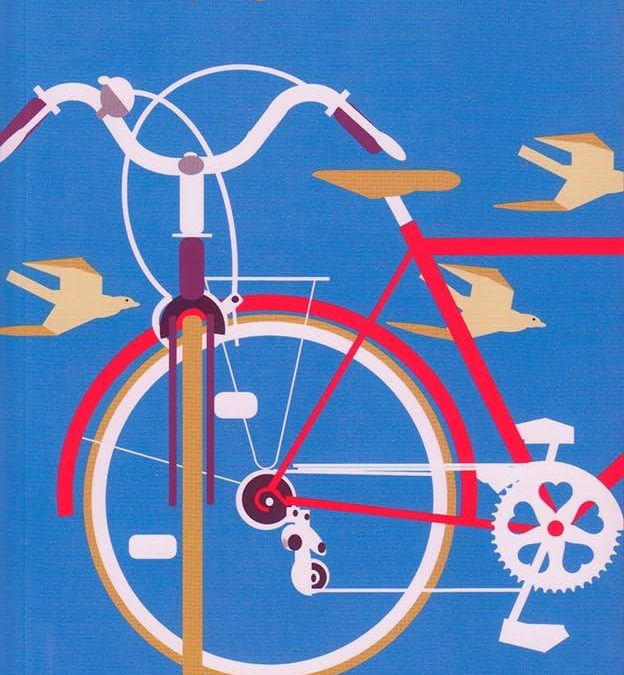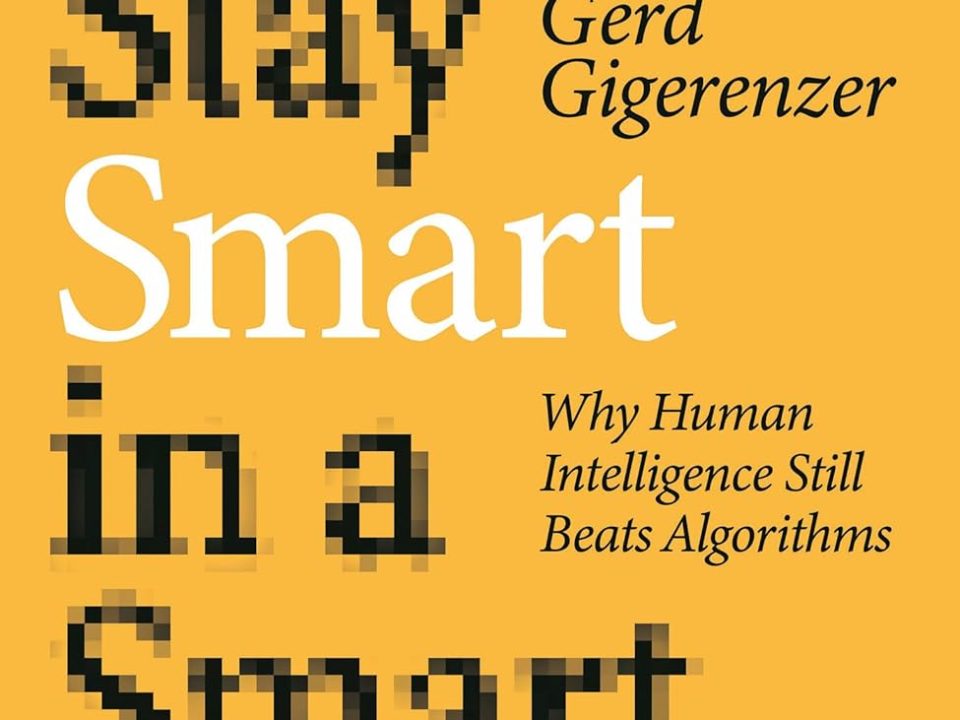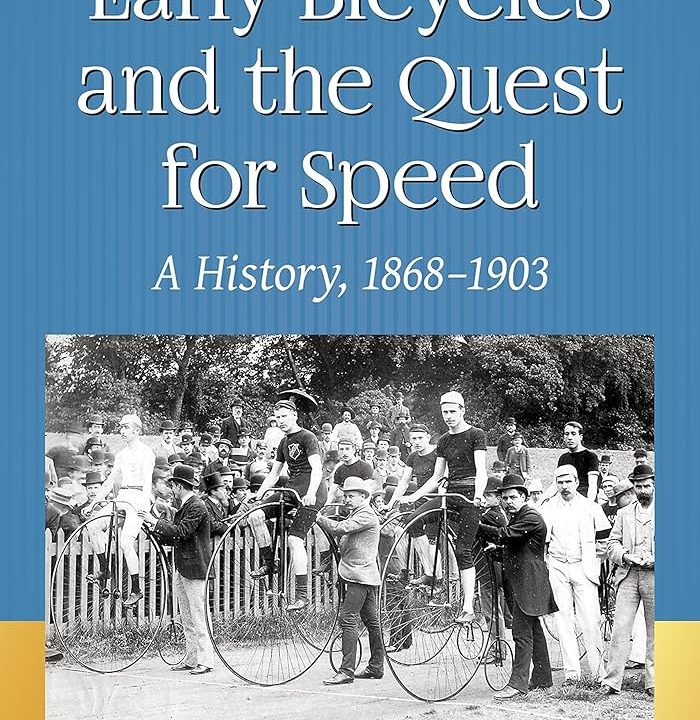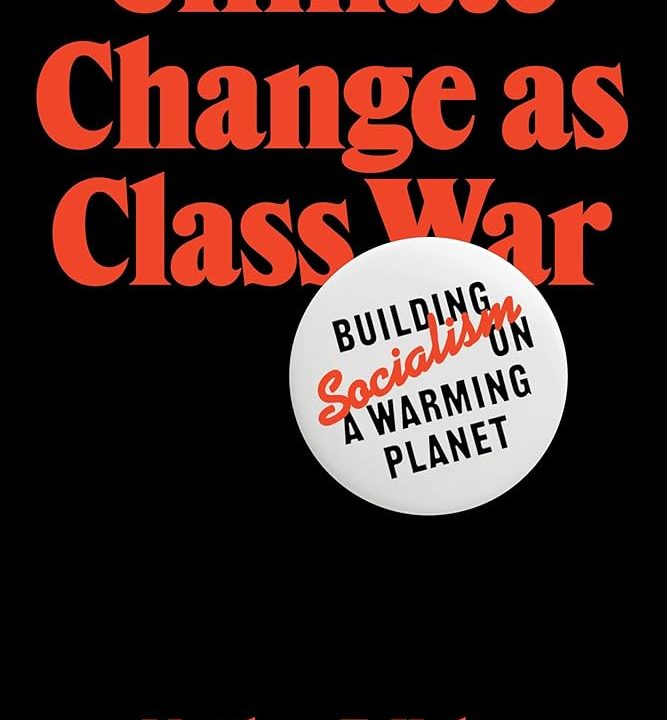Rubarubu #46
Bikenomics:
Sepeda Sebagai Penyangkalan Kapitalisme
Ketika Dua Roda Membongkar Mitos Ekonomi Modern
Elly Blue membuka Bikenomics dengan satu pengamatan sederhana namun mengguncang: di banyak kota Amerika, seseorang bisa membeli sepeda bekas murah, menggunakannya setiap hari, dan hidup lebih sehat—namun sistem ekonomi justru memperlakukan pilihan itu seolah-olah “tidak rasional.” Dalam salah satu bagian awal, Blue menulis dengan nada personal se-kaligus politis bahwa bersepeda membuatnya sadar betapa “anehnya” ekonomi arus utama: “The more you bike, the less money you need, and the more freedom you have. That’s not supposed to work in our economy.”(Blue, 2016).
Kalimat ini menjadi benang merah buku Bikenomics: How Bicycling Can Save the Economy karya Elly Blue (2016): sepeda mengungkap kebohongan struktural ekonomi berbasis mobil. Jika ekonomi konvensional mengklaim mendorong kesejahteraan, mengapa ia bergantung pada sistem transportasi yang mahal, berbahaya, boros energi, dan menciptakan kemiskinan struktural? Selain Bikenomics, Blue juga menulis dan menyunting berbagai buku bertema sepeda, seperti “Everyday Bicycling” dan seri “Pedal Zombies: Women & Bicycles”. Tulisannya muncul di media seperti The Guardian, Grist, dan Bicycling Magazine.
Dunia saat ini dikendalikan oleh ekonomi mobil. Bukan sebagai pembuat kemudahan untuk semua tetapi justru sebagai mesin ketimpangan. Bagian awal Bikenomics membedah bagai-mana ekonomi modern—khususnya di Amerika Utara, dan kini hampir dimana-mana, termasuk Indonesia—dibangun di atas asumsi bahwa kepemilikan mobil adalah kebutuhan dasar. Blue mengurai biaya tersembunyi mobil: cicilan, asuransi, bahan bakar, parkir, perawatan, hingga dampak kesehatan dan lingkungan. Mengutip data transportasi dan kesehatan publik, ia menunjukkan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah sering kali menghabiskan proporsi pendapatan yang sangat besar hanya untuk “bisa pergi bekerja.”
Di sini sepeda muncul bukan sekadar alternatif murah, melainkan kritik struktural. Bersepeda mengungkap bahwa banyak biaya hidup modern sebenarnya adalah hasil desain kebijakan, bukan kebutuhan alamiah. Blue menulis bahwa ekonomi mobil menciptakan lingkaran setan: untuk bisa bekerja orang perlu mobil, untuk membayar mobil orang harus bekerja lebih keras, dan waktu hidup pun habis di jalan.
Argumen ini sejalan dengan kritik klasik Ivan Illich dalam Energy and Equity (1974), yang menyebut mobil sebagai teknologi yang melampaui ambang keadilan sosial: semakin cepat kendaraan, semakin besar ketimpangan yang diciptakan. Illich menulis bahwa sepeda adalah “alat yang memberi kecepatan maksimum dengan biaya minimum bagi masyarakat” (Illich, 1974).
Sedangkan pada sisi yang kontrak pada kenyataannya menempatkan sepeda sebagai roda ekonomi kehidupan sehari-hari. Salah satu kekuatan Bikenomics adalah caranya menurunkan ekonomi dari grafik makro ke kehidupan nyata. Blue menghadirkan kisah pekerja, ibu tunggal, mahasiswa, dan komunitas kelas pekerja yang menemukan ruang bernapas melalui sepeda. Dengan bersepeda, mereka bukan hanya menghemat uang, tetapi juga memperoleh waktu, kesehatan, dan kemandirian—tiga hal yang jarang dihitung dalam GDP. Elly Blue adalah seorang penulis, penerbit, dan aktivis mobilitas asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai suara terkemuka dalam gerakan keadilan transportasi dan ekonomi bersepeda. Fokus karyanya adalah pada aspek sosial, ekonomi, dan feminisme dari bersepeda sebagai alat untuk transformasi urban dan kesetaraan.
Blue menantang indikator ekonomi arus utama. Ia mempertanyakan mengapa kecelakaan lalu lintas, polusi, dan penyakit akibat gaya hidup justru “meningkatkan” PDB karena memicu konsumsi layanan medis dan asuransi. Dalam logika ini, sepeda terlihat tidak produktif—padahal justru mengurangi biaya sosial. Pemikiran ini beresonansi dengan kritik ekonomi feminis dan ekonomi perawatan (care economy), yang menekankan bahwa nilai sejati ekonomi terletak pada keberlanjutan hidup, bukan sekadar pertumbuhan angka. Dalam konteks ini, sepeda adalah teknologi yang mendukung ekonomi perawatan: ia memperkuat tubuh, komunitas, dan ruang publik.
Bagian penting lain buku ini membahas bagaimana investasi publik sering kali berat sebelah. Inilah wajah kota, infrastruktur, dan politik uang yang bekerja mengatur mobilitas di bawah panji kapitalisme. Blue membandingkan biaya pembangunan jalan tol dan parkir mobil dengan biaya jalur sepeda dan transportasi publik. Ia menunjukkan bahwa satu dolar yang diinvestasi-kan pada sepeda menghasilkan manfaat ekonomi dan kesehatan jauh lebih besar dibandingkan satu dolar untuk infrastruktur mobil.
Di sini Bikenomics bersinggungan dengan karya-karya seperti Street Fights in Copenhagen (Henderson & Gulsrud) dan Less Is More (Jason Hickel): krisis ekonomi dan krisis ekologi berasal dari logika pertumbuhan dan ekspansi yang sama. Blue menegaskan bahwa sepeda mendukung ekonomi lokal—toko kecil, bengkel, pasar—karena pesepeda berhenti, melihat, dan ber-interaksi, alih-alih melaju dan pergi.
Ia mengutip studi yang menunjukkan bahwa pelanggan bersepeda sering membelanjakan lebih sedikit per kunjungan, tetapi lebih sering—menghasilkan ekonomi yang lebih stabil dan merata. Ini mengingatkan pada gagasan E.F. Schumacher dalam Small Is Beautiful (1973): skala kecil bukan kelemahan, melainkan kekuatan.
Sepeda, Keadilan, dan Siapa yang Diuntungkan
Blue, yang pernah bekerja sebagai editor dan penulis untuk berbagai publikasi, sebelum akhirnya mendalami advokasi sepeda secara penuh, juga kritis terhadap narasi sepeda yang eksklusif. Ia menyoroti bagaimana kebijakan pro-sepeda kadang hanya menguntungkan kelas menengah kulit putih, sementara komunitas miskin dan minoritas tetap terpinggirkan. Bikenomics menekankan bahwa sepeda adalah isu keadilan sosial, bukan sekadar gaya hidup hijau.
Dalam semangat ini, Blue mengaitkan sepeda dengan hak atas kota (right to the city). Jalan bukan hanya koridor ekonomi, tetapi ruang hidup. Sepeda, karena murah dan mudah diakses, berpotensi menjadi alat demokratisasi ruang—jika kebijakan dibuat dengan kesadaran kelas dan ras. Perspektif ini sejalan dengan etika Islam tentang keadilan sosial dan penghindar-an israf (pemborosan). Dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa pemborosan adalah “saudara-saudara setan” (QS. Al-Isra: 27). Sepeda, dalam konteks ini, dapat dibaca sebagai praktik hidup qana’ah: cukup, seimbang, dan tidak berlebihan.
Bikenomics yang digagas Blue ini sebagai kritik pertumbuhan. Pada akhirnya, Bikenomics bukan hanya buku tentang sepeda, melainkan tentang membayangkan ekonomi pasca-pertumbuhan. Blue tidak menolak ekonomi, tetapi menolak ekonomi yang memerlukan konsumsi berlebihan dan ketergantungan energi tinggi agar tetap berjalan. Ia sejalan dengan pemikir degrowth seperti Giorgos Kallis dan Jason Hickel, meskipun ditulis dengan gaya populer dan membumi. Pesan utamanya jelas: ekonomi yang baik adalah ekonomi yang memungkinkan orang hidup layak dengan lebih sedikit uang, lebih sedikit stres, dan lebih banyak hubungan manusia.
Dalam dunia yang menghadapi krisis iklim, utang, dan ketimpangan, Bikenomics menawarkan visi yang radikal sekaligus sederhana: dua roda bisa membuka jalan menuju ekonomi yang lebih adil, sehat, dan masuk akal.
Sepeda di Dunia yang Memburuk
Pengantar edisi kedua Bikenomics ditulis Elly Blue dengan nada yang lebih gelap sekaligus lebih jujur dibanding edisi pertama. Dunia, ia akui, tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Krisis iklim semakin nyata, ketimpangan makin menganga, dan kota-kota—alih-alih menjadi ruang hidup—kian berubah menjadi mesin logistik bagi modal dan kendaraan. Namun justru dalam situasi inilah sepeda kembali muncul, bukan sebagai nostalgia atau gaya hidup hijau yang manis, melainkan sebagai respon rasional terhadap dunia yang tidak rasional.
Blue merefleksikan bahwa banyak argumen pro-sepeda kini terdengar “radikal” bukan karena terlalu ekstrem, tetapi karena sistem ekonomi telah menjadi begitu ekstrem. Ia menulis seolah-olah sepeda adalah cermin kecil yang memperlihatkan kebengkokan besar ekonomi modern: mengapa solusi yang lebih murah, lebih sehat, dan lebih adil justru dianggap tidak realistis? Pengantar ini memberi konteks bahwa Bikenomics bukan buku optimisme kosong, melain-kan manual bertahan hidup di dalam sistem yang gagal.
Nada ini mengingatkan pada ungkapan Walter Benjamin bahwa “keadaan darurat bukanlah pengecualian, melainkan aturan.” Sepeda, dalam pengantar ini, adalah praktik sehari-hari yang diam-diam membangkang terhadap keadaan darurat permanen kapitalisme fosil.
Dalam pengantar utama, Blue membawa pembaca ke pengalaman konkret: orang-orang yang hidup “benar secara ekonomi” menurut logika pasar—bekerja keras, memiliki mobil, membayar asuransi—namun tetap terjebak dalam stres, utang, dan ketidakamanan. Ia mempertanyakan: jika ekonomi diciptakan untuk melayani manusia, mengapa begitu banyak manusia merasa gagal di dalamnya?
Sepeda masuk sebagai pengalaman tubuh yang langsung. Ketika seseorang bersepeda, ia tidak hanya bergerak lebih pelan; ia merasakan kota. Jarak, waktu, dan tenaga menjadi nyata kem-bali. Blue menekankan bahwa ekonomi modern bekerja justru dengan meniadakan peng-alaman ini: semakin cepat, semakin jauh, semakin tidak terasa. Dalam pengantar ini, ia mulai membongkar asumsi besar bahwa “efisiensi” selalu berarti kebaikan.
Di sinilah Bikenomics mulai memperlihatkan posisinya sebagai kritik ideologis: sepeda bukan sekadar alat transportasi, tetapi alat epistemologis—cara lain untuk mengetahui dunia dan menilai apa yang masuk akal.
Pada Bab Chapter 1: The Free Rider Myth Blue membedah salah satu mitos paling keras kepala dalam politik transportasi: bahwa pesepeda adalah free riders, penumpang gelap yang tidak membayar pajak jalan tetapi menikmatinya. Blue memperlakukan mitos ini seperti dongeng moral yang diciptakan untuk membenarkan ketidakadilan. Dengan gaya bertutur yang tajam namun mudah diikuti, ia menunjukkan bahwa hampir semua orang membayar jalan—melalui pajak umum, pajak penjualan, pajak properti—termasuk mereka yang tidak memiliki mobil. Sebaliknya, biaya sebenarnya mobil jauh lebih besar daripada yang ditanggung pengemudinya: subsidi bahan bakar, lahan parkir gratis, biaya kesehatan, kecelakaan, polusi, hingga krisis iklim.
Narasi bab ini mengubah sudut pandang: justru pesepedalah yang mensubsidi sistem, karena mereka menggunakan infrastruktur paling sedikit sambil memberikan manfaat kesehatan dan lingkungan terbesar. Mitos free riderdipertahankan bukan karena benar, tetapi karena berguna secara politik—ia mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih berbahaya: siapa sebenar-nya yang paling mahal bagi masyarakat?
Bab ini terasa sangat relevan untuk konteks Indonesia, di mana pengguna sepeda atau pejalan kaki sering dianggap “mengganggu lalu lintas,” padahal merekalah yang paling sedikit menuntut ruang dan subsidi.
Blue membawa kita ke jantung persoalan: jalan bukanlah ruang netral, Whose Streets? — Jalan Milik Siapa? Pada Bab ini Ia menytakan bahwa ‘jalan’ adalah arena politik. Sejarah jalan modern, kata Blue, adalah sejarah perebutan ruang antara tubuh manusia dan mesin. Ia mene-lusuri bagaimana jalan kota yang dulu merupakan ruang sosial—tempat anak bermain, peda-gang berjualan, warga berinteraksi—perlahan direbut oleh mobil melalui hukum, desain, dan kekerasan simbolik. Konsep “jaywalking,” misalnya, diciptakan untuk menyalahkan pejalan kaki atas kekacauan yang disebabkan kendaraan bermotor.
Jika di awal buku pertanyaan “Whose Streets?” diajukan sebagai kritik, di bab ini pertanyaan itu kembali dengan nada lebih tajam dan politis. Blue menunjukkan bahwa jalan bukanlah ruang netral; ia selalu mencerminkan relasi kuasa. Siapa yang diprioritaskan di jalan menunjukkan siapa yang dihitung dalam kebijakan publik. Bab ini menelusuri bagaimana sejarah perencana-an kota secara sistematis meminggirkan pejalan kaki dan pesepeda demi mobil—dan bagai-mana proses itu sering dibungkus dengan bahasa teknokratis tentang efisiensi dan pertumbuh-an. Blue mengurai bagaimana “kepentingan umum” sering kali berarti kepentingan industri otomotif, pengembang, dan kelas menengah-atas.
Namun, nada bab ini bukan putus asa. Ia menyoroti momen-momen perlawanan: komunitas yang merebut kembali jalan melalui open streets, jalur sepeda sementara, dan kebijakan berbasis warga. Pertanyaan “whose streets?” berubah menjadi undangan: jalan macam apa yang ingin kita wariskan? Di kota-kota seperti Jakarta, di mana jalan sering terasa milik kendaraan bermotor semata, bab ini terdengar seperti seruan untuk imajinasi politik baru.
Dengan gaya naratif yang hidup, Blue menunjukkan bahwa pertanyaan “siapa berhak atas jalan” selalu dijawab oleh kekuasaan. Ketika mobil menjadi simbol kemajuan, jalan pun dide-finisikan ulang untuk melayani kecepatan dan volume, bukan kehidupan. Pesepeda, dalam konteks ini, adalah tubuh yang “salah tempat”—tidak cukup cepat untuk mobil, terlalu teknologis untuk pejalan kaki.
Bab ini beresonansi kuat dengan wacana right to the city (Henri Lefebvre): hak atas kota bukan hak untuk mengonsumsi kota, tetapi hak untuk menggunakannya secara manusiawi. Sepeda muncul sebagai alat yang mengembalikan jalan kepada skala manusia.
Pada bagian lain Blue menggunakan metafora yang kuat soal Jalan: gelembung aspal. Seperti gelembung finansial, infrastruktur mobil dibangun atas janji palsu—bahwa lebih banyak jalan akan mengurangi kemacetan, bahwa pertumbuhan lalu lintas adalah tanda kemajuan, bahwa biaya bisa ditekan dengan ekspansi.
Namun kenyataannya, setiap jalan baru justru menciptakan lalu lintas baru. Kota-kota terjebak dalam spiral mahal: membangun, memperbaiki, dan memperluas infrastruktur yang semakin tidak terjangkau. Blue menulis dengan nada hampir tragis: kita tahu sistem ini tidak berke-lanjutan, tetapi terus membayarnya karena tidak bisa membayangkan alternatif. Sepeda, dalam bab ini, berfungsi sebagai “jarum” kecil yang mengancam gelembung besar. Ia tidak membutuh-kan aspal tebal, jembatan raksasa, atau utang jangka panjang. Ia bekerja dengan logika yang berlawanan: cukup, ringan, dan adaptif. Itulah sebabnya, implisit dalam argumen Blue, sepeda sering dipinggirkan—bukan karena tidak efektif, tetapi karena terlalu efektif untuk sistem yang bergantung pada pemborosan.
Setelah membongkar mitos, kepemilikan jalan, dan gelembung infrastruktur, Bikenomics perlahan mengajak kita membayangkan ekonomi yang tidak bergantung pada kecepatan, utang, dan konsumsi berlebih. Nada naratif berubah: dari membongkar kebohongan menjadi meraba jalan keluar. Sepeda tidak lagi hanya kritik, tetapi prinsip pengorganisasian ekonomi—tentang bagaimana kita bergerak, bekerja, membelanjakan uang, dan membangun kota.
Chapter 12: Human Infrastructure — Infrastruktur yang Tak Terlihat tapi Menopang Segalanya.
Di sinilah Bikenomics mencapai kedalaman etisnya. Blue memperkenalkan gagasan human infrastructure: jaringan hubungan, kepercayaan, kebiasaan, dan solidaritas yang memungkinkan kota berfungsi. Jalur sepeda bisa dibangun dalam semalam, tetapi budaya saling menghormati di jalan membutuhkan waktu—dan itulah infrastruktur yang paling rapuh sekaligus paling penting.
Blue menulis bahwa kota ramah sepeda tidak tercipta hanya dari beton dan cat, melainkan dari praktik sehari-hari: orang tua mengantar anak bersepeda, tetangga saling mengenal di jalan, pengendara melambat karena melihat wajah, bukan bumper. Sepeda memanusiakan kota karena ia memaksa perjumpaan—dan dari perjumpaan itu lahir rasa tanggung jawab bersama.
Bab ini terasa seperti kritik halus terhadap solusi teknokratik krisis iklim dan perkotaan. Tanpa infrastruktur manusia, teknologi hijau sekalipun akan gagal. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini sangat relevan dengan budaya kampung, gotong royong, dan ruang komunal yang tergerus oleh urbanisasi berbasis mobil. Sepeda, di sini, bukan sekadar alat transportasi, tetapi jembatan antara modernitas dan kebersamaan lama.
Learning to Share: Belajar Berbagi sebagai Tindakan Politik
Pada bagian Learning to Share, Elly Blue menggeser fokus dari infrastruktur dan angka menuju sesuatu yang lebih rapuh namun fundamental: etos hidup bersama. Berbagi jalan, berbagi ruang, berbagi waktu—semuanya terdengar sederhana, tetapi dalam kota modern justru menjadi tindakan politis. Kota kapitalis dilatih untuk kompetisi: siapa paling cepat, paling dulu, paling kuat. Jalan raya adalah sekolahnya.
Blue menulis tentang bagaimana berbagi bukanlah sifat alamiah dalam sistem yang dibangun atas kelangkaan buatan. Ketika ruang jalan dipersempit oleh mobil dan parkir, berbagi menjadi konflik. Pesepeda lalu dianggap “tidak tahu diri,” padahal merekalah yang mempraktikkan bentuk berbagi paling radikal: menggunakan ruang sekecil mungkin sambil tetap bergerak.
Narasi ini memperlihatkan bahwa konflik lalu lintas bukan soal perilaku individu, melain-kan arsitektur moral kota. Kota yang adil bukan kota tanpa konflik, tetapi kota yang tidak memaksa warganya saling bermusuhan demi bergerak dari satu titik ke titik lain. Sepeda, di sini, menjadi latihan harian dalam empati ruang: kita melambat, saling membaca, saling memberi jalan—bukan karena moral luhur, tetapi karena tubuh kita rapuh. Learning to Share — jalan raya sebagai ruang moral bersama.
Dalam Learning to Share, Elly Blue membawa kita ke jantung konflik paling sehari-hari namun paling ideologis dalam kehidupan urban: siapa yang berhak atas jalan? Pertanyaan ini tampak teknis—tentang marka, lajur, dan rambu—tetapi sesungguhnya menyimpan pertarungan nilai yang jauh lebih dalam tentang kepemilikan ruang publik, hierarki sosial, dan definisi kemajuan.
Blue menunjukkan bahwa jalan raya modern dibangun bukan sebagai ruang bersama, melain-kan sebagai ruang yang diprivatisasi secara implisit oleh kendaraan bermotor. Mobil, dengan ukuran, kecepatan, dan infrastrukturnya, telah lama diperlakukan sebagai “pengguna utama,” sementara pejalan kaki dan pesepeda didorong ke pinggiran—secara fisik maupun simbolik. Dalam konteks ini, seruan untuk “berbagi jalan” sering kali terdengar timpang, karena yang diminta berbagi justru pihak yang paling rentan.
Melalui kisah-kisah kebijakan kota, konflik lalu lintas, dan pengalaman personal, Blue menegas-kan bahwa sharingbukanlah sekadar soal toleransi individual, melainkan soal struktur kekuasa-an. Jalan tidak netral; ia mencerminkan prioritas politik. Ketika kota memprioritaskan kecepat-an mobil, ia secara implisit memprioritaskan mereka yang mampu membeli dan mengoperasi-kannya—sering kali kelas menengah ke atas—sementara yang lain harus “beradaptasi.”
Sepeda, dalam narasi Blue, memaksa kita belajar ulang tentang berbagi karena ia mengganggu asumsi dominan. Sepeda tidak bisa bersaing dengan mobil dalam kecepatan atau kekuatan, tetapi justru karena itu ia mengungkap ketidakadilan sistemik. Ketika pesepeda menuntut ruang, yang mereka minta bukan privilese, melainkan kesetaraan eksistensial di ruang publik.
Blue juga menekankan bahwa budaya berbagi tidak akan lahir dari kampanye moral semata. Ia membutuhkan desain kota yang adil: jalur yang aman, persimpangan yang manusiawi, dan aturan yang melindungi yang paling lemah. Dengan kata lain, learning to share adalah proses institusional sekaligus kultural—belajar hidup bersama dalam keterbatasan ruang dan per-bedaan kecepatan.
Dalam konteks yang lebih luas, bagian ini menggemakan gagasan filsafat politik klasik tentang commons. Jalan raya adalah commons modern, dan sepeda menjadi pengingat bahwa commons hanya bertahan jika kekuasaan tidak dimonopoli oleh yang paling kuat. Berbagi, di sini, bukan kebaikan hati, melainkan keadilan yang dilembagakan.
Bab 6: Slowing Things Down — Melawan Diktator Kecepatan barangkali bisa disebut sebagai jantung filosofis Bikenomics. Blue menyerang asumsi paling sakral modernitas: bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Ia menunjukkan bagaimana kecepatan—yang dijual sebagai efisiensi—sebenarnya menciptakan biaya tersembunyi: stres, kecelakaan, polusi, keterasingan, dan waktu yang hilang untuk pemulihan.
Dengan bahasa yang membumi, Blue mengajak pembaca menghitung ulang waktu. Mobil memang lebih cepat di atas kertas, tetapi waktu parkir, kemacetan, kerja tambahan untuk membayar cicilan, dan biaya kesehatan sering membuat “kecepatan” itu ilusi. Sepeda, sebalik-nya, mungkin lebih lambat secara absolut, tetapi lebih jujur terhadap waktu hidup. Bab ini terasa seperti dialog tak langsung dengan Ivan Illich, yang menulis bahwa alat yang baik adalah alat yang tidak mencuri waktu hidup penggunanya. Sepeda memperlambat kota bukan untuk membuatnya tidak produktif, melainkan untuk membuatnya masuk akal. Dalam konteks kota-kota Indonesia—Jakarta, Bandung, Surabaya—gagasan ini sangat subversif, karena kemacetan kronis justru menunjukkan bahwa obsesi pada kecepatan telah gagal total.
Jika Learning to Share berbicara tentang ruang, maka Slowing Things Down berbicara tentang waktu. Elly Blue dengan tajam menunjukkan bahwa salah satu ilusi terbesar modernitas adalah anggapan bahwa kecepatan selalu identik dengan kemajuan. Kota-kota modern dibangun dengan obsesi pada percepatan: perjalanan lebih cepat, distribusi lebih efisien, produktivitas lebih tinggi. Namun Blue bertanya dengan nada tenang namun menggugah: untuk siapa semua ini?
Dalam bagian ini, sepeda tampil sebagai teknologi yang “tidak patuh” pada logika percepatan. Ia lebih cepat dari berjalan kaki, tetapi jauh lebih lambat dari mobil. Posisi antara inilah yang membuat sepeda subversif. Ia memaksa kota—dan penggunanya—untuk kembali ke skala manusia, di mana jarak terasa, tubuh hadir, dan lingkungan tidak sekadar latar belakang yang dilalui.
Blue menguraikan bagaimana kecepatan tinggi membawa biaya tersembunyi: kecelakaan, polusi, stres, dan fragmentasi sosial. Kota yang bergerak terlalu cepat kehilangan kemampuan-nya untuk dilihat, dirasakan, dan dirawat. Dalam kota semacam itu, orang lewat tanpa benar-benar hadir; ruang menjadi koridor, bukan tempat hidup. Dengan memperlambat, sepeda membuka kemungkinan lain. Perjalanan menjadi pengalaman, bukan sekadar transisi. Interaksi sosial—sapaan, tatapan, bahkan konflik kecil—kembali mungkin. Waktu tidak lagi sepenuhnya dikolonisasi oleh logika efisiensi ekonomi, tetapi memberi ruang bagi makna.
Blue tidak mengidealkan kelambatan sebagai nostalgia romantis. Ia sadar bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak merata: mereka yang bekerja keras sering kali justru dipaksa bergerak cepat. Karena itu, slowing things down baginya adalah proyek politik, bukan sekadar pilihan gaya hidup. Kota harus dirancang sedemikian rupa sehingga orang tidak dipaksa cepat untuk bertahan hidup. Di sinilah sepeda menjadi alat pembebasan temporal. Dengan infrastruktur yang tepat, sepeda memungkinkan perjalanan yang cukup cepat tanpa biaya sosial dan ekologis dari kecepatan ekstrem. Ia menawarkan ritme yang selaras dengan tubuh manusia dan siklus kota.
Jika ada satu simbol ketimpangan paling kasat mata dalam kota modern, Blue menunjukkannya di sini: parkir. Bab ini membongkar parkir bukan sebagai isu teknis, tetapi sebagai keputusan politik yang mahal dan sarat kepentingan. Blue menulis tentang betapa banyak ruang publik dikorbankan demi menyimpan kendaraan yang tidak bergerak. Parkir gratis, ia jelaskan, adalah subsidi tersembunyi terbesar bagi mobil—lebih besar dari yang disadari warga. Toko kecil, ruang hijau, jalur sepeda, bahkan trotoar sering dikalahkan oleh “kebutuhan” parkir, seolah-olah mobil memiliki hak istimewa untuk beristirahat di ruang bersama.
Narasi bab tentang Parkir ini memperlihatkan ironi besar: sepeda, yang nyaris tidak membutuh-kan ruang parkir, sering dianggap merepotkan; sementara mobil, yang memakan ruang luar biasa, diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Dengan gaya bertutur yang tajam namun tidak menggurui, Blue menunjukkan bahwa konflik parkir adalah konflik tentang siapa yang dianggap penting di kota.
Dalam bab Redefining Safety, Blue mengajak pembaca mempertanyakan definisi keselamatan yang selama ini diterima begitu saja. Keselamatan, dalam logika mobil, berarti melindungi pengemudi dari cedera—bahkan jika itu berarti membahayakan orang lain. Helm, sabuk pengaman, dan baja tebal menjadi solusi individual untuk masalah sistemik. Blue menulis bahwa kota yang benar-benar aman bukan kota dengan kendaraan yang “lebih aman,” tetapi kota dengan lebih sedikit kekerasan struktural. Ia membedakan antara perceived safety dan actual safety: mobil mungkin terasa aman dari dalam, tetapi secara statistik menciptakan lebih banyak korban. Sepeda, meski terasa rentan, justru mendorong desain kota yang melindungi semua orang.
Bab ini terasa sebagai kritik moral: keselamatan sejati tidak bisa dicapai dengan memperkeras cangkang individu, tetapi dengan melembutkan sistem. Dalam konteks ini, sepeda bukan simbol risiko, melainkan indikator kesehatan kota. Jika bersepeda terasa berbahaya, yang sakit bukan pesepedanya—melainkan kotanya.
Bab yang cukup menarik adalah pembahasa tentang manuver seperda di Jalan Utama (Bab 9: Bikes on Main Street — Ekonomi yang Terlihat dari Sadel). Di bab ini, Bikenomics kembali ke ekonomi paling konkret: toko, jalan utama, dan kehidupan sehari-hari. Blue menuturkan kisah-kisah bagaimana pesepeda justru lebih menghidupkan ekonomi lokal dibanding mobil. Mereka berhenti lebih sering, berbelanja dalam jumlah wajar, dan berinteraksi langsung dengan ruang sekitar.
Main Street versi mobil, kata Blue, adalah koridor cepat—tempat orang lewat, bukan tinggal. Main Street versi sepeda adalah ruang pertemuan. Ia menunjukkan bagaimana jalur sepeda dan trotoar lebar bukan hanya kebijakan transportasi, tetapi kebijakan ekonomi kerakyatan. Bab ini terasa sangat relevan untuk kota-kota Indonesia dengan warung, pasar, dan usaha kecil. Ketika jalan diperlebar untuk mobil, usaha kecil sering mati. Ketika jalan dipersempit dan diperlambat, kehidupan justru muncul. Sepeda menjadi mediator antara ekonomi dan sosial—alat sederhana yang menjaga skala manusia tetap dominan.
Sepeda adalah alat transformasi sosial bagi kehidupan yang cenderung menuju pada a-sosial. Blue membahas soal ini (Bab 10). Bikenomics ke cakrawala yang lebih luas: bagaimana sepeda terhubung dengan keadilan sosial, akses kerja, kesehatan publik, dan krisis iklim. Setelah membahas ruang, waktu, dan ekonomi lokal, buku ini mulai memperlihatkan bahwa sepeda bukan solusi tunggal, tetapi simpul dari banyak solusi kecil. Nada narasinya menegas-kan satu hal: sepeda tidak menyelamatkan dunia sendirian. Tetapi tanpa sepeda—tanpa cara hidup yang ringan, lambat, dan cukup—tidak ada transformasi ekonomi yang benar-benar berpihak pada kehidupan.
Putting Bikes to Work — Ketika Sepeda Menjadi Infrastruktur Ekonomi
Pada bagian Putting Bikes to Work, Elly Blue membawa sepeda keluar dari wilayah hobi, gaya hidup, atau aktivisme simbolik, dan menempatkannya tepat di jantung ekonomi nyata. Di sini sepeda bekerja—mengantar barang, menghubungkan pekerja dengan pekerjaan, membuka akses bagi mereka yang tak terlayani oleh sistem transportasi mahal.
Blue menulis tentang kurir sepeda, pekerja layanan, perawat rumahan, dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan sepeda bukan karena idealisme, tetapi karena ia masuk akal secara ekonomi. Sepeda mengurangi biaya awal, memperluas jangkauan kerja, dan membebaskan pekerja dari ketergantungan pada bahan bakar dan cicilan kendaraan. Dalam dunia kerja yang makin tidak stabil, sepeda menjadi alat resiliensi—cara bertahan hidup yang ringan dan fleksibel. Narasi ini diam-diam menantang ide lama bahwa “kemajuan” harus selalu padat modal. Sepeda menunjukkan bahwa produktivitas tidak selalu berarti percepatan dan mekani-sasi besar, melainkan kecocokan alat dengan kebutuhan manusia. Dalam konteks kota-kota Indonesia—ojek, kurir, pedagang keliling—argumen ini terasa sangat dekat: sepeda dan kendaraan ringan sering kali menopang ekonomi informal yang justru paling vital.
Bagi Bikenomics sepeda menjadi alat hidup, bukan sekadar alat jalan. Dalam Putting Bikes to Work, Elly Blue melakukan pergeseran yang menentukan: dari perdebatan tentang ruang jalan dan kebijakan transportasi menuju pertanyaan paling radikal—apa arti kerja, dan siapa yang diuntungkan oleh sistem mobilitas kita?
Pengalaman Blue bersepeda sehari-hari di kota serta keterlibatan dalam komunitas sepeda lokal membentuk perspektif praktis dan inklusif dalam tulisannya. Karena itu dalam Bikenomics Blue menantang asumsi yang sangat mengakar dalam kapitalisme modern bahwa kerja yang “serius” harus bergantung pada mesin besar, bahan bakar mahal, dan infrastruktur berat. Ia menunjukkan bahwa di balik mitos produktivitas modern, sepeda telah lama bekerja—diam-diam, efisien, dan sering kali tanpa pengakuan. Bab ini membuka mata pembaca pada kenyata-an bahwa sepeda bukan hanya sarana menuju tempat kerja, tetapi bagian dari kerja itu sendiri. Dari kurir, pengantar makanan, tukang reparasi, pekerja kesehatan komunitas, hingga peng-usaha kecil, sepeda berfungsi sebagai means of production—alat yang memungkinkan orang bertahan hidup, membangun usaha, dan mengakses penghidupan tanpa harus berutang pada sistem otomotif.
Blue menyoroti bagaimana banyak pekerjaan berbasis sepeda berada di wilayah yang oleh ekonomi arus utama sering diremehkan atau disembunyikan: pekerjaan informal, kerja perawatan, kerja komunitas, dan kerja kreatif. Kurir sepeda di kota besar, misalnya, sering dipandang sebagai simbol gaya hidup urban, padahal mereka adalah tulang punggung logistik kota yang cepat dan fleksibel.
Namun Blue tidak meromantisasi. Ia justru mengungkap paradoks: sepeda memungkinkan pekerjaan yang lebih mandiri dan murah, tetapi karena itu pula sering dimanfaatkan oleh sistem ekonomi yang menolak memberikan perlindungan sosial. Dalam ekonomi gig, sepeda menjadi alat kerja yang “terlalu efisien” sehingga risiko, biaya, dan kelelahan sepenuhnya ditanggung oleh tubuh pekerja.
Di sinilah Bikenomics menjadi tajam secara politik. Blue menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada sepeda, melainkan pada struktur kerja yang mengeksploitasi fleksibilitas. Sepeda, menurutnya, justru membuka kemungkinan untuk membayangkan ulang kerja—lebih lokal, lebih manusiawi, dan lebih terkendali oleh pekerja itu sendiri.
Salah satu gagasan paling penting dalam Putting Bikes to Work adalah redefinisi produktivitas. Produktivitas yang berbeda: tubuh sebagai ukuran. Dalam sistem mobil, produktivitas diukur dari kecepatan, volume, dan jarak. Dalam sistem sepeda, produktivitas diukur dari kesesuaian antara energi yang dikeluarkan dan nilai yang dihasilkan.
Blue menggambarkan bagaimana sepeda memungkinkan kerja yang:
- tidak memerlukan investasi modal besar,
- tidak menciptakan ketergantungan pada bahan bakar fosil,
- dan tidak mengorbankan kesehatan pekerja demi efisiensi semu.
Sepeda memaksa kita mengakui keterbatasan tubuh manusia—dan justru dari keterbatasan itu lahir kebijaksanaan. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan sepeda cenderung lebih lokal, lebih terhubung dengan komunitas, dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata, bukan permintaan pasar abstrak.
Dalam kerangka ini, sepeda menjadi penyeimbang etis terhadap logika kapitalisme yang selalu mendorong “lebih cepat, lebih jauh, lebih banyak”.
Blue juga mengangkat kisah-kisah usaha kecil yang menggunakan sepeda sebagai tulang punggung operasional: toko roti yang mengantar pesanan dengan kargo bike, tukang ledeng yang melayani lingkungan sekitar tanpa truk, hingga pekerja seni yang memindahkan peralatan dengan sepeda. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa sepeda mendukung ekonomi skala manusia—ekonomi yang tidak perlu tumbuh tanpa batas untuk tetap layak. Dengan biaya operasional rendah, usaha berbasis sepeda bisa bertahan tanpa harus mengejar ekspansi agresif, pinjaman besar, atau efisiensi yang merusak relasi sosial.
Di sini Putting Bikes to Work bersinggungan langsung dengan gagasan post-growth dan degrowth: pekerjaan tidak harus terus membesar agar bermakna. Justru dengan tetap kecil, dekat, dan terjangkau, kerja menjadi lebih berkelanjutan—secara ekonomi, ekologis, dan sosial.
Dalam hal dimensi keadilan, Blue bertanya: Siapa yang Bisa Bekerja? Blue menekankan bahwa sepeda membuka akses kerja bagi kelompok yang sering dikecualikan oleh sistem mobil: mereka yang tidak mampu membeli mobil, tidak bisa mengemudi, atau hidup di kota padat. Sepeda menurunkan ambang masuk ke dunia kerja. Namun ia juga mengingatkan bahwa akses ini hanya adil jika didukung oleh kebijakan yang melindungi pekerja sepeda—upah layak, keselamatan jalan, dan pengakuan hukum. Tanpa itu, sepeda berisiko menjadi simbol “fleksibilitas” yang menutupi ketimpangan struktural.
Dengan demikian, Putting Bikes to Work bukan hanya tentang transportasi, tetapi tentang hak atas kerja yang bermartabat.
Blue membayangkan sebuah masa depan yang berbeda— Masa Depan yang Lebih Kecil, Lebih Dekat, Lebih Cukup. Inilah catatan masa depan yang dipaparkan pada Bab 13: Rethinking the Future. Bikenomics membayangkan masa depan tanpa obsesi kecepatan.
Bab penutup ini bukan utopia besar, melainkan ajakan untuk berpikir ulang tentang apa yang kita sebut masa depan. Blue tidak menawarkan kota futuristik penuh kendaraan otonom, tetapi kota yang lebih dekat secara jarak dan relasi. Masa depan versi Bikenomics bukan tentang teknologi yang lebih canggih, melainkan tentang kehidupan yang lebih mungkin dijalani. Ia menulis bahwa bersepeda mengajarkan satu hal penting: kita tidak perlu pergi sejauh atau secepat yang kita kira untuk hidup dengan baik. Kota yang layak huni adalah kota di mana kebutuhan dasar dapat dijangkau tanpa mengorbankan kesehatan, waktu, dan planet.
Nada akhir buku ini bersahaja namun tegas. Sepeda tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi ia membuka jalan menuju ekonomi yang lebih adil, kota yang lebih manusiawi, dan masa depan yang tidak dibangun di atas utang ekologis. Dalam bahasa degrowth, sepeda adalah praktik “cukup” yang bergerak—contoh kecil dari dunia yang tidak mengejar lebih, tetapi merawat yang ada.
Pada bab terakhir Bikenomics, Elly Blue tidak menutup bukunya dengan statistik baru atau rencana kebijakan teknis, melainkan dengan pertanyaan mendasar tentang imajinasi masa depan. Ia mengajak pembaca berhenti sejenak dari debat “berapa kilometer jalur sepeda” atau “berapa persen emisi berkurang”, dan masuk ke wilayah yang lebih dalam: masa depan seperti apa yang sebenarnya kita inginkan, dan mengapa?
Blue menunjukkan bahwa selama puluhan tahun, masa depan selalu dibayangkan sebagai sesuatu yang lebih besar, lebih cepat, lebih jauh. Kota masa depan dipenuhi jalan layang, kendaraan otonom, sistem logistik hiper-cepat, dan efisiensi tanpa henti. Dalam imajinasi ini, mobil—atau teknologi yang menggantikannya—tetap menjadi pusat. Sepeda, jika hadir, sering kali diposisikan sebagai pelengkap estetis, bukan fondasi.
Bab ini membalik logika tersebut. Blue menulis bahwa bersepeda mengajarkan pelajaran yang radikal tetapi sederhana: kita tidak perlu bergerak sejauh dan secepat itu untuk hidup dengan baik. Banyak perjalanan harian sebenarnya pendek. Banyak kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara lokal. Banyak “keharusan” mobil ternyata adalah hasil desain kota, bukan kebutuhan manusia.
Dengan nada reflektif, Blue memperlihatkan bahwa krisis ekonomi, krisis iklim, dan krisis kesehatan mental modern berasal dari sumber yang sama: obsesi pada pertumbuhan dan percepatan. Kita membangun sistem transportasi yang membuat jarak semakin jauh, lalu menjual solusi untuk menaklukkannya dengan kecepatan lebih tinggi. Dalam siklus ini, sepeda tampak “tidak cocok” justru karena ia jujur: ia memperlihatkan jarak yang sesungguhnya, waktu yang nyata, dan tubuh manusia yang terbatas.
Blue lalu menggeser fokus dari teknologi ke kedekatan. Masa depan yang ia bayangkan bukanlah kota futuristik dengan kendaraan tanpa pengemudi, melainkan kota di mana sekolah, pasar, taman, tempat kerja, dan ruang ibadah dapat dijangkau tanpa mengorbankan waktu hidup. Sepeda, di sini, bukan hanya alat transportasi, tetapi indikator desain kota yang sehat.
Jika sebuah kota nyaman untuk dilalui dengan sepeda, maka kota itu hampir pasti:
- tidak terlalu tersebar,
- tidak terlalu bising,
- tidak terlalu mematikan bagi tubuh manusia,
- dan tidak terlalu boros energi.
Dengan kata lain, sepeda menjadi semacam alat ukur moral bagi perencanaan kota. Ia menguji apakah sebuah kota dibangun untuk manusia atau untuk mesin.
Dalam konteks ini, Blue secara implisit mengkritik visi “green growth” yang percaya bahwa krisis iklim dapat diselesaikan tanpa mengubah struktur ekonomi dan ruang hidup. Mobil listrik, menurut logika Bikenomics, hanyalah mobil lama dengan baterai baru jika kota tetap dirancang untuk kecepatan, jarak jauh, dan konsumsi tinggi. Sepeda menuntut perubahan yang lebih radikal: perubahan skala hidup itu sendiri.
Maka Rethinking the Future adalah sebagai etika, bukan sekadar kebijakan. Yang paling kuat dari bab ini adalah pergeseran dari kebijakan ke etika hidup. Blue menulis bahwa memilih sepeda—baik sebagai individu maupun masyarakat—adalah memilih masa depan yang berbeda secara moral. Itu berarti menerima batas, menerima ketergantungan satu sama lain, dan menerima bahwa kenyamanan absolut tidak selalu sejalan dengan keadilan.
Sepeda membuat kita rentan di jalan, tetapi justru dari kerentanan itu lahir empati. Kita melihat wajah orang lain, mendengar suara kota, mencium udara—baik yang bersih maupun yang tercemar. Masa depan yang dibayangkan Blue adalah masa depan yang tidak menyembunyikan konsekuensi hidup, tetapi menghadapinya bersama. Di titik ini, Bikenomics bersinggungan dengan pemikiran degrowth dan etika ekologis: masa depan tidak diukur dari PDB atau kecepatan, melainkan dari kemampuan hidup layak tanpa merusak yang lain—manusia lain, generasi mendatang, dan makhluk non-manusia.
Catatan Akhir: Ruang dan Waktu yang Direbut Kembali
Dalam konteks Indonesia, bagian ini terasa sangat relevan. Jutaan pekerja informal—kurir, pedagang keliling, tukang servis, pengantar air galon—sudah lama “putting bikes to work” tanpa istilah akademik. Sepeda motor memang lebih dominan, tetapi sepeda tetap hidup di celah-celah ekonomi rakyat. Blue memberi kita bahasa untuk melihat ulang praktik ini bukan sebagai keterbelakangan, melainkan sebagai potensi masa depan: kerja lokal, rendah karbon, dan berbasis komunitas. Tantangannya adalah bagaimana melindungi dan memuliakan kerja ini, bukan menggantinya dengan sistem yang lebih mahal dan rapuh.
Putting Bikes to Work adalah pernyataan paling kuat dalam Bikenomics: sepeda bukan sekadar alat transportasi, melainkan alat pembebasan ekonomi—jika kita berani mengubah struktur yang mengelilinginya. Elly Blue mengajak kita membayangkan masa depan di mana kerja tidak diukur dari seberapa cepat kita bergerak, tetapi dari seberapa baik kita hidup. Dalam dunia yang kelelahan oleh percepatan, sepeda menawarkan kerja yang berakar pada tubuh, tempat, dan relasi.
Meski buku ini berangkat dari konteks Amerika Utara, bab Rethinking the Future sangat bergema di negara seperti Indonesia. Kota-kota kita—Jakarta, Bandung, Surabaya—sedang berada di persimpangan yang sama: apakah akan terus meniru model kota berbasis mobil, atau berani membayangkan masa depan yang lebih lokal, lebih pelan, dan lebih manusiawi?
Dalam banyak kampung kota Indonesia, masa depan versi Blue sebenarnya sudah pernah ada: jarak dekat, interaksi sosial kuat, mobilitas berbasis tubuh, dan ekonomi informal yang fleksibel. Ironisnya, justru modernisasi berbasis mobil yang menghancurkan tatanan itu. Sepeda, dalam konteks ini, bukan nostalgia, tetapi alat rekonstruksi masa depan yang hilang.
Bab Rethinking the Future menutup Bikenomics dengan pesan yang tenang tetapi subversif: masa depan tidak perlu dikejar, tetapi dirawat. Sepeda mengajarkan bahwa bergerak lebih pelan bukan berarti mundur; sering kali itu berarti melihat lebih jelas. Elly Blue tidak menjanjikan utopia. Ia menawarkan sesuatu yang lebih jujur: masa depan yang mungkin dicapai jika kita berani menurunkan ambisi palsu dan menaikkan kualitas hidup nyata. Dalam dunia yang terus berkata “lebih”, sepeda—dan bab ini—berani berkata: cukup.
Melalui bagian-bagian akhir ini, Bikenomics menegaskan diri bukan sekadar buku tentang sepeda, melainkan manifesto ekonomi sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari pilihan kecil yang konsisten. Sepeda, dalam buku ini, adalah alat kerja, medium politik, infrastruktur sosial, dan latihan etis.
Jika digabungkan, Learning to Share dan Slowing Things Down membentuk inti etis Bikenomics. Yang satu menyoal ruang bersama, yang lain menyoal waktu bersama. Sepeda berada di persimpangan keduanya—sebuah teknologi sederhana yang menantang dominasi, memperlambat ritme, dan membuka kembali kemungkinan hidup bersama yang lebih adil.
Dalam dunia yang dikuasai oleh kecepatan dan kepemilikan, sepeda mengajarkan dua pelajaran radikal: bahwa ruang harus dibagi, dan bahwa tidak semua hal harus dipercepat. Dari sudut pandang ini, bersepeda bukan hanya tindakan mobilitas, melainkan praktik etika sehari-hari—cara kecil namun nyata untuk menolak logika kota yang menyingkirkan manusia dari ruang dan waktu mereka sendiri. Dengan pendekatan yang humanis, berbasis data, dan berfokus pada keadilan, Elly Blue telah memberikan kontribusi penting dalam gerakan bersepeda global, menunjukkan bahwa sepeda bukan hanya tentang olahraga atau hobi, tetapi tentang membangun ekonomi dan komunitas yang lebih sehat dan setara.
Kapitalisme modern memiliki ciri khas yang jarang dipertanyakan: ia menuntut pertumbuhan tanpa henti, kecepatan yang terus meningkat, dan konsumsi yang harus selalu diperbarui. Di dalam logika ini, nilai suatu teknologi diukur dari kemampuannya mempercepat perputaran modal, memperluas pasar, dan menciptakan ketergantungan baru. Sepeda, justru karena kesederhanaannya, berdiri sebagai anomali—bahkan sebagai kritik sunyi—terhadap tatanan ekonomi tersebut.
Sepeda hampir tidak pernah menjadi pusat akumulasi kapital besar. Ia tahan lama, mudah diperbaiki, dan sering diwariskan. Dalam ekonomi kapitalisme, ini adalah “cacat”: barang yang terlalu awet menghambat siklus beli–buang–ganti. Seperti dicatat oleh Ivan Illich, teknologi yang baik bagi manusia sering kali buruk bagi sistem industri, karena ia membebaskan tanpa menciptakan ketergantungan. Sepeda adalah contoh paling jelas dari teknologi semacam ini.
Dalam kerangka Marxian, kapitalisme mengutamakan nilai tukar di atas nilai guna. Mobil, misalnya, bukan hanya alat transportasi, tetapi komoditas berlapis: simbol status, produk keuangan, objek asuransi, sumber data, dan mesin konsumsi energi. Sepeda hampir menolak semua lapisan itu. Ia mendekati nilai guna murni: membawa tubuh dari satu tempat ke tempat lain dengan efisien, murah, dan minim ekstraksi.
Di sinilah sepeda menjadi kritik ekonomi. Ia menunjukkan bahwa mobilitas tidak harus mahal, tidak harus bergantung pada kredit, dan tidak harus menghisap sumber daya dalam skala global. Jika mobil merepresentasikan logika kapitalisme—ekspansi, dominasi ruang, dan konsumsi energi—sepeda merepresentasikan alternatif: cukup, proporsional, dan berakar pada tubuh manusia.
Kapitalisme bekerja dengan menciptakan ketergantungan sistemik: pada bahan bakar fosil, pada infrastruktur mahal, pada jaringan finansial, dan pada spesialisasi teknis. Sepeda memutus banyak rantai ini sekaligus. Ia tidak membutuhkan bahan bakar impor, teknologi kompleks, atau jaringan layanan eksklusif. Dalam banyak konteks Global South, sepeda bahkan dirawat secara informal—di bengkel kecil, di halaman rumah, atau oleh pemiliknya sendiri. Hal ini membuat sepeda sulit sepenuhnya dikapitalisasi. Ia hidup di wilayah abu-abu antara formal dan informal, antara pasar dan swadaya. Dalam bahasa James C. Scott, sepeda beroperasi sebagai teknologi yang bersahabat dengan kehidupan sehari-hari, bukan dengan negara atau korporasi besar. Ia tidak mudah diawasi, tidak menghasilkan data bernilai tinggi, dan tidak mempercepat sirkulasi modal dalam skala besar.
Kapitalisme tidak hanya mengatur produksi barang, tetapi juga mengkolonisasi waktu. Kecepat-an menjadi kebajikan ekonomi: lebih cepat berarti lebih produktif, lebih kompetitif, lebih meng-untungkan. Mobil, pesawat, dan logistik global adalah ekspresi dari etika percepatan ini. Namun percepatan selalu memiliki korban: tubuh yang lelah, kota yang berisik, lingkungan yang rusak.
Sepeda menolak etika ini secara diam-diam. Ia tidak lambat, tetapi juga tidak memuja kecepat-an. Ia berada pada ritme manusia—cukup cepat untuk bergerak, cukup lambat untuk merasa-kan. Dalam konteks ini, bersepeda adalah tindakan politik temporal: menarik kembali waktu dari tuntutan produktivitas absolut. Perjalanan tidak lagi sepenuhnya “waktu mati” yang harus dipercepat, melainkan bagian dari hidup itu sendiri.
Sepeda dan Post-Growth Imagination
Dalam wacana degrowth dan post-growth economics, sepeda sering muncul bukan sebagai solusi teknis, melainkan sebagai simbol pergeseran nilai. Ia menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak selalu berbanding lurus dengan konsumsi energi atau PDB. Kota yang ramah sepeda bisa lebih sehat, lebih adil, dan lebih hidup—bahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
Jason Hickel dalam Less Is More berargumen bahwa krisis ekologis adalah akibat langsung dari sistem yang memaksa pertumbuhan tanpa batas di planet terbatas. Sepeda, dalam skala mikro, adalah praktik “cukup”: cukup cepat, cukup nyaman, cukup efisien. Ia tidak menjanjikan dominasi, tetapi keberlanjutan.
Di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta, sepeda sering dipandang sebagai simbol keterbelakangan atau nostalgia. Namun justru di sini kritik ekonominya paling tajam. Ketika kemacetan, polusi, dan biaya hidup meningkat, sepeda menawarkan rasionalitas ekonomi yang berbeda—bukan kemiskinan, melainkan kecerdasan penggunaan sumber daya.
Bersepeda di kota-kota ini adalah tindakan yang mengganggu narasi kemajuan kapitalistik: bahwa modernitas harus berarti motorisasi penuh. Sepeda memperlihatkan bahwa ada modernitas lain—yang lebih hemat, lebih inklusif, dan lebih bersahabat dengan kehidupan sehari-hari.
Sepeda bukan manifesto, bukan pamflet, dan bukan revolusi spektakuler. Kritiknya bekerja perlahan, melalui praktik. Setiap kayuhan adalah penyangkalan kecil terhadap logika akumulasi tanpa batas; setiap perjalanan tanpa bahan bakar adalah penolakan terhadap ekonomi ekstraktif; setiap sepeda yang diperbaiki, bukan diganti, adalah perlawanan terhadap budaya buang.
Dalam dunia kapitalisme yang berisik, sepeda mengkritik dengan diam. Dan justru dalam diam itulah kekuatannya: ia menunjukkan bahwa kehidupan yang layak tidak harus mahal, cepat, atau terus tumbuh—cukup dijalani, dengan ritme manusia dan kesadaran akan batas.
Bogor, 21 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi (APA)
Blue, E. (2016). Bikenomics: How bicycling can save the economy (2nd ed.). Portland, OR: Microcosm Publishing.
Illich, I. (1974). Energy and equity. London: Calder & Boyars.
https://monoskop.org/images/3/3a/Illich_Ivan_Energy_and_Equity.pdf
Schumacher, E. F. (1973). Small is beautiful: Economics as if people mattered. London: Blond & Briggs.
https://www.smallisbeautiful.org/
Hickel, J. (2020). Less is more: How degrowth will save the world. London: William Heinemann.
Kallis, G. (2018). Degrowth. Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing.