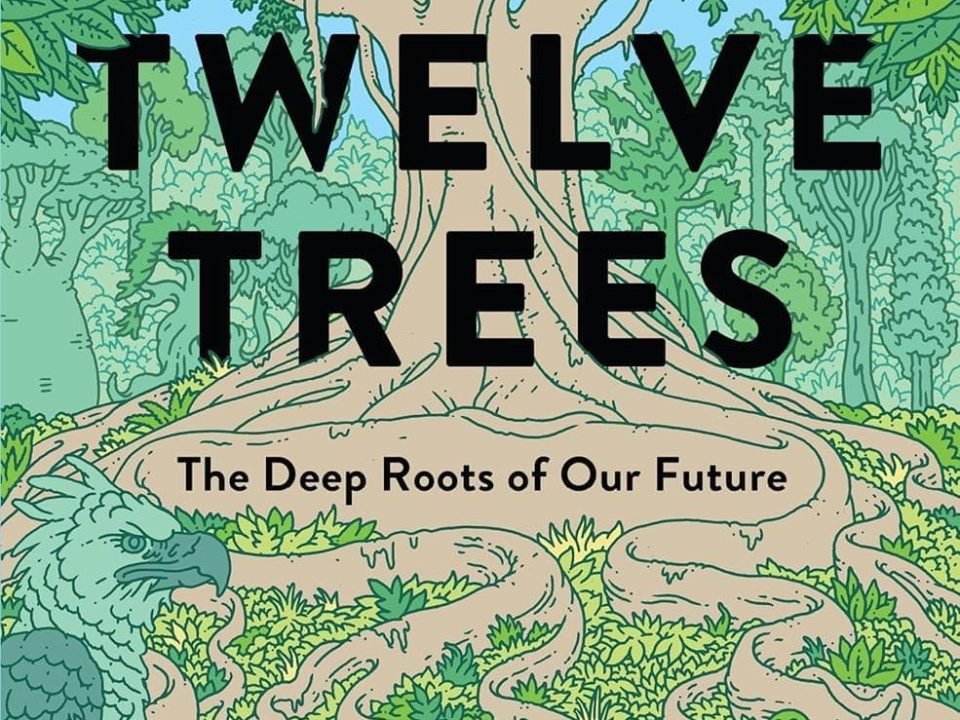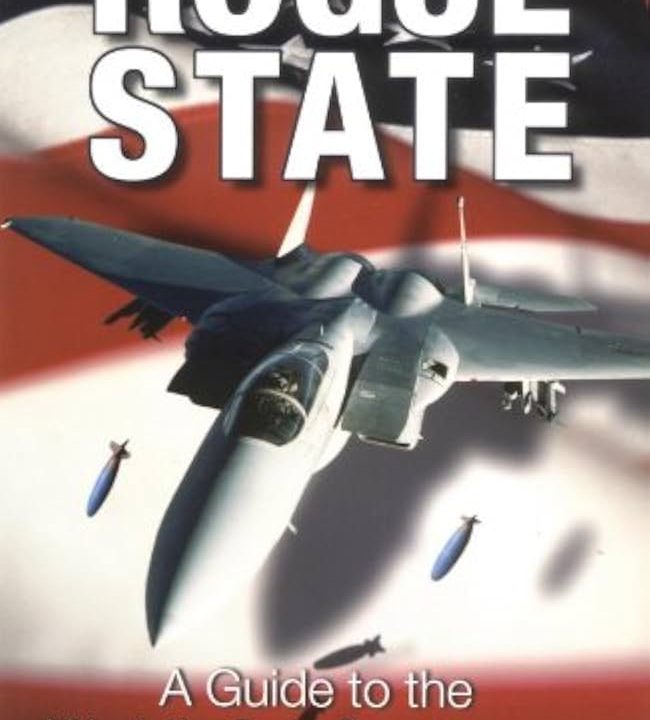Rubarubu #66
Bicycle:
Filsafat di Atas Sadel
Bayangkan seorang profesor filsafat sedang mengayuh sepeda tuanya melewati persimpangan kota yang ramai. Di tengah keseimbangan yang rapuh antara tubuh, mesin, dan lalu lintas, dia tiba-tiba disadarkan oleh sebuah pertanyaan yang mendasar: “Mengapa ini terasa begitu… berarti?”Inilah titik awal Jonathan Maskit dalam buku Bicycle (2024) yang ringkas namun padat ini, yang merupakan bagian dari seri Object Lessons Bloomsbury Academic. Jonathan Maskit adalah seorang filsuf, penulis, dan akademisi Amerika yang karyanya berfokus pada persim-pangan antara filsafat kontinental, etika, budaya populer, dan refleksi kritis tentang kehidupan sehari-hari. Meskipun profil publiknya sebagai penulis buku Bicycle (2024) kini semakin dikenal, jejaknya dalam dunia akademis dan intelektual telah dibangun melalui dedikasi yang panjang pada pengajaran dan pemikiran filosofis yang dapat diakses. Buku ini menarik karena memaparkan tentang sepeda dari sudut pandang filosof.
Maskit tidak menulis sejarah sepeda, manual perbaikan, atau manifesto aktivisme. Sebaliknya, dia menulis sebuah esai filosofis yang mendalam tentang bagaimana sebuah objek sederhana—sepeda—dapat menjadi jendela untuk memahami beberapa pertanyaan terbesar manusia: tentang kebebasan, etika, identitas, dan hubungan kita dengan teknologi serta alam. Buku ini adalah sebuah perjalanan intelektual di mana setang sepeda menjadi kemudi untuk menavigasi pemikiran para filsuf besar, dari Descartes hingga Donna Haraway.
Maskit berargumen bahwa sepeda bukanlah sekadar alat. Ia adalah “teknologi sakral” dalam arti yang sekuler—sebuah mesin yang dengan uniknya menjembatani jurang antara tubuh biologis kita dan dunia buatan manusia. Saat kita mengayuh, kita tidak sepenuhnya menjadi makhluk alam (seperti saat berlari), dan juga tidak sepenuhnya menjadi operator mesin yang teralienasi (seperti saat menyetir mobil). Kita berada dalam sebuah “simbiosis” yang harmonis. “Bersepeda,” tulis Maskit, “adalah sebuah praktik di mana kebebasan dan determinasi, agensi dan kepatuhan, menyatu dalam setiap putaran pedal.”
Dengan pendekatan ini, Maskit mengajak pembaca untuk melihat sepeda sebagai objek filosofis, sebuah artefak yang memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi tentang bagaimana kita hidup di dunia.
Roda-Roda yang Memutar Pikiran
Maskit memulai penjelajahannya dengan membahas tubuh. Mengutip pemikiran fenomenologis Maurice Merleau-Ponty, dia menggambarkan bagaimana pengalaman bersepeda menciptakan “tubuh-terhadap-dunia” yang unik. Saat kita benar-benar mahir bersepeda, kita tidak lagi memikirkan gerakan individual; sepeda menjadi “ekstensi transparan” dari diri kita. Kita “merasakan” jalan melalui sadel dan stang, mengantisipasi tikungan dengan seluruh keberadaan kita. Pengalaman ini menantang pandangan Cartesian yang memisahkan pikiran dan tubuh secara ketat. Di atas sepeda, kita berpikir dengan dan melalui tubuh kita.
Dari tubuh, perjalanan berlanjut ke kebebasan. Di sini, Maskit melakukan tarian yang rumit dengan pemikiran Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Sepeda, katanya, adalah mesin kebebasan paradoks. Di satu sisi, ia memberi kita otonomi mobilitas yang luar biasa—kita bisa pergi ke mana saja, mengikuti kehendak kita sendiri, bebas dari jadwal dan rute tetap. Ini adalah kebebasan eksistensial yang murni. Di sisi lain, kebebasan ini terikat pada determinasi fisik: hukum gravitasi, gesekan, dan terbatasnya stamina kita sendiri. Bersepeda, seperti hidup itu sendiri, adalah “pemberontakan yang absurd” (dalam istilah Camus) melawan batasan-batasan ini. Kita mengayuh meskipun kita tahu akan ada tanjakan; kita mencari angin meskipun kita tahu akan melawan. Kebebasan sejati dalam bersepeda terletak pada penerimaan akan batasan-batasan ini, bukan penyangkalan terhadapnya.
Bab yang paling provokatif mungkin adalah ketika Maskit membahas etika dan politik. Sepeda, baginya, adalah kendaraan untuk “etika kerentanan.” Saat bersepeda di jalan raya, kita secara fisik rentan terhadap pengemudi mobil yang terlindungi oleh logam. Posisi ini memaksa kita—dan seharusnya memaksa masyarakat—untuk mempertimbangkan tanggung jawab kita terhadap ‘Yang Lain’ yang lebih rentan. Sepeda menjadi alat untuk mempraktikkan apa yang disebut filsuf Emmanuel Levinas sebagai “etika respons terhadap wajah orang lain.” Dalam konteks perkotaan, infrastruktur sepeda yang aman bukanlah masalah kenyamanan kelompok hobi, tetapi sebuah tuntutan etis untuk melindungi kerentanan. Di sini, Maskit juga menyentuh ekologi, menyajikan sepeda bukan sebagai solusi teknologi hijau yang sederhana, tetapi sebagai perwujudan dari hubungan yang lebih etis dengan bumi—sebuah cara bergerak yang mengakui keterbatasan sumber daya dan dampak kita.
Maskit juga mengeksplorasi identitas dan komunitas. Dia mengamati bagaimana sepeda dapat menjadi penanda identitas yang kuat—identitas sebagai “pesepeda,” dengan budaya, pakaian, dan nilai-nilai tersendiri yang terkadang eksklusif. Namun, dia juga melihat potensi komunitas dalam fenomena seperti Critical Mass, di mana sepeda digunakan untuk secara kolektif menduduki ruang publik, menantang dominasi mobil. Di sini, sepeda menjadi alat untuk membangun “komunitas yang dirayakan” (celebrated community), meski bersifat sementara.
Sepanjang bukunya, Maskit menggunakan contoh-contoh yang konkret dan personal. Dia merefleksikan pengalamannya sendiri bersepeda di berbagai kota, ketakutannya saat hampir tertabrak, dan kegembiraannya saat meluncur bebas menuruni bukit. Dia juga menganalisis representasi sepeda dalam film seperti “The Bicycle Thief” dan karya seni, menunjukkan bagaimana objek ini telah menjadi simbol universal yang sarat makna.
Bagi Maskit ada Simbiosis Manusia-Mesin: “Sepeda adalah salah satu dari sedikit teknologi yang, alih-alih mengasingkan kita dari tubuh kita, justru memperdalam inkarnasi kita. Ia mengajarkan kita untuk berpikir dengan otot, untuk merasakan dengan roda.” – Maskit merangkum inti fenomenologi bersepeda.
Dan juga bersepeda bisa menumpahkan Kebebasan Absurd: “Mengayuh menanjak adalah latihan dalam filsafat Camusian: kita terus mendorong batu ke atas bukit, bukan karena kita akan menang, tetapi karena perjuangan itu sendiri adalah cara kita mendefinisikan diri kita sebagai manusia yang bebas.” Maskit menghubungkan pengalaman bersepeda dengan teori etika Levinasian. “Saat kita memilih untuk bersepeda,” tulisnya, “kita memilih untuk menempatkan diri kita dalam posisi yang membutuhkan belas kasihan dari orang asing di dalam mobil. Ini adalah tindakan harapan etis yang radikal terhadap masyarakat kita.”
Pemikiran Maskit menemukan gema dalam berbagai tradisi. Dalam filsafat Tiongkok kuno, konsep Dao (Jalan) menekankan tindakan yang selaras dengan alam (wu wei). Bersepeda yang mahir—mengalir dengan medan, menggunakan momentum alih-alih melawannya—adalah perwujudan dari prinsip ini. Dari tradisi Islam, konsep ‘adl (keadilan/kesetimbangan) dan ḥikmah (kebijaksanaan)dapat diterapkan pada etika berbagi jalan dan kebijaksanaan dalam memilih teknologi yang sesuai dengan skala manusia dan kapasitas ekologis bumi. Penyair Persia Jalaluddin Rumi pernah berkata, “Di luar gagasan tentang salah dan benar, ada sebuah padang. Aku akan bertemu denganmu di sana.” Bersepeda, dalam pembacaan filosofis, bisa menjadi metafora untuk mencapai “padang” itu—sebuah ruang pengalaman sebelum dikotomi, di mana tubuh, pikiran, mesin, dan dunia bertemu dalam keseimbangan yang bergerak.
Siklus Sebuah Mesin—Dari Kesaktian Hingga Kematian
Buku ini memuat kisah dua manusia-mesin (cyborg). Di sebuah malam hujan ringan, Jonathan Maskit membayangkan dua sosok yang meluncur di jalan yang sama namun terpisah oleh kesadaran yang berbeda. Yang pertama adalah “Cyborg Efisien”—seorang komuter yang mengenakan jas hujan reflektif, terhubung ke GPS di setang sepedanya, matanya terpaku pada rute optimal yang diproyeksikan di layar kecil. Tubuh dan sepedanya telah menyatu menjadi satu kesatuan yang mulus, sebuah sistem logistik bergerak yang dirancang untuk meminimalkan waktu dan usaha. Yang kedua adalah “Cyborg Puitis”—seorang pengendara yang merasakan setiap tetes hujan di wajahnya, mendengar gemerisik ban di atas aspal basah, dan membiarkan jalannya ditentukan oleh rasa ingin tahu, mungkin membelok ke jalan kecil yang menarik perhatiannya. Bagi yang satu, sepeda adalah mesin untuk mencapai tujuan. Bagi yang lain, sepeda adalah mesin untuk mengalami perjalanan itu sendiri.
Maskit menggunakan dikotomi ini untuk membuka eksplorasi filosofisnya. Apakah sepeda mengubah kita menjadi mesin yang lebih efisien, atau menjadi manusia yang lebih utuh? Dia berargumen bahwa kita selalu menjadi cyborg—makhluk yang hidupnya terjalin dengan teknologi. Sepeda, salah satu teknologi tertua dan paling sederhana, justru mengungkapkan ambiguitas kondisi kita ini. Kita bisa menggunakannya untuk mengasingkan diri dari dunia (seperti komuter yang tergesa-gesa), atau untuk memperdalam keterlibatan kita dengan dunia (seperti pengembara yang penasaran). Bab ini mengajukan pertanyaan mendasar yang akan bergema di sepanjang buku: Teknologi macam apa sebenarnya sepeda ini? Apakah ia alat kendali, atau alat pembebasan? Jawabannya, tampaknya, tergantung pada siapa yang mengayuh, dan bagaimana mereka mengayuhnya.
Maskit tidak menawarkan kronologi teknis yang kering. Sebaliknya, dia menceritakan sejarah sepeda sebagai “evolusi sebuah gagasan.” Dia mulai dengan boneshaker awal—mesin yang canggung dan menyiksa yang hampir-hampir mengolok-olok impian manusia akan kecepatan yang mudah. Kemudian datang era high-wheeler yang heroik dan berbahaya, di mana pengendara duduk begitu tinggi sehingga mereka benar-benar “mengendarai” di atas mesinnya, sebuah simbol status yang sekaligus merupakan tindakan keberanian yang ekstrem.
Titik baliknya, menurut Maskit, adalah penemuan sepeda safety. Inilah momen ketika teknologi sepeda menemukan bentuknya yang paling manusiawi. Roda yang sama besar, rantai penggerak, dan posisi berkendara yang stabil menciptakan keseimbangan yang sempurna antara kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas. “Dengan safety,” tulis Maskit, “sepeda berhenti menjadi wahana untuk petualang atau orang kaya, dan menjadi kendaraan bagi setiap orang.” Revolusi ini bukan hanya teknis; ia adalah sosial dan filosofis. Sepeda menjadi mesin demokratisasi mobilitas, sebuah alat yang memungkinkan wanita, pekerja, dan anak-anak untuk mengklaim ruang dan kebebasan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam narasi Maskit, sejarah sepeda adalah sejarah singkat tentang bagaimana sebuah teknologi berevolusi dari mainan yang eksentrik menjadi ekstensi yang hampir sempurna dari potensi tubuh manusia biasa.
Di sini, Maskit memusatkan perhatian pada pengalaman ajaib dari bersepeda itu sendiri. Ia menyebutnya sebagai Mesin Ajaib. Dia menggambarkannya sebagai “sihir teknologis”. Saat kita mengayuh, sesuatu yang luar biasa terjadi: energi dari tubuh kita—yang relatif lemah dan terbatas—dikatalisasi oleh sistem roda gigi, rantai, dan roda menjadi kecepatan dan jarak yang jauh melampaui kemampuan alami kita. Kita melesat melintasi lanskap dengan usaha yang, ketika dikuasai, terasa hampir tanpa usaha. “Ini adalah ilusi yang paling manis,” katanya, “ilusi bahwa kita telah mengalahkan hukum fisika, bahwa kita telah menjadi Superman dengan otot betis.”
Namun, keajaiban ini bukanlah ilusi belaka. Maskit menekankan bahwa ini adalah keajaiban yang partisipatif. Kita tidak duduk pasif seperti di dalam mobil; kita adalah bagian integral dari mesin tersebut. Perasaan “melayang” saat mengayuh dengan lancar adalah pencapaian, sebuah penghargaan atas kerja sama yang harmonis antara tubuh, kemauan, dan mesin. Bab ini adalah ode terhadap kenikmatan fenomenologis bersepeda—sensasi angin di kulit, medan yang terasa melalui stang, dan perasaan otonomi yang mendalam. Sepeda adalah mesin ajaib karena, tidak seperti kebanyakan teknologi modern, ia tidak mengasingkan kita dari prosesnya; justru, ia membuat kita jatuh cinta pada proses itu sendiri.
Dengan tiba-tiba dan mengejutkan, nada buku berubah. Dari keajaiban, Maskit beralih ke bayangan. Sepeda, katanya, juga adalah “mesin kematian.” Ini tidak hanya merujuk pada risiko kecelakaan yang nyata—meski itu penting—tetapi pada sesuatu yang lebih filosofis. Sepeda, dalam kecepatan dan kebebasannya, mengungkapkan kerentanan mendasar kita.
Di jalan raya, tubuh pengendara sepeda yang hanya dilindungi oleh helm dan pakaian, berhadapan dengan mobil yang merupakan “kotak baja seberat dua ton.” Ketidakseimbangan kekuatan ini brutal. Namun, bagi Maskit, kerentanan ini justru mengandung pelajaran etis yang dalam. “Bersepeda,” tulisnya, “adalah latihan terus-menerus dalam menjadi ‘Yang Lain’ yang rapuh.”Posisi ini memaksa kita (baik sebagai pesepeda maupun sebagai pengemudi yang melihat pesepeda) untuk menghadapi tanggung jawab kita terhadap kerapuhan sesama. Kematian dalam konteks ini bukan hanya akhir biologis, tetapi metafora untuk bagaimana masyarakat modern sering kali mengorbankan yang rapuh demi efisiensi dan kecepatan. Mesin kematian sepeda adalah cermin yang memantulkan kegagalan etis tata ruang kota kita, di mana ruang publik telah didominasi oleh teknologi yang secara inheren mengancam nyawa pengguna yang lebih lemah.
Maskit lantas bertanya: Apa Artinya Berbagi Jalan? Dari kontras antara keajaiban dan kematian inilah, pertanyaan terbesar buku ini muncul: Apa Artinya Berbagi Jalan? Maskit berargumen bahwa “berbagi jalan” bukanlah sekadar slogan lalu lintas atau masalah hukum hak jalan. Ini adalah pertanyaan politik dan etika yang mendalam tentang bagaimana kita hidup bersama dalam ruang terbatas.
“Berbagi” berarti mengakui bahwa jalan bukanlah medan netral. Ia adalah medan pertempuran nilai-nilai: efisiensi vs. keamanan, kecepatan vs. keadilan, hak individu vs. tanggung jawab kolektif. Saat seorang pengemudi dengan sabar mengikuti seorang pesepeda di jalan sempit, mereka tidak hanya mematuhi hukum; mereka sedang mempraktikkan etika kesabaran—mengakui hak orang lain untuk berada di sana, meskipun itu memperlambat perjalanan mereka sendiri.
Sebelum Bicycle, Maskit telah menulis dan menyunting sejumlah artikel akademis serta bab buku. Salah satu proyek editorialnya yang signifikan adalah sebagai co-editor untuk buku Environment and Philosophy (bersama dengan Susan Power Bratton). Buku ini adalah bagian dari seri Routledge Contemporary Introductions to Philosophy dan menunjukkan komitmennya untuk menjadikan filsafat lingkungan sebagai bidang kajian yang serius dan dapat dipahami.
Karyanya sering kali mengeksplorasi fenomenologi pengalaman manusia—bagaimana kita me-ngalami dunia melalui tubuh, teknologi, dan seni. Buku Bicycle merupakan puncak alami dari minat ini. Di dalamnya, ia menerapkan ketelitian seorang filsuf akademis pada objek sehari-hari, mengungkap lapisan-lapis makna tentang kebebasan, kerentanan, etika, dan masyarakat yang terkandung dalam mesin sederhana beroda dua itu. Gayanya yang naratif dan reflektif, namun tetap berakar pada tradisi filosofis yang kuat, membuat karyanya unik: ia serius secara intelektual tanpa menjadi esoterik, dan personal tanpa menjadi dangkal.
Maskit melihat potensi transformatif dalam etika berbagi jalan ini. Jika kita dapat belajar untuk benar-benar berbagi aspal dengan pengendara sepeda yang rentan, mungkin kita juga dapat belajar untuk berbagi sumber daya, peluang, dan planet ini dengan cara yang lebih adil. “Jalan raya,” simpulnya, “adalah mikrokosmos dari masyarakat. Bagaimana kita mengaturnya meng-ungkapkan siapa kita dan apa yang kita hargai.” Bersepeda, dengan demikian, menjadi lebih dari sekadar cara bergerak; ia menjadi latihan etis dan politik, sebuah tindakan sehari-hari yang menantang logika individualistik dan dominasi teknologi berat, serta mengusulkan model hubungan yang lebih peka, sabar, dan sadar akan keberadaan bersama kita yang rapuh.
Dalam narasi yang berlapis ini, Maskit telah membawa kita pada perjalanan dari tubuh individu yang menyatu dengan mesin, melalui sejarahnya yang penuh gejolak, menuju puncak peng-alaman ajaibnya, lalu terjun bebas ke dalam jurang kerentanannya, hanya untuk mendarat pada sebuah pertanyaan mendesak tentang kehidupan kolektif kita. Sepeda, dalam analisisnya, ter-nyata adalah guru yang paling tidak terduga—mengajarkan kita tentang kebebasan, batasan, keindahan, kematian, dan akhirnya, tentang arti sebenarnya dari hidup bersama.
Jonathan Maskit membelokkan setang filsafatnya ke persimpangan hukum dan moral: hak jalan. Ini bukan sekadar peraturan lalu lintas, melainkan sebuah kontrak sosial yang rapuh. Dia menggambarkan sebuah adegan: seorang pesepeda mendekati persimpangan empat arah bersamaan dengan sebuah mobil. Mata mereka bertemu sesaat melalui kaca depan. Siapa yang harus bergerak lebih dulu? Hukum mungkin memberikan jawaban, tetapi di momen tatap mata itu, yang dipertaruhkan adalah pengakuan bersama sebagai manusia yang berbagi ruang. “Hak jalan,” tulis Maskit, “adalah hak untuk diakui eksistensinya.”
Saat pengemudi mengangguk atau memberi isyarat tangan agar pesepeda lewat, mereka bukan hanya mengikuti aturan; mereka sedang menegaskan: “Aku melihatmu. Kau berhak berada di sini.” Sebaliknya, ketika hak itu dilanggar—ketika mobil menyerobot—yang terluka bukan hanya keselamatan fisik, tetapi pengakuan atas kemanusiaan dan hak untuk merasa aman di ruang publik. Bab ini menyoroti bagaimana jalan raya adalah panggung mikro untuk drama pengakuan Hegelian, di mana konflik dan pengakuan menentukan hubungan sosial kita.
Pengalaman personal Maskit menjadi bahan inspirasi penting untuk menyusun buku ini. Terbukti misalnya pada Bab 7 ia secara khusus membincangkan tentang sejumlah pengalaman yang dikemas dalam Buku Harian Sepeda. Di sini, nada berubah menjadi personal dan kontemplatif. Maskit membawa kita ke dalam “buku harian” pengalamannya bersepeda—bukan catatan jarak dan kecepatan, tetapi refleksi tentang momen-momen kecil yang filosofis. Satu hari, dia mendeskripsikan sensasi meluncur sunyi menuruni bukit di fajar, di mana dunia tampak masih kosong dan penuh kemungkinan, sebuah pengalaman akan kebebasan murni yang mengingatkannya pada konsep “liberty” dari John Stuart Mill.
Di hari lain, dia menggam-barkan kepanikan yang mendadak saat sebuah pintu mobil terbuka di depannya, sebuah ledakan adrenalin yang menegaskan kembali kerentanannya yang mutlak. Buku harian ini menjadi meditasi tentang bagaimana sepeda menjadikan perjalanan sehari-hari sebagai sumber kebijaksanaan tubuh. Setiap kayuhan adalah pelajaran tentang keseimbangan, setiap tanjakan adalah pelajaran tentang ketekunan, dan setiap interaksi dengan pengemudi adalah pelajaran tentang etika. Sepeda, dalam bab ini, adalah pena yang menulis pengalaman langsung ke dalam ingatan tubuh, sebuah cara untuk “membaca” kota dan diri sendiri dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dari dalam mobil yang terkungkung.
Maskit pada Bab memperkenalkan istilah yang provokatif: “motorisme”. Ini bukan sekadar kepemilikan mobil, melainkan sebuah ideologi, sebuah cara memandang dunia yang berpusat pada kecepatan, efisiensi, dan enclave bergerak yang terlindungi. Motorisme, katanya, menciptakan “pengemudi”sebagai subjek politik yang khas: seseorang yang mengalami ruang publik sebagai rintangan untuk dilalui secepat mungkin, di mana pejalan kaki dan pesepeda dipersepsikan sebagai “hambatan” dalam aliran logistik pribadi mereka. Dia menganalisis bagaimana desain mobil—dengan musik yang keras, kontrol iklim, dan kapsul yang nyaman—secara aktif mengisolasi pengemudi dari dunia luar, memudarkan suara, bau, dan kehadiran manusia lain. “Motorisme,” tulisnya, “adalah praktik untuk tidak merasakan—tidak merasakan angin, tidak merasakan medan, dan yang paling berbahaya, tidak merasakan keberadaan orang lain yang rentan.” Bab ini adalah kritik budaya terhadap sistem yang telah menormalkan teknologi yang secara inheren antisosial dan berbahaya, sambil menyamarkan sifat aslinya sebagai simbol kebebasan.
Bersepeda, menurut Maskit, mengubah status ontologis kita di jalan raya. Yang terlihat dan yang tak terlihat. Seorang pengendara sepeda adalah makhluk yang paradoks: sangat terlihat secara fisik (karena kerentanannya), namun sering kali tak terlihat secara politis dan perencanaan. Dia “terlihat” sebagai gangguan dalam aliran lalu lintas seorang pengemudi, tetapi “tak terlihat” ketika anggaran kota dialokasikan untuk jalan layang baru alih-alih jalur sepeda yang terlindungi. Maskit mengeksplorasi fenomena “looked-but-failed-to-see” dalam kecelakaan, di mana pengemudi bersumpah mereka melihat sekeliling tetapi otak mereka, yang terlatih untuk mengantisipasi objek besar seperti mobil lainnya, gagal mendaftarkan keberadaan pesepeda. Ini adalah ketidakterlihatan yang mematikan, yang berakar pada bias persepsi yang dibentuk oleh budaya motorisme. Bab ini membahas perjuangan untuk visibilitas politik—bagaimana aktivis berusaha membuat bersepeda “terlihat” bukan sebagai hobi, tetapi sebagai moda transportasi yang sah yang layak mendapat ruang dan perlindungan.
Dari ketidakterlihatan, kita tiba pada simbol yang paling menyentuh dan mengerikan: “Sepeda Hantu” (Ghost Bike). Sepeda cat putih yang dikunci di tempat seorang pesepeda tewas bukanlah sekadar tugu peringatan. Bagi Maskit, itu adalah “intervensi estetika yang menyayat hati ke dalam ruang publik.” Ia mengubah sebuah titik koordinat dalam statistik kecelakaan menjadi sebuah situs kesedihan dan kemarahan yang tak terbantahkan. Setiap Sepeda Hantu adalah pertanyaan yang membeku: “Mengapa?” Ia memanggil setiap orang yang lewat untuk merenung, bahkan untuk sesaat. Maskit melihatnya sebagai bentuk aktivisme memorial yang paling efektif, karena ia bekerja langsung pada tingkat emosi dan empati, mengganggu perjalanan sehari-hari dengan pengingat akan kematian yang dapat dicegah. “Sepeda Hantu,” tulisnya, “adalah bisikan terakhir dari orang yang tak terlihat, yang kini bersikeras untuk terlihat selamanya.”
Maskit lalu beralih ke solusi praktis yang filosofis: “Idaho Stop“—hukum yang mengizinkan pesepeda memperlakukan lampu merah sebagai tanda berhenti, dan tanda berhenti sebagai tanda yield (memberi jalan). Berhenti ala Idaho. Bagi para pendukungnya, ini mengakui realitas fisiologi bersepeda: mempertahankan momentum lebih aman dan efisien daripada berhenti dan mulai kembali. Jonathan Maskit adalah seorang pesepeda yang rajin, dan pengalaman personal inilah yang memberi bahan bakar otentik bagi bukunya. Ia tidak menulis tentang sepeda sebagai pengamat yang jauh, tetapi sebagai seorang praktisi yang merasakan langsung kegembiraan, ketakutan, dan pertanyaan filosofis yang muncul di atas sadel. Ia tinggal di Ohio, Amerika Serikat, sebuah negara bagian dengan lanskap yang beragam, dari kota-kota seperti Columbus hingga pedesaan, yang memberinya banyak latar untuk refleksi bersepedanya.
Dengan Bicycle, Jonathan Maskit telah melangkah keluar dari lingkaran akademis yang khusus dan menawarkan kepada khalayak yang lebih luas sebuah model untuk melakukan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa alat untuk memahami kondisi manusia tidak hanya terdapat dalam naskah-naskah kuno, tetapi juga dalam bagaimana kita bergerak, berinteraksi, dan menghadapi kerentanan kita di dunia modern. Dalam tradisi pemikir seperti Albert Borgmann atau Andrew Feenberg yang mengkaji filsafat teknologi, Maskit menambahkan suara yang puitis dan sangat personal. Ia adalah filsuf pengendara sepeda, yang menggunakan jalannya sendiri untuk membimbing kita melalui pertanyaan-pertanyaan besar tentang bagaimana kita seharusnya hidup.
Bagi Maskit, perdebatan ini adalah tentang otonomi dan kepercayaan. Apakah kita memperlakukan pesepeda sebagai agen moral yang mampu menggunakan penilaian situasional, atau sebagai anak kecil yang harus dikendalikan oleh aturan kaku yang dirancang untuk mobil? Idaho Stop adalah proposisi bahwa hukum lalu lintas harus mencerminkan sifat sebenarnya dari kendaraan yang berbeda, bukan memaksakan standar yang sama untuk semua. Ini adalah pertanyaan tentang apakah sistem hukum kita melihat pesepeda sebagai warga negara dewasa dengan tubuh dan mesin yang unik, atau hanya sebagai gangguan dalam sistem yang dirancang untuk mesin lain.
Ini adalah bab tentang geometri kekuasaan (Bab 12: Ruang). Maskit menganalisis bagaimana ruang jalan didistribusikan. Dia menggambarkan sebuah jalan kota biasa: lajur mobil yang lebar, tempat parkir di kedua sisi, dan mungkin sebuah jalur sepeda yang sempit yang berbatasan langsung dengan lalu lintas yang melaju kencang. Alokasi ruang ini, katanya, bukanlah keputusan teknis yang netral. Itu adalah pernyataan nilai. Lebih banyak ruang untuk mobil berarti masyarakat lebih menghargai kecepatan pribadi dan kepemilikan properti (mobil) daripada keselamatan tubuh, interaksi sosial, atau kelestarian lingkungan. Memperjuangkan ruang untuk sepeda, oleh karena itu, adalah pertempuran untuk mendefinisikan ulang nilai-nilai perkotaan kita. Ini adalah perjuangan untuk mengubah geometri jalan dari yang hanya memfasilitasi aliran logistik, menjadi geometri yang merangkul kehidupan manusia dalam semua kecepatan dan modalitasnya.
Maskit menarik paralel yang mengejutkan. Dia menunjukkan bagaimana argumen yang digunakan melawan sepeda di puncak “Demam Sepeda” akhir 1800-an—bahwa mereka menakut-nakuti kuda, menyebabkan kekacauan, dan digunakan oleh “orang sembrono”—bergema nyaris sempurna dengan argumen yang digunakan melawan mobil di awal 1900-an. Dan sekarang, argumen yang digunakan oleh beberapa pengemudi melawan pesepeda (mereka “melanggar hukum,” “tidak membayar pajak jalan,” “berbahaya”) adalah gema dari masa lalu itu. Siklus ini, baginya, mengungkapkan ketakutan budaya yang dalam terhadap teknologi mobilitas baru yang mengganggu tatanan sosial yang mapan. Pesepeda masa kini, seperti pengemudi mobil di masa lalu, adalah perintis yang mengganggu status quo. Pelajaran sejarahnya adalah: setiap revolusi mobilitas menghadapi perlawanan sengit, tetapi lanskap moral dan fisik pada akhirnya berubah.Pertanyaannya adalah: perubahan seperti apa yang akan kita pilih untuk diwujudkan kali ini?
Dalam bab penutupnya, Maskit mengakui realitas suram: dominasi mobil, perubahan iklim, urban sprawl, dan kematian yang terus terjadi di jalan. Ini adalah awan gelap. Namun, dari awan itu, dia melihat sisi terang. Sisi terang itu adalah kebangkitan bersepeda perkotaan, bukan sebagai tren, tetapi sebagai gerakan sosial yang sadar. Itu adalah munculnya generasi yang melihat sepeda sebagai simbol ketahanan, komunitas, dan tanggung jawab ekologis. Itu adalah tactical urbanismdi mana warga mengambil kembali ruang dengan cat dan pot bunga.
Maskit menyimpulkan dengan pandangan yang terukur namun penuh harap. Sepeda, dalam segala kerumitan filosofisnya—sebagai mesin ajaib dan mesin kematian, sebagai alat kebebasan dan kerentanan—tetap menawarkan jalan ke depan. Ia menawarkan cara untuk membangun kembali kota kita di sekitar skala manusia, untuk mempraktikkan etika kerentanan setiap hari, dan untuk menemukan kembali kegembiraan bergerak yang tidak terpisahkan dari dunia yang kita lalui. Perjalanan tidak berakhir; ia hanya berubah gigi. Masa depan, mungkin, tidak akan dimiliki oleh mesin yang paling cepat atau paling kuat, tetapi oleh mesin yang paling bijaksana—mesin yang mengajari kita, dengan setiap kayuhan, apa artinya benar-benar hidup, bersama-sama, di jalan yang kita bagi.
Catatan Akhir: Objek sebagai Cermin
Maskit memegang gelar Ph.D. dalam Filsafat dan telah menjalani karier sebagai profesor filsafat di tingkat perguruan tinggi. Selama bertahun-tlam, ia mengajar di Denison University, sebuah liberal arts college terkemuka di Granville, Ohio. Di Denison, ia dikenal sebagai pengajar yang mengilhami dan mendalam, yang mampu menghubungkan teori-teori kompleks dari pemikir seperti Heidegger, Derrida, atau Levinas dengan pengalaman konkret mahasiswanya.
Keahlian pengajarannya terletak pada bidang Filsafat Kontinental Abad ke-20, Estetika, dan Filsafat Lingkungan. Ia tidak hanya tertarik pada teks-teks klasik, tetapi juga pada bagaimana wawasan filosofis dapat muncul dari objek dan praktik budaya kontemporer—sebuah pendekatan yang jelas tercermin dalam bukunya tentang sepeda.
Bicycle karya Jonathan Maskit menyimpulkan bahwa objek sehari-hari yang tampaknya biasa ini adalah sebuah cermin filosofis yang luar biasa. Dengan melihat melalui lensa sepeda, kita dapat merefleksikan keadaan manusia modern: pencarian kita akan kebebasan dalam sebuah dunia yang penuh batasan, keinginan kita untuk keakraban tubuh dalam budaya yang semakin terdigitalisasi, dan tanggung jawab etis kita terhadap sesama dan planet ini. Buku ini bukan panduan untuk menjadi pesepeda yang lebih baik, tetapi undangan untuk menjadi pemikir yang lebih mendalam. Setelah membacanya, setiap kayuhan pedal tidak akan lagi terasa sama. Sepeda berubah dari sekadar alat transportasi menjadi mitra dalam pertanyaan, sebuah mesin yang tidak hanya membawa kita melintasi ruang, tetapi juga melintasi lanskap pemikiran yang luas. Maskit menunjukkan bahwa kadang-kadang, filsafat terdalam tidak berasal dari menatap langit-langit di menara gading, tetapi dari mengayuh dengan penuh perhatian di sepanjang jalan kota, merasakan setiap getaran aspal sebagai sebuah pertanyaan, dan setiap angin sepoi-sepoi sebagai sebuah kemungkinan jawaban.
Belitung, 27 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi:
Maskit, J. (2024). Bicycle. Bloomsbury Academic.
Sumber Kontekstual Tambahan:
- Seri Object Lessons: Konteks penerbitan buku ini.
- Fenomenologi dan Tubuh: Karya klasik Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception.
- Etika Levinasian: Buku seperti Totality and Infinity oleh Emmanuel Levinas.
- Filsafat Teknologi: Karya Don Ihde, seperti Technology and the Lifeworld, yang membahas “hubungan manusia-teknologi.”