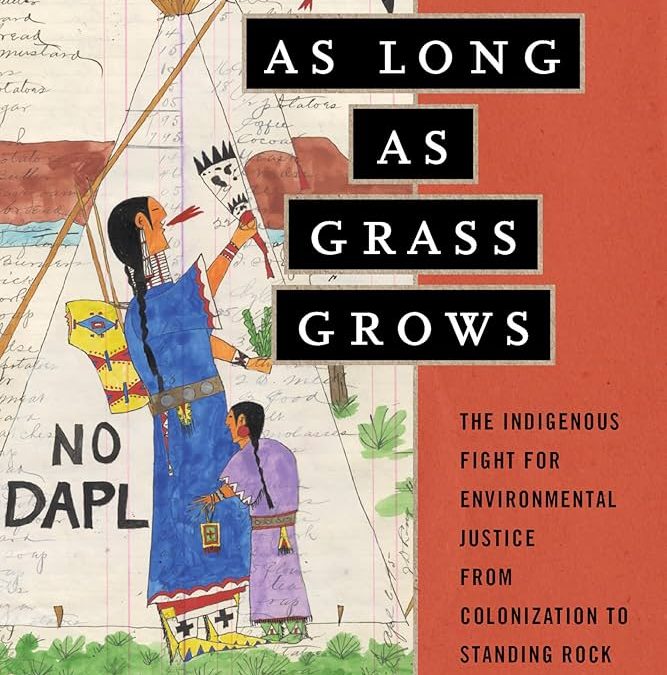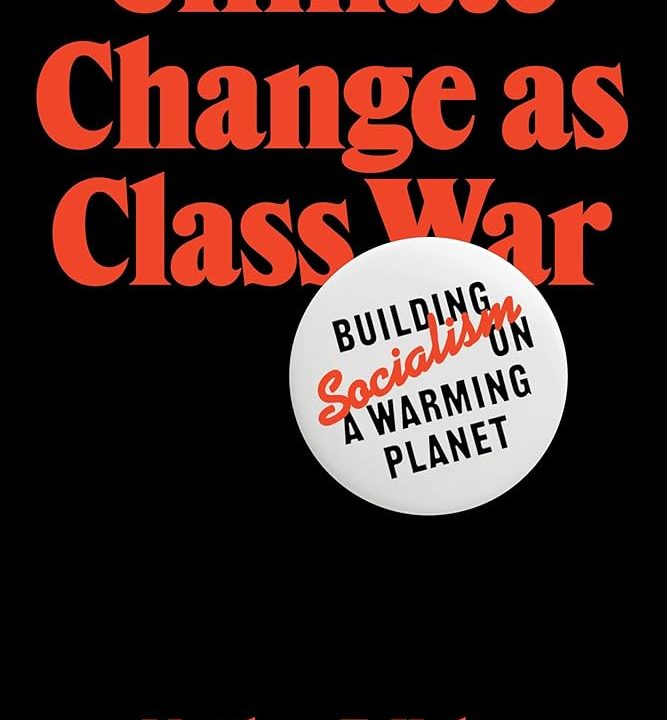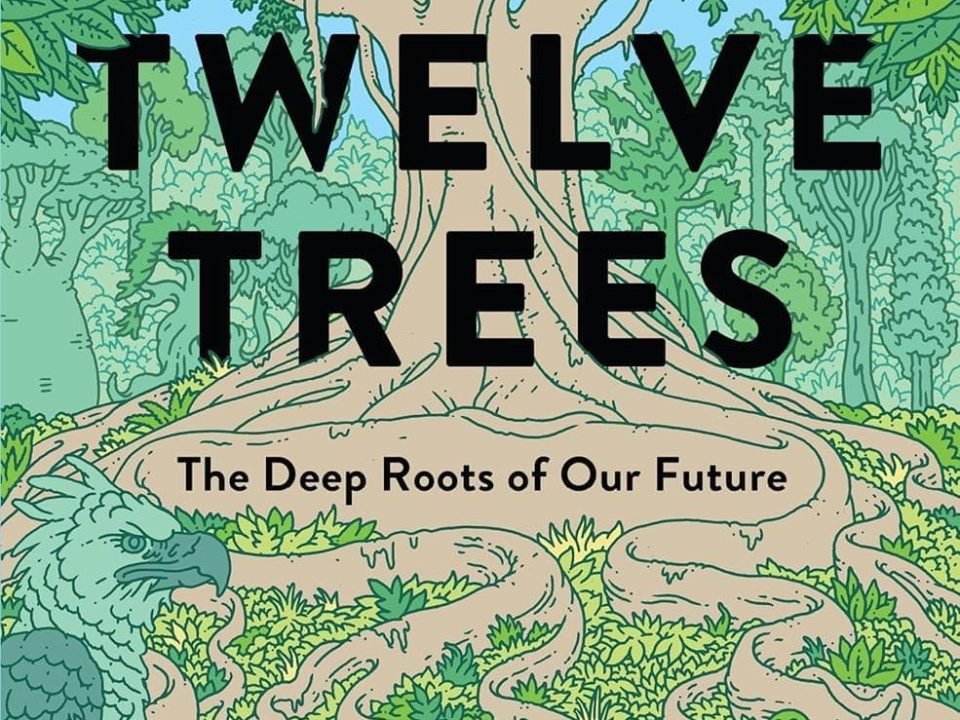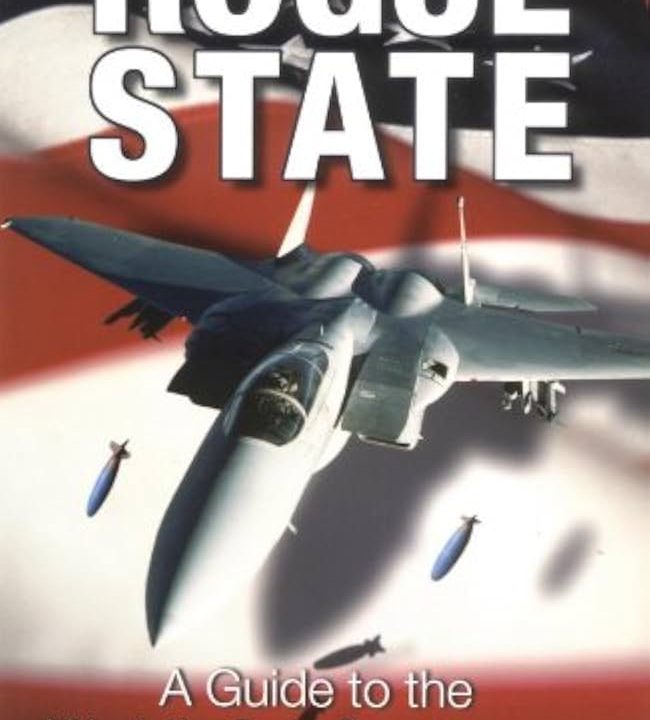Rubarubu #78
As Long as Grass Grows:
Ekologi Kolonial dan
Akar Ketidakadilan Lingkungan
Kisah dari Standing Rock
Bayangkan sebuah pagi musim gugur di Dakota Utara, 2016. Kabut menggantung di atas padang rumput yang luas, dan ribuan orang berdiri melingkar di tepi Sungai Missouri. Asap dupa dan teriakan doa bercampur dengan suara drum. Mereka bukan hanya penduduk asli suku Sioux; mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka berkumpul di Standing Rock untuk menghentikan pembangunan pipa minyak Dakota Access yang mengancam tanah leluhur dan sumber air mereka. Di sinilah Dina Gilio-Whitaker memulai kisahnya — bukan hanya kisah perlawanan, tapi kisah panjang bagaimana lingkungan, tanah, dan keberadaan spiritual bangsa-bangsa pribumi telah dirampas atas nama kemajuan. Ia menulis, “Standing Rock was not the beginning of Indigenous resistance — it was its continuation.”
Buku As Long as Grass Grows: The Indigenous Fight for Environmental Justice, from Colonization to Standing Rock karya Dina Gilio-Whitaker (2019) mengupas pergulatan masyrakat adat di Amerika Serikat untuk keadilan lingkungan. Dalam bab-bab awal, Gilio-Whitaker menelusuri akar historis ketidakadilan lingkungan yang dihadapi masyarakat pribumi di Amerika Utara. Ia menjelaskan bahwa kolonialisme bukan hanya penaklukan manusia, tetapi juga penaklukan terhadap alam — menempatkan tanah sebagai komoditas dan memisahkan manusia dari dunia spiritual mereka. Kolonialisme, katanya, “membuat lingkungan menjadi sumber daya, bukan hubungan.” Sejak kedatangan bangsa Eropa, hukum-hukum seperti Doctrine of Discovery dan Manifest Destiny melegitimasi perampasan lahan dan pemusnahan ekosistem adat. Bagi masyarakat pribumi, tanah bukan milik mereka — mereka adalah bagian dari tanah. “As long as grass grows and rivers flow,” demikian janji pemerintah AS dalam banyak perjanjian, namun janji itu dikhianati berulang kali.
Bab pertama ini merupakan fondasi teoritis dari seluruh buku, “Environmental Justice Theory and Its Limitations for Indigenous Peoples.” Dina Gilio-Whitaker memulai dengan menelusuri sejarah lahirnya gerakan keadilan lingkungan (Environmental Justice Movement, EJM) di Amerika Serikat yang muncul pada akhir 1970-an hingga 1980-an, terutama dari komunitas kulit hitam, Latin, dan kelompok miskin yang menentang pencemaran industri di wilayah mereka. Ia mengutip kasus terkenal di Warren County, North Carolina (1982), di mana masyarakat Afrika-Amerika memprotes pembuangan limbah beracun di tanah mereka—peristiwa yang kemudian dianggap sebagai “kelahiran” gerakan keadilan lingkungan modern.
Namun, Gilio-Whitaker segera menyoroti bahwa teori dan praktik keadilan lingkungan yang dibangun dari pengalaman komunitas rasial Amerika memiliki keterbatasan serius ketika diterapkan pada masyarakat adat (Indigenous peoples). Menurutnya, kerangka keadilan lingkungan mainstream berfokus pada distribusi yang adil atas beban dan manfaat lingkung-an—misalnya siapa yang menanggung polusi atau siapa yang menikmati sumber daya alam—sementara bagi masyarakat adat, isu lingkungan tidak semata soal distribusi, melainkan soal kedaulatan, sejarah kolonisasi, dan relasi spiritual dengan tanah.
Dalam bagian tengah bab ini, Gilio-Whitaker menjelaskan bahwa pendekatan “liberal” dalam teori keadilan lingkungan cenderung ahistoris, karena tidak memperhitungkan konteks kolonial yang membentuk struktur ketidakadilan di Amerika Utara. Ia menulis, “Indigenous environ-mental struggles are not only about pollution or access, but about the ongoing structures of settler colonialism that dispossess Native peoples of their homelands.” Dengan kata lain, bagi masyarakat adat, isu lingkungan adalah isu dekolonisasi — perjuangan untuk mengembalikan hubungan dengan tanah yang diambil secara paksa melalui kekerasan, hukum kolonial, dan asimilasi budaya.
Gilio-Whitaker juga mengkritik cara negara dan lembaga internasional memisahkan hak ling-kungan dari hak adat. Dalam kerangka hukum Amerika, “tanah publik” sering kali diartikan sebagai milik negara, bukan milik masyarakat adat, padahal bagi penduduk asli tanah tidak pernah dimiliki melainkan dihuni dan dirawat. Hal ini membuat banyak proyek konservasi dan kebijakan lingkungan modern (termasuk taman nasional) menjadi bentuk baru dari green colonialism — pencabutan hak masyarakat adat atas tanah dengan alasan pelestarian. “We are the land; that is the fundamental idea.” (Pepatah Lakota)
Ia menyoroti pula bahwa dalam banyak kasus, kebijakan keadilan lingkungan berbasis hak sipil (civil rights) tidak memadai untuk menangani persoalan masyarakat adat, karena identitas mereka bukan sekadar etnis minoritas, melainkan bangsa berdaulat (sovereign nations). Karena itu, upaya dekolonisasi lingkungan harus melampaui tuntutan distribusi yang adil menuju pemulihan kedaulatan dan epistemologi pribumi (Indigenous epistemologies) — cara hidup, berpikir, dan berhubungan dengan alam yang berbeda dari paradigma Barat. Dalam bab ini, Gilio-Whitaker memperkenalkan istilah “Indigenized Environmental Justice”, sebuah pendekat-an yang menempatkan pengalaman masyarakat adat sebagai pusat analisis.
Prinsip utamanya adalah:
- Tanah adalah kehidupan, bukan sumber daya.
- Lingkungan tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas dan budaya.
- Keadilan sejati hanya mungkin ketika hak atas kedaulatan diakui.
Ia menulis, “Environmental justice for Indigenous peoples is fundamentally about decolonization — the restoration of land, life, and governance.” Dengan ini, Gilio-Whitaker memperluas definisi keadilan lingkungan dari sekadar isu sosial-ekonomi menjadi isu eksistensial dan kosmologis.
Menariknya, Gilio-Whitaker juga menyentuh aspek epistemologis — bahwa ilmu lingkungan modern dibangun di atas paradigma yang memisahkan manusia dari alam, sementara pengetahuan pribumi (Indigenous Knowledge Systems) justru melihat manusia sebagai bagian dari jejaring ekologis. Karena itu, untuk mencapai keadilan lingkungan sejati, cara kita memahami “alam” itu sendiri harus berubah. Pada bagian akhir bab, ia menyerukan perlu-nya “environmental justice 2.0” — sebuah pendekatan lintas budaya yang meng-gabungkan kritik terhadap kapitalisme, kolonialisme, dan rasialisme dengan penghargaan terhadap ke-arifan lokal dan hak-hak kolektif. Ia mengutip pepatah Lakota, “We are the land; that is the fundamental idea.” Dalam kerangka ini, memperjuangkan keadilan lingkungan bukan hanya memperjuangkan kelangsungan hidup manusia, tapi juga memulihkan kesucian relasi antara manusia dan bumi.
Bab ini sangat relevan di tengah krisis iklim global dan konflik agraria yang meluas. Di Indonesia, isu serupa terlihat dalam perjuangan masyarakat adat di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi terhadap tambang, sawit, dan proyek “hijau” seperti food estate atau energi terbarukan yang sering kali mengabaikan hak-hak lokal. Pendekatan Gilio-Whitaker menegaskan bahwa keadilan ekologis tidak mungkin dicapai tanpa keadilan historis dan kultural.
Dalam konteks filosofis, pandangan Gilio-Whitaker sejalan dengan gagasan Vandana Shiva tentang “Earth Democracy” dan Achille Mbembe tentang “ecology of relation” — bahwa ke-adilan harus menyentuh akar struktur kolonialisme epistemik yang mengatur cara kita me-mandang alam dan manusia. Dalam Islam, prinsip serupa ditemukan dalam konsep amanah dan ‘adl (keadilan), yang menekankan tanggung jawab manusia menjaga keseimbang-an bumi sebagai bagian dari tugas spiritualnya. “Without sovereignty, there can be no justice for Indigenous nations.”
Salah satu bagian paling menyentuh dalam buku ini adalah penjelasan Gilio-Whitaker tentang peran perempuan pribumi sebagai penjaga bumi (earth keepers). Perempuan, tanah, dan spiritualitas yang terluka. Dalam banyak masyarakat adat, perempuan memiliki hubungan langsung dengan air, benih, dan siklus kehidupan. Namun kolonialisme patriarkal tidak hanya menghancurkan alam, tapi juga menghancurkan posisi perempuan dalam struktur sosial. Di sinilah buku ini menjadi sangat kontemporer: ia menghubungkan ecofeminism dengan per-juangan pribumi, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap bumi dan terhadap perempuan berakar dari ideologi yang sama — dominasi, pemisahan, dan eksploitasi. Mengutip penyair dan aktivis pribumi Joy Harjo, “The earth is not indifferent to our stories; she carries them in her bones.” Gilio-Whitaker menegaskan bahwa penyembuhan ekologis tidak mungkin tanpa penyembuhan gender dan spiritualitas.
Bab tentang Standing Rock menjadi inti emosional buku ini. Karena Standing Rock merupakan cermin kebangkitan solidaritas global. Gilio-Whitaker, yang ikut hadir di lokasi, menggambar-kan gerakan ini sebagai bentuk baru dari politik spiritual dan solidaritas global. Di Standing Rock, aktivisme lingkungan, spiritualitas adat, dan teknologi digital berpadu membentuk movement of movements. Hashtag #NoDAPL menjadi simbol perlawanan global terhadap ekstraktivisme. Namun ia juga mengingatkan: perjuangan Standing Rock bukan hanya tentang pipa minyak, tapi tentang hak menentukan nasib sendiri (sovereignty) dan decolonization of the environment. Ia menulis, “Environmental justice must be decolonized — it cannot be separated from the struggles for land and sovereignty.”
Penghubung Leluhur dan Identitas Spiritualnya.
Bab 7 — “Sacred Sites and Environmental Justice” ini membuka dengan kisah yang meng-guncang hati: perjuangan masyarakat Western Shoshone Nation di Nevada yang selama puluhan tahun menentang eksploitasi tambang emas dan uji coba nuklir di tanah leluhur mereka — tanah yang mereka sebut Newe Sogobia, wilayah suci yang diwariskan oleh pencipta. Di mata pemerintah Amerika Serikat, tanah itu hanyalah wilayah federal di bawah yurisdiksi Bureau of Land Management; namun bagi masyarakat Shoshone, tanah itu adalah tubuh spiritual mereka sendiri. “To destroy the land,” tulis Gilio-Whitaker, “is to destroy the people.” Dari tragedi inilah ia membuka pembahasan tentang hubungan antara situs-situs suci dan keadilan lingkungan, yang menurutnya menjadi jantung spiritual dari perjuangan masyarakat adat.
Gilio-Whitaker menegaskan bahwa situs suci (sacred sites) adalah konsep yang sering disalahpahami oleh dunia Barat modern. Dalam logika hukum Amerika Serikat, “situs suci” didefinisikan secara sempit sebagai “tempat ibadah” atau “lokasi ritual,” seperti gereja atau kuil. Tetapi dalam epistemologi masyarakat adat, seluruh lanskap adalah suci — gunung, sungai, padang rumput, bahkan batu dan hewan. Kesakralan tidak terbatas pada titik tertentu di peta, tetapi menyatu dengan tatanan kosmologis dan sejarah penciptaan. Karena itu, ketika tambang, bendungan, atau proyek militer menghancurkan tanah, masyarakat adat tidak sekadar kehilangan situs budaya; mereka kehilangan penghubung dengan leluhur dan identitas spiritualnya.
Dalam kerangka keadilan lingkungan arus utama, perlindungan terhadap situs suci sering direduksi menjadi isu “warisan budaya” (cultural resource management). Gilio-Whitaker mengkritik pendekatan ini karena mengubah kesakralan menjadi objek administratif. Ia menyebutnya sebagai bentuk “spiritual colonialism” — sebuah cara baru di mana negara mengatur bahkan dimensi spiritual masyarakat adat. Ia menulis: “The state decides what counts as sacred, defining Indigenous spirituality through bureaucratic procedures that are alien to Indigenous worldviews.” Salah satu contoh yang ia bahas adalah konflik di Bear Ears National Monument (Utah), kawasan yang disucikan oleh Navajo, Hopi, Ute, dan Zuni. Pemerintah federal sempat mencabut status perlindungan wilayah itu demi kepentingan eksploitasi minyak dan gas. Perlawanan masyarakat adat terhadap kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan melindungi situs suci adalah bagian integral dari perjuangan politik untuk kedaulatan. Bagi mereka, keadilan lingkungan hanya bisa terwujud bila hak untuk menentukan makna kesakralan dan cara melindunginya dikembalikan kepada komunitas adat sendiri.
Gilio-Whitaker juga menyoroti benturan epistemologis antara hukum Amerika yang berbasis sekularisme dengan cara pandang masyarakat adat yang holistik. Undang-undang seperti American Indian Religious Freedom Act (1978) atau National Historic Preservation Act tidak pernah benar-benar melindungi situs suci, karena hukum AS tidak mampu memahami spiritualitas sebagai sistem hidup yang menyatu dengan lingkungan. Ia mengutip seorang pemimpin Lakota yang berkata:
“You can’t protect a church by protecting only the altar; the whole mountain is the altar.”
Dalam bagian tengah bab, penulis mengaitkan isu situs suci dengan perlawanan di Standing Rock (2016), ketika masyarakat Sioux dan ribuan sekutu dari seluruh dunia menolak pem-bangunan pipa minyak Dakota Access Pipeline (DAPL). Situs suci seperti sungai Missouri dan tanah pemakaman leluhur menjadi titik fokus perlawanan. Gilio-Whitaker menyebut Standing Rock sebagai “a global moment of Indigenous resurgence”, ketika spiritualitas, ekologi, dan keadilan bersatu dalam satu arus besar perlawanan terhadap kolonialisme modern. Standing Rock, tulisnya, bukan sekadar protes terhadap pipa minyak, melainkan pernyataan kosmologis: “Water is life” (Mní Wičhóni).
Dari analisisnya, Gilio-Whitaker menegaskan bahwa gerakan keadilan lingkungan harus meng-akui dimensi spiritual dari tanah — sesuatu yang absen dalam paradigma sekuler modern. Ia menyebut perlindungan situs suci sebagai bentuk environmental justice of the spirit, yaitu keadilan yang mengakui bahwa manusia, alam, dan roh tidak bisa dipisahkan. “Sacred sites,” katanya, “are not about religion as the West defines it, but about the ecological continuity of being.”
Bab ini juga menggugah secara filosofis. Gilio-Whitaker mengutip pemikiran Vine Deloria Jr., seorang teolog Lakota yang menyatakan bahwa “spirituality in Native traditions is geography-based; to destroy the land is to erase the people’s memory of the divine.” Dalam konteks ini, penghancuran situs suci bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga kejahatan epistemik — penghancuran terhadap pengetahuan dan ingatan spiritual suatu bangsa.
Bab ini menggugah pembaca untuk melihat bahwa krisis ekologi global bukan hanya persoalan emisi dan teknologi, tetapi juga krisis spiritualitas manusia terhadap bumi. Di Indonesia, hal ini sangat relevan dengan konflik di kawasan adat seperti Pegunungan Kendeng, Wadon di Rembang, Tanah Papua, dan Lembah Kete Kesu di Tana Toraja, di mana proyek tambang, semen, dan wisata kerap mengabaikan kesucian tanah leluhur. Seperti masyarakat adat di Amerika, komunitas adat Indonesia juga memandang alam sebagai bagian dari roh kehidupan, bukan komoditas.
Filsuf Aljazair Malek Bennabi pernah menulis, “When man loses his spiritual relation to nature, he turns it into a machine.” Pandangan ini selaras dengan gagasan Gilio-Whitaker: bahwa dekolonisasi lingkungan memerlukan re-spiritualisasi cara kita memahami alam. Dalam Islam sendiri, konsep “amanah” dan “tawazun” (keseimbangan) menegaskan bahwa bumi adalah ciptaan yang suci dan harus dijaga sebagai bagian dari ibadah.
Kritik terhadap gerakan lingkungan arus utama
Gilio-Whitaker memberikan kritik tajam terhadap gerakan lingkungan di Amerika Serikat yang didominasi oleh orang kulit putih kelas menengah. Ia menunjukkan bagaimana organisasi seperti Sierra Club dan Greenpeace sering mengabaikan perspektif pribumi — memandang alam hanya sebagai objek pelestarian, bukan sebagai ruang kehidupan. “Konservasi tanpa dekolonisasi,” tulisnya, “adalah bentuk lain dari kolonialisme.”
Konsep environmental justice versi pribumi bukan hanya soal pencemaran udara atau air, tapi soal relasi spiritual, politik, dan sejarah kekuasaan. Dengan kata lain, keadilan lingkungan bagi masyarakat adat berarti mengembalikan hak atas tanah, bahasa, dan ingatan.
Gerakan itu seperti warisan kolonialisme dan kapitalisme ekstraktif. Dalam bab-bab selanjut-nya, Gilio-Whitaker menelusuri hubungan antara kolonialisme dan kapitalisme modern. Ia menyebutnya sebagai “extractive mindset” — cara berpikir yang melihat bumi sebagai tambang keuntungan. Pandangan ini, katanya, masih hidup hingga kini dalam bentuk industri energi fosil, agribisnis, dan bahkan proyek “hijau” yang menyingkirkan masyarakat adat dari wilayah mereka.
Mengutip Vandana Shiva, tokoh ekofeminis India: “The war against the earth is also a war against people.” Gilio-Whitaker menyadari bahwa krisis ekologis global saat ini adalah akibat langsung dari logika yang sama yang melahirkan kolonialisme: kerakusan tanpa batas, ketimpangan, dan pemisahan manusia dari ekosistemnya.
Buku ini memiliki gema kuat di Indonesia, negara dengan ribuan komunitas adat yang juga menghadapi perampasan lahan, tambang, dan deforestasi. Konflik di Standing Rock mencerminkan konflik di Papua, Kalimantan, atau Sulawesi — di mana proyek “pembangunan” sering menyingkirkan masyarakat adat dari wilayah leluhur mereka. Beberapa gerakan seperti masyarakat adat di Nusantara juga memperjuangkan hal yang sama: keadilan ekologis berbasis kedaulatan adat. Seperti yang dikatakan Emha Ainun Nadjib, “Tanah bukan hanya tempat kita berdiri, tapi tempat jiwa kita berakar.” Relevansi buku ini bagi Indonesia adalah pengingat bahwa pembangunan tanpa keadilan ekologis adalah bentuk kolonialisme baru.
Bagaimanakah kaitan antara gagasan decolonizing environmentalism (Dina Gilio-Whitaker) dengan tradisi pemikiran Islam tentang lingkungan — khususnya konsep khalīfah fi’l-arḍ (manusia sebagai penjaga/wakil di bumi) — dan praktik-praktik gerakan ekologi Islam kontemporer. Tentu saja ada hubungan gerakan pribumi, gerakan Islam progresif, dan aksi lingkungan di Indonesia.
Dari dekolonisasi lingkungan ke etika khalīfah: menyatukan dua wacana untuk bumi yang sembuh. Dekolonizing environmentalism menuntut perebutan kembali makna lingkungan dari narasi kolonial-ekstraktif: tanah bukan barang dagang, melainkan relasi, memori, dan identitas. Dina Gilio-Whitaker menegaskan bahwa untuk menyembuhkan alam kita harus membongkar warisan hukum, budaya, dan ekonomi yang membenarkan perampasan. Dalam konteks ini, gerakan pribumi menawarkan epistemologi alternatif — pengetahuan lokal, ritual penjagaan, tata kelola kolektif — yang bukan hanya teknis tetapi etis dan spiritual.
Dalam tradisi Islam, gagasan serupa hadir lewat konsep khalīfah fi’l-arḍ dan ajaran tentang amanah (kepercayaan). Al-Qur’an menyebut manusia sebagai khalifah (mis. QS al-Baqarah 2:30) — bukan pemilik absolut, melainkan wakil yang diberi tanggung jawab memelihara tatanan ciptaan. Amanah menegaskan batas: sumber daya adalah titipan yang harus dikelola untuk kebaikan generasi sekarang dan mendatang, bukan dieksploitasi untuk keuntungan singkat. Dengan demikian, etika Islam tradisional memberi dasar moral kuat untuk praktik penjagaan ekologis yang sejalan dengan dekolonisasi.
Keduanya — dekonstruksi kolonial dan etika khalīfah — bertemu di ruang penting: penolakan terhadap logika kepemilikan privat absolut. Kolonialisme melegalkan pengkapitalan tanah dan hak untuk mengekstrak. Banyak teks klasik Islam menekankan pembatasan kepemilikan dan tanggung jawab sosial; misalnya literatur fiqh (hukum Islam) dan maqāṣid al-sharīʿah yang menempatkan pemeliharaan nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan. Di tangan gerakan Islam progresif, gagasan ini dapat dipakai untuk merumuskan hukum dan kebijakan lingkungan yang menempatkan publik dan alam di atas akumulasi individu.
Praktik kontemporer — yang disebut ecological Islam atau Green Islam — menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini dioperasionalisasikan: fatwa lingkungan, pengelolaan wakaf untuk konservasi, penguatan wakaf tanah untuk hutan lindung, pendidikan madrasah tentang etika lingkungan, dan inisiatif komunitas berbasis masjid yang mengelola sampah atau lahan hijau. Gerakan semacam ini memperlihatkan bahwa agama dapat menjadi motor moral kolektif untuk tindakan ekologis yang adil, bukan alat legitimasi eksploitasi.
Menghubungkan dekonstruksi kolonial dan ekologi Islam melahirkan beberapa titik sinergi praktis: (a) legitimasi moral-agama untuk restitusi tanah adat dan perlindungan kawasan sakral; (b) kerangka hukum berbasis nilai (shariah informed policy) yang mendorong keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pemeliharaan alam; (c) dukungan komunitas agama untuk praktik-praktik agroekologi, sistem pangan lokal, dan kedaulatan pangan; (d) pendidikan interkultural yang menempatkan pengetahuan ilmiah dan lokal berdampingan.
Di Indonesia, sinergi ini relevan dan strategis. Negara memiliki tradisi hukum adat (adat), agama yang kuat, dan komunitas sipil yang aktif. Beberapa langkah konkret bisa ditempuh: Pengakuan legal wilayah adat: mempercepat sertifikasi adat dan hak kelola untuk mencegah konversi lahan; ini sejalan dengan amanah dan kewajiban merawat tanah. Wakaf ekologis: memfasilitasi wakaf lahan untuk konservasi hutan dan sumber air; ulama dan ormas dapat mempromo-sikannya sebagai ibadah kolektif. Kurikulum gabungan: memasukkan pendidikan lingkungan berbasis nilai (khalīfah/amanah) di pesantren, madrasah, dan sekolah umum, serta integrasi pengetahuan adat. Dialog antar-gerakan: membangun forum bersama antara AMAN (gerakan adat), organisasi Islam progresif, dan kelompok lingkungan untuk pengawalan kasus-kasus konkret (mis. menentang tambang, menolak perampasan sawit, mempromosikan restorasi lahan).
Tantangan nyata: ada risiko cooptation — mis. retorika “hijau” dipakai untuk menjustifikasi proyek besar; otoritas keagamaan koopted untuk mendukung investor; atau konflik antar-komunitas terkait prioritas pembangunan. Maka mekanisme akuntabilitas harus kuat: transparansi, pemetaan partisipatif, konsultasi bebas-pribadi-terinformasi (FPIC), dan perlindungan hukum untuk pemimpin sosial yang menghadapi intimidasi.
Dari sisi etika, perpaduan ini menuntut rejig nilai: dari konsumsi ke cukup, dari dominasi ke perawatan, dari kepemilikan ke penjagaan. Ia menuntut perubahan narasi — bahwa pem-bangunan bukan ukuran kebahagiaan mutlak, melainkan keseimbangan hidup bersama. Pesan moralnya kuat: merawat bumi adalah ibadah kolektif. Dalam kata-kata sederhana: menjaga rumput yang masih tumbuh berarti menjaga masa depan anak cucu.
Catatan Akhir: Politik Moral untuk Bumi yang Terluka
Buku ini ditutup dengan gambaran yang sangat pribadi: Dina Gilio-Whitaker menceritakan perjalanannya menghadiri Standing Rock encampment—perkemahan perlawanan masyarakat Sioux terhadap pembangunan Dakota Access Pipeline pada 2016 (Bab 8 — “Ways Forward for Environmental Justice in Indian Country”). Ia menggambarkan suasana yang “lebih dari sekadar protes”: api suci yang terus menyala di tengah padang luas Dakota, doa yang mengiringi setiap langkah demonstran, dan solidaritas lintas ras dan bangsa yang belum pernah terjadi sebelum-nya. Ia menulis, “It was a moment when the world glimpsed what Indigenous environmental justice looks like — not as theory, but as lived resistance.”
Dari pengalaman itu, Gilio-Whitaker mengajak pembaca untuk merenungkan arah ke depan bagi perjuangan keadilan lingkungan di wilayah adat (Indian Country). Ia menegaskan bahwa langkah ke depan tidak bisa hanya melalui jalur hukum, kebijakan publik, atau reformasi administratif, melainkan harus melibatkan rekonstruksi paradigma — dari cara dunia me-mandang tanah, air, dan relasi manusia dengan alam. Menurutnya, keadilan lingkungan sejati hanya mungkin bila dunia mengakui kedaulatan epistemologis dan spiritual masyarakat adat.
Dalam bagian awal bab ini, Gilio-Whitaker menyoroti kelemahan pendekatan keadilan lingkung-an (Environmental Justice Movement) arus utama yang masih berakar pada paradigma kolonial. Gerakan itu, katanya, “berusaha memperbaiki sistem yang pada dasarnya sudah rusak.” Ia menulis: “Environmental justice must not be about inclusion into the existing system, but about transforming the system itself.”
Oleh karena itu, ia mengusulkan pendekatan dekolonial, yang berpusat pada pemulihan (restoration) dan rekonsiliasi antara manusia dan bumi. Dekolonisasi, dalam konteks ini, tidak hanya berarti pembalikan kekuasaan politik, melainkan juga pembebasan cara berpikir — membebaskan dunia dari pandangan bahwa alam hanyalah sumber daya.
Gilio-Whitaker memperkenalkan konsep yang ia sebut “Indigenized Environmental Justice.” Pendekatan ini menekankan tiga prinsip utama:
- Sovereignty (Kedaulatan) – pengakuan atas hak masyarakat adat untuk menentukan kebijakan lingkungan di tanah mereka sendiri.
- Relationality (Keterhubungan) – kesadaran bahwa manusia dan alam adalah bagian dari satu jaringan kehidupan.
- Responsibility (Tanggung jawab spiritual dan sosial) – kesadaran etis untuk menjaga keberlanjutan bagi tujuh generasi ke depan, seperti pepatah Haudenosaunee: “In every deliberation, we must consider the impact on the seventh generation.”
Dalam membangun masa depan keadilan lingkungan di Indian Country, Gilio-Whitaker juga menyoroti pentingnya pendidikan dan epistemologi adat. Ia menulis bahwa sistem pendidikan kolonial telah memisahkan manusia dari alam dan menanamkan ilusi kontrol atas bumi. Sebaliknya, masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan ekologis tradisional (Traditional Ecological Knowledge / TEK) yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan. Ia menulis:
“Indigenous knowledge systems offer not nostalgia, but pathways to ecological survival in a world on fire.”
Ia juga menyoroti bagaimana perubahan iklim memperparah ketidakadilan yang sudah lama ada. Banyak komunitas adat berada di garis depan krisis iklim—terkena banjir, kekeringan, atau kehilangan habitat. Namun, mereka seringkali tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputus-an global. Gilio-Whitaker menyerukan agar keadilan iklim dan keadilan lingkungan digabung-kan dalam kerangka yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Dalam pandangan-nya, setiap solusi terhadap krisis iklim yang mengabaikan kedaulatan adat hanyalah reproduksi kolonialisme dengan wajah hijau.
Menariknya, Gilio-Whitaker tidak berhenti pada kritik. Ia juga menampilkan contoh konkret dari gerakan masyarakat adat yang berhasil menciptakan model keadilan lingkungan alternatif — seperti Yurok Tribe di California yang mengembalikan pengelolaan sungai Klamath dan reforestasi dengan sistem berbasis adat, atau Lummi Nation yang melawan polusi industri di perairan leluhur mereka. Semua itu menunjukkan bahwa solusi ekologis yang paling efektif sering datang dari masyarakat yang paling terpinggirkan.
Di bagian penutup, Gilio-Whitaker menyampaikan refleksi filosofis: bahwa masa depan bumi bergantung pada kemampuan umat manusia untuk belajar kembali dari masyarakat adat. Ia menulis, “Decolonization is not a metaphor; it is a practice of re-learning how to live in good relation with the Earth.”
Bagi Gilio-Whitaker, harapan bukanlah kata kosong. Ia mengajak pembaca untuk melihat Standing Rock bukan sebagai akhir perjuangan, tetapi sebagai awal dari kebangkitan global: kebangkitan kesadaran bahwa melindungi bumi adalah tindakan politik sekaligus spiritual. Ia menutup dengan kalimat yang menggema: “As long as grass grows and rivers flow, the struggle for Indigenous justice will continue — for in that struggle lies the future of us all.”
Gagasan Gilio-Whitaker sangat relevan di tengah krisis ekologis dan spiritual global. Dunia kini menghadapi paradoks: semakin maju teknologi hijau, semakin dalam jurang ketimpangan dan perampasan sumber daya. Indonesia, dengan kekayaan ekologinya, menghadapi tantangan serupa: ekspansi tambang nikel, sawit, dan pembangunan infrastruktur “hijau” sering meng-orbankan masyarakat adat dan ekosistem suci.
Seperti perjuangan masyarakat Sioux di Standing Rock, masyarakat Dayak di Kalimantan, Suku Wadon di Rembang, dan masyarakat Malind di Papua juga memperjuangkan hak hidup dan spiritualitas tanah mereka. Gagasan Indigenized Environmental Justice dapat menjadi inspirasi untuk membangun kebijakan ekologi berbasis kedaulatan lokal di Indonesia — bukan sekadar melindungi hutan, tetapi juga menghormati jiwa yang hidup di dalamnya. Dalam refleksi filosofis, pemikiran Gilio-Whitaker sejalan dengan pesan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, yang mengatakan bahwa “tanah adalah amanah; barang siapa mengkhianatinya, mengkhianati fitrah dirinya sendiri.” Ini menegaskan bahwa keadilan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari keadilan spiritual dan moral.
Menggabungkan dekonstruksi kolonial dengan etika khalīfah bukan sekadar latihan teoritis: ia menawarkan peta praktis untuk membangun gerakan lingkungan yang adil, bermartabat, dan berakar pada nilai lokal. Di Indonesia, pelibatan ulama, adat, ilmuwan, dan aktivis lingkungan dapat menegaskan bahwa perlawanan terhadap ekstraktivisme adalah jihad etis — sebuah perjuangan kolektif untuk melindungi amanah Tuhan bagi generasi mendatang.
Di akhir bukunya, Gilio-Whitaker menyerukan visi masa depan yang ia sebut “decolonizing environmentalism.” Ia percaya bahwa dunia yang berkelanjutan tidak akan lahir dari teknologi semata, melainkan dari transformasi nilai: dari dominasi menuju hubungan, dari kepemilikan menuju penjagaan. Ia menulis dengan nada puitis, “The earth has always remembered us. The question is, will we remember her?”
Pesan ini sangat relevan untuk dunia yang sedang terbakar oleh krisis iklim dan ketimpangan global. Seperti yang pernah dikatakan oleh penyair Sufi Jalaluddin Rumi, “The wound is the place where the light enters you.”
Dari luka kolonialisme, kita bisa menemukan cahaya baru — kesadaran bahwa penyembuhan planet ini harus dimulai dari penyembuhan relasi manusia dengan bumi.
Menuju masa depan yang dekolonial.
Bogor, 6 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Gilio-Whitaker, D. (2019). As Long as Grass Grows: The Indigenous Fight for Environmental Justice, from Colonization to Standing Rock. Beacon Press.
Harjo, J. (2019). An American Sunrise. W. W. Norton & Company.
Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. South End Press.
Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. Grove Press.
Rumi, J. (1995). The Essential Rumi. Translated by Coleman Barks. HarperOne.
Nadjib, E. A. (2006). Tanah dan Manusia. Kompas.
Deloria Jr., V. (1994). God Is Red: A Native View of Religion. Golden, CO: Fulcrum Publishing.
Simpson, L. B. (2017). As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Al-Jilani, A. Q. (n.d.). Futuh al-Ghaib. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Bennabi, M. (1959). The Question of Culture (Problème de la Culture). Paris: Seuil.