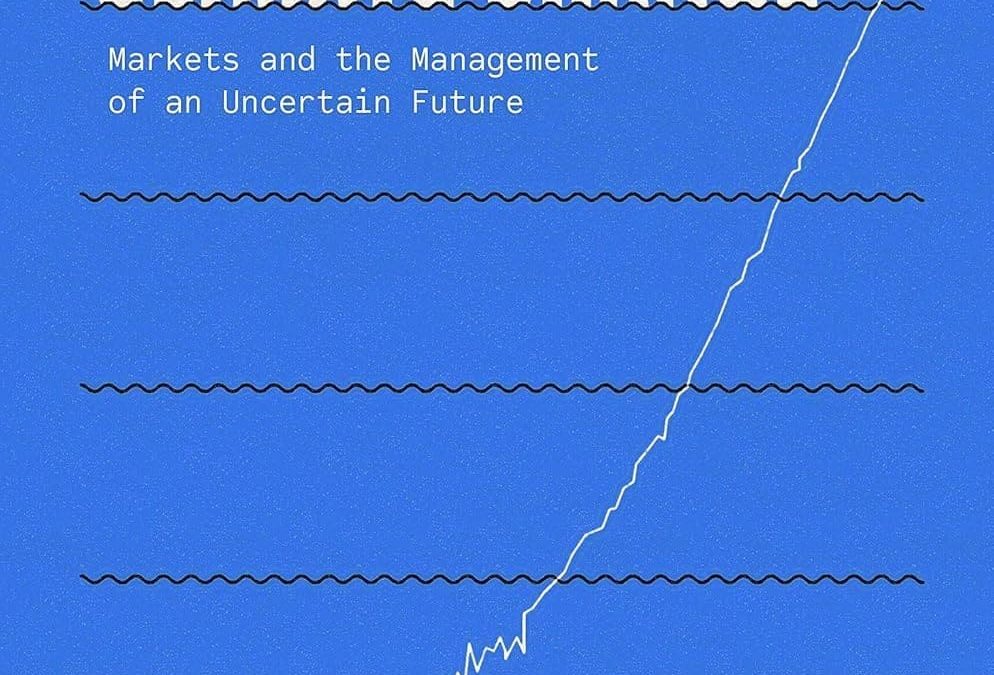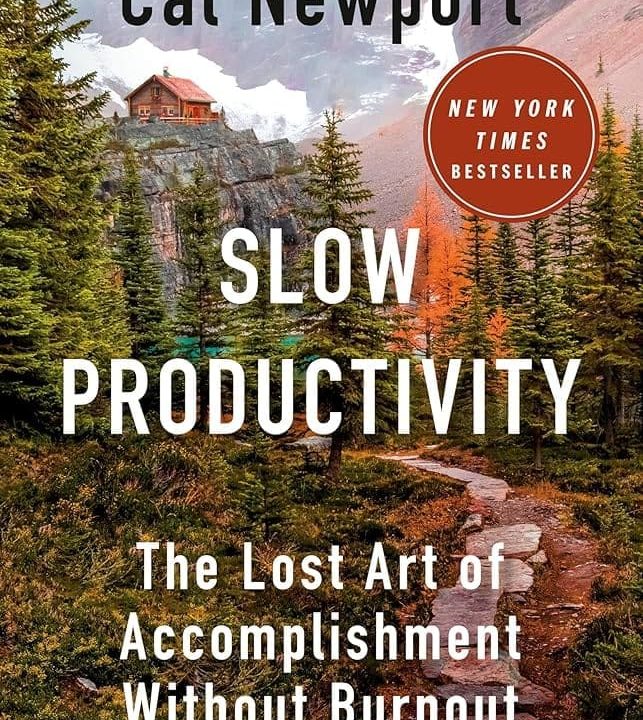Rubarubu #70
Adapting to Climate Change:
Beradapatasi dengan Ketidakpastian
Sebuah Kota di Musim Panas
Bayangkan pagi yang terik di sebuah kota besar tropis. Suhu mencapai rekor, gelombang panas menyelimuti jalanan, dan pedagang kaki lima berusaha melayani pelanggan meskipun panas terasa menekan. Di tengah kota, seorang warga berpikir untuk pindah ke daerah pegunungan yang lebih sejuk—tetapi ia juga menimbang biaya kerja yang jauh, sekolah anak, serta biaya hunian. Pilihan sederhana tentang di mana kita hidup kini terpengaruh oleh perubahan iklim. Ini bukan fiksi.
Sama halnya kisah keluarga di pesisir semarang. Di sebuah permukiman di pesisir Semarang, seorang ayah bernama Budi menyaksikan air laut yang semakin sering menggenangi teras rumahnya. Setiap tahun, genangan itu semakin tinggi dan lama surutnya. Tetangganya memilih untuk pindah, tapi Budi—yang mewarisi rumah itu dari orangtuanya—bertekad bertahan. Dengan tabungannya yang tak seberapa, ia meninggikan lantai rumah, memasang pompa air, dan beralih dari beternak ayam yang sering mati akibat panas ekstrem ke budidaya ikan bandeng yang lebih tahan suhu tinggi. Keputusannya bukan didasari oleh pemahaman ilmiah tentang perubahan iklim, melainkan oleh naluri bertahan hidup dan kalkulasi ekonomi sederhana. Kisah adaptasi lokal inilah yang menjadi jantung dari buku Matthew E. Kahn—sebuah argumen bahwa di tengah ketidakpastian iklim, manusia sebagai pelaku ekonomi akan secara spontan mengembangkan mekanisme adaptasi melalui insentif pasar dan inovasi teknologi.
Dalam Adapting to Climate Change: Markets and the Management of an Uncertain Future (Yale University Press, 2021), Matthew E. Kahn menggambarkan bagaimana perubahan iklim bukan hanya tentang suhu yang meningkat, tetapi tentang bagaimana pilihan sehari-hari manusia—tempat tinggal, pekerjaan, makanan, investasi—akan berubah secara fundamental karena iklim yang berubah. Buku ini tidak hanya bicara tentang mitigasi emisi, tetapi menggali esensi adaptasi: bagaimana pasar, pilihan individu, dan kebijakan dapat membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan masa depan yang tidak pasti. sustainability.unesco-floods.eu
“Why Adaptation?” tulis Kahn. Ia memulai dengan premis sederhana namun kuat: meskipun dunia bergerak lambat dalam mitigasi emisi karbon, perubahan iklim sudah berlangsung dan dampaknya akan terus terasa. Dengan pendekatan ekonomi mikro, ia menekankan bahwa adaptasi bukan pilihan opsional—ia adalah keniscayaan bila manusia ingin mempertahankan kualitas hidup dalam dunia yang lebih panas, lebih basah, atau lebih kering. Adaptasi berarti tidak hanya bertahan dari bencana akhir seperti badai atau banjir, tetapi menyesuaikan keputusan ekonomi harian: di mana kita tinggal, apa yang kita tanam, bagaimana kita membangun infrastruktur dan memilih investasi. sustainability.unesco-floods.eu
Kahn mengkritik pendekatan konvensional di ilmu ekonomi iklim yang sering kali mencoba mengukur dampak masa depan berdasarkan data masa lalu tanpa mempertimbangkan bahwa manusia selalu merespons insentif dan beradaptasi. Misalnya, ketika suhu naik, permintaan terhadap teknologi pendingin seperti air conditioning meningkat, mendorong inovasi dan penurunan biaya — yang pada gilirannya membuat adaptasi lebih mudah bagi lebih banyak orang. Pendekatan semacam ini menantang klaim bahwa hubungan antara perubahan iklim dan kesejahteraan ekonomi bersifat statis. Independent Institute
Dalam bab pembuka ini, Kahn juga menekankan bahwa adaptasi terjadi sekaligus di berbagai level: individu, pasar, dan pemerintahan. Individu memilih lokasi tinggal, pasar memandu investasi infrastruktur, dan kebijakan mengatur insentif ekonomi. Adaptasi tidak hadir sebagai solusi tunggal—melainkan rangkaian keputusan yang saling memengaruhi antara perilaku ekonomi dan kondisi lingkungan yang berubah. sustainability.unesco-floods.eu
Ekonomi Mikro dan Keputusan Individu
Kahn memanfaatkan kerangka microeconomics untuk menjelaskan bahwa keputusan adaptasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang perilaku ekonomi individu yang responsif terhadap insentif dan risiko. Misalnya, ketika ancaman gelombang panas meningkat, rumah dengan air conditioning menjadi lebih bernilai—sebuah ilustrasi bahwa pasar akan menyesuaikan harga dan permintaan berdasarkan kondisi iklim baru. Independent Institute
Kahn membangun kerangka teoritis yang menempatkan adaptasi sebagai proses dinamis yang dipandu oleh sinyal harga dan insentif ekonomi. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berfokus pada mitigasi, Kahn berargumen bahwa “adaptasi adalah investasi dalam ketahanan yang menghasilkan return ekonomi nyata”. Buku ini memperkenalkan konsep “urban climate resilience premium“—nilai tambah yang diperoleh kota-kota yang berhasil beradaptasi terhadap guncangan iklim. Ekonom Indonesia, Prof. Emil Salim, telah lama mengadvokasi pendekatan serupa melalui konsep “ekonomi hijau yang adaptif” yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan lingkungan.
Buku ini juga mengulas pentingnya peningkatan infrastruktur publik dalam menghadapi perubahan iklim. Kahn menunjukkan bahwa investasi publik dalam infrastruktur tahan iklim—mulai dari drainase kota hingga sistem listrik pintar—bukan sekadar biaya, tetapi cara untuk mengurangi biaya jangka panjang dari kerusakan akibat iklim ekstrem. Catatan para peninjau menyebutkan bahwa penekanan Kahn pada pentingnya perencanaan infrastruktur menghadirkan keseimbangan antara pasar dan peran pemerintah. sustainability.unesco-floods.eu
Sebagai solusinya, Kahn mengusulkan serangkaian kebijakan yang secara khusus dirancang untuk membangun ketahanan iklim bagi masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya “jaring pengaman sosial yang pro-aktif dan responsif iklim”, yang dapat berupa bantuan tunai bersyarat, asuransi tanaman dengan premi terjangkau, atau program padat karya untuk membangun infrastruktur adaptasi. Kahn juga menganjurkan investasi publik dalam “infrastruktur pelindung”seperti pertahanan banjir, sistem peringatan dini, dan penyediaan air bersih di daerah rawan kekeringan, yang manfaatnya paling dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah. Inti dari argumennya adalah bahwa “melindungi kaum miskin dari dampak iklim bukan hanya imperatif moral, tetapi juga investasi ekonomi yang cerdas”, karena pemulihan dari bencana akan jauh lebih mahal daripada pencegahan, dan masyarakat yang tangguh adalah fondasi bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Misalnya dia menganalisis bagaimana pasar properti merespons risiko iklim melalui pe-nyesuaian harga dan pola permintaan. Kahn menunjukkan bahwa properti di daerah rawan banjir atau kenaikan muka air laut mengalami “climate discount” yang semakin besar, semen-tara properti di daerah dengan infrastruktur adaptasi yang baik memperoleh “resilience premium”. “Harga properti adalah thermometer sosial yang mengukur persepsi risiko iklim,” tulis Kahn. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam perbedaan harga properti di Jakarta Utara yang rawan banjir dengan daerah yang lebih aman seperti Jakarta Selatan.
Bab kelima membahas peran pemerintah dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung adaptasi. Kahn mengkritik kebijakan yang menciptakan “moral hazard” seperti asuransi banjir bersubsidi yang justru mendorong orang tetap tinggal di daerah rawan. “Peran pemerintah bukanlah melindungi orang dari konsekuensi pilihan lokasi mereka, tetapi me-nyediakan informasi dan infrastruktur yang memungkinkan adaptasi yang efisien,” paparnya. Untuk Indonesia, ini berarti perlu reformasi kebijakan tata ruang dan penghentian subsidi yang distortif terhadap sinyal harga.
Perlindungan terhadap Ketidaksetaraan dan Kemiskinan
Adaptasi juga memiliki dimensi distribusi sosial: dampak iklim sering kali tidak merata, terutama terhadap komunitas miskin yang memiliki sedikit pilihan lokasi atau sumber daya. Kahn menyoroti bahwa kebijakan adaptasi yang baik perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan, termasuk program asuransi risiko iklim dan kebijakan hunian yang adil. sustainability.unesco-floods.eu
Kahn melemparkan kritik bahwa kerangka hukum dan regulasi yang ada justru menjadi peng-hambat utama dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Kahn berargumen bahwa banyak peraturan zonasi, bangunan, dan tata ruang didasarkan pada kondisi iklim masa lalu yang sudah tidak relevan, sehingga menghalangi inovasi dan respons yang lincah. Contohnya, peraturan bangunan pantai yang tidak memperhitungkan kenaikan muka air laut, atau kebijakan asuransi yang mendorong pembangunan kembali di daerah rawan bencana. Kahn menyebut ini se-bagai “regulatory inertia” yang berbahaya. Ia menekankan bahwa kita membutuhkan per-geseran dari pendekatan “static regulation” menuju “adaptive governance”—sistem regulasi yang dinamis, fleksibel, dan mampu belajar dari perubahan kondisi. Prinsip ini sangat relevan bagi Indonesia, di mana revisi terhadap RTRW dan peraturan bangunan di daerah pesisir mendesak untuk dilakukan.
Sebagai solusi, Kahn mengusulkan reimajinasi total terhadap sistem regulasi dengan menerapkan prinsip-prinsip “adaptive law”. Ini mencakup pengembangan mekanisme yang memungkinkan regulasi menyesuaikan diri secara otomatis berdasarkan data iklim real-time, seperti standar bangunan yang secara progresif menuntut ketahanan lebih tinggi seiring memburuknya iklim. Selain itu, ia menganjurkan peralihan dari pendekatan “command-and-control” ke sistem berbasis insentif, seperti keringanan pajak untuk properti yang menerapkan fitur adaptasi, atau premi asuransi yang lebih murah untuk daerah yang telah berinvestasi dalam infrastruktur pelindung. Inti argumen Kahn adalah bahwa “hukum harus menjadi katalis untuk inovasi adaptasi, bukan penghalang”. Dengan mendorong eksperimen di tingkat lokal dan memfasilitasi pembelajaran cepat, kerangka hukum dapat bertransformasi dari sekadar pembatas menjadi alat yang proaktif membangun ketahanan.
Kahn mengakui bahwa kapasitas adaptasi tidak terdistribusi merata. Masyarakat miskin dan rentan memiliki “adaptive capacity gap” yang membuat mereka lebih sulit beradaptasi. “Perubahan iklim memperlebar ketimpangan karena yang kaya punya lebih banyak sumber daya untuk beradaptasi,” tulisnya. Di Indonesia, ini terlihat dalam kontras antara adaptasi mewah di kompleks-kompleks elit dengan keterbatasan adaptasi di permukiman kumuh pesisir.
Kahn menganalisis tajam tentang bagaimana masyarakat miskin menanggung beban terberat dari perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi global paling minimal. Kahn menjelaskan bahwa kemiskinan membatasi “kapasitas adaptasi” (adaptive capacity)—sumber daya finansial, akses terhadap teknologi, jaringan sosial, dan mobilitas geografis—yang dibutuh-kan untuk merespons guncangan iklim. Seorang petani gurem di Nusa Tenggara Timur, misal-nya, tidak memiliki tabungan untuk membeli sistem irigasi tetes ketika musim kemarau memanjang, atau asuransi untuk menutup kerugian ketika panen gagal. Kahn menekankan bahwa “perubahan iklim memperdalam ketidakadilan yang sudah ada”, karena kelompok rentan sering tinggal di daerah yang paling berisiko, seperti pemukiman kumuh di bantaran sungai atau daerah pesisir yang rawan banjir rob, tanpa memiliki sarana untuk pindah atau melindungi diri.
Dipaparkan bagaimana pola migrasi manusia sebagai respons terhadap perubahan iklim. Kahn memprediksi munculnya “climate havens”—wilayah-wilayah yang justru diuntungkan oleh perubahan iklim karena menjadi tujuan migrasi. “Manusia akan memilih pindah ke tempat yang menawarkan kualitas hidup lebih baik dalam kondisi iklim baru,” paparnya. Untuk Indonesia, ini berarti potensi migrasi dari daerah rawan kekeringan di NTT ke wilayah dengan ketersediaan air lebih baik, atau dari kota pesisir yang tenggelam ke kota-kota dataran tinggi.
Kahn membahas adaptasi sistem pangan dan air dalam menghadapi iklim yang tidak menentu. Kahn menunjukkan bagaimana teknologi irigasi presisi, budidaya tahan kekeringan, dan manajemen sumber air terintegrasi menjadi investasi kritis. “Air adalah mata uang baru dalam ekonomi adaptasi,” simpulnya. Untuk Indonesia yang menghadapi ancaman krisis pangan akibat pola hujan yang berubah, investasi dalam riset pangan adaptif menjadi kebutuhan mendesak.
Bab penutup menawarkan visi tata kelola adaptasi yang kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kahn menekankan pentingnya “polycentric governance” dimana berbagai aktor pada tingkat berbeda berkoordinasi dalam mengelola risiko iklim. “Tidak ada solusi one-size-fits-all untuk adaptasi; yang dibutuhkan adalah ekosistem solusi yang beragam dan saling melengkapi,”tutupnya. Cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. M. Amin Abdullah, menekankan bahwa “adaptasi adalah bagian dari konsep istislah (kemaslahatan umum) dalam Islam”.
Kritik dan Apresiasi:
Ekonom lingkungan Prof. Robert Mendelsohn memuji buku ini sebagai “kontribusi penting yang mengisi kekosongan literatur tentang ekonomi adaptasi”. Namun, kritikus seperti Dr. Naomi Klein memperingatkan bahwa “pendekatan berbasis pasar bisa mengabaikan keadilan klimatik dan mengubah adaptasi menjadi komoditas mewah”. Untuk konteks Indonesia, buku ini memberikan kerangka berharga untuk merancang kebijakan adaptasi yang memanfaatkan mekanisme pasar tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Penggunaan Big Data dan Teknologi untuk Adaptasi
Salah satu ide penting dalam buku ini adalah bagaimana big data dan teknologi modern dapat mendukung adaptasiiklim—seperti prediksi kebutuhan air atau energi, pemantauan ancaman, serta optimasi operasi pertanian dalam kondisi baru yang tidak stabil. Big data dapat membantu meringankan kekurangan informasi dan memperbaiki penilaian risiko dalam skala besar. sustainability.unesco-floods.eu
Kahn mendokumentasikan munculnya “adaptation economy”—ekosistem bisnis dan inovasi yang khusus mengembangkan solusi adaptasi iklim. Dari teknologi pertanian tahan kekeringan hingga sistem peringatan dini banjir, Kahn menunjukkan bagaimana mekanisme pasar mendorong inovasi-inovasi ini. “Krisis iklim menciptakan pasar baru bagi para innovator dan entrepreneur,” tegasnya. Di Indonesia, startup seperti Igora yang mengembangkan teknologi pemantauan sungai atau eFishery yang menciptakan solusi akuakultur adaptif merupakan contoh nyata tren ini.
Buku Kahn memberikan pandangan yang berbeda dari fokus dominan pada mitigasi emisi — bahwa adaptasi adalah kunci untuk masa depan yang tidak pasti. Dalam perspektif IPCC, adaptasi berarti “proses penyesuaian terhadap perubahan iklim yang ada atau diharapkan untuk mengurangi kerugian dan memanfaatkan peluang” — termasuk di sektor infrastruktur, kebijakan, perilaku, dan ekosistem sosial. Wikipedia
Kahn menekankan bahwa tanpa adaptasi, kerugian ekonomi dan sosial bisa meningkat drastis ketika suhu, pola curah hujan, dan kejadian ekstrem berubah cepat. Namun dengan adaptasi yang efektif—melalui pasar, inovasi teknologi, dan kebijakan yang responsif—masyarakat dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial mereka terhadap kejutan iklim baru. sustainability.unesco-floods.eu Pendekatan ini penting secara global karena tidak semua negara bisa menerapkan strategi mitigasi ambisius dengan sumber daya yang sama. Negara berkembang, terutama di wilayah tropis dan pesisir, menghadapi kebutuhan adaptasi yang mendesak, seperti pembangunan sistem peringatan dini, perbaikan sistem air, atau relokasi pemukiman. Wikipedia
Di Indonesia, realitas iklim sudah melampaui sekedar teori. Banjir besar, kekeringan berulang, serta perubahan pola musim sudah mengubah cara hidup masyarakat di banyak daerah. Konsep adaptasi yang dibahas Kahn sangat relevan: keputusan individu (misalnya pindah lokasi), pasar (pengembangan teknologi irigasi hemat air), dan kebijakan publik (infrastruktur tahan iklim, zonasi lahan, sistem asuransi risiko iklim) semuanya menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan Indonesia.
Selain itu, masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia mempertegas poin Kahn tentang distribusi dampak iklim yang tidak merata: warga miskin di dataran rendah atau pesisir menghadapi risiko lebih tinggi tanpa banyak pilihan adaptasi, sementara kelas menengah memiliki lebih banyak ruang manuver ekonomi. Oleh karena itu, strategi adaptasi yang sensitif terhadap ketidaksetaraan—melalui bantuan pemerintah, sistem proteksi sosial, dan peningkatan kapasitas lokal—sangat penting untuk menjaga kesejahteraan bersama. Wikipedia
Narasi Kahn tentang adaptasi mengingatkan pada gagasan Julian Simon, seorang ekonom yang optimis tentang peran human capital dan inovasi dalam menghadapi tantangan sumber daya—bahwa sumber daya sejati adalah ide manusiayang terus berkembang. PERC Dalam konteks spiritual atau filosofis, gagasan tentang adaptasi menggaungkan prinsip iman untuk bertindak dalam ketidakpastian—bahwa manusia tidak hanya harus berusaha memahami dunia, tetapi harus menyesuaikan perilaku dan pilihan berdasarkan realitas yang berubah, serupa dengan konsep tawakkul dalam tradisi muslim yang menekankan usaha terbaik dalam batas kemampuan sambil menerima ketidakpastian masa depan.
Perubahan iklim akhirnya membawa kita ke medan yang paling purba sekaligus paling modern: ladang pangan. Dalam bab tentang Innovation in Agricultural Production, Kahn—bersama Brian Casey dan Nolan Jones—mengajak pembaca menyusuri sejarah panjang bagaimana manusia selalu beradaptasi terhadap alam melalui pertanian, tetapi kini dengan skala tantangan yang jauh lebih besar. Iklim yang tidak stabil mengubah pola hujan, memperpendek atau memperpanjang musim tanam, dan meningkatkan frekuensi gagal panen. Namun alih-alih menggambarkan pertanian sebagai korban pasif, bab ini memotret petani sebagai aktor inovatif.
Kahn menceritakan bagaimana varietas tanaman yang tahan panas, kekeringan, atau salinitas berkembang melalui riset genetika modern. Ia menyinggung praktik precision agriculture—sensor tanah, data satelit, dan algoritma prediktif—yang memungkinkan petani menyesuaikan pemupukan dan irigasi secara presisi, bukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun semata. Di sini, adaptasi bukan berarti kembali ke masa lalu yang “alami”, tetapi justru bergerak maju melalui teknologi, pengetahuan, dan pembelajaran kolektif. Petani yang mampu mengakses informasi dan inovasi menjadi lebih tangguh; sementara yang terisolasi dari pasar, modal, dan pengetahuan akan semakin rentan. Pertanian, dalam kerangka Kahn, menjadi cermin ketimpangan adaptasi: siapa yang punya akses, dan siapa yang tidak.
Narasi ini kemudian melebar ke panggung dunia. Dalam bab Globalization and International Trade Facilitate Adaptation, Kahn menolak pandangan bahwa globalisasi semata-mata memperparah krisis iklim. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa perdagangan internasional adalah salah satu mekanisme adaptasi paling kuat yang pernah dimiliki umat manusia. Ketika satu wilayah mengalami kekeringan atau gagal panen, pasokan pangan dapat dialihkan dari wilayah lain. Ketika suhu ekstrem membuat produksi lokal mahal atau tidak efisien, pasar global menyediakan alternatif.
Kahn mengilustrasikan bagaimana keterbukaan perdagangan memungkinkan negara-negara menyesuaikan struktur ekonominya terhadap iklim yang berubah: wilayah yang makin panas beralih dari pertanian intensif ke sektor jasa atau industri ringan; wilayah yang relatif stabil menjadi lumbung pangan atau pusat produksi. Dalam cerita ini, kapal kargo, rantai pasok global, dan perjanjian dagang bukan sekadar simbol kapitalisme, tetapi infrastruktur adaptasi iklim yang tak kasatmata. Proteksionisme, sebaliknya, justru meningkatkan kerentanan—membuat masyarakat terjebak pada kondisi lokal yang semakin tidak bersahabat.
Namun Kahn tidak menutup mata terhadap sisi gelap globalisasi. Ia mengakui bahwa perdagangan hanya membantu adaptasi jika disertai institusi yang adil, perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan sosial. Tanpa itu, manfaat adaptasi terakumulasi di segelintir pihak, sementara kelompok miskin tetap terpapar risiko iklim. Di sini, pasar bukan dewa penyelamat otomatis, tetapi alat—yang hasilnya ditentukan oleh tata kelola.
Semua benang pemikiran ini akhirnya disimpulkan dalam bagian penutup: Human Capital Fuels Adaptation. Jika ada satu tesis normatif yang ingin ditegaskan Kahn, maka inilah intinya. Bukan teknologi semata, bukan pasar semata, dan bukan kebijakan semata yang menentukan kemampuan adaptasi manusia—melainkan kualitas manusia itu sendiri. Pendidikan, kesehatan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, dan mobilitas sosial adalah sumber daya adaptasi paling mendasar.
Kahn menggambarkan masa depan di mana manusia akan hidup di dunia yang lebih panas dan lebih tidak pasti. Dalam dunia seperti itu, orang yang mampu belajar cepat, berpindah lokasi, mengganti pekerjaan, dan menyerap teknologi baru akan lebih bertahan dibanding mereka yang terjebak dalam kemiskinan struktural dan pendidikan rendah. Adaptasi, dalam kerangka ini, bukan hanya soal iklim—tetapi soal keadilan antar manusia.
Penutup buku ini terasa seperti pernyataan etis sekaligus politis: investasi terbaik menghadapi perubahan iklim bukan hanya pada beton tanggul, benih unggul, atau jaringan listrik pintar, tetapi pada manusia itu sendiri. Sekolah, universitas, pelatihan kerja, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi infrastruktur iklim yang sama pentingnya dengan bendungan dan panel surya. Di titik ini, adaptasi berubah dari isu teknis menjadi proyek peradaban. Dengan demikian, Adapting to Climate Change berakhir bukan dengan nada apokaliptik, tetapi dengan optimisme yang bersyarat. Masa depan memang tidak pasti, tetapi sejarah manusia adalah sejarah adaptasi. Pertanyaannya bukan apakah kita bisa beradaptasi, melainkan siapa yang diberi kesempatan untuk melakukannya—dan siapa yang dibiarkan tertinggal di bawah panas yang terus meningkat.
Masa Depan Manusia dan Adaptasi Iklim
Belajar Hidup di Dunia yang Tak Lagi Stabil
Pada suatu pagi yang terasa semakin sering kita alami, banjir datang tanpa permisi, panas terasa lebih panjang dari biasanya, dan musim seolah kehilangan ingatan. Dunia tidak runtuh sekaligus; ia berubah perlahan, hari demi hari, hingga manusia menyadari bahwa rumah ekologisnya tak lagi sama. Di titik inilah Adapting to Climate Change mengajukan pertanyaan yang sunyi namun menentukan: bukan apakah perubahan iklim akan terjadi, melainkan bagaimana manusia akan hidup di dalamnya.
Matthew Kahn tidak menulis buku ini sebagai nubuat kiamat. Ia juga tidak menawarkan penghiburan moral yang kosong. Yang ia lakukan adalah menggeser lensa: dari obsesi tunggal pada mitigasi menuju pemahaman mendalam tentang adaptasi—sebuah kemampuan tua umat manusia yang kini diuji kembali pada skala planet. Adaptasi, dalam pandangan Kahn, bukan tanda menyerah pada perubahan iklim, melainkan pengakuan jujur atas keterbatasan manusia dan kekuatan belajarnya.
Sejarah manusia, jika dibaca tanpa romantisme, adalah sejarah adaptasi terhadap ketidak-pastian. Kota-kota tumbuh di tepi sungai dan pantai, bukan karena aman, tetapi karena produktif. Risiko selalu ditukar dengan peluang. Perubahan iklim mengganggu keseimbangan lama ini: panas ekstrem menurunkan produktivitas, badai merusak infrastruktur, dan penyakit tropis bergerak melintasi garis lintang. Namun Kahn menunjukkan bahwa respons manusia tidak pernah seragam. Ada kota yang tenggelam dan ada kota yang beradaptasi; ada masyarakat yang terpuruk dan ada yang menemukan cara baru untuk bertahan.
Dalam buku ini, adaptasi tidak digambarkan sebagai tindakan heroik tunggal, melainkan sebagai akumulasi keputusan kecil: di mana orang tinggal, jenis rumah apa yang dibangun, pekerjaan apa yang dipilih, teknologi apa yang diadopsi, dan kebijakan apa yang memungkinkan pilihan-pilihan itu tersedia. Pasar—yang sering diposisikan sebagai musuh lingkungan—dipandang Kahn sebagai mekanisme informasi yang memungkinkan manusia membaca sinyal iklim dan meresponsnya. Harga tanah, upah, dan asuransi menjadi bahasa sunyi yang menerjemahkan risiko iklim ke dalam keputusan sehari-hari.
Namun pasar saja tidak cukup. Kahn berulang kali menegaskan bahwa adaptasi adalah proses yang sangat tidak setara. Mereka yang memiliki modal, pendidikan, dan mobilitas akan beradaptasi lebih cepat; mereka yang miskin, terikat tempat, dan kurang akses akan menanggung beban paling berat. Di sinilah adaptasi berubah dari isu teknokratis menjadi persoalan keadilan. Perubahan iklim, seperti cermin retak, memperbesar ketimpangan yang telah lama ada.
Pertanian menjadi panggung penting dalam narasi ini. Di ladang-ladang yang semakin panas dan kering, adaptasi berarti inovasi: benih tahan iklim ekstrem, irigasi cerdas, data satelit, dan pengetahuan baru yang menggantikan intuisi lama. Kahn menolak nostalgia agraris yang membayangkan masa lalu sebagai harmoni ekologis. Ia menunjukkan bahwa pertanian selalu bersifat eksperimental—dan masa depan pangan bergantung pada kemampuan manusia untuk terus belajar dari kegagalan ekologisnya sendiri.
Narasi kemudian melebar ke skala global. Dalam dunia yang terhubung, adaptasi tidak lagi bersifat lokal semata. Perdagangan internasional memungkinkan risiko iklim didistribusikan lintas wilayah. Ketika satu tempat gagal panen, tempat lain mengisi kekosongan. Globalisasi, dalam bingkai ini, bukan hanya sistem ekonomi, tetapi jaringan adaptasi planet. Menutup diri dari dunia bukanlah perlindungan, melainkan kerentanan baru.
Namun benang merah terkuat buku ini muncul di bagian akhirnya: human capital fuels adaptation. Pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis adalah infrastruktur adaptasi yang paling menentukan. Bendungan dapat runtuh, teknologi bisa usang, tetapi manusia yang mampu belajar dan beralih akan terus menemukan cara untuk hidup. Masa depan bukan milik mereka yang memiliki teknologi tercanggih, melainkan mereka yang memiliki kapasitas belajar tertinggi.
Di sinilah buku Kahn melampaui ekonomi dan memasuki wilayah etika. Adaptasi bukan sekadar soal bertahan hidup, tetapi soal bagaimana kita memilih untuk hidup bersama. Apakah adaptasi akan menjadi hak istimewa segelintir orang, atau proyek kolektif peradaban? Apakah kota-kota akan dirancang untuk melindungi yang paling rentan, atau hanya mengamankan aset yang paling bernilai?
Dalam konteks global—dan khususnya negara-negara seperti Indonesia—pesan ini menjadi semakin relevan. Negeri-negeri tropis berada di garis depan dampak iklim, tetapi juga memiliki modal sosial, ekologis, dan budaya yang besar. Adaptasi di sini tidak bisa disalin mentah-mentah dari negara maju; ia harus berakar pada manusia, komunitas, dan pengetahuan lokal, sambil terhubung dengan pasar dan teknologi global.
Pada akhirnya, Adapting to Climate Change mengajukan pandangan yang tenang namun menuntut tanggung jawab: masa depan manusia tidak ditentukan oleh iklim semata, tetapi oleh keputusan kolektif tentang siapa yang kita lindungi, siapa yang kita investasikan, dan nilai apa yang kita pertahankan. Dunia akan menjadi lebih panas. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghindarinya sepenuhnya, melainkan apakah kita cukup bijak untuk belajar hidup di dalamnya—tanpa meninggalkan kemanusiaan kita sendiri.
Catatan Akhir: Human Capital Fuels Adaptation
Adapting to Climate Change menantang kita untuk melihat bahwa adaptasi adalah strategi krusial selain mitigasidalam menghadapi perubahan iklim. Kahn memadukan ekonomi mikro, perilaku individu, pasar, dan kebijakan untuk membangun sebuah pandangan bahwa manusia tidak pasif terhadap iklim yang berubah; kita bisa belajar hidup dengannya—dan bahkan mengubah struktur ekonomi dan sosial kita untuk menjadi lebih resilien.
Buku ini penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat umum—terutama karena ia menawarkan cara berpikir yang realistis, optimis, namun penuh kewas-padaan tentang masa depan yang tidak pasti. Adaptasi bukan hanya tentang bertahan; ia tentang mengelola risiko dan peluang di dunia yang makin cepat berubah.
Kahn menegaskan bahwa modal manusia (human capital)—berupa pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas inovasi—adalah bahan bakar paling krusial untuk adaptasi iklim yang sukses. Ia berargumen bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sistem kesehatan yang kuat, dan budaya kewirausahaan yang dinamis akan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk merespons, berinovasi, dan berkembang dalam menghadapi gangguan iklim. Kahn menekankan bahwa “adaptasi bukanlah semata-mata tentang beton dan tembok laut, tetapi tentang neuron dan jaringan kolaborasi”. Sebuah kota mungkin membangun pertahanan banjir yang mahal, tetapi tanpa populasi yang terdidik untuk memeliharanya, memahami peringatan dini, dan mengembangkan solusi baru, infrastruktur tersebut pada akhirnya akan gagal. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan sains, teknologi, dan literasi iklim, serta jaminan kesehatan masyarakat, bukanlah pengeluaran sampingan, melainkan fondasi strategis dari ketahanan nasional.
Kahn menyimpulkan bukunya dengan visi optimis yang menempatkan manusia sebagai aktor utama, bukan korban pasif, dalam narasi perubahan iklim. Ia menggambarkan masa depan di mana kemampuan beradaptasi menjadi sumber keunggulan kompetitif baru bagi individu, komunitas, dan bangsa. Dalam ekonomi global masa depan, “green jobs” dan “adaptation entrepreneurship” akan menjadi penggerak kemakmuran. Kota-kota dan negara-negara yang berhasil menarik dan mempertahankan talenta-talenta kreatif, serta memberdayakan warganya dengan keterampilan untuk memecahkan masalah iklim, akan menjadi para pemenangnya. Pesan penutup Kahn adalah seruan untuk bertindak: “Dengan berinvestasi pada manusia hari ini, kita tidak sekadar membeli perlindungan untuk besok, kita sedang membangun mesin kemakmuran untuk masa depan yang tidak pasti.” Dengan demikian, bab penutup ini mentransformasi narasi adaptasi dari beban menjadi peluang—peluang untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya lebih tangguh, tetapi juga lebih adil, inovatif, dan makmur.
Bogor, 31 Desember 2025.
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Climate change adaptation. (n.d.). In Wikipedia. Wikipedia
How markets adapt to climate change. (2021). PERC. PERC
Book review: Adapting to Climate Change. (2021). The Independent Review. Independent Institute
Kahn, M. E. (2021). Adapting to climate change: Markets and the management of an uncertain future. Yale University Press.