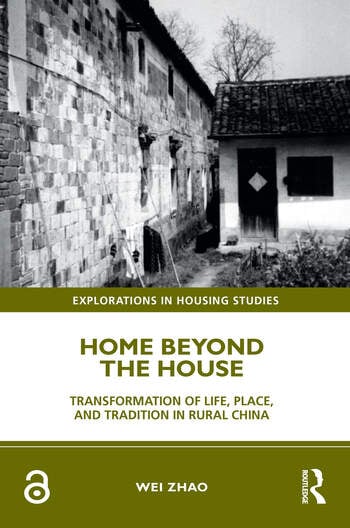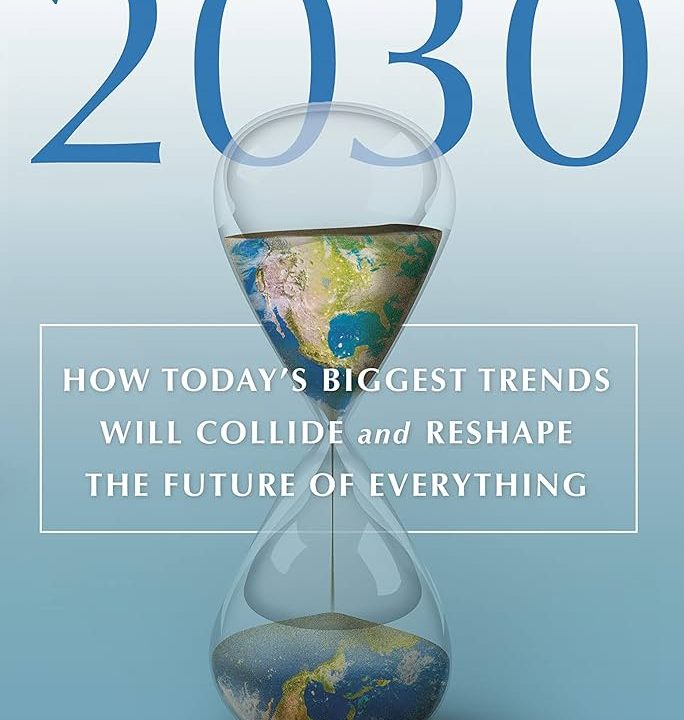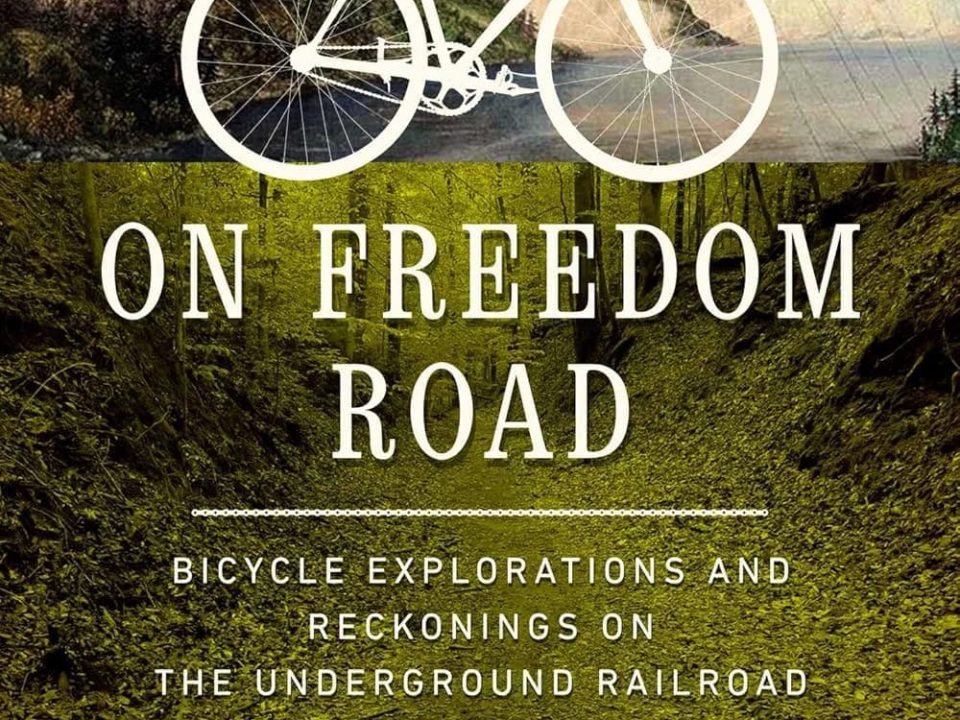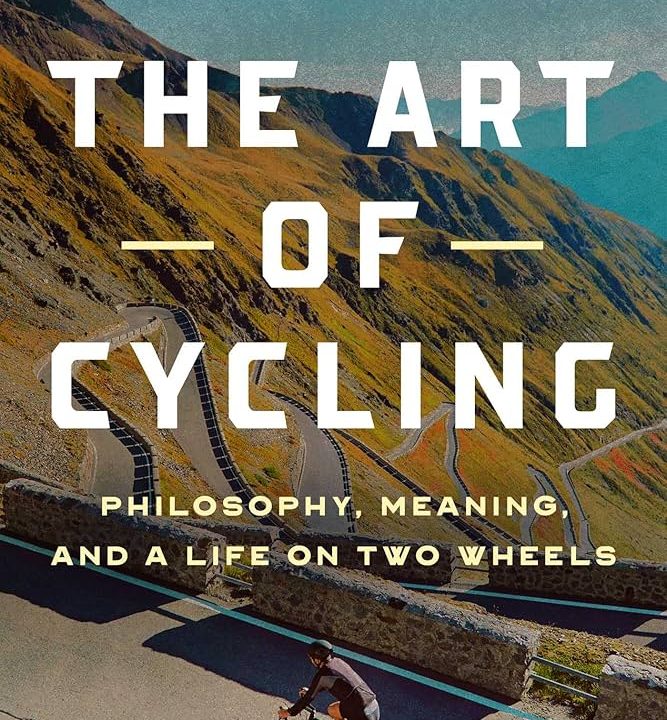Rubarubu #85
Home Beyond the House:
Memaknai Rumah di Desa China di Tengah Perubahan Sosial
Pada suatu pagi di desa Yanxia, seorang petani melihat dinding rumahnya yang retak — bukan sekadar bangunan, tetapi catatan panjang kehidupan keluarganya yang telah hidup di situ selama beberapa generasi. Rumah itu bukan sekadar tempat tidur atau penyimpanan hasil panen; ia adalah wadah ingatan, identitas, dan relasi sosial yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Kisah semacam inilah yang membuka Home Beyond the House, sebuah studi etnografis panjang yang bertanya: apa makna rumah bagi orang-orang di permukiman vernakular pedesaan China yang tengah mengalami transformasi besar? (Routledge)
Wei Zhao, yang melakukan penelitian lapangan intensif lebih dari satu dekade (2007–2019), tidak sekadar mengamati arsitektur fisik rumah-rumah ini, tetapi menggali makna sosial, budaya, historis, dan emosional rumah yang melampaui batasan fisik bangunan itu sendiri. Zhang mencatat bahwa rumah di desa China “lebih dari sekadar konstruksi batu dan kayu; ia adalah arena praktik tradisi, relasi kekeluargaan, identitas kolektif, kepemilikan lahan, dan gaya hidup pedesaan”—yang semua itu saling terjalin dalam jaringan kehidupan komunitas yang kompleks. (Routledge)
Transformasi Pedesaan China: Antara Modernisasi dan Tradisi
Buku Home Beyond the House: Transformation of Life, Place, and Tradition in Rural China oleh Wei (Windy) Zhao (Routledge, 2023) ini membuka dengan latar kontras yang mencolok: di satu sisi, kebijakan besar negara seperti Building a New Socialist Countryside (2006) dan Rural Revitalization (2018) yang mendorong perubahan cepat di desa-desa; di sisi lain, realitas kehidupan orang-orang yang hidup jauh dari pusat kebijakan. Di bawah tekanan kebijakan modernisasi, hubungan antara rumah, tanah, dan komunitas berubah secara dramatis — tidak selalu ke arah yang dianggap “lebih baik” oleh program pembangunan nasional. (Routledge)
Zhao menekankan bahwa pembangunan pedesaan China bukan hanya soal ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga tentang perubahan cara orang memahami tempat tinggal mereka. Rumah bukan lagi sekadar unit fisik yang aman dan nyaman; ia menjadi medan negosiasi antara tradisi lama dan dinamika baru modernisasi, antara pengalaman lokal dan narasi nasional. (Routledge)
Salah satu kontribusi teoritis utama buku ini adalah pembacaan konsep home (jia dalam bahasa Mandarin) yang melampaui sekadar “house” (bangunan). rumah vs “home”: melampaui batas fisik bangunan.
Argumen sentral Zhao adalah bahwa makna home berakar kuat pada ide tradisi, identitas dan dunia kehidupan pedesaan (rural lifeworlds) — bukan keberlanjutan literal pola lama tanpa perubahan, tetapi keterikatan yang mendalam terhadap:
- Identitas dan Kekerabatan: Rumah terhubung dengan sejarah keluarga, leluhur, serta hubungan darah yang memanjang melewati generasi.
- Kolektivitas dan Relasi Sosial: Rumah adalah titik temu interaksi tetangga, aktivitas komunitas, dan solidaritas sosial.
- Kepemilikan Tanah dan Lahan: Tanah di sekitar rumah — ladang, kebun, hutan kecil — adalah bagian dari pengalaman rumah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi.
- Gaya Hidup Pedesaan: Praktik keseharian — memasak dari bahan lokal, ritual agraris, metabolisme tubuh-tanah — adalah ekspresi home yang hidup. (IASTE)
Dan Zhao memetik cerita-cerita warga desa yang menunjukkan bahwa pengalaman rumah mencakup hal-hal di atas tersebut. Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan etnografi, survei bangunan, arsip sejarah, serta lebih dari 600 foto dan narasi kehidupan warga, Zhao tidak hanya menggambar-kan rumah yang tak lagi utuh secara fisik — tetapi juga mengungkap “home tanpa rumah” (home without the house): hubungan emosional dan simbolik yang tetap bertahan meskipun bentuk bangunan berubah atau hilang. (Routledge)
Pusat narasi buku ini adalah desa Yanxia di Provinsi Zhejiang. Buku ini tentang yanxia itu: studi kasus yang memberi suara pada warga desa. Yanxia, menurut Zhao, adalah contoh tipikal dari desa vernakular Cina yang telah kehilangan banyak hal akibat modernisasi dan urbanisasi. Rumah-rumah tua banyak yang ditinggalkan, generasi muda hijrah ke kota, dan sisa penduduk yang bertahan harus beradaptasi terus-menerus. Namun Zhao tidak sekadar mencatat hilang-nya; ia justru memberi ruang bagi warga untuk merekonstruksi artinya sendiri tentang rumah. Melalui foto-foto yang diambil oleh penduduk sendiri dan wawancara panjang, buku ini menampilkan konstitusi home sebagai proses yang terus bergerak, dibentuk oleh:
- ritual harian,
- kenangan kolektif,
- ceremonies penguburan dan peringatan leluhur,
- penggunaan lahan yang mencerminkan hubungan ekonomi dan sosial. (IASTE)
Dalam narasi ini, Zhao menunjukkan bahwa tradisi bukan semata masa lalu, tetapi prinsip hidup yang terus dinegosiasikan dan diadaptasi dalam kehidupan modern.
Dalam bab-bab seperti From the Land dan Rooted in the Past, Zhao menggambarkan praktik kehidupan yang menegaskan bahwa rumah tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan ekologi sosial-ekonomi desa. Inkarnasi home selalu meliputi lahan pertanian, ladang api unggun, sumur air bersama, serta ritual leluhur yang membentuk taxonomi sosial desa. (IASTE)
Mencari “Rumah” di Tengah Desa yang Bergerak
Bagian pengantar buku ini dibuka bukan dengan definisi teoretis yang kaku, melainkan dengan kegelisahan mendasar: bagaimana mungkin kita memahami “rumah” ketika bangunannya runtuh, ditinggalkan, direnovasi secara drastis, atau bahkan dihapuskan oleh kebijakan pembangunan? Wei Zhao menempatkan pertanyaan ini di jantung pengalaman pedesaan China kontemporer, di mana modernisasi tidak datang sebagai proses gradual, melainkan sebagai gelombang cepat yang mengubah lanskap fisik dan sosial sekaligus.
Dalam konteks China, “rumah” (jia) secara tradisional selalu lebih luas dari sekadar rumah tinggal. Ia mencakup relasi kekerabatan, tanah pertanian, ritual leluhur, dan posisi seseorang dalam tatanan desa. Namun, Zhao menunjukkan bahwa selama dua dekade terakhir, kebijakan negara—mulai dari reformasi tanah, migrasi tenaga kerja besar-besaran, hingga program revitalisasi desa—telah memisahkan unsur-unsur tersebut. Rumah bisa saja masih berdiri, tetapi keluarga tercerai oleh migrasi; sebaliknya, keluarga masih merasa “pulang”, meskipun bangunan fisiknya telah lama kosong atau hancur.
Wei pada bagian Introduction menegaskan pendekatan buku: bukan arsitektur sebagai objek estetik, melainkan rumah sebagai pengalaman hidup. Zhao menggabungkan etnografi jangka panjang, dokumentasi arsitektur, arsip sejarah lokal, serta metode partisipatif seperti foto dan narasi warga. Ia menolak pendekatan yang melihat desa hanya sebagai “ruang tertinggal” yang harus dimodernisasi, dan sebaliknya memperlakukan desa sebagai ruang hidup dengan logika internalnya sendiri.
Yang penting, sejak awal Zhao mengajukan tesis sentral: “home” dapat bertahan bahkan ketika “house” hilang, tetapi hanya jika relasi sosial, ingatan kolektif, dan hubungan dengan tanah masih hidup. Inilah yang kemudian diuji melalui kisah konkret desa Yanxia.
Bab pertama – Evolving Rural China (hal. 41): Desa sebagai Medan Ketegangan Modernitas, Wei memperluas lensa dari Yanxia ke konteks pedesaan China secara keseluruhan. Zhao memapar-kan bagaimana desa-desa China tidak sekadar “berubah”, tetapi mengalami rekonfigurasi struktural yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan: ekonomi, demografi, tata ruang, dan makna sosial rumah. Data nasional yang dikontekstualkan Zhao menunjukkan skala perubahan ini. Sejak awal 2000-an, ratusan juta penduduk desa bermigrasi ke kota. Banyak desa mengalami penuaan ekstrem: anak muda pergi, orang tua tertinggal. Rumah-rumah besar yang dulu dibangun sebagai simbol keberlanjutan garis keluarga kini kosong, terkunci, atau dibiarkan runtuh perlahan. Ironisnya, pada saat yang sama negara mendorong pembangunan rumah baru bergaya “modern”, sering kali seragam dan terlepas dari pola hidup lokal.
Zhao menggambarkan paradoks ini dengan tajam: desa diperlakukan sebagai masalah yang harus diperbaiki, bukan sebagai dunia yang perlu dipahami. Kebijakan “New Socialist Country-side” dan kemudian “Rural Revitalization” membawa infrastruktur, jalan, dan bangunan baru, tetapi sering mengabaikan praktik keseharian warga—seperti cara mereka menggunakan halaman, dapur luar, ruang bersama, dan relasi tetangga.
Bab ini juga menyoroti perubahan dalam relasi tanah. Tanah yang sebelumnya menjadi per-panjangan rumah—tempat kerja, ritual, dan interaksi sosial—semakin direduksi menjadi aset ekonomi atau objek regulasi negara. Ketika lahan dikonsolidasikan, dipindahfungsikan, atau dilepaskan, maka “rumah” kehilangan salah satu fondasi utamanya. Melalui pembacaan ini, Zhao menegaskan bahwa transformasi pedesaan China bukan sekadar urbanisasi, melainkan pergeseran ontologis tentang apa artinya tinggal, memiliki, dan menjadi bagian dari suatu tempat.
Bagaimana contoh sosok sebuah keluarga yang hidup dalam situati perubahan sosial yang gegas ini? Zhao memaparkannya pada Bab 2 – The Village under the Rock: The Cheng Family and the Vernacular Built Environment of Yanxia (hal. 65). Bab ini membawa pembaca masuk ke Yanxia, sebuah desa yang secara harfiah “bernaung di bawah batu”—tebing besar yang mendominasi lanskap dan membentuk imajinasi ruang warga. Di sinilah Zhao mempersempit fokus pada satu keluarga: keluarga Cheng, sebagai cara untuk memahami hubungan antara rumah, garis keturunan, dan lingkungan vernakular.
Melalui kisah keluarga Cheng, rumah tidak muncul sebagai unit tunggal, melainkan sebagai kompleks ruang hidup: bangunan utama, dapur terpisah, halaman, gudang, ladang kecil, dan jalur setapak yang menghubungkan rumah dengan rumah lain. Semua ini dibangun secara bertahap, mengikuti siklus hidup keluarga—pernikahan, kelahiran, kematian, dan migrasi.
Zhao menggambarkan bagaimana rumah keluarga Cheng menyimpan jejak sejarah yang tak tertulis: bekas perluasan ketika anak laki-laki menikah, ruang yang ditutup setelah anggota keluarga pindah ke kota, atau altar leluhur yang tetap dirawat meskipun penghuninya jarang pulang. Setiap perubahan fisik adalah respons terhadap perubahan sosial, bukan hasil perencanaan arsitektural abstrak.
Yang menarik, bab ini menunjukkan bahwa lingkungan vernakular Yanxia bukan sekadar “tradisional”, tetapi adaptif. Rumah-rumah dibangun mengikuti topografi, iklim, dan hubungan sosial. Tidak ada batas tegas antara ruang privat dan publik; halaman dan gang menjadi tempat kerja, bercengkerama, dan merayakan ritual.
Namun modernisasi mulai mengganggu keseimbangan ini. Ketika standar bangunan baru di-perkenalkan, banyak rumah lama dinilai “tidak layak”, meskipun secara sosial dan ekologis sangat fungsional. Zhao menekankan bahwa hilangnya rumah vernakular bukan hanya kehilangan bentuk, tetapi kehilangan cara hidup yang tertanam di dalamnya.
Bab ketiga – From a Local Deity to a World Heritage Site: Formation and Destruction of Vernacular Tradition (hal. 99), bergerak dari skala rumah dan keluarga ke skala simbolik dan politik budaya. Di sini Zhao menelusuri bagaimana tradisi lokal Yanxia—yang awalnya hidup melalui praktik sehari-hari dan kepercayaan terhadap dewa lokal—perlahan diubah menjadi “warisan budaya” yang dikelola dari luar. Zhao menceritakan transformasi kuil dan situs ritual lokal: dari ruang sakral yang aktif digunakan warga menjadi objek konservasi dan pariwisata. Ketika Yanxia mulai dipromosikan sebagai situs bernilai budaya tinggi, tradisi yang sebelumnya fleksibel dan kontekstual menjadi dikodifikasi, distandarisasi, dan dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Ironinya, proses pelestarian ini justru sering merusak tradisi itu sendiri. Ritual dipertahankan sebagai pertunjukan, bukan praktik hidup. Bangunan direnovasi agar “otentik” menurut standar luar, tetapi kehilangan makna bagi warga. Zhao menunjukkan bagaimana beberapa penduduk merasa terasing di desa mereka sendiri, karena ruang yang dulu milik bersama kini dikontrol oleh logika pariwisata dan birokrasi.
Bab ini – From the Land: The Foundation of Rural China (hal. 150), menyajikan kritik halus tetapi tajam: tradisi tidak mati karena modernitas semata, tetapi juga karena proses pelestarian yang memisahkannya dari konteks sosialnya. Ketika rumah, kuil, dan desa direduksi menjadi objek visual, maka “home” sebagai pengalaman hidup menjadi rapuh.
Bab ini kembali menurunkan pembaca ke lapisan paling dasar dari konsep “rumah” di pedesaan China: tanah. Sebab dari tanah itulah fondasi kehidupan pedesaan china. Zhao menunjukkan bahwa sebelum rumah menjadi bangunan, ia terlebih dahulu adalah relasi ekologis dan ekonomi dengan tanah. Di Yanxia, tanah bukan sekadar aset produksi, tetapi sumber identitas, memori, dan legitimasi keberadaan keluarga.
Zhao menggambarkan bagaimana rumah-rumah keluarga Cheng dan keluarga lain di desa selalu dirancang dengan orientasi pada lahan: sawah kecil, kebun, jalur air, dan akses ke bukit batu. Bahkan pembagian ruang dalam rumah—posisi dapur, pintu masuk, halaman—selalu mengikuti ritme kerja agraris. Rumah dan tanah membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun reformasi agraria pasca-1980-an dan kebijakan kepemilikan kolektif yang diiringi sistem kontrak jangka panjang telah mengubah relasi ini secara fundamental. Tanah tetap “milik kolektif,” tetapi pengelolaannya semakin terpisah dari kehidupan rumah tangga. Zhao mencatat bahwa banyak warga Yanxia tidak lagi mengolah tanahnya sendiri; lahan disewakan, digabung, atau dibiarkan terbengkalai karena pemiliknya bekerja di kota.
Data migrasi dan perubahan penggunaan lahan yang disertakan Zhao menunjukkan ironi yang menyakitkan: desa tetap dianggap “basis pangan nasional”, tetapi rumah-rumah desa kehilang-an fungsi ekonominya. Akibatnya, rumah tidak lagi menjadi pusat produksi, melainkan sekadar tempat singgah musiman. Tanah yang dahulu menyatukan keluarga kini justru mempercepat keterpisahan.
Bab ini menegaskan satu tesis penting: ketika tanah dilepaskan dari kehidupan rumah tangga, rumah kehilangan fondasi ontologisnya. Inilah awal dari “rumah tanpa rumah” yang akan dikembangkan lebih lanjut di bab-bab berikutnya. Jika tanah adalah fondasi material, maka leluhur adalah fondasi simbolik rumah pedesaan China. Berakar di Masa Lalu: Tempat Para Leluhur Pernah Hidup. Dalam bab ini, – Rooted in the Past: Where Ancestors Lived (hal. 192), Zhao mengeksplorasi bagaimana hubungan dengan nenek moyang membentuk makna rumah jauh melampaui generasi yang hidup saat ini.
Di Yanxia, rumah bukan hanya tempat tinggal orang hidup, tetapi juga tempat “tinggal” leluhur—melalui altar keluarga, ruang ritual, dan makam yang terletak di lanskap sekitar desa. Zhao menggambarkan bagaimana warga sering merujuk rumah mereka dengan menyebut siapa yang “pertama membangun”, bukan siapa yang sekarang tinggal. Dengan demikian, rumah menjadi node dalam jaringan waktu, bukan sekadar ruang fisik.
Namun modernisasi kembali menciptakan friksi. Ketika rumah lama dihancurkan untuk diganti bangunan baru atau direlokasi, altar leluhur sering kali dipindahkan secara simbolik—atau bahkan dihapuskan sama sekali. Zhao mencatat bahwa banyak warga merasa bersalah atau terasing, meskipun secara resmi mereka mengikuti kebijakan negara.
Bab ini memperlihatkan bahwa keruntuhan rumah leluhur bukan hanya kehilangan bangunan, tetapi krisis moral dan emosional. Beberapa warga yang tinggal di kota tetap pulang untuk ritual tahunan, meskipun rumahnya sudah tidak berpenghuni. Di sinilah mulai tampak bahwa “rumah” bertahan sebagai komitmen simbolik, meskipun struktur fisiknya rapuh.
Bagi Zhao dan keluarga di pedesaan China keluarga sebagai entitas ekonomi. Perubahan sosial menjadikan rumah dan keluarga yang terbelah. Itulah kisah dipaparkan pada Bab 6 – Family as an Economic Entity: Divided Homes and Families (hal. 236). Bab ini membahas transformasi keluarga dari unit hidup bersama menjadi entitas ekonomi yang terfragmentasi. Zhao menun-jukkan bagaimana migrasi tenaga kerja mengubah rumah menjadi simpul logistik: tempat penyimpanan, alamat administratif, dan lokasi ritual—bukan lagi pusat kehidupan sehari-hari.
Di Yanxia, rumah-rumah besar sering dihuni hanya oleh satu atau dua orang lansia, sementara anak-anak dan cucu bekerja di kota. Uang mengalir dari kota ke desa dalam bentuk remitansi, tetapi kehadiran fisik tidak mengikuti arus yang sama. Zhao menyoroti bagaimana rumah tetap dipertahankan—bahkan direnovasi—sebagai simbol keberhasilan ekonomi, meskipun nyaris kosong.
Analisis Zhao menunjukkan paradoks tajam: rumah tetap penting justru ketika tidak lagi dihuni. Ia menjadi bukti keberhasilan migrasi, jaminan status sosial, dan cadangan identitas jika suatu hari kembali. Namun secara sosial, keluarga menjadi terpecah, dan fungsi rumah sebagai ruang relasi harian memudar. Bab ini memperkuat gagasan bahwa ekonomi modern tidak meng-hancurkan rumah secara langsung, melainkan mengosongkannya dari kehidupan.
Inilah salah satu bab paling konseptual dalam buku: Bab 7 – Home without the House: Eternal Jiaxiang (hal. 263), Rumah tanpa Bangunan: Jiaxiang yang Abadi. Zhao memperkenalkan konsep jiaxiang—kampung halaman—sebagai bentuk rumah yang tidak bergantung pada bangunan fisik. Bagi banyak warga Yanxia yang telah lama tinggal di kota, jiaxiang tetap hidup sebagai ingatan, ikatan moral, dan tujuan pulang, meskipun rumah mereka telah runtuh atau diubah total.
Zhao menggambarkan bagaimana para migran berbicara tentang desa mereka dengan bahasa emosional yang kuat, meskipun kunjungan fisik semakin jarang. Ritual, makanan, dialek, dan bahkan cara berjalan di desa menjadi penanda “rumah” yang tak bisa direplikasi di kota.
Bab ini menegaskan tesis besar buku: rumah dapat bertahan tanpa rumah tinggal, tetapi hanya sebagai bentuk rapuh yang terus terancam jika tidak didukung oleh relasi sosial yang nyata. Jiaxiang yang abadi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil negosiasi terus-menerus antara ingatan, identitas, dan perubahan struktural.
Dimanapun sebuah berada selalu membangun tradisi sebagai identitias dan jalan hidup. Karena itu aspek inipun mendapatkan tempat penting yang dibahas dalam buku. Tentang Tradisi: Antara Kehidupan dan Representasi (Bab 8 – On Tradition (hal. 287)). Bab ini berfungsi sebagai refleksi kritis atas seluruh diskusi sebelumnya. Zhao mempertanyakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan “tradisi” dalam konteks pedesaan China hari ini. Apakah tradisi adalah praktik hidup yang berubah, atau kumpulan bentuk yang dibekukan oleh negara dan pasar?
Dengan merujuk kembali pada Yanxia, Zhao menunjukkan bahwa tradisi yang masih hidup selalu bersifat adaptif, tidak pernah murni. Namun ketika tradisi diposisikan sebagai “warisan”, ia sering kehilangan fleksibilitasnya. Rumah tradisional, ritual, dan tata ruang desa menjadi objek pengelolaan, bukan lagi praktik warga. Bab ini memperingatkan bahwa fetisisasi tradisi justru dapat mempercepat kehancurannya—karena memisahkannya dari konteks hidup yang membuatnya bermakna.
Rumah Setelah Rumah
Bagian penutup buku ini bukan kesimpulan yang menutup rapat, melainkan refleksi terbuka tentang masa depan rumah, desa, dan kehidupan pedesaan. Zhao kembali ke pertanyaan awal: jika rumah tidak lagi identik dengan bangunan, lalu apa yang harus dilindungi, dirawat, dan diwariskan?
Zhao menolak nostalgia romantik terhadap desa. Ia juga menolak optimisme dangkal pem-bangunan. Sebaliknya, ia mengusulkan cara berpikir baru tentang rumah sebagai proses relasional—sesuatu yang diciptakan dan diciptakan ulang melalui praktik sehari-hari, bukan sekadar melalui konstruksi fisik.
Dalam Afterword ini, Zhao menekankan pentingnya mendengarkan warga desa sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Rumah tidak bisa dipulihkan hanya dengan membangun ulang rumah; ia membutuhkan keberlanjutan relasi sosial, akses terhadap tanah, dan ruang untuk mempraktik-kan kehidupan bermakna.
Ia memberi pesan filosofis yang kuat: masa depan pedesaan tidak bergantung pada seberapa modern rumahnya, tetapi pada apakah manusia masih dapat merasa “di rumah” di dalamnya. Buku ini, pada akhirnya, adalah peringatan sekaligus harapan. Ia memperingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan makna rumah akan menghasilkan desa-desa tanpa kehidup-an. Namun ia juga menawarkan harapan: bahwa selama relasi, ingatan, dan komitmen moral masih ada, “rumah” belum sepenuhnya hilang—meskipun rumah tinggalnya telah lama runtuh.
Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana modernisasi, redistribusi, menentukan masa depan desa? Sementara banyak kebijakan China menekankan pembangunan baru dan transformasi desa, Zhao memperlihatkan bahwa ketergantungan pada model pembangunan top-down sering kali mengabaikan suara warga lokal. Rumah dapat dibangun ulang, tetapi home — pemaknaan yang melampaui fisik bangunan — sering kali hilang ketika struktur sosial dan relasi tradisi terkikis.
Zhao mengajak pembaca untuk melihat bahwa pembangunan pedesaan yang sesungguhnya harus dimulai dari pengakuan atas nilai-nilai tradisi yang hidup dalam praktik lokal, bukan sekadar desain statistik dan rencana tata ruang. Buku ini dengan lembut tetapi tegas menunjuk-kan bahwa home beyond the house bukan konsep sentimental, tetapi kerangka teoretis untuk memahami keberlanjutan sosial dalam transformasi global. (IASTE)
Dalam tradisi filsafat tempat dan ruang — dari Martin Heidegger tentang dwelling (menetap dan bermakna), hingga antihomo genisasi global dalam pemikiran Arturo Escobar tentang pluriverse — Home Beyond the House menempatkan home bukan sebagai obyek yang tetap, tetapi konstitusi pengalaman hidup yang terus berubah.
Sejalan dengan filsuf Islam seperti Fazlur Rahman yang memandang rumah sebagai centering place yang mengikat manusia pada tanah, komunitas, dan tanggung jawab moral, Zhao me-nunjukkan bahwa rumah pedesaan China adalah node etis yang melampaui sekadar struktur fisik.
Zhao dengan idiom kuat Rumah tanpa Rumah merupakan kritik pembangunan modern dan sintesis filosofis atas Home Beyond the House. Pembangunan modern selalu datang dengan janji: rumah yang lebih baik, hidup yang lebih layak, masa depan yang lebih cerah. Namun, seperti yang ditunjukkan dengan ketelitian etnografis dan kepekaan filosofis oleh Wei Zhao, janji itu sering mengandung paradoks yang dalam. Rumah dibangun, direnovasi, diperindah—tetapi rasa “berumah” justru menghilang. Dari sinilah muncul gagasan kunci buku ini: “rumah tanpa rumah”—sebuah kondisi di mana bangunan tetap berdiri, tetapi kehidupan yang memberi makna padanya telah tercerabut.
Dalam pengalaman pedesaan China yang dipaparkan Zhao, rumah tidak pernah sekadar bangunan. Ia adalah simpul relasi antara tanah, leluhur, keluarga, kerja, dan ritme kehidupan sehari-hari. Rumah adalah proses, bukan produk. Ia terbentuk melalui praktik bertani, berbagi makanan, ritual keluarga, dan kehadiran lintas generasi. Ketika pembangunan modern me-misahkan unsur-unsur ini—tanah dari rumah, keluarga dari tempat tinggal, kerja dari desa—rumah kehilangan substansi ontologisnya.
Pembangunan modern, sebagaimana dikritik Zhao, cenderung mereduksi rumah menjadi objek teknis: unit hunian, aset properti, atau simbol kemajuan. Dalam logika ini, keberhasilan diukur dari jumlah rumah baru, kualitas material, atau nilai ekonomi. Yang luput adalah pertanyaan paling mendasar: apakah manusia masih hidup di dalamnya sebagai manusia yang utuh?
Modernisasi sebagai Proses Pengosongan
Buku ini memperlihatkan bahwa kehancuran rumah tidak selalu bersifat destruktif secara fisik. Justru yang paling berbahaya adalah pengosongan fungsi sosial dan eksistensial rumah. Rumah-rumah di Yanxia tetap berdiri, bahkan direnovasi dengan dana migrasi, tetapi dihuni oleh kesunyian: orang tua yang menua sendirian, anak-anak yang pulang setahun sekali, ritual yang dipertahankan tanpa kehidupan sehari-hari yang menopangnya. Inilah kritik tajam terhadap pembangunan modern: ia mampu mempertahankan bentuk, tetapi gagal menjaga makna. Rumah menjadi monumen keberhasilan ekonomi, bukan ruang kehidupan. Desa berubah menjadi arsip ingatan, bukan komunitas hidup.
Meski berakar pada konteks China, gagasan “rumah tanpa rumah” memiliki resonansi global. Ia berbicara kepada desa-desa di Asia Tenggara yang terdampak migrasi dan industrialisasi, kepada kawasan rural yang direvitalisasi sebagai destinasi wisata, bahkan kepada kota-kota modern di mana apartemen padat tidak selalu melahirkan rasa kebersamaan. Dalam pengertian ini, Zhao tidak sedang menulis tentang China semata, melainkan tentang krisis universal pembangunan modern: pembangunan yang memisahkan manusia dari tempatnya, dari sejarahnya, dan dari relasi-relasi yang memberi rasa aman dan makna.
Salah satu kontribusi filosofis terpenting buku ini adalah kritik terhadap cara modern memperlakukan tradisi dan warisan. Serta bahaya pembekuan. Ketika rumah, desa, dan praktik lokal ditetapkan sebagai “warisan”, mereka sering kehilangan sifat hidupnya. Tradisi dipelihara sebagai representasi, bukan sebagai praktik yang boleh berubah dan beradaptasi.
Zhao menunjukkan bahwa tradisi yang dibekukan—dalam bentuk rumah adat, ritual turistik, atau desa warisan—justru lebih rentan mati. Tradisi sejati, seperti rumah sejati, hanya bisa bertahan jika ia digunakan, dinegosiasikan, dan dihidupi, bukan sekadar dilestarikan secara formal.
Catatan Akhir: Rumah sebagai Relasi
Melalui Introduction dan tiga bab awal, Zhao membangun fondasi konseptual buku: rumah bukanlah artefak statis, melainkan relasi dinamis antara manusia, tanah, bangunan, ingatan, dan praktik sosial. Transformasi pedesaan China memperlihatkan bahwa menghancurkan rumah fisik jauh lebih mudah daripada membangun kembali “home”.
Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan? Pada akhirnya, Home Beyond the House mengajukan pertanyaan filosofis yang sederhana namun radikal: apa arti hidup “di rumah” di dunia modern? Apakah rumah adalah kepemilikan, lokasi, atau rasa keterhubungan? Apakah pembangunan bertujuan menciptakan tempat tinggal, atau menciptakan kehidupan yang layak dijalani? Sintesis pemikiran Zhao dapat dirumuskan sebagai berikut:
- Rumah adalah relasi hidup, bukan sekadar bangunan.
- Pembangunan yang memisahkan manusia dari tanah, keluarga, dan ingatan akan menghasilkan rumah tanpa kehidupan.
- Tradisi hanya bermakna jika tetap menjadi praktik hidup, bukan objek beku.
- Masa depan pedesaan—dan mungkin peradaban—bergantung pada kemampuan kita merancang pembangunan yang memungkinkan manusia merasa “di rumah”, bukan sekadar memiliki rumah.
Zhao tidak menawarkan solusi teknokratis. Ia menawarkan sesuatu yang lebih mendasar: pergeseran etika dan imajinasi. Dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan menuju pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan relasi; dari rumah sebagai properti menuju rumah sebagai tempat bernaung secara eksistensial. “Rumah tanpa Rumah” adalah peringatan, tetapi juga undangan. Peringatan bahwa kita bisa kehilangan rumah bahkan ketika dikelilingi bangunan. Undangan untuk membayangkan ulang pembangunan—bukan sebagai proyek menaklukkan ruang, tetapi sebagai seni merawat kehidupan.
Dalam dunia yang semakin bergerak cepat, buku Wei Zhao mengingatkan kita akan satu hal yang pelan namun esensial: manusia tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi tempat untuk pulang—secara sosial, kultural, dan moral.
Dalam tradisi filsafat tempat dan ruang — dari Martin Heidegger tentang dwelling (menetap dan bermakna), hingga antihomo genisasi global dalam pemikiran Arturo Escobar tentang pluriverse — Home Beyond the House menempatkan home bukan sebagai obyek yang tetap, tetapi konstitusi pengalaman hidup yang terus berubah. Sejalan dengan filsuf Islam seperti Fazlur Rahman yang memandang rumah sebagai centering place yang mengikat manusia pada tanah, komunitas, dan tanggung jawab moral, Zhao menunjukkan bahwa rumah pedesaan China adalah node etis yang melampaui sekadar struktur fisik.
Home Beyond the House bukan sekadar studi tentang arsitektur rural China; ia adalah narasi tentang kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari tempat, tradisi, dan relasi manusia-tanah-keluarga. Buku ini memperluas pengertian home menjadi fenomena luas yang melibatkan identitas, cara hidup, dan ketahanan sosial di tengah transformasi cepat. Ia memberi suara kepada warga pedesaan yang selama ini tertinggal dalam penelitian akademik dan kebijakan nasional.
Rumah sebagai relasi, bukan sekadar struktur dan benda.
Bogor, 23 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi (APA)
Zhao, W. (2023). Home Beyond the House: Transformation of Life, Place, and Tradition in Rural China. Routledge. (Routledge)
Li, G. (2024). Review of Home Beyond the House. The China Quarterly. (Cambridge University Press & Assessment)
Long, L. (2023). What we are studying when we are studying home: review. Journal of Chinese Architecture and Urbanism. (accscience.com)