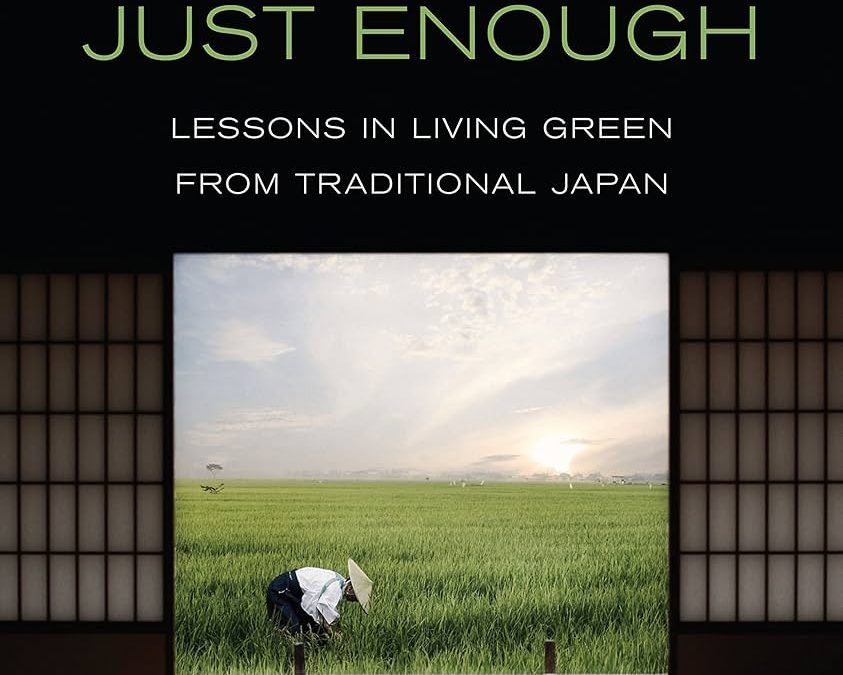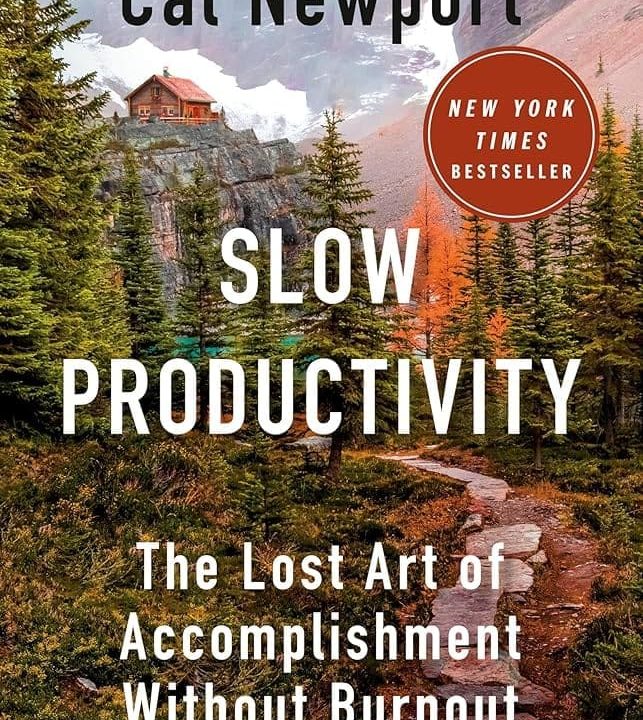Rubarubu #61
Just Enough:
Negeri yang Hidup dengan “Cukup”
Dunia yang Terlalu Banyak, Manusia yang Terlalu Lelah
Azby Brown membuka Just Enough dengan sebuah pengamatan yang sederhana tetapi mengguncang asumsi modern tentang kemajuan: selama lebih dari dua abad—khususnya pada periode Edo (1603–1868)—Jepang hidup sebagai sebuah peradaban maju tanpa bergantung pada bahan bakar fosil, tanpa eksploitasi koloni, dan tanpa kehancuran ekologis besar-besaran. Dalam keterbatasan sumber daya alam, Jepang tidak runtuh; sebaliknya, ia berkembang secara stabil.
Brown menulis: “Edo Japan was a society that had learned how to live within its means—not by retreating into poverty, but by cultivating systems of reuse, efficiency, and restraint.” (Brown, 2012). Buku Just Enough: Lessons in Living Green from Traditional Japan (Tuttle Publishing, 2012) ini tidak bernostalgia secara romantik, tetapi melakukan apa yang jarang dilakukan diskursus lingkungan modern: mempelajari masa lalu sebagai laboratorium keber-lanjutan. Dengan pendekatan lintas disiplin—sejarah, desain, ekologi, dan antropologi—Brown menunjukkan bahwa living green bukanlah penemuan abad ke-21, melainkan ingatan yang terlupakan.
Bagian awal buku menempatkan Jepang tradisional sebagai sebuah sistem tertutup (closed-loop society). Karena keterbatasan lahan, kayu, dan energi, masyarakat Edo terpaksa mengembang-kan budaya efisiensi ekstrem. Jepang Edo sebagai ekosistem sosial-ekologis. Tidak ada “sampah” dalam pengertian modern; hampir semua material—kertas, kain, kayu, logam—digunakan kembali, diperbaiki, atau didaur ulang.
Brown, seorang penulis, peneliti, dan pakar dalam bidang desain berkelanjutan, arsitektur tradisional Jepang, dan teknologi lingkungan yang futuristik, menggambarkan bagaimana kota Edo (Tokyo lama), dengan populasi lebih dari satu juta jiwa, berfungsi tanpa sistem sanitasi modern, tetapi tetap relatif bersih. Limbah manusia dikumpulkan dan dijual sebagai pupuk. Ini bukan sekadar praktik teknis, melainkan ekonomi sirkular yang matang. Prinsip ini mengingat-kan pada apa yang kini disebut circular economy, namun telah dipraktikkan secara organik berabad-abad lalu. Seperti dicatat sejarawan lingkungan Jepang: “Tokugawa Japan achieved a level of sustainability unmatched by any pre-industrial society of comparable scale.” (Totman, 1989)
Krisis iklim, keruntuhan ekologi, dan kelelahan sosial bukan semata-mata akibat kekurangan sumber daya, melainkan akibat kelebihan hasrat. Dunia modern tidak runtuh karena ia miskin, tetapi karena ia berlebihan: produksi berlebih, konsumsi berlebih, eksploitasi berlebih, dan kecepatan berlebih. Dalam konteks inilah buku Just Enough karya Azby Brown, wacana degrowth, dan ekonomi Islam bertemu dalam satu titik etik: kecukupan (enoughness) sebagai fondasi peradaban. Ketiganya lahir dari konteks yang berbeda—Jepang Edo, kritik ekonomi politik Barat, dan tradisi Islam—namun sama-sama mengajukan pertanyaan mendasar:
berapa sebenarnya yang kita butuhkan untuk hidup bermartabat tanpa menghancurkan dunia?
Just Enough adalah konsep kecukupan sebagai praktik peradaban dan itu tumbuh sudah berabad-abad lalu di Jepang. Dalam Just Enough, Azby Brown tidak sedang menawarkan nostalgia romantik terhadap Jepang tradisional, melainkan analisis peradaban yang berhasil hidup berkelanjutan selama berabad-abad. Jepang periode Edo (1603–1868) menunjukkan bahwa masyarakat kompleks dapat bertahan tanpa pertumbuhan ekonomi terus-menerus, tanpa bahan bakar fosil, dan tanpa produksi massal yang destruktif. Selain Just Enough, Azby Brown juga menulis The Genius of Japanese Carpentry (1989/2014): Buku klasik yang mendokumentasikan teknik dan filosofi di balik pertukangan kayu tradisional Jepang dan
The Very Small Home (2005): Eksplorasi tentang desain rumah cerdas dan efisien ruang di Jepang perkotaan.
Prinsip Just Enough bukan asketisme ekstrem, tetapi rasionalitas ekologis: menggunakan sumber daya secukupnya, memperpanjang usia benda, menghormati siklus alam, dan menata kehidupan sosial agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Di sini, kecukupan bukan kekurangan, melainkan keseimbangan. Yang penting, Just Enough bukan sekadar sikap individual, melainkan tatanan sosial dan moral. Norma kolektif, rasa tanggung jawab antar generasi, dan pembatasan diri menjadi bagian dari struktur masyarakat. Inilah yang sering hilang dalam modernitas: kecukupan direduksi menjadi pilihan pribadi, bukan etika bersama.
Konsep Degrowth pada sisi disampingnya adalah kritik radikal terhadap ideologi pertumbuhan yang telah menjermuskan dunia pada kehancuran ekologis. Jika Just Enough adalah narasi historis dan kultural, maka degrowth adalah kritik teoretis dan politis terhadap ekonomi modern. Degrowth menolak asumsi dasar kapitalisme dan bahkan sosialisme produktivis: bahwa kesejahteraan harus selalu diiringi pertumbuhan ekonomi.
Para pemikir degrowth seperti Serge Latouche, Giorgos Kallis, dan Jason Hickel menunjukkan bahwa pertumbuhan tanpa batas di planet terbatas adalah kontradiksi logis. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi modern terbukti tidak netral: ia bergantung pada ekstraksi ekologis, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan global antara Utara dan Selatan. Di titik ini, degrowth bertemu dengan Just Enough. Keduanya menolak mitos “lebih selalu lebih baik”. Namun degrowth lebih eksplisit bersifat politis: ia menyerukan pengurangan produksi dan konsumsi secara terencana, demokratis, dan adil—terutama di negara dan kelas yang selama ini menikmati kelebihan.
Perbedaannya, Just Enough menunjukkan bahwa kehidupan tanpa pertumbuhan bukan utopia, melainkan pernah menjadi kenyataan sejarah. Degrowth sering dituduh abstrak atau tidak realistis; Just Enough memberi contoh konkret bahwa kecukupan bisa menjadi dasar peradaban yang stabil.
Bagaimana dengan Ekonomi Islam? Ekonomi Islam memandang kecukupan sebagai perintah moral dan kosmologis. Dalam ekonomi Islam, konsep kecukupan bukan gagasan baru, melain-kan inti ajaran. Prinsip qana’ah (merasa cukup), larangan israf (berlebihan) dan tabdzir (pemborosan), serta tujuan maqasid al-shariah—menjaga kehidupan, akal, harta, keturunan, dan agama—semuanya mengarah pada pembatasan diri demi kemaslahatan bersama. Berbeda dengan degrowth yang lahir sebagai kritik modern, ekonomi Islam berangkat dari pandangan kosmologis: manusia bukan pemilik mutlak alam, melainkan khalifah (penjaga). Alam bukan sumber daya netral, tetapi amanah. Dengan demikian, eksploitasi berlebihan bukan hanya kesalahan ekonomi, tetapi dosa moral dan spiritual.
Di sini, ekonomi Islam melengkapi Just Enough dan degrowth dengan dimensi transenden. Jika degrowth menanyakan berapa cukup secara ekologis, dan Just Enough menunjukkan bagai-mana cukup secara historis, maka ekonomi Islam menanyakan mengapa kita harus cukup: karena ada tanggung jawab etis di hadapan Tuhan, generasi mendatang, dan seluruh makhluk hidup.
Maka kalau Azby Brown memaparkan tentang just enough sebagai tawaran keharusan maka ada titik temu dengan degraowth dan ekonomi Islam. Inilah etika kecukupan sebagai alternatif peradaban. Ketiga pendekatan ini bertemu dalam beberapa prinsip kunci: Pertama, penolakan terhadap akumulasi tanpa batas. Baik Jepang Edo, teori degrowth, maupun ekonomi Islam sama-sama membatasi hasrat akumulasi—entah melalui norma sosial, kebijakan politik, atau hukum agama.
Kedua, keadilan antar generasi. Just Enough menekankan warisan ekologis, degrowth menuntut pengurangan konsumsi generasi kini demi masa depan, dan ekonomi Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap keturunan (hifz al-nasl). Ketiga, re-embedding ekonomi dalam moralitas. Ketiganya menolak ekonomi sebagai sistem otonom yang bebas nilai. Produksi dan konsumsi selalu memiliki implikasi etis.
Konteks Indonesia: Dari Desa Adat ke Etika Pembangunan Alternatif
Dalam konteks Indonesia, sintesis ini sangat relevan. Desa adat yang hidup dengan prinsip cukup—mengambil hasil hutan secukupnya, bertani sesuai musim, dan menjaga keseimbangan sosial—sebenarnya telah mempraktikkan just enough, degrowth lokal, dan ekonomi Islam (atau kosmologi lokal) sekaligus. Namun desa-desa ini kini menghadapi tekanan sistem eksternal: pertumbuhan ekonomi nasional, investasi ekstraktif, dan logika pasar global. Di sinilah ketiga gagasan ini dapat menjadi kerangka etika alternatif untuk pembangunan Indonesia: bukan anti-kemajuan, tetapi anti-kelebihan; bukan anti-produksi, tetapi pro-kecukupan.
Energi, rumah, dan desain yang rendah jejak ekologis. Brown kemudian mengulas bagaimana energi digunakan secara hemat dan cerdas. Tanpa batu bara atau minyak bumi, masyarakat Jepang mengandalkan tenaga manusia, biomassa, dan desain pasif. Rumah-rumah tradisional dibangun ringan, fleksibel, dan dapat dibongkar-pasang. Ventilasi alami, pencahayaan matahari, serta penggunaan ruang yang minimal menjadikan rumah sebagai bagian dari iklim, bukan melawannya.
Estetika Jepang—wabi-sabi, shibui, dan kesederhanaan Zen—tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekologis ini. Keindahan lahir dari keterbatasan, bukan dari kelimpahan. Dalam konteks ini, Brown mengaitkan desain dengan etika: “Form followed availability. Beauty emerged from restraint.” (Brown, 2012). Gagasan ini sejalan dengan pemikiran E.F. Schumacher dalam Small Is Beautiful (1973), bahwa teknologi dan desain seharusnya “sesuai skala manusia dan ekologi”.
Makanan, Pertanian, dan Etika Konsumsi
Salah satu bagian terkuat buku ini adalah pembahasan tentang sistem pangan. Pola makan masyarakat Jepang tradisional berbasis nabati, musiman, dan lokal. Daging jarang dikonsumsi, bukan hanya karena larangan religius Buddhis, tetapi juga karena keterbatasan sumber daya.
Pertanian dilakukan secara intensif tetapi hati-hati, dengan daur ulang nutrisi tanah dan pemeliharaan lanskap jangka panjang. Brown yang telah tinggal di Jepang selama lebih dari 40 tahun dan berkeluarga di sana dan dikenal sebagai pendiri dan direktur Future Design Institute di Tokyo, Jepang ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak datang dari industrialisasi, melainkan dari pengetahuan lokal dan kehati-hatian ekologis. Hal ini menggema-kan kritik modern terhadap pertanian industri, sebagaimana dikemukakan oleh Vandana Shiva dan pemikir agroekologi lainnya.
Etika “Just Enough”: Kecukupan sebagai Kebajikan. Konsep sentral buku ini adalah just enough—cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ini bukan sekadar strategi bertahan hidup, tetapi etos moral. Dalam budaya Jepang tradisional, pemborosan dipandang tidak etis. Kesadaran akan keterbatasan sumber daya membentuk karakter sosial: disiplin, perencanaan jangka panjang, dan tanggung jawab antargenerasi.
Prinsip ini memiliki resonansi kuat dengan:
- degrowth (Latouche, Kallis),
- ekonomi Islam, khususnya konsep qana’ah dan larangan israf,
- serta etika ekologis Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah (penjaga, bukan penguasa alam).
Al-Qur’an menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isra’: 27) Dengan demikian, Just Enough dapat dibaca sebagai jembatan lintas budaya antara Timur dan Barat, masa lalu dan masa depan.
Modernitas, Kehilangan, dan Pelajaran bagi Krisis Iklim
Penulis yang juga pemikir sistem– Pendekatannya holistik, melihat keterkaitan antara arsitektur, pertanian, manajemen air, energi, dan organisasi sosial ini, tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa Jepang modern meninggalkan banyak praktik ini setelah Restorasi Meiji dan industrialisasi. Ketergantungan pada energi fosil, konsumerisme, dan pertumbuhan ekonomi cepat membawa kemakmuran—tetapi juga kerentanan ekologis.
Di sinilah buku ini menjadi reflektif dan kritis: apa yang hilang ketika masyarakat meninggalkan logika kecukupan? Dalam era krisis iklim, Brown tidak mengajak kembali ke masa lalu secara utopis, tetapi menekankan bahwa masa depan berkelanjutan memerlukan pemulihan nilai-nilai lama dalam konteks baru. Seperti ditulis oleh Arne Naess: “The rich life, with simple means.” (Naess, 1989)
Brown membuka buku ini dengan sebuah paradoks sejarah: bagaimana mungkin sebuah masyarakat besar, padat, dan maju seperti Jepang Edo bertahan selama ratusan tahun tanpa menghancurkan basis ekologinya? Jawabannya bukan teknologi canggih, melainkan etos hidup dengan cukup. The wisdom of enough: jepang edo sebagai peradaban kecukupan.
Di Jepang Edo, keterbatasan bukan dianggap kutukan, tetapi guru. Hutan tidak ditebang sem-barangan karena kayu adalah masa depan. Tanah tidak diperas karena tanah adalah waris-an. Kehidupan sosial disusun berdasarkan ritme alam, bukan tuntutan pasar global. Narasi ini sangat dekat dengan desa adat di Indonesia—Baduy, Kasepuhan Ciptagelar, Ammatoa Kajang, atau kampung-kampung adat di Flores dan Papua—yang memandang alam sebagai titipan, bukan komoditas. Namun seperti Jepang Edo yang akhirnya runtuh oleh modernisasi paksa, desa-desa Indonesia hari ini dikepung oleh logika pertumbuhan dan ekstraksi: tambang, sawit, pariwisata masif, dan proyek infrastruktur. Bab ini mengajarkan bahwa kecukupan bukan kemiskinan, tetapi sebuah peradaban etis.
Brown yang juga aktif sebagai dosen tamu, konsultan desain, dan komentator untuk media internasional tentang isu-isu keberlanjutan dan desain perkotaan di Jepang dan Asia ini mengisahkan Jepang Edo sebagai masyarakat tanpa limbah. Closed-loop society: tidak ada sampah dalam peradaban yang menghormati alam. Kain diperbaiki berkali-kali, kertas dipakai ulang, logam dilebur kembali, bahkan limbah manusia menjadi pupuk pertanian. Tidak ada istilah “buang”—yang ada hanyalah berputar. Ini bukan sekadar teknik, melainkan cara berpikir sirkular. Setiap benda memiliki siklus hidup panjang, dan setiap manusia sadar bahwa apa yang ia buang akan kembali padanya.
Bandingkan dengan desa-desa Indonesia sebelum masuknya plastik, produk instan, dan pasar ritel modern. Di banyak desa, daun, bambu, tanah liat, dan kayu adalah bahan utama. Sampah hampir tidak ada. Tetapi sistem ekonomi global memaksakan barang sekali pakai ke desa-desa, tanpa infrastruktur pengelolaan limbah. Bagian ini seolah bertanya: apakah desa Indonesia gagal mengelola sampah—atau sistem kapitalisme yang memaksa desa menerima produk yang tak sesuai dengan ekologi lokal?
Ia menggambarkan kehidupan tanpa batu bara, minyak, dan listrik sebagai hidup yang dirancang dengan cerdas, bukan hidup yang kekurangan. Energi manusia, kayu, angin, dan matahari digunakan secara efisien karena setiap tenaga berharga. Energy without fossil fuels: hidup tanpa mesin, tapi tidak primitif. Rumah-rumah ringan, mudah diperbaiki, dan menyatu dengan iklim. Tidak ada pendingin udara, tetapi ada ventilasi alami. Tidak ada beton masif, tetapi ada fleksibilitas. Di Indonesia, rumah-rumah adat—rumah panggung Bugis, rumah Minangkabau, rumah Toraja—dibangun dengan prinsip serupa. Namun modernisasi memaksa-kan rumah beton, AC, dan listrik berlebih, sering kali tidak cocok dengan iklim tropis. Bab ini menunjukkan bahwa krisis energi hari ini bukan soal kurangnya teknologi, tetapi hilangnya kebijaksanaan desain lokal.
Brown membawa pembaca ke sawah, ladang, dan dapur Jepang tradisional. Makanan seder-hana, musiman, lokal, dan nyaris tanpa limbah. Food, soil, and seasonality: ketahanan pangan tanpa industri. Tidak ada obsesif “lebih banyak”, yang ada “cukup untuk semua”.
Pola ini sangat serupa dengan pertanian subsisten Indonesia sebelum Revolusi Hijau: padi lokal, umbi, sagu, jagung, rotasi tanaman, dan pengetahuan ekologis turun-temurun. Namun seperti Jepang modern, Indonesia mengalami industrialisasi pangan: pupuk kimia, benih hibrida, monokultur, dan ketergantungan pasar. Petani kehilangan kedaulatan, desa kehilangan ke-tahanan. Kebijaksanaan ini seakan Edo berkata: kelaparan modern bukan akibat kekurangan produksi, tetapi hilangnya kontrol lokal atas pangan.
Brown menekankan bahwa Jepang Edo mengelola hutan dengan disiplin luar biasa. Forests as inheritance: hutan sebagai masa depan, bukan tambang. Penebangan diatur, penanaman ulang wajib, dan hutan dipandang sebagai aset lintas generasi. Bandingkan dengan Indonesia hari ini: hutan ditebang untuk sawit, tambang, dan proyek nasional, sering kali atas nama pembangun-an. Desa adat yang menjaga hutan justru dianggap penghambat kemajuan.
Ini terasa sangat politis jika dibaca dari Indonesia: ketika negara dan korporasi melihat hutan sebagai komoditas, sementara masyarakat adat melihatnya sebagai kehidupan.
Brown menuturkan kisah para pengrajin Jepang: penjahit, tukang kayu, pembuat kertas. Craft, repair, and the dignity of work. Profesi ini dihormati karena mereka menjaga umur benda dan mengurangi kebutuhan produksi baru. Ini sangat dekat dengan ekonomi lokal desa Indonesia: pandai besi, penganyam, penenun, tukang perahu. Tetapi pasar global menghancurkan nilai kerja ini dengan produk murah dan cepat. Bab ini mengajarkan bahwa krisis kerja hari ini adalah krisis makna, ketika kerja tidak lagi terhubung dengan keberlanjutan.
Brown menunjukkan ada social order and moral economy bahwa keberlanjutan Jepang Edo tidak hanya teknis, tetapi sosial. Norma, rasa malu, dan tanggung jawab kolektif menjaga keseimbangan. Pelanggaran ekologis adalah pelanggaran moral. Ini sangat resonan dengan hukum adat di Indonesia, di mana pelanggaran terhadap alam dihukum secara sosial dan spiritual. Namun sistem hukum modern sering mengabaikan mekanisme ini. Dan ini menegaskan bahwa tanpa etika kolektif, teknologi hijau tidak akan cukup.
Bab-bab akhir buku menjadi reflektif dan tragis. Brown menggambarkan bagaimana Jepang meninggalkan prinsip just enough demi industrialisasi cepat. Kekayaan meningkat, tetapi ketergantungan energi, konsumsi, dan kerentanan ekologis ikut tumbuh. Indonesia berada di persimpangan yang sama—bahkan lebih genting. The collapse of enough: modernisasi dan kehilangan arah. Desa-desa yang masih mandiri kini dihantam “tsunami ekonomi eksternal”: investasi besar, utang, pariwisata masif, dan ekstraksi sumber daya. Bab ini terasa seperti peringatan dini.
Bagian pertama Just Enough mengajak pembaca kembali ke lanskap paling dasar peradaban Jepang tradisional: ladang dan hutan (Field and Forest: Belajar dari Ladang dan Hutan). Bagi Azby Brown, keduanya bukan sekadar ruang produksi pangan dan bahan bangunan, me-lainkan ruang pendidikan ekologis, tempat manusia belajar batas, irama, dan kecukupan.
The Farmer from Kai Province: Manusia sebagai Penjaga Siklus
Pendiri Future Design Institute di Tokyo, Jepang ini membuka bagian ini dengan kisah seorang petani dari Provinsi Kai—figur yang tampak sederhana, nyaris anonim, namun justru merepre-sentasikan inti kebijaksanaan ekologis. Petani ini tidak memandang dirinya sebagai “penguasa tanah”, melainkan bagian dari siklus yang lebih besar: tanah, air, musim, dan komunitas.
Dalam kehidupan petani Kai, kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi tindakan etis. Ia menanam bukan untuk memaksimalkan hasil, melainkan untuk menjaga kesinambungan. Tanah tidak diperas; ia dipelihara agar tetap subur bagi generasi berikutnya. Di sini, Brown menegas-kan bahwa keberlanjutan bukan konsep abstrak, melainkan kebiasaan sehari-hari yang diwaris-kan lintas generasi. Kisah ini memperlihatkan sesuatu yang jarang hadir dalam modernitas: kerendahan hati ekologis—kesadaran bahwa manusia bergantung sepenuhnya pada alam, bukan sebaliknya.
Rice Cultivation: Sawah sebagai Ekosistem Moral
Beras, dalam masyarakat Jepang tradisional, bukan sekadar makanan pokok. Ia adalah poros kebudayaan. Brown menggambarkan budidaya padi sebagai proses yang menuntut kesabaran, koordinasi sosial, dan penghormatan terhadap alam. Sawah bukan ladang individual, melain-kan sistem kolektif. Irigasi harus diatur bersama, waktu tanam disepakati, dan hasil panen dipahami sebagai buah kerja komunitas. Di sini, pertanian menjadi pendidikan sosial: mengajarkan kerja sama, disiplin, dan saling ketergantungan.
Brown menunjukkan bahwa sawah juga merupakan ekosistem yang kaya—ikan kecil, serangga, burung, dan mikroorganisme hidup berdampingan dengan manusia. Pertanian tradisional Jepang tidak memisahkan produksi pangan dari kehidupan ekologis. Dengan kata lain, pangan dihasilkan tanpa memusnahkan kehidupan lain.
Rice Production and Its Byproducts: Tidak Ada yang Terbuang
Salah satu pelajaran terpenting dalam bagian ini adalah bagaimana masyarakat Jepang tradisional memanfaatkan seluruh bagian padi. Tidak ada konsep limbah. Sekam, jerami, dan sisa hasil panen semuanya memiliki fungsi: bahan bakar, pupuk, alas tidur ternak, bahan bangunan, bahkan bahan kerajinan.
Brown menekankan bahwa efisiensi ini bukan hasil teknologi canggih, melainkan cara berpikir. Ketika sumber daya terbatas, manusia belajar menghargai setiap serat alam. Dari sinilah lahir budaya mottainai—rasa sayang dan penyesalan mendalam terhadap pemborosan. Berbeda dengan ekonomi modern yang menciptakan limbah sebagai konsekuensi produksi massal, ekonomi tradisional Jepang justru dirancang agar siklus material tertutup, mendekati apa yang kini disebut ekonomi sirkular.
Thatching a Roof: Arsitektur dari Lanskap Sekitar
Atap jerami mungkin tampak rapuh bagi mata modern, tetapi Brown menunjukkan bahwa teknik penjeraman tradisional adalah hasil pengetahuan ekologis yang matang. Jerami dipilih, dipotong, disusun, dan dirawat dengan cara yang memastikan daya tahan puluhan tahun.
Lebih dari itu, atap jerami mencerminkan prinsip just enough: cukup hangat di musim dingin, cukup sejuk di musim panas, dan mudah diperbaiki tanpa merusak lingkungan. Ketika atap diganti, jerami lama kembali ke tanah sebagai pupuk. Bangunan menjadi bagian dari siklus alam, bukan objek yang terpisah darinya.
Di sini, rumah bukan simbol status atau akumulasi, melainkan alat hidup yang selaras dengan lingkungan.
Building Materials and Their Virtues: Etika dalam Material
Brown menutup bagian ini dengan refleksi tentang bahan bangunan—kayu, bambu, tanah liat—dan “keutamaan” yang dikandungnya. Setiap material memiliki karakter, batas, dan cara peng-gunaan yang tepat. Menggunakan kayu berarti memahami umur pohon; menggunakan tanah berarti memahami struktur bumi.
Material tidak diperlakukan sebagai komoditas anonim, melainkan sebagai entitas yang me-miliki nilai moral. Cara membangun mencerminkan cara hidup. Bangunan tradisional Jepang, dalam pandangan Brown, mengajarkan kesederhanaan, fleksibilitas, dan penghormatan terhadap alam.
Keseluruhan bagian Field and Forest dapat dibaca sebagai satu pelajaran besar: peradaban yang bertahan lama adalah peradaban yang tahu kapan harus berhenti. Ladang dan hutan mengajar-kan batas—tentang seberapa banyak yang bisa diambil, seberapa cepat alam pulih, dan se-berapa besar kebutuhan manusia yang sebenarnya. Azby Brown tidak sedang mengajak pem-baca kembali ke masa lalu, tetapi mengundang kita belajar dari cara berpikir masa lalu. Dalam dunia yang kini menghadapi krisis iklim dan kehancuran ekologi, kebijaksanaan ladang dan hutan menjadi semakin relevan: hidup bukan tentang menaklukkan alam, melainkan hidup cukup di dalamnya.
Jika pada bagian pertama Azby Brown mengajak kita ke ladang dan hutan, maka pada bagian kedua (The Sustainable City: Belajar dari Kota yang Bertahan) ia membawa kita ke jantung modernitas awal Jepang: kota Edo—sebuah kota yang pada abad ke-18 telah menjadi salah satu kota terbesar di dunia, namun tetap berfungsi dengan jejak ekologis yang relatif rendah. Di sini, Brown menantang asumsi modern bahwa kota besar pasti identik dengan pemborosan dan kehancuran lingkungan.
The Carpenter of Edo: Keahlian sebagai Etika Kota
Brown memusatkan kisahnya pada sosok tukang kayu Edo, figur yang bekerja di antara kebutuhan manusia dan batas alam. Tukang kayu ini bukan sekadar pekerja teknis, melain-kan penjaga kualitas hidup kota. Keahliannya diwariskan melalui magang panjang, bukan pendidikan instan. Ia memahami sifat kayu, kelembapan udara, dan usia bangunan. Dalam kota Edo, bangunan tidak dirancang untuk abadi, melainkan untuk dirawat, diperbaiki, dan diper-barui. Kebakaran yang sering terjadi bukan alasan untuk membangun dengan material tak berkelanjutan, melainkan dorongan untuk menyempurnakan sistem perawatan. Dengan demikian, kota menjadi organisme hidup yang terus diperbarui, bukan monumen mati yang menumpuk limbah.
Ground Transportation: Kota yang Bergerak dengan Tenaga Manusia
Brown lalu mengajak pembaca memperhatikan sistem transportasi darat Edo. Tanpa mesin uap, tanpa bahan bakar fosil, kota besar ini bergerak dengan tenaga manusia dan hewan, ditopang oleh jaringan jalan yang dirancang untuk pejalan kaki dan pengangkut barang skala kecil. Perjalanan lambat bukan kelemahan, melainkan mekanisme pengendalian konsumsi. Jarak terasa nyata; ruang memiliki makna. Barang mahal karena sulit dipindahkan, sehingga produksi lokal menjadi norma. Kota tidak tersedot oleh logika distribusi massal, melainkan hidup dari ekonomi jarak dekat.
Dalam gambaran Brown, transportasi bukan sekadar soal mobilitas, tetapi soal ritme hidup. Kota Edo bergerak sesuai kemampuan manusia, bukan memaksa manusia mengejar kecepatan mesin.
Learning from the Sustainable City: Kota Tanpa Pertumbuhan Tak Terbatas
Bagian ini ditutup dengan refleksi besar: Edo adalah contoh kota yang tidak tumbuh tanpa henti, tetapi tetap sejahtera. Kepadatan tidak diatasi dengan ekspansi, melainkan dengan efisiensi sosial dan ekologis. Limbah didaur ulang, energi berasal dari biomassa terbarukan, dan pekerjaan tersebar dalam skala yang manusiawi. Brown seorang pemikir futuris yang fokus pada bagaimana desain dan teknologi dapat menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan manusiawi, menegaskan bahwa kota berkelanjutan bukan kota yang “hijau” secara kosmetik, tetapi kota yang mengenal batasnya sendiri. Edo mengajarkan bahwa urbanisasi tidak harus berarti alienasi dari alam.
Bagian ketiga (A Life of Restraint: Etika Membatasi Diri) membawa pembaca ke lapisan elite masyarakat Jepang Edo—para samurai dan daimyo—untuk menunjukkan bahwa kecukupan bukan hanya etika kaum tani atau rakyat kecil, tetapi juga nilai yang diharapkan dari mereka yang berkuasa.
The Samurai of Edo: Kehormatan dalam Kesederhanaan
Samurai Edo, sebagaimana digambarkan Brown, hidup dalam paradoks. Mereka memiliki status sosial tinggi, tetapi sering hidup dengan sumber daya terbatas. Namun justru dari keterbatasan inilah lahir budaya pengendalian diri. Samurai ideal bukan yang hidup mewah, melainkan yang mampu menjaga martabat dalam kesederhanaan. Pengeluaran berlebihan dipandang sebagai kegagalan moral, bukan simbol keberhasilan. Kehormatan (bushido) terletak pada disiplin, bukan konsumsi.
Brown menunjukkan bahwa etika samurai membentuk psikologi sosial: menahan diri dianggap kekuatan, bukan kekurangan. Ini berbanding terbalik dengan modernitas, di mana konsumsi sering menjadi ukuran status.
Daimyo Estates: Kekuasaan yang Dibatasi
Para daimyo—penguasa wilayah—tidak bebas mengakumulasi kekayaan tanpa batas. Sistem politik Edo secara sadar membatasi kekuasaan mereka melalui kewajiban tinggal bergiliran di Edo (sankin-kotai), yang menguras sumber daya mereka dan mencegah konsolidasi kekuatan berlebihan. Brown menafsirkan sistem ini bukan hanya sebagai strategi politik, tetapi juga sebagai mekanisme ekologis dan ekonomi. Kekayaan tidak menumpuk di satu tempat, pem-bangunan tidak meledak tanpa kendali, dan elite dipaksa hidup dalam batas yang ditentukan sistem. Di sini, kekuasaan justru dijaga agar tidak menjadi sumber kehancuran sosial dan ekologis.
Learning from a Life of Restraint: Kebajikan Mengetahui Batas
Bagian ini berakhir dengan refleksi mendalam tentang pengekangan diri sebagai kebajikan peradaban. Jepang Edo bertahan lama bukan karena inovasi teknologi besar, melainkan karena kesediaan kolektif untuk hidup dalam batas. Brown menegaskan bahwa keberlanjutan bukan soal teknologi hijau semata, tetapi soal karakter manusia. Tanpa budaya menahan diri, teknologi apa pun akan menjadi alat eksploitasi baru.
Catatan Akhir: Dari Pertumbuhan ke Kecukupan
Melalui Part II dan Part III, Just Enough menunjukkan bahwa kecukupan harus hadir di semua lapisan: desa dan kota, rakyat dan elite, produksi dan kekuasaan. Kota Edo dan kehidupan para samurai mengajarkan bahwa peradaban yang tahan lama adalah peradaban yang tahu kapan harus berkata “cukup.”
Dalam dunia modern yang memuja ekspansi, efisiensi ekstrem, dan akumulasi, pelajaran dari Jepang tradisional ini terasa subversif sekaligus mendesak: masa depan mungkin tidak mem-butuhkan lebih banyak, tetapi lebih sedikit—yang dijalani dengan lebih bijaksana.
Just Enough bukan buku tentang Jepang semata. Ia adalah peta moral bagi dunia yang kelelahan oleh pertumbuhan tanpa batas.
Bagi Indonesia, buku ini menawarkan pembacaan ulang yang penting:
- desa bukan tertinggal, tetapi penyimpan pengetahuan ekologis,
- ekonomi lokal bukan tidak efisien, tetapi tahan krisis,
- dan kecukupan bukan kemunduran, tetapi jalan keluar dari krisis iklim dan sosial.
Just Enough adalah buku tentang ingatan peradaban. Ia menunjukkan bahwa kehidupan berkelanjutan bukanlah mimpi futuristik, melainkan pengetahuan yang pernah kita miliki dan kemudian kita tinggalkan. Dalam dunia yang terobsesi pada “lebih”, buku ini menawarkan kebijaksanaan yang tenang: cukup bisa menjadi bentuk kemajuan yang paling radikal.
Just Enough, degrowth, dan ekonomi Islam tidak menawarkan solusi teknokratis cepat. Mereka menawarkan sesuatu yang lebih radikal dan lebih sulit: perubahan nilai. Dari pertanyaan “bagaimana tumbuh lebih cepat?” ke pertanyaan “kapan kita berhenti?” Dalam dunia yang nyaris runtuh oleh kelebihan, mungkin masa depan bukan tentang lebih, melainkan tentang cukup—cukup untuk hidup bermartabat, cukup untuk berbagi, dan cukup untuk menjaga bumi tetap layak huni.
Bogor, 29 Desember 2025
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Brown, A. (2012). Just enough: Lessons in living green from traditional Japan. Tuttle Publishing.
Naess, A. (1989). Ecology, community and lifestyle. Cambridge University Press.
Schumacher, E. F. (1973). Small is beautiful: Economics as if people mattered. Blond & Briggs.
Totman, C. (1989). The green archipelago: Forestry in preindustrial Japan. University of California Press.
Kallis, G. (2018). Degrowth. Agenda Publishing.
Al-Qur’an al-Karim.