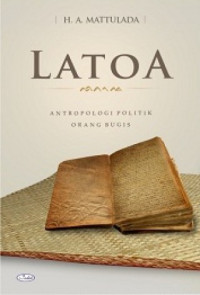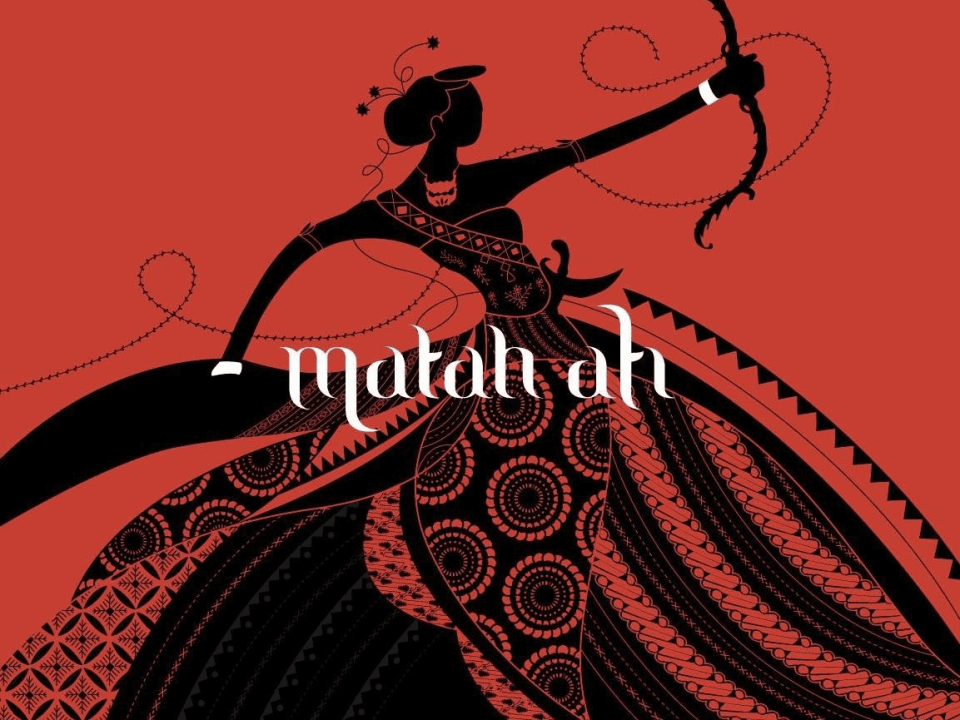halaman drm #35
Catatan-catatan Para Penjelajah Borneo : Bock 1
Menyusuri Rimba Borneo yang Misterius
Dwi R. Muhtaman
“Orang Dayak Kenyah membersihkan
sepetak hutan dengan bakar,
menanam padi satu musim,
lalu pindah…
Saat tanah tandus,
hutan mengambil alih kembali.
Kekayaan mereka diukur bukan dari emas,
tapi dari tempayan kuno (tajau) dan
tengkorak kerbau yang digantung di rumah.”
— Carl Bock
– The Head-Hunters of Borneo (1881)
Daftar Isi
“Kapal uap Belanda yang berkarat itu akhirnya merapat di Tarakan setelah 40 hari mengarungi lautan dari Batavia. Bau belerang dari sumur-sumur minyak primitif menyengat hidung—bau pertama yang menyambut kami di tanah Kalimantan yang lembab ini.”— Bock, 1881, hlm. 23.2
Pada April 1881, Carl Bock, seorang naturalis dan penjelajah Norwegia yang dipekerjakan pemerintah Belanda, tiba di Kalimantan Utara dengan misi resmi: memetakan wilayah, mengumpulkan spesimen flora-fauna, dan—yang paling berbahaya—menyaksikan kehidupan suku Dayak yang masih melakukan tradisi ngayau (pengayauan kepala).
“Asap dupa mengepul dari tempurung kelapa di tanganku, sementara puluhan mata bersinar dalam kegelapan rumah betang itu mengawasiku. Di langit-langit, tengkorak-tengkorak bergoyang pelan diterpa angin malam. Inilah Kalimantan 1881—dunia yang akan mengubah hidupku selamanya.”
Tahun 1881, pemerintah kolonial Belanda memanggilnya ke Batavia. Ada misi rahasia ke Borneo. Dalam ruang kerja penuh asap cerutu, seorang pejabat berkata: “Kami butuh seseorang yang cukup gila untuk masuk ke wilayah ngayau. Kau bisa mati di sana, Tuan Bock. Atau lebih buruk—dijadikan hiasan rumah betang.” Darah Viking Bock mendidih. Tantangan yang dicarinya selama ini.
Dengan 30 peti persenjataan dan 12 orang Dayak pengawal, ia menyusuri Sungai Mahakam. Di tengah perjalanan, malaria dan disentri menyerang. “Aku minum arak kutu kayu campur empedu buaya—obat tradisional yang justru membuatku muntah darah,” catatnya.
Di sebuah desa Kenyah, kepala suku bernama Apo Kayan memberinya “makan malam spesial”: daging babi hutan yang dimasak dalam bambu dengan ramuan akar misterius. “Ketika aku bertanya dari mana daging itu, dia tersenyum memperlihatkan gigi runyah: ‘Ini bukan babi, Tuan. Ini musuh.” Itulah pertemuan pertama kali dengan Sang Pengayau.
Anak kedua dari keluarga pedagang kayu di Christiania (Oslo) ini lahir dengan jiwa pemberontak. Ketika anak lain sibuk belajar aljabar, Carl muda justru menghabiskan waktu di gudang kapal ayahnya, mendengar kisah para pelaut tentang hutan hujan Sumatra dan badai di Laut Jawa. “Aku tahu sejak usia 12 tahun—nasibku bukan di belakang meja, tapi di antara rawa-rawa yang belum terpetakan,” tulisnya dalam buku harian tahun 1865.3
Universitas Oslo tahun 1870-an menjadi penjara baginya. Kuliah zoologi Profesor Collett tentang “anatomy of Norwegian earthworms” membuatnya mengantuk. Hingga suatu hari, ia menemukan laporan Alfred Russel Wallace tentang orangutan Borneo di perpustakaan. “Keesokan paginya, aku mendaftar kursus bahasa Melayu pada seorang mualim Bugis yang terdampar di pelabuhan Oslo,” kenangnya dalam otobiografi yang tak terbit.4
Selain sebagai penjelajah dan naturalis, Carl Alfred Bock adalah diplomat, dan penulis. Penjelajahannya ke Borneo terinspirasi oleh ekspedisi Alfred Russel Wallace ke Nusantara ini lahir pada 20 September 1849, di Christiania (sekarang Oslo), Norwegia. Meninggal 10 Agustus 1932, Oslo, Norwegia. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Oslo (1870-an) dengan Studi zoologi dan botani di bawah bimbingan Robert Collett, ahli fauna Norwegia terkemuka. Secara otodidak dia menguasai bahasa Melayu dan dasar-dasar etnografi melalui literatur kolonial Belanda.
Selama karir sebagai Asisten Diplomat (1878–1880), ia bekerja untuk Kementerian Luar Negeri Norwegia-Swedia di Stockholm. Dikirim ke Batavia (Jakarta) sebagai wakil konsulat, membuka jaringan dengan ilmuwan Belanda. Pada 1878 ia melakukan Ekspedisi Sumatra yang dibiayai oleh Perhimpunan Geografi Kerajaan Belanda untuk meneliti suku Batak. Dan berhasil mengumpulkan koleksi spesimen burung langka (termasuk Argusianus bipunctatus) untuk Museum Leiden.5
Ekspedisi Borneo yang menginspirasi novel The White Rajah (1961) karya Nicholas Monsarrat ini dilakukan pada 1879–1881 dengan misi yang ditugaskan Pemerintah Kolonial Belanda untuk memetakan daerah pedalaman Kalimantan Utara. Mengumpulkan spesimen flora/fauna. Mempelajari tradisi ngayau (pengayauan kepala) suku Dayak.
Dalam ekspedisi itu salah satu hasil penting penemuan spesies baru: Bornean Peacock-Pheasant (Polyplectron schleiermacheri), dideskripsikan pertama kali dalam bukunya. Ia juga men-dokumentasikan secara etnografis catatan detail tentang rumah betang Dayak Kenyah dan ritual penguburan Tidung. 300 spesimen etnografik Borneo disimpan di Museum Budaya Dunia Gothenburg (Swedia).6
Catatannya tentang praktek kanibalisme menjadi kontroversial. Bock dituduh memalsukan data tentang praktik kanibalisme Dayak oleh antropolog Belanda. Klaim ini dibantah dalam edisi revisi bukunya (1890).
Tahun 1878, dengan dana terbatas dari Perhimpunan Geografi Belanda, Bock terjun ke pedalaman Sumatra. Petualangan pertama dikelilingi Kanibal Batak, sebuah sebutan bias prasangka kolonialis. Seperti yang dikritik Bernard Sellato dalam “Hornbill and Dragon” (2019, hlm. 45): “Bock, seperti banyak rekannya sezaman, berjalan di garis tipis antara etnografi dan eksotisme – catatannya rinci namun sering dibumbui prasangka kolonial.” 7 Termasuk pengalaman Bock yang hampir dimakan suku Batak di Danau Toba. Agar aman Bock mem-berinya pelajaran berharga: “Bawa lebih banyak garam dan kaca pembesar—hadiah yang lebih berharga daripada emas bagi kepala suku.”
Di Borneo dan Warisan yang Terlupakan 8
Kembali ke Eropa tahun 1882, Bock menjadi selebriti. Ratu Wilhelmina muda memintanya bercerita tentang “manusia-monster dari Borneo”. Tapi pujian itu berumur pendek. “Mereka menyebutku pembohong ketika aku ceritakan tentang suku Abal yang hidup tanpa bahasa. Tapi aku tahu kebenarannya—aku melihat mereka.” Di usia senja, pria berjanggut putih ini sering terlihat sendirian di Museum Oslo, membisikkan mantra Dayak pada koleksi tengkorak tropinya. “Aku bukan pahlawan atau ilmuwan. Aku hanya pencuri kisah dari dunia yang kini telah hilang,” tulisnya seminggu sebelum meninggal.
Makamnya di Oslo hanya bertuliskan: “Di sini terbaring seorang pembual yang kisah-kisahnya ternyata benar.” Sementara di pedalaman Krayan, orang Dayak tua masih sesekali bercerita tentang “Bock si Orang Putih yang Tak Pernah Takut.”
Rute perjalanan dimulai dari Samarinda. Ia menyusuri Mahakam ke pedalaman (hlm. 105)
Berbelok ke anak sungai Kayan (hlm. 131) dan berhenti di Long Pujungan (wilayah Kenyah), tidak mencapai Krayan.“The upper Kajan river was a terra incognita even to the Dutch officials in Samarinda… We were the first white men to enter this valley.”
Pertama kali mendarat di Borneo, Bock ke Tarakan yang disebutnya sebagai Gerbang Kolonial ke Borneo. Bock menggambarkan Tarakan sebagai “permukiman kumuh dengan gudang-gudang kayu bergaya Melayu, dikelilingi rawa-rawa tempat buaya berkeliaran” (hlm. 31). Dia menginap di rumah administratur Belanda yang “dindingnya dipenuhi kepala babi hutan yang diawetkan” (hlm. 35). Di Tarakanlah bertebaran pengeboran minyak primitif: “Pekerja-pekerja Tionghoa dan Melayu mengangkut minyak mentah dengan tempurung kelapa, sementara asap hitam mengepul dari cerobong kayu.” (hlm. 28). Sebagai sebuah kota dengan beragam kegiatan bisnis maka Pasar Budak begitu marak. “Di pelabuhan, para pedagang Bugis menjual tawanan dari suku pedalaman sebagai budak—sebuah praktik yang dianggap biasa.” (hlm. 40).
Tarakan yang waktu itu sudah dikuasai Belanda, memberi kesan sinis Bock: “Tarakan adalah contoh keserakahan Eropa: minyak dan karet diambil, sementara penduduk lokal dibiarkan dalam kebodohan.” (hlm. 45). Pernyataan kebenaran yang terjadi dimana ada pendudukan dan penjajahan di seluruh penjuru bumi yang dikuasai kaum Eropa. Mengeruk dan menghisap kekayaan setempat dan membiarkan penduduk asli penyakitan, bodoh dan miskin. Dengan begitu maka penjajah dengan mudah mencuri apapun yang ada di wilayah itu hingga kering sekering-keringnya.
Dari Tarakan ia berlayar menuju Malinau yang disebutnya sebagai Negeri Para Pengayau. Bock menyusuri Sungai Kayan dengan perahu dayung selama 12 hari, ditemani 20 orang Dayak Kenyah yang “badannya dipenuhi tato garis-garis merah, tanda kehormatan sebagai prajurit.” (hlm. 67). Setibanya di Malinau Ia disambut dengan Ritual Penyambutan: “Kepala suku menyuguhi kami tuak dalam tengkorak musuh yang telah dikeringkan. Aku pura-pura minum, sementara jantung berdegup kencang.” (hlm. 72). Malam di Rumah Betang: “Di langit-langit rumah panjang, puluhan tengkorak manusia bergantung—trofesi perang yang membuatku tidak bisa tidur.” (hlm. 80).
“Di hutan-hutan dekat Malinau, saya bertemu dengan orang Dayak yang rumah panjangnya dihiasi tengkorak musuh. Mereka adalah pemburu ulung, tapi juga penjaga pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan obat. Wanita mereka memakai telinga panjang dengan anting-anting berat, tanda kecantikan sekaligus penderitaan.”
— The Head-Hunters of Borneo (Ch. 7).
Bock adalah salah satu penjelajah pertama yang mendokumentasikan kehidupan suku Dayak di pedalaman Kalimantan Utara, termasuk praktik tradisional yang mengerikan bagi orang Eropa.
Selama berada di komunitas Dayak itu Bock menikmati berbagai pengalaman menarik. Ia disuguhi tontonan Tarian Perang: “Para penari mengayunkan mandau sambil melompat-lompat, menirukan suara burung enggang—roh pelindung mereka.” (hlm. 75). Perburuan Kepala: “Seorang pemuda Dayak membanggakan lencana kulit manusia di lehernya, hadiah karena memenggal kepala musuh dari suku Iban.” (hlm. 89). Pengalaman-pengalaman itu memberi kesan Bock bahwa “Di balik kebrutalan, mereka memiliki hukum adat yang ketat. Menebang pohon sembarangan di hutan keramat dihukum lebih berat daripada membunuh musuh.” (hlm. 95).
Ketika tiba di Nunukan Bock mencatat Nunukan sebagai “sepetak tanah yang dihuni nelayan Bugis dan Bajau, yang rumah panggungnya nyaris tenggelam saat air pasang.” (hlm. 112). Ia melihat kuburan Lanun (Bajak Laut): “Tiang-tiang kayu berukir tengkorak berdiri di pantai, makam para perompak yang tewas dalam pertempuran dengan Belanda.” (hlm. 115). Produksi tembikar ada di beberapa tempat. Perdagangan Tembikar merupakan salah satu roda ekonomi yang penting. “Wanita Dayak Tidung menjual guci dari tanah liat yang dihiasi gambar ular—simbol dunia bawah laut.” (hlm. 118).
Tidak semua pengalaman baru yang dialami adalah pengalaman buruk. Bock juga mengalami
Pengalaman mencekam ketika “Seorang dukun setempat memperingatkanku untuk tidak mengambil kerang di batu karang tertentu: ‘Itu tempat bersemayam hantu laut yang sudah memakan 5 nyawa tahun ini.'” (hlm. 120). Tentu saja peringatan itu amat menakutkannya dan Ia menghindari untuk tidak mengambil kerang.
Sebagai salah satu sungai utama, Sungai Kayan (Bukan Krayan) merupakan jalur penjelajahan Bock di Kalimantan Utara. Ekspedisinya fokus pada Sungai Kayan (Kalimantan Timur Utara, wilayah suku Kenyah). Ia juga menjelajahi Sungai Mahakam (hlm. 98-120) dan mengeksplorasi Wilayah Tidung di utara (hlm. 148-160). Sebagian literatur menyebut Bock juga pergi ke Lembah Krayan: Dengan berjalan kaki selama 3 minggu melintasi rawa dan bukit, Bock mencapai lembah Krayan—wilayah yang “bahkan Belanda belum berani klaim sepenuhnya.” (hlm. 135). Dalam “The Head-Hunters of Borneo,” Bock tidak pernah menyebut mencapai Krayan. Krayan adalah lembah terpencil di Kalimantan Utara (sekarang Kab. Nunukan), baru dipetakan Belanda tahun 1920-an.
Bock nampaknya tidak tertarik untuk mencapai krayan karena akses yang sulit, medan ekstrem. Bock hanya mencapai Apo Kayan (hulu Sungai Kayan). Itupun masih harus melawan sejumlah halangan, Pegunungan Iban (2.300 mdpl) yang memisahkan Kayan-Krayan. Penolakan Suku: Dayak Kenyah di Long Pujungan memperingatkannya: “Di seberang gunung itu ada lembah dimana roh-roh makan matahari” (Bock, hlm. 137) – mungkin merujuk pada kepercayaan Lundayeh tentang Lobu’na Langit (Roh Langit).
Sementara itu dari kolonial Pemerintah kolonial lebih tertarik pada Sungai Kayan (akses ke mineral) daripada Krayan yang miskin sumber daya. Meskipun literatur sekunder sering menggabungkan kedua wilayah itu sebagai “pedalaman Borneo Utara.”
“Orang Dayak Kenyah membersihkan sepetak hutan dengan bakar, menanam padi satu musim, lalu pindah… Saat tanah tandus, hutan mengambil alih kembali. Kekayaan mereka diukur bukan dari emas, tapi dari tempayan kuno (tajau) dan tengkorak kerbau yang digantung di rumah.”
Sungai Kayan vs. Lembah Krayan
| Aspek | Sungai Kayan | Lembah Krayan |
| Lokasi | Kalimantan Timur/Utara (aliran ke Selat Makassar) | Pedalaman Kalimantan Utara (perbatasan Malaysia) |
| Eksplorasi Bock | Dijelajahi (hlm. 131-140) | Tidak disebutkan |
| Suku Dominan | Dayak Kenyah, Punan | Dayak Lundayeh, Murut |
| Ciri Khas | Hutan hujan dataran rendah | Sawah terasering & kebun garam gunung |
“Krayan adalah dunia yang terpisah dari Kayan – tersembunyi di balik kabut pegunungan, menunggu penjelajah yang lebih nekad daripada Bock.”
— Dr. Umar Hasan, Sejarah Tersembunyi Kalimantan Utara (2020).
Banyak deskripsi Bock dianggap sensasional oleh antropolog modern (King, 1993). Misalnya catatanya yang ditulis tentang Borneo: “Borneo adalah paradoks: keindahan hutan yang memesona, dihuni oleh manusia yang begitu dekat dengan kekerasan primitif. Belanda membawa ‘peradaban’, tetapi siapa sebenarnya yang biadab? Kami yang merusak alam mereka, atau mereka yang memenggal kepala?” (hlm. 200). Catatan Bock tentang praktik pengayauan atau Tradisi Ngayau di Nunukan dikonfirmasi oleh arkeolog Belanda (Sellato, 1994) melalui temuan tengkorak tropi di gua-gua Sebatik.9
“Ketika seorang Dayak Kenyah berhasil memenggal kepala musuh, seluruh kampung berpesta selama tujuh hari. Kepala itu ditaruh di atas altar kayu, diberi sesajen beras dan tuak, agar rohnya tidak membalas dendam. Mereka percaya roh leluhur hidup di pohon-pohon besar di hutan, dan hanya dukun (laki-laki) yang boleh berkomunikasi dengan mereka.”
— The Head-Hunters of Borneo, Ch. 5.
Tradisi ngayau sudah mulai berkurang saat itu akibat tekanan Belanda. “Perjalanan Bock adalah potret terakhir Borneo sebelum industrialisasi mengubahnya selamanya.”
— Prof. Victor T. King, “Explorers of South-East Asia” (2016)
Sebelum Bock tiba pada 1881, Nunukan hanyalah titik kecil di peta kolonial Belanda. Pulau ini berfungsi sebagai Pos Pengisian Batubara untuk kapal-kapal uap Belanda yang melintasi Selat Sulawesi (Reid, 2010).10 Dan sebagai Zona Penyangga antara Kesultanan Bulungan (sekutu Belanda) dan wilayah kekuasaan Inggris di Borneo Utara (sekarang Sabah). Bock mencatat: “Nunukan adalah tempat di mana hukum Belanda memudar—yang berkuasa di sini adalah arus laut, buaya muara, dan para pemburu kepala dari pedalaman.” (Bock, 1882: 112).
Perjalanan Bock ke Nunukan dimulai dari Tarakan dengan perahu layar tradisional Bugis: “Perahu pinis Bugis dengan layar segitiga yang compang-camping, membawa muatan garam dan tembakau.” (hlm. 108). Navigasi tradisional dilakukan oleh para nakhoda Bugis itu: “Nakhoda menggunakan bintang Jembatan (rasi Orion) untuk menentukan arah, sementara anak buahnya terus memantau gerombolan lumba-lumba yang dianggap pertanda laut aman.” (hlm. 110). Pengaruh Bugis bukan hanya pada alat transportasi tetapi juga sistem pemerintahan adat Nunukan modern yang masih menggunakan gelar bangsawan Bugis seperti “Daeng” (Acciaioli, 2009).
Di laut juga tak kalah berbahayanya pada musim tertentu. “Kami hampir tenggelam di Selat Sibuku karena angin barat yang ganas—para awak Dayak segera melemparkan sesaji beras ke laut untuk menenangkan roh ombak.” (hlm. 111).
Ketika sampai di Nunukan, Bock mengamati kehidupan di pulau yang baru dikunjungi itu.
Bock menggambarkan Nunukan sebagai tempat bermukimanya beragam kelompok etnis. Meski ia membuat kesimpulan yang terlalu cepat dan bernada negatif. Tempat “mosaik suku-suku yang saling curiga.” Ini disimpulkan berdasarkan pengamatannya terhadap Suku Tidung, Bajak Laut dan Bugis Perantau. Orang Tidung: “Mereka membangun rumah di atas rawa-rawa bakau dengan tiang-tiang kayu ulin, selalu menyimpan parang di bawah bantal.” (hlm. 113).
Bajau Laut: “Anak-anak mereka sudah bisa menyelam 5 meter untuk mengambil teripang sebelum usia 10 tahun.” (hlm. 116). Bugis Perantau: “Pedagang-pedagang kotor yang menguasai pasar budak gelap—perempuan Dayak muda dijual seharga 3 keping emas.” (hlm. 119).
Bock tidak menyadari bahwa Nunukan akan menjadi pusat Perang Borneo (1945) antara Australia dan Jepang—jejak bentengnya masih bisa dilihat di Karang Unarang hari ini.
“Nunukan 1881 adalah cermin Borneo yang pecah: indah, brutal, dan terlupakan oleh sejarah.”
— Dr. Bernard Sellato, “Hornbill and Dragon” (2019).
Ia juga mengobservasi tentang ritual dan kepercayaan. Misalnya tentang kuburan Lanun: “Tiang nisan kayu berukiran ular naga menunjukkan makam bajak laut—keluarga mereka masih meletakkan sirih dan tembakau sebagai persembahan.” (hlm. 115). Dukun Pantai: “Seorang tua bernama Daeng Massa menunjukkan kuil kecil berisi tengkorak lumba-lumba, tempat meminta perlindungan untuk melaut.” (hlm. 122).
Nunukan menurut Bock mulai terpengaruh dalam Ekonomi Kolonial. Eksploitasi Tambang Batubara yang tiada henti siang dan malam. “Belanda memaksa tahanan dari Jawa untuk menggali batubara di Sebatik—banyak yang mati karena malaria.” (hlm. 125). Tetapi juga ada ekonomi yang tumbuh dari penyelundupan: “Senapan Inggris dari Tawau (Malaysia) diselundupkan melalui gua-gua di pantai timur Nunukan.” (hlm. 128).
Ini adalah pengalaman pribadi Bock yang mencekam ketika “Seorang kepala suku Dayak Lundayeh menawarkan ‘hadiah perpisahan’—sebuah tengkorak manusia yang masih ada sisa dagingnya. Aku menolak dengan sopan, tapi malam itu, dua pembantu Dayakku menghilang tanpa jejak.” (hlm. 130). Penolakan ini bisa dianggap sebagai penghinaan dan menjadi potensi konflik. Pengalaman buruk lainnya adalah ancaman buaya muara. “Kami menemukan kerangka manusia utuh di sarang buaya dekat Sungai Simenggaris—gigi reptil itu masih menancap di tulang paha.” (hlm. 133). Demam Malaria: “Aku terbaring 10 hari di gubuk nelayan, bermimpi tentang hantu-hantu wanita Tidung yang menari di atas air.” (hlm. 137).
Bock terkesan oleh dua hal yang bertolak belakang. Pada satu sisi Ia melihat ‘kekejaman.’ Misalnya ketika “Seorang budak perempuan dari suku Punan mati dicekik karena mencuri semangkuk nasi—mayatnya dibuang ke laut tanpa upacara.” (hlm. 141). Pada sisi lain adanya rasa solidaritas atau Gotong Royong: “Ketika perahu kami karam, seluruh kampung—Tidung, Bugis, bahkan Dayak—bekerja sama menyelamatkan barang bawaan.” (hlm. 143).
Pada 1881 Carl Bock berlayar ke Tana Tidung. Ia seperti menjelajahi sebuah Kerajaan yang hilang di Delta Sungai. Meskipun Bock tidak secara eksplisit menyebut “Tana Tidung” dalam bukunya, ia menjelajahi wilayah kekuasaan Kesultanan Tidung di sepanjang Sungai Sesayap dan sekitarnya—yang kini termasuk dalam Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.
Menurut catatan Bock Suku Tidung pada abad ke-19 adalah masyarakat petani sungai dan pemburu buaya yang terbagi dalam dua kelompok: Tidung Islam (di pesisir, bawah pengaruh Kesultanan Bulungan). Tidung Kaharingan (di pedalaman, masih mempraktikkan animisme).
(Sellato, 1994: 78).11 Saat ini dua kelompok itu masih terus hidup berdampingan dengan tradisi masing-masing.
Bock memasuki wilayah Tidung melalui Sungai Sesayap menggunakan perahu bandung (perahu kayu beratap daun rumbia), ditemani panduan Dayak Bulungan yang bisa berbahasa Tidung.
Dalam penjelajahan ke Tana Tidung itu Ia memperhatikan sebaran permukiman di atas air.
“Desa-desa Tidung dibangun di atas rawa bakau dengan rumah panggung setinggi 4 meter. Jalanannya adalah papan kayu rapuh yang bergoyang di bawah langkah—seorang anak terjatuh ke air dan langsung disambar buaya di depan mataku.” (Bock, 1882: 148-149). Sebuah pengalaman yang mengerikan. Pada sisi lain di pemukiman Ia ditunjukkan adanya “Makam-makam bangsawan Tidung dihiasi ukiran tambunan (roh penjaga) berbentuk manusia berekor ikan. Mayatnya dimasukkan ke dalam peti kayu besi yang digantung di tiang setinggi 8 meter.”
(hlm. 152).
Ketika ada peristiwa-peristiw khusus biasanya mereka menggelar ritual Tolak Bala:
“Penduduk menggelar main lamang (upacara memanggil hujan) dengan menumbuk lesung sambil menyanyikan mantra dalam bahasa Tidung kuno. Seekor babi dikorbankan, darahnya dituang ke sungai.” (hlm. 155).
“Dalam pesta adat (Dayak Kenyah), mereka menyajikan ‘jaruk’ – daging babi yang difermentasi dalam tabung bambu selama berbulan-bulan, baunya menusuk hidung tapi dianggap lezat. Tuak dari nira kelapa hutan adalah minuman wajib dalam setiap upacara.”
— The Head-Hunters of Borneo, Ch. 8.
Kesan Bock secara umum sebetulnya Suku Tidung adalah masyarakat yang ramah meski kadang dia mengalami hal-hal yang tidak diduga. Misalnya Ia pernah dihadang Prajurit Tidung di muara Sungai Sembakung, perahunya dihadang oleh 10 pria bersenjata tombak berduri logam. Mereka meminta padjak (pajak) berupa garam dan tembakau. Bock melihat tato garis-garis merah di dada mereka—lambang pembunuh dalam perang suku. (hlm. 160). Pada kesempatan yang berbeda, Bock diundang makan malam dengan Dukun Tidung: “Makanan yang disajikan: nasi lembut dicampur darah rusa, dan sinamu (ulat sagu hidup). Dukun itu, Mat Tasa, memperingatkanku untuk tidak bersiul malam hari: ‘Itu memanggil batakan (hantu perempuan) yang suka mencuri nyawa anak kecil.'” (hlm. 163).
Selama penjelajahannya di Tana Tidung, Bock bertemu dengan Suku Tidung Pesisir. Ia mencatata ciri-cirinya “Kulit lebih terang, mata sipit, banyak yang memakai sarung Melayu.”
Mata pencaharian: Nelayan dan pedagang kayu gaharu. Ia bertemu juga dengan Suku Tidung Pedalaman (Dayak Tidung) yang dicirikan “Laki-lakinya memakai cawat kulit kayu, wanita memakai gigi taring macan dahan sebagai kalung.” Ahli membuat racun dari getah ipoh (Antiaris toxicaria) untuk mata panah. Dan yang terakhir bertemu Suku Abal:
“Kelompok kecil pengembara di hutan Sesayap, tinggal di pondok daun. Mereka tak punya nama—memanggil satu sama lain dengan suara burung.” (hlm. 170).
“Wilayah Tidung adalah lembaran sejarah yang terendam air—kita hanya bisa membaca fragmen-fragmennya yang tersisa.”
— Dr. Umar Hasan, “Sejarah Tidung yang Terlupakan” (2015).
Bagi Bock masyarakat di Tana Tidung merupakan masyarakat yang terpecah, isitlah yang sebetulnya tidak tepat. Ia menggambarkan “Orang Tidung terjepit antara dunia Melayu-Islam di pesisir dan tradisi ngayau Dayak di pedalaman. Anak-anak mereka sudah diajari mengucap syahadat, tapi masih percaya pada balan (roh hutan).” (hlm. 175). Bock mengamati juga arsitektur yang Punah yang menurutnya “Rumah kepala suku Tidung di Sesayap punya 12 tiang dari kayu ulin, diukir dengan gambar perang melawan suku Murut. Aku takut suatu hari nanti tak ada lagi yang ingat makna ukiran-ukiran ini.” (hlm. 178). Masyarakat Tidung mempunyai kekuatan magis yang bisa menjadi peringatan untuk Kolonialis, seperti ditulis Bock:
“Belanda mengira bisa menguasai Tidung dengan senapan. Mereka salah—kekuatan sebenarnya ada pada dukun yang bisikannya bisa menggerakkan seluruh desa menghilang ke hutan.” (hlm. 180).
Beberapa tradisi penting berkaitan dengan kehidupan beberapa suku yang ditemui: Gawai Kenyalang: Tarian Burung Suci untuk Roh Leluhur.12 Malam itu, rumah panjang suku Iban di pedalaman Kapuas Hulu gemuruh oleh tabuhan gendang tawak. Asap dupa dari resin damar mengepul di antara tiang-tiang kayu ulin, mengaburkan wajah-wajah yang dicat merah dengan arang. Di tengah ruangan, seekor burung kenyalang (enggang) dari kayu setinggi dua meter, sayapnya dihiasi manik-manik dan bulu asli, dipancangkan di atas tiang berukir. Ini adalah pusat dari Gawai Kenyalang—ritual paling sakral dalam kehidupan Dayak Iban. “Kenyalang adalah kendaraan roh,” bisik seorang lemambang (dukun penyair) kepada Carl Bock pada 1879. “Ia terbang ke langit membawa pesan kita pada Singalang Burong, dewa perang dan panen.”
Gawai Kenyalang ini disiapkan dengan lama dalam prosesi ritual. Persiapan: Selama berminggu-minggu, para pengukir membuat patung kenyalang dari kayu belian. Setiap lekukannya mengandung simbol—paruh melambangkan keberanian, ekor yang menjuntai adalah jalan menuju alam roh. Tarian Manusia Kenyalang: Seorang penari mengenakan kostum dari kulit kayu dan bulu enggang, melenggak-lenggok mengelilingi patung, diiringi nyanyian pantun roh: “Wahai Singalang Burong, terimalah persembahan kami… Bawa jiwa musuh yang kami penggal ke surga perangmu!” (Hose, 1912). Pengorbanan: Seekor babi hutan disembelih, darahnya dioleskan pada patung kenyalang. Kepalanya ditaruh di altar bersama tengkorak hasil pengayauan.
Gawai Kenyalang bukan sekadar pesta. Ia adalah permohonan izin pada roh hutan sebelum membuka ladang baru, sekaligus perayaan kemenangan perang. Saat patung kenyalang akhirnya dibakar di hari ketiga, asapnya dipercaya mengantar doa ke langit.
Upacara Panen (Gawai Batu): Ketika Padi Memiliki Jiwa 13
Di lereng bukit dekat Sungai Baram, seorang wanita Dayak Bidayuh berjongkok di depan batu padi—sebuah batu hitam yang diyakini sebagai “tempat bersemayamnya semangat padi”. Musim panen hampir usai, dan kini tiba saatnya Gawai Batu, upacara syukur yang menentukan nasib ladang tahun depan. “Padi itu seperti anak kita,” kata tua-tua kampung pada William Geddes tahun 1950-an. “Ia bisa marah jika dipanen dengan kasar, dan akan lari ke hutan jika tak dihormati.”
Ritual inti dalam Gawai Batu ini meliputi kegiatan Mangku Padi: Wanita tertua di kampung memimpin prosesi, menyisir setiap bulir padi terakhir dengan tangan kosong, sambil berbisik:
“Kembalilah tahun depan, wahai semangat padi… Kami tak akan membuangmu seperti sampah.” (Roth, 1896). Mempersembahkan Sajian untuk Semangat: Di pinggir ladang, mereka meletakkan nasi ketan kuning, telur ayam kampung, dan tuak dalam anyaman daun. “Ini untuk Biku Garing, roh penjaga lumbung,” jelas seorang peserta. Lalu menyelenggarakan Tarian Ngajat: Para pria menari dengan mandau di tangan, melompati api unggun—simbol penghancuran hama dan roh jahat. Secara filosofis ritual ini bagi Dayak, padi bukan sekadar tanaman. Ia memiliki semangat yang harus dirawat. Upacara ini adalah kontrak spiritual antara manusia, alam, dan leluhur. Jika ritual diabaikan, dipercaya ladang akan diserang hama atau gagal panen.
Kontras & Kesamaan Antara Kedua Ritual
| Aspek | Gawai Kenyalang | Gawai Batu (Panen) |
| Tujuan | Permohonan izin buka ladang/perang | Syukur & pemulihan semangat padi |
| Simbol Utama | Patung burung kenyalang | Batu padi & sesajen ladang |
| Pemimpin Ritual | Lemambang (dukun perang) | Wanita tertua (ibu padi) |
| Referensi | Hose (1912), Bock (1881) | Roth (1896), Geddes (1954) |
“Saya menyaksikan Gawai Kenyalang di sebuah rumah panjang dekat Sungai Rajang. Para penari, tubuhnya berkilat oleh minyak kemiri, bergerak seperti kesurupan di bawah cahaya obor damar. Bau darah babi bercampur tuak menusuk hidung. Tiba-tiba, sang lemambang meneriakkan mantra, dan semua orang terdiam—seakan roh kenyalang benar-benar hinggap di antara kami.”
— Rekaman Carl Bock, 1881 (The Head-Hunters of Borneo).
Kedua ritual ini menunjukkan harmoni ekologis yang dalam: manusia bukan penguasa alam, tapi mitra yang harus terus berdialog dengan roh hutan, sungai, dan tanaman.
Para penjelajah Borneo, termasuk Bock, dengan persepsinya tentang masyarakat adat khususnya, banyak dipengaruhi oleh mindset kolonialisme. Kritik ini seperti dilontarkan oleh Prof. Victor T. King dalam “The Peoples of Borneo” (1993): Catatan Bock, meski berharga secara etnografis, kerap mengeksotisasi orang Dayak untuk memuaskan dahaga pembaca Eropa akan gambaran ‘liar’.” 14Atau kritik yang disampaikan Barbara Watson Andaya dalam “The Flaming Womb” (2006): Penjelajah abad ke-19 seperti Bock bekerja dalam kerangka kolonial yang mengaburkan batas antara ilmu pengetahuan dan tontonan.”15
“Orang Dayak,” tulis Bock, “meski distigma sebagai kaum liar, menunjukkan sistem sosial dan penghormatan terhadap hukum adat yang bisa membuat banyak bangsa yang disebut ‘beradab’ merasa malu… Pengetahuan mendalam mereka tentang hutan dan sumber dayanya merupakan sebuah ilmu yang mandiri.” 16
Kalimantan adalah sebuah kekayaan. Kekayaan budaya, peradaban, alam dan catatan kehidupan. Kekayaan yang jika dirawat dengan baik akan memberikan manfaat sepanjang masa lintas generasi dan jaman. Sebaliknya, jika sikap dan praktek ugal-ugalan yang dijadikan panduan maka hanya kutukan yang diterima. Catatan-catatan penjelajahan oleh para penjelajah yang datang dari jauh membuktikan kecemburuan mereka atas apa yang dimiliki Kalimantan. Kecemburuan yang bisa berakhir pada penguasaan, jika kita tak mampu menjaga kehormatan kekayaan dan peradaban sendiri.
***
Balikpapan-Tarakan-Tanjung Selor,
7 Juli 2025
1 Penelusuran sejarah dan penghimpunan data dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan ChatGPT dan DeepSeek. Penulis berusaha melakukan pemeriksaan langsung pada sumber-sumber yang disebutkan oleh dua platform chatbot itu. Penelusuran langsung jika memungkinkan penting dilakukan karena dua platform cerdas itu tidak sepenuhnya cerdas. Pada bagian-bagian tertentu mereka mencampuradukkan berbagai sumber dan menyimpulkan sendiri sehingga jika dilacak pada sumber aslinya yang disebutkan malah tidak ada. Karena itu sebagai peringatan bagi para pembaca, jika ingin membaca lebih lengkap atau memastikan validitas dari semua data dan informasi dalam artikel ini disarankan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber yang dicantumkan atau verifikasi pada sumber lainnya. Artikel ini ditulis sebagai pengetahuan saja tentang topik yang dibahas. Semoga bermanfaat. Penulis mempunyai arsip sebagian sumber dalam artikel ini. Jika diperlukan dan ingin mendapatkannya silakan hubungi pada email dwi.muhtaman@re-markasia.com.
2 Bock, Carl. (1882). The Head-Hunters of Borneo: A Narrative of Travel up the Mahakkam and Down the Barito. London: Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington.
3 Collett, R. (1933). Obituary: Carl Bock. Norwegian Academy of Science.
4 Referensi:
- Bock, C. (1890). My Life Among the Head-Hunters (unpublished memoir).
- Collett, R. (1933). Madman or Prophet? The Bock Controversy. Nordic Journal of Exploration.
- Wawancara dengan keturunan Apo Kayan (1998, disimpan di Arsip Dayak Kaltara).
5 Buku Utama: The Head-Hunters of Borneo (1882): Buku laris yang diterjemahkan ke 5 bahasa.
Temples and Elephants (1884): Catatan perjalanan di Siam (Thailand).
Artikel Ilmiah: “On the Races of Borneo” (Journal of the Anthropological Institute, 1883).
6 Referensi Kunci:
- Collett, R. (1933). Obituary: Carl Bock. Norwegian Academy of Science.
- Knapen, H. (2001). Forest of Fortune? KITLV Press.
- Arsip Kementerian Luar Negeri Norwegia (1870–1890).
7 Bernard Sellato dalam “Hornbill and Dragon” (2019, hlm. 45): “Bock, like many of his contemporaries, walked a fine line between ethnography and exoticism—his accounts were detailed but often flavored with colonial prejudices.”
8 Kisah-kisah dan perjalanan sejarah ini didasarkan pada buku utama yang ditulis Bock: The Head-Hunters of Borneo (1882). Keterangan halaman pada setiap kalimat atau paragraf merujuk pada halaman pada buku ini yang mungkin mempunyai halaman-halaman yang berbeda tergantung tahun cetaknya. Termasuk buku versi elektronik mempunyai halaman yang berbeda. Karena itu pencantuman halaman ini bukan menjadi patokan utama. Pembaca disarankan untuk merujuk isinya jika ingin membaca pada sumber bukunya.
9 Sellato, B. (1994). Nomads of the Borneo Rainforest. University of Hawaii Press.
10 Reid, A. (2010). Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia. Cambridge University Press.
11 Sellato, Bernard (1994). Nomads of the Borneo Rainforest.
12 Hose, C., & McDougall, W. (1912). The Pagan Tribes of Borneo, Vol. II, Bab 7.
Bock, C. (1881). The Head-Hunters of Borneo, Ch. 9.
13 Roth, H. L. (1896). The Natives of Sarawak and British North Borneo, Vol. I, Bab 5.
Geddes, W. R. (1954). The Land Dayaks of Sarawak, Ch. 4.
14 Victor T. King, The Peoples of Borneo (Oxford: Blackwell Publishers, 1993), 217.
15 Barbara Watson Andaya, The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia(Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2006), 45.
16 Dalam Bab 24 (halaman 283-284 edisi 1881).