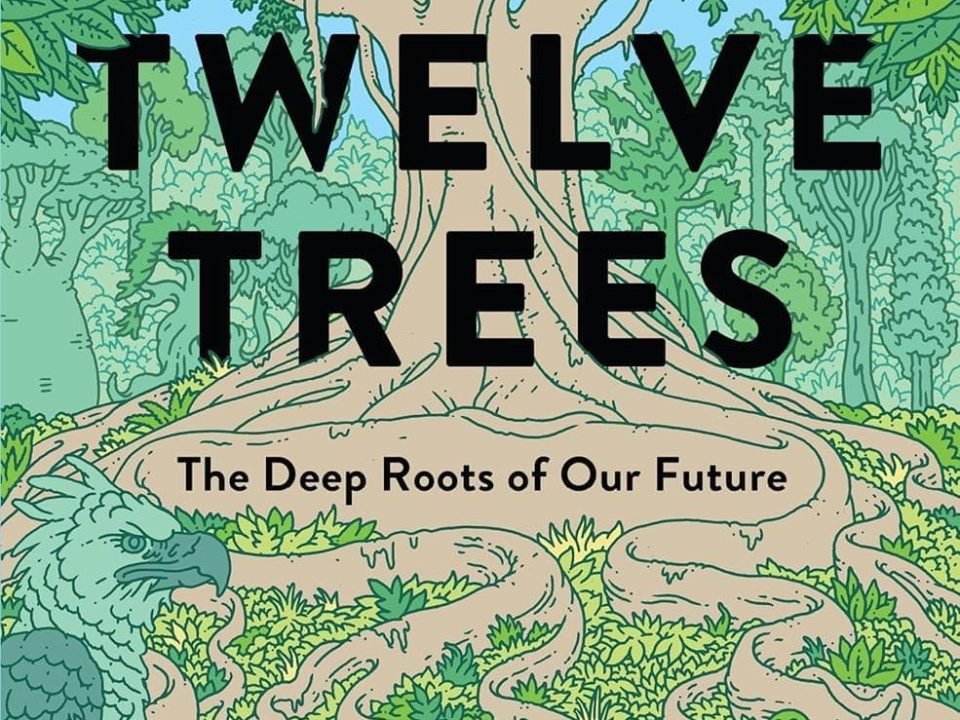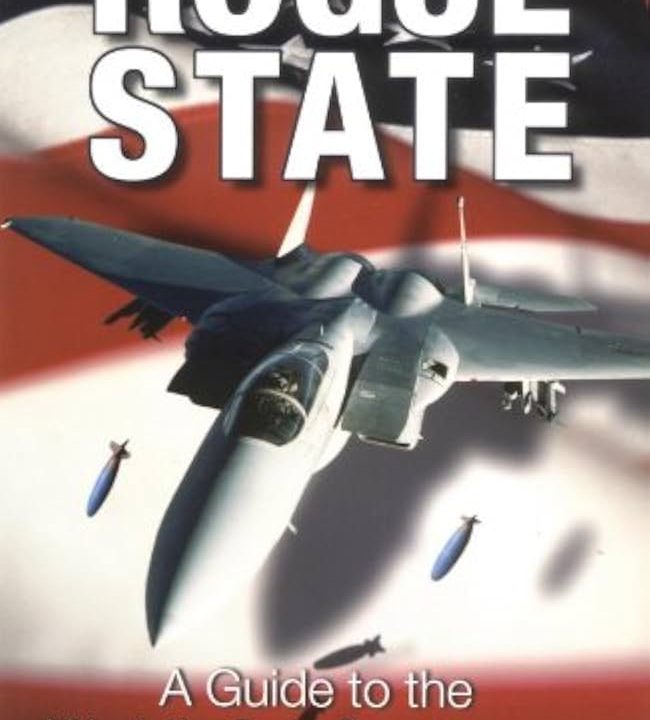Rubarubu #75
The Racket:
Retakan dalam Imperium
Dari Ruang Ber-AC ke Tambang Terbuka
Matt Kennard membuka The Racket dengan pengalaman yang terasa sederhana namun politis: seorang jurnalis Inggris duduk di ruang ber-AC milik lembaga keuangan internasional di Washington, dikelilingi grafik pertumbuhan dan jargon pembangunan. Beberapa bulan kemudian, ia berdiri di tanah retak di Afrika atau Amerika Latin—di dekat tambang terbuka, ladang minyak, atau pabrik garmen—tempat “pertumbuhan” itu menjelma menjadi upah murah, lingkungan rusak, dan kedaulatan yang terjual. Dua dunia ini, kata Kennard, tidak terpisah. Yang satu ada karena yang lain diciptakan.
Dari ketegangan inilah The Racket bergerak: sebuah laporan investigatif tentang bagaimana kekaisaran modern bekerja bukan terutama lewat pendudukan militer, tetapi melalui utang, hukum, dan institusi global. Jika Rogue State karya William Blum memetakan kekerasan terbuka imperium, maka The Racket menguliti arsitektur ekonomi-politik yang membuat kekerasan itu “tak perlu lagi terlihat.”
Dalam Foreword dan Preface, Kennard menegaskan posisinya bukan sebagai akademisi netral, melainkan sebagai reporter yang menolak bahasa kekuasaan. Ia percaya bahwa jurnalisme sebagai perlawanan terhadap normalisasi. Ia menyebut proyek ini sebagai upaya menyingkap “racket”—sebuah istilah yang sengaja dipinjam dari dunia mafia: sebuah sistem pemerasan yang dibungkus legalitas dan retorika pembangunan.
Kennard menulis dengan kesadaran bahwa banyak praktik yang ia laporkan adalah legal, bahkan dipromosikan sebagai best practices. Namun justru di situlah masalahnya. Seperti dikatakan Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan, yang paling berbahaya bukanlah kejahatan ilegal, melainkan kejahatan yang telah menjadi prosedur.
Kekaisaran Tanpa Bendera
Dalam Introduction, Kennard menyodorkan tesis utama: Amerika Serikat dan sekutunya telah membangun imperium tanpa koloni resmi, di mana kendali tidak dijalankan lewat gubernur kolonial, melainkan melalui:
- utang,
- aturan perdagangan,
- kontrak investasi,
- dan lembaga seperti IMF, Bank Dunia, serta jaringan firma hukum dan konsultan global.
Ini adalah kekaisaran yang tidak perlu menaklukkan wilayah, karena ia menguasai aturan main. Negara-negara Global South tidak “dipaksa” tunduk—mereka diposisikan dalam kondisi di mana tidak ada pilihan lain yang rasional. Kennard menggemakan kritik yang sejalan dengan Noam Chomsky: “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion.” (Chomsky, Manufacturing Consent).
Matt Kennard, reporter yang masuk langsung ke ruang mesin imperium, membuka bagian How We Owned You dengan sebuah ironi sejarah yang pahit: dunia pascakolonial merayakan kemerdekaan politik justru pada saat mekanisme baru penguasaan sedang disempurnakan. Bendera kolonial diturunkan, tetapi digantikan oleh kontrak, utang, dan “reformasi struktural” yang jauh lebih sulit dilawan karena tampil sebagai keniscayaan rasional. Inilah panggung tempat kepemilikan modern bekerja—tanpa perlu pendudukan militer, tanpa deklarasi perang, dan sering kali tanpa kesadaran mereka yang dikuasai. Inilah bagaimana kepemilikan terjadi tanpa penjajahan: sebuah narasi tentang kekuasaan yang menyamar.
Dalam The Racket, spektrum itu adalah ekonomi politik global: privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi diperlakukan bukan sebagai pilihan ideologis, melainkan sebagai hukum alam. The Racket dimulai dengan menelusuri bagaimana negara-negara pascakolonial “dibebaskan” secara politik, tetapi dikunci secara ekonomi. Kennard menunjukkan bagaimana utang luar negeri, syarat pinjaman, dan structural adjustment programs memaksa negara-negara miskin:
memotong subsidi publik, membuka pasar bagi korporasi asing, dan menekan upah tenaga kerja.
Hasilnya adalah negara yang berdaulat secara formal, namun tidak secara substantif—sebuah kondisi yang Kennard sebut sebagai modern-day slave state. Di sini, perbudakan bukan lagi rantai besi, melainkan kontrak, bunga, dan ketergantungan fiskal. Pemikir Muslim kontemporer seperti Ali Shariati pernah mengingatkan bahwa penindasan modern sering tampil sebagai rasionalitas teknokratis—penjajahan yang tidak lagi menyebut dirinya penjajahan, melain-kan reform.
Inilah jantung buku. The racket adalah jaringan kepentingan yang menghubungkan pemerintah negara kuat, lembaga internasional, korporasi multinasional, firma hukum, dan konsultan. Kennard menunjukkan bagaimana: kebijakan publik dirancang agar menguntungkan investor,
risiko disosialisasikan ke publik, sementara keuntungan diprivatisasi. Ia mengunjungi berbagai negara dan mendapati pola yang sama: sumber daya alam diekstraksi, keuntungan mengalir keluar, dan ketika krisis datang, rakyat diminta “berhemat”. Ini mengingatkan pada ungkapan Eduardo Galeano dalam Open Veins of Latin America: “We export raw materials and import poverty.”
Namun The Racket memperlihatkan bahwa sistem global tidak “rusak”—ia dirancang demikian. Kennard menguraikan bagaimana: perjanjian perdagangan memberi hak istimewa pada investor, mekanisme arbitrase internasional memungkinkan korporasi menggugat negara, dan hukum internasional lebih melindungi modal daripada manusia atau alam.
Dalam konteks keberlanjutan planet, buku ini sangat relevan. Krisis iklim bukan kegagalan teknis, melainkan hasil sistem yang memberi insentif pada eksploitasi tanpa batas. Seperti dikatakan filsuf Jerman Karl Polanyi, ketika pasar dilepaskan dari kendali sosial, maka masya-rakat dan alam akan menjadi korbannya (The Great Transformation). Yang menarik Bab Cursing Your Riches membahas resource curse—kutukan kekayaan. Negara-negara kaya sumber daya justru sering mengalami: konflik, korupsi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi.
Kennard dibesarkan dan dibentuk secara intelektual dalam tradisi jurnalisme investigatif yang tidak puas dengan pernyataan resmi dan konferensi pers. Ia adalah jurnalis yang percaya bahwa kebenaran sering bersembunyi di balik pintu tertutup, ruang rapat korporasi, dan markas militer—dan bahwa tugas reporter adalah mengetuk pintu-pintu itu, bahkan jika tidak diundang. Ia menunjukkan bahwa kutukan ini bukan takdir, melainkan hasil interaksi antara elite lokal dan kepentingan global. Minyak, mineral, dan kayu menjadi berkah bagi segelintir, tetapi beban bagi banyak orang dan generasi mendatang. Dalam konteks Indonesia, bab ini terasa sangat dekat: dari tambang nikel, batubara, hingga sawit. Pertanyaannya bukan sekadar “berapa pertumbuhan yang dihasilkan”, melainkan siapa yang menanggung biayanya—dan siapa yang mewarisi kerusakannya.
The Racket membantu kita memahami bahwa krisis keberlanjutan bukan hanya krisis lingkung-an, tetapi krisis sistem ekonomi global. Selama: alam diperlakukan sebagai komoditas, negara didorong bersaing menarik modal dengan menurunkan standar sosial–lingkungan, dan pem-bangunan diukur semata lewat GDP, maka transisi hijau akan selalu rapuh.
Bagi Indonesia, buku ini relevan sebagai peringatan strategis: transisi energi tidak boleh menjadi racket baru, hilirisasi harus disertai kedaulatan pengetahuan dan teknologi, dan keberlanjutan harus dimaknai sebagai keadilan antarwilayah dan antargenerasi.
Dalam “Creating a Modern-day Slave State”, Kennard menunjukkan bahwa bentuk perbudakan baru tidak lagi bergantung pada rantai besi, melainkan pada ketergantungan ekonomi yang dilembagakan. Negara-negara Global South, yang baru keluar dari kolonialisme formal, segera dimasukkan ke dalam rezim utang internasional. Pinjaman yang ditawarkan oleh IMF dan Bank Dunia datang dengan syarat-syarat yang tampak teknis namun berdampak politis mendalam: pemotongan subsidi, privatisasi layanan publik, pembukaan pasar, dan penekanan upah.
Negara tetap ada, pemerintah tetap berfungsi, tetapi ruang kebijakannya menyusut drastis. Kennard menyebut kondisi ini sebagai modern-day slave state—bukan karena negara-negara ini tidak berdaulat secara hukum, melainkan karena mereka tidak bebas menentukan arah ekonomi dan sosialnya sendiri. Di sini, opini Kennard berakar kuat pada kritik terhadap structural adjustment programs yang dibahas luas dalam literatur ekonomi politik pembangun-an, namun ia menyajikannya lewat kisah-kisah lapangan dan suara mereka yang terdampak langsung.
Dari kondisi inilah lahir apa yang ia sebut secara lugas sebagai “The Racket”. Dalam bab ini, Kennard meminjam istilah dunia kriminal untuk menjelaskan sistem yang secara formal legal namun secara moral bermasalah. Racket adalah jaringan kepentingan yang menghubungkan pemerintah negara kuat, lembaga keuangan internasional, korporasi multinasional, firma hukum, dan konsultan global. Negara-negara miskin tidak dipaksa dengan todongan senjata, melainkan dengan logika: jika ingin akses modal, stabilitas mata uang, dan kepercayaan pasar, mereka harus bermain sesuai aturan. Aturan itu sendiri dirancang oleh mereka yang diuntung-kan olehnya. Kennard menekankan bahwa ini bukan konspirasi rahasia, melainkan mekanisme terbuka yang dinormalisasi. Para teknokrat berbicara tentang efisiensi, investor tentang iklim usaha, sementara dampaknya—pengangguran, ketimpangan, dan kerusakan sosial—dianggap sebagai “biaya transisi”.
Narasi kemudian mengalir ke “Rigging the System”, di mana Kennard memperlihatkan bahwa sistem global tidak gagal; ia justru bekerja persis seperti yang dirancang. Perjanjian perdagang-an dan investasi internasional memberi perlindungan luar biasa kepada modal, sementara negara dan warga negaranya dibatasi ruang geraknya. Mekanisme arbitrase internasional memungkinkan perusahaan menggugat negara jika kebijakan publik dianggap mengganggu keuntungan yang diharapkan. Dalam konteks ini, demokrasi menjadi rapuh: suara rakyat bisa dibatalkan oleh kontrak yang ditandatangani bertahun-tahun sebelumnya. Opini Kennard di sini bertumpu pada analisis hukum dan politik ekonomi global—bahwa rule of law internasional sering kali lebih berfungsi sebagai rule of capital. Ia menunjukkan bagaimana bahasa hukum dan netralitas prosedural justru menjadi alat paling efektif untuk mengunci ketimpangan.
Puncak ironi bagian ini hadir dalam “Cursing Your Riches”, ketika Kennard membahas apa yang dikenal sebagai resource curse. Negara-negara yang kaya minyak, gas, mineral, atau sumber daya alam lainnya justru sering mengalami stagnasi, konflik, dan kehancuran lingkungan. Namun Kennard menolak menjelaskan fenomena ini sebagai kutukan alam atau kegagalan budaya lokal. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa “kutukan” itu adalah hasil interaksi sistemik antara kekuatan global dan elite domestik, di mana sumber daya alam dijadikan jaminan utang, objek spekulasi, dan ladang keuntungan cepat. Kekayaan yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan kolektif berubah menjadi alasan bagi intervensi, korupsi, dan keter-gantungan yang lebih dalam. Di sinilah racket mencapai bentuk paling telanjang: tanah dan tubuh manusia diubah menjadi neraca keuangan.
Disatukan, keempat bab dalam How We Owned You membentuk satu alur narasi besar: kepemilikan modern tidak membutuhkan penjajahan, karena ia bekerja melalui persetujuan yang dipaksakan oleh keadaan. Negara-negara Global South “memilih” kebijakan tertentu, tetapi pilihan itu dibuat dalam kondisi ketergantungan struktural. Kennard tidak menulis sebagai moralis yang berdiri di luar sistem, melainkan sebagai reporter yang mene-lusuri jejak-jejak konkret kekuasaan—di kantor bank, ruang negosiasi, dan ladang-ladang yang dieksploitasi.
Bagian ini juga secara implisit mengajukan kritik mendalam terhadap gagasan pembangunan konvensional. Jika pembangunan berarti pertumbuhan yang mengorbankan kedaulatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis, maka The Racket memaksa kita bertanya: siapa yang sebenarnya dimiliki oleh siapa? Negara yang berutang, atau sistem yang bergantung pada eksploitasi tanpa akhir? Dengan gaya bertutur yang tajam namun terkendali, How We Owned You bukan sekadar laporan tentang ketimpangan global, melainkan peta kekuasaan zaman kita—sebuah undangan untuk melihat bahwa di balik bahasa teknokrasi yang halus, ada relasi dominasi yang sangat tua, hanya berganti wajah.
Penegakan Tanpa Hukum: Kekerasan sebagai Bahasa Terakhir Kekuasaan
Jika Part 1: How We Owned You menjelaskan bagaimana kepemilikan global diciptakan, maka Part 2: Enforcementmenjawab pertanyaan yang lebih gelap dan lebih jujur: bagaimana sistem itu dipertahankan ketika persuasi, utang, dan kontrak tidak lagi cukup. Di sinilah Matt Kennard memperlihatkan bahwa di balik wajah legalistik dan teknokratis imperium modern, selalu ada perangkat penegakan—aliansi militer, perang narkotika, kriminalisasi perlawanan, dan kekerasan simbolik maupun nyata—yang memastikan “aturan main” tidak dilanggar.
Dalam “The Mob”, Kennard secara sengaja menggunakan metafora dunia kriminal untuk menggambarkan cara kerja kekuasaan global. Ia menunjukkan bahwa hubungan antara negara adidaya dan negara klien sering kali menyerupai hubungan antara bos mafia dan wilayah kekuasaannya: perlindungan ditawarkan, tetapi dengan harga ketaatan mutlak. Negara yang patuh mendapat bantuan militer, akses pasar, dan legitimasi internasional; negara yang membangkang menghadapi sanksi, destabilisasi, atau intervensi terbuka. Opini Kennard di sini berangkat dari pengamatan langsung terhadap kebijakan luar negeri AS, yang—menurutnya—lebih sering beroperasi melalui logika intimidasi daripada prinsip hukum internasional. Kekuasaan tidak perlu selalu digunakan; cukup diperagakan agar efektif.
Logika ini berlanjut dalam “With Friends Like These”, sebuah bab yang menguliti mitos aliansi dan persahabatan internasional. Kennard menunjukkan bahwa banyak rezim otoriter, pelanggar HAM, dan oligarki korup justru bertahan lama karena mereka adalah “teman yang berguna”. Selama mereka membuka pasar, menekan oposisi domestik, dan menjaga stabilitas yang menguntungkan modal asing, dosa-dosa mereka dapat ditoleransi, diredam, atau dihapus dari narasi resmi. Di sini, Kennard menyoroti kemunafikan moral kebijakan luar negeri: demokrasi dan hak asasi manusia dijunjung tinggi sebagai wacana, tetapi dinegosiasikan sebagai variabel sekunder dalam praktik. Bab ini memperlihatkan bahwa enforcement sering kali dilakukan bukan dengan menggulingkan rezim represif, melainkan dengan menopangnya secara selektif.
Dalam “Might Is Right”, Kennard membawa pembaca ke inti doktrin yang jarang diucapkan secara terbuka namun konsisten diterapkan: kekuatan menciptakan kebenaran. Hukum internasional, Piagam PBB, dan norma global hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan strategis kekuatan besar. Ketika bertentangan, hukum ditafsirkan ulang, dilewati, atau diabaikan. Kennard mengaitkan ini dengan sejarah intervensi militer, kudeta terselubung, dan operasi rahasia yang dibenarkan atas nama stabilitas, keamanan, atau “kepentingan nasional”. Opini dalam bab ini jelas: dunia pasca–Perang Dingin tidak menjadi lebih berbasis hukum, melainkan lebih telanjang dalam penggunaan kekuasaan—karena tidak ada penyeimbang yang setara.
Dimensi penegakan yang lebih halus namun tak kalah destruktif muncul dalam “A Drug War Colony”. Di sini, Kennard menelusuri bagaimana perang melawan narkoba dijadikan alat geopolitik untuk memperluas pengaruh militer dan keamanan di negara-negara tertentu, terutama di Amerika Latin. Dengan dalih memerangi kartel dan kriminalitas, negara-negara klien didorong untuk memiliterisasi aparat keamanan mereka, mempersempit ruang sipil, dan menerima kehadiran penasihat serta pasukan asing. Dampaknya bukan hanya kegagalan mengatasi narkotika, tetapi juga meningkatnya kekerasan, pelanggaran HAM, dan kriminalisasi kaum miskin. Kennard menekankan bahwa “perang” ini lebih efektif sebagai mekanisme kontrol politik daripada sebagai kebijakan kesehatan publik.
Narasi enforcement mencapai dimensi eksistensial dalam “War on Hope”. Di sini, Kennard tidak hanya berbicara tentang bom, senjata, atau operasi militer, tetapi tentang sesuatu yang lebih mendasar: penghancuran harapan kolektif. Perang, sanksi, dan penindasan sistemik tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga imajinasi sosial—kemampuan masyarakat untuk membayangkan masa depan yang berbeda. Ketika pendidikan dihancurkan, ekonomi dilemahkan, dan perlawanan dikriminalisasi, yang mati bukan hanya individu, tetapi kemungkinan sejarah alternatif. Opini Kennard di bab ini bersifat reflektif dan moral: penegakan imperium tidak selalu bertujuan memenangkan wilayah, melainkan mencegah lahirnya contoh bahwa dunia bisa diatur secara lain.
Jika disintesiskan, Part 2: Enforcement menunjukkan bahwa kekuasaan global modern bertahan bukan terutama karena legitimasi, tetapi karena kemampuannya mengelola ketakutan dan ketergantungan. Kekerasan tidak selalu hadir sebagai invasi spektakuler; ia hadir sebagai jaringan kebijakan, bantuan militer, narasi keamanan, dan normalisasi darurat permanen. Kennard memperlihatkan bahwa sistem ini tidak stabil karena ia kuat, tetapi kuat karena ia terus-menerus dipaksakan.
Bagian ini sekaligus memperdalam kritik Kennard terhadap tatanan global kontemporer: tanpa mekanisme akuntabilitas yang setara, “penegakan” berubah menjadi impunitas struktural. Negara kuat jarang diadili atas tindakannya, sementara negara lemah diminta mematuhi aturan yang sama persis ketika mereka melanggarnya. Dalam dunia seperti ini, enforcement bukan penegakan hukum, melainkan penegakan hierarki.
Dengan gaya reportase yang tajam dan narasi yang sarat ironi, Part 2 menegaskan bahwa memahami kekuasaan hari ini berarti memahami bagaimana kekerasan diinstitusionalisasi, disamarkan, dan dirasionalisasi. Dan di balik semua itu, seperti yang ingin ditunjukkan Kennard, pertanyaan yang paling mengganggu tetap sama: jika sistem global ini ditegakkan dengan cara-cara seperti ini, nilai apa yang sebenarnya ia lindungi—dan siapa yang dikorbankan untuk menjaganya tetap berdiri?
Sebagai jurnalis untuk Financial Times, Kennard meliput krisis keuangan global dan menyaksikan dari dekat bagaimana sistem ekonomi internasional bekerja untuk melindungi yang kuat dan mengorbankan yang lemah. Namun ia segera menyadari bahwa banyak cerita paling penting tidak bisa ditulis sepenuhnya di media arus utama. Dari ketegangan inilah lahir The Racket: A Rogue Reporter vs the American Empire (2015).
Penguatan dari Dalam: Bagaimana Imperium Dipelihara di Rumah Sendiri
Jika Part 1 menjelaskan bagaimana dunia “dimiliki” dan Part 2 bagaimana kepemilikan itu ditegakkan secara global, maka Part 3: Reinforcement membawa pembaca ke tempat yang sering luput dari kritik imperium: ke dalam jantung negeri itu sendiri. Di sini Matt Kennard menunjukkan bahwa kekuasaan global tidak mungkin bertahan tanpa penguatan domestik yang sistematis. Imperium tidak hanya dibangun lewat perang di luar negeri, tetapi lewat pengaturan ulang sejarah, kerja, kemiskinan, dan hukuman di dalam negeri. Amerika Serikat, dalam bacaan Kennard, bukan pengecualian dari hukum kekaisaran—ia adalah contoh paling mutakhirnya.
Narasi dimulai dari akar terdalam dalam “The First Peoples of America and Their Land”.
Kennard mengajak pembaca melihat bahwa kisah kekayaan dan ekspansi Amerika tidak bisa dipisahkan dari sejarah perampasan tanah masyarakat adat. Penaklukan, perjanjian yang dilanggar, dan peminggiran sistematis bukan sekadar episode masa lalu, melainkan fondasi yang memungkinkan akumulasi modal awal. Opini Kennard di sini tegas: imperium global abad ke-21 berdiri di atas kolonialisme internal yang belum pernah diselesaikan secara moral maupun politik. Dengan menyingkirkan bangsa-bangsa pertama dari tanah dan kedaulatannya, negara menciptakan preseden bahwa kekerasan struktural dapat dinormalisasi demi “kemajuan”. Bab ini berfungsi sebagai pengingat bahwa sebelum Amerika “memiliki” dunia, ia terlebih dahulu memiliki tanah dan sejarah orang lain di dalam batasnya sendiri.
Dari tanah, narasi bergerak ke tenaga kerja dalam “Working America”. Kennard membongkar mitos kelas menengah Amerika yang makmur dan berdaya, dengan menunjukkan bagaimana deregulasi, pelemahan serikat buruh, dan globalisasi produksi telah menggerus posisi pekerja. Dalam sistem yang ia sebut sebagai the racket, buruh domestik menjadi bagian dari mesin yang sama yang menindas buruh di Global South—hanya dengan bahasa yang lebih halus. Opini Kennard, yang dibangun dari observasi lapangan dan analisis kebijakan, menekankan bahwa ketimpangan bukan kecelakaan, melainkan hasil desain. Pekerja Amerika, seperti pekerja di luar negeri, dipaksa beradaptasi dengan logika pasar global yang menguntungkan segelintir elit korporasi, sambil diyakinkan bahwa penderitaan mereka adalah harga kebebasan.
Ketika kerja tidak lagi menjamin kehidupan yang layak, sistem menghasilkan apa yang digambarkan Kennard dalam “Destitute America”: kemiskinan struktural di jantung negara terkaya di dunia. Bab ini menyoroti paradoks yang mengganggu—bahwa di tengah kemegahan ekonomi dan kekuatan militer, jutaan orang hidup tanpa jaminan kesehatan, perumahan, atau pendidikan yang memadai. Kennard melihat kemiskinan ini bukan sebagai kegagalan sistem, tetapi sebagai komponen fungsionalnya. Dengan menciptakan ketakutan akan kejatuhan sosial, sistem mendisiplinkan tenaga kerja dan membatasi perlawanan. Opini yang disuarakan di sini mengaitkan kebijakan penghematan, pemotongan jaring pengaman sosial, dan kriminalisasi kemiskinan sebagai bagian dari mekanisme penguatan kekuasaan dari dalam.
Puncak paling kelam dari penguatan internal ini muncul dalam “Lock-up America”, di mana Kennard membedah sistem penjara massal. Ia menunjukkan bahwa Amerika Serikat memenjarakan warganya dalam skala yang tak tertandingi, terutama dari komunitas miskin dan rasial tertentu. Penjara, dalam analisis Kennard, bukan sekadar institusi hukum, tetapi alat kontrol sosial dan ekonomi. Industri penjara, hukum yang menghukum keras pelanggaran kecil, dan perang melawan narkoba bersatu menciptakan siklus penahanan yang menguntungkan korporasi dan aparat, sambil menghancurkan komunitas. Opini Kennard menegaskan bahwa negara yang mengklaim diri sebagai penjaga kebebasan justru memperluas definisi kriminalitas untuk mengelola surplus manusia yang tidak lagi dibutuhkan oleh ekonomi neoliberal.
Jika Part 2 memperlihatkan wajah keras imperium di luar negeri, Part 3 menunjukkan wajah sunyi namun tak kalah brutal di dalam negeri. Keempat bab ini—tentang masyarakat adat, buruh, kaum miskin, dan tahanan—disatukan oleh satu benang merah: penguatan kekuasaan melalui normalisasi ketidakadilan. Kennard ingin menunjukkan bahwa imperium bertahan karena ia berhasil membuat ketimpangan terasa wajar, sejarah terasa selesai, dan penderitaan terasa individual, bukan sistemik.
Dalam sintesis keseluruhan Part 3, Kennard menyampaikan pesan yang mengganggu: negara yang mampu menindas dari dalam akan selalu mampu menindas ke luar. Kekerasan global tidak mungkin dilepaskan dari kekerasan domestik; keduanya saling menopang. Dengan gaya reportase yang empatik namun tajam, ia mengajak pembaca untuk melihat bahwa kritik terhadap imperium tidak cukup berhenti pada kebijakan luar negeri. Ia harus menembus ke dalam—ke cara sebuah masyarakat memperlakukan tanahnya, pekerjanya, kaum miskinnya, dan mereka yang dikurung dalam sel-sel yang tak terlihat dari jalan raya kemakmuran.
Di titik ini, The Racket tidak lagi sekadar buku tentang Amerika Serikat, tetapi tentang logika kekuasaan modern itu sendiri: bahwa dominasi global selalu memerlukan penguatan domestik, dan bahwa kebebasan yang dipamerkan ke dunia sering dibayar dengan ketidakbebasan yang disembunyikan di rumah sendiri.
Retakan dalam Imperium: Saat Kekuasaan Mulai Kehilangan Cengkeramannya
Setelah tiga bagian sebelumnya membongkar bagaimana imperium Amerika dibangun, ditegakkan, dan diperkuat—di luar negeri maupun di rumah sendiri—Part 4: We’re Losing You menghadirkan nada yang berbeda. Di sini, Matt Kennard menulis bukan dari sudut pandang kekuasaan, melainkan dari titik-titik retaknya. Judul bagian ini sendiri terdengar seperti pengakuan yang tak disengaja: sebuah imperium yang mulai menyadari bahwa kendali tidak lagi absolut, bahwa ada wilayah—fisik, politik, dan kultural—yang perlahan lepas dari genggaman.
Narasi bergerak di wilayah konflik terbuka dan konflik simbolik, dimulai dengan “Turf War”. Kennard menggambarkan dunia yang semakin multipolar, di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan. Perang wilayah di sini bukan sekadar perebutan tanah, tetapi perebutan pengaruh: basis militer, jalur perdagangan, sumber daya, dan legitimasi politik. Opini Kennard menunjukkan bahwa apa yang sering disebut sebagai “ancaman keamanan” atau “ketidakstabilan regional” kerap merupakan reaksi terhadap dominasi lama yang kini dipertanyakan. Negara-negara dan kelompok yang selama puluhan tahun diperlakukan sebagai halaman belakang mulai menegosiasikan ulang posisi mereka. Imperium, dalam bab ini, tampak bukan lagi tak terkalahkan, melainkan defensif dan gelisah.
Dari perebutan wilayah, cerita beralih ke bahasa moral dan simbolik dalam “Freedom Fighters”. Kennard membedah bagaimana label ini digunakan secara selektif: satu kelompok disebut pejuang kebebasan ketika melayani kepentingan geopolitik Amerika, dan disebut teroris ketika melawannya. Dengan merujuk pada praktik kebijakan luar negeri dan narasi media, Kennard menyuarakan opini bahwa bahasa adalah senjata utama imperium. Namun, ia juga menunjuk-kan bahwa senjata ini mulai kehilangan daya. Semakin banyak aktor global—dan publik dunia—yang melihat kontradiksi tersebut. Ketika retorika kebebasan digunakan untuk membenarkan dominasi, maknanya justru terkikis. “Freedom fighter” menjadi cermin yang memantulkan kemunafikan, bukan legitimasi.
Ketegangan ini mencapai tingkat yang lebih eksplisit dalam “Revolutionaries”. Di sini Kennard menyoroti gerakan-gerakan yang tidak lagi sekadar menuntut reformasi, tetapi menantang struktur kekuasaan itu sendiri. Revolusioner, dalam bacaan Kennard, bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang mengusulkan tatanan ekonomi, politik, dan sosial alternatif—sering kali dengan cara yang dianggap radikal oleh pusat kekuasaan. Opini yang dikemukakan di bab ini menekankan bahwa revolusi lahir bukan dari ideologi semata, tetapi dari pengalaman panjang eksploitasi. Imperium kehilangan kendali ketika narasi ketidakadilan menjadi lebih kuat daripada ketakutan akan represi.
Namun Kennard tidak berhenti pada pemberontakan yang gagal atau ditindas. Dalam “Successful Defiance”, ia menghadirkan contoh-contoh perlawanan yang berhasil—atau setidaknya, cukup berhasil untuk membuktikan bahwa imperium bisa dilawan. Keberhasilan di sini tidak selalu berarti kemenangan total, melainkan kemampuan untuk bertahan, memaksa kompromi, atau mengubah arah sejarah. Kennard menunjukkan bahwa ketika masyarakat lokal membangun solidaritas, menguasai narasi mereka sendiri, dan memanfaatkan celah dalam sistem global, dominasi eksternal dapat diganggu. Opini ini penting karena menghindari romantisasi perlawanan; Kennard tetap realistis tentang harga yang harus dibayar, tetapi menolak anggapan bahwa perlawanan selalu sia-sia.
Puncak refleksi bagian ini hadir dalam “Culture as a Weapon of Resistance”, sebuah bab yang memperluas makna perlawanan melampaui politik formal dan konflik bersenjata. Kennard menulis tentang budaya—musik, seni, bahasa, ingatan kolektif—sebagai medan pertempuran yang sering diremehkan. Imperium, menurutnya, sangat bergantung pada dominasi budaya: pada kemampuan untuk mendefinisikan apa yang normal, modern, dan diinginkan. Ketika masyarakat mempertahankan atau menciptakan kembali ekspresi budaya mereka sendiri, mereka menolak logika tersebut. Opini Kennard di sini bersifat reflektif sekaligus optimistis: bahwa bahkan di bawah tekanan ekonomi dan militer, budaya dapat menjadi ruang otonomi terakhir—tempat identitas tidak sepenuhnya bisa dijajah.
Dalam sintesis Part 4, Kennard menyampaikan sebuah argumen penting: imperium tidak runtuh sekaligus; ia retak sedikit demi sedikit. Retakan itu muncul di wilayah yang tak sepenuhnya bisa dikontrol—dalam makna, dalam ingatan, dalam solidaritas lintas batas. Jika bagian-bagian sebelumnya menunjukkan betapa sistematis dan brutalnya the racket, maka bagian ini menunjukkan bahwa sistem tersebut juga rapuh, bergantung pada kepatuhan dan kepercayaan yang tidak selalu bisa dipaksakan.
We’re Losing You bukan pernyataan kemenangan, melainkan diagnosis. Kennard tidak mengklaim bahwa imperium Amerika telah berakhir, tetapi ia menunjukkan bahwa dominasi yang dulunya tampak mutlak kini menghadapi perlawanan yang semakin beragam bentuknya. Dari perebutan wilayah hingga perang narasi, dari revolusi politik hingga budaya sebagai senjata, bagian ini menegaskan bahwa sejarah belum selesai—dan bahwa masa depan tidak sepenuhnya ditentukan oleh mereka yang paling kuat secara militer atau ekonomi.
Dengan demikian, Part 4 berfungsi sebagai jembatan menuju refleksi akhir buku: bahwa melawan imperium bukan hanya soal menggulingkan kekuasaan, tetapi soal merebut kembali makna, martabat, dan kemungkinan untuk hidup di luar logika racket itu sendiri.
Berikut adalah ringkasan panjang dan mendalam untuk bagian Afterword sekaligus sintesis seluruh buku The Racket yang dirangkai menjadi esai reflektif global, ditulis mengalir, naratif–deskriptif, dengan penanda sumber opini yang jelas (merujuk pada Afterword dan keseluruhan bagian buku), serta ditutup dengan refleksi tentang apa yang perlu dilakukan warga dunia—khususnya Global South—secara kolektif demi masa depan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
Ketika Tirai Dibuka, dan Dunia Tidak Bisa Lagi Berpura-pura
Dalam Afterword, Matt Kennard menurunkan suaranya, tetapi justru memperdalam gaungnya. Jika bagian-bagian sebelumnya dari The Racket adalah laporan investigatif, peta kekuasaan, dan dakwaan sistemik terhadap imperium Amerika, maka Afterword adalah ruang kontemplasi—tempat penulis berdiri bukan hanya sebagai jurnalis, tetapi sebagai saksi zaman yang menyadari bahwa kebenaran, ketika sudah diungkap, menuntut tanggung jawab moral.
Kennard tidak menawarkan akhir yang nyaman. Tidak ada resolusi heroik, tidak ada janji bahwa sistem akan runtuh dengan sendirinya. Sebaliknya, ia menegaskan satu hal yang menjadi inti Afterword: imperium bertahan bukan hanya karena kekuatan senjata dan uang, tetapi karena kepatuhan, keheningan, dan normalisasi global terhadap ketidakadilan. Opini ini adalah benang merah yang merangkum seluruh buku—dari eksploitasi Global South (Part 1), penegakan kekuasaan melalui militer dan narkopolitik (Part 2), penguatan dominasi melalui ketimpangan domestik (Part 3), hingga retakan perlawanan (Part 4).
Dalam Afterword, Kennard secara implisit mengajak pembaca untuk keluar dari posisi penonton. Ia menyadari bahwa informasi saja tidak cukup. Dunia sudah lama tahu—tentang perang, tentang kudeta, tentang perusahaan multinasional yang merusak negara, tentang kemiskinan yang diciptakan secara struktural. Yang kurang bukan data, melainkan keberanian untuk mengganggu kenyamanan. Dengan kata lain, Afterword adalah seruan halus namun tegas: mengetahui berarti terlibat.
Jika disintesis, The Racket menunjukkan bahwa apa yang sering disebut sebagai “kesalahan kebijakan luar negeri” atau “penyimpangan demokrasi” sebenarnya adalah pola yang konsisten dan rasional dalam logika imperium. Kennard menegaskan (melalui keseluruhan struktur buku) bahwa Amerika Serikat tidak sekadar melakukan kekerasan; ia mengelola sebuah ekosistem kekuasaan global yang mencakup:
- perampasan sumber daya dan tenaga kerja (Part 1),
- penegakan melalui kekerasan, militerisasi, dan kriminalisasi (Part 2),
- normalisasi ketimpangan di dalam negeri sebagai cermin kolonialisme eksternal (Part 3),
- serta upaya memadamkan—atau menyesuaikan—perlawanan (Part 4).
Afterword mengikat semua ini dengan satu kesimpulan besar: imperium modern bekerja paling efektif ketika ia tidak terlihat sebagai imperium. Ia hadir sebagai “pasar bebas”, “keamanan global”, “demokrasi”, dan “pembangunan”. Di sinilah letak bahaya terdalamnya. Imperium sebagai Sistem, Bukan Anomali.
Refleksi yang ditawarkan Afterword—dan diperkuat oleh keseluruhan buku—adalah bahwa warga dunia tidak bisa lagi berpura-pura netral. Kennard tidak menyerukan revolusi bersenjata, tetapi ia jelas menolak pasivitas. Ia mendorong bentuk perlawanan yang berlapis:
- Ingat dan catat
Imperium hidup dari amnesia. Mengingat—melalui sejarah alternatif, jurnalisme independen, dan pendidikan kritis—adalah tindakan politik. - Ganggu narasi dominan
Bahasa adalah medan pertempuran. Menolak istilah-istilah seperti “intervensi kemanusiaan” atau “pasar bebas” tanpa konteks adalah bagian dari perlawanan. - Bangun solidaritas lintas batas
The Racket menunjukkan bahwa penderitaan di Detroit, Gaza, Tegucigalpa, dan Jakarta berasal dari sistem yang sama. Kesadaran ini harus melampaui nasionalisme sempit. - Tarik legitimasi moral dari imperium
Imperium bertahan karena ia dipercaya. Ketika kepercayaan runtuh—di mata publik global—kekuatan koersifnya melemah.
Bagi negara-negara Global South, Afterword memiliki resonansi yang sangat kuat. Kennard secara implisit menegaskan bahwa Global South bukan korban pasif, tetapi juga medan pertarungan masa depan dunia.
Sikap yang disarankan—jika disarikan dari keseluruhan buku—bukanlah isolasionisme atau konfrontasi membabi buta, melainkan aksi kolektif strategis:
- Memperkuat kerja sama Selatan–Selatan, bukan sebagai slogan diplomatik, tetapi sebagai jaringan ekonomi, teknologi, dan budaya yang nyata.
- Menolak ketergantungan struktural, terutama dalam bentuk utang, bantuan bersyarat, dan dominasi korporasi multinasional.
- Menginvestasikan kedaulatan pada manusia dan alam, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi—sebuah langkah kunci menuju keberlanjutan (sustainability).
- Mengembangkan narasi sendiri, tentang pembangunan, kemajuan, dan martabat, yang tidak disalin dari pusat kekuasaan global.
Catatan Akhir: Dari Impunitas Menuju Ingatan, dari Ingatan Menuju Masa Depan
The Racket—ditutup oleh Afterword—adalah buku tentang impunitas: tentang bagaimana kekuasaan besar jarang dihukum, dan bagaimana kejahatan struktural disamarkan sebagai kebijakan. Tetapi buku ini juga, secara implisit, adalah buku tentang ingatan. Ingatan adalah satu-satunya lawan sejati impunitas.
Tanpa ingatan, dunia akan terus mengulang pola yang sama, dengan aktor dan nama yang berbeda. Dengan ingatan, warga dunia dapat mulai membangun etika global baru—yang tidak mengukur keberhasilan dari dominasi, tetapi dari keberlanjutan; bukan dari akumulasi, tetapi dari keadilan.
Afterword tidak memberi resep instan. Ia memberi sesuatu yang lebih sulit: tanggung jawab untuk berpikir dan bertindak secara sadar di dunia yang tidak adil. Dan mungkin, seperti yang disiratkan Kennard, itulah awal dari dunia yang lebih manusiawi—bukan karena imperium runtuh, tetapi karena manusia berhenti menganggapnya tak terhindarkan.
Dalam keheningan setelah halaman terakhir, satu pertanyaan tersisa untuk kita semua:
jika kita sudah tahu, lalu apa yang akan kita lakukan?
The Racket bukan buku yang menawarkan solusi teknis cepat. Ia menawarkan sesuatu yang lebih mendasar: kejernihan melihat. Kennard menulis sebagai reporter, tetapi yang ia laporkan adalah struktur—tentang bagaimana kekuasaan bekerja ketika ia tidak lagi mengaku sebagai kekuasaan.
Seperti kata penyair Palestina Mahmoud Darwish, “Where should the birds fly, after the last sky?” Pertanyaan Kennard serupa: ke mana negara-negara miskin harus bergerak, jika semua jalan telah diprivatisasi?
Jawabannya, mungkin, dimulai dari membongkar racket—dengan ingatan, solidaritas, dan keberanian untuk membayangkan sistem yang lain.
Jakarta, 6 Januari 2026
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi:
Blum, W. (2003). Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower. Zed Books.
Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.
Galeano, E. (1973). Open Veins of Latin America. Monthly Review Press.
Kennard, M. (2015). The Racket: A Rogue Reporter vs the American Empire. Bloomsbury Academic.
Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. Beacon Press.
Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company.
UNEP. (2019). Global Environment Outlook 6. https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6