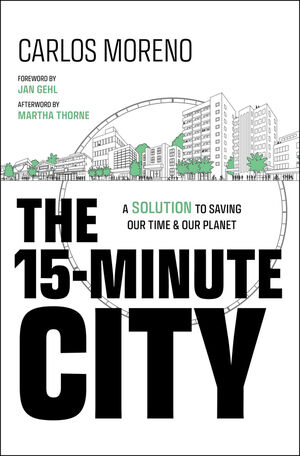Sustainability 17A #51
Habis Deforestasi Terbitlah Remediasi:
Menunda Kekalahan?
Dwi R. Muhtaman,
sustainability partner
“… educators today creating the
hope spots of a civilization reunited
with its soul.“
— Isabel Rimanoczy
Pada 4 Juni 2024, saat dunia menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni, the Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) bekerjasama dengan the Yale Center for Environmental Law and Policy menerbitkan hasil kajiannya dalam Laporan EPI 2024 (the Environmental Performance Index). EPI adalah kartu skor keberlanjutan yang berbasis bukti dan memiliki banyak aspek. Meskipun ada kemajuan menuju keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir, EPI 2024 menyoroti hal-hal yang perlu ditingkatkan.
Laporan tersebut menemukan bahwa jumlah negara yang mengalami penurunan emisi GRK lebih banyak dibandingkan sebelumnya, namun hanya lima negara yang mampu mengurangi emisi hingga mencapai net-zero pada tahun 2050, jika negara-negara tersebut terus mengurangi emisi pada tingkat yang berlaku saat ini: Estonia, Finlandia, Yunani, Timor -Leste dan Inggris. Itu berarti 175 negara lainnya yang masuk dalam peringkat analisis ini tidak akan mampu mencapai net-zero pada tahun 2050.
Amerika Serikat, yang berada di peringkat ke-34 dalam daftar tersebut, mengalami penurunan emisi namun perlahan; sementara Tiongkok, Rusia dan India terus menghasilkan tingkat emisi GRK yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Indonesia menduduki peringkat buncit kategori umum, 162 dari 180 negara dengan skor 33.8. Posisi ini menempatkan Indonesia pada peringkat 20 di tingkat regional. Jauh dari posisi Thailand pada 91 dunia dan peringkat sembilan regional. Sementara itu untuk kategori khusus Environmental Health, Indonesia menduduki peringkat 147 dan posisi 22 pada tingkat regional. Untuk kategori Ecosystem Vitality peringkat Indonesia lebih sedikit pada posisi 144 dengan peringkat 13 pada tingkat regional. Perihal urusan Climate Change posisi Indonesia bercokol pada urutan 143 dan 20 pada regional. Sedangkan kategori baru EPI 2024 yakni the Biodiversity & Habitat mendudukkan Indonesia pada posisi 143 meskipun secara regional lebih baik yakni pada peringkat 11, lebih baik dari Malaysia (152), Philippines (159), Viet Nam (160), Papua New Guinea (166). Untungnya, di Asia Tenggara, Indonesia masih dinilai merupakan negara yang mampu mengelola hutan sehingga kehilangan hutannya pada tingkat yang rendah. Laos adalah negara Asia Tenggara yang paling tinggi kerusakan hutannya.
Kinerja lingkungan Indonesia yang amat buruk berdasarkan EPI 2024 itu jelas sangat memprihatinkan. Nampaknya dengan capaian ekonomi nasional pada Q1-2024 yang relatif tinggi (pertumbuhan 5,11% (yoy)) dan diikuti tingkat inflasi bulan Mei 2024 yang terbilang rendah sebesar 2,84% (yoy), adalah harga yang harus dibayar dengan kondisi buruk lingkungan.
Untuk pertama kalinya, EPI 2024 juga memperkenalkan metrik baru dalam menghitung seberapa baik suatu negara melindungi habitat penting, serta indikator mengukur seberapa efektif kawasan lindung telah diatur oleh masing-masing negara. Metrik ini merupakan respons langsung terhadap tujuan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang bertujuan melindungi 30 persen daratan dan lautan pada tahun 2030. Dari indikator-indikator baru ini, terlihat jelas bahwa banyak negara mungkin telah mencapai tujuan perlindungan kawasan mereka, namun hilangnya ekosistem alami terus menjadi tantangan besar. Laporan ini menunjukkan pentingnya pendanaan yang memadai bagi kawasan lindung dan pengembangan standar perlindungan lingkungan yang diatur dengan baik melalui kerja sama dengan masyarakat lokal. Di 23 negara, lebih dari 10% lahan yang dilindungi terdiri dari bangunan dan lahan pertanian, sementara di 35 negara terdapat lebih banyak penangkapan ikan di dalam kawasan perlindungan laut dibandingkan di luar kawasan.
Laporan-laporan serupa mengenai kondisi bumi kita dari berbagai sudutnya, dari berbagai aspeknya menunjukkan kecemasan yang luar biasa.
“….But like the meteor that wiped out the dinosaurs,
we’re having an outsized impact.
In the case of climate, we are not the dinosaurs.
We are the meteor.
We are not only in danger.
We are the danger,” demikian tulis Antonio Guteres, Secretary-General PBB pada pernyataan 5 Juni 2024, mungkin dengan cemas dan gemas.
Namun, “..we are also the solution,” tulisnya.
Dunia Kehutanan
Dalam dunia kehutanan kita mengenal Forest Stewardship Council (FSC), sebuah organisasi pengembang standard untuk pengelolaan hutan yang baik. FSC didirikan untuk berkontribusi pada solusi persoalan dunia kehutanan yang dihadapi pada penghujung abad 20. FSC dirancang untuk menjawab banyak tantangan pada tiga dekade terakhir, saat ini dan masa yang akan datang. Hingga 2022 FSC secara global telah menyertifikasi 196.7 juta Hektar hutan, dengan 1,651 sertifikat pengelolaan hutan dan 52,827 sertifikasi Chain of Custody (CoC). Sertifikasi pengelolaan hutan FSC memverifikasi bahwa hutan dikelola sesuai dengan keramahan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi.
“Why forests matter,” tulis FSC pada lamannya. Ketika hutan tumbuh subur, masyarakat pun sejahtera. Hutan yang sehat memungkinkan umat manusia untuk berkembang. Hutan membantu kita lebih dari yang kita kira. Hutan mengatur iklim kita, membersihkan udara yang kita hirup, dan menyaring air yang kita minum. Mereka juga menyediakan habitat bagi lebih dari dua pertiga satwa liar dan tumbuhan darat. Sumber daya alam adalah salah satu sumber daya terpenting kita, yang menawarkan pasokan bahan dan barang terbarukan yang kita perlukan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Tetapi tidak semua pengelola hutan bisa berpartisipasi dalam skema sertifikasi FSC. Hutan tanaman industri yang dibuka setelah November 1994, berdasarkan kebijakan awal FSC, tidak memungkinkan untuk disertifikasi. Pintu telah tertutup bagi mereka. FSC hanya terbuka bagi perusahaan-perusahaan hutan alam, hutan tanaman industri yang dibangun sebelum November 1994 atau hutan rakyat. Sedangkan pembangunan HTI di Indonesia mulai marak setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Peraturan ini mengatur pemberian hak pengusahaan hutan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Karena itu pembangunan HTI di Indonesia sebagian besar dilakukan setelah periode 1994, batas waktu ketika standar FSC berlaku dan menutup kesempatan HTI dalam skema sertifikasi FSC.
Pada tahun 1997, misalnya, dari luas HTI yang dicadangkan yaitu 4,7 juta ha, luas HTI yang telah disetujui pemerintah sampai dengan Oktober 1998 adalah 4,6 juta ha. HTI yang sudah ditanami sampai dengan Oktober 1998 seluas 2 juta ha atau 45% dari luas HTI yang telah disetujui pemerintah. Berdasarkan jumlah luas, pembangunan, HTI Pulp menempati urutan teratas (68%), disusul HTI Pertukangan (18%), dan HTI Transmigrasi (14%). Sejak dilaksanakannya padu serasi antara TGHK dan RTRWP, kawasan hutan negara mengalami perubahan. Perbandingan data luas kawasan hutan negara tahun 1984 dan 1997 menunjukkan bahwa secara nasional kawasan hutan lindung bertambah luasnya dari 29,3 juta ha menjadi 34,6 juta ha. Kawasan hutan konservasi tetap luasnya, sedangkan kawasan hutan produksi menurun luasnya dari 64 juta ha menjadi 58,6 juta ha. Sementara itu hutan konversi yang digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan perkebunan, transmigrasi, dll. terus mengalami penurunan dari seluas 30 juta ha pada tahun 1984 menjadi 8,4 juta ha pada tahun 1997.
Sejak akhir tahun 1970-an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi sistem yang dominan dalam memanfaatkan hasil hutan dari hutan alam. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)1 digunakan untuk merancang dan mengendalikan pembangunan HPH, HTI dan perkebunan, terutama perkebunan besar, agar dapat meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara sesedikit mungkin mengkonversi hutan alam. Dalam pelaksanaannya, HPH telah mendahului sebagai penyebab degradasi hutan alam. Degradasi ini semakin besar ketika pada tahun 1990 pemerintah mengundang swasta untuk melakukan pembangunan HTI melalui sejumlah insentif. Demikian pula tingginya laju penanaman kelapa sawit yang dilakukan dengan mengkonversi hutan. Padu serasi antara TGHK dan RTRWP yang dilakukan secara top-down belum dapat menyelesaikan masalah, bahkan menghadirkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Indonesia hanyalah salah satu contoh kondisi konversi hutan alam menjadi peruntukan lainnya termasuk pembangunan HTI yang dilakukan sekitar tahun 1990-an itu. Konversi hutan alam ini bukan hal yang baru. Negara-negara industri melakukannya jauh lebih brutal pada abad awal industrialisasi. Indonesia justru banyak membuka hutan alam untuk HTI setelah periode 1994 sehingga tidak bisa disertifikasi skema FSC.
Sebab bagaimanapun, sejarah pembangunan sebuah bangsa adalah sejarah tentang pemanfaatan sumberdaya hutan. Dahulu kala, hutan Eropa, misalnya, masih liar dan tidak terganggu. Pada waktu itu hutan-hutan itu tidak dianggap sebagai lokasi harmoni dan menyenangkan tetapi sebagai tempat yang menakutkan. Gambaran itu bisa dibaca dari sejumlah cerita menyeramkan dengan putri yang diculik, penyihir kejam, dan kisah kejam para bangsawan.
Kemudian, manusia memasuki hutan, memanfaatkan kayunya, dan membuka hutan untuk penggunaan lahan lainnya. Mereka membentuk hutan sesuai dengan minat mereka dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas berkelanjutan, yang menghasilkan pohon yang seragam, tegakan spesies tunggal. Pada awal abad terakhir, pergeseran paradigma secara perlahan berlangsung di Eropa. Kelestarian hutan dipahami sebagai interaksi antara fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial yang berbeda dan tutupan hutan yang berkesinambungan dengan tegakan spesies campuran, struktur berlapis, dan tebang pilih menjadi praktek hutan yang diinginkan. Eropa dengan sisa hutan alamnya telah diselamatkan oleh perkembangan pengetahuan tentang kehutanan.
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi negara mana pun – di mana pun berada di dunia – akan memanfaatkan dan mengkonversi hutan untuk penggunaan lahan lain. Tidak ada yang bisa menahan proses ini. Berbagai upaya yang bisa dilakukan adalah meminimalkan kerusakan hutan dimanapun hutan dimanfaatkan, termasuk hutan tropika, dan untuk mengidentifikasi kawasan hutan yang memiliki nilai unik, yang harus dikecualikan dari campur tangan manusia. Hutan, dalam arti polisemiknya, telah berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan peradaban manusia sepanjang sejarah. Kehutanan tidak pernah monolitik dan selalu, dengan cara yang kurang lebih eksplisit, terus menerus mengalami proses perubahan dan adaptasi.
Sejak masa lalu, hutan di seluruh dunia digunakan dan dimodifikasi oleh kelompok pemburu-pengumpul. Dalam masyarakat yang bergantung pada hutan, sebagian kecil masih tersisa saat ini, ditandai dengan kepadatan penduduk dan tingkat pendapatan yang rendah, “hutan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kayu bakar, obat-obatan, makanan, dan bahan bangunan. Masyarakat ini memiliki kapasitas terbatas untuk mengubah lingkungan hutan secara drastis. Hutan meresapi keyakinan dan persepsi budaya, sosial dan agama” (Nair 2004 dalam Farcy et al., 2019).
Pertanian neolitik menyebar melalui sistem pertanian tebas-bakar yang bertahan selama ribuan tahun. Dengan peningkatan populasi, atau di mana deforestasi terjadi sebagai konsekuensi dari penanaman yang berlebihan, sistem agraria pascahutan berkembang secara progresif mengikuti evolusi pengetahuan dan teknik. Menggembalakan sapi, kuda, atau babi; memanen kayu, kulit kayu, kayu mati, serasah, dan daun; dan perladangan berpindah adalah komponen ekonomi yang efektif dari pertanian pedesaan.
Dalam masyarakat agraris, “hutan dipandang sebagai ruang untuk mengembangkan pertanian, termasuk ternak; sebagai sumber input berbiaya rendah untuk pertanian dan bahan bakar kayu, pakan ternak, obat-obatan dan hasil hutan bukan kayu lainnya seperti daging semak. Penjualan produk juga menambah pendapatan bagi masyarakat petani. Dengan kultivasi yang menetap, fungsi jasa hutan (misalnya, perlindungan daerah aliran sungai, menahan degradasi lahan) menjadi penting” (Nair 2004). Hutan dan pohon merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan adalah kegiatan yang membingkai erat yang dipandu oleh pengetahuan lokal yang diwarisi atau dibagikan dan sering diatur oleh kerangka kepemilikan lahan lokal yang mengandalkan penggunaan, bahkan untuk yang sementara waktu.
Masyarakat suku atau masyarakat pasca feodal mengembangkan berbagai rezim pengelolaan hutan sebagai cara adaptif dan dinamis. Penggunaan hutan secara agraris seperti itu, juga memenuhi syarat sebagai masyarakat jaman praindustri atau disebut juga sebagai hutan pertanian pangan, berdasarkan tenaga kerja dan tanah sebagai faktor produksi utama, dan berlangsung sampai sekitar akhir abad kedelapan belas di banyak wilayah Eropa.
Hal ini masih terjadi saat ini di banyak daerah pedesaan di belahan bumi selatan di mana keluarga pedesaan atau masyarakat mendapatkan penghidupan mereka dari penggarapan lahan yang ekstensif. Praktik terkait ini mungkin sering disematkan ke dalam kerangka kerja agroforestry kontemporer. Apalagi logikanya masyarakat agraris masih dapat mempengaruhi kehutanan saat ini karena inersia legislatif negara-negara Barat melalui undang-undang yang terkait dengan akses atau hak kepemilikan warisan.
Peran kunci kayu yang dimainkan dalam revolusi industri di Eropa adalah titik perubahan penting dalam munculnya kehutanan formal. Pada gilirannya, kayu adalah sumber utama
energi domestik dan industri, dukungan untuk pertambangan, bahan dasar untuk bangunan, dan bahkan pembuatan kapal di negara-negara pesisir, kayu menjadi sumber daya yang penting secara strategis di Eropa sejak abad ketujuh belas. Sebenarnya, istilah Spanyol dan Portugis untuk kayu (madera) berasal dari Latin: materia. Hutan, sebagai tempat produksi, mengalami tekanan yang meningkat dan mendapat perhatian yang meningkat. Hutan yang ada yang dapat digunakan dieksploitasi secara intensif, dan yang potensial secara aktif diprospek sementara upaya berulang dilakukan oleh pemegang kewenangan untuk mengatur dan membatasi hak ulayat yang dinikmati oleh masyarakat lokal atau membuat akses dan memanfaatkan hutan semakin sulit. Pada awal abad kedelapan belas, permintaan kayu tidak dapat lagi dipenuhi oleh ekspansi ke hutan yang sebelumnya tidak digunakan (Nair, 2004).
Di dunia sekarang ini, selain masalah lingkungan yang sering menjadi sorotan ilmiah, politik, dan media berita, kehutanan ditantang oleh beberapa penggerak perubahan sosial global, kurang dipelajari dan ditangani, sementara tidak diragukan lagi dampak yang mendalam dan panjang pada hubungan tidak hanya antara manusia dan hutan tetapi juga antara manusia itu sendiri ketika berhubungan dengan hutan.
Diidentifikasi secara khusus tiga perubahan sosial global utama yang saling berhubungan, yaitu: Yang pertama adalah urbanisasi masyarakat, sebuah proses yang telah berkembang sejak langkah pertama industrialisasi dan yang sangat signifikan saat ini ketika populasi perkotaan dunia melebihi 50%. Urbanisasi yang sedang berlangsung adalah mengubah gaya hidup dan praktik dengan kecenderungan dematerialisasi dan tidak hanya menawarkan peluang dan perspektif baru tentang dan untuk hutan dan pohon tetapi juga mendorong atau mengungkapkan perubahan mendalam dalam persepsi individu dan representasi sosial dari hutan. Urbanitas juga merupakan cermin dari perdesaan di mana berlangsung kehutanan dan berkembang selama berabad-abad dan yang entah bagaimana bisa dianaktirikan, terabaikan sehingga saat ini menjadi kekhawatiran banyak pihak.
Kedua, merosotnya nilai ekonomi hutan. Saat ini, sektor jasa sebagian besar mendominasi perekonomian dan melibatkan sebagian besar penduduk aktif di Dunia. Proses berkelanjutan ini mengubah modalitas profesional dan cara hidup dan tidak hanya membuka pintu baru ke hutan dan pohon melalui barang-barang immaterial yang bisa dihasilkan dari hutan tetapi juga sangat mengubah kerangka kerja, aturan, proses, dan modalitas produksi dan pertukaran antar pelaku ekonomi, dan cara-cara mengandung inovasi.
Yang ketiga tidak diragukan lagi adalah globalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dengan memperpendek jarak, mengatasi perbatasan, mempercepat pertukaran,
standarisasi praktik, meratakan struktur hierarki, mendorong saling ketergantungan,
globalisasi berdampak pada semua orang di mana saja dalam berbagai cara. Kehutanan tidak luput dari pisau tajam multifaset ini.
Bagaimana di Indonesia?
Sekitar 1880 Kalimantan Tenggara, demikian tulis Thomas Lindblad yang dikutip Han Knapen (2001), masih merupakan wilayah yang sama sekali tidak ada pengaruh dari luar. Penguasa kolonial Belanda pada waktu itu hanya mampu menyentuh satu dua wilayah pesisir pantai, dan menghubungkan pada pasar global. Kehidupan Dayak pedalaman hutan belantara tetap berlangsung ratusan tahun. Lindblad melakukan studinya di Kalimantan Tenggara untuk mengetahui dampak sosial ekonomi politik kolonialisme. Ia secara spesifik menganalisis situasi pada periode 1880 dan setelahnya.
Lindblad berpendapat pada periode kolonialisme 1880-1940 itulah terjadi perubahan yang signifikan di Kalimantan. Wilayah itu terintegrasi dengan pasar dunia dan ketika budaya imigran bertumbukan secara brutal dan langsung dengan mentalitas dan gaya hidup indigineous/asli yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Menurut Lindblad, transformasi sosial, ekonomi dan politik terjadi setelah 1880 dengan magnitud yang belum pernah dilihat ada. Pandangan Lindblad ini dibantah oleh Knapen yang melakukan studi tentang Kalimantan dengan rentang waktu 1600-1880. Pembangunan ekonomi memang terjadi pada periode 1880-1942. Tetapi itu tidak serta merta bisa menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan pada abad sebelumnya. Interaksi antara masyarakat asli dan luar telah berlangsung jauh sebelum 1600 dan perlahan-lahan menciptakan ekonomi baru. Kedatangan Eropa yang kemudian menguasai wilayah itu makin meningkatkan transformasi sosial ekonomi dan politik. Perubahan ini tidak bisa dihindari memberi dampak pada perubahan hutan.
Pada 1619 the Dutch East India Company (Vereenigde Oostindische Compagnie atau dikenal sebagai VOC) menaklukkan Jakarta di pantai utara dan menamainya Batavia. Belanda mempertahankan kehadiran di daerah ini selama lebih dari tiga abad, sampai tahun 1949, ketika Hindia Belanda tidak ada lagi dan menjadi Indonesia.
Bahkan sebelum Belanda mendirikan Batavia (1619), mereka telah memulai pembangunan dermaga di pulau Onrust, di seberang apa yang saat itu masih disebut Jakarta. Dermaga itu menampung sebuah galangan kapal besar, yang merupakan konsumen utama kayu untuk pembuatan kapal. Pada tahun 1675 galangan kapal ini mempekerjakan dua ratus orang; pada tahun 1700, hampir enam ratus; dan pada tahun 1755, enam ratus lima puluh. Setelah 1685 memiliki dua penggergajian kayu bertenaga angin. Di Batavia sendiri terdapat dua galangan kapan swasta, sebagian besar dijalankan oleh pembuat kapal Cina, dan setidaknya satu penggergajian kayu bertenaga air swasta (berasal dari tahun 1659).
Mulai tahun 1627 ada juga pasar kayu atau pekarangan kayu, yang dapat diakses oleh VOC dan pengusaha swasta. Kayu dibutuhkan tidak hanya untuk kapal, tetapi juga untuk bangunan di kota, untuk bahan bakar, dan untuk perabotan. Batavia berkembang pesat selama abad ketujuh belas, dan hampir semua bangunan terbuat dari kayu. Kayu, tentu saja, juga digunakan sebagai bahan bakar, baik dalam keadaan alaminya maupun sebagai arang. Permintaan arang didorong oleh kehadiran pabrik bubuk tepung di kota, yang pertama didirikan pada 1659. Pada 1787 ada tujuh pabrik seperti ini. Akhirnya, kayu dibutuhkan untuk furnitur; hingga 1650 banyak kayu jati digunakan untuk pembuatan furnitur. Karena VOC telah menaklukkan daerah dengan pedang di tangan, mereka merasa bebas untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya daerah itu sesuai keinginannya.
Perusahaan itu cukup berhasil memperoleh kayu bakar sebanyak yang dibutuhkan dari daerah yang terletak langsung di sekitar Batavia, yang disebut Lingkungan Batavia, tetapi kayu yang baik, terutama kayu jati, lebih sulit diperoleh. Sebuah organisasi yang bernama The Environs memproduksi kayu jati yang cukup untuk pembangunan rumah setidaknya sampai tahun 1644, tetapi kayu jati untuk bangunan rumah dikirim dari Jepara (Jawa Tengah) ke Batavia pada awal tahun 1622. Pada tahun 1636 sebuah armada kapal pribumi dikirim ke muara sungai Citarum di sebelah timur Batavia, untuk memperoleh kayu jati dari Krawang, di mana perusahaan tidak memiliki hak teritorial. Hingga tahun 1650, meskipun The Environs masih memasok beberapa kayu, VOC harus bergantung hampir sepenuhnya pada kesediaan penguasa pantai utara Jawa untuk pasokan kayu jati.
Bagaimana pun hutan bukanlah hanya hutan tanpa penghuni. Sebagian besar daerah hutan hujan tropis telah dihuni oleh orang-orang untuk waktu yang lama, meskipun pada kepadatan penduduk yang sangat rendah. Di banyak daerah hutan hujan tropis, bahkan di hutan yang dianggap “primer”, atau tidak terganggu, akan dapat ditemukan jejak bekas tempat tinggal manusia dan pertanian berpindah. Dengan demikian “primer” bukan berarti tidak pernah ada gangguan manusia.
Tidak banyak yang diketahui tentang laju deforestasi tropis di zaman sejarah, tetapi tampaknya antara tahun 1700 dan 1850 sekitar satu juta hektar dibuka setiap tahun, hampir secara eksklusif untuk pertanian berpindah. Dan karena pada saat yang sama hutan itu tumbuh kembali di pembukaan lahan kecil yang terbengkalai, laju deforestasi ini hampir tidak berpengaruh pada luas keseluruhan hutan hujan tropis.
Michael Williams, penulis Deforesting the Earth, seperti dikutip Martin (2015) menjelaskan
bagaimana deforestasi dipercepat pada periode kolonial setelah 1850. Budidaya padi mulai memakan banyak wilayah berhutan ketika petani pendatang membuka area yang luas di hutan dataran rendah Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Negara-negara ini menjadi wilayah pengekspor beras yang penting—mangkuk nasi Asia.
Negara-negara Asia Tenggara lainnya mengikuti, menggunduli hutan di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa. Lebih dari sepuluh juta hektar hutan telah dibuka sebelum tahun 1920, meskipun catatan tentang bagaimana ini terjadi tampaknya tidak meyakinkan. Filipina, yang telah di bawah pemerintahan kolonial Spanyol lebih dari 300 tahun, juga kehilangan hutan di bidang tengah Luzon, terutama untuk perkebunan tanaman komersial seperti tembakau dan tebu. Pengaruh kolonial terhadap ekspansi perdagangan tanaman juga terlihat di Assam, India, di mana British East Perusahaan India memperluas perkebunan tehnya dengan mengorbankan hutan tropis. Di Afrika Barat, terutama di Ghana dan Nigeria, hutan hujan ditebangi pada kuartal terakhir abad kesembilan belas untuk beberapa perkebunan kakao dan kelapa sawit komersial pertama.
Hutan hujan Amerika Latin, di sisi lain, hampir tidak dipengaruhi oleh pertanian komersial sebelum tahun 1920, dengan pengecualian beberapa perkebunan kopi, misalnya di daerah
barat laut São Paulo. Sebagian besar deforestasi di Selatan dan Amerika Tengah disebabkan oleh pertanian berpindah, yang biasanya mempengaruhi area yang relatif kecil dibandingkan dengan budidaya di Selatan dan Asia Tenggara. Pengecualian penting untuk pola moderat ini deforestasi adalah hutan pantai Atlantik Brasil, yang sudah dihancurkan pada fase awal kolonisasi di Daerah yang dikuasai Portugis.
Konversi hutan makin meningkat pesat sejalan dengan industrialisasi. Negara-bangsa yang lahir pasca kolonialisasi memacu percepatan pembangunannya dengan memanfaatkan hutan sebagai mesin penggerak roda-roda pembangunan. Termasuk Indonesia. Perkembangan pesat pemanfaatan hutan adalah ketika dikeluarkan undang-undang yang memungkinan swasta dan investor asing mendapatkan hak pemanfaatan hutan. Sejak tahun 1970-an itulah terjadi booming eksploitasi hutan.
Sektor Kehutanan di Rezim Soeharto
Di sektor kehutanan, pemerintah mengizinkan swasta untuk memanen dan ekspor log. Kebijakan ini didasarkan pada terbitnya UU No.1 Tahun 1967 dan No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, UU Kehutanan no. 5/1967 dan pemerintah
peraturan no. 21/1970. Atas dasar hukum pemberian hak pemanenan kayu dan hak industri, banyak konsesi besar dengan rentang 20-25 tahun diberikan segera setelah implementasi kebijakan pada tahun 1967. Tindakan ini mendorong perusahaan transnasional besar (TNC) dari Amerika Serikat (Weyerhaeuser, George Pacific, dll.) dan Jepang (Mitsubishi, Sumitomo, Shin Asahigawa, Ataka, dll.) untuk menginvestasikan modal di sektor kehutanan (Hurst 1990: 34) maupun sektor swasta domestik.
Sumatera dan Kalimantan adalah target pertama eksploitasi hutan dengan penebangan konsesi. Ini karena kedua pulau memiliki stok spesies pohon komersial terbesar yang berharga dan paling dekat dengan pasar Asia.
Konsesi penebangan menyebabkan peningkatan pesat ekspor kayu bulat yang belum diproses selama tahun 1970-an. Dengan keuntungan pemerintah dari sektor kehutanan meningkat menjadi sumber pendapatan terbesar kedua setelah sektor minyak, kerajaan bisnis baru Indonesia mengambil alih dan peluang kerja yang lebih besar terwujud (Robinson 1986). Namun seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor bisnis ini muncul tingkat deforestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar hutan primer telah habis, menambah kemiskinan yang melekat pada masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan-hutan tempat bergantung mata pencaharian mereka. Karena pemerintah tidak mengakui hutan adat masyarakat setempat, sengketa tanah terjadi di berbagai kabupaten. Misalnya, 14.440 ha disengketakan pada 1990-an antara komunitas lokal Muara Gusik Kabupaten Kutai dan perusahaan HPH the International Timber Corporation of Indonesia (ITCI). Konflik ini akhirnya berdampak negatif terhadap masyarakat secara ekonomi dan sosial (pendidikan dan kesehatan). Secara ekonomi, daya beli masyarakat telah menurun ke titik di mana rata-rata orang harus makan satu kali lebih sedikit setiap hari.
Sejalan dengan kegiatan pembalakan, HPH seluas hampir 11 juta ha diberikan di Kalimantan Timur dari tahun 1969 hingga 1974 (World Resources Institute 2000). Peningkatan ekspor kayu bulat ini dari 5,2 juta meter kubik pada tahun 1969/1970 menjadi lebih dari 24,3 juta m 3 pada tahun 1973/1974. Sepanjang tahun 1970-an, Kalimantan Timur memproduksi sepertiga hingga setengah kayu bulat Indonesia (Inoue 2000 ). Hanya pada tahun 1967, 4 juta m3 kayu bulat ditebang dari hutan Indonesia, dan sebagian besar untuk keperluan rumah tangga.
Lebih lanjut disebutkan pada tahun 1977, totalnya telah meningkat menjadi sekitar 28 juta m 3 dengan setidaknya 75% ditujukan untuk ekspor. Pendapatan dari sektor kehutanan naik dari US$6 juta pada tahun 1968 menjadi lebih dari US$564 juta pada tahun 1974.
Menurut Herman Hidayat, pada tahun 1979, Indonesia adalah produsen kayu bulat tropis utama, dengan pangsa 41% (US$2,1 miliar) dari pasar global dan mewakili volume ekspor kayu keras tropis yang lebih besar daripada seluruh Afrika dan Amerika Latin digabungkan (Lash, 2000). Pemerintah telah merencanakan untuk membangun sebuah industri kehutanan terpadu dari industri penebangan dan pengolahan kayu. Untuk melakukan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang penebangan dan membangun fasilitas untuk industri kayu.
Hutan Tanaman Industri (HTI)
Ada dua alasan yang mendasari pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Pertama, kurangnya kayu sebagai bahan baku industri kayu pulp dan kertas, kayu lapis, penggergajian kayu, dan sebagainya. Misalnya, dalam Pelita IV (1983–1988 Lima- Tahun Pembangunan) kebutuhan kayu adalah 40 juta m 3 , dan meningkat pesat menjadi sekitar 70 juta m 3 pada akhir 1990-an. Tapi kapasitas pasokan dari alam hutan setiap tahunnya hanya mencapai 38,4 juta m 3 , dan total produksi hutan mencapai 64 juta ha. Kedua, HTI dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kayu sebagai bahan baku. Oleh karena itu dikembangkan dari Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tiga basis: sosial, keberlanjutan, dan keuntungan pribadi (ekonomi; Tri Nugroho 1994: 6-18).
Pada tahun 1983, gagasan perlunya pengembangan HTI muncul di kalangan akademisi pada pertemuan yang diadakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 27-28 Desember 1983. Sementara itu, seluruh konsep HTI dibahas dalam seminar nasional berjudul: “Kita Tanam Hari Ini dan Kita Panen Esok” yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor pada tahun 1984.
Peran BUMN dan swasta dalam pengembangan HTI sangat signifikan. Sebagai hasil dari seminar nasional ini, Kementerian Kehutanan meluncurkan program jangka panjang program kebijakan strategis untuk membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Operasional dasar teknis pengembangan HTI dikeluarkan melalui berbagai peraturan:
(1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 1990 tentang hak pengusahaan HTI, pelengkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor 320/Kpts-II/1986 tentang Pengembangan HTI;
(2) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 29 Tahun 1990 tentang Iuran Reboisasi (Dana Reboisasi) yang pelengkap Keputusan Presiden nomor 35 Tahun 1980 tentang “Reboisasi”. Dana Asuransi dan Penanaman Kembali Hutan;”
(3) Keputusan Menteri Kehutanan nomor 19/Kpts-II/1991 tentang Pembagian Sumbangan Reboisasi untuk Pembangunan HTI, dilakukan oleh Perusahaan Kehutanan Negara ( Inhutani) di lingkungan Kementerian Kehutanan;
(4) Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan nomor 421/Kpts-II/1990 dan Nomor 931/KMK.o13/1990 tentang Pokok-pokok pelibatan modal negara dan peminjaman kontribusi reboisasi di HTI perkembangan.
Secara konseptual, HTI adalah kehutanan yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, menerapkan silvikultur intensif untuk menyediakan
kayu sebagai bahan baku. Oleh karena itu, Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah produksi
hutan dengan karakteristiknya masing-masing, memungkinkan pelaksanaan silvikultur intensif, produksi bahan baku industri kayu, pulp dan kertas, dan kebutuhan lainnya. Tumbuhan pohon dikategorikan sebagai pohon cepat tumbuh seperti Eucalyptus dan Acacia mangium. Pohon-pohon ini dari penanaman sampai panen perlu dipotong sekitar 6-7 tahun.
Deforestasi dan degradasi hutan tropis di Indonesia menjadi perhatian serius banyak pemangku kepentingan. Sekitar 16 juta hektar lahan hutan dalam konsesi terdegradasi. Selain itu, ketidakjelasan hak penguasaan dan kepemilikan tanah telah menimbulkan konflik yang signifikan, yang juga berkontribusi pada pengelolaan hutan yang tidak lestari. Menanggapi hal itu, organisasi domestik dan internasional telah memberikan tekanan yang cukup besar pada Indonesia untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pengelolaan hutan.
Era Sertifikasi Hutan
Pada tahun 1990, sertifikasi hutan pertama kali di negara berkembang dilakukan di Indonesia,
saat SmartWood mensertifikasi operasi hutan jati Perum Perhutani di pulau Jawa. Menanggapi hal ini dan tekanan LSM lainnya, Pemerintah Indonesia mendirikan skema sertifikasi hutannya sendiri – Lembaga Ekolabel Indonesia – pada tahun 1993. Pada tahun 1998, LEI secara resmi didirikan sebagai yayasan dan sejak itu telah melakukan beberapa penilaian sertifikasi. LEI dan FSC juga telah mengembangkan Protocol Sertifikasi Bersama (JCP) yang mewajibkan FSC untuk menggunakan kriteria dan indikator LEI dan FSC ketika melakukan penilaian terhadap suatu pengelolaan hutan.
Meskipun kedatangan gagasan sertifikasi lebih awal, praktik kehutanan yang buruk, kebijakan pemerintah yang tidak efektif, dan konflik terkait hutan atas hak masyarakat adat atas tanah telah menghambat pengembangan sertifikasi di Indonesia. Sementara banyak tantangan tetap ada, beberapa efek positif sertifikasi telah dicatat. Ini termasuk pembentukan insentif pemerintahan bagi perusahaan untuk lulus sertifikasi LEI, peningkatan kemauan perusahaan untuk terlibat dalam konsultasi publik, dan pembukaan ruang politik untuk LSM dan masyarakat untuk mengungkapkan keprihatinan mereka.
Sertifikasi hutan telah berlangsung di Indonesia selama 31 tahun. Kesulitan-kesulitan telah banyak yang dihadapi meski tidak selalu bisa mengatasi. Tantangan berat adalah berkaitan dengan lingkungan eksternal. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, penegakan hukum yang buruk, dan korupsi. Lingkungan eksternal yang sulit ini, ditambah dengan beberapa kasus yang memaksa pencabutan sertifikasi, telah mendorong para pengritik untuk menyimpulkan bahwa sertifikasi tidak dapat bekerja di Indonesia. Kecuali ada perubahan mendasar dalam, khususnya pengaturan kepemilikan lahan dan lingkungan kebijakan. Ini adalah kesimpulan yang terlalu pesimis. Sertifikasi dapat membuat perbedaan praktis di tingkat unit manajemen dan itu membantu sejumlah kecil perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Meskipun banyak variasi dampak sertifikasi FSC yang ditimbulkannya. Misalnya Matias, Cagnacci, dan Rosalino dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun skema sertifikasi FSC diterima sebagai sistem untuk mencapai setidaknya 11 tujuan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (FSC, 2016), sehingga dianggap efektif dan dapat diandalkan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia, tidak ada perbedaan yang jelas antara kelimpahan sebagian besar taksa di konsesi FSC dibandingkan dengan konsesi yang tidak melakukan pemanenan yang bertanggung jawab secara ekologis, yaitu tegakan yang tidak bersertifikat.
Dari perspektif pengelola hutan sendiri, sertifikasi telah membawa dampak yang lebih positif seperti memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial para staf dan membantu meningkatkan kelestarian hutan. Namun, penerapan program ini telah memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan-perusahaan ini karena adanya biaya tambahan untuk mendapatkan sertifikasi dan inspeksi tahunan. Di sisi lain, penelitian ini memaparkan dampak sertifikasi hutan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan mengenai permasalahan sertifikasi hutan.
Penelitian lain di Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor hasil hutan Tiongkok terutama didorong oleh margin kuantitatif, diikuti oleh margin harga. Sertifikasi hutan di negara-negara mitra dagang mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap margin harga dan dampak negatif yang signifikan terhadap margin kuantitatif produk hutan Tiongkok. Selain itu, dampak terhadap margin kuantitatif lebih besar dibandingkan dengan margin harga, sedangkan dampak terhadap margin ekstensif tidak signifikan. Studi ini memberikan dasar ilmiah untuk menanggapi langkah-langkah sertifikasi hutan, memperdalam kerja sama dengan negara-negara pedagang hasil hutan, dan memperkuat saling pengakuan dan koordinasi sistem sertifikasi hutan.
Dampak sertifikasi juga ditunjukkan dalam penelitian Hando Hain, 2005. Hasil studi menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan di banyak bidang, terutama dalam hal peningkatan kesadaran dan reputasi lingkungan. Peningkatan yang signifikan juga terlihat dalam pelestarian unsur-unsur biologis di lokasi penebangan habis, keselamatan kerja dan pengendalian risiko lingkungan selama operasi pengelolaan hutan. Sayangnya, sertifikasi tampaknya belum mempengaruhi banyak aspek yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang dekat dengan alam seperti penggunaan metode non-tebang habis dan pengembangan tegakan campuran yang umurnya tidak sama. Sertifikasi juga tidak membantu meningkatkan perhatian masyarakat lokal dan tidak memberikan manfaat finansial yang signifikan. Yang terakhir, pemanfaatan hasil hutan non-kayu masih belum ditangani, meskipun banyak pemangku kepentingan melihat adanya ruang untuk perbaikan dalam hal ini. Dampak negatif diamati oleh staf RMK sendiri sehubungan dengan meningkatnya jumlah dokumen dan dokumentasi yang diduga berlebihan. Peningkatan prosedur dan dokumen lainnya juga merupakan hasil dari proses transformasi dari kekacauan pasca-Soviet menjadi perusahaan yang terorganisir dan dikelola dengan baik.
Kais Bouslah et.al. melakukan penelitian untuk menguji secara empiris dampak sertifikasi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Financial Performance/FP). Pertanyaan utamanya adalah apakah ada “premi hijau” bagi perusahaan yang tersertifikasi, dan, jika ya, untuk jenis sertifikasi apa. Mereka menganalisis kinerja harga saham jangka pendek dan jangka panjang menggunakan metodologi studi peristiwa pada sampel perusahaan Kanada dan AS. Hasil dari kejadian abnormal return jangka pendek menunjukkan bahwa sertifikasi hutan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap FP perusahaan terlepas dari sistem sertifikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan hasil jangka pendek, hasil abnormal jangka panjang pasca peristiwa menunjukkan bahwa sertifikasi hutan, rata-rata, mempunyai dampak negatif terhadap perusahaan FP. Namun, dampak sertifikasi hutan terhadap perusahaan FP bergantung pada siapa yang memberikan sertifikasi, karena hanya sertifikasi yang dipimpin oleh industri (Sustainable Forestry Initiative, Canadian Standards Association, dan ISO14001) yang dikenakan sanksi oleh pasar keuangan, sedangkan organisasi sertifikasi non-pemerintah–Forest Stewardship Council tidak.
Keragaman dampak sertifikasi ini ditangkap dengan baik oleh Romero et.al. Mereka melakukan penelitian terhadap dampak sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) terhadap pengelolaan hutan alam di daerah tropis dengan mengeksplorasi pendekatan yang ketat terhadap cara penilaian intervensi konservasi yang kompleks. Penelitian ini lebih menekankan pada cara mengevaluasi dampak. Mereka menjelaskan peta jalan berdasarkan metode yang ketat untuk menilai apakah sertifikasi FSC memberikan hasil yang diharapkan dan mekanisme mendasar yang dapat menyebabkan perubahan disebabkan oleh FSC. Menurut mereka untuk mencapai tujuan ini, studi latar belakang yang memberikan pengetahuan kontekstual terkait dengan implementasi sertifikasi FSC diusulkan untuk memperhitungkan bias positif dalam seleksi mandiri dan untuk menangkap dinamika temporal sertifikasi termasuk perubahan dalam konteks sosiopolitik dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan sertifikasi. Dengan pendekatan yang ketat itu maka dampak sesungguhnya dari sertifikasi FSC bisa diidentifikasi lebih akurat.
Bagaimanapun sebagai sebuah bentuk intervensi pembangunan sertifikasi hutan mempunyai dampak positif dan negatif yang terus menerus bisa diperbincangkan. Kenyataan bahwa FSC telah bisa berlangsung hingga lebih dari 30 tahun dan mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan pada periode itu menunjukkan bahwa FSC telah berjalan pada jejak sejarah yang benar. Dengan lebih dari 1,200 anggota individu dan organisasi dari 93 negara, FSC telah menyelesaikan lebih dari 150 juta hektare hutan bersertifikat dengan lebih dari 55.000 sertifikasi yang memverifikasi sumber daya berkelanjutan, lebih dari 1.600 perusahaan yang mempunyai lisensi untuk mempromosikan produk berlabel FSC dan 46% konsumen di seluruh dunia mengenali label FSC.
Deforestasi lebih lanjut telah dihindari. Apresiasi pengelolaan hutan telah diberikan kepada mereka yang memenuhi standar pengelolaan yang baik. Akses pasar terbuka dengan lebar. Lalu apa lagi yang akan dilakukan?
Remedy Framework: Jalan Bagi Sertifikasi Hutan Tanaman
Gagasan membuka diri pada sertifikasi hutan tanaman industri melewati jalan yang panjang. Secara tradisional FSC menyertifikasi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman. Tetapi khusus untuk hutan tanaman dibatas pada perusahaan pengelolaan hutan tanaman yang dibangun hanya sebelum November 1994 yang dikenal dengan 1994 Cut-off Date. Semua hutan tanaman yang dibuka setelah November 1994 tidak bisa disertifikasi FSC. Kebijakan 1994 Cut-off date dilandaskan pada pencegahan upaya legitimasi deforestasi atau konversi hutan alam dengan sertifikasi. Kebijakan ini tanggapan terhadap kekhawatiran global tentang deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi di seluruh dunia.
Tanggal cut-off November 1994 dipilih segera setelah pembentukan FSC. Tanggal ini dipilih untuk memberikan batas temporal yang jelas guna mencegah konversi baru hutan alam menjadi hutan tanaman yang memenuhi syarat untuk sertifikasi. Pilihan tanggal ini merupakan konsensus di antara anggota pendiri FSC, yang meliputi organisasi lingkungan, kelompok masyarakat adat, dan perwakilan industri.
Terdapat empat alasan penting Kebijakan 1994 Cut-off Date
- Mencegah Insentif Deforestasi: Dengan menetapkan tanggal cut-off, FSC bertujuan untuk memastikan bahwa sertifikasinya tidak secara tidak sengaja menciptakan insentif ekonomi bagi pemilik lahan untuk mengonversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Kebijakan ini membantu melindungi hutan alam yang masih ada dari pembukaan lahan.
- Mendorong Praktik Berkelanjutan: Kebijakan ini mendorong pengelola hutan dan perusahaan untuk mengadopsi dan mempertahankan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada hutan tanaman yang sudah ada, daripada memperluas ke wilayah hutan alam. Hal ini sejalan dengan misi FSC untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia.
- Menjaga Kredibilitas dan Integritas: Kredibilitas FSC sebagai pemberi sertifikasi praktik kehutanan yang berkelanjutan bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsipnya. Tanggal cut-off membantu menjaga integritas sistem sertifikasi dengan memastikan bahwa hanya hutan tanaman yang tidak berkontribusi pada deforestasi terbaru yang memenuhi syarat.
- Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati: Hutan alam sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati. Dengan mencegah konversi hutan alam, FSC membantu melindungi ekosistem yang beragam dan spesies yang bergantung padanya.
Sejak FSC didirikan pada tahun 1994, dunia telah berubah baik dalam hal tekanan yang terus berlanjut terhadap ekosistem global yang disebabkan oleh konversi hutan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tindakan untuk mendorong konservasi dan restorasi hutan, serta untuk melawan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Menurut Prinsip dan Kriteria FSC, hutan tanaman yang dihasilkan dari konversi hutan alam setelah tahun 1994 tidak layak berpartisipasi dalam sistem FSC, sehingga seringkali menyebabkan pengelolaan yang buruk, dan menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap jasa ekosistem dan juga mengabaikan keanekaragaman hayati. Dan FSC tidak memiliki insentif atau aturan yang memungkinkan perusahaan hutan tanaman terlibat sehingga bisa memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya.
Demikian pula, tingkat konversi yang tinggi di banyak tempat di wilayah selatan selama beberapa dekade terakhir karena perkembangan ekonomi yang lebih baru, termasuk pembangunan hutan tanaman. Sedangkan tingkat konversi yang rendah di wilayah utara karena pembangunan ekonomi dan pembangunan hutan tanaman telah dimulai jauh sebelum 1994 itu. 1994. Oleh karena itu, beberapa pihak melihat kebijakan FSC tidak seimbang, tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang sama bagi semua wilayah.
Pada tahun 1996, FSC menyetujui untuk menambahkan Prinsip 10 yang secara khusus berkaitan dengan hutan tanaman. Tiga tahun kemudian, pada 1999, perubahan P&C terjadi kembali termasuk perubahan dengan penambahan kriteria tentang konversi 1994. Tidak semua anggota setuju dengan memasukkan kriteria tentang konversi 1994 ini. Karena itu perdebatan tentang sertifikasi hutan tanaman terus berlangsung. Pada 2002 FSC mengeluarkan Plantation Discussion Paper yang ditulis oleh Tim Synnott. Antara 2006-2009 sejumlah Laporan dikeluarkan oleh beberapa Expert Panel untuk membahas FSC Plantation Policy. Pada saat General Assembly di Kota Kinabalu, 2011, akhirnya anggota FSC menyetujui Policy Motion 18 “FSC Certification of Plantations.” Sejak adopsi Policy Motion 18 inilah perjalanan menuju perubahan 1994 Cut-Off Date dimulai dengan lebih gencar. Hingga akhirnya FSC General Assembly di Bali, 2022 menyetujui Motion 37 dan 45. Fitur penting Motion 37 antara lain:
- Mengubah batas waktu November 1994 menjadi Desember 2020 ketika perkebunan yang dikonversi dari hutan alam tidak termasuk dalam sertifikasi FSC.
- Mencerminkan definisi baru konversi dalam Kebijakan Mengatasi Konversi dengan memasukkan konversi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV).
- Mengharuskan pemulihan atas kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh konversi
- Merevisi definisi restorasi/restorasi ekologis menjadilebih komprehensif.
Sementara itu Motion 45 meminta agar perubahan harus dilakukan pada versi final FSC Remedy Framework untuk meningkatkan kredibilitasnya sebelum diserahkan kepada the FSC International Board untuk disetujui pada bulan Desember 2022. Saat ini FSC telah membuat Remedy Framework yang menjadi landasan utama untuk implementasi kebijakan baru Cut-off Date.
Apa arti semua perubahan ini? FSC menyampaikan tiga hal yang menarik sebagai dampak dari kebijakan radikal ini. Pertama, manfaat bagi hutan. Jutaan hektar lahan hutan yang saat ini terdegradasi, melalui perbaikan dan restorasi, dapat mengadopsi Prinsip dan Kriteria FSC dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan standar sertifikasi. Ini akan mengembalikan nilai-nilai ekologi dan sosial dari hutan-hutan tersebut dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam di banyak negara di seluruh dunia.
Langkah-langkah perbaikan yang berkaitan dengan restorasi ekologi akan mengembalikan kawasan yang dikonversi ke kondisi yang lebih dekat dengan bentuk alaminya. Hutan akan tumbuh kembali melalui proses restorasi habitat dan dampak ekologis dari aktivitas deforestasi dan degradasi di masa lalu.
Kedua, manfaat bagi masyarakat. Melalui jalur pemulihan FSC, masyarakat yang bergantung pada hutan kini memiliki akses terhadap jalur pemulihan non-yudisial dan dapat memperoleh manfaat dari kompensasi finansial dan non-finansial atas kerugian sosial yang disebabkan oleh konversi hutan. Penerapan Prinsip dan Kriteria serta Kerangka Perbaikan juga akan memberikan keadilan dan akses terhadap sertifikasi dan karenanya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh belahan dunia, terutama wilayah di mana konversi lahan berperan dalam pembangunan ekonomi setelah tahun 1994, seperti Amerika Latin, Selatan Asia Timur, dan Afrika.
Ketiga, manfaa bagi organisasi, perusahaan, dan rantai nilai. Organisasi yang lahannya dikonversi antara tahun 1994 dan tahun 2020 akan memiliki akses untuk mengadopsi peraturan FSC mengenai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, setelah adanya perbaikan. Hal ini dapat membantu pembangunan yang bertanggung jawab di negara-negara berkembang yang memiliki potensi rantai nilai hutan yang kuat dengan mendukung upaya sertifikasi FSC di negara-negara tersebut. Banyak perusahaan yang sebelumnya tidak dapat mensertifikasi sebagian tanah mereka karena batas waktu tahun 1994, kini berhak mengajukan permohonan sertifikasi atas tanah tersebut asalkan mereka memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh konversi. Misalnya, 50 persen perkebunan karet di Asia didirikan setelah tahun 1994 sehingga menjadi hambatan bagi mereka untuk memperoleh sertifikasi FSC dan memasuki sistem tersebut.
Dengan batas waktu yang baru, FSC tidak akan mensertifikasi lahan apa pun yang telah dikonversi dari hutan alam atau yang telah terjadi perusakan Nilai Konservasi Tinggi setelah tanggal 31 Desember 2020. Perusahaan mana pun yang dinyatakan bersalah atas aktivitas yang tidak dapat diterima – termasuk konversi – di masa lalu dan upaya untuk mengakhiri disosiasi atau asosiasi dengan FSC juga harus terlebih dahulu melalui proses penyelesaian terstandar yang berfokus pada persyaratan tambahan dalam Kerangka Pemulihan yang baru, yang akan berlaku efektif mulai pertengahan tahun 2023.
Menunda Kekalahan?
Apa selanjutnya? Apakah gagasan remediasi adalah berita yang menggembirakan? Atau apakah ia sebetulnya hanya langkah-langkah kecil yang cuma menunda kekalahan? Kekalahan kita dalam mempertahankan hutan dan sumberdaya alam. Bahkan ancaman kepunahan Homo pasien.
Mari kita lihat bagaimana status hutan setelah berbagai prakarsa dilakukan, dari tingkat lokal hingga global. Setelah langkah-langkah itu dilakukan dalam hampir setengah abad.
Analisis yang dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) memberi sedikit harapan. Misalnya hilangnya hutan tropis di Brazil dan Kolombia menurun tajam. Namun angka hilangnya hutan tropis secara umum tetap tinggi.
Antara tahun 2022 dan 2023, Brasil dan Kolombia mengalami penurunan kehilangan hutan primer sebesar 36% dan 49%. Meskipun terjadi penurunan drastis, laju hilangnya hutan primer tropis pada tahun 2023 tetap konsisten dengan tahun-tahun terakhir, menurut data baru dari laboratorium GLAD Universitas Maryland dan tersedia di platform Global Forest Watch WRI.
Sialnya kehilangan hutan malah bergeser dari satu negara yang menunjukkan kemauan politik untuk mengurangi hilangnya hutan ke negara lain dengan kemauan politik yang rendah. Penurunan yang signifikan terjadi di Brasil dan Kolombia diimbangi oleh peningkatan tajam hilangnya hutan di Bolivia, Laos dan Nikaragua.
Total hilangnya hutan primer tropis pada tahun 2023 mencapai 3,7 juta hektar, setara dengan hilangnya hampir 10 lapangan sepak bola (sepak bola) hutan per menit. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan sebesar 9% dibandingkan tahun 2022, angka pada tahun 2023 hampir sama dengan tahun 2019 dan 2021. Hilangnya hutan ini menghasilkan 2,4 gigaton (Gt) emisi karbon dioksida pada tahun 2023, setara dengan hampir setengah dari bahan bakar fosil tahunan. emisi Amerika Serikat.
Menurut laporan WWF, Forest Pathways Report 2023, dunia mengalami kerusakan hutan. Padahal kita tahu, seperti ditulis pada Laporan itu, hutan menyedot sepertiga emisi gas rumah kaca dunia, dan merupakan rumah bagi 80% keanekaragaman hayati bumi, dan menyediakan mata pencaharian bagi 1,6 miliar orang. Melindungi hutan adalah salah satu dari sedikit tujuan politik global, lintas partai, dan diabadikan dalam berbagai perjanjian, komitmen, tujuan dan target internasional termasuk the Glasgow Leaders’ Declaration on Forests (GLD) dan Land Use (2021) dan the New York Declaration on Forests (2014). Sejak GLD ditandatangani di Glasgow pada bulan November 2021, setidaknya 4,7 juta hektar hutan hujan tropis primer telah hilang. Hilangnya hutan, konversi dan degradasi terus berlanjut meskipun ada janji dan deklarasi global.
Kisah mengenai hutan kita saat ini adalah adanya perbedaan antara tujuan yang tertuang dalam komitmen internasional dan kenyataan di lapangan – dimana terjadi percepatan hilangnya hutan, degradasi yang terus berlanjut, penurunan jumlah satwa liar di hutan, dan tanda awal adanya ancaman terhadap fitur-fitur iklim yang penting. seperti musim hujan, sebagai respons terhadap deforestasi.
The 2023 Forest Declaration Assessment menemukan bahwa dunia masih berada di luar jalur menuju penghentian deforestasi pada tahun 2030, dengan deforestasi global pada tahun 2022 sebesar 4% lebih tinggi dibandingkan deforestasi global pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi hilangnya hutan sebesar 6,6 juta hektar, selisih 21% dari target tahun 2022, untuk menghentikan hilangnya hutan pada tahun 2030. Di wilayah tropis, 4,1 juta hektar hutan basah primer hilang pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 33%. penyimpangan dari target tahun 2022.
The Forest Declaration Assessment dilakukan untuk melacak kemajuan komitmen terhadap hutan global sasaran. Laporan pertamanya yang terbit pada tahun 2022 menanyakan
‘apakah kita berada di jalur yang tepat untuk tahun 2030?’ Jawabannya hanya ada satu kata: ‘Tidak’. The FAO Global Forest Resources Assessment (FRA) 2020 memperkirakan bahwa 420 juta ha hutan telah mengalami deforestasi (dikonversi menjadi penggunaan lahan lain) antara tahun 1990 dan 2020; walaupun lajunya menurun selama periode tersebut, deforestasi
diperkirakan masih mencapai 10 juta ha per tahun pada tahun 2015–2020 (sekitar 0,25 persen
per tahun).
Peraturan dan beragam instrumen kebijakan telah disediakan seperti dipaparkan di atas, termasuk kesepakatan politik. Uni Eropa (EUDR) telah memaksa perusahaan-perusahaan untuk menunjukkannya aktivitas mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi mulai tahun 2024. Termasuk di Indonesia melalui PP No. 71/2014 yang merupakan salah satu peraturan yang memiliki peran sentral terhadap penerbitan sejumlah peraturan yang melindungi hutan di Indonesia. Sejumlah peraturan (Perpres No.88/2017, Inpres No.8/ 2015, Inpres No.6/2017, PermenLHK No. 77/2015 serta PermenLHK No. 50, 51 dan 81 tahun 2016) mencantumkan PP No.17/2014 sebagai acuan peraturan. Hasil analisis dengan menggunakan metode Social Network Analysis menunjukkan fakta bahwa PP No. 71 merupakan peraturan sentral yang diacu hampir seluruh peraturan yang melindungi sector kehutanan di Indonesia.
“Jadi mengapa semakin banyak perangkat kebijakan dan komitmen politik yang mendukung tindakan melindungi hutan tetapi tidak diterjemahkan melakukan perubahan di lapangan?” tulis Thomas Maddox, Director, Forests and Land, CDP dalam pengantar untuk The Forest Transition: from Risk to Resilience: Global Forests Report 2023 (July 2023). Mengapa laju deforestasi, khususnya di daerah tropis, yang masih menyisakan beberapa juta hektar setiap tahunnya?
Salah satu alasannya, dari sisi sektor swasta adalah pemberantasan deforestasi dari rantai pasok bukan merupakan prioritas bagi sebagian besar perusahaan, dan tekanan dari lembaga keuangan, pembeli atau pembuat kebijakan masih terlalu lemah untuk mendorong kemajuan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan CDP, hanya satu dari 10 perusahaan yang mengelola risiko deforestasi mereka. Meskipun demikian ada sedikit optimisme. Satu dari sepuluh perusahaan yang mengungkapkan mengelola risiko mereka saat ini akan mempunyai dampak yang signifikan serbagai pioner dari pesaing mereka ketika tekanan terus berlanjut untuk tumbuh.
Remedy Framework, Remedy Mindset
Namun juga perlu diingat bahwa mengatasi deforestasi adalah sebuah upaya yang integral/holistik dalam sebuah ekosistem yang luas. Ia harus menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari sebagian besar strategi lingkungan holistik di masa depan. Ini adalah salah satu tindakan yang berkontribusi terhadap banyak tantangan termasuk iklim, keamanan air,
hilangnya keanekaragaman hayati dan potensi manfaat sosial. Inilah nilai penting dari gagasan remediasi yang dilakukan oleh FSC. Parapihak (stakeholders, rights holders) harus bahu membahu untuk menempatkan diri dan mengambil peran aktif yang bisa dikontribusikan agar tujuan memulihkan fungsi hutan bisa tercapai melalui Kerangka Pemulihan (Remedy Framework). Sebagai gagasan yang baru (bagi FSC dan parapihak) maka kita memasuki satu arena belajar bersama untuk menciptakan karya bersama (learning, co-creation). Memahami hal-hal yang baru. Berbagi pengetahuan dan pengalaman, memberi masukan dan kritik, agar menjadi upaya kolektif membangun konsep dan pelaksanaan kerangka remediasi yang terbaik yang bisa diciptakan bersama (co-creation).
Secara umum umat manusia telah memasuki Industri 4.0, sebuah era digital atau pasca-PC dengan karakteristik berupa teknologi bergerak (mobile). Teknologi sedekat sentuhan jari. Segala hal bisa didapatkan hanya dengan kelincahan balet jari jemari di layar genggam. Namun diprediksi era industri baru telah ada di depan mata: Industri 5.0. Karakteristik Industri 5.0 adalah ketika teknologi kecerdasan buatan (artificial intelliegence atau AI) telah menjadi ‘manusia.’ Ia mampu menirukan kecerdasan manusia dan membantu kegiatan operasional organisasi yang membutuhkan otomasi interaksi dengan pelanggannya dan segala keperluan. Perubahan di era Industri 5.0 sangatlah cepat. Bila era Industri 0.0 dicapai dalam waktu ratusan ribu tahun, Industri 1.0 ribuan tahun, Industri 2.0 ratusan tahun, dan Industri 4.0 puluhan tahun, maka Industri 5.0 dapat terjadi dalam waktu belasan tahun. Setiap hari selalu ada inovasi di sektor industri teknologi informasi, keuangan, layanan, dan sebagainya. Organisasi-organisasi berusia ratusan tahun bertumbangan, organisasi-organisasi berusia puluhan tahun mulai kebingungan kehilangan pangsa pasar, dan organisasi belia berusia kurang dari sepuluh tahun telah mengalahkan kapitalisasi pasar pemain lama. Maka inovasi Remedy Framework FSC adalah bagian dari adaptasi pentingnya dalam dunia kehutanan yang bergerak cepat.
Dalam proses belajar dan co-creation tentang Remedy Framework ini maka parapihak, dalam era industri baru ini, memerlukan mindset, skillset dan toolset yang baru agar tak hanya relevan dan mampu bertahan tetapi juga terus tumbuh dan berkembang. Satu-satu-nya cara untuk mengubah mindset, skillset, dan toolset adalah melalui learning. Diperlukan mindset learning yang berbeda, skillset learning yang ber-beda, dan toolset learning yang berbeda dengan gene-rasi sebelumnya. Model learning di era masa depan ini dinamakan Learning 5.0, dan organisasi perlu mengadopsi model baru ini sedari sekarang.
Perubahan mindset parapihak sangat diperlukan dalam arena belajar bersama ini. Dan learning yang efektif menuntu untuk un-learn yakni belajar melepaskan mindset, skillset, dan toolset lama. Sebab ketergantungan pada mindset, skillset, dan toolset lama akan mncegah seseorang memikirkan cara-cara baru yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik dan lebih mudah. “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn,” kata Alvin Toffler.
Karena itu Remedy Framework akan efektif jika juga dilakukan Remedy Mindset dari parapihak. Mindset atau polapikir yang antusias untuk berkembang, memimpin dan melayani dengan nilai-nilai sustainability. Mengembangkan apa yang disebut growth mindset–sebuah polapikir yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan dan peningkatan yang berkelanjutan adalah mungkin (Capozzi, 2017). Orang dengan growth mindset bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Mereka percaya bahwa dengan motivasi dan keterampilan yang tepat, potensi sejati siapa pun sebenarnya tidak terbatas. Tidak butuh waktu lama untuk mengenali seseorang yang hidup dengan pola pikir ini. Orang dengan pola pikir ini memiliki rasa ingin tahu; mereka terbuka terhadap kemungkinan, mereka memiliki pandangan yang positif, dan mereka memiliki keinginan untuk belajar dan make a difference.
Singkatnya, growth mindset mendorong pertumbuhan berkelanjutan secara pribadi dan profesional. Bertanggungjawab atas apa yang dilakukan hari ini terhadap kekayaan yang dimilikinya (kekayaan alam dan kekayaan material pribadi) dan sadar akan segala dampak bagi generasi yang akan datang. Lebih spesifik lagi Isabel Rimanoczy menyebutnya
sebagai “The sustainability mindset. “Elemen-elemen prinsip The Sustainability Mindset (polapikir keberlanjutan) berkaitan dengan the knowing (ecoliteracy), thinking (systemic and innovative thinking), and being (values, purpose).
Kalangan perusahaan yang melaksanakan Remedy Framework harus juga melakukan Remedy Mindset. Mengubah mindset lama dengan yang baru. Meningkatkan atau mengubah skillset dengan yang baru. Dan mengganti toolset lam dengan yang baru. Demikian juga kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dengan Remedy Framework. Tak lupa masyarakat baik yang interested stakeholders, impacted rights holder dan affected rights holder harus pula melakukan yang sama.
Dalam situasi belajar bersama ini, kita selain sebagai pembelajar, barangkali juga sebagai pendidik. Pendidik yang menciptakan cahaya-cahaya harapan dari bersatunya peradaban dengan jiwa… “..educators today creating the hope spots of a civilization reunited with its soul.“
Sustainability 17A #51
Habis Deforestasi Terbitlah Remediasi:
Menunda Kekalahan?
Dwi R. Muhtaman,
sustainability partner
“… educators today creating the
hope spots of a civilization reunited
with its soul.“
— Isabel Rimanoczy
Pada 4 Juni 2024, saat dunia menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni, the Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) bekerjasama dengan the Yale Center for Environmental Law and Policy menerbitkan hasil kajiannya dalam Laporan EPI 2024 (the Environmental Performance Index). EPI adalah kartu skor keberlanjutan yang berbasis bukti dan memiliki banyak aspek. Meskipun ada kemajuan menuju keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir, EPI 2024 menyoroti hal-hal yang perlu ditingkatkan.
Laporan tersebut menemukan bahwa jumlah negara yang mengalami penurunan emisi GRK lebih banyak dibandingkan sebelumnya, namun hanya lima negara yang mampu mengurangi emisi hingga mencapai net-zero pada tahun 2050, jika negara-negara tersebut terus mengurangi emisi pada tingkat yang berlaku saat ini: Estonia, Finlandia, Yunani, Timor -Leste dan Inggris. Itu berarti 175 negara lainnya yang masuk dalam peringkat analisis ini tidak akan mampu mencapai net-zero pada tahun 2050.
Amerika Serikat, yang berada di peringkat ke-34 dalam daftar tersebut, mengalami penurunan emisi namun perlahan; sementara Tiongkok, Rusia dan India terus menghasilkan tingkat emisi GRK yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Indonesia menduduki peringkat buncit kategori umum, 162 dari 180 negara dengan skor 33.8. Posisi ini menempatkan Indonesia pada peringkat 20 di tingkat regional. Jauh dari posisi Thailand pada 91 dunia dan peringkat sembilan regional. Sementara itu untuk kategori khusus Environmental Health, Indonesia menduduki peringkat 147 dan posisi 22 pada tingkat regional. Untuk kategori Ecosystem Vitality peringkat Indonesia lebih sedikit pada posisi 144 dengan peringkat 13 pada tingkat regional. Perihal urusan Climate Change posisi Indonesia bercokol pada urutan 143 dan 20 pada regional. Sedangkan kategori baru EPI 2024 yakni the Biodiversity & Habitat mendudukkan Indonesia pada posisi 143 meskipun secara regional lebih baik yakni pada peringkat 11, lebih baik dari Malaysia (152), Philippines (159), Viet Nam (160), Papua New Guinea (166). Untungnya, di Asia Tenggara, Indonesia masih dinilai merupakan negara yang mampu mengelola hutan sehingga kehilangan hutannya pada tingkat yang rendah. Laos adalah negara Asia Tenggara yang paling tinggi kerusakan hutannya.
Kinerja lingkungan Indonesia yang amat buruk berdasarkan EPI 2024 itu jelas sangat memprihatinkan. Nampaknya dengan capaian ekonomi nasional pada Q1-2024 yang relatif tinggi (pertumbuhan 5,11% (yoy)) dan diikuti tingkat inflasi bulan Mei 2024 yang terbilang rendah sebesar 2,84% (yoy), adalah harga yang harus dibayar dengan kondisi buruk lingkungan.
Untuk pertama kalinya, EPI 2024 juga memperkenalkan metrik baru dalam menghitung seberapa baik suatu negara melindungi habitat penting, serta indikator mengukur seberapa efektif kawasan lindung telah diatur oleh masing-masing negara. Metrik ini merupakan respons langsung terhadap tujuan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang bertujuan melindungi 30 persen daratan dan lautan pada tahun 2030. Dari indikator-indikator baru ini, terlihat jelas bahwa banyak negara mungkin telah mencapai tujuan perlindungan kawasan mereka, namun hilangnya ekosistem alami terus menjadi tantangan besar. Laporan ini menunjukkan pentingnya pendanaan yang memadai bagi kawasan lindung dan pengembangan standar perlindungan lingkungan yang diatur dengan baik melalui kerja sama dengan masyarakat lokal. Di 23 negara, lebih dari 10% lahan yang dilindungi terdiri dari bangunan dan lahan pertanian, sementara di 35 negara terdapat lebih banyak penangkapan ikan di dalam kawasan perlindungan laut dibandingkan di luar kawasan.
Laporan-laporan serupa mengenai kondisi bumi kita dari berbagai sudutnya, dari berbagai aspeknya menunjukkan kecemasan yang luar biasa.
“….But like the meteor that wiped out the dinosaurs,
we’re having an outsized impact.
In the case of climate, we are not the dinosaurs.
We are the meteor.
We are not only in danger.
We are the danger,” demikian tulis Antonio Guteres, Secretary-General PBB pada pernyataan 5 Juni 2024, mungkin dengan cemas dan gemas.
Namun, “..we are also the solution,” tulisnya.
Dunia Kehutanan
Dalam dunia kehutanan kita mengenal Forest Stewardship Council (FSC), sebuah organisasi pengembang standard untuk pengelolaan hutan yang baik. FSC didirikan untuk berkontribusi pada solusi persoalan dunia kehutanan yang dihadapi pada penghujung abad 20. FSC dirancang untuk menjawab banyak tantangan pada tiga dekade terakhir, saat ini dan masa yang akan datang. Hingga 2022 FSC secara global telah menyertifikasi 196.7 juta Hektar hutan, dengan 1,651 sertifikat pengelolaan hutan dan 52,827 sertifikasi Chain of Custody (CoC). Sertifikasi pengelolaan hutan FSC memverifikasi bahwa hutan dikelola sesuai dengan keramahan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi.
“Why forests matter,” tulis FSC pada lamannya. Ketika hutan tumbuh subur, masyarakat pun sejahtera. Hutan yang sehat memungkinkan umat manusia untuk berkembang. Hutan membantu kita lebih dari yang kita kira. Hutan mengatur iklim kita, membersihkan udara yang kita hirup, dan menyaring air yang kita minum. Mereka juga menyediakan habitat bagi lebih dari dua pertiga satwa liar dan tumbuhan darat. Sumber daya alam adalah salah satu sumber daya terpenting kita, yang menawarkan pasokan bahan dan barang terbarukan yang kita perlukan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Tetapi tidak semua pengelola hutan bisa berpartisipasi dalam skema sertifikasi FSC. Hutan tanaman industri yang dibuka setelah November 1994, berdasarkan kebijakan awal FSC, tidak memungkinkan untuk disertifikasi. Pintu telah tertutup bagi mereka. FSC hanya terbuka bagi perusahaan-perusahaan hutan alam, hutan tanaman industri yang dibangun sebelum November 1994 atau hutan rakyat. Sedangkan pembangunan HTI di Indonesia mulai marak setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Peraturan ini mengatur pemberian hak pengusahaan hutan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Karena itu pembangunan HTI di Indonesia sebagian besar dilakukan setelah periode 1994, batas waktu ketika standar FSC berlaku dan menutup kesempatan HTI dalam skema sertifikasi FSC.
Pada tahun 1997, misalnya, dari luas HTI yang dicadangkan yaitu 4,7 juta ha, luas HTI yang telah disetujui pemerintah sampai dengan Oktober 1998 adalah 4,6 juta ha. HTI yang sudah ditanami sampai dengan Oktober 1998 seluas 2 juta ha atau 45% dari luas HTI yang telah disetujui pemerintah. Berdasarkan jumlah luas, pembangunan, HTI Pulp menempati urutan teratas (68%), disusul HTI Pertukangan (18%), dan HTI Transmigrasi (14%). Sejak dilaksanakannya padu serasi antara TGHK dan RTRWP, kawasan hutan negara mengalami perubahan. Perbandingan data luas kawasan hutan negara tahun 1984 dan 1997 menunjukkan bahwa secara nasional kawasan hutan lindung bertambah luasnya dari 29,3 juta ha menjadi 34,6 juta ha. Kawasan hutan konservasi tetap luasnya, sedangkan kawasan hutan produksi menurun luasnya dari 64 juta ha menjadi 58,6 juta ha. Sementara itu hutan konversi yang digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan perkebunan, transmigrasi, dll. terus mengalami penurunan dari seluas 30 juta ha pada tahun 1984 menjadi 8,4 juta ha pada tahun 1997.
Sejak akhir tahun 1970-an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi sistem yang dominan dalam memanfaatkan hasil hutan dari hutan alam. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)1 digunakan untuk merancang dan mengendalikan pembangunan HPH, HTI dan perkebunan, terutama perkebunan besar, agar dapat meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara sesedikit mungkin mengkonversi hutan alam. Dalam pelaksanaannya, HPH telah mendahului sebagai penyebab degradasi hutan alam. Degradasi ini semakin besar ketika pada tahun 1990 pemerintah mengundang swasta untuk melakukan pembangunan HTI melalui sejumlah insentif. Demikian pula tingginya laju penanaman kelapa sawit yang dilakukan dengan mengkonversi hutan. Padu serasi antara TGHK dan RTRWP yang dilakukan secara top-down belum dapat menyelesaikan masalah, bahkan menghadirkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Indonesia hanyalah salah satu contoh kondisi konversi hutan alam menjadi peruntukan lainnya termasuk pembangunan HTI yang dilakukan sekitar tahun 1990-an itu. Konversi hutan alam ini bukan hal yang baru. Negara-negara industri melakukannya jauh lebih brutal pada abad awal industrialisasi. Indonesia justru banyak membuka hutan alam untuk HTI setelah periode 1994 sehingga tidak bisa disertifikasi skema FSC.
Sebab bagaimanapun, sejarah pembangunan sebuah bangsa adalah sejarah tentang pemanfaatan sumberdaya hutan. Dahulu kala, hutan Eropa, misalnya, masih liar dan tidak terganggu. Pada waktu itu hutan-hutan itu tidak dianggap sebagai lokasi harmoni dan menyenangkan tetapi sebagai tempat yang menakutkan. Gambaran itu bisa dibaca dari sejumlah cerita menyeramkan dengan putri yang diculik, penyihir kejam, dan kisah kejam para bangsawan.
Kemudian, manusia memasuki hutan, memanfaatkan kayunya, dan membuka hutan untuk penggunaan lahan lainnya. Mereka membentuk hutan sesuai dengan minat mereka dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas berkelanjutan, yang menghasilkan pohon yang seragam, tegakan spesies tunggal. Pada awal abad terakhir, pergeseran paradigma secara perlahan berlangsung di Eropa. Kelestarian hutan dipahami sebagai interaksi antara fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial yang berbeda dan tutupan hutan yang berkesinambungan dengan tegakan spesies campuran, struktur berlapis, dan tebang pilih menjadi praktek hutan yang diinginkan. Eropa dengan sisa hutan alamnya telah diselamatkan oleh perkembangan pengetahuan tentang kehutanan.
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi negara mana pun – di mana pun berada di dunia – akan memanfaatkan dan mengkonversi hutan untuk penggunaan lahan lain. Tidak ada yang bisa menahan proses ini. Berbagai upaya yang bisa dilakukan adalah meminimalkan kerusakan hutan dimanapun hutan dimanfaatkan, termasuk hutan tropika, dan untuk mengidentifikasi kawasan hutan yang memiliki nilai unik, yang harus dikecualikan dari campur tangan manusia. Hutan, dalam arti polisemiknya, telah berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan peradaban manusia sepanjang sejarah. Kehutanan tidak pernah monolitik dan selalu, dengan cara yang kurang lebih eksplisit, terus menerus mengalami proses perubahan dan adaptasi.
Sejak masa lalu, hutan di seluruh dunia digunakan dan dimodifikasi oleh kelompok pemburu-pengumpul. Dalam masyarakat yang bergantung pada hutan, sebagian kecil masih tersisa saat ini, ditandai dengan kepadatan penduduk dan tingkat pendapatan yang rendah, “hutan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kayu bakar, obat-obatan, makanan, dan bahan bangunan. Masyarakat ini memiliki kapasitas terbatas untuk mengubah lingkungan hutan secara drastis. Hutan meresapi keyakinan dan persepsi budaya, sosial dan agama” (Nair 2004 dalam Farcy et al., 2019).
Pertanian neolitik menyebar melalui sistem pertanian tebas-bakar yang bertahan selama ribuan tahun. Dengan peningkatan populasi, atau di mana deforestasi terjadi sebagai konsekuensi dari penanaman yang berlebihan, sistem agraria pascahutan berkembang secara progresif mengikuti evolusi pengetahuan dan teknik. Menggembalakan sapi, kuda, atau babi; memanen kayu, kulit kayu, kayu mati, serasah, dan daun; dan perladangan berpindah adalah komponen ekonomi yang efektif dari pertanian pedesaan.
Dalam masyarakat agraris, “hutan dipandang sebagai ruang untuk mengembangkan pertanian, termasuk ternak; sebagai sumber input berbiaya rendah untuk pertanian dan bahan bakar kayu, pakan ternak, obat-obatan dan hasil hutan bukan kayu lainnya seperti daging semak. Penjualan produk juga menambah pendapatan bagi masyarakat petani. Dengan kultivasi yang menetap, fungsi jasa hutan (misalnya, perlindungan daerah aliran sungai, menahan degradasi lahan) menjadi penting” (Nair 2004). Hutan dan pohon merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan adalah kegiatan yang membingkai erat yang dipandu oleh pengetahuan lokal yang diwarisi atau dibagikan dan sering diatur oleh kerangka kepemilikan lahan lokal yang mengandalkan penggunaan, bahkan untuk yang sementara waktu.
Masyarakat suku atau masyarakat pasca feodal mengembangkan berbagai rezim pengelolaan hutan sebagai cara adaptif dan dinamis. Penggunaan hutan secara agraris seperti itu, juga memenuhi syarat sebagai masyarakat jaman praindustri atau disebut juga sebagai hutan pertanian pangan, berdasarkan tenaga kerja dan tanah sebagai faktor produksi utama, dan berlangsung sampai sekitar akhir abad kedelapan belas di banyak wilayah Eropa.
Hal ini masih terjadi saat ini di banyak daerah pedesaan di belahan bumi selatan di mana keluarga pedesaan atau masyarakat mendapatkan penghidupan mereka dari penggarapan lahan yang ekstensif. Praktik terkait ini mungkin sering disematkan ke dalam kerangka kerja agroforestry kontemporer. Apalagi logikanya masyarakat agraris masih dapat mempengaruhi kehutanan saat ini karena inersia legislatif negara-negara Barat melalui undang-undang yang terkait dengan akses atau hak kepemilikan warisan.
Peran kunci kayu yang dimainkan dalam revolusi industri di Eropa adalah titik perubahan penting dalam munculnya kehutanan formal. Pada gilirannya, kayu adalah sumber utama
energi domestik dan industri, dukungan untuk pertambangan, bahan dasar untuk bangunan, dan bahkan pembuatan kapal di negara-negara pesisir, kayu menjadi sumber daya yang penting secara strategis di Eropa sejak abad ketujuh belas. Sebenarnya, istilah Spanyol dan Portugis untuk kayu (madera) berasal dari Latin: materia. Hutan, sebagai tempat produksi, mengalami tekanan yang meningkat dan mendapat perhatian yang meningkat. Hutan yang ada yang dapat digunakan dieksploitasi secara intensif, dan yang potensial secara aktif diprospek sementara upaya berulang dilakukan oleh pemegang kewenangan untuk mengatur dan membatasi hak ulayat yang dinikmati oleh masyarakat lokal atau membuat akses dan memanfaatkan hutan semakin sulit. Pada awal abad kedelapan belas, permintaan kayu tidak dapat lagi dipenuhi oleh ekspansi ke hutan yang sebelumnya tidak digunakan (Nair, 2004).
Di dunia sekarang ini, selain masalah lingkungan yang sering menjadi sorotan ilmiah, politik, dan media berita, kehutanan ditantang oleh beberapa penggerak perubahan sosial global, kurang dipelajari dan ditangani, sementara tidak diragukan lagi dampak yang mendalam dan panjang pada hubungan tidak hanya antara manusia dan hutan tetapi juga antara manusia itu sendiri ketika berhubungan dengan hutan.
Diidentifikasi secara khusus tiga perubahan sosial global utama yang saling berhubungan, yaitu: Yang pertama adalah urbanisasi masyarakat, sebuah proses yang telah berkembang sejak langkah pertama industrialisasi dan yang sangat signifikan saat ini ketika populasi perkotaan dunia melebihi 50%. Urbanisasi yang sedang berlangsung adalah mengubah gaya hidup dan praktik dengan kecenderungan dematerialisasi dan tidak hanya menawarkan peluang dan perspektif baru tentang dan untuk hutan dan pohon tetapi juga mendorong atau mengungkapkan perubahan mendalam dalam persepsi individu dan representasi sosial dari hutan. Urbanitas juga merupakan cermin dari perdesaan di mana berlangsung kehutanan dan berkembang selama berabad-abad dan yang entah bagaimana bisa dianaktirikan, terabaikan sehingga saat ini menjadi kekhawatiran banyak pihak.
Kedua, merosotnya nilai ekonomi hutan. Saat ini, sektor jasa sebagian besar mendominasi perekonomian dan melibatkan sebagian besar penduduk aktif di Dunia. Proses berkelanjutan ini mengubah modalitas profesional dan cara hidup dan tidak hanya membuka pintu baru ke hutan dan pohon melalui barang-barang immaterial yang bisa dihasilkan dari hutan tetapi juga sangat mengubah kerangka kerja, aturan, proses, dan modalitas produksi dan pertukaran antar pelaku ekonomi, dan cara-cara mengandung inovasi.
Yang ketiga tidak diragukan lagi adalah globalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dengan memperpendek jarak, mengatasi perbatasan, mempercepat pertukaran,
standarisasi praktik, meratakan struktur hierarki, mendorong saling ketergantungan,
globalisasi berdampak pada semua orang di mana saja dalam berbagai cara. Kehutanan tidak luput dari pisau tajam multifaset ini.
Bagaimana di Indonesia?
Sekitar 1880 Kalimantan Tenggara, demikian tulis Thomas Lindblad yang dikutip Han Knapen (2001), masih merupakan wilayah yang sama sekali tidak ada pengaruh dari luar. Penguasa kolonial Belanda pada waktu itu hanya mampu menyentuh satu dua wilayah pesisir pantai, dan menghubungkan pada pasar global. Kehidupan Dayak pedalaman hutan belantara tetap berlangsung ratusan tahun. Lindblad melakukan studinya di Kalimantan Tenggara untuk mengetahui dampak sosial ekonomi politik kolonialisme. Ia secara spesifik menganalisis situasi pada periode 1880 dan setelahnya.
Lindblad berpendapat pada periode kolonialisme 1880-1940 itulah terjadi perubahan yang signifikan di Kalimantan. Wilayah itu terintegrasi dengan pasar dunia dan ketika budaya imigran bertumbukan secara brutal dan langsung dengan mentalitas dan gaya hidup indigineous/asli yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Menurut Lindblad, transformasi sosial, ekonomi dan politik terjadi setelah 1880 dengan magnitud yang belum pernah dilihat ada. Pandangan Lindblad ini dibantah oleh Knapen yang melakukan studi tentang Kalimantan dengan rentang waktu 1600-1880. Pembangunan ekonomi memang terjadi pada periode 1880-1942. Tetapi itu tidak serta merta bisa menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan pada abad sebelumnya. Interaksi antara masyarakat asli dan luar telah berlangsung jauh sebelum 1600 dan perlahan-lahan menciptakan ekonomi baru. Kedatangan Eropa yang kemudian menguasai wilayah itu makin meningkatkan transformasi sosial ekonomi dan politik. Perubahan ini tidak bisa dihindari memberi dampak pada perubahan hutan.
Pada 1619 the Dutch East India Company (Vereenigde Oostindische Compagnie atau dikenal sebagai VOC) menaklukkan Jakarta di pantai utara dan menamainya Batavia. Belanda mempertahankan kehadiran di daerah ini selama lebih dari tiga abad, sampai tahun 1949, ketika Hindia Belanda tidak ada lagi dan menjadi Indonesia.
Bahkan sebelum Belanda mendirikan Batavia (1619), mereka telah memulai pembangunan dermaga di pulau Onrust, di seberang apa yang saat itu masih disebut Jakarta. Dermaga itu menampung sebuah galangan kapal besar, yang merupakan konsumen utama kayu untuk pembuatan kapal. Pada tahun 1675 galangan kapal ini mempekerjakan dua ratus orang; pada tahun 1700, hampir enam ratus; dan pada tahun 1755, enam ratus lima puluh. Setelah 1685 memiliki dua penggergajian kayu bertenaga angin. Di Batavia sendiri terdapat dua galangan kapan swasta, sebagian besar dijalankan oleh pembuat kapal Cina, dan setidaknya satu penggergajian kayu bertenaga air swasta (berasal dari tahun 1659).
Mulai tahun 1627 ada juga pasar kayu atau pekarangan kayu, yang dapat diakses oleh VOC dan pengusaha swasta. Kayu dibutuhkan tidak hanya untuk kapal, tetapi juga untuk bangunan di kota, untuk bahan bakar, dan untuk perabotan. Batavia berkembang pesat selama abad ketujuh belas, dan hampir semua bangunan terbuat dari kayu. Kayu, tentu saja, juga digunakan sebagai bahan bakar, baik dalam keadaan alaminya maupun sebagai arang. Permintaan arang didorong oleh kehadiran pabrik bubuk tepung di kota, yang pertama didirikan pada 1659. Pada 1787 ada tujuh pabrik seperti ini. Akhirnya, kayu dibutuhkan untuk furnitur; hingga 1650 banyak kayu jati digunakan untuk pembuatan furnitur. Karena VOC telah menaklukkan daerah dengan pedang di tangan, mereka merasa bebas untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya daerah itu sesuai keinginannya.
Perusahaan itu cukup berhasil memperoleh kayu bakar sebanyak yang dibutuhkan dari daerah yang terletak langsung di sekitar Batavia, yang disebut Lingkungan Batavia, tetapi kayu yang baik, terutama kayu jati, lebih sulit diperoleh. Sebuah organisasi yang bernama The Environs memproduksi kayu jati yang cukup untuk pembangunan rumah setidaknya sampai tahun 1644, tetapi kayu jati untuk bangunan rumah dikirim dari Jepara (Jawa Tengah) ke Batavia pada awal tahun 1622. Pada tahun 1636 sebuah armada kapal pribumi dikirim ke muara sungai Citarum di sebelah timur Batavia, untuk memperoleh kayu jati dari Krawang, di mana perusahaan tidak memiliki hak teritorial. Hingga tahun 1650, meskipun The Environs masih memasok beberapa kayu, VOC harus bergantung hampir sepenuhnya pada kesediaan penguasa pantai utara Jawa untuk pasokan kayu jati.
Bagaimana pun hutan bukanlah hanya hutan tanpa penghuni. Sebagian besar daerah hutan hujan tropis telah dihuni oleh orang-orang untuk waktu yang lama, meskipun pada kepadatan penduduk yang sangat rendah. Di banyak daerah hutan hujan tropis, bahkan di hutan yang dianggap “primer”, atau tidak terganggu, akan dapat ditemukan jejak bekas tempat tinggal manusia dan pertanian berpindah. Dengan demikian “primer” bukan berarti tidak pernah ada gangguan manusia.
Tidak banyak yang diketahui tentang laju deforestasi tropis di zaman sejarah, tetapi tampaknya antara tahun 1700 dan 1850 sekitar satu juta hektar dibuka setiap tahun, hampir secara eksklusif untuk pertanian berpindah. Dan karena pada saat yang sama hutan itu tumbuh kembali di pembukaan lahan kecil yang terbengkalai, laju deforestasi ini hampir tidak berpengaruh pada luas keseluruhan hutan hujan tropis.
Michael Williams, penulis Deforesting the Earth, seperti dikutip Martin (2015) menjelaskan
bagaimana deforestasi dipercepat pada periode kolonial setelah 1850. Budidaya padi mulai memakan banyak wilayah berhutan ketika petani pendatang membuka area yang luas di hutan dataran rendah Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Negara-negara ini menjadi wilayah pengekspor beras yang penting—mangkuk nasi Asia.
Negara-negara Asia Tenggara lainnya mengikuti, menggunduli hutan di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa. Lebih dari sepuluh juta hektar hutan telah dibuka sebelum tahun 1920, meskipun catatan tentang bagaimana ini terjadi tampaknya tidak meyakinkan. Filipina, yang telah di bawah pemerintahan kolonial Spanyol lebih dari 300 tahun, juga kehilangan hutan di bidang tengah Luzon, terutama untuk perkebunan tanaman komersial seperti tembakau dan tebu. Pengaruh kolonial terhadap ekspansi perdagangan tanaman juga terlihat di Assam, India, di mana British East Perusahaan India memperluas perkebunan tehnya dengan mengorbankan hutan tropis. Di Afrika Barat, terutama di Ghana dan Nigeria, hutan hujan ditebangi pada kuartal terakhir abad kesembilan belas untuk beberapa perkebunan kakao dan kelapa sawit komersial pertama.
Hutan hujan Amerika Latin, di sisi lain, hampir tidak dipengaruhi oleh pertanian komersial sebelum tahun 1920, dengan pengecualian beberapa perkebunan kopi, misalnya di daerah
barat laut São Paulo. Sebagian besar deforestasi di Selatan dan Amerika Tengah disebabkan oleh pertanian berpindah, yang biasanya mempengaruhi area yang relatif kecil dibandingkan dengan budidaya di Selatan dan Asia Tenggara. Pengecualian penting untuk pola moderat ini deforestasi adalah hutan pantai Atlantik Brasil, yang sudah dihancurkan pada fase awal kolonisasi di Daerah yang dikuasai Portugis.
Konversi hutan makin meningkat pesat sejalan dengan industrialisasi. Negara-bangsa yang lahir pasca kolonialisasi memacu percepatan pembangunannya dengan memanfaatkan hutan sebagai mesin penggerak roda-roda pembangunan. Termasuk Indonesia. Perkembangan pesat pemanfaatan hutan adalah ketika dikeluarkan undang-undang yang memungkinan swasta dan investor asing mendapatkan hak pemanfaatan hutan. Sejak tahun 1970-an itulah terjadi booming eksploitasi hutan.
Sektor Kehutanan di Rezim Soeharto
Di sektor kehutanan, pemerintah mengizinkan swasta untuk memanen dan ekspor log. Kebijakan ini didasarkan pada terbitnya UU No.1 Tahun 1967 dan No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, UU Kehutanan no. 5/1967 dan pemerintah
peraturan no. 21/1970. Atas dasar hukum pemberian hak pemanenan kayu dan hak industri, banyak konsesi besar dengan rentang 20-25 tahun diberikan segera setelah implementasi kebijakan pada tahun 1967. Tindakan ini mendorong perusahaan transnasional besar (TNC) dari Amerika Serikat (Weyerhaeuser, George Pacific, dll.) dan Jepang (Mitsubishi, Sumitomo, Shin Asahigawa, Ataka, dll.) untuk menginvestasikan modal di sektor kehutanan (Hurst 1990: 34) maupun sektor swasta domestik.
Sumatera dan Kalimantan adalah target pertama eksploitasi hutan dengan penebangan konsesi. Ini karena kedua pulau memiliki stok spesies pohon komersial terbesar yang berharga dan paling dekat dengan pasar Asia.
Konsesi penebangan menyebabkan peningkatan pesat ekspor kayu bulat yang belum diproses selama tahun 1970-an. Dengan keuntungan pemerintah dari sektor kehutanan meningkat menjadi sumber pendapatan terbesar kedua setelah sektor minyak, kerajaan bisnis baru Indonesia mengambil alih dan peluang kerja yang lebih besar terwujud (Robinson 1986). Namun seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor bisnis ini muncul tingkat deforestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar hutan primer telah habis, menambah kemiskinan yang melekat pada masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan-hutan tempat bergantung mata pencaharian mereka. Karena pemerintah tidak mengakui hutan adat masyarakat setempat, sengketa tanah terjadi di berbagai kabupaten. Misalnya, 14.440 ha disengketakan pada 1990-an antara komunitas lokal Muara Gusik Kabupaten Kutai dan perusahaan HPH the International Timber Corporation of Indonesia (ITCI). Konflik ini akhirnya berdampak negatif terhadap masyarakat secara ekonomi dan sosial (pendidikan dan kesehatan). Secara ekonomi, daya beli masyarakat telah menurun ke titik di mana rata-rata orang harus makan satu kali lebih sedikit setiap hari.
Sejalan dengan kegiatan pembalakan, HPH seluas hampir 11 juta ha diberikan di Kalimantan Timur dari tahun 1969 hingga 1974 (World Resources Institute 2000). Peningkatan ekspor kayu bulat ini dari 5,2 juta meter kubik pada tahun 1969/1970 menjadi lebih dari 24,3 juta m 3 pada tahun 1973/1974. Sepanjang tahun 1970-an, Kalimantan Timur memproduksi sepertiga hingga setengah kayu bulat Indonesia (Inoue 2000 ). Hanya pada tahun 1967, 4 juta m3 kayu bulat ditebang dari hutan Indonesia, dan sebagian besar untuk keperluan rumah tangga.
Lebih lanjut disebutkan pada tahun 1977, totalnya telah meningkat menjadi sekitar 28 juta m 3 dengan setidaknya 75% ditujukan untuk ekspor. Pendapatan dari sektor kehutanan naik dari US$6 juta pada tahun 1968 menjadi lebih dari US$564 juta pada tahun 1974.
Menurut Herman Hidayat, pada tahun 1979, Indonesia adalah produsen kayu bulat tropis utama, dengan pangsa 41% (US$2,1 miliar) dari pasar global dan mewakili volume ekspor kayu keras tropis yang lebih besar daripada seluruh Afrika dan Amerika Latin digabungkan (Lash, 2000). Pemerintah telah merencanakan untuk membangun sebuah industri kehutanan terpadu dari industri penebangan dan pengolahan kayu. Untuk melakukan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang penebangan dan membangun fasilitas untuk industri kayu.
Hutan Tanaman Industri (HTI)
Ada dua alasan yang mendasari pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Pertama, kurangnya kayu sebagai bahan baku industri kayu pulp dan kertas, kayu lapis, penggergajian kayu, dan sebagainya. Misalnya, dalam Pelita IV (1983–1988 Lima- Tahun Pembangunan) kebutuhan kayu adalah 40 juta m 3 , dan meningkat pesat menjadi sekitar 70 juta m 3 pada akhir 1990-an. Tapi kapasitas pasokan dari alam hutan setiap tahunnya hanya mencapai 38,4 juta m 3 , dan total produksi hutan mencapai 64 juta ha. Kedua, HTI dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kayu sebagai bahan baku. Oleh karena itu dikembangkan dari Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tiga basis: sosial, keberlanjutan, dan keuntungan pribadi (ekonomi; Tri Nugroho 1994: 6-18).
Pada tahun 1983, gagasan perlunya pengembangan HTI muncul di kalangan akademisi pada pertemuan yang diadakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 27-28 Desember 1983. Sementara itu, seluruh konsep HTI dibahas dalam seminar nasional berjudul: “Kita Tanam Hari Ini dan Kita Panen Esok” yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor pada tahun 1984.
Peran BUMN dan swasta dalam pengembangan HTI sangat signifikan. Sebagai hasil dari seminar nasional ini, Kementerian Kehutanan meluncurkan program jangka panjang program kebijakan strategis untuk membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Operasional dasar teknis pengembangan HTI dikeluarkan melalui berbagai peraturan:
(1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 1990 tentang hak pengusahaan HTI, pelengkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor 320/Kpts-II/1986 tentang Pengembangan HTI;
(2) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 29 Tahun 1990 tentang Iuran Reboisasi (Dana Reboisasi) yang pelengkap Keputusan Presiden nomor 35 Tahun 1980 tentang “Reboisasi”. Dana Asuransi dan Penanaman Kembali Hutan;”
(3) Keputusan Menteri Kehutanan nomor 19/Kpts-II/1991 tentang Pembagian Sumbangan Reboisasi untuk Pembangunan HTI, dilakukan oleh Perusahaan Kehutanan Negara ( Inhutani) di lingkungan Kementerian Kehutanan;
(4) Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan nomor 421/Kpts-II/1990 dan Nomor 931/KMK.o13/1990 tentang Pokok-pokok pelibatan modal negara dan peminjaman kontribusi reboisasi di HTI perkembangan.
Secara konseptual, HTI adalah kehutanan yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, menerapkan silvikultur intensif untuk menyediakan
kayu sebagai bahan baku. Oleh karena itu, Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah produksi
hutan dengan karakteristiknya masing-masing, memungkinkan pelaksanaan silvikultur intensif, produksi bahan baku industri kayu, pulp dan kertas, dan kebutuhan lainnya. Tumbuhan pohon dikategorikan sebagai pohon cepat tumbuh seperti Eucalyptus dan Acacia mangium. Pohon-pohon ini dari penanaman sampai panen perlu dipotong sekitar 6-7 tahun.
Deforestasi dan degradasi hutan tropis di Indonesia menjadi perhatian serius banyak pemangku kepentingan. Sekitar 16 juta hektar lahan hutan dalam konsesi terdegradasi. Selain itu, ketidakjelasan hak penguasaan dan kepemilikan tanah telah menimbulkan konflik yang signifikan, yang juga berkontribusi pada pengelolaan hutan yang tidak lestari. Menanggapi hal itu, organisasi domestik dan internasional telah memberikan tekanan yang cukup besar pada Indonesia untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pengelolaan hutan.
Era Sertifikasi Hutan
Pada tahun 1990, sertifikasi hutan pertama kali di negara berkembang dilakukan di Indonesia,
saat SmartWood mensertifikasi operasi hutan jati Perum Perhutani di pulau Jawa. Menanggapi hal ini dan tekanan LSM lainnya, Pemerintah Indonesia mendirikan skema sertifikasi hutannya sendiri – Lembaga Ekolabel Indonesia – pada tahun 1993. Pada tahun 1998, LEI secara resmi didirikan sebagai yayasan dan sejak itu telah melakukan beberapa penilaian sertifikasi. LEI dan FSC juga telah mengembangkan Protocol Sertifikasi Bersama (JCP) yang mewajibkan FSC untuk menggunakan kriteria dan indikator LEI dan FSC ketika melakukan penilaian terhadap suatu pengelolaan hutan.
Meskipun kedatangan gagasan sertifikasi lebih awal, praktik kehutanan yang buruk, kebijakan pemerintah yang tidak efektif, dan konflik terkait hutan atas hak masyarakat adat atas tanah telah menghambat pengembangan sertifikasi di Indonesia. Sementara banyak tantangan tetap ada, beberapa efek positif sertifikasi telah dicatat. Ini termasuk pembentukan insentif pemerintahan bagi perusahaan untuk lulus sertifikasi LEI, peningkatan kemauan perusahaan untuk terlibat dalam konsultasi publik, dan pembukaan ruang politik untuk LSM dan masyarakat untuk mengungkapkan keprihatinan mereka.
Sertifikasi hutan telah berlangsung di Indonesia selama 31 tahun. Kesulitan-kesulitan telah banyak yang dihadapi meski tidak selalu bisa mengatasi. Tantangan berat adalah berkaitan dengan lingkungan eksternal. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, penegakan hukum yang buruk, dan korupsi. Lingkungan eksternal yang sulit ini, ditambah dengan beberapa kasus yang memaksa pencabutan sertifikasi, telah mendorong para pengritik untuk menyimpulkan bahwa sertifikasi tidak dapat bekerja di Indonesia. Kecuali ada perubahan mendasar dalam, khususnya pengaturan kepemilikan lahan dan lingkungan kebijakan. Ini adalah kesimpulan yang terlalu pesimis. Sertifikasi dapat membuat perbedaan praktis di tingkat unit manajemen dan itu membantu sejumlah kecil perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Meskipun banyak variasi dampak sertifikasi FSC yang ditimbulkannya. Misalnya Matias, Cagnacci, dan Rosalino dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun skema sertifikasi FSC diterima sebagai sistem untuk mencapai setidaknya 11 tujuan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (FSC, 2016), sehingga dianggap efektif dan dapat diandalkan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia, tidak ada perbedaan yang jelas antara kelimpahan sebagian besar taksa di konsesi FSC dibandingkan dengan konsesi yang tidak melakukan pemanenan yang bertanggung jawab secara ekologis, yaitu tegakan yang tidak bersertifikat.
Dari perspektif pengelola hutan sendiri, sertifikasi telah membawa dampak yang lebih positif seperti memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial para staf dan membantu meningkatkan kelestarian hutan. Namun, penerapan program ini telah memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan-perusahaan ini karena adanya biaya tambahan untuk mendapatkan sertifikasi dan inspeksi tahunan. Di sisi lain, penelitian ini memaparkan dampak sertifikasi hutan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan mengenai permasalahan sertifikasi hutan.
Penelitian lain di Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor hasil hutan Tiongkok terutama didorong oleh margin kuantitatif, diikuti oleh margin harga. Sertifikasi hutan di negara-negara mitra dagang mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap margin harga dan dampak negatif yang signifikan terhadap margin kuantitatif produk hutan Tiongkok. Selain itu, dampak terhadap margin kuantitatif lebih besar dibandingkan dengan margin harga, sedangkan dampak terhadap margin ekstensif tidak signifikan. Studi ini memberikan dasar ilmiah untuk menanggapi langkah-langkah sertifikasi hutan, memperdalam kerja sama dengan negara-negara pedagang hasil hutan, dan memperkuat saling pengakuan dan koordinasi sistem sertifikasi hutan.
Dampak sertifikasi juga ditunjukkan dalam penelitian Hando Hain, 2005. Hasil studi menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan di banyak bidang, terutama dalam hal peningkatan kesadaran dan reputasi lingkungan. Peningkatan yang signifikan juga terlihat dalam pelestarian unsur-unsur biologis di lokasi penebangan habis, keselamatan kerja dan pengendalian risiko lingkungan selama operasi pengelolaan hutan. Sayangnya, sertifikasi tampaknya belum mempengaruhi banyak aspek yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang dekat dengan alam seperti penggunaan metode non-tebang habis dan pengembangan tegakan campuran yang umurnya tidak sama. Sertifikasi juga tidak membantu meningkatkan perhatian masyarakat lokal dan tidak memberikan manfaat finansial yang signifikan. Yang terakhir, pemanfaatan hasil hutan non-kayu masih belum ditangani, meskipun banyak pemangku kepentingan melihat adanya ruang untuk perbaikan dalam hal ini. Dampak negatif diamati oleh staf RMK sendiri sehubungan dengan meningkatnya jumlah dokumen dan dokumentasi yang diduga berlebihan. Peningkatan prosedur dan dokumen lainnya juga merupakan hasil dari proses transformasi dari kekacauan pasca-Soviet menjadi perusahaan yang terorganisir dan dikelola dengan baik.
Kais Bouslah et.al. melakukan penelitian untuk menguji secara empiris dampak sertifikasi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Financial Performance/FP). Pertanyaan utamanya adalah apakah ada “premi hijau” bagi perusahaan yang tersertifikasi, dan, jika ya, untuk jenis sertifikasi apa. Mereka menganalisis kinerja harga saham jangka pendek dan jangka panjang menggunakan metodologi studi peristiwa pada sampel perusahaan Kanada dan AS. Hasil dari kejadian abnormal return jangka pendek menunjukkan bahwa sertifikasi hutan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap FP perusahaan terlepas dari sistem sertifikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan hasil jangka pendek, hasil abnormal jangka panjang pasca peristiwa menunjukkan bahwa sertifikasi hutan, rata-rata, mempunyai dampak negatif terhadap perusahaan FP. Namun, dampak sertifikasi hutan terhadap perusahaan FP bergantung pada siapa yang memberikan sertifikasi, karena hanya sertifikasi yang dipimpin oleh industri (Sustainable Forestry Initiative, Canadian Standards Association, dan ISO14001) yang dikenakan sanksi oleh pasar keuangan, sedangkan organisasi sertifikasi non-pemerintah–Forest Stewardship Council tidak.
Keragaman dampak sertifikasi ini ditangkap dengan baik oleh Romero et.al. Mereka melakukan penelitian terhadap dampak sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) terhadap pengelolaan hutan alam di daerah tropis dengan mengeksplorasi pendekatan yang ketat terhadap cara penilaian intervensi konservasi yang kompleks. Penelitian ini lebih menekankan pada cara mengevaluasi dampak. Mereka menjelaskan peta jalan berdasarkan metode yang ketat untuk menilai apakah sertifikasi FSC memberikan hasil yang diharapkan dan mekanisme mendasar yang dapat menyebabkan perubahan disebabkan oleh FSC. Menurut mereka untuk mencapai tujuan ini, studi latar belakang yang memberikan pengetahuan kontekstual terkait dengan implementasi sertifikasi FSC diusulkan untuk memperhitungkan bias positif dalam seleksi mandiri dan untuk menangkap dinamika temporal sertifikasi termasuk perubahan dalam konteks sosiopolitik dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan sertifikasi. Dengan pendekatan yang ketat itu maka dampak sesungguhnya dari sertifikasi FSC bisa diidentifikasi lebih akurat.
Bagaimanapun sebagai sebuah bentuk intervensi pembangunan sertifikasi hutan mempunyai dampak positif dan negatif yang terus menerus bisa diperbincangkan. Kenyataan bahwa FSC telah bisa berlangsung hingga lebih dari 30 tahun dan mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan pada periode itu menunjukkan bahwa FSC telah berjalan pada jejak sejarah yang benar. Dengan lebih dari 1,200 anggota individu dan organisasi dari 93 negara, FSC telah menyelesaikan lebih dari 150 juta hektare hutan bersertifikat dengan lebih dari 55.000 sertifikasi yang memverifikasi sumber daya berkelanjutan, lebih dari 1.600 perusahaan yang mempunyai lisensi untuk mempromosikan produk berlabel FSC dan 46% konsumen di seluruh dunia mengenali label FSC.
Deforestasi lebih lanjut telah dihindari. Apresiasi pengelolaan hutan telah diberikan kepada mereka yang memenuhi standar pengelolaan yang baik. Akses pasar terbuka dengan lebar. Lalu apa lagi yang akan dilakukan?
Remedy Framework: Jalan Bagi Sertifikasi Hutan Tanaman
Gagasan membuka diri pada sertifikasi hutan tanaman industri melewati jalan yang panjang. Secara tradisional FSC menyertifikasi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman. Tetapi khusus untuk hutan tanaman dibatas pada perusahaan pengelolaan hutan tanaman yang dibangun hanya sebelum November 1994 yang dikenal dengan 1994 Cut-off Date. Semua hutan tanaman yang dibuka setelah November 1994 tidak bisa disertifikasi FSC. Kebijakan 1994 Cut-off date dilandaskan pada pencegahan upaya legitimasi deforestasi atau konversi hutan alam dengan sertifikasi. Kebijakan ini tanggapan terhadap kekhawatiran global tentang deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi di seluruh dunia.
Tanggal cut-off November 1994 dipilih segera setelah pembentukan FSC. Tanggal ini dipilih untuk memberikan batas temporal yang jelas guna mencegah konversi baru hutan alam menjadi hutan tanaman yang memenuhi syarat untuk sertifikasi. Pilihan tanggal ini merupakan konsensus di antara anggota pendiri FSC, yang meliputi organisasi lingkungan, kelompok masyarakat adat, dan perwakilan industri.
Terdapat empat alasan penting Kebijakan 1994 Cut-off Date
- Mencegah Insentif Deforestasi: Dengan menetapkan tanggal cut-off, FSC bertujuan untuk memastikan bahwa sertifikasinya tidak secara tidak sengaja menciptakan insentif ekonomi bagi pemilik lahan untuk mengonversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Kebijakan ini membantu melindungi hutan alam yang masih ada dari pembukaan lahan.
- Mendorong Praktik Berkelanjutan: Kebijakan ini mendorong pengelola hutan dan perusahaan untuk mengadopsi dan mempertahankan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada hutan tanaman yang sudah ada, daripada memperluas ke wilayah hutan alam. Hal ini sejalan dengan misi FSC untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia.
- Menjaga Kredibilitas dan Integritas: Kredibilitas FSC sebagai pemberi sertifikasi praktik kehutanan yang berkelanjutan bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsipnya. Tanggal cut-off membantu menjaga integritas sistem sertifikasi dengan memastikan bahwa hanya hutan tanaman yang tidak berkontribusi pada deforestasi terbaru yang memenuhi syarat.
- Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati: Hutan alam sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati. Dengan mencegah konversi hutan alam, FSC membantu melindungi ekosistem yang beragam dan spesies yang bergantung padanya.
Sejak FSC didirikan pada tahun 1994, dunia telah berubah baik dalam hal tekanan yang terus berlanjut terhadap ekosistem global yang disebabkan oleh konversi hutan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tindakan untuk mendorong konservasi dan restorasi hutan, serta untuk melawan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Menurut Prinsip dan Kriteria FSC, hutan tanaman yang dihasilkan dari konversi hutan alam setelah tahun 1994 tidak layak berpartisipasi dalam sistem FSC, sehingga seringkali menyebabkan pengelolaan yang buruk, dan menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap jasa ekosistem dan juga mengabaikan keanekaragaman hayati. Dan FSC tidak memiliki insentif atau aturan yang memungkinkan perusahaan hutan tanaman terlibat sehingga bisa memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya.
Demikian pula, tingkat konversi yang tinggi di banyak tempat di wilayah selatan selama beberapa dekade terakhir karena perkembangan ekonomi yang lebih baru, termasuk pembangunan hutan tanaman. Sedangkan tingkat konversi yang rendah di wilayah utara karena pembangunan ekonomi dan pembangunan hutan tanaman telah dimulai jauh sebelum 1994 itu. 1994. Oleh karena itu, beberapa pihak melihat kebijakan FSC tidak seimbang, tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang sama bagi semua wilayah.
Pada tahun 1996, FSC menyetujui untuk menambahkan Prinsip 10 yang secara khusus berkaitan dengan hutan tanaman. Tiga tahun kemudian, pada 1999, perubahan P&C terjadi kembali termasuk perubahan dengan penambahan kriteria tentang konversi 1994. Tidak semua anggota setuju dengan memasukkan kriteria tentang konversi 1994 ini. Karena itu perdebatan tentang sertifikasi hutan tanaman terus berlangsung. Pada 2002 FSC mengeluarkan Plantation Discussion Paper yang ditulis oleh Tim Synnott. Antara 2006-2009 sejumlah Laporan dikeluarkan oleh beberapa Expert Panel untuk membahas FSC Plantation Policy. Pada saat General Assembly di Kota Kinabalu, 2011, akhirnya anggota FSC menyetujui Policy Motion 18 “FSC Certification of Plantations.” Sejak adopsi Policy Motion 18 inilah perjalanan menuju perubahan 1994 Cut-Off Date dimulai dengan lebih gencar. Hingga akhirnya FSC General Assembly di Bali, 2022 menyetujui Motion 37 dan 45. Fitur penting Motion 37 antara lain:
- Mengubah batas waktu November 1994 menjadi Desember 2020 ketika perkebunan yang dikonversi dari hutan alam tidak termasuk dalam sertifikasi FSC.
- Mencerminkan definisi baru konversi dalam Kebijakan Mengatasi Konversi dengan memasukkan konversi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV).
- Mengharuskan pemulihan atas kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh konversi
- Merevisi definisi restorasi/restorasi ekologis menjadilebih komprehensif.
Sementara itu Motion 45 meminta agar perubahan harus dilakukan pada versi final FSC Remedy Framework untuk meningkatkan kredibilitasnya sebelum diserahkan kepada the FSC International Board untuk disetujui pada bulan Desember 2022. Saat ini FSC telah membuat Remedy Framework yang menjadi landasan utama untuk implementasi kebijakan baru Cut-off Date.
Apa arti semua perubahan ini? FSC menyampaikan tiga hal yang menarik sebagai dampak dari kebijakan radikal ini. Pertama, manfaat bagi hutan. Jutaan hektar lahan hutan yang saat ini terdegradasi, melalui perbaikan dan restorasi, dapat mengadopsi Prinsip dan Kriteria FSC dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan standar sertifikasi. Ini akan mengembalikan nilai-nilai ekologi dan sosial dari hutan-hutan tersebut dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam di banyak negara di seluruh dunia.
Langkah-langkah perbaikan yang berkaitan dengan restorasi ekologi akan mengembalikan kawasan yang dikonversi ke kondisi yang lebih dekat dengan bentuk alaminya. Hutan akan tumbuh kembali melalui proses restorasi habitat dan dampak ekologis dari aktivitas deforestasi dan degradasi di masa lalu.
Kedua, manfaat bagi masyarakat. Melalui jalur pemulihan FSC, masyarakat yang bergantung pada hutan kini memiliki akses terhadap jalur pemulihan non-yudisial dan dapat memperoleh manfaat dari kompensasi finansial dan non-finansial atas kerugian sosial yang disebabkan oleh konversi hutan. Penerapan Prinsip dan Kriteria serta Kerangka Perbaikan juga akan memberikan keadilan dan akses terhadap sertifikasi dan karenanya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh belahan dunia, terutama wilayah di mana konversi lahan berperan dalam pembangunan ekonomi setelah tahun 1994, seperti Amerika Latin, Selatan Asia Timur, dan Afrika.
Ketiga, manfaa bagi organisasi, perusahaan, dan rantai nilai. Organisasi yang lahannya dikonversi antara tahun 1994 dan tahun 2020 akan memiliki akses untuk mengadopsi peraturan FSC mengenai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, setelah adanya perbaikan. Hal ini dapat membantu pembangunan yang bertanggung jawab di negara-negara berkembang yang memiliki potensi rantai nilai hutan yang kuat dengan mendukung upaya sertifikasi FSC di negara-negara tersebut. Banyak perusahaan yang sebelumnya tidak dapat mensertifikasi sebagian tanah mereka karena batas waktu tahun 1994, kini berhak mengajukan permohonan sertifikasi atas tanah tersebut asalkan mereka memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh konversi. Misalnya, 50 persen perkebunan karet di Asia didirikan setelah tahun 1994 sehingga menjadi hambatan bagi mereka untuk memperoleh sertifikasi FSC dan memasuki sistem tersebut.
Dengan batas waktu yang baru, FSC tidak akan mensertifikasi lahan apa pun yang telah dikonversi dari hutan alam atau yang telah terjadi perusakan Nilai Konservasi Tinggi setelah tanggal 31 Desember 2020. Perusahaan mana pun yang dinyatakan bersalah atas aktivitas yang tidak dapat diterima – termasuk konversi – di masa lalu dan upaya untuk mengakhiri disosiasi atau asosiasi dengan FSC juga harus terlebih dahulu melalui proses penyelesaian terstandar yang berfokus pada persyaratan tambahan dalam Kerangka Pemulihan yang baru, yang akan berlaku efektif mulai pertengahan tahun 2023.
Menunda Kekalahan?
Apa selanjutnya? Apakah gagasan remediasi adalah berita yang menggembirakan? Atau apakah ia sebetulnya hanya langkah-langkah kecil yang cuma menunda kekalahan? Kekalahan kita dalam mempertahankan hutan dan sumberdaya alam. Bahkan ancaman kepunahan Homo pasien.
Mari kita lihat bagaimana status hutan setelah berbagai prakarsa dilakukan, dari tingkat lokal hingga global. Setelah langkah-langkah itu dilakukan dalam hampir setengah abad.
Analisis yang dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) memberi sedikit harapan. Misalnya hilangnya hutan tropis di Brazil dan Kolombia menurun tajam. Namun angka hilangnya hutan tropis secara umum tetap tinggi.
Antara tahun 2022 dan 2023, Brasil dan Kolombia mengalami penurunan kehilangan hutan primer sebesar 36% dan 49%. Meskipun terjadi penurunan drastis, laju hilangnya hutan primer tropis pada tahun 2023 tetap konsisten dengan tahun-tahun terakhir, menurut data baru dari laboratorium GLAD Universitas Maryland dan tersedia di platform Global Forest Watch WRI.
Sialnya kehilangan hutan malah bergeser dari satu negara yang menunjukkan kemauan politik untuk mengurangi hilangnya hutan ke negara lain dengan kemauan politik yang rendah. Penurunan yang signifikan terjadi di Brasil dan Kolombia diimbangi oleh peningkatan tajam hilangnya hutan di Bolivia, Laos dan Nikaragua.
Total hilangnya hutan primer tropis pada tahun 2023 mencapai 3,7 juta hektar, setara dengan hilangnya hampir 10 lapangan sepak bola (sepak bola) hutan per menit. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan sebesar 9% dibandingkan tahun 2022, angka pada tahun 2023 hampir sama dengan tahun 2019 dan 2021. Hilangnya hutan ini menghasilkan 2,4 gigaton (Gt) emisi karbon dioksida pada tahun 2023, setara dengan hampir setengah dari bahan bakar fosil tahunan. emisi Amerika Serikat.
Menurut laporan WWF, Forest Pathways Report 2023, dunia mengalami kerusakan hutan. Padahal kita tahu, seperti ditulis pada Laporan itu, hutan menyedot sepertiga emisi gas rumah kaca dunia, dan merupakan rumah bagi 80% keanekaragaman hayati bumi, dan menyediakan mata pencaharian bagi 1,6 miliar orang. Melindungi hutan adalah salah satu dari sedikit tujuan politik global, lintas partai, dan diabadikan dalam berbagai perjanjian, komitmen, tujuan dan target internasional termasuk the Glasgow Leaders’ Declaration on Forests (GLD) dan Land Use (2021) dan the New York Declaration on Forests (2014). Sejak GLD ditandatangani di Glasgow pada bulan November 2021, setidaknya 4,7 juta hektar hutan hujan tropis primer telah hilang. Hilangnya hutan, konversi dan degradasi terus berlanjut meskipun ada janji dan deklarasi global.
Kisah mengenai hutan kita saat ini adalah adanya perbedaan antara tujuan yang tertuang dalam komitmen internasional dan kenyataan di lapangan – dimana terjadi percepatan hilangnya hutan, degradasi yang terus berlanjut, penurunan jumlah satwa liar di hutan, dan tanda awal adanya ancaman terhadap fitur-fitur iklim yang penting. seperti musim hujan, sebagai respons terhadap deforestasi.
The 2023 Forest Declaration Assessment menemukan bahwa dunia masih berada di luar jalur menuju penghentian deforestasi pada tahun 2030, dengan deforestasi global pada tahun 2022 sebesar 4% lebih tinggi dibandingkan deforestasi global pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi hilangnya hutan sebesar 6,6 juta hektar, selisih 21% dari target tahun 2022, untuk menghentikan hilangnya hutan pada tahun 2030. Di wilayah tropis, 4,1 juta hektar hutan basah primer hilang pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 33%. penyimpangan dari target tahun 2022.
The Forest Declaration Assessment dilakukan untuk melacak kemajuan komitmen terhadap hutan global sasaran. Laporan pertamanya yang terbit pada tahun 2022 menanyakan
‘apakah kita berada di jalur yang tepat untuk tahun 2030?’ Jawabannya hanya ada satu kata: ‘Tidak’. The FAO Global Forest Resources Assessment (FRA) 2020 memperkirakan bahwa 420 juta ha hutan telah mengalami deforestasi (dikonversi menjadi penggunaan lahan lain) antara tahun 1990 dan 2020; walaupun lajunya menurun selama periode tersebut, deforestasi
diperkirakan masih mencapai 10 juta ha per tahun pada tahun 2015–2020 (sekitar 0,25 persen
per tahun).
Peraturan dan beragam instrumen kebijakan telah disediakan seperti dipaparkan di atas, termasuk kesepakatan politik. Uni Eropa (EUDR) telah memaksa perusahaan-perusahaan untuk menunjukkannya aktivitas mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi mulai tahun 2024. Termasuk di Indonesia melalui PP No. 71/2014 yang merupakan salah satu peraturan yang memiliki peran sentral terhadap penerbitan sejumlah peraturan yang melindungi hutan di Indonesia. Sejumlah peraturan (Perpres No.88/2017, Inpres No.8/ 2015, Inpres No.6/2017, PermenLHK No. 77/2015 serta PermenLHK No. 50, 51 dan 81 tahun 2016) mencantumkan PP No.17/2014 sebagai acuan peraturan. Hasil analisis dengan menggunakan metode Social Network Analysis menunjukkan fakta bahwa PP No. 71 merupakan peraturan sentral yang diacu hampir seluruh peraturan yang melindungi sector kehutanan di Indonesia.
“Jadi mengapa semakin banyak perangkat kebijakan dan komitmen politik yang mendukung tindakan melindungi hutan tetapi tidak diterjemahkan melakukan perubahan di lapangan?” tulis Thomas Maddox, Director, Forests and Land, CDP dalam pengantar untuk The Forest Transition: from Risk to Resilience: Global Forests Report 2023 (July 2023). Mengapa laju deforestasi, khususnya di daerah tropis, yang masih menyisakan beberapa juta hektar setiap tahunnya?
Salah satu alasannya, dari sisi sektor swasta adalah pemberantasan deforestasi dari rantai pasok bukan merupakan prioritas bagi sebagian besar perusahaan, dan tekanan dari lembaga keuangan, pembeli atau pembuat kebijakan masih terlalu lemah untuk mendorong kemajuan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan CDP, hanya satu dari 10 perusahaan yang mengelola risiko deforestasi mereka. Meskipun demikian ada sedikit optimisme. Satu dari sepuluh perusahaan yang mengungkapkan mengelola risiko mereka saat ini akan mempunyai dampak yang signifikan serbagai pioner dari pesaing mereka ketika tekanan terus berlanjut untuk tumbuh.
Remedy Framework, Remedy Mindset
Namun juga perlu diingat bahwa mengatasi deforestasi adalah sebuah upaya yang integral/holistik dalam sebuah ekosistem yang luas. Ia harus menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari sebagian besar strategi lingkungan holistik di masa depan. Ini adalah salah satu tindakan yang berkontribusi terhadap banyak tantangan termasuk iklim, keamanan air,
hilangnya keanekaragaman hayati dan potensi manfaat sosial. Inilah nilai penting dari gagasan remediasi yang dilakukan oleh FSC. Parapihak (stakeholders, rights holders) harus bahu membahu untuk menempatkan diri dan mengambil peran aktif yang bisa dikontribusikan agar tujuan memulihkan fungsi hutan bisa tercapai melalui Kerangka Pemulihan (Remedy Framework). Sebagai gagasan yang baru (bagi FSC dan parapihak) maka kita memasuki satu arena belajar bersama untuk menciptakan karya bersama (learning, co-creation). Memahami hal-hal yang baru. Berbagi pengetahuan dan pengalaman, memberi masukan dan kritik, agar menjadi upaya kolektif membangun konsep dan pelaksanaan kerangka remediasi yang terbaik yang bisa diciptakan bersama (co-creation).
Secara umum umat manusia telah memasuki Industri 4.0, sebuah era digital atau pasca-PC dengan karakteristik berupa teknologi bergerak (mobile). Teknologi sedekat sentuhan jari. Segala hal bisa didapatkan hanya dengan kelincahan balet jari jemari di layar genggam. Namun diprediksi era industri baru telah ada di depan mata: Industri 5.0. Karakteristik Industri 5.0 adalah ketika teknologi kecerdasan buatan (artificial intelliegence atau AI) telah menjadi ‘manusia.’ Ia mampu menirukan kecerdasan manusia dan membantu kegiatan operasional organisasi yang membutuhkan otomasi interaksi dengan pelanggannya dan segala keperluan. Perubahan di era Industri 5.0 sangatlah cepat. Bila era Industri 0.0 dicapai dalam waktu ratusan ribu tahun, Industri 1.0 ribuan tahun, Industri 2.0 ratusan tahun, dan Industri 4.0 puluhan tahun, maka Industri 5.0 dapat terjadi dalam waktu belasan tahun. Setiap hari selalu ada inovasi di sektor industri teknologi informasi, keuangan, layanan, dan sebagainya. Organisasi-organisasi berusia ratusan tahun bertumbangan, organisasi-organisasi berusia puluhan tahun mulai kebingungan kehilangan pangsa pasar, dan organisasi belia berusia kurang dari sepuluh tahun telah mengalahkan kapitalisasi pasar pemain lama. Maka inovasi Remedy Framework FSC adalah bagian dari adaptasi pentingnya dalam dunia kehutanan yang bergerak cepat.
Dalam proses belajar dan co-creation tentang Remedy Framework ini maka parapihak, dalam era industri baru ini, memerlukan mindset, skillset dan toolset yang baru agar tak hanya relevan dan mampu bertahan tetapi juga terus tumbuh dan berkembang. Satu-satu-nya cara untuk mengubah mindset, skillset, dan toolset adalah melalui learning. Diperlukan mindset learning yang berbeda, skillset learning yang ber-beda, dan toolset learning yang berbeda dengan gene-rasi sebelumnya. Model learning di era masa depan ini dinamakan Learning 5.0, dan organisasi perlu mengadopsi model baru ini sedari sekarang.
Perubahan mindset parapihak sangat diperlukan dalam arena belajar bersama ini. Dan learning yang efektif menuntu untuk un-learn yakni belajar melepaskan mindset, skillset, dan toolset lama. Sebab ketergantungan pada mindset, skillset, dan toolset lama akan mncegah seseorang memikirkan cara-cara baru yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik dan lebih mudah. “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn,” kata Alvin Toffler.
Karena itu Remedy Framework akan efektif jika juga dilakukan Remedy Mindset dari parapihak. Mindset atau polapikir yang antusias untuk berkembang, memimpin dan melayani dengan nilai-nilai sustainability. Mengembangkan apa yang disebut growth mindset–sebuah polapikir yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan dan peningkatan yang berkelanjutan adalah mungkin (Capozzi, 2017). Orang dengan growth mindset bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Mereka percaya bahwa dengan motivasi dan keterampilan yang tepat, potensi sejati siapa pun sebenarnya tidak terbatas. Tidak butuh waktu lama untuk mengenali seseorang yang hidup dengan pola pikir ini. Orang dengan pola pikir ini memiliki rasa ingin tahu; mereka terbuka terhadap kemungkinan, mereka memiliki pandangan yang positif, dan mereka memiliki keinginan untuk belajar dan make a difference.
Singkatnya, growth mindset mendorong pertumbuhan berkelanjutan secara pribadi dan profesional. Bertanggungjawab atas apa yang dilakukan hari ini terhadap kekayaan yang dimilikinya (kekayaan alam dan kekayaan material pribadi) dan sadar akan segala dampak bagi generasi yang akan datang. Lebih spesifik lagi Isabel Rimanoczy menyebutnya
sebagai “The sustainability mindset. “Elemen-elemen prinsip The Sustainability Mindset (polapikir keberlanjutan) berkaitan dengan the knowing (ecoliteracy), thinking (systemic and innovative thinking), and being (values, purpose).
Kalangan perusahaan yang melaksanakan Remedy Framework harus juga melakukan Remedy Mindset. Mengubah mindset lama dengan yang baru. Meningkatkan atau mengubah skillset dengan yang baru. Dan mengganti toolset lam dengan yang baru. Demikian juga kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dengan Remedy Framework. Tak lupa masyarakat baik yang interested stakeholders, impacted rights holder dan affected rights holder harus pula melakukan yang sama.
Dalam situasi belajar bersama ini, kita selain sebagai pembelajar, barangkali juga sebagai pendidik. Pendidik yang menciptakan cahaya-cahaya harapan dari bersatunya peradaban dengan jiwa… “..educators today creating the hope spots of a civilization reunited with its soul.“