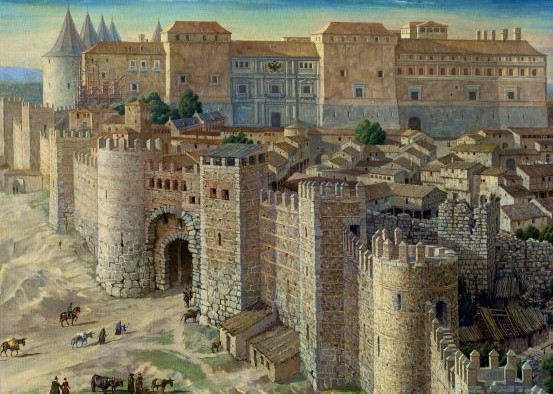halaman drm #48
Sekali lagi Gencatan Senjata:
Harapan dan Skeptisisme
Dwi R. Muhtaman
“Di antara reruntuhan,
seorang anak menuliskan
namanya di atas debu,
seolah ingin membuktikan
bahwa ia pernah ada.”
— Mahmoud Darwish, A State of Siege (2002)1
Nafsu Settler Colonialism
Malam itu, di atas langit Gaza yang berwarna tembaga karena api, seorang ibu mengangkat wajahnya dan berbisik: “Apakah ini berarti damai?”
Bom telah berhenti sejenak. Orang-orang keluar dari puing. Anak-anak menatap langit kosong — bukan karena bintang, tapi karena tak ada lagi drone yang berputar di atas kepala, dengung yang memekakkan telinga dan ketenangan.
Media menyebutnya ceasefire. Sebuah kata yang manis dalam bibir diplomat, tapi getir di telinga yang hidup di bawahnya. Dalam reruntuhan manusia, satu-satunya hal yang tetap indah adalah hati yang selalu penuh harapan. Albert Camus pernah menulis, “In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.” — sebuah refleksi tentang harapan dalam reruntuhan.2
Namun di Gaza, bahkan hati pun belajar bersembunyi.
Israel adalah sebuah entitas pendatang yang para ahli menyebutnya sebagai Settler Colonialism, kolonialisme pemukim. Settler colonialism adalah bentuk kolonialisme di mana tujuan utama bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya atau tenaga kerja lokal, melainkan menggantikan populasi dan mendirikan masyarakat-pemukim yang permanen di atas tanah yang dikuasai. Dalam bahasa teori: ia adalah sebuah logic (logika) dan structure (struktur) — bukan sekadar peristiwa historis temporal — yang menuntut kontrol atas tanah dan eliminasi, marginalisasi, atau assimilasi penduduk asli sehingga proyek pemukim bisa menjadi negara berdaulat. Konsep ini dirumuskan dan dipopulerkan dalam kajian modern oleh para sarjana seperti Patrick Wolfe (konsep “logic of elimination”) dan berkembang menjadi bidang studi tersendiri: settler colonial studies.3
Wolfe juga menyebutkan ciri-ciri khas settler colonialism, yakni, berbasis tanah (land-based): Kepemilikan/desakan atas tanah adalah tujuan utama — bukannya sekadar ekstraksi komoditas. Logika eliminasi: Pemukim berusaha menghapus kemampuan kolektif penduduk asli—melalui pembantaian, pembersihan etnis, pengusiran, asimilasi paksa, atau pembatasan reproduksi sosial politik—agar tanah “tersedia” bagi pemukim. Patrick Wolfe menekankan bahwa logika ini bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan hanya episodik.4 Selanjutnya adalah tentang pembentukan negara-pemukim: Seiring waktu, pemukim mendirikan institusi politik, hukum, dan budaya yang membuat keberadaan mereka menjadi permanen (mis. konstitusi, undang-undang tanah, sistem pendidikan). Kemudian menciptakan perangkap legal dan retorik: Narasi tentang “penemuan”, “kembalinya ke tanah leluhur”, atau “peradaban” dipakai untuk melegitimasi klaim. Lalu secara perlahan dan sistematis melakukan penggantian demografis dan ekonomi: Kebijakan pemukiman, redistribusi tanah, kontrol atas akses sumber daya, serta struktur kerja yang menempatkan penduduk asli pada posisi subordinat.
Secara praktis, metode eliminasi bisa berupa kekerasan langsung (pembunuhan massal, pembersihan etnis), paksaan ekonomi (pengambilalihan lahan, larangan bertani), hukum (penetapan status hukum yang merampas hak), atau kontrol mobilitas (penjara terbuka, checkpoint, status tanpa kewarganegaraan/apatrid dan juga praktik apartheid).5
Kita bisa menghimpun sejumlah contoh Settler Colonialism dalam sejarah peradaban modern. Ia muncul berkaitan erat dengan ekspansi Eropa modern sejak abad ke-15–19, tetapi juga memiliki varian lebih luas di luar kasus Eropa. Contoh-contoh utama yang diakui dalam literatur:
- Amerika Utara (AS, Kanada): Pemukiman Inggris/Prancis, pengusiran dan pemusnahan populasi pribumi, penetapan undang-undang tanah, boarding schools (sekolah asrama) untuk asimilasi.
- Australia dan Selandia Baru: Pemberangusan suku Aborigin dan Māori, pengambilalihan tanah, serta kebijakan asimilasi.
- Afrika selatan dan Rhodesia (Zimbabwe): Pemukiman Eropa (Belanda/British/Dutch) yang membentuk struktur minoritas berkuasa (hingga apartheid di Afrika Selatan).
- Amerika Latin dan Karibia: Varian Iberia (Spanyol/Portugis) yang sering dimodelkan sebagai campuran antara kolonialisme pemukim dan eksploitasi—menggantikan dân asli pada skala besar.
- Lain-lain: kasus-kasus yang dianalisis dengan kerangka ini termasuk Algeria (bagian dari kolonisasi Prancis), Canary Islands, beberapa wilayah di Asia (contoh perdebatan: Xinjiang/Tibet dalam kajian kontemporer), serta kolonisasi Eropa di kepulauan Pasifik. (Daftar komparatif lengkap ada dalam literatur settler-colonial studies).6
Catatan penting: klasifikasi “settler” vs. “extraction colony” tidak selalu mutlak; beberapa kolonisasi bercampur karakter. Namun, di wilayah-wilayah yang akhirnya menjadi negara-negara yang didominasi keturunan pemukim (US, Canada, Australia, New Zealand), pola penggantian penduduk dan pembentukan negara-pemukim jelas terlihat.
Tentu saja pada masa penjajahan itu dunia masih tidak terhubung dengan alat komunikasi seperti saat ini. Pada awal 15 seseorang harus melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk menyampaikan berita yang dialami di benua seberang. Informasi harus dibawa langsung oleh pembawa informasi untuk bisa mencapai tujuan pada penerima pesan. Itu pun jika dalam perjalanan tidak ada halang rintang. Komunitas-komunitas, peradaban satu dengan lainnya tidak terhubung dengan baik. Semua wilayah di muka bumi terisolasi. Satu-satu cara untuk bis amengetahui apa yang terjadi di seberang lautan atau di benua lainnya adalah dengan melakukan perjalanan langsung. Mengirim para penjelajah untuk mengetahui apa yang ada di seberang sana dan apa yang terjadi. Maka ketika ada settler colonialism di wilayah seberang maka tidak ada orang atau pihak manapun yang mengetahui langsung apa yang terjadi.
Abad 20, Abad 21 sama sekali berbeda. Dunia telah berubah menjadi desa. Satu tempat dan tempat lainnya terhubung begitu dekat. Marshall McLuhan, seorang filsuf dan teoretikus komunikasi asal Kanada, dalam bukunya yang sangat berpengaruh berjudul The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962), menyebutnya sebagai “global village.”7 Dalam buku ini, McLuhan menjelaskan bagaimana teknologi komunikasi — terutama media elektronik seperti televisi (dan, dalam konteks modern, internet) — telah “menyusutkan” dunia, menjadikannya seperti sebuah desa global di mana setiap orang dapat mengetahui dan merespons peristiwa di bagian dunia lain hampir secara seketika. “The new electronic interdependence recreates the world in the image of a global village.” 8
Ia berargumen bahwa media elektronik menghapus jarak dan waktu, menghubungkan manusia secara langsung dalam ruang budaya yang sama — layaknya warga desa yang saling tahu kabar satu sama lain.
Maka ketika hampir lebih dari 100 tahun Israel sebagai settler colonialism menjajah Palestina dan gagal menaklukkan sepenuhnya tanah dan air, dan utamanya rakyat Palestina, maka makin sulit kini menguasainya. Kekejaman dan kebiadaban yang dilakukan seperti settler colonialism pendahulunya menghadapi perlawanan dimana-mana. Sebagian besar negara di bumi ini mengutuk dan membencinya. Warga dunia melawan dengan berbagai cara kekejian tanpa batas itu. Hanya segelintir negara-negara yang ada di ketiak zionisme yang mendukung.
Dengan tabiat yang disebutkan Wolfe itu maka sejatinya upaya apapun untuk berdamai menjadi sebuah utopia. Apalagi upaya-upaya gencatan senjata yang berkalli-kali sebelumnya selalu dilanggar.
Sekali Lagi Gencatan Senjata
Sejak 2007, Gaza telah menjadi panggung dari perjanjian yang selalu lahir dari darah, dan mati dalam kecurigaan. Di setiap putaran — 2008, 2012, 2014, 2021, 2024 — dunia mendengar nada yang sama: seruan untuk berhenti menembak, untuk memberi waktu kemanusiaan bernapas.9
Para mediator datang dan pergi — Mesir, Qatar, PBB — membawa peta kecil berisi janji: pembebasan tahanan, pertukaran sandera, rekonstruksi, penghentian serangan udara.
Namun di catatan sejarah, lebih banyak yang dilanggar daripada dijalankan. “Israel and Hamas agree to ceasefire,” tulis Reuters tahun 2014. Lima hari kemudian, langit kembali bergetar.
“Israel and Hamas agree to ceasefire,” tulis Guardian tahun 2021. Dua minggu kemudian, rumah-rumah di Rafah runtuh lagi. Sejarah di Gaza ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan debu dari bangunan yang roboh. Desmond Tutu pernah berkata, “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.”
Dan mungkin itulah yang membuat banyak warga Gaza tidak percaya pada kata “netral”. Karena di sini, netralitas sering berarti keheningan yang menutupi kejahatan.
Israel dan Hamas dilaporkan telah, sekali lagi, menyetujui rancangan awal gencatan senjata di Jalur Gaza — sebuah perjanjian yang, di atas kertas, tampak menjanjikan sebagai langkah menuju penghentian kekerasan dan penderitaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Perjanjian awal antara Israel dan Hamas untuk menghentikan pertempuran di Gaza terdengar, di permukaannya, seperti sebuah jeda kemanusiaan yang lama dinantikan. Namun, di balik teks diplomatik dan narasi “perdamaian,” tersimpan banyak lapisan persoalan yang mencerminkan kompleksitas konflik kolonial, politik domestik, dan kalkulasi strategis kedua belah pihak. Sebagaimana sejarah mencatat berulang kali menunjukkan, setiap gencatan senjata di Palestina jarang berarti akhir dari penderitaan. Lebih sering, ia hanyalah jeda singkat di antara dua babak kekerasan yang belum selesai.
Memang berbagai pihak menyambut gembira meski skeptis, termasuk kupasan yang dibuat oleh analis dari Instagram dengan ID: @criticalanalysisuk.
Isi pokok kesepakatan menurut draf awal yang beredar dalam laporan-laporan diplomatik (Reuters, Al Jazeera, The Guardian, 2025), tahap pertama perjanjian ini mencakup penghentian penuh operasi militer Israel di sebagian besar wilayah Gaza, disertai dengan penarikan pasukan hingga ke batas yang disebut sebagai “Red Line” — garis batas de facto yang masih membuat Israel menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Dalam bahasa diplomatik, ini disebut redeployment; dalam kenyataan, ini hanyalah reposisi kekuasaan kolonial.
Dalam setiap perjanjian, ada angka-angka dingin: Hamas berjanji akan membebaskan sejumlah sandera — sekitar 20 orang hidup dan 25 jenazah — sebagai imbalan atas pembebasan 2.000 tahanan politik Palestina dari berbagai penjara di wilayah pendudukannya. Di penjara-penjara Israel terdapat sekitar 11.000 warga Palestina. Di atas kertas, ini tampak seimbang. Tapi di bawahnya, ketimpangan moral dan politik terlalu dalam untuk dijembatani oleh angka.
Dan di balik angka, ada wajah-wajah — seorang anak yang menunggu ayahnya dari penjara Israel, atau seorang ibu yang berharap putranya masih hidup di bawah reruntuhan.
Pertukaran semacam ini sudah terjadi puluhan kali. Pada 2011, Gilad Shalit, prajurit Israel, dibebaskan setelah lima tahun ditahan. Sebagai gantinya, 1.027 warga Palestina dilepas dari penjara. Namun sebagian dari mereka ditangkap lagi dalam tahun yang sama.
Seorang mantan perunding Mesir pernah berkata dalam wawancara: “Every ceasefire is an illusion painted on smoke. It disappears the moment you try to touch it.”
Hamas melihat gencatan sebagai cara bertahan hidup; Israel melihatnya sebagai jeda untuk mempersiapkan operasi berikutnya. Dan dunia melihat — seperti penonton yang tak pernah tahu kapan pertunjukan ini akan berakhir.
Setelah fase ini diterapkan, akan ada jendela waktu 72 jam yang menjadi periode pertukaran tahanan dan sandera.
Tahap-tahap selanjutnya, yang disebut fase dua dan tiga, akan mengatur penarikan lebih lanjut pasukan Israel dan transisi ke pengawasan keamanan gabungan — di mana kekuatan keamanan Palestina dan pasukan penjaga internasional akan mulai ditempatkan di wilayah Gaza.
Dalam fase kedua dan ketiga dari perjanjian yang direncanakan, berbagai ketidakjelasan muncul: kapan pasukan Israel benar-benar ditarik, siapa yang akan mengontrol Gaza pasca-Hamas, dan bagaimana “keamanan” akan didefinisikan dalam situasi yang seluruh infrastrukturnya telah hancur. Jika perjanjian ini dimaksudkan sebagai langkah menuju perdamaian, maka perdamaian itu masih tampak sebagai bayangan di cakrawala — jauh, kabur, dan mungkin hanya ilusi.
Jurnalis dan analis politik Amira Hass pernah mengatakan: “Di Israel, damai selalu berarti tidak ada kekerasan terhadap orang Yahudi — bukan terhadap semua manusia.” Kutipan ini membuka pertanyaan mendasar: apakah perdamaian bisa lahir dari definisi yang eksklusif, dari kemanusiaan yang dipilah-pilah berdasarkan etnis?
Menurut analisis itu perjanjian baru ini dinilai penuh dengan kerapuhan dan keraguan meski sangat menggembirakan bagi rakyat Palestina yang mengalami penderitaan luar biasa karena genosida dan pembersihan etnik oleh settler colonialism Israel. Sejarah panjang perundingan damai di Timur Tengah menunjukkan bahwa setiap kata dalam perjanjian semacam ini tidak pernah berdiri di ruang hampa. Skeptisisme publik dan analis internasional tumbuh dari pengalaman masa lalu — ketika Israel berulang kali melanggar kesepakatan-kesepakatan gencatan senjata sebelumnya,10 baik melalui operasi militer lanjutan, blokade yang diperketat, atau pembunuhan tokoh-tokoh Hamas di tengah masa tenang.11
Tidak hanya bom yang membunuh di sini — tetapi juga peluru yang diarahkan pada harapan itu sendiri. Yitzhak Rabin, perdana menteri Israel yang menandatangani Oslo Accords, ditembak mati oleh warganya sendiri pada 1995. Ia baru saja bernyanyi bersama massa: “Shir LaShalom” — Lagu untuk Perdamaian. Ketika ia jatuh, kertas lirik itu terselip di sakunya, bernoda darah.
Sastrawan Palestina Mahmoud Darwish menulis setelah kematian Rabin: “We have learned that peace can be killed as easily as a man.”
Rabin bukan satu-satunya.
Sheikh Ahmed Yassin, pendiri spiritual Hamas, dibunuh oleh rudal Israel pada 2004 setelah doa subuh. Sebulan kemudian, penggantinya, Abdel Aziz al-Rantisi, tewas dalam serangan udara.
Dan pada 2010, Mahmoud al-Mabhouh, pejabat Hamas, ditemukan tewas di kamar hotel Dubai — dunia menuduh operasi rahasia Israel. Pembunuhan seperti itu sering dibenarkan sebagai “kontra-terorisme”, tapi bagi dunia Arab, itu adalah pesan dingin: bahkan meja perundingan pun tak aman dari rudal.
Seorang aktivis perdamaian Israel, Nurit Peled-Elhanan — yang kehilangan anaknya dalam serangan bom — pernah berkata: “Kita tidak butuh lebih banyak keamanan. Kita butuh lebih banyak keberanian untuk mengakui kemanusiaan orang lain.”
Banyak pengamat, seperti Noam Chomsky dan Rashid Khalidi, berpendapat bahwa gencatan senjata sering kali digunakan sebagai alat taktis oleh negara kuat untuk mengatur ulang strategi militernya, bukan sebagai tanda komitmen terhadap perdamaian sejati. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa Israel mungkin akan menggunakan kesepakatan ini sebagai jeda sementara, hanya untuk kemudian melanjutkan serangan setelah sandera-sandera mereka dibebaskan.
Tanda-tanda awal kerapuhan itu bahkan sudah tampak: laporan lapangan dari Gaza menunjukkan bahwa operasi militer Israel masih berlangsung di beberapa sektor utara, sementara Hamas menuduh pihak Israel memanipulasi beberapa detail teknis dari kesepakatan, termasuk lokasi dan jumlah tahanan yang dibebaskan. Kecurigaan terhadap keseriusan Israel tampak dalam tindakan-tindakan militer itu yang masih berlanjut bahkan setelah jam gencatan resmi diumumkan. Serangan artileri di Gaza Utara dan laporan mengenai pelanggaran jalur kemanusiaan memperlihatkan betapa rapuhnya komitmen tersebut. Dari pihak Hamas, tuduhan muncul bahwa Israel telah memanipulasi detail teknis perjanjian — termasuk urutan pembebasan dan kontrol wilayah — sebuah pola lama dalam negosiasi asimetris antara penjajah dan yang dijajah.
Banyak pengamat mengingatkan agar tak terlalu berharap. Israel memiliki sejarah panjang melanggar kesepakatan yang mereka sendiri tandatangani. Dari Oslo hingga berbagai “de-eskalasi” sebelumnya, setiap gencatan senjata selalu berakhir di tangan senjata yang sama. Profesor Rashid Khalidi, dalam bukunya The Hundred Years’ War on Palestine (2020), menulis bahwa “setiap perjanjian damai yang lahir dari ketidakseimbangan kekuasaan bukanlah perjanjian, melainkan jeda dalam kolonisasi.” Pandangan ini tampaknya kembali menemukan relevansinya hari ini.
Lebih dalam lagi, persoalan utama terletak pada dua hal: pertama, siapa yang mengendalikan waktu dan makna “damai”; kedua, siapa yang menulis narasi sejarah dari setiap kesepakatan. Dalam banyak hal, gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan bab baru dari proyek yang lebih panjang — proyek settler colonialism yang sejak 1948 berusaha menyingkirkan satu bangsa untuk menegakkan “keamanan” bagi bangsa lain.
Edward Said, dalam The Question of Palestine (1979), pernah menulis dengan getir: “Setiap kali mereka mengatakan ‘damai’, yang mereka maksud adalah ‘penyerahan’.” Kalimat ini tetap menggema dalam konteks hari ini — seolah waktu tidak berjalan, hanya penderitaan yang berganti wajah.
Tantangan perjanjian ini akan dihadapi di fase dua dan tiga. Fase-fase lanjutan perjanjian menjadi sumber kebingungan dan kontroversi tersendiri. Tidak ada kejelasan penuh mengenai garis waktu penarikan pasukan Israel, proses perlucutan senjata Hamas, maupun mekanisme pemerintahan transisi di Gaza.
Dalam setiap gencatan, ada ritme yang sama: Pengumuman dengan harapan besar. Warga bergembira penuh harapan baru seperti menyambut sebuah pesta. Diplomat tersenyum, foto berjabat tangan beredar, dan dunia menulis tajuk “Peace at last.” Kali ini Trump berharap dengan rasa optimis: Mestinya saya mendapatkan Nobel Perdamaian. Bahkan The Economist edisi October 9th 2025 menulis pada sampul depan dengan ilustrasi pintu terowongan dari dalam suatu ruang gelap serupa peta Palestina: A New Beginning. Jeda 24, 72 jam atau berapapun yang penuh waspada. Konvoi bantuan bergerak. Anak-anak keluar untuk mencari air. Di udara, drone masih mengintai. Insiden kecil yang meledak besar. Sebuah roket ditembakkan — mungkin oleh kelompok kecil. Sebuah serangan udara membalas. Korban muncul. Gencatan pun runtuh.
Sejarawan menyebutnya cycle of asymmetry. Hamas kehilangan lusinan prajurit; Israel kehilangan legitimasi moral; rakyat kehilangan segalanya. Israel, sebagai negara dengan militer konvensional, menempatkan prioritas keamanan nasional, penghancuran kapabilitas militer lawan (atau setidaknya mengubahnya secara signifikan), dan kadang-kadang perubahan rezim atau penundaan ancaman jangka panjang. Hamas, sebagai gerakan bersenjata dan kekuatan politik di Gaza, menuntut pengakhiran blokade, pemulangan tahanan, dan pengakuan politik — tuntutan yang seringkali tidak linier dengan tujuan Israel. Ketidaksesuaian tujuan ini membuat perjanjian sulit mendasar.
Tidak adanya jaminan penegakan yang kredibel adalah faktor rapuhnya kesepakatan. Perjanjian damai yang berhasil di banyak konflik modern memerlukan pihak ketiga dengan kapasitas dan kemauan untuk menjamin pelaksanaan (mis. pasukan penjaga internasional yang kuat, sanksi otomatis jika dilanggar). Di Gaza, gagasan jaminan semacam itu sering tidak disepakati (siapa yang menjadi pengawas? PBB? kekuatan regional?), atau jika ada, dianggap lemah. Barbara Walter dan literatur tentang “spoilers” menekankan perlunya jaminan komitmen untuk menahan aktor-aktor yang ingin “mencampuri” proses.12
Sementara itu praktik militer yang terus berjalan (targeted strikes) selama jeda juga menyulitkan untuk penerapan kesepakatan secara konsisten. Salah satu modus pelanggaran yang sering dilaporkan adalah serangan terarah atau operasi khusus yang dilakukan dalam masa jeda — secara Israel sering dibenarkan sebagai “melumpuhkan ancaman” (strike on specific commander, cell, or weapons cache). Walau targetnya militer, efeknya adalah mengikis kepercayaan dan memicu balasan roket yang merusak jeda. LSM HAM mencatat bahwa selama jeda, tindakan-tindakan seperti pembunuhan terarah, penutupan lintasan bantuan, atau penahanan massal menjadi alat tekanan. 13
Adanya spoilers — kelompok atau individu yang ingin merusak perdamaian. Konsep “spoilers” (Stedman, Walter, dan peneliti lain) relevan: kelompok atau figur yang merasa terancam oleh sebuah perjanjian (karena kehilangan pengaruh, keamanan, atau sumber ekonomi) bisa melakukan tindakan untuk menggagalkan proses. Di Israel, elemen politik domestik (sayap kanan) dan organisasi militan di Gaza dapat bertindak sebagai spoilers. Sasaran spoiler dapat pula termasuk negosiator sendiri atau tokoh moderat yang menjadi penopang perjanjian.14
Kesenjangan hak politik dan ekonomi. Gencatan yang tidak diikuti langkah-langkah ekonomi-politik (akhir blokade, rekonstruksi masif, pembukaan jalur politik) tidak membangun insentif jangka panjang bagi perdamaian. Tanpa perspektif perbaikan kehidupan, jalan radikal kembali menarik dukungan. Laporan-laporan internasional (Human Rights Watch, OHCHR) menegaskan bahwa blokade, pembatasan bahan pokok, dan penghancuran infrastruktur menciptakan tekanan struktural untuk kekerasan berulang.15
Arundhati Roy pernah menulis, “The trouble is that once you see it, you can’t unsee it. And once you’ve seen it, keeping quiet, saying nothing, becomes as political an act as speaking out.” Maka Gaza berbicara — dengan tubuhnya sendiri, dengan luka yang tak sempat sembuh.
Apakah Hamas akan tetap memegang kendali administratif di sebagian wilayah? Apakah akan ada peran PNA (Palestinian National Authority)? Ataukah Gaza akan ditempatkan di bawah protektorat internasional sebagaimana sempat diusulkan oleh beberapa negara Eropa dan PBB? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung tanpa jawaban pasti. Dalam banyak kasus di masa lalu — dari Bosnia hingga Sudan Selatan — perjanjian yang tidak jelas mengenai masa depan kekuasaan lokal justru menjadi pemicu kekerasan baru, bukan penyelesaiannya. Para analis dari International Crisis Group dan Carnegie Middle East Center memperingatkan bahwa tanpa jaminan politik yang kredibel, gencatan senjata di Gaza hanya akan menjadi “jeda dalam tragedi,” bukan transformasi menuju perdamaian.
Gencatan senjata yang disponsori oleh Amerika Serikat yang nafsu berperang tak pernah selesai ini, juga merupakan cermin dari struktur ketimpangan. Lebih dalam dari sekadar urusan militer dan diplomatik, perjanjian ini kembali menyoroti struktur kekuasaan yang timpang antara penjajah dan yang dijajah. Dalam terminologi teori politik kontemporer, seperti dijelaskan oleh Ilan Pappé dan Patrick Wolfe, konflik Israel–Palestina tidak bisa dilepaskan dari konteks “settler colonialism” — yaitu sistem kolonial pemukim di mana pendatang (dalam hal ini Israel sebagai proyek kolonial Barat) mendirikan negara di atas tanah penduduk asli dengan menghapus eksistensi mereka secara politik dan fisik.
Dalam struktur semacam itu, setiap “gencatan senjata” bukan berarti berakhirnya kekerasan, tetapi hanya transformasi bentuk kekerasan: dari bom dan peluru menjadi blokade, kelaparan, dan kontrol administratif yang membatasi kehidupan manusia sehari-hari.
Gencatan Senjata, Cermin Dunia dan Ilusi Perdamaian
Gencatan senjata Gaza tahun ini juga bukan hanya persoalan regional. Ia adalah cermin dunia modern — dunia yang cepat mengutuk kekerasan, tetapi lambat dalam menantang akar kolonialnya. Dunia yang memuja “hak asasi manusia” tetapi terus memasok senjata bagi penjajahnya. Seperti ditulis oleh Achille Mbembe dalam Necropolitics (2019): “Kolonialisme tidak pernah mati; ia hanya berubah bentuk — dari eksploitasi lahan menjadi pengelolaan kematian.”
Dengan demikian, perjanjian Israel–Hamas bukan hanya kesepakatan politik, melainkan juga dokumen etika zaman kita: sejauh mana dunia bersedia menerima ketidakadilan yang disamarkan sebagai diplomasi.
Ketika suara senjata menghilang, yang tersisa bukanlah keheningan, melainkan desisan generator dan tangisan yang tertahan. Rumah-rumah tidak dibangun kembali secepat trauma yang tumbuh.
“Peace is not the absence of war,” kata Dalai Lama. “Peace is the manifestation of human compassion.”
Albert Camus pernah menulis, “In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.” — sebuah refleksi tentang harapan dalam reruntuhan (Camus, Return to Tipasa, 1954). Namun di Gaza, bahkan hati pun belajar bersembunyi.
Namun di Gaza, “damai” sering berarti izin untuk mengubur mayat tanpa dibom. Sebuah keheningan yang disalahartikan sebagai ketenangan. Seorang dokter Gaza berkata dalam laporan PBB: “Kami memerlukan lebih dari sekadar jeda untuk bernafas. Kami memerlukan alasan untuk percaya bahwa napas ini akan ada besok.”
Desmond Tutu memperingatkan dunia: “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.” (No Future Without Forgiveness, 1999).
Dan di Gaza, netralitas justru berarti keheningan yang menutupi kekejaman.
Setiap kali gencatan diumumkan, dunia bersorak seolah bab terakhir telah ditulis. Namun mereka jarang membaca halaman berikutnya: blokade tetap, kamp pengungsi membesar, air bersih berkurang, dan anak-anak tumbuh dengan bahasa baru — bahasa ledakan.
Nelson Mandela pernah memperingatkan dunia: “We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.”
Tapi di ruang konferensi, kata “Palestine” sering bergema seperti bayangan — disebut, tapi tak dihadirkan.
Perjanjian gencatan senjata terbaru ini — seperti banyak yang mendahuluinya — membuka ruang harapan, namun juga menuntut kewaspadaan moral dan politik. Sejarah mengajarkan bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari tekanan militer atau diplomasi yang timpang, melainkan dari pengakuan terhadap kemanusiaan dan hak politik rakyat yang dijajah.
Selama struktur kolonial, blokade, dan apartheid tetap menjadi fondasi hubungan Israel–Palestina, maka setiap gencatan senjata hanyalah interupsi sementara dalam siklus panjang penindasan.
Seperti yang dikatakan Edward Said dalam The Question of Palestine (1979): “Perdamaian tanpa keadilan bukanlah perdamaian, melainkan hanya bentuk lain dari penaklukan.” Mungkin benar kata penyair Mahmoud Darwish: “We suffer from an incurable disease called hope.”
Harapan itulah yang membuat seorang anak menggambar bendera di reruntuhan tembok,
yang membuat seorang ayah mengangkat bayi di tengah puing dan berkata: “Kau akan hidup.”
Gencatan boleh rapuh, perjanjian boleh gagal, dan dunia boleh menutup mata. Selama masih ada satu manusia yang menolak membalas dengan kebencian, perdamaian belum mati — ia hanya bersembunyi, menunggu kita menemukannya lagi.
Penutup: Jeda yang Membuka Luka
Kini, dunia menunggu: apakah fase pertama akan dijalankan sebagaimana mestinya, atau apakah ini hanya satu lagi “gencatan senjata yang gagal”? Sementara itu, di antara reruntuhan Gaza, anak-anak bermain di bawah bayang-bayang drone. Mereka belum tentu tahu apa itu ceasefire — tetapi mereka tahu kapan suara bom berhenti, dan kapan ia kembali datang.
Mungkin, seperti kata penyair Mahmoud Darwish: “Di tanah ini, ada sesuatu yang layak untuk hidup.” Dan dunia tampaknya masih berdebat, apakah hidup itu hanya milik yang berkuasa.
Kita tidak tahu kapan Gaza akan benar-benar diam. Namun jika suatu hari ada kesepakatan yang tidak dilanggar — bukan karena ketakutan, tapi karena pengertian — mungkin saat itu dunia akan belajar apa artinya gencatan senjata yang sejati.
Seperti kata Martin Luther King Jr.: “Peace is not merely a distant goal that we seek, but a means by which we arrive at that goal.”
Pada akhirnya, perdamaian bukanlah perjanjian — melainkan keputusan manusia untuk tidak lagi saling membunuh atas nama masa lalu.
Cirebon, 11 Oktober 2025
Daftar Pustaka
- Al Jazeera English. (2025). Ceasefire deal explained: What we know so far.
- A Brief History of Israel–Hamas Ceasefire Agreements. (n.d.). Israel Policy Forum [PDF chronology]. Israel Policy Forum.
- Chomsky, N. (2010). Gaza in crisis: Reflections on Israel’s war against the Palestinians. Haymarket Books.
- International Crisis Group. (2024). Israel–Palestine: Managing ceasefire fragility (Report No. 247).
- Khalidi, R. (2020). The hundred years’ war on Palestine. Metropolitan Books.
- Laporan-laporan kronologis Pemerintah Israel (mis. catatan operasi Protective Edge dan pernyataan resmi terkait pelanggaran gencatan). (n.d.). Gov.il.
- Pappé, I. (2006). The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld Publications.
- Said, E. W. (1979). The question of Palestine. Vintage Books.
- The Guardian. (2025, April). Israel–Hamas ceasefire: Key terms and challenges ahead.
- “Assassination of Yitzhak Rabin.” (n.d.). Encyclopaedia Britannica / Time / The Guardian [Historical summary and analysis].
- UN. (1988). Letter and reports regarding the assassination of Khalil al-Wazir (Abu Jihad). United Nations Archives.
- Wolfe, P. (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of Genocide Research, 8(4).
- Liputan berita: Al Jazeera, Reuters, Associated Press, Anadolu Agency, Middle East Monitor (untuk kejadian dan tuduhan percobaan pembunuhan terkini). (n.d.). Al Jazeera / Anadolu Ajansı.
1 “In the ruins, a child writes her name in the dust, as if to prove she once existed.”
— Mahmoud Darwish, A State of Siege (2002)
2 Kalimat “In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer” memang dikaitkan dengan Albert Camus, dan secara umum sumber yang paling valid adalah esei “Return to Tipasa” yang termuat dalam kumpulan L’été (“Summer”), diterbitkan pertama kali tahun 1954. Philosophy+3blackwellpublishing.com+3Philosophy+3
Berikut detail dan konteksnya: Esei Return to Tipasa adalah salah satu esei puitis dalam buku L’été (“Summer”) oleh Albert Camus yang diterbitkan oleh Gallimard (1954). ILAB – EN+1
Camus menulis tentang kunjungannya kembali ke Tipasa — sebuah kota kuno di pantai Aljazair yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Dalam esei ini, ia membandingkan antara musim dingin (secara literal dan metaforis: kondisi kehidupan / dunia yang dingin, keras, penuh penderitaan) dengan kekuatan batin yang “tak terkalahkan” — musim panas yang tetap ada di dalam dirinya sebagai simbol harapan dan ketahanan. Philosophy+2blackwellpublishing.com+2
Versi aslinya dalam bahasa Prancis menggunakan ungkapan “Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible.” — yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai kutipan di atas (“In the depth/midst of winter … invincible summer”). blackwellpublishing.com+2Philosophy+2
3 Max Ajl, “Logics of Elimination and Settler Colonialism: Decolonization or National Liberation?”, Settler Colonial Studies, 13(2–3), 259–283 (2023). https://doi.org/10.1080/19436149.2023.2191401; lihat juga tulisan ini: Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of Genocide Research, 8(4), 387–409 (2006). https://doi.org/10.1080/14623520601056240
4 Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of Genocide Research, 8(4), 387–409 (December 2006). https://doi.org/10.1080/14623520601056240 Artikel ini bisa diperoleh dari tautan ini: https://apeoplesliberationhistory.org/wp-content/uploads/2021/04/Wolfe_Settler-Colonialism.pdf?utm_
5 Max Ajl, “Logics of Elimination and Settler Colonialism: Decolonization or National Liberation?”, Settler Colonial Studies, 13(2–3), 259–283 (2023).
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Settler_colonialism?utm_
7 McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press. Baca juga McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill.
Di sini ia memperluas gagasannya bahwa media bukan sekadar alat komunikasi, tetapi “perpanjangan dari pancaindra manusia,” dan globalisasi media membuat seluruh umat manusia hidup dalam kesadaran bersama — a single global village.
8 Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy (1962).
9 Sumber: B’Tselem, Gaza Conflicts Chronology 2008–2024; Al Jazeera, “Timeline of Gaza-Israel Ceasefires,” 2024.
10 Gambaran umum historis: seberapa sering gencatan senjata terjadi? Sejak pembentukan Israel (1948) dan terutama setelah pemisahan kekuasaan antara Gaza dan Tepi Barat (pasca-2007), konflik bersenjata antara Israel dan berbagai aktor Palestina (PLO/Fatah, Hamas, Jihad Islam, kelompok bersenjata lain) telah berganti-ganti antara fase intensitas tinggi dan jeda relatif. Gencatan senjata bersifat sangat sering: selama periode 2007–2024 saja terdapat puluhan jeda (ceasefires, lulls, truces, humanitarian pauses), biasanya ditengahi oleh pihak ketiga (Mesir, Qatar, PBB, kadang-kadang Amerika Serikat). Ringkasan singkat per putaran besar:
- 2008–2009 (Operasi Cast Lead / Perang Gaza pertama) — diakhiri gencatan yang dimediasi Mesir/Jordan; pola: serangan Israel → gempuran rudal dari Gaza → gencatan. https://israelpolicyforum.org/wp-content/uploads/2024/02/A-Brief-History-of-Israel-Hamas-Ceasefire-Agreements.pdf?utm_
- 2012 (Operasi Pillar of Defence / short war) — gencatan diperantarai Mesir/Qatar-AS; kesepakatan mencakup penghentian serangan dan pembukaan sebagian jalur kemanusiaan.
- 2014 (Perang 50 hari / Operation Protective Edge) — ditengahi oleh Mesir; gencatan berulang karena putaran negosiasi gagal menyelesaikan masalah struktural (blokade, pemukiman, status Gaza).
- 2018–2021 (berbagai eskalasi dan lulls) — termasuk protes Great March of Return (2018–2019) dan mobilisasi 2021 (Mei 2021) yang diakhiri dengan gencatan yang dimediasi Mesir/Qatar-AS. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaza–Israel_conflict?utm_
- 2023–2025 — beberapa gencatan pendek/humanitarian pauses tercatat; draf-draf perjanjian awal seperti yang Anda tanyakan adalah bagian dari rangka negosiasi besar yang melibatkan tawar-menawar penukaran sandera vs tahanan.
Ringkasnya: gencatan senjata adalah praktik berulang — tetapi hampir semua bersifat sementara dan tidak mengatasi penyebab struktural konflik (pendudukan, blokade, status pengungsi, pemukiman). Sumber ringkasan dan kronologi tersedia di analisis kebijakan (mis. Israel Policy Forum) dan laporan think-tank/organisasi internasional.
11 Kasus-kasus pembunuhan/percobaan pembunuhan terkait proses negosiasi (yang terdokumentasi)
Ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah konflik Israel–Palestina di mana tokoh-tokoh kunci dibunuh atau menjadi target serangan — beberapa berkaitan langsung dengan proses perdamaian/negosiasi, beberapa lagi terkait perebutan pengaruh politik. Saya ringkaskan kasus-kasus paling relevan yang kredibel dan terdokumentasi:
A. Pembunuhan Yitzhak Rabin (1995) — dampak langsung terhadap proses Oslo
- Kronologi / fakta: Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, yang menandatangani Perjanjian Oslo (1993) dan memimpin proses perdamaian dengan PLO, ditembak dan dibunuh pada 4 November 1995 oleh Yigal Amir, seorang ekstremis sayap kanan Israel yang menentang perjanjian. Pembunuhan ini secara luas dianggap memukul mundur momentum perdamaian. https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Yitzhak_Rabin?utm_
B. Khalil al-Wazir — “Abu Jihad” (1988) — operasi rahasia yang dituduh Israel
- Kronologi / fakta: Khalil al-Wazir (Abu Jihad), pemimpin senior PLO dan arsitek sejumlah operasi melawan Israel, dibunuh di Tunis (April 1988) oleh tim operasi yang secara luas dilaporkan sebagai agen Israel (operasi rahasia). Abu Jihad bukan “negosiator formal Oslo” (dia tewas sebelum Oslo), tetapi adalah figur PLO sentral; pembunuhannya mengguncang elit PLO. DK PBB/negara lain mengecam aksi tersebut dalam pernyataan resmi. Pengungkapan dan dokumentasi tersedia dalam laporan media dan arsip PBB. https://main.un.org/securitycouncil/sites/default/files/en/sc/repertoire/85-88/Chapter%208/85-88_08-38-Letter%20dated%2019%20April%201988%20from%20the%20Permanent%20Representative%20of%20Tunisia.pdf?utm_
C. Salah Khalaf — “Abu Iyad” (1991) — pembunuhan di Tunis
- Kronologi / fakta: Salah Khalaf (Abu Iyad), salah satu pendiri Fatah dan tokoh penting PLO, dibunuh pada 14 Juli 1991 di Tunis oleh agen dari organisasi Abu Nidal (ekstremis Palestina). Serangan itu dilakukan di lingkungan diaspora Palestina (bukan di medan perundingan Oslo secara langsung). Ada tuduhan politik dan keterlibatan perantara, tetapi tanggung jawab terbukti diarahkan ke kelompok Abu Nidal. https://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_al-Wazir?utm_
D. Pembunuhan/penculikan tokoh Hamas dan upaya serangan terhadap negosiator (kasus kontemporer)
- Kronologi / contoh: Dalam beberapa putaran konflik, pemimpin Hamas dan komandan militer menjadi sasaran operasi udara Israel, termasuk tokoh-tokoh yang sedang berada dalam jalur negosiasi atau berada di negara ketiga tempat perundingan berlangsung. Media melaporkan — dan pihak Hamas mengklaim — beberapa kasus percobaan pembunuhan terhadap negosiator yang sedang melakukan pembicaraan (mis. laporan percobaan serangan di Doha terhadap Khalil al-Hayya baru-baru ini; Israel menolak/menjaga kerahasiaan operasi). Kasus-kasus seperti ini menjadi sumber ketegangan besar dalam proses mediasi. Laporan berita AA / Middle East Monitor / The Times memberi dokumentasi awal terkait percobaan serangan/ancaman ini. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/hamas-negotiator-appears-in-public-after-failed-israeli-assassination-attempt-in-doha/3707967?utm_
12 https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/5333789.pdf?utm_
13 https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises?utm_
14 https://nap.nationalacademies.org/read/9897/chapter/6
15 https://www.hrw.org/report/2024/11/14/hopeless-starving-and-besieged/israels-forced-displacement-palestinians-gaza?utm_