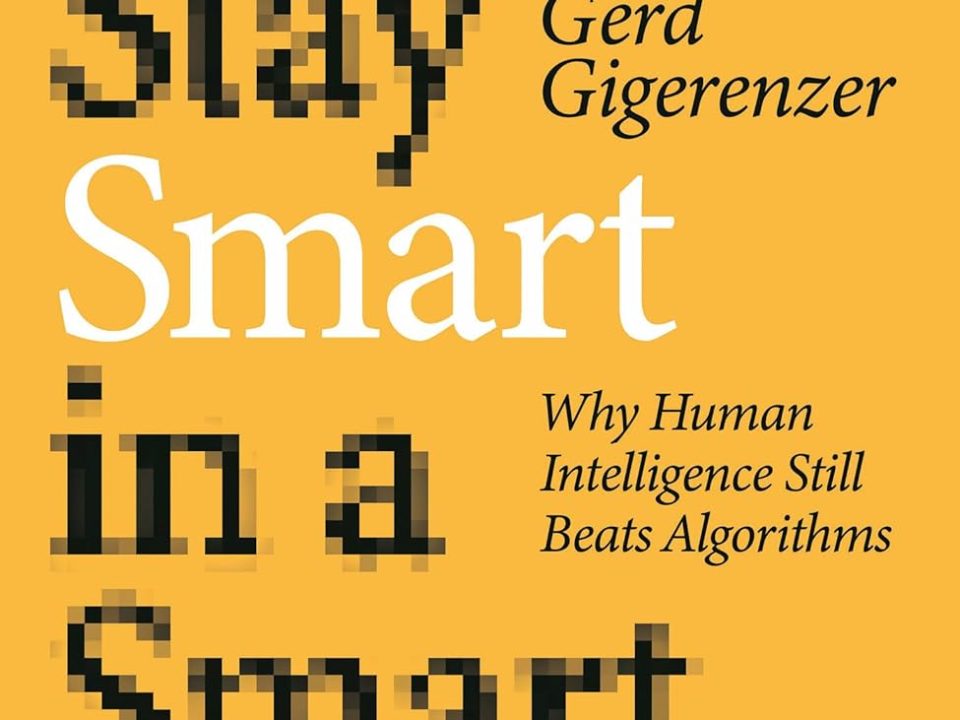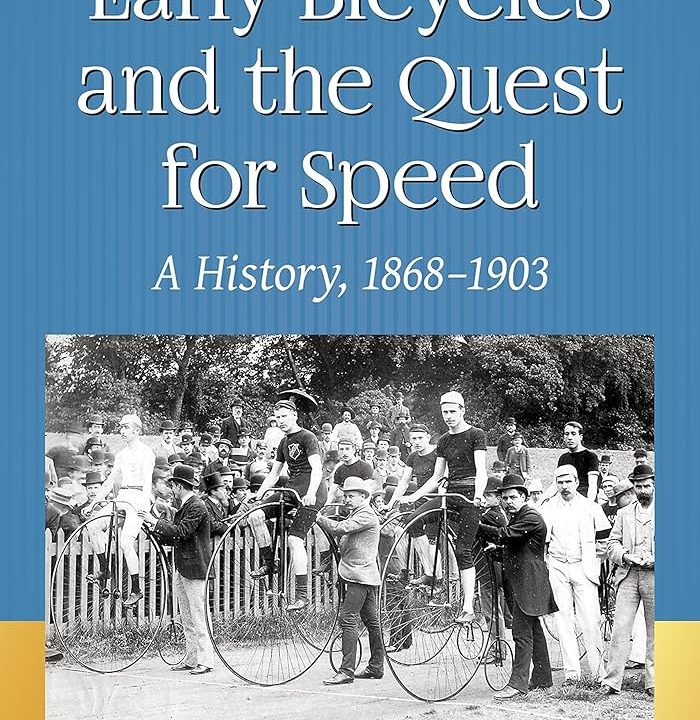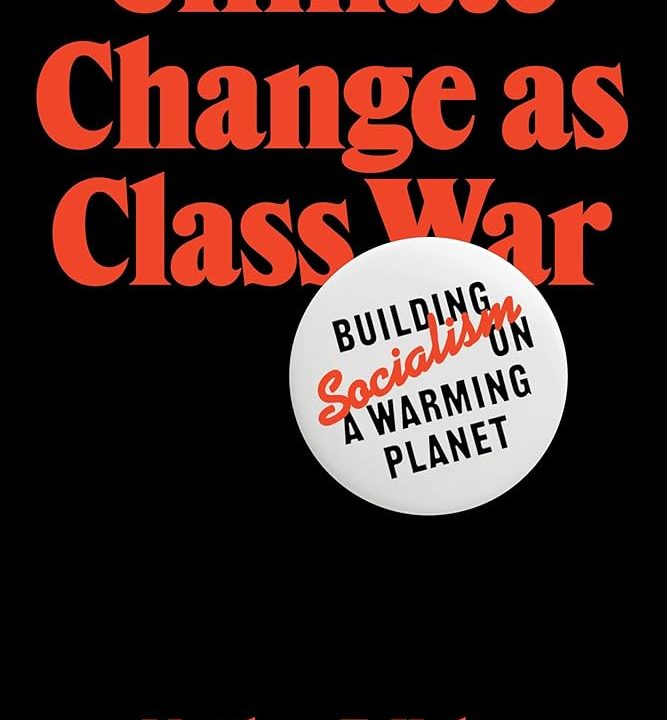Rubarubu #08 i
Pulau-pulau Antroposen: Menyibak Dunia yang Saling Terjalin
Pulau yang Menolak Tenggelam
Bayangkan pagi hari di Funafuti, ibu kota Tuvalu. Lautan biru yang indah kini naik setengah meter lebih tinggi dibanding satu generasi sebelumnya. Di bawah sinar matahari tropis, seorang perempuan tua menatap laut dan berkata, “Kami tidak akan meninggalkan pulau ini. Kami bagian dari laut, dan laut bagian dari kami.”
Pulau-pulau kecil di Pasifik—Tuvalu, Kiribati, atau Marshall Islands—setiap tahun disapu gelombang lebih tinggi dari sebelumnya. Bagi dunia global, mereka adalah “korban” krisis iklim; bagi warganya sendiri, mereka adalah penjaga sejarah dan roh bumi. Dari kisah inilah Jonathan Pugh dan David Chandler memulai eksplorasi dalam Anthropocene Islands: Entangled Worlds. Buku ini bukan sekadar studi geografi, tetapi refleksi filosofis tentang bagaimana “pulau” bukan hanya tempat di peta, melainkan metafora tentang keterhubungan dan ketahanan di era Anthropocene—zaman di mana aktivitas manusia telah mengubah bumi secara geologis. Melalui narasi ilmiah, etnografis, dan teori poskolonial, buku ini mengajak pembaca membongkar pandangan lama bahwa pulau adalah entitas terpisah dan rentan.
Kisah semacam ini—yang terdengar sederhana, bahkan lirih—menjadi pintu masuk bagi Jonathan Pugh dan David Chandler untuk menantang cara dunia memahami Anthropocene, zaman ketika manusia dianggap sebagai kekuatan geologis utama. Buku ini menolak definisi umum tentang Anthropocene sebagai “era manusia” yang menguasai bumi. Menurut Pugh & Chandler, Anthropocene justru adalah era keterjeratan (the entangled era): manusia tidak lagi bisa berpikir terpisah dari laut, udara, batu, atau makhluk lain.
“The Anthropocene is not about human dominance, but about human dependence.”
Di sinilah island thinking menjadi metafora: pulau bukan entitas terisolasi, melainkan simpul dari jaring kehidupan global.
Dalam pembuka buku Anthropocene Islands: Entangled Worlds, Pugh dan Chandler menunjuk-kan bahwa pulau bukan sekadar tempat di peta, melainkan metafora tentang keberadaan manusia di dunia yang rapuh dan terhubung. Mereka menulis bahwa sejak masa kolonial, pulau-pulau selalu diposisikan sebagai “tepi dunia”, tempat eksperimen biologi, sosial, dan politik. Seperti laboratorium hidup, pulau dipakai oleh ilmuwan dan kolonialis Barat untuk mengamati “keanehan” atau “kemurnian” alam dan budaya — seolah-olah dunia luar tidak memengaruhi mereka.
Namun, bagi masyarakat kepulauan, cara berpikir seperti ini keliru sejak awal. Dalam kosmologi Pasifik dan Karibia, laut bukanlah batas; laut adalah ruang relasi. “Kami tidak dikelilingi oleh laut,” kata salah satu tokoh dari Kiribati yang dikutip Pugh, “kami dikelilingi oleh kehidupan.” Dengan memulai dari kisah nyata seperti ini, para penulis mengguncang fondasi epistemologi modern: bahwa pengetahuan tidak lahir dari keterpisahan, tetapi dari keterikatan (entanglement).
Lebih jauh, Pugh dan Chandler mengajak pembaca melihat bahwa krisis iklim bukan hanya bencana fisik, tetapi juga krisis makna dan cara mengetahui. Jika selama ini dunia memandang pulau sebagai simbol keterisolasian dan kerentanan, maka buku ini menegaskan kebalikannya: pulau adalah simbol keterhubungan dan ketahanan. Seperti mereka tulis, “Islands do not stand alone; they make worlds with others.”
Kalimat ini menjadi jantung pemikiran mereka — sebuah undangan untuk menafsir ulang seluruh cara kita memahami dunia, dari pusat ke pinggiran, dari pemisahan ke pertautan.
Pugh dan Chandler meminjam gagasan Édouard Glissant tentang Relation — bahwa setiap entitas di dunia “berpikir melalui yang lain”, bukan terhadap yang lain. Dalam pengertian ini, pulau bukanlah metafora keterbatasan, tetapi metafora keberlanjutan kosmik, di mana setiap batu karang, arus laut, burung laut, dan manusia berpartisipasi dalam “politik kehidupan bersama”.
Jika kita tarik ke konteks Indonesia, narasi ini terasa sangat dekat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mentawai hingga Maluku, laut selalu menjadi penghubung, bukan pemisah. Masyarakat adat pesisir hidup dengan ritme pasang surut, bukan melawan laut, tetapi menyesuaikan diri dengan siklusnya. Dengan cara ini, Pugh dan Chandler menegaskan bahwa masa depan dunia mungkin terletak di pulau-pulau — bukan karena mereka kecil dan terancam, tetapi karena mereka mengajarkan cara berpikir baru: cara bertahan hidup di dunia yang terjalin rapat antara manusia dan alam.
Pulau-pulau Antroposen
Judul “Anthropocene Islands: Entangled Worlds” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa berarti: “Pulau-pulau Antroposen: Dunia yang Terjalin.” Istilah Antroposen berasal dari kata Yunani anthropos (manusia) dan kainos (baru). Ia menunjuk pada era geologis baru di mana aktivitas manusia telah menjadi kekuatan dominan yang membentuk bumi — mengubah iklim, ekosistem, dan bahkan struktur geologi planet ini. Jadi, “Antroposen” bisa dimaknai sebagai zaman manusia sebagai faktor geologis.
Pugh dan Chandler menyebut Islands (Pulau-pulau/Kepulauan) tentu bukan hanya pulau secara geografis, tetapi juga metafora cara berpikir. Mereka menggunakan pulau sebagai simbol keterhubungan dan keterbatasan, bukan keterpisahan. Pulau mewakili dunia kecil yang menggambarkan bagaimana manusia dan alam saling terkait — seperti mikrokosmos bumi itu sendiri. “Dunia yang terjalin” berarti dunia di mana segala sesuatu — manusia, laut, hewan, iklim, dan teknologi — saling berhubungan dan tidak dapat dipahami secara terpisah.
“Anthropocene Islands: Entangled Worlds” menggambarkan: Sebuah cara berpikir baru di era Antroposen, di mana pulau-pulau (dan dunia secara keseluruhan) dipahami sebagai ruang kehidupan yang saling terkait, saling memengaruhi, dan tidak bisa dipisahkan antara manusia dan alam.
Buku ini pada dasarnya mengajak kita untuk berpikir seperti kepulauan — bukan sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai jaring kehidupan yang saling bergantung. Bagian awal buku menelusuri bagaimana dunia Barat selama berabad-abad membentuk imajinasi tentang “islands” sebagai ruang eksperimen kolonial dan sains modern. Penulis membongkar imajinasi pulau dalam wacana barat.
Dalam wacana kolonial dan modernitas, pulau sering digambarkan sebagai laboratorium mini untuk memahami dunia—terisolasi, terkendali, dan dapat “diteliti”. Pugh dan Chandler menyebut ini sebagai warisan imperial epistemology yang menyingkirkan cara hidup masyarakat pulau sendiri. Mereka menulis, “The island has been the laboratory of modernity, the site where the world’s separations are staged.” Pandangan ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga membentuk cara berpikir tentang ruang dan hubungan manusia dengan alam. Dalam konteks kini, narasi yang sama muncul dalam wacana perubahan iklim—di mana pulau-pulau kecil kembali dijadikan simbol penderitaan global, bukan agen pengetahuan alternatif.
Epistemologi ini menolak cara berpikir biner: pusat vs pinggiran, manusia vs alam, global vs lokal. Pulau-pulau dipahami bukan sebagai “miniatur dunia” yang tertutup, tetapi sebagai ruang belajar relasional.
Ciri-ciri utama “Island Epistemology“
| Aspek | Karakteristik “Mainland Thinking” | Karakteristik “Island Thinking” |
| Ontologi | Dunia dipisah ke dalam kategori (alam/sosial) | Dunia sebagai jaringan keterhubungan |
| Pengetahuan | Objektif, dikumpulkan dari luar | Partisipatif, lahir dari dalam relasi |
| Etika | Manusia sebagai penguasa | Manusia sebagai bagian dari ekosistem |
| Politik | Pusat menentukan pinggiran | Tiap simpul punya otonomi dan suara |
“To think with islands is to think with connection, not isolation.” (Pugh & Chandler, 2021)
Buku ini mengkritik warisan kolonial di mana pulau sering dijadikan laboratorium atau ruang eksperimen. Misalnya, dalam sejarah Eropa, kepulauan Pasifik dijadikan tempat penelitian ilmiah dan uji coba senjata nuklir — representasi “jarak” dan “keterpisahan” yang dipaksakan.
Namun kini, Pugh & Chandler membalik narasi itu: pulau bukan “objek”, tapi “subjek pengetahuan.”
Mereka menyebutnya decolonizing the island — menjadikan pulau bukan lagi simbol keterbatasan, melainkan ruang epistemik baru bagi masa depan planet.
Dari Isolasi ke Entanglement: Melihat Dunia Secara Terhubung
Konsep sentral buku ini adalah entanglement—keterikatan atau saling keterhubungan antara manusia, non-manusia, laut, dan teknologi. Dalam perspektif ini, pulau bukanlah entitas terpisah di lautan, tetapi simpul dalam jaringan kehidupan global. Pugh dan Chandler menolak dikotomi “pulau kecil vs dunia besar,” karena keduanya saling menciptakan. Mereka menulis, “Islands do not stand alone; they make worlds with others.” Pendekatan ini sejalan dengan teori posthuman dan ekologi relasional dari Donna Haraway dan Bruno Latour, yang menekankan bahwa manusia bukan pusat kehidupan, melainkan bagian dari jejaring eksistensi planet.
Keterhubungan ini relevan dengan realitas Indonesia—negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau, di mana laut bukan sekadar pemisah, tetapi penghubung. Konsep “entangled worlds” membuka cara berpikir baru tentang kebijakan maritim, migrasi, dan lingkungan di Nusantara.
Indonesia — negara kepulauan terbesar di dunia — adalah contoh hidup dari apa yang dimaksud Pugh & Chandler. Krisis ekologi di Nusantara (abrasi, deforestasi mangrove, overfishing) memperlihatkan bagaimana politik pembangunan daratan gagal memahami epistemologi kepulauan. Maka, Anthropocene Islands bisa dibaca sebagai panduan konseptual untuk reimajinasi Indonesia sebagai “epistemic archipelago” — bukan sekadar geografi, tetapi cara berpikir dan hidup.
Kesimpulan besar buku ini mengarah pada etika baru: planetary entanglement ethics. Ia mengajak kita mengganti ambisi “menguasai bumi” dengan kemampuan merawat hubungan.
Kita tidak lagi bisa menyelamatkan dunia dengan teknologi saja, tapi dengan perubahan cara berpikir dan merasakan.
“We are all islands, and the ocean between us is our shared responsibility.” Buku ini berakhir dengan semacam doa bagi dunia — untuk membangun peradaban yang tidak lagi terpusat pada manusia, tapi pada kehidupan bersama. Dalam konteks spiritual Islam, kita bisa mengingat ayat “wa ja‘alnâ min al-mâ’i kulla syai’in ḥayy” (Kami jadikan dari air segala yang hidup) — sebuah resonansi mendalam antara teologi dan island ontology.
Konsep ini menekankan bahwa dunia kini terdiri dari relasi yang tumpang tindih: ekologi, ekonomi, spiritualitas, dan teknologi. Tidak ada batas yang benar-benar memisahkan “manusia” dan “alam”. Pugh & Chandler mengadaptasi ide Édouard Glissant tentang Relation dan Donna Haraway tentang sympoiesis (co-making). Dunia adalah hasil ko-produksi dari manusia, hewan, angin, laut, dan bahkan arus data. “Entanglement is not a problem to be solved but a condition to be lived.” (Pugh & Chandler). Relevan dengan masyarakat kepulauan Indonesia — di mana kehidupan pesisir, perikanan tradisional, dan budaya laut selalu menunjukkan simbiosis ekologis yang kompleks.
Bab tengah buku membahas bagaimana pulau menjadi ruang politik dan etika yang penting di era krisis ekologis. Pulau, tulis mereka, “is a political figure that reveals both the limits and possibilities of the Anthropocene.” Dalam arti ini, pulau adalah ruang perlawanan terhadap wacana global yang homogen. Banyak komunitas di Pasifik dan Karibia menolak narasi bahwa mereka “akan tenggelam”—mereka justru menegaskan kapasitas adaptif dan spiritual mereka.
Buku ini mengangkat kasus-kasus lokal seperti Fiji dan Vanuatu, yang mengembangkan eco-cosmologies—cara hidup yang menempatkan laut, angin, dan batu sebagai bagian dari kekerabatan ekologis. Dalam konteks ini, Anthropocene Islands beresonansi dengan gagasan dekolonisasi pengetahuan: bahwa solusi terhadap krisis iklim tidak bisa datang dari luar, melainkan dari pengetahuan yang berakar di tempat.
Pugh dan Chandler menantang konsep Anthropocene yang masih berpusat pada manusia Barat. Mereka mengajukan pendekatan Island Studies yang kritis terhadap humanisme modern—karena humanisme sering mengabaikan keterlibatan non-manusia. “Islands think otherwise,” tulis mereka, menunjukkan bahwa cara berpikir kepulauan mengandung epistemologi alternatif: relasional, ekologis, dan plural. Inilah epistemologi pulau dan kritik terhadap humanisme modern. Ini sejalan dengan pemikiran Édouard Glissant (Martinique) tentang Relation—bahwa setiap entitas hidup saling berkelindan tanpa dominasi.
Kita dapat membandingkan gagasan ini dengan pemikiran Syed Hossein Nasr, filsuf Muslim, yang menulis: “When the sacred is forgotten, the world becomes an object to be used rather than a reality to revere.” Perspektif ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya krisis ekologi, tetapi krisis spiritual dan epistemik.
Relevansi buku ini bagi dunia kini sangat besar. Ia telah meresonansi global: dari lautan pasifik ke nusantara. Krisis iklim global, kebijakan migrasi, dan geopolitik maritim semuanya memperlihatkan bagaimana pulau menjadi titik panas dalam pertarungan wacana global. Dalam konteks Indonesia, Anthropocene Islands membantu kita merefleksikan posisi bangsa kepulauan dalam politik dunia. Konsep entangled worlds mengingatkan kita bahwa laut adalah ruang hidup dan sejarah bersama—bukan sekadar wilayah ekonomi. Ini memperkuat gagasan Presiden Soekarno tentang “Negara Maritim Besar” dan visi “Poros Maritim Dunia”, tetapi dengan makna ekologis dan etis yang lebih dalam: menghidupkan laut sebagai relasi, bukan sekadar sumber daya.
Daripada berbicara soal “adaptasi” atau “ketahanan” (yang sering beraroma teknokratik),
Pugh & Chandler mendorong konsep relasional resilience — ketahanan yang dibangun dari keterhubungan sosial, budaya, dan spiritual, bukan sekadar infrastruktur. “Resilience is not bouncing back; it is staying connected.” Dalam konteks Indonesia, gagasan ini membuka peluang untuk menilai ulang pendekatan pembangunan pesisir, reklamasi, dan migrasi iklim.
Masyarakat adat dan nelayan kecil — yang sering diabaikan — justru mewujudkan relational resilience yang paling kuat.
Bagian ini bisa dibaca sebagai jembatan menuju filsafat dan spiritualitas ekologis. Pulau-pulau, kata Pugh dan Chandler, memaksa manusia untuk “berpikir dengan batas dan keterbatasan, bukan untuk melampauinya.” Ini sejalan dengan pemikiran Muhammad Iqbal, filsuf Muslim dari abad ke-20, yang menulis: “The ocean is not a separation, but an invitation to humility.”
Dan juga resonan dengan gagasan Thich Nhat Hanh tentang interbeing — bahwa keberadaan kita selalu “bersama yang lain.”Dengan demikian, “island spirituality” bukan agama baru, tapi kesadaran ontologis baru tentang keterikatan hidup bersama dunia.
Kritik dan Apresiasi atas Buku Ini
Para pengamat akademik menilai buku ini sebagai salah satu kontribusi paling penting dalam critical island studies. Reviewer dari Island Studies Journal (2022) menyebut karya ini “a paradigm shift in understanding relational ontology through islands.” Namun, kritik juga muncul: beberapa akademisi berpendapat bahwa Pugh dan Chandler terlalu teoretis dan kurang memberikan strategi praktis bagi komunitas pulau yang benar-benar menghadapi ancaman tenggelam. Meski begitu, keunggulan buku ini justru terletak pada daya reflektifnya—mendorong kita berpikir ulang tentang hubungan antara tempat, kekuasaan, dan planet.
Catatan Akhir: Membangun Dunia yang Terhubung
Akhirnya, Anthropocene Islands mengajarkan bahwa bertahan di dunia krisis bukanlah tentang menguasai alam, melainkan menghidupi keterhubungan. Seperti kata Rumi, “You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop.” Pulau-pulau dalam buku ini menjadi simbol dunia yang saling berkelindan—antara manusia, laut, dan waktu. Dalam konteks global dan Indonesia, pesan buku ini menegaskan urgensi membangun spiritualitas ekologis dan politik solidaritas lintas batas—sebuah kesadaran baru bahwa kita hidup bukan di dunia yang terpisah, tetapi di dunia yang saling menubuh.
Pada bagian akhir (Conclusion), Pugh dan Chandler membawa kita pada refleksi filosofis dan politis yang sangat kuat. Mereka menolak melihat pulau hanya sebagai “objek penderita” krisis iklim. Sebaliknya, mereka menulis bahwa pulau adalah tempat lahirnya imajinasi baru tentang dunia yang saling terikat — dunia yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika pusat-pinggiran atau manusia-nonmanusia.
Dalam simpulan ini, mereka mengajukan konsep island thinking — bukan berarti berpikir secara sempit, tetapi berpikir dengan kesadaran relasional. “Thinking with islands,” tulis mereka, “means learning from the ways islands live through connection.” Mereka menegaskan bahwa masyarakat pulau mengajarkan dunia sesuatu yang telah lama hilang: rasa keterikatan dengan dunia yang lebih luas tanpa kehilangan identitas lokal.
Mereka juga mengingatkan bahwa pendekatan dominan terhadap krisis iklim masih bersifat technocratic and anthropocentric. Dunia masih sibuk mencari solusi berbasis geoengineering, transisi energi industri, dan adaptasi berbasis data, tetapi lupa memulihkan hubungan spiritual dan sosial antara manusia dan lingkungan. Dalam kalimat yang menggema secara etis, mereka menulis:
“What if survival is not about saving the islands, but learning from them?” Kesimpulan ini bukan hanya seruan akademis, tetapi juga seruan moral dan eksistensial. Ia menegaskan bahwa penyelamatan planet tidak datang dari menaklukkan alam, tetapi dari memulihkan relasi ekologis — sesuatu yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat kepulauan.
Jika dihubungkan dengan Indonesia, pesan ini sangat relevan. Kebijakan lingkungan sering kali dipusatkan di daratan: deforestasi, energi, atau pangan. Padahal, identitas kepulauan Indonesia menuntut epistemologi maritim — cara berpikir yang melihat laut sebagai ruang sosial, bukan sekadar sumber ekonomi. Menghidupkan kembali cara berpikir kepulauan berarti juga membangun masa depan politik dan ekologis yang lebih adil.
Dalam nada yang hampir spiritual, bagian penutup buku ini bergema seperti doa bagi planet ini: agar dunia berhenti berpikir dalam garis batas, dan mulai berpikir dalam simpul-simpul keterhubungan. Sebagaimana ditulis Rumi, yang kutipannya muncul di epilog:
“You are not a drop in the ocean. You are the ocean in a drop.”
Kalimat ini merangkum seluruh tesis buku: bahwa setiap manusia, setiap pulau, dan setiap spesies adalah bagian tak terpisahkan dari jalinan bumi — dan menyelamatkan bumi berarti menyelamatkan diri sendiri.
Bagian pembuka dan penutup Anthropocene Islands berkelindan: keduanya menolak narasi keterpisahan dan menawarkan paradigma kehidupan terhubung (entangled life). Di tengah krisis iklim, buku ini mengajak kita untuk melihat bahwa solusi tidak hanya ada di laboratorium atau konferensi internasional, tetapi di cara hidup sehari-hari masyarakat kepulauan — dari solidaritas, ritual laut, hingga cara menanam dan berlayar.
Bagi Indonesia, pesan ini adalah cermin identitas dan tantangan: berani mengakui bahwa kita bukan hanya negara maritim, tapi peradaban kepulauan yang dapat mengajarkan dunia bagaimana hidup bersama planet ini secara lebih rendah hati, adil, dan penuh makna.
Bogor, 27 Oktober 2025.
Dwi Rahmad Muhtaman
Referensi
Pugh, J., & Chandler, D. (2021). Anthropocene Islands: Entangled Worlds. University of Westminster Press.
i Ruang Baca Ruang Buku (Rubarubu) adalah sebuah prakarsa yang mempunyai misi untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan lewat bacaan dan buku. Merangsang para pembaca Rubarubu untuk membaca lebih dalam pada buku asal yang diringkas, mendorong percakapan untuk membincangkan buku-buku yang telah diringkas dan juga meningkatkan gairah untuk menulis pengalaman baca dan berbagi dengan khalayak. Prakarsa Rubarubu adalah bagian dari prakarsa ReADD (Remark Asia Dialogue and Documentation), sebuah program untuk menjembatani praktik dan gagasan — agar pengalaman lapangan dapat berubah menjadi narasi yang inspiratif, dokumentasi yang bermakna, dan percakapan yang menggerakkan.
ReADD mendukung penulisan, penerbitan, dan dialog pengetahuan agar Remark Asia memperluas perannya bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai rumah gagasan tentang masa depan berkelanjutan.
ReADD (Remark Asia Dialogue and Documentation) lahir dari kesadaran bahwa keberlanjutan tidak hanya dibangun melalui proyek dan kebijakan, tetapi juga melalui gagasan, refleksi, dan narasi yang menumbuhkan kesadaran kolektif. Buku, diskusi, dan dokumentasi menjadi medium untuk menyemai dan menyerbuk silang pengetahuan, membangun imajinasi masa depan, serta memperkuat hubungan antara manusia, budaya, dan bumi.
Dengan kemajuan teknologi kita juga bisa memanfaatkan kecanggihannya untuk meringkas buku-buku yang ingin kita baca singkat. Rubarubu memanfaatkan teknologi intelegensia buatan untuk meringkas dan mengupas buku-buku dan dijadikan bacaan ringkas. Penyuntingan tetap dilakukan dengan intelegensia asli untuk memastikan akurasinya dan kenyamanan membaca. Karena itu tetap ada disclaimer bahwa setiap artikel Rubarubu tidak menjamin 100% akurat berasal dari seluruhnya buku yang dikupas. Penulisan artikel dilakukan dengan sejumlah improvisasi, olahan dari sumber lain dan pandangan/interpretasi pribadi penulis. Pembaca disarankan tetap membaca sumber aslinya untuk mendapatkan pengalaman dan jaminan akurasi langsung.